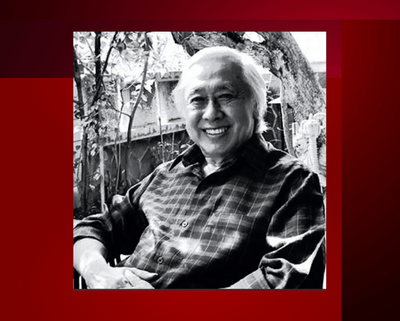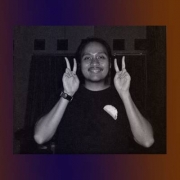Durga, I Love You!
Oleh : Agus Dermawan T.
Batari Durga adalah sosok perempuan yang sangat dimuliakan.
Namun ikon perempuan digdaya ini juga diwarnai dengan reka
riwayat amat menyudutkan. Di Bali, selain dianggap
perempuan hebat, Durga juga dianggap setan.
*
Durga! Dialah perempuan yang dalam banyak abad membius kepercayaan banyak orang kepada dua mitos sekaligus. Yang pertama mitos yang mutlak mulia, dan yang kedua mitos yang setengah durjana. Walaupun mitos kedua ini pada kemudian hari selalu diralat, lantaran dianggap sebagai rekayasa cerita yang menyimpan pretensi menegasi.
Mitos yang mutlak mulia ditunjukkan lewat presentasi Durga Mahisasuramardhini, yang wujudnya terpahat di Candi Prambanan, Candi Penataran, Candi Kedulan, Candi Sukuh dan sebagainya. Di situ Durga diceritakan sebagai perempuan sangat kuat, yang sengaja dicipta oleh para dewa untuk menaklukkan Mahisasura. Raksasa berwujud lembu yang ditengarai akan mengobrak-abrik kahyangan tempat para dewa nyaman bersemayam.

Relief Batari Durga di Candi Kedulan, Jawa Tengah. Durga digambarkan sebaga perempuan mulia yang memiliki kesaktian sepuluh dewa. (Foto: SJS).
Lalu mitologi bertutur bahwa Durga dilahirkan dari lidah api, yang merupakan dari puncak kesaktian dewa Brahma, Wisnu, Syiwa dan tujuh dewa utama lainnya. Oleh karena itu Durga yang berwujud wanita cantik ini memiliki tangan sepuluh, dengan masing-masing membawa senjata andalan milik sepuluh dewa yang dititisnya. Maka senjata cakra milik Wisnu, trisula milik Syiwa, busur dan panah milik Wayu, pisau milik Agni, kilat cahaya milik Surya, digenggamnya. Di medan laga Durga diberi tunggangan harimau Himalaya yang gesitnya luar biasa.
Dan lantaran Durga itu perempuan, dalam berperang selalu mengenakan abharana, atau busana yang indah dengan perhiasan memikat mata. Gelang dan antingnya merupakan hadiah dari Dewi Ksiarnawa, kalung mutiara dari Dewi Sesha.
Dengan perangkat kesaktian itu Durga meluruk Mahisasura di Gunung Windya. Pertempuran terjadi, dan tentu saja Durga menang. Peristiwa ini kemudian disebut-sebut sebagai peperangan antara kubu putih (Durga) dan kubu hitam (Mahisasura). Namun meski Mahisasura mati, pada saatnya ia akan hidup lagi dalam bentuk lain, dan si cantik Durga kembali memerangi sampai si “neo mahisasura” tewas lagi. Itu sebabnya pertempuran Durga dan Mahisasura ini disebut “peperangan abadi”. Yang di Jawa disebut pupuh langgeng, dan dalam kosmologi Bali difilosofikan sebagai rwa bhineda. Konsep keseimbangan hidup yang sengaja diciptakan oleh Sang Hyang Widhi Washa, yang kemudian disimbolkan dalam poleng, motif kotak putih-hitam. Semacam yin-yang dalam konsep Cina kuno.
Mitologi dan mitos Durga itu dijunjung tinggi di Jawa dan Bali. Namun, apabila di Jawa sang Durga utuh tampil sebagai perempuan lengkap-martabat dengan latarbelakang yang luhur, di Bali Durga hadir dengan sejumlah nuansa. Bahkan dengan latarbelakang dramatik serta liku cerita amat sinematik. Lantaran masyarakat Bali (juga) mempercayai bahwa Durga adalah Dewi Uma.
Begini ceritanya.
Syahdan Uma sedang melakukan tapabrata di tengah samudera. Melihat begitu khusyuknya Uma bertapa, para dewa di kahyangan merasa resah. Mereka kawatir : apabila Uma memiliki kelebihan kekuatan, akan mengusik ketenteraman kahyangan. Karena itu, agar tidak menjelma jadi mahluk yang amat berkesaktian, Uma harus dikeluarkan dari pertapaan.
Sejumlah dewa pun diutus untuk membatalkan tapa Uma. Tapi selalu berujung kegagalan. Melihat kenyataan itu Batara Guru, yang juga disebut Batara Syiwa, mengambil peran. Dewa ini lalu turun ke samudera. Namun begitu bertemu dengan Uma yang aduhai cantik, Batara Guru terpesona. “Minta ampun, saya mendadak jatuh cinta,” kata hatinya.

Lukisan I Gusti Made Baret. Batara Guru atau Batara Syiwa. (Foto: Arsip Penulis).
Maka, alih-alih membatalkan tapa, Batara Guru malah merayu-rayu. Tapi perempuan ini bergeming. Batara Guru yang semakin mabuk kepayang lantas minta bantuan kepada Sang Hyang Wenang. Dikatakan bahwa Uma tidak bisa ditangkap hanya dengan dua tangan, sehingga ia memerlukan tangan tambahan. Lalu tangan Batara Guru yang semula hanya dua bertambah jadi empat. Dewi Uma pun berhasil ditangkap. Perempuan ini lantas diboyong ke kahyangan, dan dikawini.
Berbulan-bulan sudah Uma hidup di kahyangan. Sampai akhirnya Uma yang pintar dan sakti itu tahu maksud Batara Guru menghentikan pertapaannya. Karena itu Uma lantas mengambil sikap selalu berdingin hati. Bahkan tidak pernah mau melayani nafsu asmara si suami. Tapi Batara Guru tidak henti mencari cara.
Lalu pada suatu hari Uma diajak bertamasya nostalgia dengan mengendarai Lembu Nandi, melongok tengah samudera tempat dulu Uma bertapa. Ketika matahari menjelang tenggelam dan langit menghadiahkan warna jingga, rasa romantik Batara Guru mendidih. Uma pun diajak bercinta di atas Lembu Nandi. Uma tentulah menolak. Batara Guru tak bisa membendung hasratnya. Ia memeluk Uma erat-erat, sampai kama (air kehidupan, sperma) Batara Guru keluar. Kama itu melejit dan jatuh ke samudera. Melihat itu Uma risih dan malu.
Di kahyangan Batara Guru terus mengungkit peristiwa itu dengan hati jengkel. Dewi Uma yang semula sangat sabar akhirnya marah. “Bila menyakiti terlalu sering, mulut Kakanda akan bertaring!” Mulut Batara Guru pun mendadak bertaring. Mengetahui dirinya bertaring, Batara Guru terkejut, dan dengan spontan membalas. “Sifatmu jahat seperti raksasa. Kalau begitu, mengapa kau tidak jadi raksesi saja, hei Uma!” Maka dalam sekilatan cahaya, Dewi Uma sudah menjadi raksesi. Wajahnya yang jelita menjadi buruk. Tubuhnya yang lencir bagai kijang kencana jadi membesar bagai badak tak bercula.
Kahyangan heboh. Aneh memang, Batara Guru, salah satu ketua dari para dewa, yang setiap hari gagah memimpin rapat untuk mengatur kehidupan manusia, bertempur rumah tangga dengan tiada malunya.
Waktu terus berguling. Air kama Batara Guru yang jatuh ke samudera itu telah menjelma jadi bayi lelaki. Bayi itu kemudian jadi dewasa, dengan postur seperti raksasa. Karena tidak tahu dari mana asalnya, raksasa muda itu tidak punya nama. Ia lalu bertanya ke sana ke mari, sampai ditemukan jawaban bahwa dirinya adalah wujud dari kama Batara Guru. Raksasa ini lalu bertandang ke kahyangan untuk menemui orang tuanya. Tanpa sepengetahuan Uma, Batara Guru menerima kedatangannya dengan baik. Dan menamai anaknya: Batara Kala.
Batara Kala belum puas. Ia mengatakan bahwa ayahnya telah menyia-nyiakan dirinya begitu lama. Karena itu ia minta agar dirinya dicarikan jodoh. Batara Guru pun teringat Uma yang sudah menjadi raksesi. Lalu dijodohkanlah Batara Kala dengan Uma. Uma yang tidak tahu bahwa Batara Kala adalah “anak”nya, bersedia saja. Dua sejoli ini lantas hidup di Setra Gandamayu, sebentang kuburan yang letaknya di tengah samudera. Di sini nama Uma diganti jadi Batari Durga, yang artinya : perempuan yang tak bisa disentuh oleh siapa pun.
Dari kurun ke kurun Batara Kala dan Batari Durga hidup bersama. Sampai akhirnya tahu bahwa mereka sesungguhnya berstatus ibu dan anak. Atas hal ini Durga marah tak alang kepalang kepada Batara Guru. Ia berjanji kepada dirinya sendiri : akan mengganggu tatanan kehidupan yang dibentuk oleh Dewan Dewa yang diketuai mantan suaminya. Dalam aksinya itu Durga akan menjelma jadi apa saja, di antaranya sebagai Calonarang. Sementara Batara Kala juga akan melampiaskan dendam. Ia mengancam bahwa pada saat tertentu akan dikunyahnya matahari, agar gulita menyelimuti semesta.

Lukisan Ida Bagus Nyoman Tjeta, 1937. Durga digambarkan sedang menjadi rangda dan siap mengacau kehidupan manusia. (Foto: Arsip Penulis).

Lukisan Ida Bagus Made Togog, 1939, yang menggambarkan orang-orang sedang memerangi Calonarang. (Foto: Arsip Penulis).
Empati pelukis kepada Durga
Pada tahun 2009 Panitia Bali Bangkit menggelar pameran lukisan tradisional di Plaza Indonesia, Jakarta. Dalam jajaran lukisan itu yang hadir di kanvas adalah gambaran suasana sukacita, yang disebut sebagai “Bali sekala”, atau Bali yang tampak. Pemandangan jajaran lukisan dianggap (telah berhasil) mengurangi keberadaan lukisan “Bali niskala”, Bali tak tampak, atau Bali gaib. Yang biasanya terwujud dalam lukisan tenget, karena membawakan suasana yang hening, muram, cenderung gelap dengan sentuhan mistis dan magis.
Apa yang terlihat sebagai realitas itu ditegaskan kebenarannya oleh banyak pelukis yang ikut serta dalam pameran. Mereka bahkan mengatakan bahwa dirinya mungkin tidak terlalu terpikat untuk menggarap tema-tema niskala, yang didefinisikan sebagai lukisan alam roh. Tema yang diberangkatkan dari mitos dan mitologi seram, yang sebagian besar bermuara pada sisi gelap Durga.
“Dunia Durga milik generasi sebelum tahun 1940-an, yang sekali-sekali diulang dengan versi sekular oleh seniman Pita Maha, Golongan Pelukis Ubud dan seterusnya,” kata Ketut Sadia, pelukis generasi 1990-an mashab Batuan.
Para pelukis Bali yang hidup di pemikiran modern menyadari benar bahwa mitos Durga adalah presentasi dari ketidakadilan pikiran (dewa) lelaki. Durga adalah mahluk yang sengaja dicipta untuk menghadirkan sisi gelap manusia, dengan perempuan sebagai sarananya. Tujuan dari upaya absurd itu adalah untuk mengukuhkan maskulinitas yang berpokok pada konsep patriarki. “Durga adalah Dewi Uma yang diperdaya,” begitu budayawan Anak Agung Made Djelantik berkata.
Oleh karena itu, apabila ada pelukis Bali masa kini (bahkan masa 50 tahun terakhir) yang mencipta lukisan bertema ke-durga-an, itu bukan lantaran diberangkatkan dari kepercayaannya atas mitos kebuasan Durga. Namun karena sekadar ingin menampilkannya sebagai cerita. Sebagai dongeng yang terlanjur diwariskan sebagai khasanah tradisi, dan dikenalkan sebagai legenda. Karena itu yang terlukis adalah peristiwa-peristiwa permukaan, yang tak lain ditransformasi dari adegan-adegan pentas pertunjukan.
Suatu kali Ida Bagus Made Nadera dan I Ketut Kebut melukis Petani dan Dewi Uma, atau Kisah Sudamala, yang ditafsir dari relief Hindu Candi Tegowangi, Kediri, abad XVII. Di situ diceritakan bahwa Batara Guru mengaku sedang menderita sakit keras, sehingga harus dicarikan obat khusus yang adanya hanya di mercapada (bumi, tempat hidup manusia). Uma diminta untuk mencari obat itu.

Lukisan I Ketut Kebut yang menggambarkan “Petani dan Dewi Uma” atau “Cerita Sudamala”. (Foto: Arsip Penulis).
Sesampai di mercapada Uma mendapat kabar bahwa susu itu hanya ada pada seekor sapi berwarna putih. Setelah mencari selama berbulan-bulan, akhirnya ditemukanlah sapi itu. Tapi petani pemilik sapi itu baru bersedia memberikan secawan susu sapinya, setelah Uma mau bersanggama dengannya. Uma bingung dan lantas mencari kabar kondisi terakhir suaminya. Dari kahyangan diberitakan bahwa Batara Guru sedang sekarat. Maka Uma, yang sangat menginginkan suaminya sembuh, terpaksa mau bersanggama dengan petani. Namun begitu menyatakan mau, sapi itu menjelma jadi Batara Guru. Ternyata Batara Guru hanya ingin tahu, sejauh mana kesetiaan Uma kepadanya. Uma pun sepenuhnya dikutuk. Batara Guru yang menjebak tak tersangsi apa-apa.
Nadera dan Kebut mengatakan bahwa ia tidak ingin melukiskan makna dari mitologi yang berisikan siasat Batara Guru itu. Ia hanya ingin menggambarkan rame-ramenya adegan sandiwara yang diambil dari panggung. Karena kisah Sudamala menjanjikan nilai piktorial yang untuk lukisan. Mereka seperti mengabaikan pendapat Zoetmulder yang memaknai cerita tersebut secara filosofis : proses penyucian diri perempuan.

Lukisan Anak Agung Gde Sobrat, “Mangkatnya Raja Airlangga”, 1970-an. Rangda dan setan-setan dihayati sebagai fragmen pertunjukan. (Foto: Arsip Penulis).
Anak Agung Gde Sobrat beberapa kali mencipta lukisan yang menggambarkan wafatnya Raja Airlangga. Di kanvasnya tergambar tubuh Airlangga yang kaku sedang dikerumumi setan, dengan disaksikan rangda. Sosok rangda adalah bentuk jahat dari Durga. Ia juga melukis leak sedang menari bersama-sama setan-setan kecil. Figur leak itu disadari merupakan transformasi dari Durga. Pada bagian lain pelukis Ida Bagus Made Poleng menggambarkan leak yang berkuda sedang berperang melawan dua burung besar.

Lukisan Anak Agung Gde Sobrat, 1938, yang menggambarkan transformasi Durga menjadi leak, dan menari bersama setan-setan. (Foto: Arsip Penulis).

Lukisan Ida Bagus Made Poleng. Leak naik kuda berperang melawan dua burung besar. (Foto: Arsip Penulis).
Namun Sobrat dan Gus Made tak hendak melukis moralitas kisah Durga yang ganjil. Mereka hanya menjumput atraksinya, sebagai bagian dari anasir artistik karyanya. Gus Made mengatakan, apabila ada seniman yang menggubah Calonarang, sesungguhnya yang dilukis adalah ceritanya. Yang dilukis adalah unsur-unsur kegambarannya atau visualnya. Bukan makna cerita yang menyebut Calonarang itu penjelmaan perempuan keji bernama Durga.

Lukisan I Ketut Yuliarta. Rangda dan barong berpotret bersama. (Foto: Arsip Penulis).
Melupakan Durga sebagai setan
Dewi Uma atau Batari Durga diam-diam terposisi sebagai perempuan yang luhur. Seperti halnya di India yang meletakkan Uma sebagai perempuan yang ramah, baik hati, berpengetahuan luas dan sakti. Yang hanya akan menggunakan 8 (delapan) tangannya kala ia marah kepada para (lelaki) jahanam. Sehingga ia dijuluki sebagai Dewi Laksmi atau Dewi Parwati.

Margaret Mead dan Rudolf Bonnet. (Foto: Arsip Penulis).
Kelemahan logika yang mencipta keburukan perempuan lewat sosok Durga sesungguhnya telah disadarkan oleh Rudolf Bonnet dan Walter Spies pada 1940-an lewat perkumpulan seni lukis Pita Maha. Sikap penyadaran Bonnet dan Spies itu tumbuh ketika mereka membaca hasil penelitian antropolog Margaret Mead dan Gregory Bateson pada 1930-an. Sebuah penelitian yang diawali dengan permintaan agar seniman tradisional Bali menggambarkan segala sesuatu yang tidak kelihatan di benderang siang, namun bersliweran di tenget malam. Hasilnya adalah lukisan tentang leak, memedi, gamang dan tonya, segenap setan yang membawa celaka dan penyakit. Semua mahluk menakutkan itu oleh para pelukis dipercaya dikomandani oleh Durga.

Lukisan I Dewa Ketut Baroe, 1940. Leak memakan bayi. (Foto: Arsip Penulis).
Bonnet berpikir, jika mitologi Durga ini terus dihidupkan sebagai kebenaran, perempuan akan terus dipersepsikan sebagai setan, sebagai mahluk destruktif. Dan memang sudah terbukti, dalam banyak lukisan tradisional Bali zaman dahulu, setan itu terlanjur digambarkan berwujud perempuan.

Lukisan I Made Djata, 1937. Calonarang mendemonstrasikan sikap destruktifnya, membakar hutan. (Foto: Arsip Penulis).
Maka lewat Pita Maha para pelukis dianjurkan untuk tidak terpaku di kisah itu. Para pelukis diajak untuk melukis hal-hal yang cenderung sekular. Panen padi, keindahan perangkat upacara di pura, keartistikan angkul-angkul, pertunjukan tari pendet dan sebagainya. Upaya penghindaran itu diteruskan oleh para pelukis Bali tradisional sekarang, yang disebut mashab Pita Prada.
Dengan begitu tersimpul bahwa Durga adalah batari yang sangat dihormati. Itu sebabnya di setiap Pura Dalem di Bali, selalu ada altar Durga. Kepadanya siapa pun boleh memohon apa yang diinginkan. Maka, Uma, aku cinta padamu. Durga, I love you!
*Agus Dermawan T. adalah penyusun buku “Bali Bravo – Leksikon Pelukis Tradisional Bali 200 Tahun”.