Jalan Setapak Umat Ibrahim (Sebuah Esai Menyambut Hari Puisi)
Oleh Arip Senjaya
karena aku ingin merdeka dan menemukan diri.
(Subagio Sastrowardoyo, “Kampung”1)
Kapak penyair
Puisi adalah tentang sejarah kesulian pengucapan yang bersifat individualistik. Ada kesulitan pada setiap penyair untuk mengatakan sesuatu dan akhirnya masing-masing mencari jalan ucap sendiri-sendiri, dan dengan demikian sejarah puisi selalu sebagai sejarah kesulitan per individu penyair, bukan sejarah mereka secara bersamaan yang memudahkan mereka mengatakan sesuatu. Mereka punya jalan setapak masing-masing.
Masing-masing mereka mungkin saling belajar untuk saling memahami, saing bertemu di persimpangan jalan, dan bahkan sering juga beberapa dari mereka bersatu untuk menerbitkan antologi bersama dengan tema atau karena momen tertentu, tapi jangan berharap bahwa mereka akan punya kesamaan. Setiap antologi bersama adalah wujud dari ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an semata.
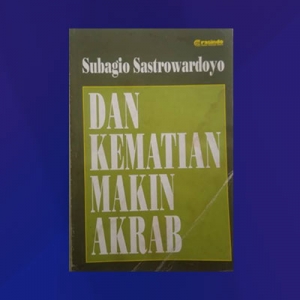
Buku Subagio Sastrowardoyo
Berbeda misalnya dari bahasa pidato para pejabat, dalam keterpisahan atau dikumpulkan jadi satu buku sekali pun mereka adalah tulisan yang sama. Bahkan kalau kita mau membaca artikel akademik dalam jurnal-jurnal ilmiah, dengan alasan gaya selingkung jurnal, mereka akhirnya menjadi sama. Ada kelisanan dalam tradisi pidato dan artikel akademik, dengan catatan “kelisanan” itu bermakna keberulangan pola, bentuk, daya ucap, dan bahkan tren gaya bahasa2.

Buku A. Teeuw “Indonesia Antara Kelisanan dan Keberaksaraan” 1994, Pustaka Jaya.
Sedangkan dalam tradisi penulisan puisi, jangankan dengan orang lain, rata-rata penyair bahkan tidak mau sama dengan karya yang pernah mereka buat sebelumnya. Penyair adalah para pendiri berhala bahasa yang dikapakinya lagi setelah bisa disembahnya. Mereka adalah umatnya Nabi Ibrahim. Antologi-antologi tunggal setiap penyair merupakan kebhinekaan dalam kedirian mereka masing-masing yang isinya adalah reruntuhan puing berhala bahasa itu. Mungkin kutipan puisi Acep Zamzam Noor berikut relevan untuk menjelaskan fenomena tersebut:
…
Di jalan setapak
Yang disediakan bumi tulus ini
Kata-kataku tumbuh dari udara
Kata-kataku membangun menara tinggi
Namun akhirnya runtuh juga3
…
Kini saya bisa mengerti mengapa beberapa penyair yang juga akademisi agak malas menulis artikel ilmiah, karena mereka tak mau jadi sama. Mereka lebih senang menulis esai atau artikel bebas (tubuh dari udara) yang memberi tempat pada keindividuan mereka. Itu sebabnya para penyair sebaiknya jangan jadi dosen macam saya sebab akan sulit mengurus karier akademik sepanjang menulis merupakan pilihan ideologis-individualis. Esai-esai atau artikel bebas akan sulit dinilai dalam kepangkatan atau laporan Beban Kerja Dosen atau Remun tiap semester. Karya-karya puisi apa lagi, sulit dapat tempat, kecuali mendapatkan penghargaan, dan bukan puisinya yang dinilai, tetapi penghargaannya itu. Di hadapan penilaian dokumen, puisi-puisi harus runtuh oleh penghargaan! Dan penghargaan kepenulisan adalah bagian dari kelisanan tradisi tulis. (Maksud saya, sering seorang penyair dibangga-banggakan bukan karena para pembangganya ini membaca puisi-puisi penyair itu, tetapi karena mereka tahu sang penyair mendapatkan penghargaan.)
Pada intinya, beberapa dosen penyair yang sempat saya kenal adalah para penganut Bhineka Tunggal Ika yang sulit toleran pada berhala-berhala persamaan. Kecondongan mereka lebih berat pada ideologinya daripada kepada kariernya. Pepatah “di mana langit di jungjung di situ bumi di pijak” agak berat diterapkan para penyair dalam lingkungan kerja yang menuntut sama. Bumi mereka adalah bumi tulus ini kata AZN.
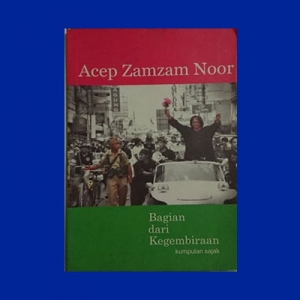
Buku Puisi Acep Zamzam Noor “Bagian dari Kegembiraan” Pustaka Azan
Penyair Wan Anwar alm. adalah contoh yang paling saya kenali. Di masa hidupnya sebagai dosen ia adalah salah satu redaktur majalah Horison, ia membaca dan menulis berbagai esai selain berbagai makalah bahan ajar dan berbagai puisi atau cerpen serta beberapa usaha kerasnya dalam penulisan novel. Sangat jarang ia menulis artikel untuk beberapa jurnal yang ia terlibat dalam pendiriannya, seperti jurnal Gagasan (FKIP Untirta) atau Litera (Pendidikan Bahasa dan Sastra FKIP Untirta).
Satu-satunya yang membatasi Wan Anwar dalam penulisan esai dan cerpen saya kira adalah batas panjang halaman jika ia menulis esai untuk Horison atau media cetak lainnya. Tapi ia tidak menyerah dengan batas sehingga menulis pula ia esai-esai panjang yang lalu terbit menjadi buku (diterbitkan setelah ia meninggal oleh murid-muridnya yang militan di Kubah Budaya4). Hal yang sama terjadi pada Nandang Aradea alm. (beliau bukan penyair, tapi sutradara teater TSI dan sempat menjuarai lomba teater di Hongkong), juga penyair Herwan FR (ini masih hidup dan sangat produktif menulis buku-buku puisi dan buku lainnya hingga sekarang5) yang sama-sama mengajar bersama saya di Untirta. Nandang pernah pula menulis puisi di masa masih mahasiswa S1, tapi pada dasarnya setiap seniman dalam arti luas memang mengurus beda saja. Yang tidak begitu bukan seniman sebenarnya meskipun mengaku-ngaku seniman.
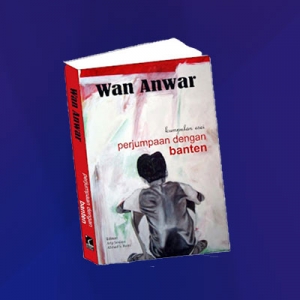
Buku kumpulan esai Wan Anwar yang diterbitkan murid-muridnya setelah ia meninggal “Perjumpaan dengan Banten” (2009), Kubah Budaya.
Beberapa dosen lain dari kampus lain yang berdarah penyair pada dasarnya sama-sama kurang bisa mengurus karier mereka dengan alasan yang sama: ideologi kebhinekaan itu. Dirjen Perguruan Tinggi mesti teliti dalam menerima dosen di suatu hari nanti, jangan sampai yang kelas penyair ambil bagian karena mereka sulit dibikin sama. Atau, mereka boleh menjadi dosen dengan kriteria penilaian kepangkatan yang berbeda dengan para akademisi yang bukan penyair; asesor untuk karya-karya mereka tentu tidak bisa didasarkan pada siapa saja yang bergelar akademik lebih tinggi6, mereka perlu aseseor kritikus sastra atau kritikus seni. Yang jelas, jika mereka tidak menjadi bagian dari lembaga akademik, maka lembaga akademik itu akan seperti Burung Garuda tanpa semboyan Bhineka Tunggal Ika. Mereka penting untuk menciptakan beda, dan beda itu inti cinta dan mencintai itu kesediaan menerima beda7. Sedangkan lembaga-lembaga akademik tentu dibangun dalam rangka menumbuhan cinta tersebut. Apakah ada tujuan lebih tinggi dari cinta?
Kerja keras dalam kebhinekaan individual
Dan sebenarnya meski setiap individu penyair menemukan jalannya sendiri-sendiri, masing-masing tetap dalam kesulitan. Tidak jarang beberapa penyair mengambil jalan setapak berbeda lagi setelah ia beberapa lama memiliki bentuk ucap tertentu yang khas. Sama sekali saya tidak melihat upaya yang tetap dari Sapardi Djoko Damono, misalnya, setiap puisinya selalu memperlihatkan keinginannya untuk lepas dari cara ucap yang sudah ia buat sendiri. Bentuk-bentuk puisi Sapardi dengan jelas memperlihatkan upaya-upaya pelarian. Dan inilah rupanya pokok pertama menjadi penyair: bisa bebas dari bahasa umum yang berlaku dan bahasa individualistik dirinya sendiri yang sempat berlaku.
Mungkin pertama-tama adalah menjadi individualis terlebih dahulu, maka sangat mungkin bagi individu itu untuk memiliki bahasa individual. Atau sebenarnya kepenyairan dan daya ucap itu tumbuh berbarengan. Atau keindividuan itu malah disumbang oleh proses penciptaan: pada mulanya mungkin eksplorasi gaya ucap yang menjadikannya berbeda dari bahasa umum, lalu gaya ucap itu membentuk pribadi penyair. Yang jelas, apa pun prosesnya, kepenyairan adalah kerja menjadi individu yang kesulitan mengucapkan keindividuannya. Tanpa modal ini, penyair tidak akan meneruskan kariernya lagi sebagaimana tampak pada beberapa teman saya yang dulu berbakat menulis puisi, tapi mereka kehilangan dinamika pencarian dan pelarian lagi, maka pensiunlah mereka sejak muda dan mungkin saja kini mereka sedang menyembah berhala kesamaan-kesamaan.
Apakah penyair muda macam Willy Fahmi Agiska mendapatkan kemudahan dengan puisi-puisi medsosnya yang memanfaatkan bahasa anak-anak milenial, khususnya bahasa yang tumbuh dan dipakai oleh anak-anak zamannya di Bandung? Saya kira tidak juga. Saya sering mengikuti puisi-puisi IG-nya dan semua itu merupakan ekspresi kesulitan dia dalam mengolah bahasa kekinian yang akrab dengan dia sendiri. Apakah Joko Pinurbo gampang membuat puisi-puisi encer? Tentu saja itu merupakan kesulitan Jokpin sehingga memilih yang encer-encer. Bahasa umum memang encer, tapi belum cukup encer buat Jokpin sehingga menggencerkan bahasa yang sudah encer itu perlu kerja keras lagi.
Munculnya puisi-puisi manterawi Sutardji Calzoum Bachri beberapa puluh tahun lalu adalah disebabkan gejala serupa8. Sutardji kesulitan dengan daya ucap puitik modern pasca Chairil Anwar sehingga ia mengambil mantera dan matera lama menyusahkannya juga sehingga jadilah mantera modern. Rendra pun begitu, ia mesti lari ke bahasa Indonesia yang sangat rumahan seakan bahasa remaja yang masih kemanja-manjaan kepada emaknya.
Dulu Agus R. Sarjono membuat puisi-puisi yang lebih kekanak-kanakkan lagi, benda-benda saling bicara seperti dalam animasi kartun, dan puisi seperti fabel benda-benda, dan pembaca dibuatnya untuk merasa jadi anak sekolah rendah yang sedang membaca dongeng pembangunan.
Hal serupa juga saya rasakan ketika pertama kali membaca Afrizal Malna, bukan saya yang pertama-tama kesulitan memahaminya, tetapi karena Afrizal sendirilah yang pertama-tama kesulitan mengucapkan diri. Dia adalah contoh paling representatif dalam kesulitan pengucapan itu. Pertama-tama adalah Afrizal, pertama-tama adalah Sapardi, pertama-tama adalah Sutardji, pertama-tama adalah Sarjono, pertama-tama adalah para penyairnya sendiri yang kesulitan, barulah saya atau pembaca lain yang kesulitan.
Jadi, setiap kita kesulitan memahami puisi, sadarlah memang penyairnya sendiri kesulitan! Dan itu artinya, kita pun ditantang untuk merasakan jadi seorang individu yang ternyata tidak mudah. Lebih mudah kita menjadi orang umum, berpikir umum, berbicara secara umum, dalam otoritas keumumam macam keselingkungan jurnal ilmiah itu. Lebih mudah kita jalan bersama di jalan raya kesamaan daripada jalan sendiri di jalan setapak kesulitan.
Dulu waktu saya S1, puisi-puisi Acep Zamzam Noor sangat disukai sejumlah teman dan sejumlah senior saya. Saya tidak yakin mereka suka karena mendapatkan kemudahan memahami puisi-puisi Acep. Karena itu yang mereka kenal bahkan hapal hanya beberapa yang menurut mereka mudah. Sisanya mereka tidak kenal karena sebagian besar puisi Acep menurut saya mengekspresikan kesulian tersebut.
Bahasa Acep secara umum di mata saya adalah bahasa yang malah kaku, formal, tertib aturan berbahasa, sedangkan ia sendiri adalah pelukis yang dalam lukisan-lukisannya lebih bebas. Saya heran juga mengapa Acep bisa bekerja dalam dua lapangan seni yang berbeda bentuk: satu tertib, satu bebas. Kenapa ia tidak membuat puisi-puisi yang sama bebasnya dengan lukisan-lukisan dia? Saya mengira justru menjadi tertib aturan dalam berbahasa adalah kesulitan tersendiri bagi Acep dan melukis yang tidak tertib adalah kesulitan tersendiri juga dalam urusan melukis. Intinya, jalan kuas atau jalan pena, kesulitan-kesulitanlah yang dipilih Acep.
Sebagai ilustrasi saya akan kisahkah salah satu penyair tidak penting berikut ini, dan mengapa ia termasuk penyair tidak penting. Dia mengklaim dirinya sebagai dokter spesialis literasi digital serta pemerhati ilmu multidisiplin macam bidang sel, teknologi nano, neurosains, neourologi (bahkan neurolinguistik); pernah bekerja di sebuah media online ternama di Indonesia; aktif di kelompok muda pemerhati kesehatan Indonesia; tersertifikasi CME Universitas Harvard, dan Universitas Oxford, ATLS, ACLS, ANLS, Hiperkes, Battra. Dia lulusan salah dua fakultas kedokteran di dua kampus ternama Indonesia. Menjadi delegasi riset serta pelatihan di beberapa negara seperti Italia dan Hungaria. Menjadi dokter di sebuah rumah sakit ternama. Dia juga mengarang buku-buku macam Empat Puluh Delapan Penyakit Syaraf, Seni Mengobati. Riset-risetnya dimuat di berbagai jurnal bereputasi internasional, dan inisiator Penyair Indonesia poetrynesia, bahkan dia adalah dokter yang juga aktif dalam forum Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI). Begitu banyak penghargaan dia terima sejak dia masih pelajar SMA. Memang dia adalah akademisi tulen. Ada sepuluh lembar biodata prestasi dia, dan saya tidak temukan media sastra atau media umum berkelas yang pernah memuat satu saja puisinya. Saya pun mengerti mengapa dia tidak pernah bisa menembus satu pun media sastra dengan puisi-puisinya itu, karena rupanya dia tidak memiliki keindividuan. Latar belakang akademiknya dengan segudang prestasi itu sampah belaka di mata saya ketika saya membaca puisi-puisinya. Ia berharap saya bisa membantunya mengirimkan puisi-puisi itu ke media terpandang. Tentu saja saya keberatan!
Puisi-puisinya tak lebih dari status galau orang-orang, refleksi biasa saja dan sangat umum, dan diwarnai nasehat serta kata mutiara atau quote yang juga umum. Kalau memakai pandangan Acep dalam kutipan di atas, orang ini tidak punya jalan setapak di atas bumi yang tulus, juga tidak mendapatkan kata-kata dari udara sehingga ia tidak bisa menciptakan menara kediriaan yang akan runtuh itu.
Setinggi apa pun menara akademik seseorang, ia tidak akan sampai menemukan dirinya sendiri jika ia tidak mengurus individualitasnya sendiri. Tentu akademisi tulen macam dia tidak mungkin bisa jadi penyair karena dia hidup dengan mengikuti bahasa yang berlaku umum atau selingkung. Akademisi perlu “selingkuh” berkali-kali ke dalam kedirian kalau mau jadi penyair.
Seorang dengan pengalaman sains kolektif tidak bisa dan tidak cukup menjadi penyair. Imuwan berkaliber internasional macam itu, di hadapan sejarah kesulitan pengucapan, rupanya hanya puing-puing berserakan dalam arti banyak ditemukan dan bukan runtuh karena dikapaki sendiri, tapi runtuh begitu saja! Ia tak punya masa depan dalam puisi, tak punya masa depan juga dalam kepribadiannya. (Kalau kita bicara kepribadian, adakah kepribadian kolektif?)
Karena itu, seorang Herwan FR bagi saya jauh lebih ber-Bhineka Tunggal Ika ketimbang dokter yang tadi saya contohkan. Seorang Willy Fahmi Agiska jauh lebih tinggi juga meskipun penghargaannya belum sampai satu halaman penuh. Mereka yang sering membangun menara dan sering merobohkannya, tentu termasuk kelas arsitek paling edan. Mana ada Firaun merobohkan bangunan-bangunan istananya sendiri. Mana ada Gustave Eiffel merobohkan menara Eiffel. Mana ada Sunan Kudus merobohkan menara masjid Kudusnya sendiri. Hanya penyair yang mendirikan menara kata-kata lalu merobohkannya, karena mereka hanya menginginkan dirinya sendiri yang tetap jadi menara individualistik itu, yakni menara yang tetap kesulitan dalam membangun menara-menara puisi berikutnya.
Yang bukan penyair mungkin yang sudah merasa jadi menara dan tak mungkin bisa roboh lagi. Firaun benar orang yang macam itu!***
—–
1 Subagio, Dan Kematian Makin Akrab, 1995, Jakarta: Grasindo, h. 12.
2 Kajian tentang kelisanan dalam pidato sangat komprehensif dalam kajian A. Teeuw, Indonesia Antara Kelisanan dan Keberaksaraan, 1994, Jakarta: Pustaka Jaya.
3Lihat puisi Acep Zamzam Noor “Cerita Buat Imana Tahira” dalam Bagian dari Kegembiraan, Tasikmalaya: Pustaka Azan, h. 18.
4 Semasa hidupnya ia menerbitkan buku Sebelum Senja Selesai: Kumpulan Puisi Pilihan 2001-1991 (Serang: Imaji Indonesia, 2002), kumpulan cerpen Sepasang Maut (Yogyakarta: Matahari, 2004), buku Kuntowijoyo: Karya dan Dunianya (Jakarta: Grasindo, 2007). Kumpulan esainya yang diterbitkan murid-muridnya setelah ia meninggal adalah Perjumpaan dengan Banten (Kubah Budaya, 2009), sedangkan buku antologi 76 penyair Berjalan ke Utara (ASAS UPI, 2009) adalah kumpulan puisi yang dipersembahkan kepada almarhum. Beberapa novel beliau tidak sempat terbit karena belum selesai. Sempat pula menulis naskah drama dengan Nandang Aradea, berjudul Teknologi Penjara (1999).
5 Peleburan Luka (1996) adalah kumpulan tunggal pertamanya, Domba Kata Padang Makna (2017), Semakin Senyap Semakin Mampu Mendengar (2018), serta dalam beberapa antologi bersama, dan mengarang juga rupa-rupa buku ajar sastra serta beberapa novel, selain esai-esai di berbagai media atau pengantar buku pengarang lain.
6 Sering juga terjadi, dokumen-dokumen dosen sastra dinilai oleh dosen teknik dan juga sebaliknya. Alasannya bukan kepatutan, tetapi kepangkatan.
7 Lihat filsafat cinta dan beda ini dari Alain Baudiou, Sanjungan Kepada Cinta, terj. Andreas Nova, 2020, Yogyakarta: Circa.
8 Mudah-mudahan istilah “manterawi” ini sama artinya dengan tidak benar-benar mantera, karena menurut Ajip Rosidi mantera itu tidak ditulis. Lihat dalam perdebatan Ajip dan Umar Junus dalam tema tipografi Sutardji dalam “Mantera dan Puisi yang Mantera” h. 275-294 buku Ajip Rosidi, Sastera dan Budaya: Kedaerahan dalam Keindonesiaan, 1995, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
*Penulis adalah dosen filsafat dan sastra di FKIP Untirta. Mengarang sejumlah buku teks, novel, kumpulan-kumpulan esai, cerpen, puisi-puisi berbahasa Indonesia dan Sunda, artikel-artikel ilmiah, dimuat di berbagai media ternama serta jurnal bereputasi.













terimakasih pak arip telah menulis ini, membuat saya berpikir lebih jauh ke dalam diri ini dan menimbulkan pertanyaan, sebenarnya individu yang menulis puisi yang hilang keindividualistikannya mereka menulis puisi atau hanya menulis kegundahan mereka atas segala hal yang membuat mereka gundah sehingga menjadi berhala kata-kata bagi mereka?
Terima kasih atas komentarnya. Dalam esai saya tersirat yg penting adalah individualisme.
Ulasan Pak Arip sungguh menggelitik…. sik asyik
A-ha! Senang bisa jumpa di sini, Sobat.