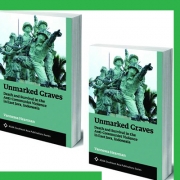Festival Tokyo 2012-2013, Sebuah Kenangan
Oleh Seno Joko Suyono
1
Sebuah lubang besar menganga di halaman Nishi Sugamo Factory,Tokyo 22 November 2012. Tanah-tanah bekas galian dibiarkan berserakan tak rapi. Karya itu bagian dari Festival Tokyo. Beberapa cangkul tergeletak di timbunan tanah. Lalu ada peti-peti kayu―seperti peti kemas yang dibiarkan bertumpuk di pinggir lubang. Saya dengan rasa ingin tahu mendekati galian tersebut. Saya ingat, waktu itu saya bersama Nandang Aradea (almarhum), sutradara teater dari Serang yang pernah belajar teater di Moskow dan saat itu juga hendak pentas di Festival Tokyo. Mulanya saya kira galian lobang itu bakal sebuah karya instalasi. Sebagai instalasi terlihat biasa saja.
Galian lobang yang pernah dibuat Semsar Siahaan di Taman Ismail Marzuki misalnya jauh lebih mencekam daripada galian lubang di halaman Nishi Sugamo Factory itu. Apalagi bila galian itu dibandingkan dengan karya seniman Perancis, Jean Michel Bruyere – tiga minggu sebelumnya, yang disajikan di Nishi Sugamo Factory juga. Di aula Nishi Sugamo Factory, Bruyere membangun sebuah tenda putih raksasa. Tenda itu bagaikan sebuah rumah sakit darurat. Bila kita masuk ke dalamnya –kita melihat berbagai peralatan medis canggih. Kita melihat beberapa aktor berpakaian dokter dan perawat tengah mengoperasi seorang pasien negro (yang juga aktor tentunya). Orang kulit hitam itu tergeletak telanjang di ranjang bedah. Ia hanya mengenakan cawat putih. Negro tua itu kurus kering. Matanya sayu. Sorot matanya nanap seakan sekarat.
Menyaksikan tatapan matanya yang mengenaskan, kita mendapat kesan bahwa sesungguhnya ia bukan pasien yang tengah diobati penyakitnya oleh para dokter Perancis itu tapi ia kelinci percobaan. Sebagaimana ditulis Michel Foucault dalam buku The Birth Clinic –prestasi-prestasi medis atau pencapaian-pencapaian ilmu kedokteran di Eropa sesungguhnya memiliki sejarah gelap. Banyak wawasan penyakit organ-organ dalam atau peningkatan pengetahuan kedokteran – didapat dari hasil eksprimen pembedahan terhadap mereka – para gelandangan, para tahanan, para orang gila – semua yang dikelompokkan “the other” dan berbeda dengan kelas menengah Eropa. Perfomance Bruyere secara kuat menyuarakan- wacana yang digulirkan Foucault itu serta menggemakan problem rasialisme, diskriminasi dan kolonialisasi yang tak henti-hentinya memetamorfosiskan diri pada zaman sekarang.
Dibandingkan dengan karya Bruyere, galian lobang itu sebagai sebuah karya instalasi terlihat asal-asalan dan tidak menyuarakan apa-apa. Ternyata saya salah kira. Galian itu bukan untuk sebuah karya instalasi tunggal. Galian itu ternyata bagian pertunjukan teater Green Pig Korea Selatan di Festival Tokyo berjudul: Step Memories-Return of the Oppressed―karya sutradara Hansol Yoon. Dan ternyata galian menganga yang sederhana itu bisa lebih tajam pesan sosialnya daripada karya Jean Michel Bruyere yang pasti memakan beaya “super mewah”.
Pertunjukan Teater Green Pig Krea Selatan berlangsung di salah satu ruangan Nishi Sugamo Factory. Sepenuhnya pentas berbahasa Korea yang saya tak mengerti. Tapi dari adegan-adegan awalnya penonton bisa meraba suasana yang diinginkan. Saya ingat mula-mula ada peti-peti kemas dibopong ke panggung. Para kru membuka peti itu dan ternyata di dalamnya terdapat sesosok tubuh yang dibelit oleh plastik. Segera – persoalan yang ingin disodorkan kelompok teater ini terasa. Tubuh-tubuh yang diikat di dalam peti-peti itu tentu metafora dari suatu tragedi politik di Korea Selatan suatu waktu. Tubuh-tubuh itu merupakan alegori dari korban-korban penangkapan politik yang pernah terjadi di Korea Selatan. Step-Memories Return of the Oppressed ternyata memang berkisah tentang ingatan-ingatan kelam perang saudara Korea. Konon tema ini waktu itu masih tabu dipertunjukan di Korea. Setelah adegan awal yang cukup menohok – saya meraba-raba maksud adegan demi adegan.
Titik dramatik pertunjukan menurut saya naik, saat adegan di dalam tiba-tiba mengaitkan adegan dengan lubang yang digali di luar – yang mulanya saya anggap biasa tersebut. Itu dimulai saat di sebuah adegan, seorang aktor perempuan tiba-tiba diseret keluar oleh serombongan aktor lelaki. Penonton terkejut. Bersamaan dengan itu secara paralel layar di dalam ruangan menampilkan adegan video lubang di luar yang saat itu juga kembali digali kedalamannya. Penonton secara refleks berusaha ingin keluar dari dalam ruangan – menuju lubang yang sedari pagi sudah ada di depan Nishi Sugamo Factory, melihat apa yang terjadi. Tapi para kru Teater Green Pig mencegah penonton berhamburan keluar. Pintu keluar ruangan ditutup rapat-rapat. Benar dugaan penonton. Perempuan itu ternyata dibawa ke lubang tadi dan dimasukkan ke dalam lubang. Lubang itu secara tak terduga dan amat mengagetkan – ternyata metafor dari sebuah ladang Killing field.
Dan di malam yang sangat dingin itu – para penonton dalam kegelapan ruangan menyaksikan layar menampilkan tayangan langsung dari luar para lelaki tanpa sepatah kata pun menyekop tanah – mengguyurkan tanah ke tubuh perempuan itu. Rambut perempuan itu penuh tanah. Perempuan itu seolah hendak dikubur hidup-hidup. Adegan itu menjadi menohok ,justru pertama, karena penonton – tahu adanya lubang itu sedari siang namun tak menduga bahwa lubang itu akan menjadi bagian dari adegan Killing Fields. Kedua, penonton secara ironis kemudian hanya bisa melihat “kekerasan” yang terjadi itu dari layar. Penonton seolah ditempatkan sebagai penyaksi yang tak berdaya. Lubang galian yang tadinya sama sekali tidak bermakna ―tiba-tiba menjadi bermakna keji sekali.
Adegan itu demikian membekas. Melihat adegan itu, pikiran saya saat itu segera melayang pada tragedi yang terjadi di tanah air. Saya ingat kebetulan, Majalah Tempo tempat saya bekerja, pada bulan Oktober 2012 baru saja menurunkan sebuah laporan khusus bertema: Algojo 1965. Ini berkenaan dengan pembantaian lebih satu juta jiwa orang-orang Partai Komunis Indonesia dan simpatisannya pada tahun 1965. Pada tahun 1965―terjadi peristiwa berdarah di Indonesia. 7 Jendral diculik dan dibunuh. Militer mengatakan pelakunya adalah Partai Komunis Indonesia. Luapan amarah terjadi di Jawa, Bali, Sumatra Sulawesi,Nusa Tenggara dan daerah lainnya. Dengan backing militer banyak organisasi-organisasi masyarakat melakukan pembalasan. Mereka mengejar dan membunuh anggota PKI.
Majalah Tempo berhasil mewawancarai para algojo atau orang-orang yang saat itu ikut terlibat dalam aksi pembunuhan. Waktu itu rata-rata umur mereka sudah 60-70 tahun. Mereka mengaku bagaimana terlibat dalam pencarian hampir setiap hari―hampir selama 6 bulan. Mereka mengenang para anggota PKI yang tertangkap akan digiring bersama-sama. Para anggota PKI tersebut disuruh berdiri berjejer dan kemudian satu persatu ditebas lehernya. Mayat mereka dilemparkan ke jurang, sungai atau lobang-lobang galian. Sampai sekarang para algojo tersebut tidak menyesal atas perbuatan sadis tersebut. Karena bagi mereka itu tugas negara. Mereka beranggapan bahwa komunis adalah ateis yang sangat membahayakan Indonesia. Sampai sekarang pemerintah Indonesia juga tidak mau meminta maaf kepada keluarga korban, karena menurut pemerintah pembantaian masal saat itu merupakan luapan spontan masyarakat atas kekejaman yang dilakukan oleh PKI sebelumnya. Baru-baru ini di Youtube saya juga melihat sebuah petilan dokumenter yang memilukan. Video itu penuh footage penangkapan ribuan para simpatisan PKI di Banyuwangi di tahun 1965 yang dilakukan oleh paramiliter yang dibentuk masyarakat bernama Gagak Hitam. Entah dibuat siapa video itu. Yang jelas nada narator malah terkesan bangga saat mengisahkan bagaimana Operasi Gagak Hitam mampu menangkap dan membunuh ribuan keluarga simpatisan PKI tanpa belas kasihan sampai ke akar-akarnya.
Sebuah pertunjukan – apa itu teater maupun tari dapat dikatakan berhasil, apabila pertunjukan itu mampu membawa penonton merefleksikan pengalaman yang dimiliki sendiri. Adegan bagaimana perempuan di atas dibenamkan ke lobang membawa saya merenung kembali bagaimana kekerasan terjadi di berbagai belahan Asia. Korea ternyata pernah mengalami tragedi yang sama dengan Indonesia. Adegan itu persis seperti yang diceritakan oleh algojo-algojo pembunuh PKI di Indonesia. Pertunjukan Hansol Yoon satu-satunya pertunjukan dalam Festival Tokyo yang bernafas politik kuat. Keberhasilannya, tapi adalah karena kemampuannya menyajikan tragedi politik itu dengan cara yang tak terduga.
2
Festival Tokyo – merupakan sebuah festival performing arts internasional tahunan di Tokyo – yang berpusat digedung Tokyo Metropolitan Theater kawasan Ikebukuro. Festival Tokyo dikenal sebagai sebuah festival yang sangat concern pada pencarian bentuk-bentuk baru ekspresi teater. Kuratorial Festival Tokyo beberapa tahun sebelum 2012 itu misalnya pernah secara berani memproklamirkan bahwa Festival Tokyo adalah sebuah festival yang dihasratkan mempertanyakan kembali esensi teater. Apa itu teater? Apa itu tari? Masih perlukah batas-batas antara tari, teater dan perfomance? Apakah masing-masing disiplin itu harus selalu punya identitas otonom yang bisa membedakan tegas satu sama lainnya? Apakah itu seni?
Festival ini artinya memberi kesempatan pada karya-karya teater maupun tari yang memiliki gagasan-gagasan yang unik dan radikal, baik dari segi keaktoran dan pemanggungan. Gagasan yang mempertanyakan bentuk-bentuk dan batas-batas teater yang mapan. Sampai di mana limitasi estetika teater? Festival ini mendorong seniman menggunakan ruang-ruang alternatif. Tidak hanya di gedung tapi juga di situs-situs spesifik, taman-taman atau bila pertunjukan di gedung la membuat desain yang tidak sebagaimana biasa.
Bahkan dalam kuratorial itu dinyatakan bahwa festival ini memberi peluang bagi pertunjukan yang membuat orang akan bingung apakah memang pertunjukan itu teater atau bukan. Artinya – sesungguhnya festival ini menempatkan diri sebagai laboratorium – bagi jenis-jenis karya yang berusaha mencari jalan-jalan baru yang belum dirambah. Itulah saya kira esensi avant garde. Festival ini menjadi tambah menarik karena porsi yang besar dipikulkan pada seniman Asia. Adalah menarik festival ini bertolak dari keyakinan bahwa gagasan-gagasan yang dimiliki teater Asia tak kalah memukau dan mengejutkan dibanding teater-teater di barat.
Saya ingat kuratorial Festival Tokyo pada 2012 itu berkaitan dengan tragedi Tsunami dan bocornya Pusat Tenaga Nuklir Fukushima. Saya berharap, ada banyak pementasan dengan keliaran-keliaran artistik saat merespon tema itu. Saya berharap akan menyaksikan pementasan yang lain daripada lain.Yang mengejutkan, yang tak terduga. Bila perlu sebuah pertunjukan yang meneror dan memiliki daya shocking tinggi.
Memang ekspetasi saya tidak sepenuhnya terpenuhi. Beberapa pertunjukan utama di Main Forum saya lihat tak begitu “mengganggu”. Pertunjukan Record of a Journey to Antigone, and its Perfomance dari Merebito Theater Company misalnya. Pertunjukan ini berlangsung di Nishi Sugamo Factory. Kelompok ini, serupa dengan Jean Michel Bruyere dan Hansol Yoon menggunakan beberapa ruangan. Kelompok ini sesuai judul pertunjukannya ingin memparalelkan korban Tsunami dengan Antigone ― yang menjadi korban dalam tragedi klasik Yunani. Tapi, yang jadi soal – dari keseluruhan pertunjukan itu saya sama sekali tak mendapat bayangan tentang Antigone tersebut. Dimana letak keparalelan itu? Sama sekali tak ada adegan yang mengindikasikan Antigone.
Saya ingat di lantai atas Nishi Sugamo, Merebito Theater menggunakan tiga ruangan bekas kelas. Kelas itu kosong. Penonton bisa duduk di bangku-bangku mana saja. Di tiap kelas ada sebuah tape. Tape itu kemudian menyuarakan kalimat-kalimat dan dialog-dialog dalam bahasa Jepang. Penonton duduk dan mendengar percakapan-percakapan dan kalimat-kalimat yang dibuat efeknya surrounding itu. Mereka yang tak memahami bahasa Jepang, bisa membaca terjemahan rekaman tersebut di sebuah meja yang disediakan.
Kalimat-kalimat itu berisi tentang kesaksian mata warga-warga Fukushima mulai nelayan, seorang gadis, seorang tua dan sebagainya. Tentang mobil yang terangkat air, tentang rumah yang terbenam, tentang anjing yang mati. Semua kalimat itu dideskripsikan secara setengah surealis. Seluruh kalaimat itu bertolak dari wawancara para anggota Merebito Theater dengan penduduk Fukushima yang selamat dari Tsunami. Terasa teater ini ingin memberi efek sensasi tragedi menjadi sesuatu yang puitis dan imajis. Tapi instalasi suara ini kurang begitu menghentak.
Itu berbeda dengan pertunjukan Jean Michele Buyere di Nishi Sugamo di atas. Selain membangun tenda rumah sakit di atas, dia juga menggunakan bekas ruangan dapur dan ruangan laboratorium. Begitu kita masuk ruangan dapur, kita tersentak karena ruangan itu penuh dengan uap-uap panas. Berbagai uap memancar. Mulai uap telur yang direbus di meja-meja sampai uap oven.
Bersamaan dengan itu kita melihat ada bermeter-meter gelembung-gelembung besar seperti gelembung ulat raksasa keluar masuk tak beraturan di seluruh sudut ruangan. Gelembung itu keluar dari cerobong, melingkar di meja-meja, membelit oven, tergeletak di lantai. Sementara begitu kita memasuki ruang laboratorium, kita disuguhi pemandangan menakjubkan. Seluruh wastafel, kran air, telephone, lonceng, bel, bergerak dan berbunyi sendiri. Kita seolah melihat pertunjukan musik benda-benda yang diorkestrasi oleh hantu. Berbagai kran mengucurkan air sendiri dengan tingkat pancuran yang berbeda-beda. Itu semua seperti komposisi. Betul-betul secara visual dan musikal mengagetkan.
Akan halnya pertunjukan Rechnictz (Der Wurgeengel) yang disutradarai Jossi Wieler di Tokyo Metropolitan Theater juga cukup memikat. Pentas ini salah satu yang paling diunggulkan di Festival Tokyo 2012. Jossi Wieler,yang dikenal sebagai sutradara opera menggunakan teks Elfriede Jelinek, sastrawan Austria pemenang nobel yang berkisah tentang pembantaian Yahudi di perang dunia 2. Tiga orang laki-laki dan dua wanita tampil di panggung bercerita tentang kesaksian mereka. Yang menarik adalah cara mereka memberikan kesaksian itu.
Mereka masing-masing duduk dengan latar belakang sebuah panil-panil pintu kayu. Menggunakan gaun dan jas malam yang anggun, mereka seolah bersiap untuk dinner. Satu persatu lalu bercerita. Percakapan begitu intim sampai mereka duduk di lantai bercakap hangat, minum,bergembira ria sampai lambat laun mereka melepas semua gaun dan jas mereka sampai hanya mengenakan pakaian dalam yang dekil. Dari tingkah laku yang aristokrat dan terdidik gaya mereka berubah menjadi kampungan, jorok serta liar. Mereka kemudian ada yang saling belai membelai, menjilat lengan, ada yang mekangkang memperlihatkan celana dalam dan sebagainya. Bersamaan dengan itu pintu-pintu di belakang mereka bisa berubah fungsi, bukan lagi sebuah pintu dari restauran kelas atas tapi menjadi bilik telepon, ruang penyimpanan mantel-mantel musim dingin sampai gudang baju-baju bekas. Kesan saya atas pertunjukan ini adalah – adalah pertunjukan ini berusaha menelanjangi moralitas lapisan-lapisan kelas menengah Eropa – yang di balik penampilannya yang civilized juga – seperti pernah dinyatakan Michel Foucault terinternalisasi suatu kesakitan dan ketidakwarasan.
Sementara untuk pertunjukan teater Jepang seperti the Absence of Neighbour Jimmy karya Okazaki Art Theater dan Word karya Takuya Murakawa, saya melihat ada kecenderungan untuk kembali ke sebuah teater bersahaja yang ekstrem. Saya menyebutnya dengan istilah “extreme realism” — sebuah usaha yang mengembalikan teater menjadi tak ubahnya akting dan percakapan biasa sehari-hari. Aktor tampil di panggung tanpa make up dan menyajikan cara akting tanpa dramatisisasi. Tak ada gerak, gesturkulasi dan moving yang dilebih-lebihkan sebagaimana misalnya kita sering lihat dalam pertunjukan Teater Koma atau pertunjukan-pertunjukan realis dari IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Tak ada percakapan dengan intonasi dan artikulasi yang diberat-beratkan, dilantang-lantangkan, atau dipanjang-panjangkan suku katanya.
Pertunjukan Word misalnya. Kita melihat dua orang laki dan perempuan bercakap seperti percakapan sehari-hari. Mereka tengah membicarakan pengalaman-pengalaman mereka menolong korban Tsunami. Lalu layar menampilkan slide-slide foto kenangan perjalanan mereka ke tempat yang terkena bencana. Cara mereka mengomong sangat bersahaja, seolah mereka bukan mengadakan pentas di panggung. Betapapun demikian efeknya terasa kita dibawa ke sebuah kenangan-kenangan realis yang menyakitkan. Dari slide-slide itu ada hal-hal yang yang tak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Pengaruh Hirata Oriza, pemikir teater Jepang yang terkenal dengan konsepnya “quiet theater”–sebuah konsep yang ingin mengembalikan akting pada kewajaran yang mendekati keseharian, mungkin besar di sini.
Dari berbagai pertunjukan itu saya menyaksikan di sana sini ada pemikiran untuk meninggalkan realisme konvensional. Dalam pertunjukan realisme biasanya aktor-aktor berusaha merepresentasikan suatu situasi dalam naskah. Aktor-aktor menjadi karakter lain selain dirinya. Aktor-aktor melakonkan suatu cerita fiksi. Aktor berpura-pura menjadi seorang tokoh. Pertunjukan-pertunjukan yang saya lihat cenderung anti representasi. Panggung tidak menampilkan suatu cerita. Aktor-aktor tidak menjadi karakter lain. Aktor-aktor tidak menjadi tokoh, si anu, atau si itu.
Yang mereka sajikan adalah sebuah teater yang makin mendekatkan diri pada tubuh seorang perfomer happening art ― yang biasanya menghadirkan kepada penonton tubuh mereka sendiri bukan tubuh orang lain. Tubuh mereka di panggung adalah tubuh saat itu juga, bukan tubuh fiktif. Saya melihat di sana sini ada usaha kelompok teater memperluas pemaknaan tentang realisme dengan cara masing-masing. Saya melihat berbagai usaha untuk memperluas realisme ini sebagai sebuah upaya eksplorasi post realisme.
Salah satu yang saya anggap paling mengguncangkan adalah pertunjukan Daisuke Miura: The Dream Castle. Pertunjukan ini menampilkan 8 orang pemuda dan pemudi yang tinggal bersama dalam sebuah apartemen. Apartemen mereka ditata tak ubahnya anak muda underground, penuh simbol-simbol perlawanan seperti Rasta dan juga ikon-ikon dunia anime dan komik. Pertunjukan berusaha menyajikan apa yang terjadi dalam apartemen itu sehari-hari, dari pagi sampai pagi lagi. Yang mereka lakukan minum bir, main game, berkelahi, cekcok dan melakukan seks. Seks, seks dan seks.
Adegan seks diperlihatkan secara blak-blakan. Orgy. Di sana sini delapan aktor, laki dan perempuan setengah telanjang, telanjang dada, telanjang bulat. Mereka saling bergelut. Berpindah dari tubuh satu ke tubuh lain. Kencing di toilet. Keluar lagi dan menindih lagi. Saling tumpuk menumpuk. Suasana demikian chaos. Setelah melakukan seks, bermain game, menyedu indomie, mabuk, berkelahi, berebutan remote control, muntah, kemudian melakukan senggama secara brutal. Kita diperlihatkan bagaimana tubuh diforsir habis untuk seks. Sampai tubuh tak berdaya,lunglai, tertidur,tapi tatkala bangun melakukan seks lagi. Adegan-adegan seks seluruh dilakukan secara realis.Kita bahkan melihat seorang aktor sampai muncrat spermanya dan seorang aktris sampai sqiurting –memencarkan air orgasme. Dan pertunjukan itu berlangsung selama 10 hari. Artinya setiap hari pasti terjadi demikian.
Menonton pertunjukan ini bisa jadi ada penonton yang shock. Jelas pertunjukan seperti ini di negara-negara Asia lain katakanlah di Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun Thailand sukar dipentaskan. Seorang pengamat teater asal asal Ukraina yang menonton pertunjukan ini mengatakan seandainya ini diundang ke Ukrainia pun pasti mengundang kontroversi.
Saya sendiri beberapa bulan sebelumnya, di Jakarta tepatnya di Teater Salihara menonton pertunjukan tari yang seluruh penarinya bugil. Pertunjukan itu karya Daniel Leveille Danse, koreografer dari Kanada berjudul: Amour,Acide et Noix. Tiga penari laki-laki, satu penari perempuan selama satu jam, mulai menit pertama masuk panggung dengan bugil. Wajah mereka tanpa ekspresi. Mereka membawa gerakan yang membuat seluruh gerak otot mereka, keringat yang mengucur, buah dada dan buah zakar mereka bergoyang saat tubuh menyajikan adegan-adegan balet yang membutuhkan ketrampilan gymnastik.
Pertunjukan itu meski bugil tapi tak mengguncang. Dan sama sekali tak membersitkan imajinasi erotis. Bahkan di beberapa adegan andaikata mereka menggunakan kostum juga tetap memberikan efek sama. Seorang kritikus bahkan dalam perbincangan setelah pertunjukan – mempertanyakan mengapa mereka harus bugil sepanjang pertunjukan. Hal ini yang menurut saya berbeda dengan pertunjukan The Dream Castle. Kita kaget keberanian para aktor melakukan adegan radikal serealis-realisnya. Saat sang aktris―sampai squirting— mengeluarkan air orgasme yang memancar jauh, suasana menjadi liar, kacau, anarkis, panik, emosi, kehausan seks yang tak habis-habisnya, erotisme yang penuh penyimpangan.
Pentas yang sama sekali tanpa dialog itu mampu membetot seluruh perasaan kita. Berbagai adegan terasa spontan, apa adanya, walau bagaimanapun kita tahu trik tetap ada. Bloking para pemain, keluar masuk aktor, posisi dan variasi persenggamaan, adegan coitus yang tidak diperlihatkan dari depan secara langsung-tapi menegangkan tentunya semua diatur oleh tangan dingin Daisuke Miura.
Keberhasilan pertunjukan itu bagi saya adalah karena ia mampu menggambarkan bagaimana sub kultur kehidupan anak muda Jepang. Bagaimana video game mendominasi anak muda. Tokyo misalnya menurut saya adalah Pachinko City. Dimana-mana, selama 24 jam, di sudut sudut Tokyo, tempat-tempat pachinko terang benderang dan selalu penuh penjudi. Tua muda melarikan diri dalam pachinko. Dalam The Dream Castle disajikan bagaimana, bermain game sama addictnya dengan bermain seks.
Realisme vugar sendiri bukan hal baru dalam sejarah estetika Jepang. Pertunjukan ini misalnya mengingatkan saya pada gambar-gambar shunga—cetak saring erotis ukiyo-e –dari zaman Edo dimana banyak digambarkan para samurai bersenggama dengan geisha dengan ukuran kelamin baik penis dan vagina divisualisasikan berlebih-lebihan.
Menonton pertunjukan itu juga mengingatkan saya pada tokoh Nagasawa dalam novel Haraki Murakami: Norwegian Wood. Nagasawa adalah mahasiswa cerdas berwajah tampan, yang terus menerus melakukan hubungan seks dengan berbagai perempuan yang tak dikenal yang ditemuinya di cafe. Tiap malam ia keluyuran di daerah Shinjiku, Shibuya atau pusat-pusat kehidupan malam Jepang. Di cafe ia mencari perempuan yang mau melakukan seks one stand night di hotel. Ia merasa hampa tapi tetap terus menerus melakukan hubungan seks, tanpa bisa menahannya. “Kalau kamu merasa hampa itu membuktikan kamu manusia normal dan itu menggembirakan. Terus menerus tidur dengan perempuan yang tidak dikenal tidak menghasilkan apa-apa. Yang didapat cuma rasa lelah dan benci pada diri sendiri.” kata Nagasawa.
Saya kira kalimat dari Nagasawa itu bisa mendeskripsikan suasana batin adegan terakhir dari pertunjukan The Dream Castle. Di penghujung pertunjukan seorang aktor, berdiri, tubuhnya sempoyongan, kontolnya lunglai. Teman-temannya lain bergelimpangan karena kelelahan melakukan seks. Ia mencari remote dan menyalakan sebuah channel televisi. Saat televisi menayangkan gambar bendera Jepang berkibar-kibar dan menyuarakan lagu kebangsaan Jepang Kimi Ga Yo,ia termangu dan menatap lama bendera Jepang tersebut. Ia terlihat masygul. Detik itu terasa tertangkap adanya perasaan hampa dari anak-anak muda liar tersebut. Betul-betul adegan itu sebuah ironi. Betul-betul sebuah kritik diri dan kritik sosial. Tapi disinilah letak kedasyatan karya ini. The Dream Castle adalah salah satu pertunjukan yang paling “menganggu” benak saya di Main Forum
***
Di samping pertunjukan-pertunjan di seksi utama, Festival Tokyo juga menggelar pertunjukan-pertunjukan yang disebut Emerging artist Progam. Pertunjukan ini dikompetisikan. Dan pesertanya adalah berbagai kelompok teater Asia yang dipilih dan diseleksi oleh Festival Tokyo berdasarkan ratusan aplikasi yang masuk. Juri dari kompetesi ini adalah berbagai kritikus teater senuor dari Asia mulai Jepang, Korea, Taiwan sampai Cina. Yang menarik pentas-pentas di Emerging artist Progam juga tidak kalah kuat dengan pertunjukan di Main Forum. Banyak gagasan-gagasan menggelitik bertebaran di seksi ini. Pertunjukan Gay Romeo karya Daniel Kok dari Singapura di Big Tree Theatre, Theatre Green adalah salah satunya (Daniel Kok saya ingat kemudian pada tahun 2016 memberikan workshop untuk Indonesia Dance Festival (IDF) di Malang). Ini betul-betul sebuah realisme yang menurut saya cerdas dan sangat jujur. Daniel kok, tampil seorang diri di panggung. Yang ia tampilkan bukan sebuah akting. Yang ia tampilkan adalah cerita mengenai dirinya sendiri.
Mula-mula ia menyebarkan puluhan buku kecil kepada penonton. Buku itu berisi catatan hariannya. Ia bercerita ia seorang gay. Baru-baru ini ia menjadi anggota dari situs gay bernama Gay Romeo di internet. Situs ini berbasis di Berlin. Kebetulan Daniel Kok tengah menjalani masa studi di Berlin. Situs Gay Romeo adalah situs kencan. Seorang gay bisa masuk, berteman dan berjanji untuk bertemu. Daniel menceritakan bagaimana ia bisa berkencan dan melakukan hubungan seks dengan 40 laki-laki. Setiap perasaan erotisnya terhadap masing-masing pria yang bersenggama dengannya dicatatnya dalam buku harian.
Buku harian itulah yang dibagikan ke penonton. Di panggung, Daniel duduk di sebuah meja. Ia membuka lap top dan menghadapkan layar lap topnya ke penonton. Di layar kemudian ia mengetik sebuah nomor. Ia kemudian menyuruh penonton membuka halaman buku hariannya sesuai dengan nomer yang dipencet di keyboardnya. Nomer yang dikeluarkannya tidak urut. Ia memberi kesempatan sekitar lima menit bagi penonton untuk membaca masing-masing halaman.
Sedari awal, maka Daniel menjadikan penonton bagian aktif dari pertunjukannya. Di tiap halaman penonton dapat membaca pengalaman dan fantasi Daniel yang berbeda terhadap masing-masing pria. Tulisan Dany puitis. Setiap pria diuraikan memiliki kekhasan masing-masing, mulai bau tubuhnya, besar kelaminnya, kemampuan komunikasinya, kemisteriusannya. Penonton dipaksa Daniel untuk menyelami insting-insting erotisnya. Selama penonton membaca halaman Daniel mempermainkan obyek-obyek kecil di meja, yang dibesarkan secara visual di layar. Saat penonton misalnya diminta membaca sebuah adegan persenggamaan, dia mengelupas sebuah bawang. Asosiasi antara bawang dan percintaan tak jelas tapi memberikan sensasi aneh.
Yang menarik kencan Daniel tidak berhenti di catatan harian. Daniel bahkan menjadikan penonton salah satu sasaran pencarian kencannya. Di tengah pertunjukan Daniel berdiri dan tiba-tiba menceritakan bahwa ia menemukan sebuah kemeja di kamar hotelnya. Kemeja itu masih sangat bersih. Ia ingin memberikan kemeja itu sebagai hadiah kepada penonton. Bila ada yang mau –Daniel menawari bertemu di sebuah cafe selepas pertunjukan, untuk sekedar mengobrol dan makan malam.
Pertunjukan Daniel maka dari itu adalah bukan semata-mata pertunjukan tapi sebuah peristiwa yang riil. Karena setelah pertunjukan mungkin saja ia mendapat teman kencan baru dari penonton dan mungkin bersenggama dengannya. Saya ingat Daniel Kok di atas panggung itu berkata: “Saya tahu sebagian penonton di sini tertarik pertunjukan saya dari sisi intelektual.Tapi juga saya tahu sebagian tertarik secara seksual.” Ia kemudian juga menampilkan bagaimana ia mengulur-ngulur sebuah benang, dan membelit-belitkan benang itu ke paha dan badannya. “Ada yang bisa bantu saya melepaskan benang ini?”tanyanya menggoda.
Di akhir pertunjukan, Daniel membuka bajunya. Ia telanjang dada, hanya menggunakan cawat. Tampak badannya yang atletis dan bagus. Di panggung itu ada sepancang tiang pol dance―tiang besi yang biasa digunakan para penari striptease di klub-klub malam. Tak terduga, Daniel mampu melakukan tari pol dance dengan ketrampilan luar biasa. Ia mampu melakukan posisi-posisi yang sulit semisal kepala di bawah dengan kaki yang hanya menempel pada tiang.
Tampak seluruh otot Daniel keluar. Keringatnya bercucuran membuat tubuhnya mengkilap. Ia tampak sengaja menampilkan keindahan, kejantanan tubuhnya. Bagi mayoritas penonton yang straight―tontonan ini membuat sadar bahwa ternyata vokabuler tari-tari kehidupan malam seperti striptease dapat menjadi sebuah materi pertunjukan kontemporer yang serius. Tapi bagi mereka yang gay tentu adegan itu sesuatu yang merangsang. Pertunjukan itu sendiri mampu membuat penonton melihat bagaimana dunia gay adalah dunia global. Dan bagaimana para gay terlibat dan memanfaatkan pergaulan internasional tersebut.
Pertunjukan menarik lain adalah Behind of Head karya Arata Mino. seorang fotografer dan modelnya. Di panggung kita melihat ada peralatan lampu dan background layar untuk pemotretan bergambar bunga-bunga. Seorang fotografer terlihat muncul dengan modelnya. Tapi pemotretan selalu gagal. Karya ini menampilkan hubungan antara fotografer dan model sesungguhnya adalah hubungan yang tidak mudah. Relasi antara fotografer dengan obyeknya sesungguhnya adalah relasi kuasa.
Menyaksikan pertunjukan ini tiba-tiba saya teringat bagaimana problem dunia fotografi seperti disinyalir Rolland Barthes atau Susan Sontag . Menurut Sontag mata kamera sesungguhnya adalah ibarat phallus. Karya-karya foto dari dunia fashion menurutnya banyak mengobjektivikasi perempuan. Karya-karya tersebut sering menempatkan tubuh wanita sebagai obyek voyeurisme. Para fotografer fashion bagi Sontag harus mulai melakukan inovasi-inovasi yang tak lagi menempatkan model dalam struktur hubungan voyeurisme.
Inti pertunjukan Behind of Head walhasil sesungguhnya mempertanyakan kamera sebagai medium. Hal yang sama juga disuguhkan oleh Soohyun Hwang dan Jeeae Lim, dua koreografer Korea. Mereka menyajikan pertunjukan berjudul: Co-Lab Berlin Seoul. Mereka berusaha merefleksikan fenomena Skype di internet. Skype, kita ketahui adalah media komunikasi melalui internet yang gratis. Orang bisa saling berkomunikasi antar negara dengan beaya murah dan bisa melihat langsung wajah orang yang diajak bicara melalui webcam. Co-Lab Berlin Seoul menyajikan kisah komunikasi via skype dua sahabat yang satu di Berlin dan yang satu di Seoul. Terjadi masalah apabila hubungan terganggu, putus komunikasi. Hal ini yang dieksplorasi. Pada dua pertunjukan ini dunia kamera dan webcam bukan digunakan sebagai alat bantu pertunjukan tapi justru obyek yang dipersoalkan.
Satu-satunya pementasan yang mengeksplor dunia arkaik dan disajikan di outdoor adalah pertunjukan Teater Studio Indonesia: Emergency. Emergency dipentaskan di Taman Ikebukuro yang disutradarai Nandang Aradea almarhum. 7 aktor TSI masing-masing membawa bambu-bambu. Di hadapan penonton mereka merakit-rakit bambu dan menyatukan bambu yang dipegang aktor satu dengan yang lain menjadi bentuk-bentuk tertentu. Ini sejenis teater kerja. Seluruh kerja dihadirkan terbuka kepada penonton. Mereka tidak berpura-pura bermain drama. Mereka tidak menyembunyikan proses. Dengan menggumamkan kalimat sakaroba sakarobi secara bersama-sama–yang artinya: Yang terjadi terjadilah (Kun fayakun dalam bahasa Sunda kuno) mereka membuat konstruksi-konstruksi bambu.
Bambu-bambu di tangan para aktor TSI bisa bermetaforsis dari bentuk segitiga sampai kuncup bunga. Saat bambu-bambu disatukan dengan sebuah poros membentuk sebuah jari-jari yang bisa diputar 180 derajat, pertunjukan merambah titik ketegangan. 6 orang aktor terlihat memutar dengan kencang jari-jari bambu itu, sementara seorang aktor bernama Otong Durahim berdiri di tengah poros. Bagai seorang pendeta ia memimpin seluruh kerjasama yang berbahaya itu. Gerak badannya berlawanan dengan arah putaran bambu.
Pada klimaksnya bambu-bambu tersebut bisa membentuk konstruksi serupa kincir angin atau baling-baling raksasa yang bisa digelindingkan dan bisa dinaiki. Otong akhirnya memanjat pucuk baling-baling itu. Ini adegan yang menggiriskan. Sekali terpeleset tubuhnya bisa babak belur. Dari ketinggian tubuh Otong berpegangan pada bambu-bambu kecil melorot ke bawah, membuat baling-baling itu berbalik menimbulkan bunyi gedubrak keras. Dengan pertunjukan ini TSI ingin memperlihatkan bagaimana tubuh-tubuh secara kolektif bekerja sama dalam menghadapi bencana, bagaimana tubuh-tubuh agraris mengantisipasi sesuatu yang tak terduga.
Yang mengkhawatirkan dari setiap pentas, potensi gagal selalu tinggi. Sedikit saja para aktor lengah dan tidak konsentrasi bambu-bambu bisa tidak tersambung ke dalam poros sehingga konstruksi ambyar. Daya tahan bambu juga tidak bisa diprediksi. Bambu-bambu bisa pecah dan retak saat dihentak terlalu keras. Berkali-kali melihat latihan TSI di markas mereka di kota Serang Banten, berkali-kali saya selalu cemas. Saat tiga kali menonton pertunjukan TSI di Taman Ikebukuro, saya juga masih merasa takut, was was ―jangan-jangan bambu patah, jangan-jangan poros kontruksi lepas ikatannya, jangan-jangan bambu penyangga yang dipegang Otong Durahim tak kuat, apalagi bambu di Jepang ukurannya lebih kecil daripada bambu di Indonesia dan digunakan selama tiga hari berturut-turut tanpa diganti .
Tapi di situlah justru letak dramaturgi pertunjukan. Tontonan ini menegangkan―karena kemungkinan konstruksi yang mereka susun bisa patah, runtuh, ambruk di hadapan penonton. Tontonan ini terasa memicu adrenalin karena ada kemungkinan gagal di tengah jalan. Bahkan bisa melukai para aktor atau membuat cedera penonton. Suasana Emergency bukan hanya hadir dalam diri para aktor tapi juga dirasakan penonton.
Akan halnya pertunjukan dari Cina A Madman’s Diary karya New Youth Group dengan sutradara Jianjun Li cukup sugestif. Pertunjukan ini diangkat dari novel terkenal sastrawan Cina Lu Hsun. Para aktor membawa batu-batu ke panggung. Batu-batu itu adalah idiom tengkorak-tengkorak manusia. Mereka kemudian mengangkat dan melempar-lempar batu itu ke panggung. Sesungguhnya pertunjukan itu bisa lebih memiliki energi bila lemparan-lemparan itu tak beraturan,kasar dan anarkis. Tapi adegan lempar melempar, tangkap menangkap batu itu terlalu hati-hati―mungkin karena adegan itu diperagakan di stage (dalam hal ini panggung Owlspot Theater―tempat mereka pentas). Menurut saya pertunjukan ini lebih bertaji bila dilakukan di outdoor. Pertunjukan di gedung menyebabkan kegilaan kurang liar. Kegilaan yang diekspresikan sang orang gila masih sebuah kegilaan yang tertib.
Dari 11 kelompok teater dan tari yang tampil di forum emerging artist, juri akhirnya menetapkan Teater Studio Indonesia sebagai pemenang. Mereka menganggap TSI mampu menampilkan sesuatu yang berbau ritual menjadi sesuatu avant garde. Tahun berikutnya – yaitu tahun 2013 Teater Studio Indonesia berhak tampil di forum utama. Nandang Aradea (almarhum) , sutradara Teater Studio Indonesia saat itu mengaku mendapat banyak pelajaran dari Festival Tokyo. Dalam perbincangan-perbincangan hingga larut malam dengan penulis di Sakura Hotel Ikebukuro – selepas menonton beberapa pertunjukan dan mengikuti forum diskusi – ia mengakui ada yang kurang dari pementasannya. Ia melihat para penonton hanya sebatas menikmati visual bambu yang berubah-ubah, tapi tak bisa memahami konteks sosial yang ditawarkan.
Untuk itulah November,2013 nanti ia membayangkan membawa sesuatu pertunjukan yang bertolak dari sejarah kongkrit. Ia berencana melakukan riset tentang katastropa Krakatau dan pelabuhan Karang Antu. Seperti kita ketahui , Krakatau –yang letaknya dekat Banten pernah meletus hebat pada abad 19. Letusannya sampai mempengaruhi iklim Asia. Sementara Karang Antu adalah pelabuhan tua di Serang. Pada abad 16, pelabuhan ini adalah pelabuhan internasional. Dahulu di sini kapal-kapal Portugis,spanyol,Belanda berlabuh mengangkut dan membawa lada putih Banten ke Eropa. Pada saat itu lada putih Banten adalah lada terbaik di dunia. Pasar lada Eropa dikuasai oleh lada banten.
Pelabuhan Karang Antu sekarang terbengkelai. Pelabuhan ini menjadi kampung nelayan miskin yang mengenaskan. Namun bila kita berdiri di sana, dan mengimajinasikan bagaimana masa lalu terjadi di pelabuhan tersebut,sisa-sisa kejayaan itu masih teraba. Ia juga merencanakan membawa lada―atau rempah-rempah lain dari Indonesia yang dahulu merajai Eropa. Rempah-rempah akan digunakan sebagai suatu medium terapi yang menenangkan sebuah chaos.Yang menarik gagasan Nandang ini disambut oleh Festival Tokyo. Mereka bahkan merencanakan –pentas Teater Serang ini akan menjadi Opening Festival Tokyo November 2013. TSI, tahun 2013 memang kembali pentas di Taman Ikebukuro Mereka membawa karya baru berjudul: Overdose. Mereka kembali datang tapi tanpa Nandang – karena dia meninggal di tengah latihan-latihan keras TSI.
3
Saya ingat temperatur melorot sampai 10 derajat celcius. Tokyo, awal November 2013 itu. Begitu menggigilkan. Warga Tokyo sendiri mengatakan suhu dingin datang lebih cepat dari jadwal tetapnya. Biasanya suhu yang menusuk baru terjadi pertengahan Desember. Dan puncak jekut berlangsung sekitar Februari . Namun untuk tahun 2013 itu, hawa beku sudah menyambangi Tokyo semenjak November. Agaknya di mana-mana terjadi kekacauan cuaca. Tak hanya di Jakarta – dimana hujan deras masih saja datang dan pergi di saat musim kemarau. Di Tokyo juga cuaca tak bisa diprediksi. Cuaca berubah-ubah secara ekstrem. Pagi, Tokyo bisa disinari cahaya lembut matahari, membuat badan agak hangat. Sore, temperatur bisa anjlok.
Saya ingat waktu itu, 13 November 2013 menjelang hari keempat pentas Teater Studio Indonesia Serang di Taman Ikebukuro, Tokyo. Otong Durahim, aktor senior TSI dan juga eks anggota Teater Payung Hitam yang bermukim di Seattle Amerika (dan khusus terlibat pementasan ini datang dari Seattle latihan di Serang) yang menjadi penata artistik TSI – mengumpulkan seluruh aktor lain di kamar hotelnya. Saya ingat ia mengatakan tubuhnya sudah mulai agak drop. Ia mulai melihat ada tanda-tanda gerak reflek tubuhnya makin kurang. Ia merasakan respon motoriknya mulai tak cepat .Seolah aliran darahnya macet. Dan itu bahaya.
“Saya tidak ingin terjadi kecelakaan di panggung.” katanya.
Ia mengusulkan agar, semua aktor menggunakan kostum ketat hitam-hitam seperti yang biasa dipakai latihan para penari balet. Itu gunanya setidaknya untuk menahan udara dingin. Masih ada waktu beberapa jam membeli kostum itu di Tobu―toserba Jepang- yang lokasinya tak jauh dari tempat pentas. Selama tiga pertunjukan sebelumnya sebagaimana latihan di Serang seluruh aktor telanjang dada.
Bagaimana perbedaan udara antara Serang dan Tokyo mempengaruhi tubuh aktor segera terlihat saat membandingkan tiga pertunjukan di Tokyo dengan latihan-latihan di Serang. Bila di Serang pada setiap latihan-latihan tubuh para aktor sampai terlihat mengeluarkan uap, akibat begitu “mendidihnya” tubuh mereka – di Tokyo, tubuh mereka sama sekali tak mengeluarkan asap. Bahkan saat udara dingin makin mencokot, keringat pun seolah mampet.
“Keringat seolah tak keluar,” kata Ade Ii, salah seorang aktor.
Mereka kemudian sepakat pertunjukan terakhir mengenakan kostum hitam –agar bisa mengurangi hawa dingin yang merasuk ke tubuh – betapapun itu memberikan image visual yang berbeda bagi para aktor.
“Kita utamakan keselamatan. Udara dingin sudah tak bisa dilawan.Kita jangan berpura-pura kuat dengan udara dingin.”tambah Otong.
Pertunjukan TSI memang sangat beresiko. Pertunjukan TSI: Overdose: Psycho-Catastrophe karya Nandang Aradea adalah pertunjukan outdoor. Enam orang aktor akan berinteraksi dalam sebuah konstruksi bambu. Tinggi bambu itu kurang lebih 10 meter. Bentuk konstruksi itu seperti kubah. Mereka memanjat, merayap, bergelantungan, lalu berdiri di puncak ketinggian. Mereka juga berayun dari satu bambu ke bambu lain.
Sebuah batang pohon kayu utuh digelantungkan di konstruksi itu. Aktor-aktor akan berdiri di atasnya dalam kondisi pohon itu bergoyang-goyang. Aktor juga mengayun-ayunkan batang pohon itu hingga batang itu berputar-putar liar membentur bambu-bambu. Semua adegan membutuhkan tenaga fisik dan stamina yang tinggi. Semua adegan membutuhkan tubuh yang memiliki daya keseimbangan, kesigapan dan kewaspadaan. Sekali lengah mereka bisa jatuh dari ketinggian. Sekali tertumbuk kayu mereka akan terluka. Sementara dalam MOU dengan pihak Festival Tokyo, telah ditandatangani bahwa panitia sama sekali tidak akan memberikan ganti rugi beaya apabila aktor-aktor mengalami kecelakaan saat pentas.Panitia tidak menyediakan asuransi bagi aktor.
Saya sendiri, saat melihat bagaimana konstruksi bambu mulai dibangun di Taman Ikebukuro mendadak merasa cemas dan khawatir. Ternyata konstruksi bambu yang didirikan di lapangan di Taman Ikebukuro tidak bisa persis sama bentuknya dengan yang biasa didirikan di tempat latihan sehari-hari. Konstruksi bambu di Taman Ikebukuro ternyata lebih tinggi. Itu dikarenakan karena panitia memberikan jatah luas ruang pendirian konstruksi hanya selebar 9 meter.Meski jauh-jauh hari kepada panitia Tokyo, TSI sudah meminta―seperti sebagaimana di Dalung,Serang lebar konstruksi adalah 10 meter, ternyata luas Taman Ikebukuro menurut panitia tidak memungkinan untuk itu.
Pengurangan ini membuat dampak posisi bambu menjadi lebih tegak, lurus ke atas. Karena kemiringannya berkurang, bambu akan lebih susah dipanjat. Butuh tenaga lebih banyak dan ekstra kehati-hatian. Kesan lurus makin terjadi karena kini konstruksi itu dibangun di tengah-tengah pemandangan gedung-gedung tinggi. Itu berbeda dengan di Dalung, Serang, konstruksi didirkan di tanah lapang yang panorama sekitarnya adalah semak-semak. Sekarang , dengan adanya pembanding ketinggian – berupa gedung-gedung tersebut, konstruksi terasa “lebih mengerikan” .
Untuk keamanan konstruksi, Abah Djatnika, ahli bambu yang mendampingi TSI di Tokyo menginstrusikan agar pada konstruksi ditambah palang dada. Abah adalah seorang yang sehari-hari bekerja melalukan pembibitan bambu. Ia memiliki berhektar-hektar tanah di Cibinong untuk pembibitan. Bambu-bambu yang digunakan TSI adalah bambu-bambu yang dikirim dari Cibinong. Abah maka hafal betul seluruh jenis bambu yang akan digunakan. Yang dimaksud Abah dengan palang dada, adalah pada tiap sisi tengah konstruksi ditambah diikat bambu panjang dari arah yang saling berlawanan. Palang dada menambah kesan bambu menjadi semakin memiliki sirip-sirip.
“Palang dada itu akan makin menambah kuat dan kokoh konstruksi. Itu untuk menahan atau menyangga apabila bambu bergoyang ke satu arah akan ditahan oleh palang itu. Tanpa palang kalau geraean keras dari satu sisi konstruksi berpotensi bisa doyong. Dengan palang ini ada gempa pun akan tahan,” kata Abah.
Problem konstruksi yang makin tinggi itu dari segi keamanan sudah teratasi. Udara dingin yang menjadi-jadi tapi kemudian membuat kondisi bambu menjadi seperti berembun. Bambu susah dipegang. Tangan tak bisa cekat memegang bambu. Kaki bisa melorot. Untuk ada ide agar bambu diampelas supaya bisa geret atau dibaluri madu agar tangan bisa melengket .
“Bambu menjadi licin, tangan bisa tergelincir saat menangkap bambu atau merambat bambu,” kata Dindin, aktor sekaligus stage manager.
Pada hari pertama pertunjukan, Dindin sesungguhnya akibat bambu yang licin itu mengalami suatu kecelakaan. Dari ketinggian sekitar empat meter,ia meloncat untuk menangkap bambu dan seharusnya bergelantungan. Namun tangannya mrucut, saat memegang. Ia jatuh ke lantai berupa rakit-rakit. Peristiwa itu tak terlihat oleh penonton yang duduk di sisi bersebrangan. Tapi penonton yang duduk di depannya langsung memekik.
Dindin secara reflek melakukan koprol. Penonton menahan nafas, menunggu apakah Dindin bisa bangun. Tapi mereka kemudian menyaksikan –secepat kilat Dindin bangkit dan kemudian segera balik menuju bambu dan cepat naik lagi sampai ketingghian 4 meter, mengulangi adegan dan untungnya sekarang bisa menangkap bambu-bambu kecil yang bergantungan. Penonton yang memekik sebelumnya sampai mengira adegan jatuh bangun Dindin adalah bagian dari dramaturgi pertunjukan. Sebenarnya ini adalah kecelakaan kedua yang dialami Dindin. Saat latihan di Dalung, Serang, pernah ia juga saat melorot bergantungan di bambu bambu karena kurang konsentrasi – ia jatuh Kepalanya membentur lantai. Waktu itu latihan dihentikan, karena Didin merasa kepalanya sangat pusing, berputar-putar. Belajar dari pengalaman latihan itu, maka terlihat saat di Tokyo ia jatuh, reflek tangannya melindungi kepalanya. Dan sigap ia bangkit, naik ke ketinggian dengan gesit.
Saya ingat di hari ketiga, ketika udara makin dingin tersebut juga terjadi peristiwa yang agak mendebarkan. Di tengah pertunjukan tiba-tiba Mang Uti, salah seorang aktor – tubuhnya tampak kaku. Ia tampak tak bisa bergerak. Seharusnya dalam adegan itu, ia harus menangkap batang bambu dan merambat ke atas. Tapi telapak kakinya seolah terlem di lantai. Penonton tak tahu apa yang terjadi.
“Tong, tolong dorong,”
Di pentas itu ,kami kru dari Indonesia, mendengar Mang Uti memanggil Otong.Ia meminta agar Otong mendorong tubuhnya agar bisa bergerak. Kejadian sekitar tiga menit itu mengagetkan. Untungnya aliran darah yang mampat di tubuh Mang Uti itu tidak berlangsung lama. Demikianlah, baik pertunjukan hari pertama, kedua, ketiga sampai keempat selalu mendebarkan. Namun sesungguhnya itulah bagian dari pentas, sebagaimana menonton pertunjukan di sebuah auditorium. Kekhawatiran, ketakutan, kewas wasan menjadi bagian dari pertunjukan.
“Ini pertunjukan yang sangat,sangat berbahaya,” kata Direktur Festival Tokyo, Chiaki Soma saat itu. Selama empat kali pertunjukan termasuk saat latihan ia setia menengok dan menyaksikan pentas Overdose. Orang nomer satu di festival Tokyo (sekarang sudah dganti oleh direktur lainnya) ini adalah orang yang berani memutuskan bahwa pertunjukan TSI layak untuk mengawali Festival Tokyo 2013. Betapun demikian karena konstruksi terlihat sangat tinggi ia awalnya sempat miris. “Saya tidak menyangka konstruksinya begitu tinggi. Rasanya lebih tinggi konstruksi di Serang yang saya lihat di foto-foto. Saya mulanya kaget sekali.”
***
Untuk sampai ke Jepang, pentas Overdose membutuhkan perjalanan panjang. Penuh haru biru. Hampir 8 bulan TSI mempersiapkan pertunjukan ini. Seluruh beaya proses dibeayai oleh pihak Festival Tokyo. Beaya terbesar adalah pengiriman bambu ke Jepang. Tahun lalu, untuk keperluan pementasan Emergency, bambu-bambu dibeli dari Jepang. Bambu-bambu di Jepang saat itu meski bisa digunakan, namun kenyataannya lebih kecil dan rapuh daripada yang tumbuh di Indonesia.
Demi keperluan Overdose, maka TSI memutuskan mengirim bambu dari Indonesia. Itu juga lantaran pertimbangan beaya. Diperkirakan beaya akan lebih murah jika dibanding membeli di Jepang. Apalagi tahun lalu, diluar dugaan untuk pembelian bambu di Jepang TSI terkena tambahan beaya pengangkutan. Total jendral TSI harus mengeluarkan beaya ekstra lebih dari Rp 50 juta. Sekarang jumlah bambu yang akan digunakan jauh lebih banyak. Bila untuk pentas Emergency hanya dibutuhkan puluhan bambu , kini dari Serang akan dikirim 200-an batang bambu panjang—baik bambu besar maupun kecil termasuk di antaranya bambu jenis betung,bambu gombong, bambu tali atau bambu apus, bambu ater. Proses shipping ini yang pastinya memerlukan beaya tinggi. Proses shipping ini akan ditanggung sepenuhnya oleh panitia.
Sudah sering teater-teater modern Indonesia pentas di Jepang.Teater Kubur misalnya pernah mementaskan karya On/Off di gedung Setagaya – sebuah gedung teater prestisius di Tokyo. Halim H.D pernah magang di sarang Black Tent pimpinan Makoto Sato. Teater Mandiri pernah dengan tafsiran bebasnya mementaskan naskah dramawan Singapura Kuo Pa Kun (almarhum) : The Coffin is to Big for the Hole di Tokyo tahun 2000. Juga naskahnya sendiri : War di forum Asia Meets Asia tahun 2001 di Kyoto dan Tokyo. Tahun 2000, sutradara Jepang Yoji Sakate dari Teater Rinkogun pernah membawa aktor-aktor Indonesia diantaranya Tony Broer (aktor Payung Hitam saat itu), Joko Bibit Santoso (teater Ruang Solo) dan sebagainya untuk berlatih beberapa bulan di Jepang mementaskan karyanya berjudul: Whalers in the South Sea. Naskah ini dibuat setelah melakukan riset tentang perburuan ikan paus di desa Lamalera,Flores.
Tahun 2013 itu beberapa bulan sebelum kedatangan TSI di Tokyo, Sardono W Kusumo juga pentas kolaborasi bersama komponis Toshi Tsuchitori. Tsuchitori dikenal luas dalam percaturan teater kontemporer dunia sebagai komponis yang selalu mendampingi pementasan-pementasan besar Peter Brook, termasuk: Mahabrata. Di Tokyo dan Kyoto, Sardono bereksprimen dengan cat dan kanvas. Ia menari―dan bagaikan Jakson Pollock ia menumpahkan, mencipratkan cat ke kanvas-kanvas, ia melukis dengan menari–sementara Tsuchitori merespon gerakan dan lelehan cat Sardono dengan berbagai perkusi Jepang. Sardono sendiri bukan sosok yang asing dalam pergaulan seniman kontemporer Jepang . Ia pernah melakukan perjalanan tari dari kuil ke kuil Jepang.
Pada bulan November itu, Yudhi Tajudin, sutradara Teater Garasi – juga terlibat pementasan internasional. Lebih dari sebulan ia tinggal di Shizuoka. Ia menyutradarai pertunjukan Das Gauklermarchen karya Michael Ende, dengan aktor-aktor Jepang. Pertunjukan ini ditaja oleh Shizuoka Performing Arts Center. Setelah selesai menggarap Das Gauklermarchen di Shizuoka ia pindah di Tokyo. Di Tokyo ia menjadi dramaturg bagi pementasan tari To Belong karya koreografer muda Jepang Akiko Kitamura .
Bambang Prihadi dari Teater Syahid Ciputat– pada saat bersamaan dengan kedatangan TSI di Tokyo terlibat dalam workshop Asian Performing Arts Festival. Lokasinya juga berada di Gedung Metropolitan Tokyo Theater yang menjadi tempat utama berlangsungnya Festival Tokyo. Workshop ini mempertemukan berbagai seniman teater Asia untuk membuat kolaborasi karya. Masing-masing kelompok workshop pada akhirnya merencanakan suatu pertunjukan yang akan dipresentasikan tahun depan. Dari mulai Teater Kubur sampai Bambang Prihadi terlihat semua diundang oleh kepanitiaan Festival yang berbeda-beda. Itu menandakan begitu banyaknya festival teater di Tokyo. Namun mungkin baru pertama kalinya ada pengalaman pentas outdoor dari sebuah teater Indonesia membuka sebuah festival di Jepang yang membawa bambu begitu banyak seperti TSI .
Saya melihat ide dasar Overdose adalah melanjutkan ide pertunjukan: Emergency yang pernah dipentaskan di Taman Ikebukuro. Baik Emergency maupun Overdose menggambarkan sebuah situasi darurat, situasi genting yang dicoba diatasi secara kolektif. Bambu sendiri adalah suatu metafor bagi suatu tubuh liat yang memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap ancaman bencana. Di Emergency, sepanjang adegan aktor-aktor bekerja membuat konstruksi kecil. Bambu dari sebatang disusun-susun, disambung-sambung menjadi berbagai variasi.
Di setiap variasi, bambu dibanting, diputar, diinjak-injak, sampai akhirnya bambu membentuk suatu konstruksi besar yang bisa mengancam para aktor. Bambu menggelinding menerjang dan kemudian berhasil dijinakkan bersama. Secara keseluruhan diperlihatkan betapapun koyak moyaknya konstruksi-konstruksi, bambu tak pernah patah. Nandang ingin meneruskan ide keliatan bambu dan paralelitasnya dengan tubuh ini. Dalam Overdose, Nandang ingin menggunakan bambu-bambu panjang –wungkul yang tak dipotong-potong. Bambu di sini menjadi metafora bagi suatu tubuh yang kokoh dalam suasana chaos atau situasi katrastrope.
Saya ingat tatkala di Jepang tahun lalu itu, almarhum Nandang suka mendengar kisah-kisah mengenai Tsunami yang melanda Jepang dan kebocoran Pusat Tenaga Nuklir Fukushima. Warga Tokyo banyak memperbincangkan kemungkinan-kemungkinan efek radiasi yang belum terlihat sekarang. Bisa jadi efek radiasi baru bisa beberapa tahun kemudian. Satu hal yang menarik bagi Nandang adalah mereka tidak larut dalam kecemasan. Sebaliknya, hidup mereka penuh antisipasi-antisipasi. Nandang memperoleh cerita bagaimana saat tragedi Tsunami tersebut terjadi surat-surat kabar dan televisi-televisi di Jepang misalnya tidak menambah kepanikan.
Dengan tenang siaran-siaran mereka banyak menayangkan tahapan-tahapan penyelamatan dan informasi-informasi berguna kepada publik tentang bagaimana menolong korban bencana. Itu berbeda dengan di Indonesia saat Tsunami di Aceh terjadi. Yang dimunculkan televisi-televisi kita sangat melodramatik. Pernyataan duka cita dan belasungkawa disertai lagu-lagu Ebiet G Ade yang menyedihkan terus menerus disiarkan. Berita-berita kunjungan pejabat dan sukarelawan-sukarelawan di-blow up habis-habisan. Jarang disiarkan hal-hal berupa info praktis yang dapat membantu eksvakasi secara efektif. Misalnya bagaimana membuat kantong-kantong mayat darurat. Atau bagaimana langkah-langkah membuat wifi agar saluran komunikasi di lokasi bencana tak putus. Walhasil siaran televisi memperpanjang kepanikan dan ketidakmenentuan. Kultur kita masih sebatas kultur reaksioner bukan kultur yang antisipatif.
Salah satu pengalaman mengesankan almarhum Nandang saat di Jepang adalah juga pernah suatu waktu ia menonton teater dan tiba-tiba di tengah pertunjukan terjadi gempa. Kita tahu Jepang sering kali dilanda gempa-gempa kecil. Waktu itu kami tengah menonton pertunjukan teater sebuah kelompok dari Taiwan bernama Against again Trope. Kelompok ini salah satu peserta Festival Tokyo 2012. Mereka membawakan lakon berjudul: American Dream Factory dengan sutradara Szenung Hang. Lokasi pementasan adalah digedung Box in Box Theater. Saya ingat tempat pertunjukan ada di lantai lima. Tiba-tiba di tengah pertunjukan terasa ada gempa. Goyangannya cukup kuat. Saya melihat aktor yang berada di panggung juga terkesiap. Ia sampai berhenti mengucapkan kata-kata. Saya dan Nandang (alnarhum) yang kebetulan duduk di barisan belakang, mencoba melihat pintu dan berinisiatif hendak keluar. Namun anehnya, penonton Jepang semuanya terlihat tenang. Mereka sama sekali tidak panik. Mereka percaya gedung tahan gempa. Dan memang gedung-gedung di Tokyo dalam pembangunanya harus memenuhi kriteria tahan gempa .
Di Serang, sepulang dari Tokyo, almarhum Nandang membaca buku Krakatau karangan Simon Winchester dan buku Syair Lampung Karam—yang merupakan sebuah dokumen kesaksian seorang pribumi saat meletusnya Krakatau. Krakatau kita tahu meletus pada jam sepuluh pagi hari Senin, 27 Agustus 1883. Ledakan Krakatau bisa disebut peristiwa vulkanik paling meluluh lantakkan dalam sejarah modern manusia. Ledakan Krakatau adalah ledakan terbesar kelima setelah: letusan Gunung Toba, Gunung Tambora, Gunung Taupo di Selandia Baru dan Gunung Katmai di Alaska. Saat Krakatau meletus, terjadi gelombang raksasa yang menghancur leburkan wilayah Anyer, Merak, Banten. Menewaskan ribuan orang. Efeknya juga sampai membuat awan gelap menyelubungi Eropa.
Dari pembacaan ini, gagasan almarhum Nandang tentang katastrope meletik. Ia membayangkan membuat suatu kontruksi bambu yang memuat unsur- unsur ketinggian, untuk memetaforkan gunung.Sekaligus ada unsur-unsur air yang memetaforkan laut. Nandang selalu tertarik dengan kemungkinan-kemungkinan ruang. Karya-karyanya selalu berusaha membebaskan teater dari panggung konvensional. Nandang yang pernah kuliah teater di Rusia tertarik dengan ide-ide konstrukvisme yang muncul di Rusia pada awal abad 20 .
Konstrukvisme adalah suatu gerakan yang mulanya timbul dari kalangan pematung seperti Alexander Rodchenko dan Vladimir Tatlin yang penemuannya banyak menginspirasikan kalangan teater untuk membangun sebuah set stage yang berbeda dengan tipe auditorium.Rodchenko dan Tatlin membuat karya patung yang tak lazim. Karyanya berbentuk konstruksi-konstruksi geometrik yang melingkar-lingkar tak beraturan. Ini menginspirasikan kalangan teater seperti Meyerhold untuk menciptakan bentuk panggung berupa set geometrik tiga dimensi yang muskil-muskil – dimana di dalamnya aktor akan menyajikan pengalaman tubuh lain dibanding bila bermain di atas panggung polos auditorium.
Almarhum Nandang berniat membangun sebuah set besar dari bambu lengkap dengan tempat duduknya. Di dalam set itu – ia merencanakan akan menampilkan sebuah pertunjukan physical teather –yang intinya mengetengahkan bagaimana manusia bisa mengantispasi situasi yang chaos. Dramaturginya bertolak dari bayangan mengenai situasi katastrope yang menurutnya penuh intervensi-intervensi kejutan. Teater Nandang adalah teater tanpa dialog. Tidak ada naskah tertulis. Teaternya sepenuhnya bertumpu pada tubuh aktor yang saling berinteraksi memunculkan imaji-imaji. Nandang juga ingin mengembangkan suatu jenis teater objek. Aktor-aktornya berinteraksi dengan objek tertentu. Pada Emergency, misalnya batang-batang bambu adalah objek mati yang oleh aktor dicoba dihidupkan menjadi serangkaian imaji yang terus berubah seperti roda, kincir, kelopak bunga dan sebagainya.
Untuk membangun set Overdose, mulanya almarhum Nandang mencoba menghubungi beberapa arsitek untuk mendapat masukan. Banyak gagasan set yang terlintas. Salah satunya adalah membayangkan set bagaikan suatu kerangka perahu. Suatu tulang punggung yang memiliki sirip-sirip. Sirip-sirip akan menjadi tempat duduk. Dan struktur tulang punggungnya akan menjadi tempat aktor melakukan perfomance.Tapi yang demikian itu membutuhkan sebuah poros las besi yang kuat yang beayanya sangat mahal. Akhirnya, direktur artistik Otong membuat contoh berbagai maket set. Setelah melalui serangkaian diskusi , maket konstruksi- berupa semacam segitiga kubah –yang makin meininggi ,sampai bagian paling ujung sekitar 10 meter dipilih. Di kubah itu akan ada bambu-bambu yang bergantungan. Dari situ aktor-aktor akan turun melorot dan memanjat. Batang-batang bambu itu nantinya akan seperti akar-akar sebuah pohon. Tentu dibutuhkan suatu teknik ikatan tertentu yang kuat,agar bambu itu tidak lepas saat dipakai bergelayutan oleh aktor. Itu tantangannya.
Saya melihat, proses merealisasikan Overdose maka dari itu sama sekali berbeda tahapan-tahapannya dengan proses teater pada umumnya. Bila proses latihan teater pada umumnya dimulai dengan mempelajari naskah, lalu kemudian dilanjutkan dengan latihan membaca, maka proses Overdose diawali dengan riset di hutan-hutan bambu. Teater tidak bertolak dari naskah baku. Adegan demi adegan nanti baru akan dicari setelah konstruksi selesai. Maka yang pertama-tama dilakukan adalah mewujudkan konstruksi. Para aktre melakukan riset di hutan bambu Ciwidey untuk melihat jenis-jenis bambu. Di hutan bambu Ciwidey, Bandung pertama kali saya melihat maket itu diwujudkan meski hanya separuh. Beberapa aktor untuk keperluan ini, sampai ikut menebang bambu.Seluruh ikatan konstruksi menggunakan ijuk dan kawat. Sama sekali tanpa paku.
Tahap selanjutnya setelah konstruksi selesai adalah mencari rangka sebuah perahu betulan. Rangka itu nantinya akan digantung di konstrukis. Perahu itu akan menjadi objek yang akan dimain-mainkan aktor. Ia akan menjadi metafor bagi kapal-kapal yang tergulung dan terombang ambing saat dihantam Tsunami yang diakibatkan ledakan Krakatau. Perahu itu akan menjadi “aktor tamu”. Ia akan menjadi makhluk hidup. Anggota teater mencari perahu lapuk di pelabuhan Karang Serang dan pelabuhan Merak .Perahu atau sampan-sampan tua yang sudah dicampakkan. Sampan yang sudah bolong-bolong sama sini, koyak moyak ,karatan, bulukan. Sampan-sampan rusak yang sudah terendam air puluhan tahun.
Tapi di tengah pencarian itu, ide almarhum Nandang berubah. Menurutnya ide mengusung perahu itu terlalu verbal. Ide perahu itu diganti oleh Nandang dengan ide menggantung sebatang pohon utuh. Betul-betul sebatang pohon besar. Itu yang nanti menjadi obyek yang akan dihidupkan. Kayu itu nantinya akan diliarkan oleh para aktor. Para anggota TSI kemudian mencari sebuah kayu besar lengkap dengan batang-batang kecilnya di sekitar markas teater di Dalung, Serang. Mereka sendiri yang kemudian menebang.
“Batang pohon akan lebih imajinatif. Bisa menjadi perahu. Bisa menjadi apa saja. Fantasi penonton bisa kemana-mana,” saya ingat Nandang mengatakan demikian.
Satu hal yang gila sesungguhnya, adalah gagasan almarhu Nandang bahwa tempat duduk yang berada di kiri dan kanan konstruksi bisa bergerak-gerak mengikuti dinamika aktor. Sedari awal seluruhnya konstruksi adalah terbuat bambu, termasuk tempat duduk penonton. Tempat duduk penonton dibuat menyambung dengan konstruksi. Seluruh pergerakan para aktor memanjat, menuruni, bergelantungan di bambu dan berjalan di bambu akan bisa dirasakan oleh penonton. Apalagi jika para aktor sengaja membuat adegan menggoyang-goyang konstruksi. Atau para aktor memutar-mutar batang pohon dan membentur-benturkannya keras ke tiang-tiang bambu, tentu tempat duduk penonton akan semakin berderak derik .
Teater Nandang memang didesain untuk melibatkan emosi penonton. Bahkan direncanakan suatu alat yang bisa merekam kecemasan penonton. Alat itu berupa kamera tersembunyi – yang bisa merekam segala, ekspresi kekhawatiran penpnton. Kecemasan penonton yang masuk ke kamera ini kemudian akan diolah dan disalurkan ke cahaya membentuk permainan-permainan pola. Cahaya ini nanti di sorotkan ke genangan air yang ada di dalam konstruksi. Jadi sesungguhnya di samping menyaktikan para aktor, penonton juga akan melihat pantulan emosinya sendiri.
Tapi ide radikal ini tak terjadi. Tatkala pihak panitia Festival Tokyo mengirim Koordinator Produksi Aya Komori dan Technical Director Eiji Torakawa ke Serang untuk mengecek persiapan, mereka mengatakan, gagasan tempat duduk yang bisa menggeliat-geliut itu sangat berbahaya. Jelas gagasan tersebut tak akan diijinkan oleh pemerintah kota Tokyo yang mendanai festival. Yang menjadi ukuran pertama pemerintah kota selalu adalah pertimbangan keselamatan penonton. Direktur Teknis festival Tokyo Eiji Torakawa mengatakan untuk tempat duduk mereka telah menyiapkan tempat duduk knock down dari besi yang sudah menjadi standart untuk tempat menonton di ruang publik. Secara bentuk tempat duduk besi itu bisa diatur menyesuaikan dengan konstruksi. Dengan agak bercanda, Tora San mengatakan: “Saya akan sedikit loskan mur dan bautnya agar tempat duduk bisa bergoyang-goyang.”
Kedatangan dua elite Festival Tokyo itu sendiri menunjukkan bagaimana seriusnya mereka memantau persiapan TSI. Menurut Aya dan Tora ini baru pertama kalinya festival Tokyo mengirim orang ke luar negri untuk melihat persiapan teater yang hendak tampil di pembukaan. Sebelum-sebelumnya hal seperti itu tak pernah terpikirkan oleh mereka. Menurut mereka, kasus TSI ini bisa menjadi preseden yang baik untuk pertunjukan-pertunjukan teater luar lainnya yang bakal manggung mengawali Festival Tokyo. Sebab dengan kunjungan panitia langsung ke lapangan bisa dipahami kesulitan-kesulitan kongkrit yang dihadapi teater tersebut. Serta juga bisa diprediksi anggaran yang dibutuhkan.
Selama di Serang, Aya dan Tora sampai dibawa oleh anggota TSI ke Cibinong dan Ciwidey, dua hutan bambu yang menjadi tempat latihan TSI. Jarak yang jauh antara Serang ke Ciwidey lalu ke Cibinong membuat mereka mengerti bahwa proses latihan tak biasa. Bahwa proses latihan menguras energi dan membutuhkan beaya yang tak sedikit. Mereka bahkan diajak untuk melihat bagaimana bambu-bambu bakal dipotong. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana seluruh pekerjaan berat dilakukan oleh anggota teater sendiri.
Saya ingat, latihan intens almarhum Nandang dan kawan-kawan dimulai pada bulan Agustus, saat bulan telah memasuki puasa. Aktor-aktor latihan setelah Isya sampai Subuh . Aktor-aktor TSI sama sekali tak memiliki latar belakang dunia akrobat atau dunia sirkus. Mereka belajar sendiri cara untuk naik turun bambu. Mula-mula pergerakan badan mereka tampak lambat, tapi kemudian bisa turun naik dengan cepat dan tangkas. Bahwa banyak aktor yang merasakan tubuhnya lebam-lebam dan tangan lecet-lecet, itu tak terelakkan . Berbeda dengan Emergency yang masih menggunakan dua aktor peremopuan, proses Overdose sama sekali tak melibatkan aktor perempuan.
Seraya mencari dramaturgi, dari hari ke hari para anggota TSI juga memperbaiki teknik naik dan turun sehingga aman. Bagaimana teknik tangan saat mencengkram bambu dan bagaimana posisi kaki saat melorot. Mulanya diagendakan ada sebuah workshop khusus cara memanjat bambu yang cepat dan aman. Nandang merencanakan mendatangkan para pemain akrobat Laies. Laies adalah akrobat tradisional yang berkembang di daerah Jawa Barat. Seorang pemain Laies sanggup melakukan adegan berbahaya berjalan meniti tali yang direntangkan di atas dua buah batang bambu setinggi lebih 10 meteran. Di ketinggian itu seoarang aktor bisa seperti berjumpalitan menggayut-gayut di tali. Kelompok-kelompok Laies sering ditemui di derah Tasikmalaya, Cirebon, Cilacap atau Ciamis. Nandang bahkan memiliki gagasan mengajak satu orang anggota Laies menjadi aktor yang akan berangkat ke Tokyo.
Almarhum Nandang kemudian berusaha mensurvei kelompok-kelompok Laies ini. Ia akhirnya bertemu dengan salah satu kelompok Laies. Ia mengutarakan keinginannya agar mereka memberi workshop memanjat dan ia juga mengungkapkan idenya meminjam satu anggota Laies untuk keperluan pentas di Tokyo. Namun ternyata kelompok ini menolak memberikan latihan, karena mereka mengaku selama ini mereka menggunakan magic saat menampilkan atraksi. Mereka juga mengatakan tidak bisa meminnjamkan satu orang anggotanya untuk latihan teater. Bila berangkat ke Jepang harus berangkat keseluruhan satu kelompok. Ide untuk melibatkan Laies akhirnya gagal.
Sudah bisa dibayangkan karena latihan yang keras banyak aktor yang tak kuat. Beberapa aktor mengundurkan diri. Formasi aktor maka dari itu berganti-ganti. Sampai kemudian diantaranya Nandang melibatkan Mabsuti atau biasa dipanggil Pak Utik . Mabsuti sehari-hari berprofesi sebagai nelayan di Serang. Ia sama sekali tak pernah bermain teater. Nandang tertarik dengan Mabsuti, karena tubuh Mabsuti sehari-hari biasa menghadapi ombak dan gelombang ganas. Ia tangkas naik tiang-tiang perahu, ia juga biasa menarik tambang, menebarkan jala. Itu semua ketrampilan tubuh yang dibutuhkan dalam pertunjukan. Mabsuti akhirnya meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan selama 3 bulan untuk ikut dalam latihan.
Aktor terakhir yang masuk latihan menjelang 2 bulan keberangkatan ke Tokyo adalah Godi Suwarna. Bekas aktor Studi teater Klub Bandung ini akan menjadi seorang yang akan melantunkan mantra-mantra. Pada ujung konstruksi itu akan digantung sebuah gong besar. Gong yang dibuat sendiri oleh anak-anak TSI ini bentuknya meniru—gong kabuyutan, gong sakral yang dimiliki tempat-tempat ziarah atau petilasan-petilasan di dusun-dusun Jawa Barat. Godi akan mengusap-usap gong, mendaras mantra dan memukul gong pada titik-titik tertentu adegan. Godi akan memberikan suasana ritual pada pertunjukan. Godi yang akan menggiring adegan-adegan yang penuh chaos menuju suasana ruwatan. Godi bercerita di desanya di Ciamis—saat masa kecil ia sering ingat betapa gong selalu ditutupi oleh kain putih karena dianggap suci. Masuknya Godi membuat formasi final Overdose adalah: Otong Durahim, Ade ii Syarifudin, Hendra Setiawan, Mabsuti, Dindin Saprudin, Godi Suwarna.
Betapapun Godi sudah masuk, struktur dramaturgi tidak langsung jadi. Dalam dua bulan ide-ide justru makin deras keluar. Di dalam konstruksi misalnya mulanya tidak ada rakit. Lantai dasar konstruksi direncanakan akan digenangi air. Lantai dasarnya seperti sebuah kolam. Pada saat latihan di Serang, unsur air itu belum bisa dicoba, lantaran sungai yang berada di dekat sanggar airnya tengah kering. Padahal kru TSI telah menyiapkan selang panjang untuk menyedot air dari sungai .Pihak panitia di Jepang akan tetapi menyanggupi unsur air ini. Mereka akan menyalurkan air dari kran-kran. Air bahkan dikatakan akan mengalir terus. Berita ini membuat Nandang berpikir menambah properti konstruksi dengan rakit yang mengambang. Rakit yang bisa diangkat dan dijatuhkan ke air sehingga airnya bisa menciprat dan meneror penonton .
Juga mulanya tidak ada pikiran membuat jaring atau jala. Namun ide ini muncul , saat melihat batang kayu yang saat diputar-putar liar ternyta menjorok-jorok masuk ke penonton terdepan dan itu bisa membahayakan penonton. Jaring itu fungsinya sebagai pengaman. Saat adegan “kayu mengamuk” jaring akan diluncurkan dari atas menutupi kedua sisi konstruksi. Almarhum Nandang meminta aktor membuat jala dari kulit kayu. Sesungguhnya aktor bisa mencari jala nelayan betulan, namun Nandang menginginkan agar ada asosiasi dengan batang pohon- jala dibuat dari kulit kayu. Muncul juga gagasan Godi menggunakan topeng merah Cirebonan yang mengekspresikan unsur kemarahan. Saat adegan kayu chaos, Godi akan mengenakan topeng itu. Dan setelah aktor mampu menjinakan kayu, ia direncanakan melarung topeng. Topeng dibuang ke air. Pertanda meredam segala bencana.
Sebulan menjelang keberangkatan ke Tokyo, dramaturgi baru benar-benar ketemu. Almarhum Nandang tampak lega dramaturgi telah terlihat strukturnya. Para aktor tinggal melatih detail-detail. Namun tiga minggu menjelang keberangkatan itu sebuah musibah besar terjadi. Di tengah perasaan senangnya melihat dramaturgi yang sudah jelas, Nandang, mendadak meninggal dunia. Malam itu, sehabis latihan, ia tidur di sanggar dan tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Selama ini menderita gagal ginjal. Dua kali dalam seminggu sekali cuci ginjal atau membersihkan ginjalnya di Rumah sakit di Bandung. Ia bolak balik Serang-Bandung. Tatkala mengalami kejang-kejang tersebut pembuluh darah di otaknya pecah.Setelah diinfus selama tiga hari di rumah sakit Serang, ia meninggal. Darah kata dokter menggenangi otaknya. Semua aktor panik. Mereka kemudian mensholatkan jenasah Nandang di sanggar dalung. Kolega-kolega dosen dan mahasiwa Nandang berdatangan. Sehari-hari Nandang adalah pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Para anggota teater kemudian membawa jasad Nandang ke Ciamis, ke desa kelahirannya untuk disemayamkan di sana.
Di Jepang pun, mendengar berita kematian Nandang, panitia shock. Mereka betul-betul tidak menyangka. Apalagi Aya dan Torakawa yang dua bulan sebelumnya datang dan masih melihat Nandang sehat-sehat saja. Saya ingat Direktur festival Tokyo, Chiaki Soma mengirim email yang panjang berisi belasungkawa. Ia mengatakan sangat kaget dan speechles. Ia menurutnya masih berusaha memahami kejadian yang sama sekali diluar dugaan itu .Tiga hari latihan dihentikan. Setelah tiga hari itu, Panitia Festival Tokyo dengan hati-hati mulai menghubungi TSI via skype menanyakan kesiapan mental para aktor untuk berangkat ke Tokyo. Di Serang terasa berat menyiapkan latihan tanpa Nandang. Suasana kesedihan terasa menggelayut di sanggar. Saya melihat Hendra Setiawan dan Mabsuti – membuat jaring dari kulit kayu namun dalam suasana diam. Tampak mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. Penyair Sunda Godi Suwarna mengaku lemah lunglai .”Ini berat,”katanya. Ia masih tak percaya bahwa Nandang pergi. Beberapa aktor melihat ia sering merenung sendirian di bawah konstruksi.
Toh the show must go on. Di bawah kepempinan Otong Durahim, latihan digenjot lagi. Sampai akhirnya rombongan TSI tiba di Bandara Narita. Berita kematian Nandang mewarnai Festival Tokyo. Website Festival Tokyo menampilkan condolence khusus. Koran Jepang berbahasa Inggris : The Japan Times pada edisi Minggu 7 November 2013 menyinggung soal kematian Nandang. Dalam artikel head lines berjudul: Festival Tokyo Pushes a Return to Story Telling yang ditulis oleh Nobuko Tanaka menyinggung kepergian Nandang. Ia juga mengatakan bahwa pementasan TSI adalah salah satu pementasan yang menampilkan grand design disamping pentas Back to Back theater dari Australia yang akan menyajikan pertunjukan berjudul: Ganesh Versus the Third Reich.
Saya kutipkan kalimatnya:
“…Another troupe with grand designs is Theatre of Studio company from Indonesia who last year won F/T promising young artist award but this month suffered the loss of its founder and director, Nandang Aradea, who ndied of a stroke at 42. Despite the loss though, the troupe has decide its F/T show, Overdose: Psycho-Catastrophe ini nIkebukuro West Gate Park – which involveserecting a huge set made of bamboo and a dynamic enacment of the 1883 explosion of Krakatoa- must go on...”
Begitu tiba di Tokyo, rombongan langsung survey ke lokasi. Taman Ikebukuro, masih seperti tahun lalu. Taman yang berada tak jauh dari Metropolitan Tokyo Theater itu tampak ramai dilalui orang lalu lalang. Masih ada pojok tempat orang-orang merokok. Itu pojok yang yang bila malam menjadi tempat tidur para orang tua yang homeless tapi paling menjadi tempat favorit Nandang dan anak-anak Serang nongkrong tahun lalu. Yang berbeda kini di taman itu sudah dipasang deretan sap-sap tempat duduk untuk menonton pertunjukan Overdose. Sap-sap itu namun ternyata jauh berbeda dengan yang dibayangkan. Sap-sap berupa bangku panjang itu terasa solid. Dan antara ruang tempat bakal didirikan konstruksi dan tempat duduk penonton itu –“celakanya” diberi pagar pembatas.
“Nanti kita ubah semua. Di pagar pembatas—nanti kita beri bambu panjang untuk tempat Mas Godi berjalan—menabur-naburkan rempah. Tempat duduk akan kita lapisi dengan bambu-bambu. Bambu-bambu panjang juga akan kita pasang di belakang tempat duduk sehingga suasananya berubah. Kita akan pasang bambu-bambu itu tak beraturan, asimetris—sehingga kesan liar muncul.”Saya ingat Otong mengatakan demikian..
Esok harinya, bambu datang sari pelabuhan dibawa sebuah truk tronton panjang. Batang-batang bambu itu digerojokkan. Jumlahnya ratusan -lebih dari cukup. Ide Otong untuk membuat sekeliling panggung—seperti sebuah “hutan kecil” bisa direalisir. Masalahnya adalah waktu. Cukupkah dalam waktu tiga hari kru, semua bambu itu ditegakkan? Sementara untuk memasang konstruksi saja,susah dibayangkan akan bisa selesai cepat. Di Serang, untuk mendirikan konstruksi butuh waktu seminggu. Itu pun dibantu dengan puluhan sukarelawan. Sementara di sini cuma enam aktor dan beberapa kru.
Ternyata yang tak terduga Panitia Tokyo memberi bantuan luar biasa. Mereka mendatangkan tukang-tukang profesional yang memang sehari-harinya adalah pekerja bangunan. Tukang ini membawa forklift, stagger-stagger yang bisa disusun-susun sampai mencapai ketinggian 10 meter—sehingga memudahkan untuk mengikat pucuk bambu dan alat-alat berat lain seperti gergaji mesin. Bambu-bambu tidak diangkat secara manual lagi namun diangkat dengan forklift. Selain itu Torakawa menyiapkan pasukan sukarelawan yang membantu merealisir ide Otong membuat “hutan kecil” .
Mereka bergotong royong melapisi tempat duduk dengan bilah-bilah bambu. Mereka beramai-ramai mengikat-ikatkan bambu-bambu ke sekujur tempat duduk. Mereka juga menegakkan batang-batang bambu di belakang tempat duduk. Para anggota TSI tidak berpangku tangan. Mereka ikut memanjat, mengikat bambu dengan kawat. Sebagaimana di Serang mereka bekerja tanpa helm, tanpa sabuk penyelamat. Tanpa dinyana, hal itu dilaporkan oleh seorang tua yang duduk-duduk di taman kepada polisi. Adalah kewajiban di Jepang, bahwa pekerja bangunan harus menggunakan helm. Polisi datang ke area pementasan. Mereka memeriksa panitia. Panitia dianggap lalai. Akhirnya oleh polisi panitia didenda..
Denda lantaran para anggota TSI bekerja tidak menggunakan helm, menunjukan memang di Jepang, sebuah pertunjukan di ruang publik—apalagi yang memungut bayaran (tiket untuk pertunjukan Overdose adalah 3500 yen atau sekitar 350 ribu rupiah) harus mematuhi prosedur yang ketat. Untuk bunyi saja ada aturan-aturan tertentu. Di Taman Ikebukuro sendiri ada air mancur. Suara air mancur ini mengganggu suara sound scape yang disiapkan oleh TSI. Sebelum aktor-aktor muncul,untuk menggiring penonton masuk dalam suasana laut—diperdengarkan rekaman sound scape suara ombak, suara debur air dari pelabuhan Serang sampai merak. Bila tak ada bunyi air mancur—suara ini akan lebih bisa terdengar. Pihak Taman Ikebukuro tapi tak mengijinkan air mancur itu dimatikan. Rencana untuk menggenangi konstruksi dengan air setinggi dengkul juga tak bisa dilaksanakan. Kolam hanya bisa dibuat dengan maksimal air setinggi tumit. Pada titik ini kompromi-kompromi harus dilakukan.
***
Tema kuratorial Festival Tokyo tahun 2013 ini adalah: Travels in Narratives. Chiaki Soma, Direktur Festival Tokyo (saat itu) yang lulusan Universitas Lyon Perancis itu mengutip pendapat filsuf Perancis, Jean Francois Lyotard untuk menjelaskan dasar kuratorialnya. Menurutnya 30 tahun lalu Lyotard berbicara tentang datangnya suatu masa “collapse of the grand narrative”. Masyarakat dunia akan memasuki suatu periode yang tidak lagi menggantungkan diri kepada narasi-narasi besar. Keyakinan Lyotard ini – bergema luas di kalangan intelektual. Bahwa dunia akan memasuki suatu babakan baru dalam sejarah dunia. Tapi menurut Chiaki Soma kenyataannya grand narratives masih mendominasi alam pikir warga dunia sampai sekarang. Narasi besar tidak mudah untuk dilenyapkan. Festival Tokyo sekarang ini menurutnya memberi tempat pada berbagai teater dari penjuru dunia untuk mempertanyakan kembali apakah yang disebut narratives itu.
“Itulah saat TSI ingin mengangkat kembali ingatan Krakatau dengan cara baru, saya menganggapnya cocok dengan spirit festival,” kata Chiaki. Seperti tahun lalu Festival Tokyo memberi tempat pada berbagai kecenderungan teater yang berbeda. Pertunjukan kedua setelah pentas TSI misalnya sangat kontras sekali dengan tontonan TSI. Pertunjukan itu karya sutradara Lina Saneh dan Rabih Mroue dari Lebanon berjudul: 33 r pm and few second. Bila penonton pada pentas TSI dibawa ke suasana yang arkaik, yang menampilkan pergulatan tubuh-tubuh riil menghadapi mara bahaya . Maka pada karya Rabih Mroue penonton dibawa mengelana ke sebuah dunia maya. Dunia Face Book. Pertunjukan teater ini bahkan sama sekali tanpa menghadirkan aktor.
Memasuki ruang Theatre East, Tokyo Metropolitan Theater kita dihadapkan pada sebuah layar. Layar itu menampilkan halaman face book milik seorang aktivis Lebanon bernama Diyaa Yamout. Halaman face book itu masih menyala. Yang ditampilkan di layar adalah percakapan-percakapan berbagai orang seputar diri dan keberadaan Diyaa. Diyaa mulanya di halaman face booknya menyatakan akan bunuh diri. Ia menulis surat di Face Book-nya. Ia menyatakan muak dengan kehidupan politik dan sosial Arab. Status dan pernyataan Diyaa di wall-nya menimbulkan respon para sahabatnya. Mereka menanyakan apakah itu sekedar lelucon atau benar-benar ingin dilakukan Diyaa.
Penonton selanjutnya bisa membaca saling silang pendapat dan informasi antar kenalan-kenalan Diyaa. Ada yang menganggap Menganggap martir bagi Lebanon. Tindakan adalah tindakan murni yang menampar pemerintah. Tindakan itu adalah tindakan kemanusiaan yang luar biasa. Suatu jenis filsafat yang tinggi. Namun sebagian menganggap tindakan itu adalah kekonyolan .Tindakan bodoh yang terlalu anarkis. Tindakan yang tak meghormati tubuhnya sendiri. Kita dibawa kepada sebuah perdebatan panas. Dari berita simpang siur di face book itu ternyata dipastikan Diyaa bunuh diri. Para kenalan Diyaa kemudian mengupload aneka dokumentasi mulai foto dan dokumentasi. Penonton kemudian bisa menyaksikan cuplikan Diyaa memimpin demonstrasi. Cuplikan Diyaa sehari-hari . Bahkan kemudian, ditayangkan diskusi sebuah televisi yang mengangkat topik mengapa Diyaa bunuh diri. Diskusi itu membenturkan para aktivis sosial dengan para politisi. Tokoh Diyaa sendiri adalah fiksi ciptakan Rabih Mroue. Tapi Rabih meski hanya melalui face book mampu menghadirkan seolah memang Diyaa betul-betul tokoh nyata. Melalui perdebatan tentang kematian Diyaa kita dibawa kepada kondisi-kondisi sosial Arab masa sekarang. Rabih seolah ingin mengatakan bahwa Arab Spring penuh dengan gejolak-gejolak ketidakmenentuan.
Di depan layar itu ada seperangkat audio, tape deck, speaker, mesin print dan telpon, televisi kecil. Semua barang-barang itu diandaikan milik Diyaa. Yang menarik tiba-tiba mesin print itu berderak sendiri dan kemudian keluar sebuah kerta fax. Seolah-olah ada surat dari seorang teman Diyaa yang masuk. Lalu tiba-tiba musik hidup dan televisi menyala menampilkan Janis Japlin. Suara parau Janis Joplin menyanyikan Summer Time terdengar . Ini sebuah kode kematian. Kita tahu, Janis adalah penyanyi blues Amerika yang meninggal di usia muda. Sosok Janis yang muncul ini segera membuat kita mengasosiasikan dengan Diyaa yang juga mati muda. Pertunjukan Rabih Mroue ini bisa menimbulkan diskusi sengit pada penonton. ”Menurut saya ini adalah video art,bukan teater.”kata seorang penonton. Ia berpendapat sebuah pertunjukan teater tetap harus ada unsur aktor yang tampil di panggung Sebaliknya penonton lain menganggap karya sangat cerdas karena mampu menggugah secara intelektual. Soal tak adanya aktor, ia menampik. Ia mengatakan, bukankah banyaknya orang dalam face book yang percakapannya kita ikuti sesungguhnya sudah menampilkan aktor, meski secar fisik tubuh mereka tak hadir?
Festival Tokyo – saya lihat juga adalah festival yang terlihat memberi ruang bagi teater-teater yang ingin melibatkan publik awam. Banyak karya yang berkolaborasi dengan publik awam. Tokyo Heteropia karya Akira Takayama misalnya mengajak penonton menjelajahi kantong-kantong komunitas imigran yang ada di Tokyo. Juga Rimini Protokoll sebuah kelompok teater dari Jerman –mengajak 1000 warga biasa Tokyo ke atas panggung. Satu hal lagi yang saya amati, baik tahun lalu maupun tahun sekarang, Festival Tokyo sangat memberi tempat pada gagasan dramawan asal Austria bernama Elfriede Jelinek. Pada festival Tokyo lalu, selain seorang sutradara Swiss Jossi Wieler menampilkan salah satu naskah Jelinek berjudul: Rechnitz seperti dikatakan di atas, ada progam bernama Jelinek Series. Dua sutradara Jepang Akira Takayama dan Motoi Miura diundangbuntuk menafsirkan karya Jelinek berjudul: Kin Licht. Kini apresiasi terhadap Jelinek diteruskan. Sutradara Tsuyoshi Ozawa mementaskan salah satu naskah Jelinek.
Adalah menarik mengapa Jelinek mendapat tempat begitu terhormat di festival Tokyo. Nama Jelinek sama sekali belum pernah disebut-sebut di Indonesia, baik dalam khazanah perbincangan sastra maupun teater. Elfriede Jelinek adalah seorang perempuan penulis lakon drama.Dia belajar musik di Vienna conservatory dan sejarah teater di Universitas Vienna. Ia meraih nobel sastra pada tahun 2004.Tampak denganan, Festival Tokyo selalu juga berusaha membuka diri terhadap naskah-naskah terbaru teater.
Dengan seluruh karakter itu, adalah menarik sebetulnya mencoba mencari tahu apa yang dirasakan penonton dan kritikus Jepang tentang pertunjukan Overdose. Selama 4 hari pertunjukan Overdose saya melihat ada beberapa kritikus teater Jepang hadir menonton. Chiaki Soma mengatakan, ada kemiripan antara butoh dan tubuh-tubuh aktor TSI .”Terutama soal energi,”Penata lampu asal Jepang– yang membantu menata cahaya Overdose – saya lupa mencatat namanya mengatakan dirinya sering bekerja sama dengan Sankai Junku. Seraya tertawa ia mengatakan tubuh-tubuh anak-anak Serang ini tampaknya liat.
Daisuke Moto, kritikus tari juga menonton. Ia bukan nama asing dalam dunia tari kontemporer Indonesia karena sering menjadi kurator IDF atau Indonesia Dance Festival. Ia dikenal kritis dengan perkembangan tari kontemporer di Indonesia. Ketika ditanya bagaimana ia membandingkan pertunjukan TSI misalnya dengan Sankai Junku. Ia menjawab demikian: ”Tubuh-tubuh aktor Sankai Junku meski sangat kuat, namun penampilannya selalu diestetisasikan. Itu yang berbeda dengan tubuh-tubuh aktor TSI. Tubuh mereka cenderung pada tubuh apa adanya. Itu yang saya suka.” Tapi ia juga memberi kritik pada Overdose. Ia membandingkan Overdose dengan Emergency. “Pada Emergency ya unsur ketakterdugaan tinggi. Dramaturgi tidak bisa diprediksi. Dari adegan ke adegan lain saya selalu bertanya-tanya bakal apa yang terjadi. Sementara dalam Overdose begitu 20 menit pertunjukan saya sudah mulai bisa membaca kemana arah eksplorasi… “.
”Kalau saya, suka dengan adanya unsur bau-bauan,” kata Hiro seorang pemusik dan dosen bahasa Indonesia di Universitas bahasa asing Tokyo (yang kini tinggal di Indonesia dan menjadi musikus dengan beberapa album) . Pada akhir Overdose, aktor-aktor menjadikan batang pohon sebagai tempat menumbuk rempah. Rempah itu dibawa dari Serang. Tumbukan rempah tersebut kemudian dibagikan kepada penonton. Penonton bisa membau dan mengusapkan ke wajah atau dada aktor. Unsur suasana yang kacau diakhiri dengan sebuah katarsis membau tumbukan rempah yang memiliki efek memenangkan ”Menonton pertunjukan TSI kedua kalinya, saya bisa meraskan bencana yang kami hadapi sendiri ” kata Hidenaga Otori, krtitikus teater senior Jepang. Hal itu disepakati oleh rekannya, Chikara Fujiwara, kritikus seni pertunjukan.
Pertunjukan : Overdose adalah pengalaman ketiga TSI tampil di Festival Internasional. Pengalaman pertama adalah pentas di Gdansk,Polandia dalam sebuah festival outdoor FETA..Kala itu membawakan: Perempuan Gerabah. Kedua kemudian di Ikebukuro tahun lalu itu. Dibanding kedua pertunjukan sebelumnya itu—persiapan Overdose lebih kompleks. Yang tidak dinyana, sama dengan tahun kemarin–bambu menyimpan masalah finansial. Bambu yang akhirnya setelah pertunjukan dihancurkan karena tidak ada tempat penyimpanan–ternyata sesungguhnya hampir tidak lolos di imigrasi pelabuhan. Menurut pihak imigrasi pada bambu-bambu yang dikirim dari Indonesia itu muncl serangga-serangga kecil. Untuk dapat lolos maka harus dilakukan fumigasi-atu penyemprotan kimia.
Beaya fumigasi itu menelan sampai 1 juta 600 ribu yen atau sekitar 160 juta rupiah. Dan itu ternyata tidak ditanggung oleh Panitia Festival Tokyo. Mereka mengatakan bahwa beaya ini harus ditanggung oleh TSI. Jelas ini ditolak oleh TSI, karena fumigasi bukan tanggung jawab TSI tapi shipping company. Seharusnya yang melakukan tugas karantina bambu adalah shipping company. Setelah dicross-check yang terjadi adalah salah pengertian antara panitia, shipping company dan TSI tentang siapa yang harus melakukan fumigasi. Di hari-hari terakhir selama d Tokyo , maka terjadi rapat antara tim produser TSI, pihak Panitia festival Tokyo dan shipping company. Keputusannya beaya fumigasi akan ditanggung renteng bersama. Namun prosentase berapa beaya urunan itu belum ketahuan, karena masih harus menunggu akhir Desember ini– setelah festival Tokyo selesai .
Sepulang Festival Tokyo namun Teater Studio Indonesia Serang vakum. Dan bubar. Tidak kedengaran lagi sampai sekarang. Tidak ada yang bisa meneruskan konsep-konsep kerja Nandang Aradea almarhum. Betapapun demikian perjalanan mereka ke Polandia dan dua pementasan mereka di Festival Tokyo patut dicatat dalam sejjarah teater Indonesia modern.
*Penulis seorang kerani biasa.Tinggal di Bekasi.