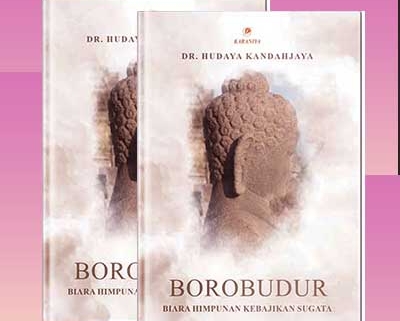Tafsir Baru Borobudur
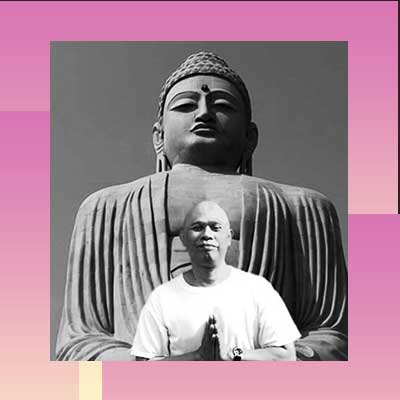
Oleh Budi Murdono
Judul : Borobudur Biara Himpunan Kebajikan Sugata
Penulis : Dr. Hudaya Kandahjaya
Penerbit : Karaniya
Cetakan : Kedua 2021
Tebal : xxiv + 400 halaman
ISBN : 978-602-1235-66-9
Pertengahan Februari lalu, Pemerintah resmi mencanangkan candi Borobudur (bersama candi Mendut, Pawon) menjadi tempat ibadah umat Buddha Indonesia dan seluruh dunia. Selama ini umat Buddha telah beberapa kali menggunakan candi Borobudur sebagai tempat untuk merayakan hari Waisak atau hari-hari suci lainnya. Namun akses untuk memanfaatkan komplek candi itu sebagai tempat ibadah masih sering dibatasi oleh pengelola candi yang juga memanfaatkan Borobudur untuk kegiatan-kegiatan lain, khususnya pariwisata dan hiburan. Padahal sebagai situs keagamaan Buddha, Borobudur sudah menarik perhatian dunia sejak penemuannya kembali di awal abad ke 19. Sudah banyak kajian tentang Borobudur, baik yang ditulis di masa-masa awal penemuannya maupun masa sesudahnya hingga tahun-tahun belakangan ini. Pada 1927 saja kira-kira sudah terbit 300 publikasi tentang penyelidikan Borobudur dan menjelang akhir abad 20 jumlahnya sudah melebih 500.
Sudah sejak awal abad 20 karya tulis yang membahas secara komprehensif Borobudur kebanyakan dibuat oleh sarjana-sarjana asing, seperti karya-kaya klasik Krom (1927), Stutterheim (1929), de Casparis (1950). Belakangan, sarjana-sarjana lainnya juga menulis tentang Borobudur seperti Voute dan Long (2008), Woodward (2009) dan Founein (2012) Beberapa sarjana Jepang juga menulis artikel tentang Borobudur, seperti Shoun Toganoo (1982), Omura Segai (1995), dan Kazuko Ishii (1991). Tulisan sarjana Indonesia yang tentu saja tidak boleh terlewatkan adalah karya Noerhadi Magetsari (1997) dan Daoed Joesoef (2015). Kini, bertambah lagi satu buku karya putera bangsa tentang Borobudur yang ditulis oleh Hudaya Kandahjaya, Sebelumnya, pada 2020 telah terbit juga karya Salim Lee, Borobudur Bersemburat: Peninggalan Leluhur, Kini Warisan Dunia.
Hudaya Kandahjaya adalah lulusan S2 Institut of Buddhist Studies, Barkeley California dan S3 kajian budaya dan agama di Graduate Theological Union, Bakeley, California. Dia banyak menulis tentang Borobudur serta ajaran, kitab-kitab dan ritual agama Buddha. Buku Borobudur Biara Himpunan Sugata ini terdiri atas enam bab yang masing-masing berisi pebahasan tentang apa itu Borobudur, latar belakang sejarah pendiriannya, pokok ajaran yang dikandungnya, rancangan asrsitektur, fungsi dan ritual serta liturgi yang terkait dengannya.
Seperti biasa, sebelum menjawab pertanyaan apakah Borobudur itu, orang akan membahas lebih dulu arti dari nama Borobudur. Berbeda dengan para sarjana sebelumnya, seperti de Casparis yang berpendapat bahwa nama Borobudur berasal dari kata bhumisambhara-budhara dan Prof. Poerbatjaraka mengatakan bahwa kemungkinan nama Borobudur berasal dari kata bara (tranformasi dari kata vihara dan byara) dan budur (kemungkinan adalah toponim Indonesia purba), Kandahjayha berpendapat bahwa nama Borobudur berasal dari Bahasa Singhala vara-budu-r (dalam Bahasa Sansekerta vara-buddha-rupa) yang berarti Arca Buddha Istimewa. Bagaimana kata dalam bahasa Singhala ini bisa menjadi nama sebuah candi di Jawa yang didirikan pada abad ke 9 M? Jawabannya terkait dengan hubungan antara Jawa dan Srilanka yang sudah terjalin sejak abad ke 8 M. Hubungan ini ditandai dengan adanya prasasti Ratu Boko (792 M) yang mencatat pendirian biara Abhayagiri oleh orang Sinhala.
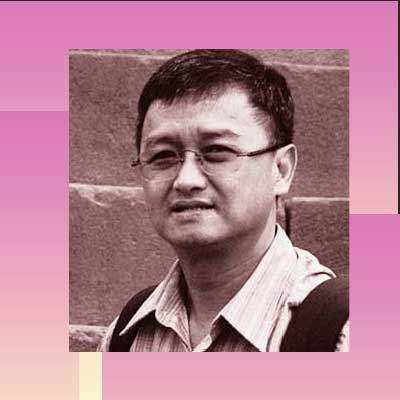
Dr. Hudaya Kandahjaya (Foto: Arsip Borobudur Writers and Cultural Festival)
Tentang apakah Borobudur itu, sejak awal buku ini sudah lebih dulu menegaskan bahwa Borobudur disiapkan menjadi sebuah mandala yang membuat pelaku spiritual bisa melaksanakan laku dan tekad Samantabhadra (Samantabhadracaryapranidhana mandala) atau meneladani, menghayati dan mengamalkan laku Buddha (Buddhacaritai), seperti yang ditempuh oleh oleh Sudhana dan Sakyamuni (hal. x-xi). Penegasan ini tentu tidak datang begitu saja, tetapi melalui analisis atas perdebatan yang pernah terjadi antara para sarjana baik di masa-masa awal maupun waktu belakangan ini yang diuraikan pada Bab 3.
Tentang latar belakang sejarah dibangunnya Borobudur, buku ini secara khusus menganalisis kejadian-kejadian historis sebelum dan sesudah pendirian Borobudur, khususnya yang terkait dengan penyebaran agama Buddha di kepulauan Nusantara serta terjalinya hubungan antara Cina, Kepulauan Nusantara, India dan Srilanka melalui jalur laut. Pembahasan latar belakang sejarah ini mengacu pada sumber-sumber berupa catatan perjalanan yang melibatkan banyak nama. Mulai dari Faxian (Fa-hsien) dan Gunawarman (abad ke 5) hingga nama-nama, Yijing (I-Cing), Jnanabhadra, Sakayakirti, Vajrabodhi, Amogavajra, Huiguo (siswa Amogavajra), Bianhong (bhiksu Jawa murid Huiguo), Dharmakirti, Atisa hingga nama-nama pemuka agama Buddha abad 20, yaitu Benqing, Bhiku Narada dan Ashin Jinarakkhita. Uraian tentang sejarah penyebaran agama Buddha di Nusantara ini cukup panjang dan kaya dengan referensi terkait kebesaran agama Buddha di Nusantara masa lalu. Tapi sayang kaitan langsung dengan penjelasan mengapa Borobudur didirikan tidaklah jelas.
Bab 3 yang berisi uraian dan analisis tentang konsep-konsep dasar di belakang pendirian Borobudur secara khusus menganalisis dua sumber penting untuk memahami pokok ajaran agama Buddha yang melandasi pembangun candi ini, yaitu prasasti Kayumwungan dan kitab Sang Hyang Kamahayanikan. Untuk itu kita masuk ke perdebatan yang menyangkut apa itu Borobudur, stupa atau mandala? Seperti disinggung sebelumnya, buku ini berkesimpulan bahwa Borobudur adalah sebuah mandala setelah menganalisis perdebatan yang melibatkan banyak sekali sarjana, mulai dari Krom, Stuttenheim, de Casparis, Moens, Fontein (1981), Togano (1982), Ishii (1991), Segai (1991), Klokke (1995), Chandra (1995), dan Senllgrove (2000) sebagaimana terangkum di Bab 3 (hal. 80-87).
Bermula dari keyakinan Krom bahwa Borobudur pada dasarnya adalah stupa. Pendapat ini kemudian ditinggalkan karena munculnya pendapat Stuttenheim yang mengaitkan pembangunan Borobudur dengan perguruan Vajradhara atau agama Buddha Tantra. Suttenheim berpendapat bahwa Borobudur adalah sebuah stupa-prasada, persisnya sebuah replika tridhatu (tiga alam: kamadhatu, rupadhatu dan arupadhatu). Konsep ini dengan cepat diterima luas di mana-mana ini sejak 1980-an mulai diragukan. Ini juga berkaitan dengan mulai diragukannya keterkaitan antara pendirian Borobudur dengan aliran Tantra. Mereka yang berpendapat bahwa Borobudur dibangun oleh perguruan sekte Vajrayana umumnya berpendapat bahwa Borobudur adalah sebuah mandala, sedangkan yang menolak tegas-tegas menyatakan bahwa Borobudur bukanlah sebuah mandala.
Kesimpulan bahwa Borobudur adalah sebuah mandala diambil setelah mengkaji prasasti Kayumwungan (sering disebut juga prasasti Karang Tengah) yang dibuat oleh Raja Samarotunga (824 M), dan kitab Sang Hyang Kamahayanikan yang berasal dari abad ke 8 M. Kandahjaya menerjemahkan kembali prasasti Kayumwungan itu dan berdasarkan terjemahan tersebut ia pun berkesimpulan bahwa prasasti ini menuturkan sebuah kronologi yang cukup lengkap yang mengarah ke pengukuhan satu biara Buddha, yaitu Borobudur (hal. 95-110). Selanjutnya, dari Sang Hyang Kamahayanikan, Kandahjaya melihat dalam kitab itu adanya muatan tentang prosedur pemilihan situs mandala. Kriteria-kriteria untuk memilih situs mandala yang terdapat di dalamnya sesuai dengan letak Borobudur.
Para sarjana percaya bahwa sebuah stupa besar pada awalnya direncanakan untuk memahkotai Borobudur. Ini ditunjukkan dengan penemuan 160 panel relief Karmavibhanga-sutra di balik teras lebar pada bagian kaki Borobudur pada 1885, dan lapik teratai besar yang tidak selesai di puncak panggung persegi di bawah teras melingkar pada waktu pemugaran pertama 1907-1911. Lalu mengapa rancangan awal Borobudur yang berupa stupa itu diubah oleh para arsiteknya? Jawaban Kandahjaya menarik. Menurutnya, beberapa syair dalam prasasti itu menggambarkan adanya penolakan terhadap rancangan asal Borobudur dan perusakan beberapa panel relief Karmavibhanga-sutra. Raja Samarotunga kemudian memodifikasi rancangan arsitektur asal untuk menyelesaikan persoalan itu. prasasti Kayumwungan yang sudah ia terjemahkan ulang, diketahui telah terjadi penolakan terhadap rancangan asal Borobudur dan perusakan beberapa panel relief Karmavibhanga-sutra. Raja Samarotunga kemudian memodifikasi rancangan arsitektur asal untuk menyelesaikan persoalan itu. Relief Karmavibhanga-sutra itu pun ditutup dengan ribuan kubik batu yang kemudian membentuk selasar lebar di lantai bawah. Kandahjaya tidak menyinggung sama sekali pedapat sarjana lain tentang penyebab ditutupnya relief Karmavibhanga, seperti Stutterheim yang berpendapat hal itu terjadi karena penggambaranyang terlalu keras tentang adegan neraka atau Salim Lee yang melihat penutupan itu dilakukan karena pertimbngan teknis bangunan untuk mencegah tembok-tembok candi tidak terdorong ke sisi luar karena limbasan air hujan.
Bab 5 (hal. 151-256) yang dimaksudkan untuk membahas fungsi Borobudur memakan paling banyak halaman buku ini, namun sebagian besar halaman-halamannya dihabiskan untuk membicarakan kitab Bhadracari yang menjadi sumber bagi cerita pada salah satu dinding relief Borobudur, mulai dari pembahasan tentang sumber-sumber kitab Bhradacari yang tersedia degan berbagaai versi dan terjemahannya, identifikasinya dengan penel-panel relief Borobudur, versi kitab mana yang menjadi sumber bagi panel-panel di Borobudur, hingga penjelasan panel satu per satu lengkap dengan bait sajaknya dalam Sanskerta dan terjemahan Indonesianya. Pada intinya, bab ini ingin menunjukkan bahwa Borobudur dirancang untuk mengajak orang berimajinasi atau membayangkan berada di hadapan Buddha Sakyamuni dan banyak Buddha lainnya, dan memungkinkan orang untuk menyembah, memuji, menyajikan persembahan, mengakui kesalahan, bersukacita dan memohon kepada semua Buddha melalui ritual-ritual, seperti yang juga digambarkan di panel-panel relief Jataka dan Avadana, Lalitavistara, Lalitavistara atau Bhradacari (hal. 240-241).
Selanjutnya, mengacu pada kitab Sang Hyang Kamahayanikan, buku ini menjelaskan fungsi tiap selasar pada bangunan Borobudur dalam proses pengembangan spiritual. Selasar lebar persegi paling bawah tempat persembahan anuttarapuja dan ritual pengeramatan sesuai dengan tahap pertama (Jalan Agung). Empat selasar persegi berlangkan menjadi tempat mempelajari laku Buddha (buddhacarya) untuk memperoleh sepuluh kesempurnaan sesuai dengan tahap kedua (Jalan Tertinggi). Selasar di atasnya berisi stupa berterawang yang mengambarkan keadaan siswa mulai menampak Buddha ketika melaksanakan tahap ketiga (Rahasia Agung). Dan, stupa induk mencerminkan keadaan pencapaian melihat secara jelas kepekatan rahasia Tathagata yang tak mendua (advaya) sesuai dengan tahap terakhir (Rahasia Tertinggi).
Pembahasan kitab Sang Hyang Kamahayanikan juga mencakup lima Tathagata (Buddha). Para peneliti dapat mengetahui keberadaan lima Tathagata di Borobudur melalui postur dan posisi arca-arca yang diletakkan di relung di atas lantai serambi lantai persegi. Vairocana di tengah, Aksobhya di timur, Ratnasambhawa di selatan, Amitabha di barat dan Amoghasidi di utara. Berdasarkan kitab Sang Hyang Kamahayanikan, penulis buku ini menyimpulkan bahwa arca-arca Buddha dengan dharmacakra-mudra di dalam stupa berterawang di lantai melingkar teratas adalah Buddha Sakyamuni dan Sri Lokesvara dan Sri Vajrapani di dua lantai melingkar di bawahnya. Dan, stupa induk di puncak Borobudur adalah Sang Hyang Buddha atau Sang Hyang Divarupa.
Bab terakhir buku ini menguraikan ritual apa saja yang diduga menjadi bagian tak terpisahkan dari keberadaan candi Borobudur ini. Pembahasannya meliputi bentuk-bentuk awal ritual umat Buddha yang masih dilaksanakan hingga sekarang, ritual perlindungan dan penyucian kesalahan (pertobatan), serta liturgi pujian dan ikrar.
Referensi tentang bentuk awal ritual umat Buddha diambil dari cerita-cerita dalam kanon Pali dan beberapa kitab Mahayana. Begitu juga referensi tentang ritual perlindungan dan penyucian kesalahan diambil dari sumber-sumber Pali dan sutra Mahayana ditambah dengan kitab-kitab bacaan perlindungan seperti paritta dan gatha dalam tradisi Theravada dan liturgi pertobatan tradisi Mahayana. Liturgi pujian dan ikrar terdiri atas sajak pujian kepada Adi Buddha, sajak pujian kepada Triratana, sajak pujian kepada Pancatathagata, sajak Anuttarapuja yang kesemuanya mengacu pada kitab Sang Hyang Kamahayanikan serta perlambangan yang ditampilkan di candi Borobudur, bagian dari Ovada-patimokkha versi Mahayana (dalam Sanskerta), dan kitab Bhradacari versi Amoghavajra.
Dari penjelasan bab demi bab buku ini, jelaslah bahwa pengkajian Borobudur sebagai situs kehidupan beragama umat Buddha sama sekali bukanlah hal yang mudah. Ini disebabkan terutama sekali karena tidak adanya data historis tentang Borobudur kecuali tubuh candi itu sendiri. Kalaupun ada sumber-sumber sejarah yang dijadikan acuan oleh penulis buku ini, baik berupa kitab maupun prasasti atau transkripsi, tidak ada fakta yang merujuk langsung ke Borobudur itu sendiri. Ini terlihat sejak penentuan asal-usul nama Borobudur, penjelasan tentang latar belakang sejarah, kesimpulan bahwa Borobudur adalah mandala hingga idenifikasi ritual dan liturgi.
Pengecualian terjadi pada uraian dan analisis mengenai bagan dan apa yang ditampilkan Borobudur melalui relief, stupa dan arca-arca Buddha. Meskipun cukup panjang dan memakan lebih dari seratus halaman, pembaca mendapat cukup penjelasan untuk memahami makna dari relief, stupa dan arca-arca Buddha yang terpahat di Borobudur. Ini dimunginkan karena yang menjadi data historis adalah tubuh Borobudur itu sendiri yang kemudian dijelaskan dengan mengacu pada sumber-sumber ajaran yang ada. Itu pun tidak selamanya mudah karena sumber-sumber ajaran itu banyak versinya. Ini khususnya terjadi ketika peneliti menafsirkan gambar-gambar pada relief Borobudur.
Terlepas dari kekurangan tersebut di atas, buku ini telah memberi kontribusi yang sangat penting dan berharga bagi studi tentang Borobudur. Buku ini telah memutar kembali rekaman perdebatan mengenai asal-usul nama, maksud pendirian, sumber-sumber ajaran, penafsiran atas prasasti Kayumwungan dan identifikasi sutra-sutra yang dipahatkan pada relief Borobudur yang melibatkan para ahli dari berbagai negara. Di samping itu, sumber-sumber bacaannya juga sangat kaya terkait dengan sejarah, kiteratur sejarah dan kanon-kanon Buddha, baik yang berbahasa Pali, Sanskerta maupun Cina, sehingga menambah khazanah pengetahuan kita tentang Borobudur khususnya dan agama Buddha Mahayana umumnya. Terakhir, yang mungkin paling penting, buku ini mengangkat kitab Sang Hayang Kamahayanikan yang merupakan kitab asli Nusantara sebagai sumber ajaran penting untuk menafsirkan Borobudur.
*Penulis adalah pengajar yoga-meditasi freelance