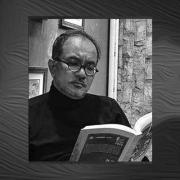Mengadili Ibrahim
Oleh Taufiqurrahman
Beberapa tahun terakhir ini, setiap kali Idul Adha, saya selalu dihantui pertanyaan: Tidakkah ritual kurban itu mencerminkan watak agama yang antroposentris, yang lebih mengutamakan kepentingan manusia daripada makhluk hidup lain di dunia? Mungkinkah kita beragama tanpa terjebak ke dalam antroposentrisme? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu hanya muncul untuk kemudian hilang begitu saja, bersamaan dengan hilangnya nyawa jutaan hewan yang digorok manusia atas nama agama. Tapi toh tanpa agama sekalipun, sebagian besar manusia memang doyan makan daging. Dan barangkali itu memang “dorongan alamiah” manusia, sehingga kita bisa berada puncak rantai makanan selama kurang-lebih 2 juta tahun.
Sudah banyak juga para filsuf moral yang berusaha memproblematisasi “dorongan alamiah” manusia tersebut. Karenanya, dalam artikel pendek ini, saya tidak akan membahas persoalan itu lagi. Saya akan mencoba menyoroti peristiwa tragis dan sekaligus epik yang menjadi asal-usul dari praktik kurban dalam agama-agama Abrahamik, yaitu upaya pembunuhan Ishak (versi Yahudi dan Kristen) atau Ismail (versi Islam) oleh Ibrahim.
Pembunuhan, apalagi terhadap orang yang tak berdosa, jelas merupakan tindakan immoral. Demikian juga dengan upaya untuk melakukannya. Namun, Ibrahim malah mendapat perintah dari Tuhan untuk menyembelih anaknya, Ishak/Ismail. Apakah perintah Tuhan bisa mengubah status moral sebuah tindakan, dari yang immoral menjadi tak lagi immoral? Jika iya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sebuah perintah berasal dari Tuhan sementara Tuhan, dalam ajaran agama-agama, selalu digambarkan berada di luar batas kemampuan indrawi manusia?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memunculkan setidaknya dua respon “negatif” terhadap peristiwa tragis-epik upaya pembunuhan Ishak/Ismail oleh Ibrahim, yaitu respon Ibn ‘Arabi dan Immanuel Kant. Ibn ‘Arabi menyebut Ibrahim salah paham dengan mimpinya sendiri. Ketika berkali-kali bermimpi menyembelih anaknya, Ibrahim memahami mimpi tersebut secara harafiah. Padahal, menurut Ibn ‘Arabi, mimpi itu adalah ranah imajinasi (haḍarah al-khayāli) yang untuk memahaminya butuh interpretasi (ta’bīr). Apa yang dimaksud interpretasi di sini adalah “melintas dari bentuk yang terlihat ke sesuatu yang lain” (al-jawāz min ṣūrati mā raāhu ilā amrin ākhar) (lih. Fuṣūs al-Hikam, bab “Faṣ Hikmah Haqqiyah fī Kalimah Ishāqiyyah”).
Apa yang dimaksudkan Tuhan dengan menampakan wajah Ishak/Ismail dalam mimpi Ibrahim sebenarnya adalah domba, bukan diri Ishak/Ismail secara harafiah. Itulah kenapa, ketika Ibrahim hendak menyembelih anaknya berdasarkan pemahaman literal atas mimpinya, Tuhan segera menggantinya dengan domba. Tuhan menyelamatkan Ishak/Ismail dari kesalahpahaman Ibrahim. Itulah kenapa juga, ketika berseru kepada Ibrahim, Allah tidak bilang “Wahai, Ibrahim. Sungguh engkau telah benar terkait mimpi itu” (An yā Ibrāhim qad ṣadaqta fi al-ru’yā), tetapi bilang “Wahai, Ibrahim. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu” (An yā Ibrāhim qad ṣaddaqta al-ru’yā).
Tuhan di situ tidak membenarkan Ibrahim. Dia hanya menggambarkan sikap afirmatif (taṣdīq) Ibrahim yang, menurut Ibn ‘Arabi, sebenarnya tidak tepat untuk menyikapi mimpi. Ibn ‘Arabi menggunakan kisah ini untuk menggambarkan bagaimana konstruksi epistemik imajinasi. Bentuk pengetahuan yang tersingkapkan melalui ranah imajinasi bukanlah pengetahuan literal, melainkan pengetahuan metaforis. Sebab ranah itu adalah semesta metafora (‘ālam al-miṡāl), semesta yang menghubungkan “dunia atas” dan “dunia bawah”, dunia konkret dan dunia ideal. Dengan demikian, bagi Ibn ‘Arabi, Ibrahim tidak salah secara moral, tapi mungkin keliru secara epistemik lantara memahami mimpinya secara literal.
Tanggapan Kant jauh lebih keras daripada tanggapan Ibn ‘Arabi. Kant tidak hanya menganggap Ibrahim keliru secara epistemik, tetapi juga salah secara moral. Tentang tuduhan Kant terhadap Ibrahim ini, dan bagaimana agama-agama Abrahim memberikan pembelaan terhadap Ibrahim, menarik sekali jika kita baca artikel Stephen R. Palmquist dan Philip McPherson Rudisill yang berjudul “Three Perspectives on Abraham’s Defense against Kant’s Charge of Immoral Conduct“ (2009).
Artikel ini menarik bagi saya dari segi metode penulisannya. Ia melakukan sebuah eksperimen pikiran untuk membela Ibrahim dari tuduhan Immanuel Kant. Dalam eksperimen pikiran ini, Nabi Ibrahim dibawa ke Pengadilan Kantian untuk diadili. Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah upaya Ibrahim untuk membunuh Ishak/Ismail itu benar secara moral atau tidak. Ada 4 pihak yang terlibat dalam pengadilan tersebut: 1) Nalar sebagai Hakim; 2) Ibrahim sebagai Terdakwa; 3) Immnuel Kant sebagai Jaksa Penuntut Umum; dan 4) tiga agama Abrahamik (Yahudi, Kristen, Islam) sebagai Pengacara Ibrahim.
Perkaranya bermula dari tuntutan Kant terhadap Ibrahim yang mengaku mendapat perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya (Ishak/Ismail). Kant menuntut Ibrahim dihukum saja, alih-alih dipuji sebagaimana yang dilakukan oleh para pemeluk agama Abrahamik, karena ia telah melakukan tindakan immoral. Kant menulis dasar tuntutannya terhadap Ibrahim itu di dalam artikelnya yang berjudul “The Conflict of the Faculties”. Begini kira-kira terjemahan bebasnya:
“Jika Tuhan memang benar-benar berbicara pada manusia, maka manusia tidak akan pernah bisa tahu bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan. Sangat mustahil manusia dengan alat indranya bisa memahami perkataan Zat Yang-Takterbatas, membedakannya dari perkataan makhluk biasa, dan mengetahuinya sebagaimana adanya. Akan tetapi, dalam kasus tertentu, manusia bisa memastikan bahwa suara yang dia dengar itu bukan suara Tuhan; jika suara itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum moral, meski tampak sangat agung dan bahkan tampak melampaui seluruh alam semesta, manusia mesti menganggapnya sebagai ilusi belaka”.
Selain di dalam “The Conflict of the Faculties”, Kant juga menulis hal yang serupa di dalam Religion within the Boundaries of Mere Reason (6:87). Begini terjemahan bebasnya:
“Jika sesuatu dianggap sebagai perintah Tuhan yang menampak secara langsung darinya tetapi ia bertentangan dengan moralitas, maka ia tidak mungkin merupakan keajaiban ilahiah meskipun memang tampak begitu (seperti, jika seorang ayah diperintah untuk menyembelih anaknya yang, sejauh yang dia tahu, sama sekali tidak berdosa.)”.
Atas dasar itulah, Kant menganggap upaya Ibrahim untuk menyembelih anaknya itu tidak bisa dibenarkan secara moral alias immoral. Suara yang oleh Ibrahim diyakini berasal dari Tuhan itu memerintah tindakan immoral dan, karenanya, pasti bukan dari Tuhan. Ia hanya halusinasi Ibrahim saja. Menghadapi tuntutan seperti ini, tiga pengacara Ibrahim memiliki versi pembelaannya masing-masing.
Pertama, Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim sebenarnya sudah tahu bahwa Ishak tidak akan terbunuh, apa pun yang ia lakukan. Dengan demikian, apa dilakukan Ibrahim bukanlah tindakan immoral sebagaimana dituduhkan Kant, karena dalam tindakannya itu tidak ada intensi untuk membunuh anaknya—intensinya hanya demi menaati perintah Tuhan.
Kedua, Kristen mengatakan bahwa Ibrahim memang tahu bahwa setelah disembelih nanti Ishak akan mati. Tapi ia punya keyakinan bahwa Tuhan akan membuatnya hidup kembali. Keyakinan ini, menurut perspektif Kristen, sudah membebaskan Ibrahim dari tuduhan Kant. Sebab apa yang dilakukan Ibrahim bukan untuk menghabisi hidup manusia, melainkan semata untuk melewati proses ujian terhadap kadar keimanannya.
Ketiga, Islam mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ibrahim kepada Ismail itu didasari rasa cinta seorang ayah kepada anaknya. Ini ditunjukkan oleh sikap Ibrahim yang meminta persetujuan Ismail terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya; dan Ismail dengan begitu tulus menyetujuinya. Menurut pengacara yang satu ini, meskipun akhirnya memang terjadi proses pembunuhan, tetapi itu bukan pembunuhan biasa, karena orang yang akan dibunuh secara sadar memang memilihnya dan pembunuhan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Karena itu, Ibrahim bebas dari tuduhan immoralitas Kant.
Dua pengacara pertama (Yahudi dan Kristen) membela Ibrahim dengan berdasar pada pengetahuan Ibrahim akan konsekuensi tindakannya (bahwa Ishak tidak akan mati dan bahwa Ishak akan hidup kembali). Pembelaan ini, menurut saya, tidak bisa membebaskan Ibrahim dari tuduhan Kant, karena justru menilai sebuah tindakan dari standar etika non-Kantian (konsekuensialis). Padahal, menurut Kant, nilai moral sebuah tindakan itu tidak ditentukan oleh konsekuensinya, tetapi oleh sifat intrinsik dari tindakan itu sendiri. Apa pun konsekuensinya, yang namanya tindakan membunuh itu tetap tidak dapat dibenarkan secara moral.
Dengan demikian, berdasarkan pembelaan Yahudi dan Kristen, Ibrahim tetap sosok immoral di hadapan Kant. Ia tetap harus dihukum. Namun, menurut saya, Ibrahim diselamatkan oleh pembelaan Islam. Tentu bukan karena kebetulan saya Muslim. Pembelaan Islam terhadap Ibrahim lebih dapat diterima oleh Nalar Kantian karena tidak menggunakan kerangka berpikir konsekuensialis. Pembunuhan itu tidak salah secara moral karena, menurut Pengacara Islam, didasari oleh persetujuan (consent) yang tulus dan cinta yang dalam. Adanya persetujuan inilah yang secara intrinsik membedakan tindakan Ibrahim dari tindakan pembunuhan biasa. Karena secara intrinsik berbeda, maka status moralnya juga berbeda.
Namun, perlu dicatat bahwa itu hanya kesimpulan saya berdasarkan fakta persidangan imajiner yang dihadirkan Palmquist dan Rudisill dalam artikelnya. Saya tidak tahu apakah Yahudi dan Kristen memiliki pembelaan lain terhadap Ibrahim yang tidak dimasukkan ke dalam persidangan imajiner tersebut. Terlepas dari itu semua, saya ingin mengatakan bahwa agama dalam batas-batas nalar selalu lebih menarik, dan barangkali juga lebih manusiawi, daripada agama yang di luar nalar.
*Penulis adalah Alumnus Filsafat, Universitas Gajah Mada