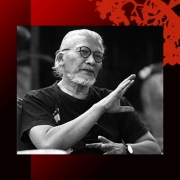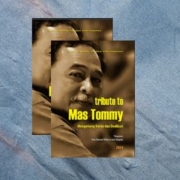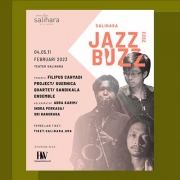Filsafat Sangkan-Paran Syekh Siti Jenar Ditilik dari Filsafat Identitas Baruch de Spinoza
Oleh Tony Doludea
Karena telah lama Syekh Siti Jenar tidak bersembahyang jemaah di masjid, maka Sunan Giri membuka musyawarah para wali dan mengajukan masalah ini kepada Dewan Wali Songo. Syekh Maulana Maghribi berpendapat bahwa hal itu akan menjadi contoh yang buruk dan memberi kesan bahwa para wali telah meninggalkan syariat. Kemudian Sunan Giri mengutus dua orang santrinya ke gua tempat Syekh Siti Jenar bertapa dan memintanya untuk datang ke mesjid. Ketika mereka sampai di tempat itu mereka diberitahu bahwa Syekh Siti Jenar tidak berada di dalam gua tersebut, hanya Allah saja yang ada. Mereka kembali ke mesjid dan melaporkan hal itu kepada Sunan Giri dan para wali lainnya. Sunan Giri kemudian menyuruh mereka untuk kembali ke gua itu dan meminta supaya Allah segera menghadap para wali. Kedua santri itu kemudian diberitahu bahwa Allah tidak ada di situ, yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Mereka kembali kepada Sunan Giri untuk kedua kalinya. Sunan Giri menyuruh mereka untuk meminta datang baik Allah maupun Syekh Siti Jenar. Kemudian Syekh Siti Jenar keluar dari gua dan menghadap para wali di mesjid. Ia diberitahu bahwa ia diundang untuk menghadiri musyawarah para wali tentang doktrin sufi. Dalam musyawarah tersebut, Syekh Siti Jenar menjelaskan doktrin kesatuan khalik dan mahluk, yaitu bahwa tidak ada perbedaan ontologis antara Allah, manusia dan semua ciptaan lainnya. Sunan Giri mengatakan bahwa doktrin itu benar, tapi ia meminta jangan diajarkan karena dapat membuat kosong mesjid dan orang akan mengabaikan syariat. Syekh Siti Jenar menjawab bahwa ketundukan buta kepada ibadah ritual yang tanpa isi, hanyalah perilaku keagamaan orang bodoh dan kafir. (Muhammad Sholikhin, 2004, hlm: 107-109)
Tulisan ini merupakan suatu percobaan untuk memperlihatkan makna filsafat sangkan-paran dalam ajaran kebatinan Syekh Siti Jenar, dengan memandangnya dari sudut pandang perkembangan sejarah Filsafat Barat, sebagai cara untuk menganalisanya.
Dalam mistisisme Jawa, yang dimaksudkan dengan sangkan-paran adalah pandangan yang menjelaskan asal-tujuan manusia. Ini merupakan tema pusat ajaran kebatinan orang Jawa. Secara umum, orang Jawa lebih tertarik kepada nilai pragmatisnya, kebijaksanaan praktis untuk mencapai ketenangan dan harmoni, daripada spekulasi metafisikanya. Meskipun demikian, pandangan ini tidak dapat dilepaskan sama sekali dari spekulasi teori emanasi-remanasi (tanazzul-taraqqi), di mana Yang Mutlak itu turun ke dalam realitas ini dan kemudian kembali kepada keadaannya yang semula.
Syekh Siti Jenar lahir tahun 1426, dengan nama kecil San Ali, di lingkungan Pakuwan Caruban, pusat kota Caruban Larang, sekarang dikenal sebagai Astana Japura, sebelah Tenggara Cirebon. Sebuah lingkungan yang multi-etnis dan multi-bahasa, sebuah titik temu berbagai kebudayaan dan peradaban. Syekh Siti jenar adalah putra seorang ulama dari Malaka, Syekh Datuk Shaleh. Selama kurang lebih 15 tahun, yaitu sampai umur 20 tahun, San Ali belajar di Padepokan Giri Amparan Jati di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Kemudian ia bertekad untuk mencari sangkan-paran dirinya. Di luar padepokan tersebut, banyak terdapat pertapa dan ahli hikmah Hindu-Budha, dari antara mereka adalah Rsi Samsitawratah. San Ali mempelajari kitab Catur Viphala, warisan Prabu Kertawijaya Majapahit dari Sang Rsi ini. Kitab rontal Catur Viphala mengajarkan tentang nihspraha, nirbana, niskala, nirasraya. Rsi Samsitawratah menjelaskan bahwa nihspraha merupakan keadaan di mana manusia tidak lagi ingin mencapai sesuatu. Nirbana adalah keadaan di mana manusia telah melepaskan kebertubuhan dan badannya sehingga tidak ada lagi tujuan. Niskala adalah keadaan di mana manusia menyatu dengan Yang Hampa, Yang Tak Terbayangkan, Tak Terpikirkan dan Tak Terbandingkan. Nirasraya merupakan keadaan di mana jiwa meninggalkan niskala dan melebur ke Prama-Laukika, yaitu Yang Bebas Dari Segala Bentuk Keadaan, yang tidak memiliki ciri dan sifat, dan mengatasi Aku. Inilah ajaran yang ikut membentuk pencarian diri San Ali.
San Ali melanjutkan pengembaraannya ke Palembang, belajar tentang kosmologi emanasi (martabat tujuh) kepada Arya Damar, seorang santri Maulana Ibrahim Samarkandi. Dari Palembang, San Ali pergi ke Malaka dan memasuki dunia dagang dengan menjadi saudagar emas dan barang kelontong. Ia banyak bergaul dengan para bangsawan Tamil dan Melayu. Di situlah San Ali mempelajari beberapa karakter nafsu manusia, sekaligus menguji laku zuhudnya di tengah gelimang harta. Pada saat yang sama, San Ali juga menyiarkan agama Islam dan diberi gelar Syekh Jabaranta oleh masyarakat setempat. Di situ pula dia bertemu dengan pamannya, Syekh Datuk Ahmad dan dianugerahi nama keluarga dan nama keulamaan yaitu Syekh Datuk Abdul Jalil.
Syekh Siti Jenar memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pencariannya itu sampai ke Timur Tengah. Syekh Siti Jenar menuju ke Timur Tengah bersama ulama Malaka asal Baghdad, Ahmad al-Tawalud. Sesampainya di Baghdad dan menumpang di rumah keluarga besar Ahmad al-Tawalud, Syekh Siti Jenar bersentuhan dengan paham Syiah Jafariyyah, yang dikenal sebagai mazab ahl al-bayt. Ia juga membaca dan mempelajari dengan baik tradisi sufi yang ditulis
oleh al-Bustami, al-Hallaj, al-Ghazali, Ibnu Arabi dan terutama sekali al-Jili. Lalu di tahun 1457, Syekh Siti Jenar menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Sekembalinya dari Mekkah, Syekh Siti Jenar tidak langsung ke Jawa. Ia singgah lagi di Baghdad, kemudian ke Ahmadabad, berdakwah di Gujarat, Goa, Calicut, Pasai, Palembang dan kembali ke Caruban Larang, tempat kelahirannya yang telah ia tinggalkan hampir selama 17 tahun itu. Karena menyebar-ajarkan Filsafat Sangkan-Paran itulah, maka Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Giri, menjatuhkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Pada Maret 1517, Syekh Siti Jenar meninggal di Cirebon.
Inti Filsafat Sangkan-Paran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar masih dapat dilacak dalam Kitab-kitab Serat dan Suluk, meskipun itu bukan tulisan langsung Syekh Siti Jenar sendiri. Berikut ini ajaran Syekh Siti Jenar yang dirangkum oleh Muhammad Sholikhin dari berbagai Serat dan Suluk tersebut:
“Sesungguhnya aku inilah haq Allah pun tiada wujud dua, nanti Allah, sekarang Allah, tetap dzahir batin Allah, kenapa kawan-kawan masih memakai pelindung?”
“…, sesungguhnya ingsun inilah Allah. Nyata Ingsun Yang Sejati, bergelar Prabu Satmata, yang tidak ada lain kesejatiannya, yang disebut sebangsa Allah…”
“… marilah kita berbicara dengan terus terang. Aku ini Allah. Akulah yang sebenarnya disebut prabu Satmata, tidak ada lain yang bernama Allah… saya menyampaikan ilmu tertinggi yang membahas ketunggalan. Ini bukan badan, selamanya bukan, karena badan tidak ada. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati dan untuk semua orang kita membuka tabir.”
“Tidak usah banyak tingkah, saya inilah Tuhan. Ya, betul-betul saya ini adalah Tuhan yang sebenarnya, bergelar Prabu Satmata, ketahuilah bahwa tidak ada bangsa Tuhan yang lain selain saya… Saya ini mengajarkan ilmu untuk betul-betul dapat merasakan adanya kemanunggalan.”
“Ashadu-keberadaanku, Ia ilahi-bentuk wajahku, illallah-Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya.”
“Syahadat Allah, Allah, Allah badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi (roh) idhafi, (roh) idhafi lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati, tinggallah hanya Allah semata yang abadi tidak terkena kematian.” (Muhammad Sholikhin, 2004, hlm: 169-180, 189).
Berdasarkan kutipan Serat dan Suluk di atas, dapat disimpulkan bahwa Syekh Siti Jenar percaya bahwa Innalillahi wa inna ilaihi raaji’un. Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali padanya. Allah adalah tempat kembali manusia yang sesungguhnya. Allah adalah dari mana manusia berasal dan hanya kepada-Nyalah semua kembali (Allah iku sangkan paraning dumadi). Manusia dan Allah secara ontologis, sungguh-sungguh merupakan satu kesatuan hakiki. Tidak ada yang berbeda sama sekali di dalam-Nya. Kesehakikatan Allah-manusia digambarkan oleh Syekh Siti Jenar:
“Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af’al (perbuatan) Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah”
“Af’al Allah harus dipahami dari dalam dan dari luar diri. Saat manusia menggoreskan pena, misalnya, di situlah terjadi perpaduan dua kemampuan kodrati yang dipancarkan oleh Allah kepada makhluknNya, yakni kemampuan gerak pena. Di situ berlaku dalil Wa Allahu khalaqakum wa ma ta’malun (Qs. Ash-Shaffat: 96), yang maknanya Allah yang menciptakan engkau dan segala apa yang engkau perbuat. Di sini terkandung makna mubasyarah. Perbuatan yang terlahir dari itu disebut al-tawallud. Misalnya saya melempar batu. Batu yang terlempar dari tangan saya itu adalah berdasar kemampuan kodrati gerak tangan saya. Di situ berlaku dalil Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allaha rama (Qs. Al-Anfal: 17), maksudnya bukanlah engkau yang melempar, melainkan Allah jua yang melempar ketika engkau melempar…” (Muhammad Sholikhin, 2004, hlm: 211-212)
Dari ajaran ini kemudian muncul pandangan yang dikenal sebagai Manunggaling Kawula-Gusti, bersatunya hamba-Allah. Kemanunggalan ini merupakan kunci pengetahuan dan segala kesempurnaan hidup. Manusia yang telah mencapai kesatuan dengan Allah, berada dalam kebahagiaan hidup yang sejati. Dan bagi Syekh Siti Jenar, kesempurnaan hidup itu dapat diraih hanya melalui pengalaman kematian. Karena, Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan ini sebenarnya adalah alam kematian. Hidup manusia dipandangnya sebagai kematian. Oleh karena itu ia bertekad untuk mengakhiri kematian yang dialami di dunia ini, untuk mencapai kehidupan yang abadi.
“Di dunia ini manusia mati. Siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, mengharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali. Tapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam
alam kematian…”
“… Kelahiranku di dunia alam kematian itu demikian susah payahnya karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru.”
“… kayun daim layamuta abadan, artinya hidup tidak kenal mati, langgeng untuk selama-lamanya. Oleh karena ini bukan alam kehidupan. Itulah sebabnya kamu itu mati, di dunia ini kamu dalam alam kematian…”
“Itulah sebabnya dunia yang saya tempati sekarang ini saya namai alam kubur…”
“ Siang malam saya menangis memilukan, menyesal sekali karena saya tersesat di dunia kematian ini. Saya menyandang daging dan tulang, naik kereta dipayungi sakit, tidur di kasur dikipasi, tapi badan terasa kaku, lagi pula hati merasa sedih…” (Muhammad Sholikhin 2004, hlm: 242-253)
Pandangan ini bukan ajaran mistik spekulatif dan ajakan untuk membenci
kehidupan di dunia ini. Justru dari sini, Syekh Siti Jenar mengajak manusia untuk menjadi orang yang saleh rohani, bermanfaat secara sosial, menjadi penggerak peradaban, memiliki kinerja yang tinggi serta produktif, aktif dalam gerakan kemanusiaan dalam melawan segala bentuk kezaliman. Dalam jasadnya, memang manusia memiliki sifat atau watak buruk, yang kemudian memunculkan perilaku buruk. Namun sifat dan watak buruk itu bukanlah bersifat azali (asli) dan hakiki.
Manusia di alam kematian ini harus melakukan aktivitas untuk memelihara tubuh jasadnya ini dari kerusakan, untuk menunda kematian, yang disebut sebagai ibadah kepada Allah yang menyediakan raga ini. Syekh Siti Jenar menegaskan kehidupan di dunia alam kematian ini berguna untuk menjalani kodrat diri kita masing-masing. Kodrat adalah cetak biru yang telah ditetapkan Allah atas setiap roh sejak sebelum dilahrikan di dunia. Dan perjalanan kodrat seiring dengan iradat. Iradat ini terdapat dalam roh, dan untuk terwujud sebagai kodrat membutuhkan kendaraan yang berupa raga atau jasad jasmaniah. Tubuh jasmaniah ini tidak kekal dan membutuhkan pangan, sandang dan papan untuk memelihara dan mengaturnya. Oleh karena itu hidup di dunia alam kematian ini adalah untuk menunda kematian.
Usaha keras ini, apabila dilandasi oleh pengertian yang diperjuangkan oleh Syekh Siti Jenar, dikenal juga sebagai mati sajeroning urip (mati dalam hidup). Maka sebagai kawula, manusia hanya memiliki satu tempat untuk ia kembali, yakni Allah, sebagai asalnya. Manusia tidak boleh terjebak dalam wadag yang hanya berfungsi sementara sebagai wadah Roh Ilahi. Justru Roh Ilahi inilah yang
harus dijaga guna sampai pada kemanunggalannya kembali. Syekh Siti Jenar menekankan kemanunggalan dengan mengacu kepada kehidupan sejati setelah kehidupan di alam kematian ini. Oleh karenanya syariat Islam dipandang tidaklah begitu diperlukan di dunia alam kematian sekarang ini. Kemanunggalan di dunia ini hanyalah langkah awal saja menuju kemanunggalan abadi. Setelah melewati pintu kematian, manusia masuk ke alam kehidupan sejati dan bersatu dengan Allah. Pada bagian lain Syekh Siti Jenar menegaskan bahwa:
“Sungguh telah keliru mereka yang mengatakan kematian adalah akhir dari kehidupan. Sebab, apa yang disebut Sang Maut (al-Mumit) sejatinya adalah Satu Diri dengan Sang Hidup (al-Hayy). Hanya mereka yang bodoh dan lancang mulut yang mengatakan kematian adalah akhir dari kehidupan. Apakah mereka sangka Allah bisa mati tidak bernyawa? Aku katakan sekali lagi, sungguh bodoh dan lancang mulut mereka yang mengatakan Mati sebagai sesuatu yang tidak bernyawa.”
“… Sang Maut adalah Sisi Lain dari Sang Hidup. Namun sekaligus adalah Satu Diri yang sama…” (Agus Sunyoto, 2004, hlm: 227-229)
Tidak ada perbedaan antara kematian dan kehidupan, mati dan hidup adalah suatu kewajaran. Namun bagi mereka yang terikat, melekat dan mencintai kehidupan, kematian merupakan sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Mereka takut mati, karena mereka menganggap hidup ini bersifat abadi dan mutlak. Mereka sangat mengagungkan kehidupan dan menyepelekan serta menyangkal kewajaran kematian. Sementara di sisi yang lainnya, ada yang sangat mendambakan kematian sebagai suatu yang luhur-ilahi, namun membenci dan memusuhi kehidupan sebagai suatu kutukan neraka. Syekh Siti Jenar menempatkan ajarannya pada sisi yang tepat. Ia memandang kehidupan dan kematian sebagai suatu kewajaran yang normal, netral tanpa muatan nilai etis atau moral. Demikian juga masalah baik-buruk yang terjadi di dalam dunia ini tidak lepas dari kemanunggalan dengan Allah, seperti yang telah dikatakannya:
“Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini pada hakikatnya adalah af’al (perbuatan) Allah. Berbagai hal yang dinilai baik maupun buruk pada hakikatnya adalah dari Allah juga. Jadi keliru dan sesat pandangan yang mengatakan bahwa yang baik dari Allah dan yang buruk dari selain Allah”… (Muhammad Sholikhin, 2004, hlm: 211)
Dari penjelasan Syekh Siti Jenar seperti itu, para pengikutnya menarik nilai pragmatis Filsafat Sangkan-Paran untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai ketenangan dan harmoni hidup. Sebagaimana dicatat oleh Achmad Chodjim, bahwa dalam menyongsong kematian, para pengikut
ajaran Syekh Siti Jenar harus menyadari tiga hal, yaitu: Syahadat Tanpa Iman, bahwa kebenaran itu bukan kebenaran ajaran ini atau itu, melainkan pengalaman sadar akan Kebenaran Tunggal yang menyatu dalam diri manusia. Takbir Tanpa Tauhid, sadar bahwa manusia itu tenggelam dalam kebakaan Yang Tunggal itu sebagaimana ikan di tengah samudra raya yang tidak dapat lolos dari sergapan air. Syakaratul Maut Tanpa Makrifat, sadar bahwa yang mengetahui dan yang diketahui itu Tunggal adanya, hanya ada entitas yang manunggal, bukan dua tetapi juga bukan satu. Lebih praktis lagi,
Muhammad Sholikhin menjelaskan bahwa Syekh Siti Jenar mengajarkan dua macam bentuk shalat, yaitu shalat tarek dan shalat daim. Shalat tarek adalah shalat thariqah, di atas sedikit dari syari’at. Shalat tarek ini diperuntukkan bagi orang yang belum mampu untuk sampai pada tingkatan Manunggaling Kawula-Gusti. Sedangkan shalat daim merupakan shalat yang tiada putus sebagai dampak dari pengalaman batin kemanunggalan itu. Shalat tarek masih terbatas dengan lima waktu shalat, sedangkan shalat daim adalah shalat yang tiada putus sepanjang hayat, dan teraplikasi dalam keseluruhan tindakan sehari-hari, sebagai pemandu hati, nalar dan tindakan ragawi. Dalam istilah lain, semua itu disebut sebagai eling lan waspada; sadar, ingat dan waspada, berjaga (tahajud). Dari kedua praktik berdasarkan ajaran Syekh Siti Jenar tersebut, maka doa yang kita panjatkan di sini sebagaimana doa yang diajarkan oleh Meister Eckhrat (1260-1328), yaitu doa permohonan kepada Allah supaya kita dijauhkan dan terbebas dari Allah.
Dalam Sejarah Filsafat Barat, Filsafat Sangkan-Paran seperti ini dapat juga bahkan ditemukan pada awal mula Filsafat Yunani Kuno sekitar 700 tahun sebelum Masehi, atau lebih dari 2700 tahun yang lalu. Mereka mencari tahu dan mempersoalkan arkhe, asas atau prinsip pertama alam semesta ini. Menurut Thales air adalah arkhe itu, Anaximandros menyebutnya sebagai to apeiron (yang tak terbatas), bagi Anaximenes segala sesuatu itu berasal dari udara, Herakleitos menyatakan api sebagai asal semesta ini, Empedokles melihat ada empat anasir (rizomata): air, udara, api dan tanah, Anaxagoras menyebutnya spermata, dan Demokritos menyebutnya sebagai atomos. Untuk mempertajam refleksi kita terhadap Filsafat Sangkan-Paran Syekh Siti Jenar, ada baiknya kita meninjau juga Filsafat Identias Baruch De Spinoza (1632-1677).
Spinoza memandang bahwa arkhe hanya terdiri dari satu substansi, yaitu Allah itu saja. Allah, alam semesta dan manusia itu adalah satu substansi yang tunggal, satu-satunya. Seluruh kenyataan ini merupakan satu kesatuan, kesatuan yang sama sekali lebur dalam Allah. Dengan pandangannya ini, Spinoza telah merintis apa yang kemudian disebut oleh para ahli Filsafat sebagai Filsafat Identitas. Filsafat Identitas, yaitu usaha untuk mendamaikan antara subjek dan objek, yang tidak terbatas dengan yang terbatas, yang sampai zaman itu menjadi problem dan skandal dalam Filsafat. Dengan Filsafat
Identitasnya tersebut, Spinoza berhasil melebur-hilangkan perbedaan subjek-objek. Realitas kemudian dipahami sebagai suatu satu keseluruhan yang utuh, di mana subjek sekaligus merupakan objek. Berkaitan dengan manusia, Spinoza menjelaskan bahwa Allah sebagai substansi ini memiliki atribut, dan atribut itu mempunyai modi. Atribut adalah ciri hakiki dari substansi. Pada dasarnya substansi memiliki ciri hakiki (atribut) yang tak berhingga, namun ada dua atribut yang dapat kita kenali, yaitu keluasan (extensio) dan kesadaran (cogitato). Atribut ini memiliki cara-cara berada (modi), dan secara tidak langsung merupakan cara berada dan bentuk dari substansi itu sendiri. Manusia adalah bentuk dan cara berada atribut Allah itu sendiri. Manusia dengan tubuh (extensio) dan pemikirannya (cogitato) sebagai ciri hakiki substansi Allah.
Penerus Filsafat Identitas Spinoza ini, yaitu FWJ. Schelling (1775-1854), menegaskan bahwa dalam pandangan ini, Yang Mutlak tidak memiliki prioritas atau lebih utama terhadap yang tidak mutlak. Atau juga, yang tidak mutlak tidak lebih unggul dibandingkan dengan Yang Mutlak. Karena kedua-duanya berasal dari sumber yang sama dan satu, dan yang bersifat sama sekali netral, yang oleh Schelling diberi nama sebagai Identitas Mutlak atau Indiferensi Mutlak Murni. Dasar atau asal atau sumber realitas ini tidak dapat dianggap subjektif atau objektif, material atau spiritual, sebab pertentangan atau oposisi yang terdapat di sini ada dalam bentuk kesatuan yang tak terpisahkan dan tak berlawanan. Yang natural dan yang spiritual tidak saling mengungguli, melainkan membentuk dua kutub yang derajatnya sama. Yang spiritual selalu hadir dalam yang natural dan yang natural selalu hadir dalam yang spiritual. Dalam istilah teknik kebatinan Jawa, pemikiran Filsafat Identitas ini adalah Manunggaling Kawula-Gusti, yang merupakan juga sangkan paraning dumadi.
Dalam Filsafat Identitas Spinoza, Allah yang tiada batasnya itu dipahami sebagai aktivitas yang tak terhingga. Aktivitas ini meliputi berpikir yang murni dan menghendaki yang murni. Allah adalah pikiran yang sedang memikirkan dan menyadari pikiran dan diri-Nya sendiri. Menegaskan Spinoza, Schelling menyatakan bahwa Yang Mutlak ini pada dirinya adalah suatu aktivitas menyadari diri yang bersifat kekal, yang terjadi terus-menerus. Secara teori, aktivitas ini digambarkan sebagai suatu peristiwa yang terjadi dalam tiga tahap. Yaitu tahap subjektif, objektif dan mutlak. Bagi Schelling, gambaran ini harus dipandang sebagai cara kita memahami dan menguraikan saja, namun tidak boleh dimengerti sebagai peristiwa yang terjadi dalam urut-urutan waktu.
Filsafat Identitas mencapai puncaknya dalam filsafay GWF. Hegel (1770-1831), Di mana Filsafat Fenomenologi Roh Hegel, menjelaskan bahwa secara dialektis Yang Mutlak itu menyadari dirinya sendiri secara subjektif dalam bentuk logika pada diri psikologis perorangan manusia (tahap subjektif); lalu keluar dari dirinya dan menjadikan dirinya berbeda di luar dirinya dalam bentuk tatanan peraturan, hukum, moral, kesusilaan, dan lembaga-lembaga seperti keluarga,
masyarakat dan negara (tahap objektif); dan kemudian dari situ kembali berada dalam keadaan dalam dirinya dan bagi dirinya sendiri dan bermukim dalam seni, agama dan filsafat (tahap mutlak). Lebih jauh lagi, bagi Hegel, dalam diri manusia, Yang Mutlak atau Roh itu sudah menjadi sadar akan dirinya sendiri. Tetapi proses penyadaran ini secara dialektis berlangsung terus dalam sejarah manusia, hingga akhirnya mencapai titik penghabisan.
Hegel percaya bahwa pada masanya itu, yaitu awal abad 19, Roh sudah menjadi Mutlak dan karena itu proses penyadaran Roh sudah selesai. Pengejawantahan Roh Absolut mencapai puncaknya dan berhenti dalam segala bidang, dalam bidang politik adalah negara Prusia, setelah revolusi Perancis dan peristiwa di sekitar Napoleon, dalam bidang agama adalah agama Kristen Protestan Lutheran Jerman, dalam seni adalah musik klasik masa itu, dalam bidang filsafat adalah filsafat Hegel itu sendiri yang sanggup memperlihatkan Roh Absolut menjadi sadar akan dirinya dalam arti sepenuh-penuhnya. Sejarah manusia kemudian hanyalah mengulang bentuk dan tahapan lama, tidak ada lagi peristiwa yang sungguh-sungguh baru akan terjadi. Allah dalam pikiran Hegel sungguh-sungguh menjelma secara imanen, identik dengan seluruh peristiwa historis manusia, sampai yang sekecil-kecilnya. Bagi Hegel, Manunggaling Kawula-Gusti itu secara imanen sedang terjadi dan terlaksana dalam kenyataan historis manusia sehari-hari saat ini. Pada masa kita ini, pemikiran Hegelian seperti itu telah direlevansikan dengan perkembangan sejarah masa kini oleh Francis Fukuyama (1952).
Bagi Spinoza kesadaran manusia merupakan kemanunggalan dengan substansi. Spinoza memperhitungkan pengenalan dan kesadaran itu sebagai kebahagiaan dan kebebasan. Kebebasan di sini, dilihat agak lain dari pendapat umum. Spinoza memandang kebebasan itu sebagai suatu perasaan atau anggapan manusia saja. Karena kebebasan untuk memilih itu tidak ada. Sehingga perasaan bebas ini hanya dapat diraih dengan pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif yang dimaksudkan di sini merupakan bentuk pengetahuan yang memandang realitas segala sesuatu dari sudut pandang keabadian (sub specie aeternitatis). Pengetahuan ini, disebut juga sebagai kontemplasi yang menyadari kemanunggalan segala sesuatu sebagai suatu kesatuan substansial, dan sebagai hasilnya, manusia mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan, karena dia tidak lagi membeda-bedakan realitasnya. Tidak ada beda antara manusia-semesta-Allah, maka kita menyadari Allah. Kesadaran ini sangat membahagiakan. Kebahagiaan ini membuat kita mencintai Allah, cinta intelektual kepada Allah (amor Dei intellectualis). Cinta kepada Allah, karena merupakan keterbukaan kita pada realitas yang sebenarnya, yang bersifat abadi. Cinta ini sebenarnya adalah cinta Allah terhadap diriNya sendiri. Manusia adalah modus atau cara Allah menyadari sekaligus mencintai diri-Nya sendiri.
Kesejajaran Filsafat Sangkan-Paran Syekh Siti Jenar dengan Filsafat Identitas Spinoza kiranya dapat membantu kita untuk memiliki pilihan cara memandang realitas, tidak hanya dari sudut pandang kemewaktuan (sub specie temporis), melainkan juga kita dapat memandang dari perspektif keabadian (sub specie aeternitatis). Kita dituntut untuk dapat menjaga ketegangan kedua sudut pandang tersebut, sekaligus ditantang untuk meloloskan diri dari apa yang disebut oleh Georges Bataille (1897-1962) sebagai “escape” dan “plan”.
“Escape” dan “plan” adalah sebuah bentuk usaha manusia karena tidak tahan terhadap pedih-perihnya penderitaan dalam menghadapi misteri Sang Mutlak yang tak terungkapkan dan tak terpahami (tan kena kinaya apa), lalu terjebak dalam pikiran yang tenggelam dalam kemewaktuan (“Filsafat non-identitas”) ataupun dalam keabadian (“Filsafat identitas”). Pengakuan tentang keselamatan, sorga, moksa, nirwana, dst., merupakan bentuk umum dari “escape” dan “plan”. Tulisan ini menawarkan sebuah langkah kecil yang harus diambil untuk keluar dari jebakan “escape” dan “plan”, yaitu keheningan, kasunyatan. Keberanian untuk keluar dari tirani kata dan pikiran. Langkah kecil ini bukan merupakan tahapan lebih tinggi dari ketegangan yang harus kita pertahankan seperti yang telah dijelaskan di atas tadi. Langkah kecil ini merupakan sesuatu yang simultan terjadi dengan ketegangan tersebut dalam suatu momen traumatis yang mengerikan sekaligus menggembirakan. Langkah ini membuka sebuah ketegangan lagi, yang harus tetap dipelihara bersama ketegangan antara cara pandang dalam keabadian dan dalam kemewaktuan yang telah ada sebelumnya tadi itu.
Sebagaimana Nietzsche (1844-1900), yang tidak hanya ingin dijauhkan dan terbebas dari Allah seperti halnya Meister Eckhart, tetapi kita harus tega secara jujur dan elegan, membunuh bahkan Allah yang paling kita imani dan cintai itu sekalipun. Pengalaman batiniah manusia seperti ini, apabila kepadanya diajukan pertanyaan tentang arkhe atau sangkan-paran, maka yang ia ketahui hanyalah: “Knowing of unknowing” dan pengakuan imannya adalah: “I know nothing” (mbuh ‘ra ruh). Hening-Suwung. Seperti yang dikatakan oleh Kho Ping Hoo, bahwa sesungguhnya Yang Ada itu Bukan, karena Yang Ada itu diadakan oleh Pikiran Manusia. Oleh sebab itu kita hendaknya belajar meneliti diri sendiri, mengenal diri sendiri dan segala gerak-gerik pikiran dan perasaan kita.
*Penulis adalah Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia
Kepustakaan
Bataille, Georges. Inner Experience. SUNY Press, New York 1988.
Bertens, Kees. Ringkasan Sejarah Filsafat. Kanisius, Yogyakarta, 1975.
Bertens, Kees. Sejarah Filsafat Yunani. Kanisius Yogyakarta, 1999.
Chodjim, Achmad. Syekh Siti Jenar. Makna Kematian. Serambi, Jakarta 2002.
Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 1. Kanisius, Yogyakarta, 1980.
Hadiwijono, Harun. Sari Sejarah Filsafat Barat 2. Kanisius, Yogyakarta, 1980.
Hamersma, Harry. Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern. Gramedia, Jakarta, 1990.
Kho Ping Hoo. Sepasang Pedang Iblis. Gema, Solo, 1973.
Magnis-Suseno, Franz. 13 Tokoh Etika. Kanisius, Yogyakarta, 1997.
Magnis-Suseno, Franz. 13 Model Pendekatan Etika. Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Magnis-Suseno, Franz. Pijar-Pijar Filsafat. Kanisius, Yogyakarta, 2005.
Magnis-Suseno, Franz. Menalar Tuhan. Kanisius, Yogyakarta, 2006.
Sholikhin, Muhammad. Sufisme Syekh Siti Jenar. Narasi, Yogyakarta, 2004.
Sunyoto, Agus. Suluk Abdul Jalil. Perjalanan Ruhani Syaikh Siti Jenar. Jilid 1. LKIS, Yogyakarta, 2003.
Sunyoto, Agus. Sang Pembaharu. Perjuangan Dan Ajaran Syaikh Siti Jenar. Jilid 5. LKIS, Yogyakarta, 2004.
Van Der Weij, P. A. Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia. Gramedia, Jakarta, 1988.