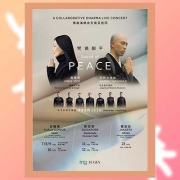Penerimaan Yang Terlambat
Oleh Adi Prayuda
“Pikiran selalu terlambat untuk menerima. Kesadaran lebih dulu menerima sebelum pikiran berusaha dan berpura-pura menerima. Karena pikiran perlu mengumpulkan alasan dulu, argumentasi dulu, kalimat-kalimat indah tentang masa depan yang cerah dulu, menciptakan halusinasi tentang kebahagiaan dulu, supaya ada pegangan dulu. Itulah kenapa pikiran selalu terlambat dalam urusan melepas.”
~Adi Prayuda
Menerima adalah kata yang cukup sering didengungkan oleh para praktisi meditasi. Sungguh kata yang meneduhkan dan ‘menyembuhkan’. Karena dengan begitu, harapannya, penolakan atau resistensi terhadap pikiran dan perasaan yang muncul di dalam batin pelan-perlahan menjadi berkurang. Dengan berkurangnya resistensi ini, penderitaan pun berkurang.
Namun, tentu saja ‘menerima’ di sini tidak berhenti pada dimensi kata, tapi menjadi sesuatu yang disadari di dalam batin. Saya menggunakan kata ‘disadari’, agar ‘menerima’ bisa menjadi sesuatu yang melampaui upaya tertentu yang bisa dilakukan oleh pikiran. Karena justru ‘upaya’ itulah yang lebih sering terjadi.
Ketika ditangkap oleh pikiran, ‘menerima’ menjadi sesuatu yang ‘perlu dilakukan’ terhadap kemunculan pikiran dan perasaan tertentu. Biasanya ‘upaya’ ini dilakukan terhadap pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan, tidak enak rasanya, atau dianggap negatif. Karena kalau menyenangkan, untuk apa ada ‘upaya menerima’? ‘Yang menolak’ adalah pikiran, ‘yang berusaha menerima’ itu adalah pikiran juga. Dan seringnya, setelah itu, terjadi konflik di dalam batin.
‘Upaya menerima’ ini tentu tidak salah. Ini adalah hal yang juga bisa menjadi objek meditasi. Kita bisa amati apa yang terjadi dalam ‘proses penerimaan’ yang dilakukan pikiran. Mula-mula penolakan terhadap pikiran dan perasaan tertentu teramati, kemudian dicoba ‘dilawan’ dengan ‘upaya lain’ yang disebut dengan ‘penerimaan’. Terjadi dua level penolakan. Dan yang kedua ini lebih halus dan religius.
Dalam berusaha menerima, pikiran selalu punya motif. Sekalipun motif itu adalah sesuatu yang ‘mulia’: Agar yang diterimanya menjadi ‘hilang’ atau bertransformasi menjadi ‘sesuatu yang lain’. Sedih diterima, agar sedih itu berubah menjadi senang. Marah diterima, agar kemarahan itu tidak terlalu lama ada. Jengkel diterima, agar jengkel itu segera pergi. Ada motif yang ‘sangat halus’ dari penerimaan yang dilakukan pikiran. Dalam meditasi atau jeda, kita sebenarnya bukan belajar untuk mengubah sedih menjadi senang, marah menjadi sabar, namun melihat sedih sebagai sedih dan melihat marah sebagai marah. Melihat sesuatu yang terjadi di dalam batin sebagaimana adanya.
Tidak ada rasa yang kekal dengan intensitas yang sama terus-menerus. Setiap rasa berpotensi untuk bertransformasi. Namun, transformasi atau perubahan itu tidak dijadikan tujuan dan dengan sengaja diupayakan melalui penerimaan, seolah-olah harus terjadi dan mengarah kepada rasa yang dianggap lebih baik. Apa yang sebenarnya ada di dalam rasa sedih? Apa yang terkandung di dalam rasa marah? Itulah yang dieksplorasi atau diselami. Rasa sedih tentu berbeda “tekstur” dan “sensasinya” dengan rasa senang, begitu juga dengan rasa-rasa yang lain. Namun, bila dilihat dengan jelas dan langsung menuju pusat rasanya, dengan mengabaikan seluruh drama yang ada, apakah bahan pembentuk dari rasa-rasa tersebut berbeda? Sama seperti ombak-ombak di lautan yang berbeda bentuk dan ketinggiannya, tapi apakah bahan dasar dari setiap ombak berbeda?
Saya jadi teringat pertanyaan seseorang, “Saya sudah sering meditasi, tetapi kenapa perasaan saya masih tidak enak?” Saya pun menjawab, “Karena bermeditasi bukan untuk mendapat perasaan enak dengan melawan perasaan tidak enak.” Esensi meditasi adalah menyadari. Namun, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa tujuan dari meditasi adalah untuk mencapai ketenangan, untuk mendapat rasa tenang. Rasa tenang ini dikejar dengan berbagai upaya, bahkan sampai dengan cara yang paling halus, yakni menerima rasa tidak tenang AGAR bisa mencapai rasa tenang. Semakin rasa tenang itu dikejar, justru rasa jengkel yang didapat.
Bila diamati dengan lebih seksama, rasa-rasa yang ‘tidak enak’ itu sebenarnya ‘sudah diterima’ di ‘ruang kesadaran’. Oleh karenanya, bisa muncul dan memberikan sensasi tertentu. Kemudian, pikiran yang ‘sudah diajari’ untuk ‘menerima’ segera ‘berupaya untuk menerima’ perasaan yang tidak enak itu. Jelas ada tujuannya. Gerakan ‘penerimaan’ yang dilakukan pikiran ini bisa diamati. Dan ‘penerimaan’ itu sebenarnya sudah terlambat. Rasa itu ‘sudah diterima’ terlebih dahulu oleh kesadaran, sehingga bisa ada di dalam batin kita. Pikiran memang “seolah-olah” bisa menerima, tapi tentu ada syarat-syaratnya, tentu ada perhitungannya sehingga sesuatu itu menjadi “layak” untuk diterima. Pikiran pun bisa “seolah-olah” bersyukur, tapi tentu ada ketentuannya. Perlu ada pembanding yang lebih buruk, sehingga syukur itu bisa terpancar keluar. Pikiran pun bisa “seolah-olah” mencintai, tapi cintanya pikiran tentu tidak bebas dari pertimbangan untung dan rugi.
Upaya ‘penerimaan’ yang dilakukan pikiran ini sudah cukup memberi informasi bahwa ada resistensi di dalam batin. Ada ‘ketidaksukaan’ yang muncul sebagai respon terhadap rasa yang hadir. Yang itu memunculkan penderitaan. Amati saja gerakan penerimaan yang dilakukan pikiran ini. Karena ini pun tidak salah. Hanya saja, dengan mengamati itu, kita sedikit ‘menyingkir’ dari arus gerakan pikiran dan tidak terjebak di dalamnya. Kalaupun akhirnya ‘terseret kembali’, tidak apa-apa. Disadari kembali.
Beberapa orang mungkin pernah mencoba ‘cara baik’ untuk menerima rasa sedih, marah, jengkel, kecewa, dengan harapan, agar rasa-rasa itu bertransformasi menjadi rasa yang ‘lebih positif’. Ada yang bisa, ada yang seperti melawan sesuatu. Ada juga yang akhirnya kelelahan karena harus ‘sok kuat’ menerima rasa yang sebenarnya masih cukup sulit untuk diterima. Menjadi sulit karena ada ‘harapan terselubung yang sangat halus’ sebagai tanda dari gerakan pikiran. Bila masih sulit, tidak perlu terlalu keras kepada diri sendiri. Cukup mulai dengan menerima bahwa diri ini belum bisa menerima. Dan pelan-pelan menyadari, bahwa semenjak rasa itu muncul, rasa itu ‘sudah diterima’ di ruang batin kita sendiri.
***
*Penulis adalah Pengasuh “Ruang Jeda”