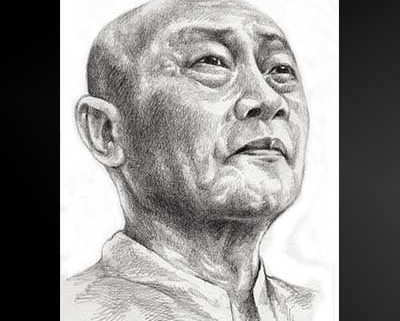Riset Kesenian dan Perubahan Sosial, Sejumlah Masalah
(surat terbuka untuk Agung Hujatnikanjenong & Gita Hastarika)
Oleh Halim HD
Jenong dan Gita, Kemarin, setelah mendengarkan paparan tentang “riset” (di antara tanda petik!) anda berdua melalui daring, pada tanggal 17 Desember 2021, Jum’at jam 15.-17.00, bertajuk “Ranah Labil: Seni dan Perubahan Sosial di Indonesia” program dari Selasar Sunaryo dan didukung oleh Kurawal Foundation, Bandung, dengan titik tolak melihat kesenian pada era pasca Reformasi, ada dorongan untuk menulis surat. Tapi saya batalkan. Beberapa kali saya mencoba duduk di depan laptop untuk menulis tapi gagal. Hari ini, 18 Desember 2021, saya pikir, ada baiknya saya lanjutkan niatan saya untuk menulis surat ini sebagai upaya saya untuk berpartisipasi dalam “riset” anda.

Foto poster acara diskusi Ranah Labil: Seni dan Perubahan Sosial di Indonesia.
Rangsangan untuk menulis surat itu, sehubungan dengan banyak hal yang anda sodorkan kepada saya, tapi sodoran masalah itu rasanya seperti melayang-layang dan sibuk dengan kesimpangsiuran. Itu kesan saya. Sebagai kesan tentu saja karena hal itu saya rasanya seperti derasnya lintasan informasi, mirip seperti grup-grup WA atau di fesbuk. Saya pikir, ada baiknya juga saya kemarin menunda berulang kali rencana menulis surat, dan baru siang hari ini saya kerjakan.
Menurut saya, penyelenggaraan diskusi daring “hasil riset” anda itu kurang terarah. Jika saja anda mengirimkan ringkasan atau poin-poin “hasil riset” anda beberapa hari sebelumnya via imel kepada teman-teman yang diundang, sangat mungkin diskusi itu akan lebih intensif, dan yang diundang sudah lebih tahu isi “hasil riset” yang ingin anda paparkan. Jadi, paparan yang begitu panjang dari Gita yang bagaikan laporan “daftar istilah” bisa dipersingkat, dan tinggal memaparkan konten dari “daftar istilah” itu. Sayangnya paparan yang begitu panjang, saya merasa seperti membaca status di fesbuk yang tak memberikan analisa yang lebih mendalam. Itulah makanya, komen saya kepada apa yang disampaikan oleh Yudi Tajuddin pada chat yang menyatakan bahwa “riset” anda itu “grounded” (di antara tanda petik!), saya beri komen: jika pesawat grounded ada di hanggar. Sementara Yudi punya persepsi “grounded” yang disampaikan berkaitan dengan suatu periode dari peristiwa kesenian dan kebudayaan dalam rentang kesejarahan, yakni pasca Reformasi. Bagi saya, pasca Reformasi bisa saja menjadi “obyek dari grounded research”. Tapi saya tidak bisa membayangkan, suatu rentang periode kesejarahan yang demikian panjang, dua puluhan tahun sementara tak ada fokus dan ruang sosial yang menjadi titik perhatian di dalam memahami dan melacak akar persoalan. “Grounded research” yang menarik bagi saya, terletak pada fokus kasus. Sementara “riset” anda begitu luas. Itulah makanya bagi saya, apa yang anda kerjakan barulah tahapan “kompilasi” sejumlah masalah kesenian sebagai subyek yang akan jadi materi di dalam pemetaan.
Jika sekiranya anda bersetuju dengan “pemetaan”, yang kalau tidak salah juga disinggung oleh Iwan Pirous, bahwa “hasil riset” anda baru tahap sejenis inventarisasi dari “jenis-jenis gerakan” atau “aksi kesenian”. Pemetaan ini penting walaupun menurut saya, peta yang anda sodorkan itu belumlah sepenuhnya bisa mewakili semua dari “aksi dan gerakan kesenian”. Misalnya saya mau ambil contoh tentang “aksi” atau kegiatan yang dilakukan oleh jaringan komunitas seni di Makassar yang menciptakan jaringan dengan berbagai daerah dalam kaitannya dengan tema kemaritiman dan ekologi-arkeologi. Hal yang lainnya, apa dilakukan oleh komunitas teater di Sumatera Utara berkaitan dengan situs-situs arkeologi dan kesejarahan. Ini hanya untuk menyebut dua kasus. Sementara itu di Jembrana jaringan seniman, pelajar dan kampus dengan warga desa. Tentu saja anda bisa memasukan hal itu ke dalam suatu “kategori” seperti apa yang dipaparkan oleh Gita.
Tapi, titik kelemahan yang disampaikan oleh Gita terletak pada tiadanya pendalaman pada “data-data” yang masuk dalam kompilasi. Itulah makanya saya menyebut pada chat, semuanya masuk ke dalam keranjang. Ini mirip seperti anda masuk ke pasar, super market, atau mall dan anda “memborong” semuanya. Sekali lagi saya ingin menyatakan, bahwa “riset” anda bertajuk waktu pasca Reformasi bukanlah suatu “grounded research”. Walaupun anda bertemu dengan beberapa narasumber. Tapi itu bukan “grounded”. Grounded research” mestilah memasuki peristiwa, dan mengetahuinya secara langsung.
Dan sekali lagi juga saya ingin menyatakan, bahwa “borongan” anda ini lumayan penting untuk dilanjutkan agar pemetaan bisa lebih detil. Kerincian dari pemetaan “aksi dan gerakan kesenian” sangat dibutuhkan oleh kita semuanya agar kita tahu di mana ruang-ruang kesejarahan yang tidak tunggal bisa dibentuk, dan sejauh manakah dinamika ruang-ruang sosial itu memberikan suatu inspirasi kepada ruang sosial lainnya. Di antara begitu banyak “aksi dan gerakan kesenian” sangat mungkin ada benang merah, namun juga sekaligus ada sesuatu yang mungkin tak terjalin, tak terhubung karena basis material yang berbeda dari proses penjadian “aksi dan gerakan kesenian” yang tercipta.
Saya membayangkan, dan ini berkaitan dengan prosedur riset sehubungan dengan bahasan yang disampaikan oleh Iwan Pirous dan Hendro Wiyanto. Sekiranya saja kerangka awal “riset” anda sebelum “turun ke lapangan” dibahas oleh Iwan Pirous dan Hendro Wiyanto, saya kira sangat mungkin tercipta suatu penajaman perspektif dalam memandang masalah, suatu fokus. Sangat menarik melalui bandingan Iwan Pirous memberikan perspektif yang membuka kepada dasar pemikiran tentang suatu ‘kategori” yang mungkin tidak bisa diterapkan kepada suatu “obyek” tertentu karena adanya waktu yang berbeda. Lebih menarik lagi yang dilontarkan oleh Iwan Pirous tentang “spirit nasionalisme” berkaitan dengan dengan zaman yang kuat kaitannya dengan topik dan tematik dari yang akan diriset.
Apa yang disampaikan oleh Hendro Wiyanto melalai kasus “Perdebatan Sastera Kontekstual 1984-86”, dan peristiwa lain yang dilakukan oleh Danarto, dan kutipan dari riset Prof Sartono Kartodirjo ingin mengajak kepada kita, bahwa ada pola-pola dari suatu “aksi dan gerakan kesenian” yang satu dengan lainnya saling berkait. Itu penangkapan saya. Jika penangkapan saya benar, maka apa yang terjadi pada pasca Reformasi tak bisa lepas dari peristiwa pra Reformasi. Bayangkan, betapa tugas anda berdua makin berat, karena lintasan sejarah yang lampau menguntit terus di antara periode yang ingin anda lacak ke dalamannya.
Saya jadi teringat ketika anda berdua datang ke Plesungan, dan kita kongko, dan ketika anda melontarkan pertanyaan tentang pasca Reformasi, saya malah mencoba untuk mempertanyakan apa yang dikerjakan pada pra Reformasi. Pertanyaan-pertanyaan selalu bermunculan pada saya tentang pra Reformasi, pada rezim Orba, dan bahkan saya tarik kepada periode ketika Lekra, Lesbumi, LKN masih Berjaya dengan ideologi mereka. Misalnya saya selalu bertanya-tanya, apa sebenarnya “teater pembebasan”, apa sebenarnya “kesenian terlibat”, “Seni Untuk Masyarakat” ataukah “Seni Dari Masyarakat”, dan sebagainya. Saya banyak kasus tentang hal ini dari periode tahun 1970-80-90-an, dan kasus-kasus itu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan juga seiring dengan perubahan cara berpikir dan tentu saja seiring dengan bermunculan berbagai teori kajian.
Saya ingin menyinggung soal “desentralisasi” yang kini saya ragukan, walaupun saya pernah ikut arus pemikiran ini sejak tahun 1970-80-an. Keraguan saya pada, pertama secara politik ekonomi kebudayaan yang dikelola pemerintah di pusat dan daerah. Praktek politik ekonomi kebudayaan ini sekarang justeru makin menguatkan “sentralisasi” kegiatan pada sektor pemerintah, apalagi secara khusus dikaitkan antara kesenian dengan pariwisata. Bermunculannya berbagai komunitas memang terjadi, dan itu sangat menggembirakan. Saya sendiri punya prinsip bahwa komunitas ini merupakan basis dalam sistem produksi kesenian, dan hal itu terbukti sejak jauh sebelum Republik ini berdiri, di mana komunitas adat, keluarga tradisi dan lalu bermunculan sanggar seni modern menjadi tulang punggung dari perkembangan kesenian “nasional”. Menarik yang disampaikan oleh Iwan Pirous tentang tarikan “ideologi nasional”, yang saya anggap ada benarnya dalam ikut mempengaruhi kerangka “riset”, dan juga sekaligus tarik menarik antara suatu kerangka “nasionalisme” dengan nilai-nilai keberagaman. Apalagi ditimpali dengan isu “estetika subyektif” yang berkembang seiring dengan posisi Dewan Kesenian Jakarta yang menjadi kekuatan politik kesenian yang mempengaruhi “pembebasan seniman” dalam berekspresi pada periode awal rezim Orde Baru.
Salah satu kelemahan dari banyak riset tentang aktifitas kesenian, saya pikir pada ketiadaan perspektif untuk melacak politik ekonomi kebudayaan dalam wujud anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Banyak riset hanya melihat hal yang seolah-olah “politis”, sementara dengan politik ekonomi kebudayaan, justeru sektor ekonomi inilah sangat mempengaruhi perkembangan kesenian, sekaligus bentuk serta wujud “estetika” yang hadir di tengah-tengah masyarakat, misalnya kasus kesenian produk pariwisata, sementara disektor swasta, kita saksikan bagaimana politik ekonomi kebudayaan dalam wujud pasar senirupa membentuk “selera pasar”. Dalam kaitannya dengan senirupa, seniman sebagai “agen perubahan” sesungguhnya hanya dampak dari sirkulasi “game estetika” yang dimainkan oleh kolektor dan balai lelang yang kuat kaitannya dengan kapitalisme global.
Jenong dan Gita, saya senang dengan “riset” anda, yang saya anggap “riset awal” yang membutuhkan kelanjutan berkaitan dengan kelengkapan pemetaan dan sekaligus juga mengisi peta-peta yang membentang itu dengan isian melalui pelacakan yang “grounded”, tidak sekedar mengumpulkan data dari fesbuk atau wawancara daring dan memungut berita kesenian. Sebab, satu tambahan lagi, bahasan yang disampaikan Diah Kusumaningrum mengambil kasus tentang seni nirkekerasan (non violence?) yang dibuka dengan peristiwa seorang bikhu yang membakar diri pada peristiwa politik di Vietnam setengah abad yang lampau, itu mengingatkan apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi pada periode 1940-an dengan gerakan non-violence-nya di India, seperti juga Nelson Mandela pada tahun 1990-an di Afrika Selatan. Gerakan dengan pendekatan non violence ini sangat menarik dan membutuhkan pertimbangan yang lebih mendalam, daan dengan kompleksitas yang lebih rumit. Pembacaan terhadap konsep dan arsip gerakan itu saja rasanya tak cukup. Riset terhadap gerakan ini membutuhkan empati.
Demikianlah Jenong dan Gita, surat terbuka sebagai obrolan membahas “hasil riset” anda, yang saya harap tak berhenti hanya disini, masih membutuhkan waktu yang lain, yang terbuka untuk kita kembali mempertanyakan sejumlah kategori, asumsi dan persepsi kita sekarang dan yang lalu. Salam, dan sehat selalu.
*Halim HD, Networker Kebudayaan.