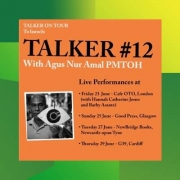Memanen Buah-buah Cendekia di Sekitar Kita
(Sekedar tanggapan untuk Aminudin TH Siregar; dan supaya ia mulai menulis lagi…)
Oleh Danuh Tyas Pradipta
1
Berangkat dari “surat” Aminudin kepada Hendro, sepotong ungkapannya menarik minat saya. Syahdan katanya, “Bahwa sejauh ini kita gagal panen buah cendekia yang mustahak”. Pikir punya pikir, mungkin ada benarnya juga; rasa-rasanya tidak ada isu yang menjadi perbincangan menarik dan seru dalam lapangan seni rupa kita belakangan.
Aminudin rupanya juga pernah berungkap senada kepada Hendro sebelumnya. Di dalam surat jawabannya pada Aminudin, Hendro menulis, “Saya ingat, Bung bilang, seni rupa kita krisis scholar, sosok ini absen merumuskan masalah”. Saya jadi terpikir; bila seorang cendekiawan salah satunya diharapkan untuk merumuskan masalah, maka siapa pun yang mengambil peran—atau ingin mengambil peran—sebagai cendekiawan dalam lapangan seni rupa kita, mestinya tidak akan kehabisan bahan untuk dirumuskan sebagai masalah. Toh, kita belum pernah menyatakan bahwa lapangan seni rupa kita sudah mapan, apalagi ideal. Pun, kalau akhir-akhir ini lapangan seni rupa kita dirasa kurang menarik dalam menyediakan bahan-bahan untuk dirumuskan menjadi masalah, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh.
Lapangan seni rupa kita sesungguhnya sudah ditumbuhi banyak buah cendekia hasil tanam para cendekiawan terdahulu. Dan buah-buah itu masih bisa kita panen untuk hari ini; ada yang berupa rumusan masalah, asumsi-asumsi, hingga sebentuk ikhtiar menjawab. Ya memang, saya juga mafhum, memanen buah-buah lama itu punya kemungkinan terbentur sangkaan sebagai mengulang-ulang masalah. Tapi sebentar; Dick Hartoko pernah menulis jika cendekiawan mampu melihat dan menafsirkan dunia sekitar beserta peristiwanya dalam suatu lingkup yang lebih luas dan mendalam. Ia pun mampu melihat segala sesuatu di sekitarnya dalam kebertautannya, dalam kesatuannya (Golongan Cendekiawan: Meraka yang Tinggal di Angin, Penerbit PT Gramedia: 1980). Jadi saya pikir, dengan pekerti kecendekiawanan seperti itu dalam mendekati masalah-masalah lama, dapat memperluas cakupan, memperdalam pemaknaan serta menemukan kebertautannya dengan perkara-perkara lain dan situasi hari ini. Barang satu-dua contoh barangkali bisa diajukan.
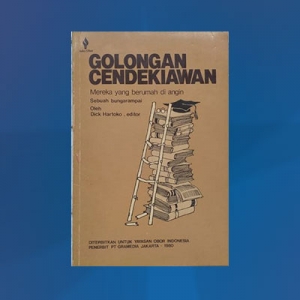
Buku Golongan Cendekiawan: Meraka yang Tinggal di Angin oleh Dick Hartoko, Penerbit PT Gramedia: 1980 (Sumber foto: bukalapakcom)
Keindonesiaan; satu perkara yang berkali-kali dipersoalkan dalam lapangan seni rupa kita. Sejak nujum belum akan adanya seni lukis Indonesia dalam tulisan Moyen, kemudian Hopman yang ditangkis oleh Sudjojono; surat menyurat Basuki Resobowo dengan Oesman Effendi tentang sudah tampaknya corak keindonesiaan tersebut; hingga di akhir 1960-an, OE sendiri meragukan keberadaan seni lukis Indonesia yang juga diamini oleh Sudjojono; dan bahkan Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia masih mengungkitnya dalam lima jurus gebrakan mereka. Keindonesiaan adalah contoh bagaimana suatu rumusan masalah terus dipersoalkan dari satu dekade ke dekade berikutnya. Ya iya sih, kesimpulannya apa, tidak juga kita dapati. Tapi kita menemukan berbagai asumsi dan saran tentang keindonesiaan. Dan kita juga melihat, bagaimana karenanya banyak seniman berikhtiar mewujudkan corak keindonesiaan dalam karyanya; melalui gambaran bentang alam, kegiatan serta penampilan sehari-hari rakyat, kemunculan unsur-unsur dari kesenian lama, hingga gambaran suasana masa perjuangan revolusi. Dari situ, setidaknya lapangan seni rupa kita telah diperkaya dengan keberagaman wujud perupaan dalam karya-karyanya.

Oesman Effendi (Sumber foto: id.wikipedia.org)
Internasionalisasi mungkin contoh lain. Tampak pada keikutsertaan seniman kita dalam berbagai pameran di luar negeri, semisal Affandi di tahun 1950-an. Istilah internasionalisasi kemudian digunakan Jim Supangkat untuk menjelaskan fenomena keterlibatan banyak seniman Indonesia dalam biennale dan triennale internasional—terutama dalam lingkup Asia-Pasifik—melalui peran dominan Australia dan Jepang pada awal 1990an. Dan rupanya, istilah itu masih diperbincangkan. Tahun lalu—dalam forum diskusi di Salihara—perbincangan memunculkan istilah “internasionalisme baru”. “Baru” di situ bisa kita maknai: menunjukkan kebertautannya dengan gagasan internasionalisasi sebelumnya, sekaligus menunjukkan perbedaan dengan rumusan sebelumnya, dengan memaknainya melalui situasi lapangan seni rupa kita hari ini.
2
Sejarah seni rupa Indonesia juga satu perkara yang masih terus dipersoalkan sampai sekarang; keraguan serta perbaikan atas versi yang sudah ada sering disuarakan. Dan saya tahu betul, salah seorang yang punya minat pada perkara ini, ya Aminudin Siregar. Di dalam beberapa forum diskusi belakangan, seruannya untuk merevisi—atau merombak—sejarah seni rupa Indonesia makin kerap; dan gagasannya tentang itu tampak semakin mantap. Boleh jadi itu karena studi doktoral yang membawanya ke Negeri Belanda, juga mengantarnya menemukan berbagai arsip “baru” tentang seni rupa Indonesia. Alhamdulillah.
Naga-naganya, karena itupula di dalam tulisan Takjub Ajoeb ia mencetuskan gagasan “historiografi penyadaran”. Katanya soal itu, “…penulisan sejarah secara lebih progresif, panggungnya dipeluas seraya mempertajam konteks untuk mengangktifkan kesadaran orang banyak. Dan jangan lupa, analisis arsip baik-baik!” Nah, gagasan ini adalah perkara kedua dari tulisan Aminudin yang menarik bagi saya; dan makin menarik lagi bila kelak ia menjawab “tantangan” koleganya di kampus, Asmudjo Irianto—yang juga sudah berkali-kali diungkapkan dalam beberapa forum diskusi—soal penulisan “buku putih” sejarah seni rupa Indonesia. Moga-moga aja.
Bertaut dengan perkara sejarah seni rupa, saya teringat ucapan pendek Aminudin dalam salah satu sesi diskusi buku Sanento Yuliman, Keindonesiaan, Kerakyatan dan Modernisme yang lalu, tentang belum adanya penulisan sejarah estetik seni rupa Indonesia. Saya pun jadi ingat, agak-agaknya Sanento Yuliman sudah menyediakan landasan bagi penulisan sejarah semacam itu. Di dalam Seni Lukis Indonesia Baru, ia membagi alur perkembangan seni lukis (rupa) kita ke dalam tiga masa perkembangan utama, dan tiap masa diisi oleh kecenderungan yang lebih khusus.

Sanento Yuliman (Sumber foto: Tempo)
Masa pertama diisi oleh Sanento dengan lukisan-lukisan tamasya alam. Masa kedua, ditandai dengan lukisan yang hendak mengungkapkan pengalaman dan kehidupan manusia; pada masa ini terdapat kecenderungan pertama yang berorientasi pada subjektivitas, pelukis digerakkan oleh emosi, sehingga menghasilkan distorsi rupa pada kanvas. Baik pengalaman sosial dalam tema kehidupan rakyat, maupun pengalaman perseorangan hadir melalui pengungkapan semacam itu. Kecenderungan kedua berorientasi pada objektivitas; pelukis berperan sebagai pengamat yang lebih objektif, dan tidak membiarkan emosinya mendistorsi apa yang dilihat. Kecenderungan ketiga, juga berorientasi pada subjektivitas, namun kali ini Sanento menghubungkannya dengan sifat fantasi (khayal, mimpi, mitos, dsb). Kecenderungan keempat adalah kecenderungan pada gaya hias, yang terbagi kepada dua kelompok: yang menggayakan bentuk objek yang dijadikan model dan lainnya, seniman menggubah unsur rupa menjadi bentuk yang mengingatkan pada gambaran umum suatu objek—di sinilah muncul kecenderungan pada abstraksi. Masa ketiga, adalah masa kemunculan seni lukis abstrak dengan berbagai coraknya. Dan di masa ketiga inilah muncul apa yang disebut sebagai “lirisisme”—ini juga berorientasi pada subjektivitas. Bersamaan dengan kecenderungan itu, muncul juga kecenderungan lainnya, yang disebut Sanento sebagai: “anti-lirisisme”—ini lebih berorientasi pada objektivitas. Kecenderungan ini terbagi dalam dua kelompok: pertama, penyingkiran asosiasi terhadap alam dan emosi, kedua adalah kecenderungan pada kekonkretan. Begitulah pembabakan yang diupayakan Sanento; bahkan di tulisan lainnya, ia juga menyediakan cara untuk melanjutkan pembabakannya itu. Ia melihat hadirnya perkembangan lanjut dari kecenderungan pada kekonkretan yang dibagi ke dalam dua bentukan: karya yang merupakan intervensi pada lingkungan alam dan intervensi pada lingkungan sosial.
Apa yang kentara dalam pembabakan Sanento tersebut adalah pemaparan tentang berbagai gejala perupaan yang muncul dalam karya para seniman, serta apa-apa yang mungkin dihasilkannya pada persepsi kita. Yang juga menarik, di sana ia nyaris tidak menyebutkan isme-isme yang lumrah ditemukan dalam narasi sejarah seni rupa modern Barat—apakah ini masih berkait dengan kritik dalam skripsinya terhadap penggunaan berbagai—isme dalam penulisan kritik seni rupa kita? Barangkali. Yang jelas—bagi saya—pembabakan itu belum selesai. Kita masih mungkin melanjutkannya dengan memperjelas kategori pembabakan dan melanjutkannya hingga situasi hari ini, menambahkan istilah-istilah yang lebih spesifik, serta memperkaya contoh-contoh karya di tiap masa disertai penjelasan yang mendetail. Pun, dengan memakai konsep historiografi penyadaran, kita bisa mempertajam dan memperdalam konteks-konteks yang melatari kemunculan kecenderungan karya di tiap masa; dan Sanento sudah mulai melakukannya.

Foto dari kiri ke kanan: Sudjoko, Imam Boechori, Yusuf Affendy, Sanento Yuliman, But Mochtar. (Sumber foto: Koleksi CIVAS ITB)
Demikian, satu lagi contoh buah cendekia yang ada dan bisa kita panen—kalau mau. Selain dari Sanento, masih ada buah-buah cendekia lain yang boleh jadi mustahak. Konsep tentang kagunan yang dicuatkan ke dalam lapangan seni rupa kita sejak Sudjoko dan dilanjutkan oleh Jim dalam upayanya “menegosiasikan seni rupa Indonesia di ranah global”—sila, terbuka bagi siapapun untuk melanjutkannya. Sudjoko juga meninggali kita rumusannya tentang masalah-masalah seni moden Indonesia. Ini masih bisa kita lanjutkan kebertautannya, untuk melihat apakah setelah sempat memperdebatkan posmodernisme di awal 1990an, dan kini sampai pada seni rupa kontemporer, masalah-masalah itu sudah teratasi. Dan misalnya; apakah yang disebut oleh Asmudjo dalam tulisannya sebagai “kolektif seni”, menjadi siasat jitu dan telah mengatasi salah dua masalah dalam rumusan Sudjoko: yaitu soal pemribadian dan pemasyarakatan serta soal respon dan pemahaman publik. Bisa juga saya sebutkan beberapa gagasan-gagasan yang bisa kita lanjutkan dan kembangkan; semisal konsep “bahasa rupa”-nya Primadi Tabrani yang memperkaya cara kita membaca beberapa aspek perupaan dalam karya, atau konsep modernitas Indonesia ala Yustiono yang bisa membantu melihat latar kultural perkembangan seni rupa modern Indonesia; sekedar untuk menyebutkan beberapa contoh saja yang terlintas dalam kepala.
Tentu, bila kita dengan cermat mengamat-amati arsip serta berbagai bacaan tentang seni rupa kita, masih akan kita dapati lebih banyak lagi buah cendekia yang telah ditanam para cendekiawan seni rupa kita. Bahwa semua itu bisa jadi sesuatu yang mustahak serta bermanfaat untuk kita hari ini; ya, itu balik lagi pada pintar-pintar kita memanen serta mengolahnya. Di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Insya Allah.
3
Nah, saya sudahi dulu tulisan ini. Menyenangkan juga bisa menyelesaikan tulisan ini setelah berhari-hari lamanya; dan lebih menyenangkan lagi karena ada “bonus” yang menyertainya. Beberapa waktu lalu, Aminudin Siregar bilang pada saya, bahwa ia akan melanjutkan lagi tulisannya kalau saya ikut nimbrung menulis. Dan sekarang tulisan saya kelar sudah, malah mungkin sudah ada di hadapan pembaca sekalian. Jadi, mari Bang…
*Penulis mengajar di Seni Rupa ITB; di kampus biasa dapat sebutan sebagai dosen muda.