Masih Adakah Otonomi Seni?
(Tanggapan terhadap Chabib dan Aminudin Siregar)
Oleh: Nurman Hakim
Menarik sekali membaca polemik seni rupa di Kompas yang dilanjutkan di portal budaya BWCF beberapa hari ini. Tampaknya pembahasan meluas sampai ke soal teori ilmu sosial sebagaimana yang dapat dilihat dalam tulisan Bung Chabib. Oke. Saya mau ikutan berpolemik melalui pandangan saya terhadap seni secara umum dari perspektif antropologi budaya.
Saya akan mulai dari kalimat yang paling menggelitik dari tulisan Bung Aminudin TH Siregar a.k.a. Ucok : “Senirupa Indonesia seakan-akan hanya berpapasan dengan gempita pembangunan, seni rupa seakan tidak diajak berpartisipasi atau mengalami inferioritas”. Saya kira, ini adalah salah satu inti dari tulisan Bung Ucok. Tampaknya ia ingin mengatakan bahwa seni rupa paska 1965 seolah terpisah dari peristiwa sosial masyarakatnya, gejala-gejala sosial yang selayaknya bisa ditangkap oleh seniman dan kemudian dihadirkan di dalam lukisannya tapi tak dilakukan, hanya segelintir saja yang melakukan.
Bung Ucok menyebut pengecualian terhadap S. Sudjojono dengan karyanya: Maka Lahirlah Angkatan 66” dan karya A.D Pirous : Mentari Setelah September 1965. Tampaknya Bung Ucok telah meletakan seni sebagai sesuatu yang instrumentalis, tidak ‘otonom’ seni yang memiliki fungsi praktis. Pada konteks inilah historiografi penyadaran yang dilontarkan oleh Bung Ucok menemukan relevansinya dan menjadi penting.
Di dalam antropologi, karya seni adalah material culture. Pandangan Claude Levi-Strauss, secara antropologis, dari material culture ini, memungkinkan kita untuk bisa mengungkap level terdalam dari struktur masyarakat berikut dengan maknanya, ia juga membuka pintu untuk memahami pola pikir suatu masyarakat (Strauss: 1961), sebab ia adalah artefak kebudayaan. Ia berisi endapan dan manifestasi seniman dan masyarakatnya. Ia adalah perluasan dari usaha manusia memaknai kehidupan ini. Pemaknaan kehidupan dalam seni bergerak ke segala arah dan acap kali berakhir kepada subyektifitas.

Claude Levi-Strauss di sungai Amazon Brazil tahun 1936
Seni adalah representasi, maka disadari ataupun tidak, apapun yang diciptakan oleh seniman itu, kita akan menemukan endapan-endapan dari pandangan-pandangan hidupnya, persoalan sosial politik, ekonomi, dan mungkin juga agama. Singkatnya, worldview seniman ada di dalam karyanya. Seperti yang dibahas oleh Bung Ucok dalam Lukisan S. Sudjojono “Maka Lahirlah Angkatan 66” yang menampilkan seorang pemuda berjaket merah berdiri berdiri membelakangi kerumunan di Jalan Thamrin. Ini adalah contoh usaha mengungkap worldview dari si seniman. Worldwiew adalah sikap, nilai-nilai, cerita, dan harapan tentang dunia di sekitar kita, yang menginformasikan setiap pemikiran dan tindakan kita (Sire: 2004).
Sementara itu, Bung Chabib menginginkan pembahasan mengenai otonomi seni bukanlah pada taraf perbincangan art for art sake (seni untuk seni) tapi pada level yang lain, yaitu otonomi seni seperti halnya otonomi teori-teori ilmu sosial seperti yang digagas oleh Syed Hussein Alatas yang ia kutip. Padahal untuk masuk pada level perbincangan tentang otonomi seni seperti yang dimaksud terakhir, kita tak bisa menafikan pembahasan otonomi seni yang ada pada level pertama, ia bisa sebagai pintu masuk, ini ada saling keterkaitan dan berkelindan.
Sekalipun sebuah karya seni dimaksudkan hanya sebagai seni untuk seni, yang mengklaim aliran ini sebagai seni paling otonom, ia tidak akan kedap oleh persoalan-persoalan yang ada di masyarakatnya. Seni sebagai objek tak muncul dari ruang hampa sebagaimana seniman sebagai subjek manusia yang hidup dalam suatu masyarakat, meskipun seniman itu mengucilkan diri, mengunci rapat-rapat hidupnya dari suatu masyarakat, pasti akan ada pintu-pintu di mana peristiwa-peristiwa sosial diinternalisasikan oleh dirinya dan kemudian disadari ataupun tidak termanifestasikan dalam karyanya. Karya seni sebagai material culture tentu saja fluid dan terus bergerak mengikuti pergerakan sosial budaya.
Perbincangan soal seni otonom dan tidak otonom memang sudah lama sekali diperdebatkan terlebih di era saat wacana marxisme hangat dibicarakan di masa lalu. Kita tahu bahwa paham Marxian meletakan seni sebagai sesuatu yang instrumental, yang berelasi dengan persoalan sosial politik, ia bahkan bisa dikatakan bersifat ‘pragmatis’. Anehnya, Adorno yang Marxian justru mengutamakan otonomi seni. Otonomi seni yang dimaksud oleh Adorno bukanlah seperti yang dikutip dan dimaksudkan oleh Syakieb Sungkar dalam tulisannya menanggapi polemik ini.
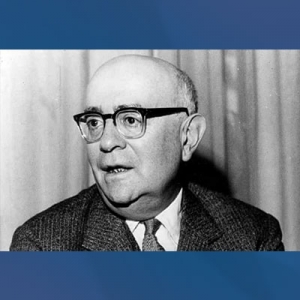
Theodor W Adorno
Adorno mengutarakan pendapatnya dalam suatu catatan yang ditujukan kepada Walter Benjamin: seni untuk seni perlu suatu pembelaan (Adorno:1977). Jika diamati lebih lanjut maksud Adorno itu, seni untuk seni bukanlah yang secara simplistis beroposisi biner dengan non otonomi seni, tetapi yang berdialektika diantara keduanya dengan tetap memberikan intensi pada otonomi seni. Proses produksi seni bisa keluar dari otonomi seni, tetapi estetika seni dipertahankan tetap ‘otonom’. Di sisi lain, dalam konteks kecemasannya terhadap kerja kapitalisme, Adorno berpendapat bahwa industri budaya pasti melibatkan perubahan karakter yang ada pada komoditas seni, sehingga membuat karakter komoditas seni diakui, dan seni “meninggalkan otonominya” (Haskins:1989). Dan kita semua tahu, kapitalisme hingga saat ini semakin menguasai panggung dunia.
Bagaimana dengan relasi otonomi seni rupa (seni) dengan ilmu-ilmu sosial yang dimaksud oleh Bung Chabib? Dengan merujuk pada konsep otonomi ilmu sosial Syed Hussein Alatas dalam The Development of an Autonomous Social Science Tradition in Asia: Problems and Prospects (2002), sebagaimana yang disinggung oleh Bung Chabib. Akar tulisan Alatas itu bermula dari pemikiran dia sebelumnya yang ia tuliskan di sebuah jurnal terbit pada tahun 1972, berjudul The Captive Mind in Development studies. Konsep Captive Mind (pikiran yang terbelenggu) merujuk pada cara kita (timur) berpikir meniru cara berpikir orang-orang Eropa/Barat. Pola pikir masyarakat paska kolonial dalam soal ekonomi, sosial, politik dan bahkan juga seni, mirip dan paralel dengan cara berpikir para kolonialis.
The Captive Mind ini terbentuk melalui suatu proses panjang melibatkan sejarah masa lalu kita sebagai bangsa yang diawali pada era kolonial, lalu dirawat dengan berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk seni yang berasal dan diformulasikan oleh para kolonial. Sesungguhnya The captive mind ini adalah buah dari orientalisme. The Captive mind ini mengandung inferioritas yang kita selalu indenial terhadapnya dan membuat kita menjadi tidak kritis. Kita hanya meniru apa-apa yang datang dari Barat. Peniruan mulai pada tingkat membangun metode, metodologi, konsep-konsep dan bahkan teori-teori sosial yang digunakan untuk membaca dan menganalis masyarakat non barat dengan kacamata Barat, yang belum tentu tepat. Alatas berharap supaya kita mencari teori-teori sosial sendiri yang berangkat dari masyarakat kita. Teori yang kontekstual dengan masyarakat kita sendiri.
Jika dalam ilmu sosial pemikiran kita sudah terbelenggu oleh pemikiran barat, maka itupun tak bisa dihindari terjadi pada seni, setidaknya seni dalam kerangka proses produksi dan idea. Cara-cara kita membuat dan memahami karya seni nyaris tak ada bedanya dengan cara-cara orang barat. Teori-teori seni yang kita pelajari sebagian besar berasal dari barat. Lalu apa yang bisa kita katakan dengan otonomitas dalam karya seni? Nyaris tak ada. Pasar, infrastruktur, komoditas dan sejenisnya secara laten mempengaruhi seni yang kemudian membentuk valueladen (Jika kita ingin meletakkan ilmu pengetahuan ‘sejajar’ dengan seni). Valuladen adalah memandang ilmu telah disisipi nilai-nilai tertentu, atau dengan kata lain, ilmu tidak bebas nilai tetapi telah disusupi worldview masyarakat barat.
Eric Wolf seorang antropolog dalam bukunya Europe and The People Without History (1982), tidak percaya lagi bahwa ada suatu masyarakat yang tidak tersentuh oleh globalisasi. Globalisasi memungkinkan terkoneksinya antar masyarakat di segala penjuru dunia. Globalisasi memunculkan penetrasi dengan segala macam bentuknya termasuk pada ekonomi sampai seni. Transformasi dalam jaringan global ini sebagai akibat dari pertumbuhan kapitalisme yang masif dengan revolusi industrinya. Dengan begitu maka hampir semua masyarakat di dunia ini telah “terintervensi” pengetahuannya, juga cara pandangnya dengan cara pandang masyarakat yang menghegomoni. Diperlukan pikiran yang kreatif dan kritis untuk melawannya agar pikiran kita tidak terbelenggu. Pengetahuan adalah kuasa. Pengetahuan memiliki kekuatan untuk mengonstruksi kenyataan, mendisiplinkan bahkan menormalkan terhadap apa yang dianggap menyimpang (Foucault:1980). Jika di era kolonial, ekspoloitasi sumber daya manusia dan alam bekerja dengan hebatnya, kini di masa paska kolonial ini, kerja-kerja itu masih berlanjut melalui kuasa pengetahuan yang datang dari Barat.
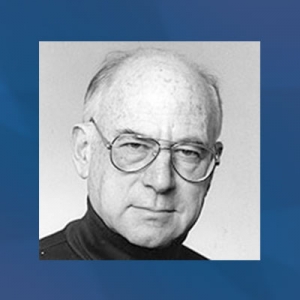
Eric R Wolf
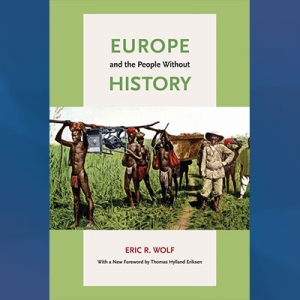
Buku Eric Wolf “Europe and The People Without History” (1982)
Dari uraian singkat ini, bagaimana lagi kita bisa mengatakan otonomi seni masih bisa berdiri tegak di era sekarang ini? Dan bagaimana cara menegakkannya? Terlebih cara-cara kerja seni berbeda dengan cara kerja teori-teori sosial. Apa yang disampaikan oleh Bung Chabib, saya kira tak mudah untuk bisa diterapkan dalam karya seni termasuk seni rupa apalagi seni film (bidang yang saya geluti). Kemandirian untuk lepas dari belenggu pikiran masih bisa dilakukan pada level worldview seniman pada karyanya, sementara pada level proses produksi seni dan seni sebagai komoditas yang tentu saja memberikan pengaruh pada aspek estetika, tampaknya otonomi seni masih harus melalui jalan yang berliku dan terjal untuk mencapainya. ***
*Nurman Hakim. Filmmaker, Mahasiswa S3 Antropologi UI, dan dosen sinema IKJ.













