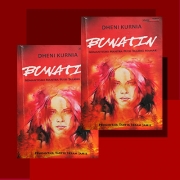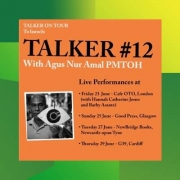Manusia dan Alam: Sekularitas yang Mencari Keterhubungan Kembali
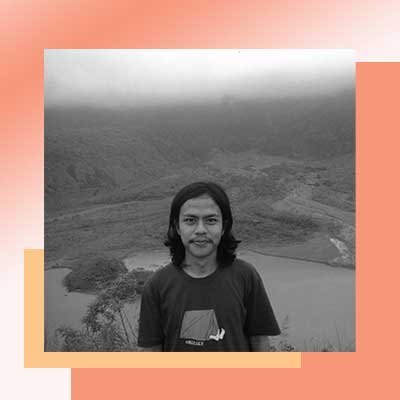
Oleh Mohammad Hagie
Judul Buku: Sembahyang Bhuvana: Renungan Filosofis tentang Tubuh, Seni, dan Lingkungan
Penulis: Saras Dewi
Penerbit: Tanda Baca
Tahun: 2022
Tebal: 113
Tenggat akhir bulan Januari di tahun ini, penerbit Tanda Baca merilis terbitan baru yang dua bulan sebelumnya telah diwartakan. Sebuah kumpulan esai yang kemudian dipilah menjadi satuan tema berkait, dan menjadi buku. Karya itu berjudul Sembahyang Bhuvana: Renungan Filosofis tentang Tubuh, Seni, dan Lingkungan. Tulisan reflektif ini lahir dari Saras Dewi, seorang perempuan Bali yang bekerja di departemen filsafat Universitas Indonesia. Untuk kali ini, terbitan Tanda Baca bernomor serie, saya mendapat nomor 313. Ditambah pula ada bubuhan tanda tangan dari penulisnya langsung. Karena jumlah halaman buku ini 113, maka saya membacanya dengan sekali duduk saja.
Sebelum menelaah isi kumpulan esai yang terbilang berat dan meditatif ini, saya malah awal mengenal Saras Dewi dari sebuah lagu berjudul Lembayung Bali. Kala itu, seorang teman senior Mapala yang menghabiskan masa kecilnya di Bali, disela-sela obrolan kami usai memasang tenda, ia memperkenalkan lagu itu pada saya. Sebuah potret lagu tentang perjumpaan sepasang kekasih yang menelusuri masa kecil platoniknya di tepi pantai. Cahaya temaram senja, menjadi potret pertemuan magi yang abadi. Kini, sepasang kekasih itu telah tumbuh dewasa, merindukan cahaya magi itu kembali. Namun dunia telah berubah, dan cahaya magi tak bertepi lagi. Sebuah ‘pengalaman rasa’ seorang Saras Dewi yang kemudian terejawantah dalam teori fenomenologi Mearlou Pounty ini, akan kita temukan kepingannya dalam kumpulan esai berikut.
Pembuka esai ini bertemakan tentang Teknik dan Magi, lewat karya Federico Campagna berjudul Technic and Magic: The Recontruction of Reality. Dalam tema ini bagi Saras Dewi, yang ingin ditampilkan Teknik dan Magi Campagna adalah mengenai yang tak terkatakan (the ineffable), yaitu kesukaran untuk mengatakan atau membahasakan realitas. Karena apa yang disebut realitas, bagi Campagna merupakan persoalan pergolakan dan penderitaan untuk memahami yang tak terkatakan. Itulah realitasnya; kegamangan berdiri diantara buana alit, buana jagat, dan buana hyang. (Hlm, 7).
Di awal masa studinya di Filsafat, Saras Dewi mempertanyakan dikotomi filsafat yang lazim disebut dualitas persitegangan, antara Timur dan Barat. Antara Apologia Socrates, dan Bhagavad Gita, yang tengah dibacanya saat itu. Lalu ia mencoba mendedah dikotomi keduanya. Dalam penelusurannya, ia beranggapan bahwa persoalan terdasar dikotomi keduanya adalah upaya mengembalikan metafisika, dan menghadirkannya dalam struktur terdasar realitas kehidupan. Ia menambahkan, bahwa realitas manusia secara total adalah upaya membahasakan relasinya dengan Tuhan. Dalam menggapai relasinya itu, diperlukan perangkat kesadaran metafisis, yaitu suatu usaha pelampauan atas materialitas yang ada dan melekat. Sehingga teknik dan magi sebagai perangkat metafisis, dapat merengkuh sang sublim absolut yang akan tertampung dalam peristiwa rasa.
Kesadaran metafisis ini akan membawa manusia pada satuan genesis alam raya, bahwa alam dan manusia tidak terpisah. Dengan sintesa demikian, sang absolut atau Tuhan hadir dalam logos manusia. Manusia dapat merengkuh kemengertian kemengadaan dan keterjalinannya dengan Tuhan, saat akal mampu menggapai kontemplasinya paling tinggi. Momen kontemplatif ini, teknik dan magi ini dalam agama disebut semhbahyang; yaitu diri (logos) bertemu dengan kosmos (Tuhan).
Selain persoalan filsafat, pertanyaan tentang kosmos, terutama sejak abad ke-19 dengan munculnya kosmologi sebagai disiplin ilmu, hal itu menjadi kajian menarik. Begitu pula pasca abad pencerahan di Eropa, para saintis yang bekerja di laboratorium astronominya, berusaha mencari jawaban atas misteri besar dalam hidup ini: dari mana manusia berasal, dan akan ke manakah ia menuju?
***
Di esai kedua, renungan filsafat menjelajah pada laut, atau Filsafat Samudera. Kali ini Saras Dewi mencoba bertanya ulang pemahaman manusia modern yang dinilai mekanis dan antroposentris, yaitu suatu objektivasi total atas laut sebagai sumber kehidupan material. Sementara jalinan batin darat dan laut menjadi tercerai dan terpisah. Saras Dewi kemudian mencoba menelusuri lebih jauh, bahwa Nusantara diabad sebelum kolonial masuk, yang sohor karena kosmopolitnya, sangat berporos pada maritim. Sebelum, pemerintah kolonial mengubahnya menjadi agraris kepulauan (archipelago), dan membelakangi lautan.
Saras Dewi mengajak untuk memikirkan ulang persepsi kita pada laut. Ia mengambil referensi masyarakat adat Bali, yang memahami laut dalam dua sisi. Sekala dan Niskala. Sekala adalah laut sebagai wujud yang tampak, dikaji, dikategorisasi, yang secara empiris dapat dicerap. Sedangkan Sekala, merupakan sisi yang subtil dan tersembunyi dari persepsi objektif manusia. (Hlm, 11). Artinya, ada yang tidak menyeimbang pada manusia abad ini dalam melihat dan memperlakukan laut. Manusia tidak lagi bertaut dengan laut sebagai keterhubungan dan pertautan dirinya, pertautan terjadi sebatas aktifitas material saja. Saras Dewi mencoba memotret pertautan spiritual dalam praktik Ngaben, selepas upacara abu mayat di larung ke laut. Begitu pula sebelum hari raya Nyepi, masyarakat Bali menjalankan ritual yang bertautan dengan laut.
Sebagai bagian dari masyarakat Bali yang mengelami persentuhan langsung, Saras Dewi kemudian mendedah semua itu dalam problem teoritik. Sebagaimana telaah disertasinya, dengan mengambil teori fenomenologi Husserl yang dikembangkannya menjadi ekofenomenologi. Dalam persoalan ini ia mengambil teori Mearleau-Ponty. Saras Dewi berangkat dari Kuliah Paris Husserl, sebagai metode kritik pada bangunan antroposentis. Corak berfikir yang menandakan zaman modern, lalu terkonsepsikan oleh Imanuel Kant dan Descartes. Namun yang unik, kritik Husserl tidak dilayangkan pada kedua pendahulunya itu, namun lebih ke dalam dirinya sendiri.
Feneomenologi lautan, Saras Dewi banyak merujuk pada tradisi Bugis, yaitu dalam naskah La Galigo di abad ke-14. Tokoh dalam naskah itu bernama Sawerigading, tokoh yang menjadi legenda pelayaran yang memikat. Naskah itu bercerita bahwa samudera lepas tidak menjadi sebatas latar belakang perjalanan. Samudera adalah kehidupan itu sendiri, berlayar bukan hanya aktifitas, melainkan juga eksistensi pembentukan diri. (Hlm, 15). Tokoh dari naskah ini pula yang ditulis ulang oleh sastrawan muda bernama Faisal Odang.
Laut dalam telaah fenomenologis, merupakan problem eksistensialistik. Metafor pergulatan dengan laut merupakan sesuatu yang menggugah: ia indah sekaligus menakutkan. Daya gugah inilah yang melahirkan reflektifitas pada manusia. Bagaimana manusia menempatkan dirinya dalam ambiguitas perasaan: bahagia sekaligus cemas di hadapan lautan. Serupa dengan kisah Sawerigading yang berlayar melampaui badai dan bahaya ombak, laut merupakan yang misterius dan asing bagi manusia. (hlm, 16)
Lewat Mearleau-Ponty, Saras Dewi memahami secara fenomenologis, bahwa laut sebagai suatu fenomena dilihat sebagaimana adanya. Ia istimewa, karena laut dan manusia terbalut dalam suatu perjumpaan. Dalam cerita Sawerigading, laut adalah kisah penjelajahan itu sendiri. Begitu pula di arus waktu penjelajahan, momen istimewa masa kecil, bersama sahabat lawas, juga sang kekasih, menjadi bayangan sublim yang amat dirindukan. Itu semua adalah potret fenomenologis yang tergambarkan dalam perjalanan hidup manusia. Dari pengalaman tersebut, metafisika heidegger menyebutnya sebagai in-der-Welt-Sein; yaitu suatu keberadaan eksistensial untuk mewujudkan otentisitas diri.
***
Esai berikutnya adalah tentang Tari, Tubuh dan Spiritualitas. Boleh saja saya mengamini lirik sebuah lagu, judulnya Balerina dari Efek Rumah Kaca, bahwa hidup dengan segala gerak maju dan iramanya, adalah upaya menghimpun energi untuk mencari keseimbangan, serta mengisi ketiadaan.
Dalam kehidupan masyarakat Bali, sejak kecil setiap individu sudah diperkenalkan pada tari. Maka tari sebagai tradisi mendahului individu. Tradisi itu pula yang mendefinisikan individu serta fungsi ketubuhannya dalam tradisi. Selain sebagai aktifitas privat dan ruang ekspresif, menari menjadi medium bercakap-cakap dengan Tuhan. (Hlm, 20).
Tradisi yang mendahului eksistensi, akan diuji eksisntensinya di saat setiap individu dalam tradisi itu mulai eksis sebagai diri, dengan kata lain eksistensi mendahului esensi. Hanya dengan jalan itu, tradisi bisa terus eksis dan bertransformasi. Berkait dengan ini, Oka Rusmini yang juga bagian dari perempuan masyarakat adat bali, memotret dan mendokumentasikannya lewat karya fiksi yang kontroversial sekaligus memukau berjudul Tarian Bumi. Di novel ini, pembaca bisa melihat bagaimana individu berhadapan dengan tradisi yang telah turut membentuknya.
Kebertubuhan adalah proses peng-alaman, maka tubuh adalah alam itu sendiri. Ia yang melekat sekaligus eksisten. Di saat bersamaan, tubuh membutuhkan medium untuk ia bisa melepas dari pengalamannya. Maka, spiritualitas hadir untuk membantu manusia ke luar dari keterpasungan intensionalitas kebertubuhan. Spiritualitas dibutuhkan untuk menjadi katarsis dalam menggapai yang transenden. Sehingga, ia bisa mencapai kebebasan dari segala keterbelengguan tubuh yang melekat. Menari memberikan ruang dan gerak bagi tubuh, agar ia bisa menyeimbang dari segala keterhimpunan energi yang telah diserapnya. Maka dendang irama spiritual, ia mengisi ruang dan gerak kembali pada tubuh itu sendiri. Begitulah siklus tubuh dan alam ini berjalan.
***
Seperti pungkasan pertanyaan saya di ulasan esai pertama, dalam esai keempat Saras Dewi mengungkapan bahwa misteri terbesar manusia adalah memahami hubungannya dengan alam. Alam menjadi misteri akut, sekaligus memukau dan mempesona. Pertanyaan tentang alam ini pula yang coba dijelajahi oleh sains, melalui perkembangan terbarunya yaitu kosmos. Einstein dengan hukum relatifitasnya mengungkapkan, bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan dari awal sampai akhir, oleh kekuatan yang berada di luar kontrol manusia. Kita semua: manusia, sesayur, dan debu kosmis, menari mengikuti irama misterius yang didendangkan dari kejauhan oleh pemusik yang tersembunyi.
Dalam kosmos digambarkan alam sebagai jagat, yaitu jagat dalam diri manusia, sekaligus jagat di luar diri manusia. Misteri saintifik yang begitu rumit ini bisa sesaat kita mengerti lewat serial cerita fiksi berjudul Star Maker, yang dikarang oleh Olaf Stapledon. Star Maker yang digambarkan sebagai seorang pengelana dan pergi jauh, mencari kosmos dan mengalami berbagai perpindahan energi. Hingga ketika di puncak pengembaraannya, ia baru menyadari: kini, ia bukan lagi si pengelana yang mencari kosmos, tapi ia sudah menjadi kosmos itu sendiri.
Saras Dewi menggambarkan pengertian kosmos lebih merujuk pada Chandogya Upanisad, dinyatakan bahwa Tat Twan Asi, yang berarti “Engkau adalah Aku”: bahwa alam, Tuhan dan juga diriku, sejatinya adalah satu. (hlm, 28)
Kemudian, dalam judul ini mencoba mengurai masalah lingkungan hidup dan keterbatasan filsafat. Kompleksitas isu lingkungan, berkelindan dengan laju modernitas. Saras Dewi dalam hal ini menyuguhkan jalan seni, untuk mengetengahi keterbatasan filsafat, problem lingkungan, dan modernitas. Ia kemudian merujuk pada tradisi Frankfurt, khususnya Adorno dan Horkheimer, keduanya mengkritik abad pencerahan yang telah mereduksi alam sebagai objek penumpukan kapital. Maka seni yang merupakan bagian penting di dalamnya, menjadi tercerabut dari alam. Manusia menjadi terasing dari alam, dan seni direduksi sebatas kegunaannya untuk memajukan Pencerahan.
Pertanyaannya kemudian, apakah dimungkinkan poblem lingkungan dan keterbatasan filsafat terketengahi dan terjawab melalui seni?
***
Sembahyang Bhuvana. Judul terakhir, sekaligus tema dalam buku. Esai ini merupakan teks pidato kebudayaan yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta, tahun 2018. Saya akan mengutip kalimat pembukanya:
“tidak ada daya muslihat pada alam. Alam adalah angan-angan terhadap nirmala, segala yang murni dan baik. Alam bukan hanya bumi yang dipijak, tempat bernaung, melainkan juga ruang menyejarah bagi manusia. Alam menuangkan saripatinya untuk menyangga kehidupan, bahkan manusia juga bergantung terhadapnya.” (hlm, 74).
Terhitung sejak Husserl memberikan kuliah-kuliahnya di Paris, ia mengkritik struktur pandangan antroposentris Cartesian. Yaitu cara pandang dunia yang meletakan manusia sebagai pusat kehidupan di bumi. Subjek ada sebagai aku yang berpikir, dirayakan kemampuan rasionya yang melepas dan memisahkan diri dari mitos dan agama. Corak berpikir yang melahirkan abad pencerahan ini, beriring pesat dengan laju sains dan teknologi. Implikasinya, capaian kemajuan sains dan teknologi menjadi bersifat sekuler. Begitupun dengan agama, ia terpisah dari urusan kehidupan publik. Sejak lahirnya negara bangsa pasca revolusi Prancis, karena agama dianggap wilayah privat, maka Tuhan diletakan di pojok paling gelap. Ia telah terusir dan menggosongkan diri dari alam semesta.
Oleh karena dunia di luar rasio manusia terobjektivasi secara keseluruhan, maka ia berakhir dan terjebak pada objek material sebagai hakikat kenyataan. Tidak ada ruang, kekosongan, dan yang tersembunyi, dalam menggapai misteri alam raya dan persoalan Tuhan. Kekayaan misteri dan persoalan Tuhan ini, yang kemudian ingin diketengahi dan dihadirkan kembali oleh fenomenologi Husserl lewat meditasi Cartesian, juga metafisika Heidegger dalam karyanya berjudul Being and Time.
Sembahyang Bhuvana mengajak kita untuk merenung, dan menjalin kembali keterhubungan manusia dengan alam. Sembahyang merupakan medium kontemplatif yang bisa menjadi praktik di-antara, dalam menggapai momen sublim atau Sang Mutlak dalam sebuah pengalaman rasa. Keterjalinan itu mampu dicapai saat kita mampu mengenali dan merawat keterjagaan keduanya, yaitu manusia dan alam. Sebagaimana ungkapan Mearleau Ponty, dikutip Saras Dewi yang mengatakan bahwa:
“Alam adalah yang primordial, ia adalah yang tidak dikonstruksikan, tidak disituasikan; maka karena itulah terdapat gagasan kekekalan alam, keutuhan alam. Alam adalah objek enigmatis, objek yang sesungguhnya bukan objek sama sekali; ia tidak terungkap gamblang begitu saja. Ia adalah tanah itu, bukan hanya berada di depan kita, atau di hadapan kita, tetapi ia yang meliputi kita.” (Hlm, 102).
*Mohammad Hagie, menyelesaikan studi di ilmu sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, sedang menekuni dunia antropologi dan kesusastraan. Bergegiat di Komunitas Kuluwung, bekerja paruh waktu di Langgar.co, dan Genius Book Media Kreasindo. Saat ini tinggal di Yogyakarta, dan Magelang.