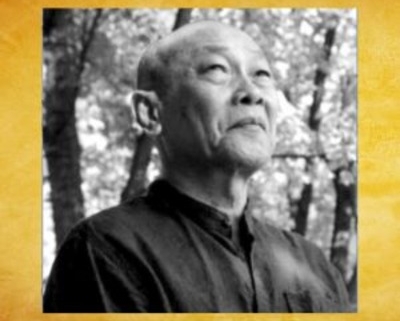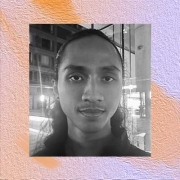Yang Kian Lenyap, Teater
Oleh: Halim HD*
Perbincangan kali ini tentang seni pertunjukan, teater moderen. Dan perbincangan inipun tak jauh jauh amat. Saya fokuskan di Jawa Tengah, bukan Indonesia, dan secara khusus kasus di Solo. Walaupun sesekali saya singgung kondisi teater di kota di luar Jawa Tengah. Saya selalu merasa jengah ketika bertemu dengan teman-teman pelaku seni pertunjukan yang bertanya tentang kondisi teater di Solo. Mau cerita blak-blakan, rasanya rada pakewuh, dan kalau nggak diceritakan, begitulah kondisinya. Tapi saya juga ingin kasih gambaran dengan bandingan. Betapa dahsyaatnya pelaku teater di Jakarta. Bayangkan, kota sudah demikian sibuk, transportasi nggak mudah dan nggak murah, sementara ruang publik kian menyempit, tapi Jakarta masih punya teater dan tradisi Festival Teater Jakarta (FTJ) yang dulu dikenal dengan Festival Teater Remaja (FTR). FTJ sudah berumur puluhan tahun, lebih dari tiga puluh tahun dihitung dari FTR. Coba anda bayangkan diantara kota yang demikian ribetnya dan hidup kian ruwet serta himpitan ekonomi menggencet urat syaraf, kok masih ada puluhan, bahkan seratusan lebih grup yang masih terus melakukan uji coba diri, masih mencari dan terus menciptakan ruang pertunjukan. Yang menarik mereka semuanya dengan keseriusan yang rasanya tak dimiliki oleh kota-kota lainnya. Sungguh bikin kepala saya geleng-geleng diantara rasa kagum dan tanda tanya yang menggantung.
Dunia teater memang berat. Ada pelaku teater di Yogyakarta marah kepada saya, dan berucap, Mas, melakukan teater itu nggak gampang. Ungkapannya meluap ketika saya tanya, kok lama nggak berteater, kapan nggarap teater lagi? Luapan dia membuat saya berucaap, yang menganggap teater itu gampang dan mudah itu siapa? Pelaku teater yang pada tahun 1990-an, ketika dia masih mahasiswa, saya mengaguminya dan saya mengorganisir pementasannya di Solo, di Teater Arena TBJT, dan saya juga yang awal tahun 2000-an memilih dia menjadi pengisi Panggung Aktor Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Sekarang dia menikmati dirinya menjadi “pengamat”, “penganalisa” dan sesekali kalau dapat job menggarap. Posisi seperti dia banyak banget. Sudah lumrah kalau ada perpindahan posisi dan fungsi, karena hidup memang harus dilanjutkan dengan pekerjaan dan kocek mesti ada isinya.
Sementara itu Solo yang rasanya masih nikmat karena populasi yang tak menghimpit, dan mudah dijangkau, dan betapapun ruang publik kebudayaan dibekuk oleh birokrasi, rasanya ruang ruang alternatif masih lumayan tersedia. Bersyukur dengan mereka yang membukakan ruangan untuk kegiatan. Tapi, teater di Solo, rasanya memang sulit. Bukan karena, sekali lagi, tiadanya ruangan untuk latihan dan hidup yang menggencet. Ada sesuatu yang lenyap.
Teater itu suatu sistem produksi yang tak mirip dengan pabrik. Itu sudah pasti. Teater memang membutuhkan kelekatan relasi personal untuk menyampaikan gagasan, konsep serta pemahaman kepada casting yang dipilih, disamping untuk menjabarkan tematik. Juga, dalam proses berteater mesti memiliki keberanian untuk berdiskusi agar perbedaan persepsi serta pemahaman bisa disatukan. Hal ini yang mungkin lenyap dari kehidupan teater di Solo. Bukti dari hal itu, beberapa garapan yang tak selesai saya tonton dalam bentuk teater moderen dan ketoprak garapan, rasanya saya menemukan hal itu. Teater yang manggung itu, dramatic reading saja tak tercapai, dan sekedar hafalan serta pakai kostum sudah dianggap layak panggung. Maka jadilah sejenis “teater proyek”, pokoke manggung, ada foto dan ada laporan. Lalu sebarkan fotofoto di fesbuk, maka tanda jempol like mengisi, dan sutradara serta pemain sudah senang. LSM-NGO’s sama saja kerjanya dengan birokrasi: narsis nggak ketulungan.
Mereka yang tahu dan pernah menonton teater di Solo pada periode tahun 1980-90-an akan geleng geleng kepala menyaksikan teater di Solo sekarang. Dan lebih geleng-geleng kepala lagi, karena tak ada diskusi dan kritik. Narsisme memang sudah menjadi bagian penting dalam dunia panggung yang membutuhkan puja-puji, keplok tangan, karena menganggap apa yang dikerjakannya sudah berdarah-darah. Berdarah-darah, itulah ungkapan yang secara diam-diam sering disampaikan namun secara tersembunyi, sambil mengasihani diri sendiri dan sambil menarik nafas panjang seolah perjuangan telah dilaluinya. Maka ketika ada informasi tentang teater saya kirimkan via WA atau posting di fesbuk, beberapa teman dari kota lain sering kirim balasan dan bertanya, gimana kiranya pertunjukan itu, apakah menarik. Saya tak bisa menjawab. Saya bilang, saya ingin ikut menonton karena hanya “solidaritas saja”, bukan kepentingan kesenian. Ngapain mendahulukan kesenian diantara pelaku kesenian sendiri sudah jeblok dan ambyar kerjanya? Bukankah lebih baik kita ikut menghibur mereka yang sudah dan masih berkesenian. Secara bergurau tapi serius saya juga bilang, tak ada salahnya setor muka kepada rekan kita, walaupun setelah nonton ada kedongkolan yang mengganjal di tenggorokan. Kan ada prodi S1-2 dan bahkan S-3 prodi penciptaan teater di ISI Solo, apa nggak ada karya mereka? Tanya beberapa teman. Saya kira teman yang bertanya itu antara serius dan basa basi. Serius karena masih menganggap bahwa lembaga pendidikan kesenian ISI bisa menghasilkan teater khususnya. Padahal, prodi teater itu sendiri kerepotan oleh apologi untuk dirinya yang menganggap bahwa mahasiswa yang masuk ke prodi teater itu bukan karena minat utama. Mereka hanya mencari gelar. Kambing hitam memang dibutuhkan di negeri ini.
Teater kampus sudah lama surut dan makin lenyap pula. Basis sosial terpenting dalam perkembangan seni pertunjukan teater yang tumbuh dan berkembang sejak tahun 1970-an ini pernah melesat pada periode 1980-90-an dan bermunculan grup-grup teater, yang bukan hanya secara kuantitatif jumlahnya sangat menggembirakan, tapi juga garapannya. Bahkan diantara mereka banyak yang memasuki dunia teater secara lebih serius dan membentuk grup teater di luar kampus, dan membuat sanggar dengan semangat yng meluap. Suatu keberanian moral yang perlu kita kagumi, dan dengan kesadaran independen dan dorongan untuk melakukan eksplorasi sebagai wujud dari pencarian teknik dan konsep-konsep garapan. Di Solo pada periode 1980-90an terdapat belasan dan terus berkembang menjadi dua puluhan grup teater kampus, yang satu dengan lainnya saling menjalin jejaring, dan saling ikut mendukung. Teater arena atau pendapa, atau auditorium tak pernah hanya diisi oleh puluhan penonton. Dua-tiga-empat ratus penonton sekali main dan membayar tiket. Solidaritas dalam wujud tiket hanyalah salah satu bukti ikatan kuat antara grup teater kampus yang ikut menghidupkan Solo menjadi kota yang diperhitungkan. Pada sisi lainnya, program kaderisasi pelaku teater setiap tahunnya berjalan dengan produktifitas yang tinggi. Antara romantisme dan semangat meluap untuk menyatukan diri dalam grup teater dibentuk sejak tahun pertam ketika mereka, para pemint teater, menginjakan kakinya di kampus.
Kondisi itu sangat mungkin dikarenakan oleh pengelola kampus yang masih terbuka kepada gagasan mahasiswa dalam berkesenian, dan birokrasi tak terlalu membekuk, dan masih bisa tawar menawar bahkan posisi pelaku kesenian di kampus rasanya lumayan dihormati. Dan masih banyak dosen Yunior dan senior yang ikut menyaksikan pertunjukan, bahkan terlibat dalam diskusi setelah pementasan. Kini ketika kampus mengejar sebanyak-banyaknya lulusan dan birokrasi menelikung serta apresiasi kesenian hanya sekedar basa basi dalam kaitannya dengan upacara dan menjadikan kegiatan kesenian sekedar seremonial. Dengan kondisi seperti itu, maka kampus sebagai basis sosial dunia teater moderen mengalami masa surut dan bahkan kemandegan dan menuju degradasi. Sesekali cuma ada festival teater mahasiswa, dan itu dalam kaitannya dengan Peksimida-Peksiminas yang entah untuk apa program ini yang biayanya miliaran tapi tak jelas ukuran di dalam menilai perkembangan kesenian mahasiswa di kampus. Karena kondisi kampus yang tak lagi apresiatif, maka yang ada wujudnya teater dadakan, yang jika kita ikut menonton membuat semua indera kita jadi seperti disumpeli oleh sejenis polutan. Tapi Solo memang bukan Solo kalau nggak ada usaha untuk terus berusaha. Itulah makanya ada Hatedu. Sejenis festival memperingati Hari Teater Dunia yang selalu dipenuhi oleh peserta dari berbagai kota lain dan membuat kepala kita makin tujuh keliling: ini teater atau cuma sekedar orang manggung dan sedang memuntahkan unek-unek. Tak ada pertimbangan dalam kebutuhan ruang dan artistic. Pokonya mereka naik panggung. Di samping itu, juga ada Festival Teater yang bersifat lomba diselenggarakan setiap tahun oleh Fakultas Ekonomi UNS. Rasanya ini sekedar acara yang tak bisa dihitung dalam konteks kualitas. Dua acara Hatedu dan Festival Teater itu, membuktikan bahwa menciptakan peristiwa teater memang nggak gampang. Sudah taak mudah dan tak gampang, dibarengi oleh perasaan sok tahu dan sok paham. Bayangkan jika kehadiran teater tanpa kurasi. Kurasi memang soal yang paling sulit, bagaimana memilih teater yang akan hadir, yang bisa menyajikan karya yang membuat penonton bisa berpikir. Dua acara ini memang yang dihitung adalah bagaimana adanya keramaian, bukan perbincangan tematik dan mutu setelah kita menyaksikannya.
Solo juga sekarang sudah jarang dikunjungi oleh grup-grup teater yang memukau. Coba bayangkan pada tahun 1980-90-an sampai awal 2000-an. Saya bukan bermaksud bernostalgia. Apa yang saya sampaikan disini berupa fakta peristiwa melalui data tentang grup teater yang pernah datang ke Solo, seperti Teater keliling, Komunitas Payung Hitam (KPH), Studiklub Teater Bandung (STB), Bengkel Muda Surabaya (BMS), Teater Surabaya, Teater Emper, Teater Sanggar Merah Putih (SMP) Makassar, Teater Mandiri, Teater Garasi, Teater RSPD Tegal, dan ada yang dari Jepang The Black Tent Theater, Le Moment du Theatre dari Swiss, dan puluhan grup lainnya dari berbagai daerah-kota di Indonesia. Periode itu ketika TBJT dikelola oleh makhluk anomali, Mas Murtijono – RIP. TBJT dengan tata kelola de-birokratisasi dan melibatkan pelaku kesenian sebagai penyusun program dan dengan adanya jejaring personal yang intensif. Ingat, betapapun jejaring itu bersifat personal, tapi tak terperangkap ke dalam subyektifisme. Hal itu dikarenakan adanya batu uji diskusi dan dialog serta usaha untuk menjelaskan suatu tematik secara rasional. Rasionalitas dalam menyusun program kerja harus didukung oleh fakta tentang kualitas grup teater yang akan tampil.
Kini Solo rasanya kehilangan rasionalitas dalam kehidupan kesenian. Padahal, konon kajian kesenian sudah begitu penuh dijejali oleh sejumlah teori yang dicomot dari mancanegara yang penuh dengan beban ideologis dalam kerangka teoritik. Ada yang bertanya, bagaimana lulusan kajian seni pertunjukan yang doktor-doktor itu, sejauh mana peranannya membongkar kejumudan? Pertanyaan itu, rasanya bisa jadi konyol. Kekonyolan muncul karena sesungguhnya antara kajian yang ada di dalam kampus dengan realias, dinamika kesenian dan kebudayaan, sama sekali tak memiliki korelasi. Kajian-kajian itu sekedar melengkapi untuk meraih jenjang posisi di dalam birokrasi kampus. Jadi lupakan saja. Tapi hilangnya daya rasionalitas juga ikut membuntuti orang non-kampus.
Namun demikian Solo tak sepenuhnya buram. Ada Langkah-langkah kecil yang menarik yang bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran dan sekaligus membentuk ikatan sosial melalui kegiatan yang intensif. Kasus kelompok teater di wilayah Mojosongo, Sanggar Pasinaon Pelangi, Toprak Ngampung dan Teater Ruang. Ketiga jenis grup teater dan (ke)toprak ini punya cara yang berbeda. Salah satu yang menarik kapasitasnya untuk berada dalam suatu lingkungan sosial dan dengan lingkungannya mereka menciptakan produksi. Seperti juga banyak grup, ujian untuk mereka adalah waktu: kesinambungan di dalam menciptakan rencana kerja tanpa harus memasuki ruang-ruang birokratis. Sebab, banyak jebakan birokratis yang telah membuat grup grup teater justeru mati kutu. Dalam kasus ketiga kelompok kesenian ini, kita berharap tumbuh berkembang secara organik dan menjadi khasanah tradisi baru di lingkungan sosialnya. Dan hal itu membutuhkan proses pencarian mereka ke dalam ruang estetika sosial yang dibutuhkan bukan hanya oleh mereka tapi juga lingkungan sosial yang menjadi lahan kehidupannya. Diantara kehirukpikukan banyak grup teater yang terasa seperti silat lidah memainkan isu tentang tubuh namun lupa kepada lingkungan sosialnya, mereka mungkin bisa menjadi pilihan. Dan Kembali, waktu yang ikut menentukannya. Mungkin Teater Akar, kalau saja bisa intensif dan tidak sekedar menggantungkan sodoran program bas abasi dari instansi, menghindari jebakan “teater dalam rangka”.
Pernah ada Mimbar Teater Indonesia (MTI), yang kalau nggak salah berjalan selama enam tahun. Pelontar gagasannya Hanindawan dan meminta saya untuk menjadi kurator. Hanindawan ingin memanfaatkan bagaimana rangkaian acara Festival Seni Jawa Tengah yang dikelola oleh Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) di Solo itu bukan hanya kesenian tradisi. Saya menerima saja tawaran itu, dan kami merumuskan suatu konsep MTI dengan tematik yang secara spesifik punya kaitan dengan figur teater Indonesia. Itulah makanya MTI diselenggarakan dengan mengangkat lakon-lakon karya Arifin C. Noer, Putu Wijaya, Danarto. Di samping itu, suatu tematik diangkat melalui lakon “Waiting for Godot”. Bahkan pada tematik “Waiting for Godot” itu kami mengundang suatu grup yang menggarap melalui pendekatan teater tari. Sayang Heri Lentho jeblok garapannya. Tapi MTI lalu stop. Hanindawan dan saya menolak ketika pengelola TBJT hanya memberikan waktu yang sangat pendek. Untuk mengundang dan menghadirkan 6-7-8 grup mereka menyediakan waktu hanya 3 hari termasuk persiapan pembukaan. Saya meminta minimal 7 hari dan ruang galeri besar-kecil serta amfiteater bisa digunakan, agar setiap grup bisa menggarap ruang bermain. Bagi birokrat TBJT mengira kami butuh. Mereka memainkan posisi kuasanya sebagai pengelola ruang pertunjukan. Betul kami butuh, tapi kebutuhan kami didasarkan kepada pertimbangan artistik dan kenyamanan penonton. Sangat tidak mungkin pada satu ruang teater arena dijejali dengan tiga grup dalam satu malam. Grup teater tak mungkin bisa menyiapkan disain artistic dan gladi resik. Tiga grup satu malam berarti sekitar tiga jam ditambah jeda. Itu melelahkan. Jadi ketika kesepakatan awal dilanggar, kami mundur.
Pada waktu itu MTI juga menyelenggarakan sarasehan dari kalangan pengamat dan pelaku teater. Afrizal Malna, Beni Johanes, Mas Putu Wijaya, Mas Bakdi Soemanto, Mas Genthong HSA misalnya hadir. Jadi, dengan sadar dan sepenuh hati MTI kami stop karena pertimbangan martabat teater yang oleh birokrat kesenian dianggap sekedar ada di panggung dan banyak orang berjejal. MTI jelas jelas bukan Hatedu, juga bukan lomba-festival teater mahasiswa.
Jika Solo kian merana dalam kehidupan teater, walaupun ada secercah sinar yang masih harus ditunggu pada masa yang akan datang, bagaimana dengan kondisi teater di kota kota lain di Jawa Tengah? Di Tegal masih ada teater, karena ada Daryono yang betapapun kondisi fisiknya kian ringkih tapi semangat berteaternya terus menyala. Rudy Iteng mengiringinya, walau tidak seproduktif dulu. Semarang? Gimana yaa kita mau ngomong soal teater di Semarang? Kota ini sibuk dengan isu yang gede-gede diantara kondisi inferior psikologis soal senirupa yang ingin menandingi Yogyakarta, Bandung, Bali dan Jakarta. Semarang bukan seperti masih ada Mas Darmanto Jt – RIP – dan Agus Maladi Irianto. Sementara itu, Mas Ton, dedengkot Teater Lingkar, rasanya sudah lama mengundurkan diri dari teater dan menikmati wayang kulit. Sesekali kita dengar ada monolog. Itu kehadiran Eko Tunas yang sejak lama menghadirkan dirinya dalam monolog dalam berbagai lintasan waktu dan ruang. Daya tahannya bukan main. Mungkin Semarang bersibuk dengan isu industri kreatif walaupun serba mertanggung namun bersyukur bisa mengangkat isu kegiatan di media sosial sehingga orang Jakarta tertarik. Ada kelompok Hysteria yang punya daya tahan sepanjang dua puluh tahun terakhir ini bergiat bikin aktifitas dan rajin mendokumentasikannya. Ini kelebihan Hysteria yang bisa diingat, yang konon membuat jejaring ratusan komunitas seantero nusantara, seperti deretan daftar referensi kepustakaan sebuah skripsi. Lumayan, sampe-sampe bisa ke luar negeri dan diundang pada setiap peristiwa nasional di Jakarta. Tapi itu bukan teater. Jenis teater lain dalam politik kebudayaan atas nama generasi millennial dan generasi Z dalam industri kreatif yang kebetulan sedang diminati oleh rezim infrastruktur.
Jadi kota mana lagi yang ada teater di Jawa Tengah? Konon lamat-lamat saya dengar ada teater di Salatiga. Konon. Juga di Purwokerto. Konon. Juga di Kudus. Konon. Yang konon konon ini jenis teater yang setahun-dua nongol, muncul dalam rangkaian acara, entah apa. Tapi pasti ada kaitannya dengan seremonial. Saya sendiri nggak pernah melihat. Saya hanya mendasarkan diri informasi dari kalangan teman di kota tersebut. Jadi, teater memang susah, sulit dan banyak masalah. Apalagi teater juga sudah digusur oleh teater politik pembangunan infra struktur yang demikian gencar seiring gencarnya tontonan di media sosial yang lebih menarik minat, timbang membayar tiket dan disodori oleh sumpah serapah dari lakon yang mentah.
Betapa dada rasanya sesak ketika banyak peminat dan pelaku teater diberbagai kota yang pernah mengetahui Teater Gapit, Teater Gidag Gidig dan Teater Surakarta (TERA) pada periode 1980-90an, bertanya kepada saya, bagaimana dengan grup-grup teater itu. Maka bersyukurlah ada basa basi betapapun saya kurang suka dengan hal itu: Teater Gapit sudah lama sutradaranya wafat, maka teater itupun lenyap. Kan menjelma menjadi Teater Lungid? Mungkin juga, tapi penjelmaannya jauh berbeda. Sangat jauh, nggak bisa diukur. Jangan anda berpikir bahwa proses kerja dan garapannya seperti Teater Gapit yang pernah ditangani oleh Bambang “Kentut” Widoyo Sp. – RIP – Itu lengket melekat dibawa oleh penerusnya. Yang dulu menggarap dan menghadirkan teater dengan semangat penciptaan tradisi baru dengan seluruh enerjinya melalui riset, diskusi dan pendekatan personal yang intensif dalam eksplorasi aktornya, dan secara mendalam disain artistik panggung diwujudkan melalui studi pemahaman ruang sosial. Jadi, Teater Lungid terasa seperti mengejar produksi dan jatah sambil menghibur diri dari krisis eksistensial. Sedangkan TERA nampaknya masih sesekali muncul dengan keterpaksaan dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Tokohnya yang ada hanya Gigok Anurogo, Bambang A.Erte. dan St. Wiyono – RIP – yang baru saja pada tanggal 8 November 2024 wafat. Sedangkan Teater Gidag Gidig, punya kompleksitas masalah yang rumit berkaitan dengan kesibukan anggotanya, orientasi ingin membuat film, dan masuk ke dalam berbagai kegiatan. Pokoknya berjalan dengan santai, masih saling bersua, kongko, dan saling membantu kalau ada kegiatan. Catatan yang perlu saya tulis disini berkaitan dengan kondisi Teater Gidag Gidig adalah, bahwa betapa rumitnya relasi personal dan sosial untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk menggali dan menghidupan kembali enerji yang pernah ada. Saya masih percaya bahwa figur Hanindawan sebagai sutradara memiliki kapasitas yang boleh dihandalkan diantara generasi pelaku teater sejak 1980an, dialah yang masih mumpuni. Dialah yang masih memiliki ketajaman pikiran di dalam melacak lakon dan menyajikan ke panggung, dan tahu betul bagaimana menggarap seseorang menjadi aktor. Dia punya kepiawaian dan tehnik personal yang bisa menciptakan ruang bermain dan menjadikan hadir di atas panggung. Sedangkan pelaku teater lainnya, seperti dan bagaikan iklan minuman, Teh Botol, apapun lakonnya cara menggarapnya sama: semua aktor menjadi streotipe, dan lakon, dan suara suara dari teks itu, hanya di ujung lidah.
Mari kita kembali kepada tradisi kita, cari kambing hitam: jika teater di Solo sekarang ini lesu lemah lunglai dan lenyap, itu karena Hanindawan nggak mau turun gunung dan masuk kembali dalam dunia – meminjam istilah persilatan – kangow, rimba hijau yang penuh tantangan.
Ayooo, Hanin…….
***
Studio Plesungan, Dukuh Plesungan, Karanganyar, 10 November 2024
*Halim HD, Networker-Organizer Kebudayaan