Otonomi Seni dan Problem Epistemologi
(Tanggapan untuk Chabib Duta Hapsoro)
Oleh: Syarif Maulana
Berbagai tulisan yang pada pokoknya adalah memperdebatkan “gerhana seni rupa Indonesia” merupakan diskursus yang menarik untuk dicermati. Saya memutuskan untuk nimbrung setelah membaca tulisan Chabib Duta Hapsoro yang berjudul Gerhana dan Otonomi Seni Rupa Indonesia.
Tesis Chabib berangkat dari pemikiran Syed Hussein Alatas dalam bukunya yang berjudul The Development of an Autonomous Social Science Tradition in Asia: Problems and Prospects (2002). Gagasan utamanya adalah usaha formulasi persoalan di negara sendiri secara independen, tanpa bergantung pada kacamata-kacamata luar. Jika diasumsikan bahwa “kacamata-kacamata luar” itu mengarah pada warisan kolonial, maka sudah seharusnya intelektual di negara bekas jajahan ini mengembangkan cara pandangnya sendiri, yang otonom dan lepas dari kepentingan negara-negara penjajah.
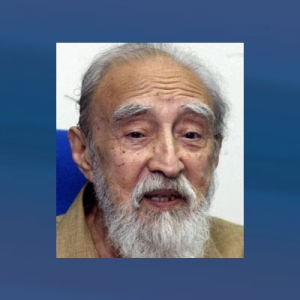
Syed Hussein Alatas
Chabib kemudian menawarkan gagasan Alatas tersebut untuk diterapkan pada wilayah seni rupa di Indonesia. Menurut Chabib, sebagaimana ilmu pengetahuan, baik itu alam maupun sosial, pembahasan seni rupa juga semestinya bisa dilepaskan dari “kacamata-kacamata luar” yang malah berpotensi menjadikan seni rupa Indonesia senantiasa berada pada posisi subordinat. Chabib menawarkan independensi pelaku dan intelektual seni di Indonesia ini untuk mempermasalahkan situasi kebudayaan lokal secara jernih, sehingga formulasi kebijakan baru atau langkah-langkah riil benar-benar disuling dari seni dan budaya yang konkret berada di tengah masyarakat. Ujungnya, Chabib mendorong jalan keluar berupa otonomi seni rupa Indonesia, sebagaimana halnya Alatas juga menyerukan otonomi keilmuan dari negerinya sendiri.
Tesis tersebut mengesankan, dengan mengusahakan seni rupa Indonesia untuk keluar dari kerangkeng epistemik yang berbau “kacamata luar”, tetapi sebenarnya tanpa sadar menjebloskannya pada kerangkeng epistemik yang lain. Misalnya, istilah “otonomi” sendiri merupakan gagasan khas “kacamata luar”, jika tidak kita sebut saja langsung sebagai “Barat” (diberi kutip, untuk menghindari esensialisme dan pemutlakan). Immanuel Kant, dalam Groundwork of Metaphysics of Moral, menempatkan istilah otonomi dalam konteks putusan moral, yang mestinya mengacu pada peran akal budi sendiri sebagai sumber hukum yang wajib ditaati secara mutlak. Kant mempertentangkan konsep otonomi dengan heteronomi, semacam ketertundukan pada kekuatan di luar si individu. Artinya, alih-alih seni rupa Indonesia menjadi otonom seperti yang dicita-citakan oleh Chabib, ternyata dari sejak permulaan, gagasan otonomi itu sendiri sudah mengacu pada kekhasan kacamata luar.
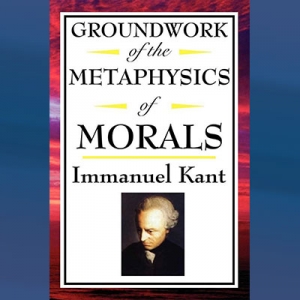
Buku Immanuel Kant “Groundwork of Metaphysics of Moral”
Tentu persoalannya tidak berhenti pada problem semantik istilah “otonom” itu saja. Gagasan Chabib kemudian bisa dibaca dalam dua perspektif, pertama, bahwa Chabib tengah menawarkan purifikasi, semacam seni rupa Indonesia yang steril dari pengaruh-pengaruh luar, dan/ atau kedua, seni rupa Indonesia yang diabstraksi dari “bawah ke atas” (semacam dialektika materialis jika menggunakan bahasa Marxis) dan bukannya “atas ke bawah” seperti selama ini digadang-gadang oleh “kacamata luar” yang cenderung mengkolonialisasi itu.
Kedua perspektif tersebut mempunyai masalahnya masing-masing. Tentang butir pertama, usaha purifikasi adalah usaha yang bisa dikatakan utopis. Usaha pemurnian pada akhirnya hanya akan membawa kita pada permasalahan esensialisme, seolah-olah ada yang inti dari segala sesuatu, padahal yang inti tersebut merupakan hasil reduksi saja. Sebagai contoh, tidakkah istilah “Indonesia” sendiri sudah problematis untuk ditarik pada satu esensi saja? Dalam konteks seni rupa, tentu Chabib lebih paham bahwa Sudarto – seorang tokoh dalam roman karangan Imam Supardi, berjudul Kintamani (1942) – mengatakan tentang “Indonesia” sebagai “yang elok-elok, yang jika ditunjukkan di negara lain, akan besar hatinya”, sementara Sudjojono mengatakan tentang kekhasan masa kini, yang tidak menyalin dari apa yang nampak di luar, melainkan menampakkan apa yang tersembunyi di dalam. Manakah yang benar tentang Indonesia? Bisa jadi dua-duanya benar, tetapi jika kita terima jawaban tersebut, hal demikian sekaligus menggugurkan kemungkinan purifikasi terhadap apa itu “seni rupa Indonesia”.

Buku karangan Imam Supardi, berjudul Kintamani (1942)
Tentang butir kedua, bagaimana seni rupa Indonesia seharusnya disuling dari kenyataan-kenyataan material historis yang ada di Indonesia, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana jika kenyataan-kenyataan tersebut juga melibatkan hal-hal “non-Indonesia”, apakah tidak kemudian menggugurkan tesis Chabib sendiri tentang “otonomi seni rupa Indonesia”? Jika benar bahwa butir kedua ini adalah gagasan yang dimaksud Chabib untuk otonomi seni rupa Indonesia, maka bisa jadi Chabib sejalan dengan pernyataan Basuki Resobowo dalam Dua Seni Rupa (2001) yang ditulis oleh Sanento Yuliman berikut ini, “Untuk memberi bukti corak keindonesiaan cukup apabila hasil kesenian itu dapat menyesuaikan diri dengan masalah-masalah psikologi dan sosial dari tempat kelahirannya dan pada masanya.”
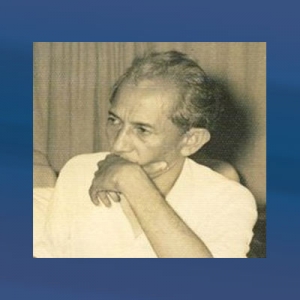
Basuki Resobowo
Penerimaan atas pernyataan Basuki tersebut mengandung konsekuensi, bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat dikatakan sebagai persoalan “khas Indonesia”, karena yang lebih tepat adalah persoalan psikologi dan sosial yang terjadi “di Indonesia”. Basuki hendak mengatakan bahwa ada aspek performatif dalam gagasan tentang apa itu “Indonesia” dan pergerakannya yang lentur ini melibatkan aspek apapun yang tidak perlu dipersoalkan apakah itu “Barat” – “Timur”, otonom – heteronom, atau luar – dalam.
Jika dikotomi-dikotomi itu sudah tidak lagi relevan, maka sudah semestinya kita meninjau ulang gagasan otonomi yang berpotensi terpeleset pada esensialisme tersebut. Pada akhirnya, yang lebih diperlukan adalah menghayati tegangan pada setiap polarisasi. Kenyataan bahwa kita mesti tunduk pada beberapa “produk Barat”, semestinya tidak menjadi soal jika memang “produk Barat” diterima sebagai usaha “menaiki pundak ‘raksasa’” agar kita bisa melihat ke dalam secara lebih jernih. Bisa jadi, usahanya lebih pada bagaimana kita menempatkan aneka gagasan itu pada “ruang liminal” yang jauh dari kebekuan dan senantiasa performatif.
*Syarif Maulana adalah pengajar di Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dan mahasiswa doktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Syarif menginiasi kelas belajar filsafat daring “Kelas Isolasi” dan menulis buku berjudul Kumpulan Kalimat Demotivasi (2020) serta Nasib Manusia: Kisah Awal Uzhara, Eksil di Rusia (2021). Syarif juga merupakan ketua panitia Philofest ID 2020, festival filsafat terbesar di Indonesia.













