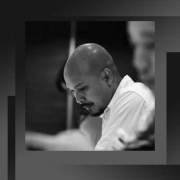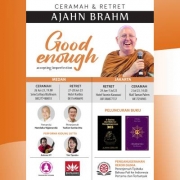Catatan dari Menonton Pertunjukan Peserta FTJS 2025 (Bagian 1)
*Oleh: Dendi Madiya (Juri FTJS 2025)
Festival Teater Jakarta Selatan (FTJS) berlangsung lagi tahun ini. Semua pementasan peserta dilaksanakan di Gedung Pertunjukan Bulungan, Gelanggang Remaja Jakarta Selatan, pada pukul 20.00 WIB, minggu pertama hingga pertengahan September 2025. Sebagaimana beberapa agenda kesenian lainnya, penyelenggaraan kegiatan ini sempat diundur karena force majeur: terjadinya demonstrasi di Jakarta.
Catatan ini ingin membaca pertunjukan para peserta dengan sebisa mungkin menghindar dari sifat evaluatif meskipun pada titik tertentu evaluasi tidak terhindarkan pada diskusi-diskusi dengan kelompok peserta setiap sore.
Membaca Efek Rashomon dengan Playfulness
Teater K. – Membaca Efek RASHOMON
Berdasarkan karya Ryunosuke Akutagawa
Sutradara: MM Al Muhtadi MD
5 September 2025
Teater K. sepertinya sudah menemukan identitasnya sebagai teater Jejepangan. Kali ini, Teater K. menampilkan semacam diskusi anak muda, sekaligus sebentuk teater-dalam-teater atau cerita-dalam-cerita, tentang efek Rashomon.
Efek Rashomon adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu peristiwa dapat digambarkan dengan berbagai cara karena keterlibatan banyak saksi. Subjektivitas para saksi merupakan akibat dari perbedaan situasi, sosial, dan budaya. Istilah “Efek Rashomon” dicetuskan setelah sineas ikonik Akira Kurosawa pertama kali menggunakan teknik penceritaan ini dalam film Rashomon (1950). Film tersebut telah memengaruhi banyak film sepanjang sejarah. Efek Rashomon melampaui dunia perfilman dan menjadi istilah yang umum digunakan dalam psikologi maupun hukum.[1]
Sebenarnya film Rashomon itu sendiri lebih banyak memakai cerita dari cerpen Akutagawa yang lain yang berjudul “In A Grove.”[2]
Pada buklet pertunjukan ini, Teater K. menuliskan sinopsis: “Empat narator sedang memperdebatkan tentang mana kebenaran yang paling masuk akal, atau bahkan paling benar. Mereka menghadirkan reka ulang adegan, sembari mencoba menelaah dan membaca pikiran mereka yang sudah terdampak dengan Efek Rashomon. Kembali dihadirkan adegan demi adegan dalam kisah pembunuhan Kanazawa no Takehiko, sang samurai, suami dari Masage. Berbagai versi pembunuhan dihadirkan sesuai dengan kesaksian masing-masing karakter. Apakah para narator bisa sepakat dengan versi kebenaran yang “no debat”, ataukah justru sifat dasar dan kebenaran itu memang cair dan mengikuti bentuk perspektif dari masing-masing kepala?”

Pertunjukan dari Teater K. ini dan efek Rashomon itu sendiri rasanya ingin menegaskan pandangan Richard Rorty, seorang filsuf kontemporer yang mempopulerkan pandangan relativisme mengenai kebenaran. Menurut Rorty, kebenaran adalah hasil dari percakapan yang berkelanjutan di dalam suatu komunitas. Ia berargumen bahwa kebenaran ilmiah tidaklah mutlak tetapi ditentukan oleh konteks sosial dan historis tempat teori itu berkembang. Rorty menunjukkan bahwa meskipun objektivitas adalah tujuan dalam penelitian ilmiah, pengakuan terhadap faktor-faktor sosial dan budaya dalam interpretasi ilmiah juga penting untuk memahami bagaimana “kebenaran ilmiah” dibangun dalam konteks tertentu.[3]
Pertunjukan ini tarik-ulur antara komedi dan tragedi untuk pada akhirnya ditutup dalam nuansa parodi. Adegan-adegan kesaksian dari para tokoh (Tajomaru, Masage dan Takehiko) cenderung dimainkan oleh para aktor dan aktris dengan pola akting serius-dramatis sambil sesekali diselingi oleh pola ucap dan gestur komedi dari Hafid yang memerankan tokoh Tajomaru. Daffa yang memakai topeng kuda juga membumbui pentas ini dengan nuansa komikal. Persoalan kehormatan perempuan, maskulinitas dan feminitas, serta relativisme kebenaran dibawakan oleh para tokoh yang disebut sebagai narator dengan pembawaan anak muda yang ceria, tak lupa diisi candaan dan saling meledek.
Tata panggung memperlihatkan bidang-bidang level yang diberdirikan dan mengubah-ubah setting yang ingin diterangkannya sesuai pengadeganan yang sedang berlangsung. Ketika panggung menampilkan adegan-adegan dari cerpen Akutagawa, ditambahkan elemen-elemen dedaunan dan ranting-ranting di atas level untuk menggambarkan hutan. Bergantian dengan adegan perdebatan para narrator, ranting dan dedaunan itu dihilangkan menjadi setting yang terbuka untuk ditafsirkan oleh penonton.
Pembacaan terhadap efek Rashomon itu sendiri dalam pentas ini berada dalam artikulasi yang keluar-masuk antara ringan, samar, tegas, juga menegang dengan perdebatan di antara para narator. Sebenarnya, selain membaca efek Rashomon, pertunjukan ini juga membaca teks Akutagawa sebagai sebuah tubuh karya seni. Ini adalah pentas yang membincangkan karya sastra Akutagawa dalam sudut pandang Teater K. yang playfulness.
Pertunjukan ini berpotensi mengangkat beberapa wacana yang terkandung dalam karya Akutagawa secara diskursif tanpa kehilangan unsur playfulness. Sebagaimana dipertunjukkan pada bagian ending, Teater K. dalam pandangan saya menyerahkan kembali kepada penonton untuk beropini tentang kebenaran di benak masing-masing. Tidak ada kesimpulan tentang kebenaran yang dimutlakkan dalam pertunjukan ini. Sebuah sikap yang moderat tetapi juga beririsan dengan kondisi post-truth. Konsep post-truth menjadi populer pada tahun 2016, saat Oxford Dictionaries menetapkannya sebagai “Word of the Year.” Istilah ini merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi.[4]
Kolektivitas dan Kegembiraan Berteater
Aktor Kulit Luar – ORKES MADUN III ATAWA SANDEK PEMUDA PEKERJA
Karya Arifin C. Noer
Sutradara: Yuanditra Bhayu Utarto
6 September 2025
Menurut pengamat teater, Noorca M. Massardi, inilah naskah Arifin C. Noer yang “bernafsu berbicara tentang sistem kapitalisme, penindasan kaum buruh, dan pola ekonomi negara industri. Hal-hal yang dianggapnya merupakan kenyataan sosial yang dihadapi sehari-hari.” Menurut Noorca, Arifin dekat dengan kehidupan buruh karena pernah menjadi manager pabrik di Pulogadung, Jakarta Timur.[5]

Kelompok ini memainkan lakon Orkes Madun III atawa Sandek Pemuda Pekerja dengan keasyikan bermain yang memancar ke luar panggung. Semua pemain kelihatan menikmati permainannya, tidak banyak beban, enjoy, celetukan-celetukan meletup di sana-sini. Cocok dengan tuntutan naskah yang memang menghadirkan grouping di sanasini. Sebuah pentas yang berhasil menghadirkan manusia-manusia pinggiran yang tercekik dan tertindas oleh sistem kekuasaan.
Sebagaimana dicatat oleh pengamat teater, Syu’bah Asa:
Maka inilah sebuah cerita sosial. Ada anak-anak yang bekerja di bawah umur — seperti Si Oni, pacar Sandek “yang bahkan belum haid”. Ada masalah murahnya tenaga kerja dan “rendahnya keahlian”. Ada peristiwa kegemaran berburu para majikan yang membawa akibat tertembaknya seorang buruh –dan si tuan menyesali karena yang mati ternyata “tak bermutu” — bukan babi yang gemuk. Ada suara-suara mesin. Ada sirene pabrik, dan suara bayi di perkampungan buruh yang baru lahir (dan layar diangkat khusus untuk dua suara ini). Ada pula, tertu saja, pemogokan — atau hampir pemogokan, “karena, ingat, mogok itu dilarang,” kata seorang tokoh.[6]
Saya menangkap pertunjukan dari kelompok Aktor Kulit Luar (Akular) ini all out dari beberapa lini pementasan, terutama pengadeganan p=ara pemain yang menghadirkan pola-pola grouping seturut ciri khas serial naskah Orkes Madun karya Arifin C. Noer. Para pemain melangsungkan daulat aktor di atas panggung dengan semangat yang tinggi, energi yang membuncah-buncah terasa hingga ke bangku penonton.
Para pemain yang memainkan umang-umang (saya membacanya sebagai ‘wong cilik’ di lorong-lorong dan pinggiran kota), para pemain yang memerankan buruh pabrik, para pemain yang berlaku sebagai jajaran eksekutif perusahaan beserta anak buahnya, semua menciptakan totalitas dalam performance mereka.
Sheikh Zaidan, Rues dan Athallah yang memerankan kubu pemilik pabrik (Tuan, Yang Satu dan Yang Dua) menjadi zombie penghisap darah dan daging kehidupan buruh. Kepala dan tubuh mereka yang kaku dan patah-patah hampir menjedot drum sebagai alat produksi pabrik mereka sendiri.
Melalui pertunjukan ini, saya melihat sebagai sebuah kelompok, Akular memiliki kekompakan kolektif serta kegembiraan dalam berteater, satu hal yang rasanya semakin jarang saya temui belakangan ini. Perjalanan kolektivitas dan kegembiraan itu sampai hingga pertunjukan di atas panggung. Apakah kualitas ini lahir sebagai konsekuensi dari rahim teater kampus tempat mereka berasal? Beberapa teater kampus dan turunannya yang saya ketahui dengan biografi mereka memang menciptakan jejak panjang mengenai kesolidan kolektif.
Saya teringat pendapat Nano Riantiarno:
Hakikat teater adalah kebersamaan. Sudah terbukti sejak lama, bahwa, peristiwa teater dibangun secara kolektif. Peristiwa teater lahir dari kegiatan bersama. Para teaterawan wajib mencipta komunitas kebersamaan, lalu menjaganya, dan bukan malah mempertajam kesendirian. … Maka, jika terjadi penyimpangan (melulu kesendirian), kesinambungan bisa mandek. Bisa jadi, teater kemudian akan dipandang sebagai alien, “monster” yang mengerikan, egoistis, rumit, kompleks, tidak menarik karena terfokus “hanya” kepada diri pribadi-personal, sangat subjektif. … Akibatnya, teater bisa terpinggirkan oleh masyarakatnya sendiri.[7]
Menonton Akular ini, saya merasa mereka sedang melakukan demonstrasi lewat pertunjukan. Barangkali karena totalitas energi yang dikerahkan oleh para pemain. Tetapi juga pengadeganan rombongan buruh yang bernyanyi, berbaris, bergerak dan bekerja bersama dalam keperihan karena diperas oleh kapitalisme, membuat pertunjukan ini terasa sebagai unjuk rasa dan bersolidaritas terhadap kaum buruh di pusat-pusat industri. Selain di luar panggung, kita semua sedang berada dalam bayang-bayang demonstrasi terhadap pemerintahan dan legislatif, baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia.
Adegan-adegan yang diberlangsungkan dalam pertunjukan ini mengalir secara komikal, bergantian dengan kelirihan. Celetukan yang banal-keseharian bertaburan dalam adegan rapat antara Waska dengan para umang-umang. Sedangkan adegan-adegan antara Sandek dengan Oni seperti menciut dalam atmosfir manusia jelata sebagai individu-individu mungil berhadapan dengan kekuasaan kapitalisme dan keangkuhan kota yang massif.
Steger kayu yang menjadi singgasana Waska mengingatkan saya kepada steger-steger atau jembatan-jembatan kayu dan bambu di kampung-kampung pesisir Jakarta Utara, sarana penghubung darurat antar ruang aktivitas warga. Steger Waska bergoyang mengikuti irama tubuh para pemain yang menaikinya, menciptakan ruang emergency dan teror, antara bertahan atau rubuh.
Empat pilar aktor berada di tubuh Umat sebagai Sandek, Sandy sebagai Oni, Djunaedi Lubis sebagai Waska dan Semar, serta Bendow sebagai Bigayah. Selain Djunaedi yang bermain ganda sebagai Waska dan Semar seturut tuntutan naskah, Bendow juga bermain double-casting sebagai Bigayah dan Kakares. Djunaedi menunjukkan kelasnya sebagai aktor yang liat, keluarmasuk berganti peran antara Waska dan Semar tanpa kehilangan kemampuan komunikasi dengan penonton. Bendow berhasil mengekspresikan kegenitan dan kebinalan Bigayah. Umat dan Sandy cukup total dalam porsi dan karakter peran yang mereka mainkan.
Tata musik yang digarap Widiyansyah menyuguhkan komposisi live-music dengan playback, juga beberapa momen adegan diisi dengan permainan solo gitar dan bas. Musik hadir bukan sekadar ilustrasi adegan tetapi turut menyatu untuk menubuh dalam aksentuasi adegan.
Penjara Mobile
Naung Collective Arts – BUI karya Akhudiat
Sutradara: Casandra Decak
7 September 2025
Kelompok ini menubuhkan naskah dengan strategi memberikan latar belakang etnis kepada ke-dua tokoh dalam naskah, satu tahanan beretnis Minang dan satu lagi beretnis Batak. Dengan strategi seperti ini, dialek dari dialog-dialog dan pola tubuh mengalir dengan mempertahankan identitas etnis-etnis tersebut. Apalagi ketika adegan-adegan bela diri muncul, maka pola-pola gerak yang bernuansa tradisional mengemuka. Alasan di balik pemberian identitas etnis kepada para tokoh ini adalah untuk memperkuat karakter setiap tokoh. Misalnya, dialek Minang pada tokoh OB1 untuk mencerminkan karakter yang berpengalaman, cerdik, dan sinis.
Barangkali tidak seperti pentas BUI lainnya yang memisahkan antara tokoh OB1 dengan OB2 dalam penjara masing-masing, BUI dari kelompok ini lebih banyak mempertemukan ke-dua tokoh dalam kesatuan ruang adegan. Salah seorang pemain BUI saat disutradari Akhudiat tahun 1976, Sian Dyhs, mempunyai pendapat, “Naskah ini sebenarnya bercerita tentang dua tahanan yang dikurung di dalam sel terpisah, tidak bisa saling bertemu muka. Yang bisa mereka lakukan adalah berkhayal. Nah khayalan atau imajinasi kedua tahanan inilah yang ada di naskah.”[8]
Tata panggung pertunjukan kelompok Naung Collective Arts yang digarap oleh Ahmad Rifqi ini menyajikan bentuk jeruji penjara yang plastis mengikuti pengadeganan. Jeruji penjara menjadi terbuka dan tertutup, membentuk beberapa komposisi garis di atas panggung. Penjara yang bergerak berubah-ubah ini menyiratkan bahwa penjara bisa berada dimana-mana dalam macam-macam bentuk.
Penjara di mana-mana sama, seperti halnya negara di mana-mana sama saja. Tidak di Amerika, tidak Rusia, tidak Cina, tidak Irlandia atau British, Prancis, Germania, Hollanda, Hindustan, Brazil, Nigeria, Parsi, Kueait, Majapahit, Cocos Island, Banglades, Abassiah, Monte Carlo, IGGI, PanAm, ITT, Hilton, Sheraton, Shell, Bodrex, Japan Inc, Time Inc, Kultur Kredit, juga Republik bangsa dewek. Negara ini penjara besar, lebih tempurung dari tempurung. Sehingga saya kodok tidak bisa bedakan ngorek atau ngorok atau ngok. Heee….saya bukan kodok, ndoro![9]

Penjara yang mobile itu terutama bergerak pada adegan-adegan seksual sesama lelaki antara tokoh OBI dengan OBII. Mereka menjadi kucing yang sedang birahi, pantat ketemu pantat, setelah sebelumnya mereka mengintip sesuatu entah apa.
Akting yang dimainkan para aktor, Ikhsan Haryanto sebagai OBI, Vigo Ravindo sebagai OBII dan Muhammad Yaser Mahardika sebagai Sipir, berada pada kisaran akting yang formal, clean, dengan tehnik-tehnik akting yang mengingatkan saya pada pertunjukan-pertunjukan ujian jurusan teater di kampus kesenian. Gaya akting yang saya kira juga berpengaruh pada kelompok-kelompok teater umum di luar kampus kesenian.
Tata artistik panggung beserta set dan properti juga terasa rapi seperti menonton film layar lebar tanpa scratch atau kerusakan gambar oleh jamur atau bakteri dalam ruang penyimpan pita seluloid. Bola-bola kecil berwarna-warni masih berbau baru seperti belum lama dibeli dari toko mainan anak-anak. Semua ini membentuk bahasa pertunjukan yang terasa resmi.
Saya jadi teringat dengan apa yang dituliskan Afrizal Malna ketika mengamati tiga karya pertunjukan dari Teater Aristokrat, sebuah kelompok teater yang tumbuh dan dimotori oleh mahasiswa-mahasiswa di lingkungan kampus Institut Kesenian Jakarta:
Ketiga pertunjukan itu memperlihatkan kerja teater yang berusaha bertahan pada keresmian bahwa aktor hanya bisa dihadirkan pada keresmian tempat, kata, dan pemeranan yang telah digariskan pada polanya. Pertaruhannya terletak pada bagaimana mereka bisa meyakinkan konvensi mimesis dalam dunia teater terhadap penonton, sehingga pesan-pesan yang dikandung naskah bisa diterima. Pemilihan kerja seperti ini, dimana kausalitas dan pemeranan telah dipola sedemikian rupa, tidak bisa menghindari linearitas yang membalut struktur pertunjukan.[10]
Kematian Dijemput Kematian
Teater Ciliwung – PELANGI karya Nano Riantiarno
Sutradara: Bagus Ade Saputra
8 September 2025
Teater Ciliwung menampilkan pertunjukan dengan lakon Pelangi pada FTJS tahun ini. Para pemain bermain dengan apik, dialog-dialog terucapkan dengan kesungguhan inner-acting. Karakter dan biografi tokoh juga terwujudkan dalam tubuh-tubuh para pemain, seperti mereka telah melalui berbagai peristiwa. Blocking dan moving pemain tertata apik, ada motivasimotivasi kuat di balik pergerakan mereka. Klimaks pun terasa.
Lakon ini berlatar belakang komplek perumahan masyarakat Maluku di tengah kebisingan kota Jakarta. Naskah ditulis oleh Nano Riantiarno pada Juni 1975 dan ditulis ulang pada Desember 1998. Pada naskah ini, Papua masih disebut dengan kata “Irian.”[11] Keluarga yang diceritakan dalam naskah ini adalah sebuah keluarga yang berasal dari Maluku yang memutuskan pindah ke Jakarta untuk bisa mendapatkan kuota dari pemerintah agar dapat pindah ke Belanda. Konflik utamanya lebih mengarah ke persoalan anak bungsu yang memutuskan untuk menikah tapi ditentang oleh kakaknya.
Saya kira Teater Ciliwung sudah menemukan jalurnya. Lewat beberapa kali saya menonton pertunjukan kelompok ini, termasuk tahun lalu pada forum yang sama dan jauh beberapa tahun ke belakang, saya kira Teater Ciliwung sudah bertungkus lumus dengan bentuk teater realis selama ini dan sudah menemukan semacam kemapanan pada jalur tersebut. Sudah saatnya Teater Ciliwung menemani Teater Satu-Lampung, misalnya, sebagai kelompok teater yang juga sering memanggungkan bentuk teater realis. Teater Ciliwung pun berpotensi menemani Teater Koma pada jalur teater-teater yang digemari penonton dan berpeluang melahirkan segmen penonton tersendiri.

Adegan terakhir pada pertunjukan ini mengambil bahasa medium film. Mama yang diperankan oleh Kunti Dewanggani menghembuskan nafas terakhir di kursi roda. Di tengah tangisan anak sulungnya yang bernama Siska, Mama yang telah menjadi arwah berdiri bangkit dari kursi roda dan berjalan menuju pintu rumah yang terbuka diam-diam. Dari pintu rumah yang terbuka diam-diam itulah, masuk arwah Papa yang dimainkan oleh aktor senior, Ayez Kassar (yang saya tunggu-tunggu pemunculannya dan cukup bikin penasaran akan seperti apa permainan aktor senior ini di pertunjukan ini), merentangkan tangan dan memeluk Mama. Kematian dijemput kematian. Sedangkan Siska terus menangis di kursi roda. Adegan yang manis sekaligus menguras emosi untuk menutup pertunjukan ini. Mata penonton pun berkaca-kaca.
Teks dialog yang dilontarkan para pemain pada pertunjukan ini sepertinya bersetia pada naskah dengan mempertahankan bahasa lama. Misalnya, kata “tidak” tidak berubah menjadi kata “nggak.” Pada satu sisi berkesan formal tetapi para pemain berhasil menekuk keformalan tersebut melalui akting mereka sehingga jarak wantu antara pemain dengan teks dan penonton dengan pertunjukan berhasil diatasi.
Bagus Ade Saputra, sutradara pertunjukan ini, menyampaikan bahwa naskah Pelangi dibuat Nano ketika ia masih aktif di Teater Populer. Saat itu Teater Populer aktif menggelar pementasan di Hotel Indonesia, Jakarta. Pada saat bergabung di Teater Populer itu pula, Nano banyak bertemu orang-orang dari Indonesia bagian timur. Saya jadi membayangkan pertunjukan Pelangi ini sebagai bentuk reenactment dari pertunjukan Teater Populer, semacam teater dokumenter dalam bentuk teater realis, menghidupkan kembali bentuk teater pada periode tertentu dalam masa lampau teater kita, juga menangkap kondisi zaman dimana dan ketika teater itu hidup.
Kunti Dewanggani, Lefi Wilmala, Lala Jasin, Gusvari Ibrahim, Nadya Angelina, Rini Paramaratu, Ravi Pestrani, Bobby Kardi dan Ayez Kassar adalah himpunan aktor dan aktris yang menghidupkan pertunjukan ini dalam sebuah orkestrasi akting, menyematkan sebuah frasa dalam bahasa Inggris, yaitu ensemble cast.
Serigala-Serigala dalam Rumah
Hujan Mimetik – RUMAH YANG DIKUBURKAN
Adaptasi dari Naskah BURIED CHILD
Karya: Sam Shepard
Terjemahan: Akhudiat
Diadaptasi oleh Afrizal Malna
9 September 2025
Doj adalah seorang petani Amerika berusia 70-an, kepala keluarga yang menua dan disfungsional, seorang pecandu alkohol yang sedang sekarat. Semangatnya telah hilang oleh tingkah laku anaknya dan ketidaksuburan ladangnya. Doj menanggung beban malu dan rasa bersalah karena anak dan istrinya melakukan hubungan seksual dan Doj membunuh anak hasil hubungan inses tersebut. Sehari-harinya Doj duduk-duduk, menonton televisi, dan minumminum. Hali-e, istri Doj berusia pertengahan 60-an, seorang ibu pemimpin keluarga, sering mengomeli Doj. Hali-e berhubungan seks dengan putranya. Dia juga kerap meninggalkan keluarga untuk bergaul dengan Pastor Dewis dan bersuka ria. Sedangkan Tilden; putra tertua mereka yang berusia akhir 40-an. Seorang anak yang tidak punya tujuan, tidak punya arah dalam hidupnya. Tilden berhubungan seks dengan ibunya. Dia bingung, malu, dan merasa bersalah tentang kematian anak hasil hubungan tersebut. Tilden juga kerap diintimidasi oleh karakter lain.[12]
Tokoh Doj yang diperankan oleh Tri Yoko mencoba untuk menggambarkan Doj sebagai sosok yang masih berupaya bangkit dalam keterpurukan hidupnya dan keluarganya. Tubuhnya memancarkan energi perlawanan terhadap kondisi yang mengepungnya. Pemeran tokoh Halie (Ageng R Fauziah) bersemangat mengomeli Doj, kata-kata nyerocos keluar dari mulutnya. Pemeran tokoh Tilden (Hery Sunandar) dengan pola vokal yang berat tetapi tubuhnya bisa memainkan pola-pola gestur anak kecil yang merengek-rengek.

Niat Shepard dengan naskah ini adalah untuk menciptakan narasi yang mengomunikasikan dan mencerminkan rasa frustrasi rakyat Amerika. Berlatar dalam konteks yang mudah dikenali, keluarga petani Amerika, naskah ini berpusat pada isu-isu yang universal dan kekecewaan terhadap impian Amerika.[13]
Mimetik Hujan menggunakan naskah adaptasi Afrizal Malna untuk pertunjukan ini yang membuat puitika Afrizal masuk ke dalam pertunjukan. Semangka yang dicacah-cacah, gergaji mesin, perbincangan tentang kota dan puisi, menjadi narasi tandingan yang puitik terhadap teks asli maupun terjemahan Akhudiat. Ladang jagung bersanding dengan semangka.
Penggunaan mesin gergaji betulan pada pertunjukan ini yang dikendalikan Bredli (diperankan oleh Pramono) menjadi semacam teror dalam bayang-bayang ketragisan. Gergaji mesin itu seperti menggantikan keperkasaan Bredli yang kakinya cacat.
Ladang jagung di sisi kanan panggung berdempetan dengan rumah keluarga Doj, berdesakdesakkan mengurung rumah dalam atmosfir suram. Sebuah rumah yang menyimpan rahasiarahasia busuk, sebuah rumah yang menghasilkan tindakan-tindakan serigala para penghuninya, sebuah rumah yang tidak mampu bertahan dari pengaruh luar.
(BERSAMBUNG)
Foto-foto pertunjukan peserta FTJS 2025 oleh Dio
Catatan Kaki
[1] https://www.studiobinder.com/blog/what-is-the-rashomon-effect-definition/
[2] https://www.encyclopedia.com/arts/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/rashomon-rashomonakutagawa-ryunosuke-1917
[3] Peran Filsafat Ilmu Tentang Konsep Teori Kebenaran Ilmiah; Isnawia R. Djou ,Sumarni P. Ola , Samsul Pahmi, https://belaindika.nusaputra.ac.id/article/
[4] https://jogja.kemenkum.go.id/
[5] https://seputarteater.wordpress.com/2016/10/24/kompas-1983-noorca-m-massardi-sandek-oleh-teaterluka/
[6] https://seputarteater.wordpress.com/2015/10/04/tempo-1979-arifin-kendali-dan-sumbat-pementasansandek-oleh-teater-kecil/
[7] Kitab Teater, Tanya Jawab Seputar Seni Pertunjukan. (N. Riantiarno, Grasindo, 2011, hlm. vii)
[8] https://www.ngopibareng.id/read/teater-bui-tidak-bisa-membui-waktu-2003680
[9] Antologi 5 Lakon Akhudiat (Pagan Press, 2014, hlm. 203)
[10] Perjalanan Teater Kedua, Antologi Tubuh dan Kata (Afrizal Malna, iCAN, 2010, hlm. 316)
[11] Potret Riantiarno, Delapan Sandiwara: N. Riantiarno, Kompas Gramedia, September 2016, halaman 228.
[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Buried_Child
[13] idem
——
*Dendi Madiya. Seorang pembuat pertunjukan. Naskah teaternya, Api Seluloid, terpilih dalam Rawayan Award DKJ 2017. Ia pernah diundang sebagai sutradara ke Asian Performing Arts Forum (Jepang, 2018), berkolaborasi dengan Shan Dong Ye Troupe di Taiwan (2019), dan menjabat sebagai anggota Komite Teater DKJ (2020–2023). Kini, Dendi aktif di Garasi Performance Institute dan Artery Performa, serta terlibat dalam Festival Bantargebang 2025.