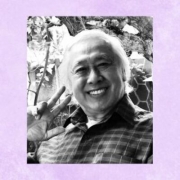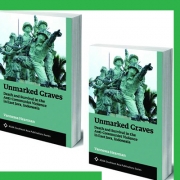Dicky Senda dan Gastrosofi Mollo

Oleh Royyan Julian
Diakui atau tidak, makanan adalah episentrum yang menggerakkan sejarah peradaban Homo sapiens. Seluruh aktivitas, ekspresi, dan hasrat manusia berpusat pada makanan. Hal ini masuk akal karena makanan merupakan kebutuhan dasariah serta sumber nutrisi paling sahih yang memungkinkan manusia—dan makhluk hidup lainnya—sintas.
Nuansa gastronomis inilah yang begitu pekat terhidu di dapur Dicky Senda (33). Di sana, Dicky tidak hanya menjadikan makanan sekadar pemenuh kebutuhan. Ia juga memperlakukan makanan sebagai medium untuk mengurai masa lalu, cermin rasa syukur, dan penanda jati diri.
Saya singgah di kediaman Dicky pada tahun 2019 di bulan Oktober yang kering. Beralamat di Desa Taiftob, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Dicky tinggal bersama sahabatnya yang ramah, seekor anjing jantan cokelat bernama Doggy. Pria berkulit cokelat itu memiliki rambut bergelombang sebahu, tidak terlalu hitam, dan kerap disanggul sebagaimana lelaki Dawan kuno. Warna matanya yang kecokelatan seperti ingin memajankan bahwa leluhurnya, fam Kamlasi, telah bercampur darah Kaukasia. Pada figur Dicky kita bisa melihat interseksi antara modernitas dan tradisionalitas. Lengannya yang tertera rajah paukolo—simbol burung elang, semacam totem yang melambangkan kearifan, watak yang kerap disematkan kepada seorang usif (raja)—seolah-olah hendak menunjukkan bahwa pendidikan tinggi tidak membuatnya memunggungi identitas Timor.
Dengan tubuh ramping dan bertinggi rata-rata, gerakan Dicky amat lincah. Kegesitannya mengolah makanan membuat saya terpaku. Melihat saya bengong, Dicky berkata tanpa berpaling dari kesibukannya di depan kuali, “Kamu duduk saja, Roy. Beta sudah biasa melakukan ini sendirian.”
Dalam waktu sebulan, saya dituntut mempelajari kosmologi Mollo yang amat kaya—dan itu mustahil. Di rumah Dicky, saya membaca beberapa buku penting, antara lain: Mollo, Pembangunan, dan Perubahan Iklim: Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak karya Siti Maemunah, Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban & Penyintas Tragedi ’65 di Nusa Tenggara Timur yang disunting Mery Kolimon dan Liliya Wetangterah, Mama Aleta Fund: Menyelamatkan Hidup, Memulihkan Alam yang merupakan wawancara Siti Maemunah dengan Aleta Baun, Citra Manusia Berbudaya: Sebuah Monografi tentang Timor dalam Perspektif Melanesia karya Gregor Neon Basu, Surat-Surat dari Kapan: Benih Cinta Kasih Allah dalam Budaya Atoni karya Krayer van Aalst, dan sebagainya. Terkait persoalan pandangan dunia manusia Mollo ini, saya juga berbicara dengan sejumlah orang, antara lain Willy Oematan, Marlinda Nau, Arit Oematan, Deci Bernadeta Nifu, dan lain-lain.

Arit Oematan di depan Ume Kbubu marga Oematan
Di samping itu, pengetahuan tentang jagat kebudayaan Mollo saya peroleh di meja makan Dicky. Dicky tidak hanya menjadi saudara perjamuan (table fellowship) yang berbagi makanan di atas meja, tetapi juga peta pertama saya menelusuri rimba tradisi Mollo. Intensitas perbincangan dengannya kerap menyinggung dunia gastronomi Mollo. Di dapurnya, kulkas dan rak memajang awetan-awetan makanan/minuman yang diolah sendiri, seperti asinan sawi, manisan belimbing wuluh, keripik nangka bumbu-bumbu, saus ranti, sambal lu’at, kismis kulit limau, selai jeruk, likeur lakoat, dan biang teh jamur kombucha.
Pada suatu Kamis, ia mengajak saya berbelanja ke Pasar Kapan, membeli bahan-bahan makanan tanpa melalui mekanisme tawar-menawar. Pada hari yang lain, ia mendemonstrasikan kelihaiannya membuat roti tepung ubi bersama para relawan LSM Pikul. Ia amat selektif memilih komposisi makanan. Baginya, menggunakan bahan-bahan lokal menentukan martabatnya sebagai orang adat.
Kita jarang menyadari bahwa ideologi dan mitos yang kita yakini, ritual dan gaya hidup yang kita jalani, bisa dibaca dari sepiring makanan yang kita konsumsi. Kuliner tradisional orang Timor, jagung bose, misalnya, memiliki riwayat sakral sebelum terhidang di meja makan. Sebagaimana tanaman pangan lainnya, ia mengalami proses yang kudus, mulai dari penyimpanan benih, buka kebun, penanaman, hingga panen. Semua itu dilakukan melalui upacara. Orang-orang Timor percaya, tumbuhan memiliki smanaf (sukma). Bertani dan berkebun tidak boleh sembarangan, harus dilakukan pada musim yang tepat serta ditakzimi sebagai aktivitas suci agar terhindar dari ancaman kekurangan makanan, gagal panen, serangan hama, paceklik. Oleh karena itu, mereka juga memiliki kultus figur-figur mitis yang dianggap sebagai pemberi hidup, seperti Uis Maka’ (dewa boga), Fut Ane (dewa padi), Uis Oe (dewa air), dan Uis Pah (dewi pertiwi).
Akhirnya, lopo (rumah bulat) dan ume kbubu (lumbung bersama) juga menjadi lokus sakral. Bangunan tradisional dari kayu ampupu, gewang, atau kasuari serta beratap jerami itu bukan cuma artefak banal. Devosi gastronomis diselenggarakan di tempat tersebut karena di sanalah bahan pangan dirawat, disimpan, diolah, dan diawetkan. Orang-orang Timor memberi dimensi ilahiah pada bangunan itu melalui sebuah tiang yang dianggap sebagai referensi fisik sesembahan tertinggi mereka, Uis Neno (secara sederhana bisa diartikan ‘sang pencipta’, tuhan utama yang identik dengan dewa matahari di banyak agama kuno).
Ritual panen madu—yang merupakan komoditas penting Pulau Timor—tidak kalah kompleks. Ritual ini dipimpin seorang anatobe, penguasa hutan, yang menunaikan fungsinya dengan mengerahkan kekuatan alam. Masyarakat Mollo memberi derajat antropomorfis dengan menganggap lebah madu sebagai fetonai (secara harfiah berarti ‘puan agung’, gelar yang kerap disandangkan kepada para perempuan aristokrat Timor). Maka, seorang meo yang bertugas di atas pohon mengundang para fetonai dengan himne-himne rayuan. Penghormatan kepada sang putri dijalankan dalam sikap hening selama ritual berlangsung.
Sebagaimana musim tanam, panen madu tidak bisa dilakukan sepanjang tahun; hanya pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, tidak semua pohon bisa menjadi inang sarang madu. Cuma pohon dengan kriteria khusus, pokok-pokok tinggi yang bercabang banyak seperti randu dan beringin. Tetapi lebah tidak hanya bersarang di pohon. Para fetonai juga menghasilkan madu di batu. Setelah dipanen, madu harus dibagi secara adil. Sifat kikir diyakini akan menyebabkan gagal panen pada musim berikutnya.
Orang kedekut memang tidak cocok tinggal di Timor yang memiliki lingkungan fisik ekstrem. Secara sadar, orang-orang Timor menyebut diri mereka atoni pah meto (manusia bumi tandus). Masuk akal jika kebakhilan menjadi tabiat yang amat dibenci, sebab kelangsungan hidup komunitas bergantung pada kerja sama solid di antara anggota-anggotanya. Kemurahan hati terasa berguna ketika seseorang meminjamkan bibit atau bahan pangan kepada yang sedang berkekurangan.
Maka, memelihara keselarasan alam menjadi tanggung jawab tak terhindarkan. Elemen-elemen ekosistem seperti batu, tanah, air, dan pohon adalah material penting pada fitur-fitur upacara adat orang Mollo. Dalam peribahasa Mollo, unsur-unsur alam tersebut dipersonifikasi sebagai sistem yang bekerja bagaikan organisasi tubuh manusia. Selain menjadi sarang lebah, batu dipandang sebagai wahana identitas marga. Orang-orang Mollo menyebutnya fatukanaf (batu nama). Mereka juga menganggap batu sebagai persinggahan arwah sebelum bersemayam abadi ke hadirat Uis Neno di Gunung Mutis, aras paling kudus dalam kosmologi Mollo.

Dicky Senda meracik minuman bersama LSM Pikul
Aktivitas tambang Bukit Nausus—dan batu-batu besar lainnya—yang pernah dioperasikan di awal milenium kedua menuai murka masyarakat Mollo. Mereka meyakini Nausus sebagai batu besar yang memiliki kualitas maternal. Ia adalah almamater yang menyusui batu-batu di sekitarnya. Baik secara saintifik maupun pengetahuan tradisional orang-orang Mollo, batu-batu itu berperan sebagai tandon alami. Pertambangan batu tidak hanya akan mencemari air, tetapi juga akan melenyapkannya.
Perlawanan yang sama juga meledak ketika pemerintah mengokupasi tanah ulayat dan menjejalinya dengan program-program yang justru merusak keselarasan alam. Bagi masyarakat Timor, hutan adalah sumber makanan, padang gembala, dan pohon-pohon dijadikan material utama lopo dan ume kbubu. Singkatnya, kehilangan semua unit ekosistem tersebut akan bermuara pada problem ketersediaan makanan.
Perlakukan yang khas orang-orang Mollo terhadap makanan dipengaruhi situasi fisik alamnya yang ekstrem. Mereka memiliki siasat gastronomis yang unik sebagai upaya agar tidak kekurangan makanan di sepanjang tahun. Sejarah telah merekam trauma publik akibat bencana kelaparan yang pernah terjadi di Timor Tengah Selatan pada tahun 65 karena kemarau panjang. Malapetaka tersebut diperparah huru-hara politik yang tengah melanda di seluruh Indonesia. Strategi gastronomis mestinya berubah karena iklim juga telah berubah. Perubahan iklim mengacaukan almanak pertanian yang sudah lama tercatat sebagai bagian dari tradisi membaca musim.
Merestorasi kesadaran masyarakat Mollo untuk kembali ke pangan lokal merupakan langkah awal Dicky beserta proyek-proyek Komunitas Lakoat. Kujawas dalam menghadapi kekacauan iklim. Gastronomi ala Dicky mengawinkan metode tradisional dengan teknik modern yang diharapkan mampu mengatasi persoalan krisis pangan di masa depan. Ia mengampanyekan kearifan ragam pangan lokal, baik di majelis nasional maupun internasional, yang sudah dihancurkan politik berasisasi Rezim Orde Baru. Jagung, ubi, dan putak telah terbukti menjadi pahlawan yang mengurangi derita kelaparan 65 saat beras tidak hadir di atas meja makan orang-orang Mollo.
Memproyeksikan masa depan pangan dengan mengembalikannya kepada kebijaksanaan masa silam secara tak langsung telah meningkatkan status gastronomi menjadi gastrosofi. Itulah yang dikerjakan Dicky. Ia tidak hanya memperlakukan makanan sebagai asal-usul nutrisi. Ia juga mendudukkan kuliner beserta laku makan sebagai sumber intelektual dan moral. Dicky dan program-program Lakoat. Kujawas adalah resonansi dari deklarasi mantra kedaulatan pangan lokal yang pernah digaungkan pada tahun 2009 oleh persekutuan masyarakat adat Tiga Batu Tungku: Amanatun, Amanuban, dan Mollo. Menurut kosmogoni Mollo, Uis Neno menciptakan sepasang manusia pertama, Tae Neno dan Bifel, hidup dalam ekonomi agraria. Kini, Dicky Senda tengah memikul takdir leluhur mitisnya di kedua pundaknya.
*Royyan Julian adalah penulis sejumlah buku, bergiat di Sivitas Kotheka dan Universitas Madura, serta tinggal di Pamekasan.