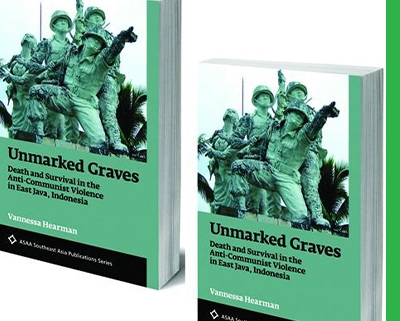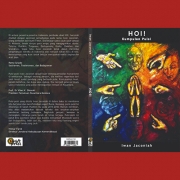Peran Militer dan Paramiliter dalam Penghilangan PKI di Jawa Timur

Oleh Imam Muhtarom
Judul buku: Unmarked Graves, Death and Survival in the Anti-Communist Violence in East Java, Indonesia
Penulis: Vannessa Hearman
Penerbit: Asian Studies Association of Australia bersama National University of Singapore Press
Tahun: 2018
Tebal Buku: xiv + 272 hlm
Buku ini menegaskan persoalan banyaknya korban setelah Gerakan 30 September1965 di Jawa Timur bukan konflik horizontal yang sifatnya spontan antara kelompok sosial (social group) satu terhadap kelompok sosial lainnya. Korban tersebut akibat konflik yang didesain sedemikian rupa oleh militer yang melibatkan organisasi massa NU terhadap pendukung PKI dan simpatisannya. Pembantaian oleh Ansor dari NU terhadap massa PKI setelah 30 September 1965 tidak saja karena pertentangan ideologi di antara keduanya dan provokasi massa atas nama ideologi sebelum 30 September 1965. Pembantaian itu terjadi oleh instruksi militer yang secara sistematis dan sengaja menghilangkan PKI dan pendukungnya di Jawa Timur. Sepanjang Bab 3 buku ini (hlm. 68-111) menjelaskan peran militer dengan menggunakan Ansor dan Banser dalam membasmi PKI beserta pendukung dan simpatisannya. Kemudian peran Banser dan Ansor dari NU di lapangan pada saat itu adalah eksekutor teknis dengan membantai pendukung dan simpatisan PKI. Daftar nama siapa saja yang menjadi bagian PKI berada di tangan militer dan juga dari NU. (hlm. 82, 84, 92) Pertemuan antara pimpinan NU dan jenderal dari Brawijaya setelah peristiwa 30 September 1965 membahas agenda penumpasan PKI beserta lembaga di bawah naungannya dengan segenap anggota dan simpatisannya. Dalam subbab “Planning and Carrying out the Violent Suppression of the PKI” di Bab 3 uraian tentang perencanaan itu dijelaskan dengan terang. (hlm. 75-82).
Usai peristiwa 30 September 1965, di Jawa Timur dukungan militer kepada Soekarno masih kuat. KKO dari Angkatan Laut dan juga dari kalangan Angkatan Udara di Jawa Timur merupakan pendukung kuat Soekarno. Divisi Angkatan Darat juga terbelah. Bahkan siang hari pada 1 Oktober 1965, militer Jawa Timur mendukung siaran radio yang dilakukan militer pimpinan Letkol Untung selaku komandan penculikan 30 September 1965. Ada beberapa penggantian jenderal di tubuh organisasi militer di Jatim hingga pada 1969. Mayjen Soemitro enggan melakukan operasi sapu bersih kala itu. Baru pada 1969 di bawah Mayor Jendral Muhamad Jasin asal Aceh militer Jawa Timur khususnya Angkatan Darat “bersih” dari unsur Soekarno dan Kiri. Pada 1969 Angkatan Darat di Jawa Timur siap melakukan pembasmian perlawanan sisa PKI di Blitar selatan.
Buku ini menggunakan kasus Kediri dan Bangil untuk menunjukkan data pembantaian pendukung dan simpatisan PKI. Dibandingkan dengan Bangil, Kediri merupakan wilayah penting adanya pembantaian tersebut. Dari data yang digali Vannesa Hearman adalah menggunakan data informan dari pihak NU maupun dari pihak PKI. Dari NU menggunakan pimpinan sementara dari PKI dari anggota atau Lembaga di bawah payung PKI yang masih hidup.
Pelarian Politik dan Munculnya Orde Baru
Menariknya buku ini, mengisahkan dengan lumayan lengkap mengenai proses dari pendukung PKI asal Blitar sejak lepas 1 Oktober 1965, pelariannya di kota-kota besar di Jakarta atau Surabaya. Lantaran ada kebijakan dari Jakarta ada operasi yang opresif di kota-kota, para anggota kiri ini harus keluar dari persembunyian dan bergabung di Blitar untuk membangun kembali basis PKI yang baru. Wilayah yang dicurigai sebagai markas PKI penghuninya didata ketat oleh pemerintah kota seperti di kawasan Bratang dan Ngagel di Surabaya. Ibarat sarang, tempat persembunyian itu telah dibongkar.
Adanya pembantaian bulan Oktober hingga Desember 1965 membuat pendukung dan simpatisan Kiri melarikan diri. Tujuan mereka Jakarta, Malang atau Surabaya. Mereka menghilangkan identitas lama dan mengganti identitas baru untuk menghilangkan jejak dengan menjadi pedagang kaki lima, pengemis, tetapi ada yang bekerja di sebuah bank milik asing. Ada yang bertahan secara berkelompok dengan mencari kawasan aman di daerah Ngagel, Bratang atau Gubeng di Surabaya. Mereka merasakan lebih aman di kota karena anonimitas identitas bisa dilakukan.
Tetapi pelarian dengan cara menyamar dan bersembunyi ini tidak bertahan lama. Rezim Orde Baru di bawah Soeharto mengendus pola ini. Kebijakan baru dikeluarkan sehingga aparat mengintai gang-gang di sekujur kota Surabaya maupun Jakarta. Di sinilah kemudian Sudisman, anggota politbiro PKI, ditangkap di sebuah gang sempit di Jakarta dan para tokoh-tokoh Kiri keluar dari sarang di kota-kota besar. Pilihannya kemudian jatuh kepada Blitar Selatan sebagai tempat pelarian sekaligus menyusun kekuatan kembali. Blitar Selatan dipilih lantaran secara geografis sulit dicapai lantaran bergunung-gunung kapur dan, yang terpenting, pada pemilu raya 1955 dan 1964 di Kabupaten Blitar, secara khusus Blitar Selatan PKI menang mutlak. Artinya, selain sulit untuk diserbu militer atau kelompok beragama, mereka pasti diterima baik oleh masyarakat.
Menariknya, dalam operasi Trisula pada 1969 yang dilakukan militer untuk memberangus PKI di Blitar Selatan tidak menggunakan label NU dan organisasi di bawah naungannya seperti pada Oktober hingga Desember 1965. Mereka menggunakan Hansip yang diambil kawasan Blitar utara Kali Brantas. Hansip (pertahanan sipil) ini merupakan aparat di tingkat desa yang bertugas untuk menjaga keamanan. Tiadanya NU dalam operasi Trisula ini menurut penulis buku ini sebagai pesan kepada semua pihak baik di dalam maupun di luar negeri bahwa rezim baru di bawah Soeharto ini tegas dan bisa menumpas pemberontak.
Faktanya, apa yang disebut Hansip itu adalah orang-orang Banser yang juga berperan aktif pada Oktober-November 1965. Hansip yang dikerahkan pada 1969 di Blitar Selatan sebagian besar berasal dari Banser. Militer meminta NU untuk menyediakan tenaga yang membantu operasi ini. Hanya saja, dalam pelaksanaannya mereka tidak berseragam Banser, melainkan mengenakan seragam Hansip. Justru para Banser berpakaian Hansip ini yang berada di garis depan dalam melaksanakan operasi. Para Banser tanpa pelatihan militer yang memadai diterjunkan di daerah sulit dan tidak tahu di mana musuh berada. NU menjadi kecewa karena peran mereka ditiadakan oleh pemerintah dan militer. (hlm. 152)
Yang Tersisa dari Operasi Trisula
Operasi Trisula merupakan operasi khas yang melekat pada Orde Baru dalam menghadapi pemberontak. Operasi ini kemudian diidentifikasi serupa dengan operasi-operasi lain semasa Orde Baru di Aceh dan Timor-Timur. Operasi ini tidak hanya menyasar para aktor, tetapi juga masyarakat umum yang lahir dan besar di sana. Operasi “bumi-hangus” semua orang yang ada dalam suatu wilayah menjadi kuncinya. Dalam kasus penumpasan PKI di Blitar Selatan, buku ini menjelaskan dengan rinci bagaimana warga yang buta huruf, miskin, hidup di tengah geografi yang sulit, diperlakukan dengan kejam. Hasil bumi maupun hewan hasil peternakan rakyat dimanfaatkan secara sepihak untuk operasi ini.
Setelah operasi Trisula sebagian besar wanita menjadi janda lantaran suami mereka terbunuh. Diperkirakan ada 2.000 jiwa yang melayang selama operasi Trisula. Mayat mereka dibuang di Gua Tikus, di kuburan massal, atau ditimbun tanah sekadarnya lantaran keluaga takut menguburnya dengan benar.
Janda-janda yang suaminya dibunuh tersebut diperlakukan tidak bermartabat, dimanfaatkan secara seksual, dan sepanjang hidup harus menyandang anggota masyarakat yang terstigma organisasi terlarang, yaitu PKI. Dalam perspektif Orde Baru, masyarakat Blitar Selatan ini harus diluruskan dengan cara mengenalkan pada Pancasila, UUD 1945, dan agama. Bahkan, tempat tinggal penduduk direlokasi di area baru di pinggir jalan utama, rumahnya berdekatan satu sama lain. Tujuannya, agar mudah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah dan militer.
Masalahnya, masyarakat sudah semenjak awal tersakiti dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Dibandingkan mengingat “jalan lurus” yang diberikan pemerintah, seperti pernyataan James Scott yang dikutip Vannesa Hearman perlu didengarkan “sekalipun pemberontakan gagal meraih citanya … sebuah memori akan resistensi dan keberanian telah tertanam untuk masa depan”. (hl 196)***
*Penulis adalah Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang.