Gerhana dan Otonomi Seni Rupa Indonesia
(Tanggapan untuk Aminudin TH Siregar, Hendro Wiyanto, Yuswantoro Adi dan Asmudjo J. Irianto)
Oleh: Chabib Duta Hapsoro
Empat tulisan sebelumnya telah mendiskusikan dan memperdebatkan “gerhana dalam seni rupa Indonesia”. Gerhana itu menghalangi produksi-diseminasi seni rupa Indonesia, perkembangan medan seni rupa Indonesia dan pembentukan historiografi seni rupa Indonesia. Tulisan ini menawarkan sebuah konsep atau cara pandang, yang melaluinya saya berharap kita bisa melihat masalah-masalah itu secara lebih jernih dan kritis.
Saya mengawali tulisan ini dengan menawarkan sebuah konsep “otonomi seni rupa Indonesia”. Saya terinspirasi oleh sebuah tulisan sosiolog Malaysia, Syed Hussein Alatas yang berjudul The Development of an Autonomous Social Science Tradition in Asia: Problems and Prospects (2002). Ia menyerukan urgensi otonomi ilmu sosial di Asia. Sebagai intelektual antikolonial dan dekolonial, Alatas menyerukan bahwa otonomi ilmu sosial di Asia diperlukan agar intelektual-intelektual ilmu sosial di kawasan ini dapat melihat dan memformulasikan permasalahan-permasalahan sosial di negara mereka sendiri secara independen, dan dengan demikian bisa menggunakan pendekatan apapun yang diperlukan, baik dari dalam maupun luar, secara jitu. Konteks dari ajakan ini adalah, selama ini intelektual di negara bekas terjajah dan berkembang masih amat bergantung kepada kacamata-kacamata luar untuk memformulasikan masalah-masalah lokal dan terlebih belum mampu menciptakan teori-teori sendiri untuk membaca permasalahan-permasalahan sosiokultural di negara mereka sendiri. Ini merupakan warisan kolonial, yakni produksi ilmu pengetahuan alam dan sosial di negara-negara jajahan berada di bawah kepentingan negeri-negeri penjajah.

Foto Syed Hussein Alatas
Maka otonomi seni rupa Indonesia menunjukkan bagaimana pelaku-pelaku-pelaku dan intelektual seni di dalamnya independen dalam mempermasalahkan situasi-situasi kebudayaan lokal yang khas secara jernih. Dengan melakukannya kita dapat memformulasikan kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang lebih riil dalam mengarusutamakan seni dan budaya di tengah masyarakat. Maka konsep otonomi seni rupa Indonesia ini sangat berbeda dengan konsep otonomi seni dalam jargon “seni untuk seni” dari seni rupa modern. Saya berharap setelah ini kedua konsep ini tidak dipertukarkan penerapannya
Kita bisa menggunakan konsep otonomi seni rupa Indonesia untuk membaca pernyataan Asmudjo. Dalam awal tulisannya ia menyangsikan bahwa sejarah seni rupa tidak dibutuhkan lagi oleh seniman muda. Saya pun berasumsi bahwa publik pun demikian. Sejak dulu, Asmudjo selalu terjebak bahwa jika sejarah seni rupa Barat berakhir, kita pun di Indonesia harus merasakan dampaknya. Asmudjo selalu merasa kita tidak punya alternatif untuk keluar dari situasi yang menghambat ini atau setidaknya mempertanyakannya. Bahwa kepercayaan pada faktor luar itu tidak bisa ditawar-tawar dan tidak akan bisa dicari solusinya. Untuk keluar dari situasi itu sebenarnya secara mudah kita bisa tidak mempercayainya dan mulai bekerja. Otonomi seni rupa Indonesia memerlukan produksi-produksi pengetahuan lokal yang dapat dibaca oleh seluruh pelaku seni rupa Indonesia dan publik. Produksi, pertukaran dan diseminasi pengetahuan tidak akan bisa terjadi jika kritik seni dan kajian seni mandek.
Mandeknya kritik seni rupa mencerminkan ketidakberpihakan produksi seni kepada publik. Ketidakmampuan medan seni rupa kontemporer dalam merawat keberlangsungan kritik seni menunjukkan bahwa medan seni rupa kita elitis. Ia hanya melayani sekumpulan pelaku-pelaku seni dengan privilese-privilese pengetahuan dan kekayaan ekonomi yang memadai. Karya-karya seni hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang-orang di lingkaran itu tanpa adanya kemauan untuk menyebarluaskan pengetahuannya kepada publik.
Kritik seni akademik yang berujung kepada kajian seni juga tak kalah penting. Kritik akademik dibutuhkan untuk menengarai sejumlah permasalahan-permasalahan yang layak menjadi objek kajian dan penelitian. Produk kritik akademik seharusnya dapat menelaah dan meneorisasikan konsep-konsep partikular seniman dalam karya seninya. Ini berguna untuk menguji sejauh mana karya seni dari seorang seniman menanggapi lingkungan masyarakatnya, karena seniman, sebagai intelegensia, adalah konsekuensi dari situasi sosial yang spesifik. Meneorisasikan pemikiran-pemikiran seniman dan cendekiawan seni di masa lalu pun penting untuk merumuskan bagaimana gagasan-gagasan Indonesia tentang seni rupa, yang sarat kelindan dengan identitas, representasi dan kekuasaan.
Kritik dan kajian seni rupa membutuhkan pula keberadaan literatur yang memadai berupa dokumentasi manuskrip dan karya seni. Riset dalam kritik dan kajian seni rupa adalah kerja membanding-bandingkan untuk menilai sejauh mana sebuah karya seni menunjukkan pencapaian-pencapaian baru. Maka, kegiatan riset yang melandasi kritik dan kajian seni adalah alasan yang mutlak untuk perawatan dan pelestarian arsip dan karya seni secara profesional.
Kesadaran akan otonomi juga berlaku terhadap medan seni rupa. Membaca tulisan Yuswantoro Adi kita akan berasumsi bahwa seni rupa kita baik-baik saja dan seniman tidak membutuhkan produksi pengetahuan seni rupa, selama karya mereka laku di pasar. Seniman bisa hidup berkecukupan dan bahagia karena ada patron, baik patron negara maupun kolektor. Memang betul patron dibutuhkan dalam sebuah medan seni rupa. Namun, dengan hanya mengandalkan patron, kita tidak bisa membicarakan otonomi seni rupa Indonesia. Hanya mengandalkan patron dapat membuat seniman terjebak pada bias-bias kepentingan patron yang mengusik nurani kesenimanan dan kemanusiaan.
Kita memang tidak sepatutnya mendikte kemauan dan sikap seniman, apakah ia kritis, netral, atau menjadi corong propaganda kekuasaan. Namun jika di Indonesia hanya ada tipe seniman kedua dan ketiga, berarti keadaan ini tidak sehat. Kita juga tidak bisa menuntut seniman untuk membaca produksi-produksi pengetahuan seni rupa. Namun, jika seluruh seniman tidak membaca, berarti ada yang tidak beres dalam seni rupa kita. Otonomi seni rupa Indonesia memerlukan tidak hanya keberagaman praktik artistik, melainkan juga ideologi dan pandangan. Keunikan dan kekhasan cara pandang seniman, yang dihasilkan dari pertukaran pengetahuan yang memadai, diperlukan oleh kesenian untuk mencerahkan publik.
Menanggapi Bang Aminudin TH Siregar (Ucok), saya sepakat dengan “historiografi penyadaran” karena ia sejalan konsep otonomi seni rupa Indonesia. Saya pun sepakat bahwa dalam proyek ini kita perlu membaca dan menganalisis arsip baik-baik.
Dengan kerangka historiografi penyadaran itu saya menawarkan kita untuk mulai membaca ulang seni lukis mooi indie, yakni dengan tegas menyebut seni lukis sebagai produk budaya orientalis. Memang mooi indie tidak masuk dalam kanon seni lukis orientalis macam lukisan-lukisan Delacroix maupun Gerome. Namun, ini tidak menghindarkan Mooi Indie sebagai produk budaya orientalis. Sebagai produk budaya orientalis, mooi indie hanya menggambarkan keindahan alam Indonesia kolonial, dengan mensenyapkan dan mengaburkan dampak-dampak buruk penjajajahan dan kapitalisme kolonial. Sebagai produk budaya orientalis, mooi indie juga hanya mengabadikan representasi kemegahan dan kejayaan masa lalu dengan kerap kali menggambarkan reruntuhan candi. Ini selaras dengan cara pandang orientalis yang merepresentasikan sang liyan sebagai entitas yang antik, eksotik dan tidak akan berubah.
Historiografi penyadaran juga termasuk saat membaca seni lukis mooi indie sebagai representasi institusi otoritas kolonial yang berurusan dengan orient atau yang terjajah (Said, 2003). Seni lukis mooi indie, yang visualisasinya stagnan namun terus populer sejak abad 19 hingga abad 20 menunjukkan tidak berkembangnya medan seni rupa Indonesia dalam periode kolonial. Seni lukis mooi indie terus dirawat kepopulerannya untuk memenuhi kebutuhan pasar turis-turis Eropa yang menghambat iklim kreasi seniman-seniman di Hindia Belanda saat ini. Hal ini sudah secara tegas disampaikan oleh S. Sudjojono dalam beberapa tulisannya. Beberapa sejarawan seni pun menyebut bahwa iklim kritik seni rupa di Hindia Belanda juga tidak menggembirakan. Manerisme mooi indie dan iklim kritik seni yang tidak berkembang adalah dampak dari tidak adanya kebijakan yang nyata dari pemerintah kolonial untuk mengembangkan seni rupa di Hindia Belanda. Ketidakpedulian pemerintah kolonial dengan perkembangan kesenian—dan juga sains modern—adalah wajar, karena mereka melihat Hindia Belanda hanya penting sebagai objek ekspansi kolonial. Seni lukis mooi indie pada akhirnya menjadi pelumas bagi kapitalisme kolonial untuk mengundang investasi pada turisme dan industri perkebunan di Hindia Belanda.
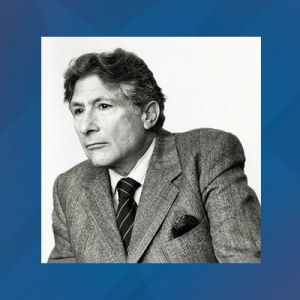
Foto Edward Said

Jan Daniel Beynon, Lansekap Jawa setelah Panen Padi (Landschap en Javanen na de rijstoogst), cat minyak di atas panel, 35,5 x 48,5 cm, 1873. Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam.(Public domain, via Wikimedia Commons)
Dengan tegas menyebut mooi indie sebagai produk budaya dan kebijakan seni yang orientalis, kita kemudian bisa menengarai warisan-warisan kolonial dan orientalis dalam seni rupa kita setelah Indonesia merdeka. Melalui kesadaran otonomi seni rupa Indonesia kita bisa terhindar dari penilaian-penilaian yang bias sosok, gender dan privilese. Kita bisa mulai menilai bahwa Soekarno, sebagai “saudara kandung seni rupa Indonesia”, ternyata terjebak pada ide orientalis melalui kegemarannya terhadap lukisan-lukisan mooi indie. Mungkin Soekarno dalam hati kecilnya selalu mendambakan abadinya alam pedesaan Indonesia yang gemah-ripah.
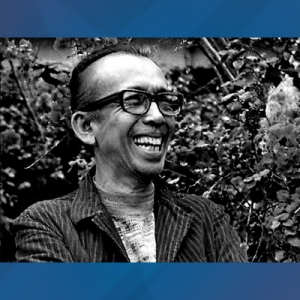
Foto Sudjojono
Kita juga bisa mencurigai ekses-ekses warisan orientalis itu pada karya-karya seni rupa Indonesia setelah merdeka. Bahwa dengan membekukan keindahan pedesaan Hindia Belanda adalah manifestasi seni yang tidak kritis kepada kekuasaan kolonial. Ini berlaku juga kepada lirisisme yang juga hanya menunjukkan keindahan visual dan netral dari ekspresi politis. Dan kita bisa membandingkan pula bahwa mooi indie yang menjadi arus utama pada masa kolonial ternyata sejajar dengan maraknya lirisisme dalam rezim otoriter Orde Baru. Kita bisa mulai meyakini bahwa watak kolonial dan orientalis ini ternyata memang diwarisi oleh rezim Orde Baru dengan mendayagunakan seni-seni yang netral. Maka saya juga sepakat dengan Hendro Wiyanto bahwa naif jika menyatakan ada jenis-jenis estetisme tertentu yang bukan menjadi cara berpolitik. Estetisme yg netral pada ujungnya hanya akan mendukung atau ditunggangi oleh ideologi yang menghegemoni.
Kita juga dapat menilai kecenderungan seniman yang mendayagunakan rupa-rupa tradisi dalam karya-karyanya dengan berpedoman kembali ke Timur. Kita bisa membuka kemungkinan bahwa pedoman seniman-seniman itu terjebak dalam cara pandang orientalis. Jika kita renungkan pedoman kembali ke Timur tidak ada pada masa prakolonial. Pada masa kolonialisme lah ajakan-ajakan kembali ke Timur mulai mendengung. Orientalisme lah yang membuat kita menjadi objek yang eksis berdasarkan sudut pandang Barat. Baratlah yang kemudian memaksakan prasangka mereka kepada kita, bahwa kita tidak benar-benar Timur dan seyogyanya kembali ke Timur.
Historiografi penyadaran dalam seni rupa Indonesia untuk “mengaktifkan kesadaran orang banyak” mustahil dilakukan jika kita mengabaikan relasi-relasi penindasan, penundukkan dan eksploitasi. Watak-watak orientalis pada masa kolonial masih perlu kita telaah dan waspadai untuk menggapai otonomi seni rupa Indonesia, karena ia merabunkan dan “meng-gerhana-kan” kita dari masalah-masalah sosiokultural di depan mata.
*Penulis seni rupa. Tinggal di Singapura.













