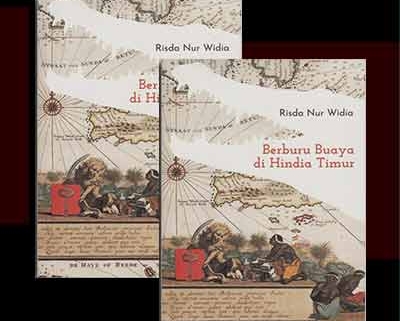Sejarah dan Ingatan Kolektif Tentang Kolonialisme

Oleh Dimas Indiana Senja
Judul: Berburu Buaya di Hindia Timur
Penulis: Risda Nur Widia
Penerbit: Pojok Cerpen
Cetakan: Pertama, Februari 2020
Tebal: vi + 154 Halaman
ISBN: 9786239062477
Penindasan dan kematian seolah tidak pernah selesai menggilas kehidupan masyarakat pribumi negeri ini. Penindasan dan kematian terus berulang dari waktu ke waktu
(1913, hal 102)
Sejarah dan sastra memanglah dua hal yang sangat dekat. Sudah sangat banyak karya sastra yang diciptakan dengan mengambil materi narasi sejarah. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam struktur dan substansi. Perbedaan itu—sebagaimana diutarakan Thomas Clark Pollock dalam The Nature of Literature, Its Relation to science: Language in Human Experience—ialah karena sejarah adalah referential symbolism, sementara sastra adalah evocative symbolism (Pollock, 1965: Passim). Dalam pada ini sejarah merujuk pada sesuatu di luar dirinya (referensi), sedangkan sastra merujuk pada dirinya sendiri (ekspresi). Sebagai bagian dari ilmu, sejarah senantiasa hidup di tengah dunia realitas, fungsinya adalah merekonstruksi realitas itu. Sedangkan sastra sebgai seni hidup dalam dunia imajinasi fungsinya merekonstruksikan imajinasi itu. Namun keduanya adalah symbolic form—istilah Cassirer—yang diciptakan manusia.
Tidak banyak sastrawan muda yang menggarap tema-tema sejarah kolonialisme dalam karyanya. Di antara yang tidak banyak itu ada nama baru yang cukup konsisten dan tekun dalam upaya menggali narasi sejarah dan menggubahnya dalam karya sastra. Adalah Risda Nur Widia, sastrawan muda Yogyakarta yang baru-baru ini menerbitkan sebuah buku berjudul “Berburu Buaya di Hindia Timur”. Buku ini berisi 6 cerita eksperimental dengan latar sejarah mengenai Hindia Timur secara kuat.
Buku ini mengupas ingatan panjang tentang hal-hal yang telah berlalu dan menyisakan cerita-cerita pilu di masyarakat. Cerita-cerita itu, yang kemungkinan besar telah berceceran dan berserakan, telah dirangkai dengan sangat baik oleh Risda. Cerita-cerita yang ia tulis bukan semata imajinasi, ada kerja riset panjang yang dilakukan, baik riset lapangan maupun penelusuran referensi tertulis, setidaknya itu terlihat dari beberapa cerita yang dibubuhi catatan kaki di dalamnya, seperti dalam judul “Para Bandit dan Hantu Ophaalbrug”, “Babad Goa Jlamprong”, “1913”, dan “Thomas Matulessy dalam Kenangan Benteng Victoria”. Catatan kaki yang tertera bukan semata penjelasan mengenai istilah asing, sebagaimana pembaca sering menemukan di buku prosa pada umumnya. Catatan kaki yang ditulis Risda adalah data, referensi dan keterangan lain yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Cerita-cerita Risda menjadi semacam esai, lantaran ada penjelasan lain yang disuguhkan. Barangkali kelengkapan data sejarah yang ditemukan Risda inilah yang membuat cerita-cerita dalam buku ini ditulis dengan halaman yang panjang-panjang.
Sejarah dan Ingatan Kolektif
Semua cerita yang ditulis Risda dalam buku ini memiliki sejarah dan ingatan kolektif yang kuat. Missal, dalam cerita “Para Bandit dan Hantu Ophaalbrug”, Risda mengisahkan perampokan yang dilakukan oleh sekelompok Bandit yang menjadi “hantu” bagi pelayaran kapal barang milik Dirk Van Duyen di sungai Marengan. Para Bandit itu adalah sekelompok penduduk lokal yang memiliki pengalaman dan inatan pahit, sehingga perampokan kepada rombongan yang dipimpin Kapten Roff itu juga terkandung muatan dendam yang memuncak. “Sukantang sebenarnya tidak pernah mau terlibat hal-hal semacam ini. Sebagai penduduk desa, ia malah terbilang lurus. Saat sebagian besar kawannya merampok di Sungai Mangeran, Sukantang memilih menjadi petani garam. Hal itu berubah seketika dalam empat hari terakhir. Sukantang melakukan penyergapan ini, sesungguhnya bukan karena garam. Ia ingin membalas dendam” (hal 10). Cerpen ini menyajikan fakta sejarah, tentang konflik yang dialami penduduk pribumi dengan kompeni. Hal serupa juga diterangkan dalam cerita “Babad Goa Jlamprang”, “1913”, dan “Thomas Matulessy dalam Kenangan Benteng Victoria”.
Cerita “Babad Goa Jlamprang” adalah sepenggal kisah tentang pelarian dan perjuangan Diponegoro dari kejaran pasukan Hindia-Belanda yang datang dari Keraton Jogja. Cerita itu terjadi pada 1828, digambarkan mengenai kekejaman kompeni dalam menyiksa penduduk Mojo, lantaran jejak pelarian Diponegoro tercium menuju ke arah selatan Jogja itu. Kisah heroic Pangeran Diponegoro dalam menghindar sekaligus menumpas pasukan kompeni diceritakan dengan detail dan menegangkan. Risda sangat terlihat memiliki referensi yang lengkap dalam mengisahkan muasal terbentuknya Gua Jlamprang ini. Ingatan kolektif masyarakat Mojo dihadirkan melalui dialog-dialog batin, “Memang, kami memercayai pertanda alam dengan segala hukum-hukumnya. Aku dan warga Desa Mojo meyakini kalau alam memiliki cara untuk mengingatkan warga bila dalam waktu dekat akan terjadi suatu peristiwa” (hal 84).
Sementara di dalam cerita “1913”, sebagaimana dikutip di awal, mengisahkan tentang masyarakat pribumi yang terus dipaksa menelan perlakuan tak manusiawi kebijakan pemerintah putih. “Takdir seperti digerakkan oleh tangan-tangan kotor bernama kolonialisme. Pendindasan dan kematian seolah tidak pernah selesai menggilas kehidupan masyarakat pribumi di negeri ini. Penindasan dan kematian terus berulang dari waktu ke waktu” (hal 102). Cerita ini mengisahkan perjuangan tiga sekawan Suwardi, Tjipto Mangoenkoesoemo, Ernest Douwes Dekker dalam menyuarakan perjuangan merebut kebebasan dan keadilan yang berakhir pada pengasingan.
Sedangkan di cerita “Thomas Matulessy dalam Kenangan Benteng Victoria”, Risda menceritakan mengenai perjuangan tokoh pahlawan Maluku, Thomas Matulessy. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama Risda mengisahkan kisah pilu penangkapan Thomas Matulessy dan para pahlawan lainnya. Risda memosisikan diri sebagai Benteng Victoria yang menjadi saksi kekejaman kompeni terhadap pribumi. Dengan sangat detail Risda mengisahkan hari-hari di Benteng yang penuh dengan upaya penumpasan para pemberontak. “Hari itu juga, dari tubuh betonku, Mayor Beetjes pergi menuju Saparua untuk mengamankan pemberontakkan yang dilakukan thomas Matulessy dan kawan-kawannya.” (hal 145).
Dalam ketiga cerita itu, sejarah dan ingatan kolektif mengenai kekejaman kompeni di masa kolonial sangat kuat dinarasikan oleh Risda. Melalui cerita-ceritanya, Risda menutupi “kekurangan” dari narasi sejarah yang selama ini ada. Sebab, sejauh ini narasi sejarah di dalam teks-teks mainstream kerap kali hanya terbatas pada periode waktu tertentu dan melupakan keterkaitan sebuah peristiwa yang terjadi secara bersamaan di tempat lain. Cerita-cerita yang dikemas dengan baik ini, memainkan logika peristiwa yang berkait yang selama ini diabaikan oleh teks sejarah. Membaca cerita dalam buku ini, pembaca menemukan imajinasi peristiwa lampau yang terasa dekat. Sejarah tidak lagi menjadi sesuatu yang asing dan jauh.
Rumah Kertas, 2020.
*Penulis adalah sastrawan, peneliti, dan dosen di IAIN Purwokerto