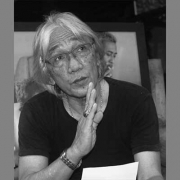PM Laksono: Sebuah Antitesa
Oleh: Riwanto Tirtosudarmo
Profesor Doktor Paschalis Maria Laksono MA, biasa dipanggil Pak Laksono adalah Orang Jawa yang dibesarkan di pusat kebudayaan Jawa, Yogyakarta, memilih antropologi sebagai jalan hidup, melanglang buana ke pusat-pusat studi Indonesia di Leiden dan Ithaca, untuk menemukan Jawa (dan Indonesia), dan kemudian kembali ke Yogyakarta, tetap sebagai Orang Jawa. Pada tanggal 4 April 2023 beliau resmi pensiun sebagai guru besar antropologi di FIB UGM setelah kurang lebih mengabdi di kampus itu. Pak Laksono pensiun pada saat yang tepat. Tepat ketika dunia akademia yang dicintainya sedang dalam krisis, krisis identitas, krisis makna dan krisis arah kemana mau menuju. Persoalannya sebagian sebagian besar orang tidak merasakan adanya krisis. Sebuah krisis yang sesungguhnya sangat berat sebagai akumulasi kegagalan negeri yang dicintainya membangun sistim pendidikan, mungkin selama setengah abad terakhir. Artinya bersamaan waktunya dengan masa pengabdian Pak Laksono sendiri.
Saya mengenal Pak Laksono dari dekat relatif belum lama, mungkin baru sekitar sepuluh tahunan terakhir. Tentu nama PM Laksono sudah saya dengar lama, karena kami sesungguhnya mendiami planet yang sama, planet akademia. Tapi memang planet ini besar dan semakin besar secara spasial yang membuat penghuninya bisa tidak saling kenal satu sama lain, kecuali dipertemukan oleh semacam “cosmic power”, dan saya merasa dipertemukan dengan Pak Laksono melalui “cosmic power” itu, mungkin karena kami sama-sama Orang Jawa, meskipun saya Jawa pesisiran, beliau Jawa “negoro gung”.
Sekedar sebagai anekdot tentang Pak Laksono berdasarkan ingatan saya, ada dua yang bisa saya ceritakan yang menggambarkan bagaimana sesungguhnya “keistimewaan” nama Pak Laksono di benak saya sebelum mengenalnya dari dekat. Keduanya mungkin terjadi sekitar tahun 2000-an. Yang pertama adalah dari cerita sahabat saya Hairus Salim. Bung Hairus bercerita bagaimana dia bertemu dengan sosok Ben Anderson, dirumah Pak Laksono. Tentu Bung Hairus tidak hanya cerita melihat Ben, tapi cerita lain malam itu yang terlalu panjang kalau saya ceritakan disini. Ilustrasi kedua adalah ketika suatu saat saya membaca catatan pinggir Goenawan Mohamad di majalah mingguan Tempo. Dalam catatan pinggir itu Goenawan Mohamad mengutip Pak Laksono yang menyinggung tentang sosok Semar dalam dunia pewayangan Jawa sebagai sesuatu yang “samar”. Dua anekdot itu cukup bagi saya untuk menilai “keistimewaan” Pak Laksono – yang terhubung dengan dua nama yang menurut saya besar, Ben dan GM; sebelum saya mengenalnya dari dekat.
Ketika saya mendengar Pak Laksono akan pidato saat pensiun, melalui WA, sebuah alat berkomunikasi yang bagi saya luar biasa, dan WA satu-satunya sosmed yang saya punya, saya bertanya nanti akan berpidato tentang apa? Jawabnya tipikal Pak Laksono, “belum tahu, mungkin saya akan cerita tentang diri saya saja, sesuatu yang paling dekat dengan saya”. Biasanya, pidato para profesor yang lain selalu bersifat akademis, memperlihatkan kelebihan atau penemuannya yang sangat dia banggakan dan sesuatu yang belum pernah dicapai orang lain. Tapi kemudian kita tahu isi pidato Pak Laksono memang bukan soal pencapaian akademik yang serba formal itu, melainkan tentang perjalanannya meniti karir di dunia akademik. Pengalaman perjalanan meniti karirnya sampai ke posisi paling tinggi di dunia kampus itu dibawakannya dengan dengan gaya bertutur orang pertama, aku atau saya, yang bagi saya adalah sebuah etnografi dari dunia dalam sang penulisnya, dunia dalam Orang Jawa yang “berantropologi”. .
Pidato itu tidak tangung-tanggung panjangnya, 40-an halaman satu spasi, dan judulnya mengejutkan “Siap Kejut” yang tidak akan kita mengerti makna dan maksudnya jika kita tidak membaca teks pidatonya itu. Tulisan ini adalah reaksi dan komentar saya yang agak spontan setelah membaca teks pidato, yang telah saya terima dari Pak Laksono sendiri sebelum dibacakan dalam sebuah acara di UGM tanggal 4 April 2023. Saat itu saya sudah merencanakan untuk hadir pada acara yang terbuka untuk umum itu. Pak Laksono dan Bu Laksono sudah menawari saya nanti nginap dirumahnya saja. Saya bayangkan acara itu pasti akan rame dan banyak teman dan sahabat Pak Laksono yang datang, pokoknya pasti akan gayeng, semacam klangenan yang sangat penting bagi orang yang sudah berusia diatas 70 tahun. Rupanya takdir menentukan lain, cucu saya yang kedua, Djati, demam tinggi dan harus diopname di RS, saya tidak mungkin meninggalkannya. Saya memang sekitar tiga minggu kemudian liwat Jogya, setelah cucu saya benar-benar sehat, dan menginap di rumahnya, dalam perjalanan saya ke Solo, karena diundang untuk ikut menari bersama sembilan maestro tari, untuk membuka acara Solo Menari pada tanggal 29 April 2023.
Dalam membaca teks pidatonya itu tentulah tidak dengan kepala kosong. Benak saya berisi ingatan-ingatan yang banyak bersifat pribadi berdasarkan pertemuan saya secara fisik maupun spiritual dengan Pak Laksono sejak saya merasa dekat sekitar sepuluh tahunan terakhir. Teks itu dengan sendirinya saya baca dalam konteksnya. Konteks ini adalah semacam frame atau lensa (lens) yang saya miliki tentang sosok Pak Laksono. Sekedar ilustrasi, saya pernah dua kali diminta oleh Pak Laksono untuk menguji dua disertasi doktor dari dua muridnya yang keduanya menulis tentang Papua. Saya juga pernah tinggal di Bulak Sumur karena diminta oleh Dekan FIB saat itu, sekarang bergelar profesor, Dr. Pujo Semedi, di program S2 Antropologi, saya mengajar matakuliah pilihan “migrasi, etnisitas dan politik” yang ternyata cukup banyak yang meminatinya. Interaksi langsung dan tidak langsung dengan Pak Laksono membuat ketika membaca teks pidatonya, secara otomatis saya tempatkan dengan konteks yang saya konstruksi kan berdasarkan frame dan lens saya tentang sosok Pak Laksono.
Ada sedikitnya tiga makna (meaning) atau pesan (message) penting yang bisa saya kemukakan setelah membaca teks pidato yang diberi judul singkat “Siap Kejut” itu.
Makna pertama yang saya tangkap adalah anti-struktur dan flash back. Pidato itu merupakan flash back dari 50 tahun berkecimpung di dunia civitas akademia UGM, khususnya di FIB dan lebih khusus lagi di Jurusan Antropologi. Anti-struktur karena dari cerita flash back yang sangat rinci itu kita bisa melihat bagaimana Pak Laksono meskipun berada dalam struktur (kedinasan) bergerak dalam pola anti-struktur karena dia melihat tempatnya bergerak adalah sebuah komunitas yang hubungan-hubungan yang ada bukan ditentukan oleh hal-hal yang bersifat kedinasan tetapi sesuatu yang lebih bersifat informal, cair, didasarkan cinta kasih, trust dan respect antara sesama dalam suasana yang kolegial, bukan hirarkis-struktural. Saya kutipkan disini kata-katanya di halaman 3: “Kemampuan mengendalikan diri agar tidak terjebak latah adalah inti agar hidup itu lumrah, biasa-biasa saja (ora nganeh-anehi) tetap dalam relasi sosial (silaturahmi) komunitas kita. Untuk inilah antropologi ada”. Meskipun ceritanya adalah sebuah flash back tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, namun membacanya kita merasakan ada pesan untuk masa yang akan datang. Bisa saya tambahkan disi bahwa dalam makna pertama ini juga bisa dikatakan bahwa Pak Laksono sejatinya anti kemapanan (anti establishmen), dan anti kemandegan.
Makna kedua yang saya tangkap adalah bahwa Pak Laksono memaknai antropologi, atau ilmu antropologi, sebagai ilmu yang eklektik, reflektif sekaligus holistik. Eklektik karena antropologi selalu bersentuhan hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, ekonomi, politik, etik sosial; dan kesemuanya itu harus dikembalikan dalam diri si antropolog secara reflektif. Sementara bagi Pak Laksono, antropologi juga bersifat holistik, menyatunya subyek dan obyek, seperti dikatakannya di halaman 5: Jadi kerja antropologi itu adalah menautkan gagasan atau imajinasi hidup berkomunikasi kita sendiri dengan fakta etnografi dari liyan kita sehingga pengertian dan identitas baru tentang situasi diri (kemanusiaan) kita dapat terperikan.
Makna ketiga adalah tafsir antropologis Pak Laksono tentang hidup dan kehidupan yang pada dasarnya penuh dengan kontradiksi dan ambiguitas. Dan disinilah judul singkat pidatonya, “Siap Kejut” memperoleh maknanya, yaitu sebuah sikap atau cara pandang, semacam world view, yang diambil sebagai posisi-nya (positioning) selaku seorang antropolog. Sikap ini juga secara tersirat menunjukkan perspektif teoretik yang dipilihnya, dan selama ini telah ditularkan ke murid-muridnya, koleganya maupun dalam praksis antropologi-nya di masyarakat. “Siap Kejut” merepresentasikan keyakinannya bahwa yang dibutuhkan dalam menghadapi hidup yang penuh perubahan, ambiguitas dan disana-sini mengesankan adanya kontradiksi; tidak lain adalah adalah kerendahhatian (humility) dan kejujuran (honestly). Saya kutipkan refleksinya tentang hal ini, dari halaman 6: Mungkin sekali saya telah menjadi pengagum keanehan. Mohon maaf, bila wacana saya pada Bapak, Ibu dan hadirin semua telah terlalu tajam dan kurang tenggang-rasa. Anggap saja kalau saya sebenarnya terlalu percaya, bahwa retorika polos serta biasa-biasa tanpa basa-basi itu dapat membebaskan kita dari jebakan moral hipokrit dan oportunistik.
Secara keseluruhan pidato pamitan sebagai guru besar antropologi UGM ini mencerminkan kepribadian, sudut pandangnya sebagai akademisi dan posisinya sebagai intelektual yang memilih terlibat dalam upayanya untuk berperan dalam perubahan masyarakatnya. Judulnya “Siap Kejut”, singkat tapi padat makna yang bisa dianggap sebagai warta terakhir yang ingin disampaikan sebelum turun dari kursi resminya di akademia. Seperti saya katakan dimuka PM Laksono pamit dari kampus UGM dalam waktu yang tepat. Juga, seperti telah saya kemukakan dimuka, PM Laksono pada dasarnya seorang yang anti struktur, anti kemapanan dan anti kemandegan dan menyadari posisinya yang berada di pinggiran dari arus utama struktur yang baginya tidak selalu memuaskan minat pribadi maupun kecenderungan akademisnya. Saya mau tegaskan disini tentang posisinya yang berada di pinggiran (in the margin) yang membuatnya sadar diri, empan papan, dan disinilah sekaligus berpilin antara marginalitas dan kejawaannya.
“Siap Kejut” oleh karena itu sesungguhnya sebuah “warning,” bagi koleganya yang masih berada di struktur kedinasan resmi maupun kaum intelektual di masyarakat, akan berbagai jebakan yang muncul seiring dengan perubahan yang penuh ambiguitas dan kontradiksi itu. Bagi saya Profesor Doktor PM Laksono secara keseluruhan hidupnya, pribadinya dan posisinya sebagai akademisi, adalah sebuah anti-tesa. Sebagai anti-tesa dari suara yang terdengar gemuruh dari arus utama (main stream) tapi sesungguhnya rapuh. Sebagai suara yang terdengar lirih di pinggiran namun sesungguhnya penuh nalar yang tidak hanya dilandasi oleh lingkungan kecilnya dalam kebudayaan Jawa namun juga perjalanan akademik yang diperolehnya di pusat-pusat ilmu pengetahuan: Yogyakarta, Jakarta, Leiden dan Ithaca, sebuah jejak langkah yang sesungguhnya sulit tertandingi oleh akademisi lain di negeri ini. Secara rinci dan menarik perjalanannya yang kaya itu dapat kita baca dari teks pidato perpisahan-nya itu. Dalam teks itu kita bisa melihat sebuah refleksi pribadi yang penuh-nilai dan makna yang secara tersirat ingin dikemukakannya. Dalam teks itu kita dibawa oleh Pak Laksono menemui orang-orang yang telah ikut mempengaruhi karirnya sebagai seorang akademisi, lembaga-lembaga yang menjadi rumahnya; semua itu dikisahkan dengan penuh afeksi dan rasa cinta.
Saya ingin mengakhiri ocehan saya ini dengan menceritakan sebuah pengalaman bersama Pak Laksono, di sebuah hotel bintang lima di Yogyakarta. Acaranya berjudul Dialog Papua Damai, sebuah seri dialog yang dipimpin oleh almarhum Dr. Muridan S. Widjojo, dan seingat saya mungkin ini dialog terakhir sebelum wafatnya. Saat itu Pak Laksono diundang sebagai narasumber dan saya sebagai peserta biasa. Pertemuan dialog Papua itu selalu menghadirkan pejabat-resmi selain para akademisi dan aktifis yang peduli dengan masalah Papua yang kita tahu sampai hari belum usai dan menjadi api dalam sekam di negeri ini. Dalam sebuah sesi Pak Laksono mengusulkan bahwa sangat penting bahasa ibu untuk diajarkan di sekolah-sekolah di Papua karena bahasa ibu adalah bagian yang sangat vital dan merupakan sesuatu yang bersifat inti untuk mempertahankan kebudayaan Papua.
Di meja panelis di depan, seorang pejabat dari Departemen Luar Negeri, menjawab apa yang diusulkan oleh Pak Laksono sambil tertawa, dan berkata “masa orang Papua mau dibawa kembali ke zaman batu”. Mendengar jawaban pejabat Deplu itu saya tidak bisa menahan emosi saya. Langsung saya mengangkat tangan dan mengatakan bahwa sebagai pejabat dia tidak memahami Papua, ucapannya tidak saja mencerminkan rendahnya pengetahuan tapi juga tidak ada empati sama sekali dengan Orang Papua. Mungkin seluruh hadirin di ruangan besar hotel mewah itu terkejut dengan kata-kata saya yang tidak mampu menahan kemarahan itu. Tapi yang membuat saya kemudian merasa lega karena seorang ibu Papua yang duduk dibelakang saya mengucapkan terimakasih karena saya dikatakannya sebagai telah menyuarakan suara Orang Papua. Sementara itu seorang bapak Papua di sebelah saya yang ternyata tidak lain adalah Pater Neles Tebay (almarhum, bersama Muridan memimpin Dialog Papua Damai) menyalami dan menjabat erat tangan saya.
Kalau saya ingat peristiwa itu, meskipun kelihatannya trivial, jangan-jangan itulah pandangan para pejabat kita tentang Papua, dan dari pandangan seperti itulah kemudian lahir kebijakan-kebijakan yang pada dasarnya tidak didasari oleh pengetahuan tentang Papua dan lebih dari itu tidak dilandasi oleh adanya rasa empati terhadap Orang papua.
Itulah Pak Laksono yang sedikit saya tahu, harus saya akui ada banyak hal yang saya tidak ketahui, dan saya kira setiap dari kita yang mengenal beliau memiliki kenangan dan penilaiannya masing-masing.
Lido, Sorong 21 Mei 2023.
*Riwanto Tirtosudarmo adalah peneliti.