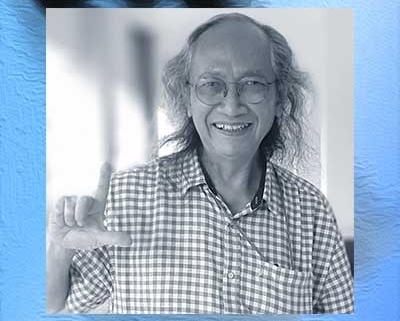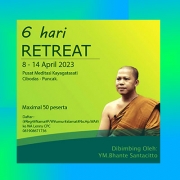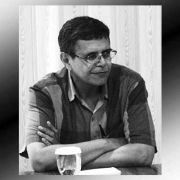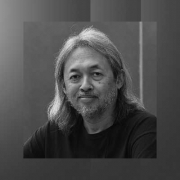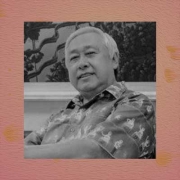Pemahaman Seni
Oleh Prof. Dr. Mudji Sutrisno, SJ*
Pemahaman seni itu bergantung pada sikap dan apresiasi orang terhadap karya seni atau seni “as such” sebagaimana yang ada. Perubahan/transformasi mendalam esensi seni (atau kontekstualisasinya) ditentukan oleh penyikapan orang pada “penempatan baru”; konteks baru karya seni, misalnya: dari ranah cipta studio lalu dipindah ke museum.
Disinilah letak posisi ‘konteks’ (atau bingkai konteks) sebuah karya seni. Contoh ekstrim sajak Sitor tentang ‘lebaran’ dalam kalimat “bulan di atas kuburan” bila dilepas dari konteks ‘lebaran’ akan berubah analoginya menjadi sekedar “bulan di atas kuburan” …, (inilah de-kontekstualisasi puisi atau karya seni (sastra)).
Jadi kontekstualisasi adalah bingkai dimana karya seni itu diproses kreatifkan sehingga lahirlah ia dalam “konteksnya” (misalnya: ruang = ‘kuburan’ dan waktu = purnama lebaran atau saat seniman menuliskan dan menghasilkan karya itu). Sementara, de-kontekstualisasi adalah upaya melepas bingkai dimana dan darimana serta saat mana karya seni itu dicipta! Inilah problem awal motto seni untuk seni, mungkinkah? Atau yang riil seni itu kontekstual?
Kontekstualisasi dan de-kontekstualisasi menunjukkan pokok penting, yaitu: karya seni tidak bisa dilepas dari konteksnya tanpa merubah essensinya (it’s nature). Bedanya adalah: apakah penciptaannya ‘diheningi’ atau di-kontemplasikan atau tidak! Penentunya: adakah kontemplasi estetis dalam penciptaan karya seni? (umumnya dipahami (masih debat) karya-karya seni tradisional tidak melalui kontemplasi estetis, maka sering disebut ‘traditional works’ dan belum merupakan ‘artworks’). Tetapi subyek pengapresiasi seni yang tidak kontemplatif menurut makna kontemplasi religius (the aesthetic subject is not contemplative in a religious way) seumumnya. Di Eropa, perspektif estetis bersamaan dengan ‘pertimbangan krisis (rasional) estetika’, yang berkaitan erat dengan soal: subjektivitas dan obyektivitas karya seni. Maka, perspektif estetis mensyaratkan dibuatnya ‘jarak’ untuk menimbang-nimbang karya seni. Di sini diandaikan diperlukan untuk mencipta ruang hening sendiri dengan mata tetap ‘kritis’ untuk apresiasi/penilaian estetika.
Ketika kita masuk museum ‘Budha’ lalu saat sedang apresiasi estetis datang serombongan tamu budhis dari Jepang lalu menyanyikan mantra dan memberi ‘derma’ serta persembahan di patung Budha dengan serentak ‘museum’ sekejap berubah menjadi kuil. Dengan perkataan lain, ‘yang estetis lalu menjadi religius, lantaran lantunan kidung doa’. Ada dua mata pandang atau sudut pandang, yang pertama: dengan berjarak (estetis) dan yang kedua: mata terlibat (ikut partisipasi: ritualis religius). Semisal: Seni india yang berbasis yoga.
Indian art is , a yoga, in other words, a way of reunification yoga coming from the root “Yuj” meaning to yoke, to join of the individual with the absolute. (Chantal Maillard, “What is meant by ‘art in India-Western Misunderstanding”, in Ken-ichi Sasaki (ed.), Asian Aesthetics, National Univ. of Singapore 2010, p.188 etc).
Di sini, karya (seni) menjadi ekspresi energi-energi dasar dimana penonton, peserta terbuka dan menyelaraskannya. Lewat pertunjukaan dramatis, diharapkan terjadi proses transformasi rasa/emosi-emosi bisa ke dalam rasa (atau emosi estetis) melalui kemampuan akting aktor masuk ke kesatuan batin/mendalam melalui proses universalisasi rasa-rasa (yang awalnya subyektif menjadi rasa bersama). Maka si pelukis ‘lotus’ tak hanya fisik menggambar bunga kamboja (lotus sebagi bunga) tetapi memuat ‘ruh’, taksu ke dalamnya.
Dalam Hindu, ada personifikasi daya kuasa kehidupan yaitu KALI. Apa itu?
“KALI” is the great dark goddess the personification, par exellence of “shakti”: Shiva’s power essence. Shiva’s power essence represented majority in white, but KALI is “the black goddess” ̴ as all colours fade into black, so all form Vanish in Shiva the great destroyer.
Jadi dalam kosmologi siklus Hindu , di satu sisi ‘Shiva’ memparipurnakan lingkaran putar hidup/dunia dengan menghancurkan total kosmos, namun pada saat yang sama, Shiva meretas “ignorance” (avidya) agar setelah siklus-siklus berikut menjadi ‘Vidya’.
Both things: world and ignorance are to Hinduism, a result of the same process. “Shiva (she)” is represented wearing a drindle composed of hands and forearms, and covered with hair. Her nakedness is reality it self, her hair is the veil of illusion that covers it. Her girdle consists the severed heads of her enemies symbolizing the action-karma-that perpetuates existence.
KALI absorbs ‘kala’ (time) and causes the destruction of phenomenal illusion, reintegrating the forms into her unity. “yantra” = diagramatic, drawing = menggambarkan pesona, simbol dari Siva dengan gambar Shri (Shri Yantra: 9 triangles = 4 males and 5 females – are enturned; 8 lotus; 16 senjata di tangan; semuanya melukiskan 5 unsur penyusun kosmos: tanah, air, udara, api dan eter, dan melukiskan seluruh edaran kosmos.
Begitu juga saat saya membawa teman untuk menghadiri ritual paskah, mulai dari jamuan basuh kaki para murid Yesus sebagai ungkapan melayani dalam kerendahan hati (membasuh kaki yang dilakukan hamba sahaya saat kaki dibersihkan dari debu-debu yang melekat setelah perjalanan dan disiap bersihkan untuk jamuan). Pembasuhan kaki oleh sang guru sebagai contoh melayani dengan kasih iklas, rendah hati merupakan persiapan “bersih kaki” dan bersih hati sebagai disposi batin untuk siap ikut terlibat dalam perjamuan perpisahan Yesus dengan murid-muridNya, dimana perjamuan ini menjadi “ekaristi” perayaan syukur pada Allah atas hidup dan pemeliharaanNya sampai kini. Dalam perjamuan ekaristi inilah ditinggalkan warisan pengenangan akan penebusan karya kasih Allah dalam Yesus yang memecahkan roti dan memberikan hidupnya bagi penyelamatan manusia dengan kasih tuntas mati disalib demi kita.
Pada teman mesti dijelaskan perjamuan ekaristi dengan pembasuhan kaki itu dirayakan dalam liturgi Kamis Putih. Lalu pengenangan sengsara dan jalan salib sampai penyaliban Yesus dikenang di hari Jumat Suci, didalamnya seni tableau, seperti Oberam Mergau atau dramatisasi Passio (kisah sengsara Yesus dipentaskan dalam suasana ritual religius).
Dari paparan sebelumnya, bisa ditarik benang merah. Pertama, dengan metode berpikir dikotomi atau ‘biner’, maka penghayatan ranah pengalaman merupakan induksi menghayati hidup dari laku hidup didalamnya dengan mengalaminya. Misalnya ‘live in’ untuk nyantrik, belajar sebagai siswa ke guru seni dengan ‘mengabdi dan melakukan’ apa yang guru minta untuk saya lakukan. Biasanya seorang calon dalang wayang kulit, setelah pengetahuan dan pemahaman mengenai (baca: tentang) pedalangan atau menjadi dalang, sudah ditimba dari Institut Seni pedalangan rampung, maka si calon dalang dianjurkan untuk berguru mendalang dengan cara “menjadi cantrik atau murid” ke dalang, untuk mengalami proses pemuridan itu bagaimana menjalani tugas mendalang dalam praxis, dalam laku. Inilah induksi yang merupakan konteks dari teks pemahaman tentang mendalang.
Sebagai teks, yang merupakan “teori”, rangkuman rasional pengalaman belajar mendalang, itu selalu merupakan pengetahuan, atau teori mengenai mendalang. Kedua, teori lalu berisi hal mendalang sebagai teks, how mendalang? Sebagai pengalaman mendalang itu kontekstualisasi teori ke praktek dengan mendalang itu sendiri, yang dihayati dan dialami intens biasanya didampingi oleh Ki dalang yang dihambai atau dimana ia menjadi cantrik atau murid dalam mendalang.
****
*Prof. Dr. Mudji Sutrisno, SJ. Budayawan.