Foklor Desa Golan-Mirah Ponorogo, Konflik Kepercayaan Dan Solusi Centhini
Oleh Frengki Nur Fariya Pratama
1
Golan-Mirah identik dengan kisah percintaan yang begitu masyhur di masyarakat Ponorogo. Kisah itu melibatkan dua sosok bernama Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah. Foklor ini bercerita mengenai kegagalan persuntingan Joko Lancur anak Ki Honggolono dengan Dewi Amirah anak dari Ki Ageng Mirah. Lantaran marah lalu Ki Honggolono mengucapkan sumpah : 1. Warga Desa Golan tidak boleh menikah dengan warga Mirah 2. Segala jenis barang dari Desa Golan seperti kayu, batu, air, dan lainnya, tidak boleh dibawa ke Desa Mirah, dan sebaliknya 3. Segala jenis barang dari kedua Desa Golan dan Mirah tidak dapat dijadikan satu, 4 Warga Desa Golan tidak boleh membuat atap rumah berbahan jerami, dan 5.Warga Desa Mirah tidak boleh menanam dan membuat benda apa pun berbahan kedelai
Foklor ini menciptakan pranata yang kokoh di masyarakat sampai sekarang. Kelima larangan tersebut sampai kini masih dipatuhi oleh masyarakat kedua desa. Sapata yang keluar dari mulut Ki Honggolono menjadi angger-angger yang sangat ditaati dan di wanti-wanti dampaknya oleh warga kedua desa. Kedua Desa itu seakan tersekat dinding tebal bernama sapata/pantangan.
Mengesampingkan berbagai pantangan yang begitu sering dibahas, saya ingin menganalisis kemungkinan motif seperti apa yang melatarbelakangi sapata tragedi percintaan Golan-Mirah di atas. Analisis ini bukan bermaksud ingin meruntuhkan foklor yang menjadi bagian local genius masyarakat Ponorogo, namun sekedar mencari benang merah kemunculan cerita melalui penafsiran hermeneutik. Serta menganalisa kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi jika kewaspadaan luput dari masyarakat.
Saya mulai dari catatan J. Knebel. J.Knebel dalam bukunya Over de Plaatsen van de hogste vereering (poenden) en eenige andere bijzonderheden in de afdeeling Panaraga, mengatakan bahwa di desa Golan terdapat kuburan Kyai Ageng Golan yang pada hari Jum’at Pon digunakan sebagai sarana nyadran bagi orang yang ingin segera sembuh dari penyakit (1909: 25). Catatan pada buku berbahasa Belanda ini membuktikan adanya perhatian khusus dari Kolonial terhadap punden-punden yang berada di daerah jajahannya. Begitu pula di Panaraga (Ponorogo) terkhusus desa Golan, yang masuk dalam catatan etnografi J. Knebel ini.
Kyai Ageng Golan mungkin serupa dengan Ki Honggolono yang dalam tradisi lisan masyarakat Ponorogo dinilai sebagai sosok warok yang memiliki ilmu linuwih, yang digambarkan menganut kepercayaan lama, kadang kala disebut wong budha (mungkin merujuk pada kepercayaan Hindu-Budha). Sedangkan Ki Ageng Mirah merupakan sosok Kyai yang taat menjalankan dan menyebarkan ajaran agama Islam, yang menurut cerita adalah pendamping dari Bathara Katong menyiarkan agama Islam di wilayah Ponorogo.
Sebab-musabab penolakan rencana pernikahan kedua anak mereka inipun nampak lebih ditekankan karena perbedaan keyakinan Hindu/Buddha – Islam dari kedua sosok tersebut. Narasi latar perbedaan kepercayaan Hindu/Buddha-Islam yang menjadi sebab gagalnya persuntingan ini menurut saya penting. Dampak terburuk seperti apa yang akan mucul bila dilanggar? Hal ini yang penting untuk diperbincangkan lebih mendalam.
Sebelum lebih jauh, tradisi lisan kisah percintaan Golan-Mirah jika distrukturasi terdiri dari Kondisi + Pantangan + Akibat Negatif dalam struktur ceritanya. Struktur ini begitu diyakini oleh masyarakat. Bahkan tradisi lisan lingkup kecil yang diyakini oleh lingkup masyarakat yang terikat ruang kewilayahan (hanya warga Golan dan Mirah) ini lebih kuat lagi diyakini dengan adanya simbol pertemuan sungai dari masing-masing desa yang airnya tak bisa menyatu. Hal ini menjadi parameter kukuhnya kepercayaan masyarakat terhadap tradisi lisan yang tersebar.
2
Dorson (Sukatman, 2011: hal 4) berpendapat tradisi lisan bersinggungan dengan 4 dimensi. Pertama dimensi kelisanan sebagai cara penyebarannya. Kedua dimensi kebahasaan sebagai media transfer ide atau informasi. Ketiga dimensi kesusastraan sebagai bentuk dari kisah yang dituturkan dan disebarkan. Terakhir adalah dimensi nilai budaya yang mendarah daging, mewujud pranata yang dipercaya masyarakat.
Dimensi nilai budaya ini banyak sekali melahirkan praktik-praktik kebudayaan berbentuk aturan, kesenian dan berbagai falsafah hidup, yang jika bernilai positif akan membangun kemanusiaan. Namun jika interpretasi masyarakat cenderung negatif malah akan meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan, bahkan memupuk egoisme kultural dari masing-masing kelompok masyarakat. Seperti tumbuhnya paradigma kekolotan menerjemahkan pemahaman agama.
Dalam konteks – kisah Golan-Mirah pertanyaannya: Bagaimana jika stigma rasial yang terbalut pemahaman letterlijk paradigma agama yang kemudian lebih menonjol menyeruak kepermukaan?
Saya melihat foklor Golan-Mirah yang tertanam dimasyaraat Ponorogo titik fokus hanya pada latar historis heroisme Ki Ageng Mirah sebagai penyebar agama Islam. Stigma rasial seperti ini menurut saya muncul akibat adanya cara pandang pemahaman agama yang tertutup. Fanatisme keagamaan demikian membutakan cara pandang, mengesampingkan pandangan kultural lainnya.
Marilah kita lihat riwayat siapa Ki Ageng Mirah ini . Ki Ageng Mirah dalam kepercayaan masyarakat Ponorogo dianggap sebagai tokoh historis yang membantu Raden Bathara Katong menyebarkan Islam di Ponorogo (sekitar abad ke-15 Masehi. Saya berhipotesis kemunculan foklor Golan-Mirah ini secara historis dan sinkronis, sezaman dengan periode saat Bathara Katong dan Ki Ageng Mirah menyebarkan Islam di Ponorogo. Secara asumtif kisah foklor kejadian gagalnya persuntingan Joko Lancur dan Dewi Amirah maka muncul pada masa maraknya Islamisasi di Ponorogo.
Di sini kita melihat adanya polarisasi dua kepercayaan antara Hindu-Buddha dan Islam. Beberapa foklor lain di Ponorogo saya lihat mengindikasikan adanya faktta penyebaran Islam secara masif, sehingga menggeser kepercayaan lama di Ponorogo. Foklor-foklor ini di antaranyya juga menampilkan kisah mengenai adanya resistensi di wilayah Ponorogo terhadap penyebaran Islam yang masiif itu . Asumsi resistensi itu dapat diamati melalui foklor mengenai pertempuran antara Ki Ageng Kutu dengan Raden Bathara Katong.
Foklor ini mengisahkan kisah peperangan sengit antara Ki Ageng Kutu dengan Raden Bathara Katong. Entah kebetulan atau tidak—bila kita amati strukturcerita, foklor ini memiliki kemiripan dengan kisah Ki Honggolono dan Ki Ageng Mirah. Keduanya sama-sama melibatkan sosok yang berbeda kepercayaan. Selain penaklukan dan percintaan, asumsi lain yang muncul seolah-olah kedua cerita menunjukkan motif yaitu konflik kepercayaan di masa silam. Dengan memanfaatkan cerita yang mungkin diciptakan, melalui proses penuturan berulang (repretitive style) itu digunakan sebagai pengingat dan pertahanan sebuah kepentingan tertentu di masyarakat (ibid: hal 8). Kepentingan itu adalah strategi suksesi syiar agama Islam di Ponorogo.
3
Yang menarik saya amati ada kisah lain yang berusaha menjadi wacana solutif dari konflik Golan-Mirah tersebut. Yaitu kisah sosok Angganala dalam Serat Centhini Jilid VIIdalam sesi l pengembaraan Seh Amongraga di Telaga Ngebel Ponorogo. Serat Centhini merupakan manuskrip Jawa yang selesai ditulis tahun 1814 M (1742 Jawa) atas prakarsa KGPAA Hamengkunagara III (Sunan Pakubuwana V) dibantu oleh R.Ng. Ranggasutrasna, R. T. Sastranagara dan R.Ng. Sastradipura serta dibantu pula Pangeran Junggut Mandurareja, Ulama Besar Ponorogo Kiai Kasan Besari dan Kiai Mohammad Minhad (Margana, 2004: 216). Teks ini dapat dijadikan narasi penengah dari keberadaan narasi yang berkembang.
Dalam Serat Centhini sosok Angganala digambarkan sebagai penduduk dusun Saba, asli penduduk Ngebel yang memeluk kepercayaan lama. Angganala diceritakan sebagai sosok penduduk asli (setempat) yang menemani pengembaraan Seh Amongraga beserta kedua abdinya Jamal-Jamil selama berada di Ngebel. Selama di Ngebel, mereka melakukan pengembaraan spiritual mulai dari Bale Batur, Sumber Bethara, Sumber Padusan, Sumber Upas,Telaga Ngebel dan Celangap warih (saluran irigasi zaman Belanda) yang secara rinci digambarkan.
Di salah satu babak, diceritakan terjadi gelegar petir yang mengagetkan. Timbullah debat atas nama kepercayaan antara Jamal-Jamil dan Angganala. Angganala warga asli dusun Saba berucap mantra: “hong ilahèng, hong hong jati wênang Hyang Astuti”. Jamal-Jamil sembari tertawa mengejek, mendebat ucapan Angganala “bagaimana bisa petir ditangkal dengan ucapan hong?”
Angganala menjelaskan, bahwa mantra hong sudah menjadi piranti (sarana) untuk menanggulangi peringatan Hyang melalui pertanda yang terjadi di gunung ini. Seh Amongraga pun melerai berdebatan tersebut dengan ucapan “memang begitulah adatnya, tak bisa memaksakan lain cara, kecuali orang-orang yang sudah menyatu dengan Hyang pribadi dan luhur budinya”.
Kita bisa menganalisa , alusi sosok Angganala dalam teks Serat Centhini ini adalah kisah Ki Honggonolo yang berada di Desa Golan. Apalagi konteks yang diceritakan berada di wilayah Ponorogo dan dalam Centhini itu terlibat pula Kyai Kasan Besari sosok ulama besar Ponorogo. Saya menduga, mungkin dengan sengaja sosok Ki Honggolono di-pleset-kan dengan nama Angganala.
Melihat lingkup besar teks Serat Centhini yang lebih pada ejawantah kepercayaan Islam. Sosok Angganala dimunculkan menganut kepercayaan berbeda, mungkin Pujangga (penulis Serat Centhini) ingin memunculkan antitesis kepercayaan Islam secara letterljk, yang senyatanya terdapat akulturasi antara agama Islam dengan segala bentuk warisan budaya di masyarakat.
Cerita Seh Amongraga dan Angganala dijadikan simbol sinkretisme antara budaya Jawa dengan agama Islam dalam konteks yang dibangun dalam cerita. Serat Centhini yang terbalut berbagai ajaran Islam dijadikan penengah berbagai ritus kebudayaan Jawa lama yang masih lestari. Tak lain dengan menghindari cara pandang kacamata kuda dan memaki cara pandang konservatif-progresif dalam penelaahannya. Hal ini menunjukkan bahwa para Pujangga terdahulu telah memprediksi akan adanya pertentangan antara Agama Islam dengan warisan budaya Jawa. Dengan begitu cerita Golan-Mirah yang begitu sensitif dapat terdamaikan dengan melihat narasi solutif cerita Serat Centhini jilid VII ini.
Kisah Centhini sebagai solusi ini – saya kira penting dikemukakan kembali – mengingat kemungkinan adanya kelompok tertentu di zaman sekarang yang mencoba memanfaatkan tradisi lisan yang lumayan sensitif seperti kisah percintaan Golan-Mirah. Amat sangat mungkin – kisah Golan-Mirah mengalami penggorengan dan dibenturkan dengan dalil-dalil agama yang memecah belah masyarakat kedua desa. Amat mungkin terdapat kelompok-kelompok tertentu yang mencoba menciptakan polarisasi di masyarakat.
Saya melihat banyak masyarakat Ponorogo yang menyatakan bahwa kisah percintaan legendaris Golan-Mirah adalah warisan budaya yang bertentangan dengan nilai agama (Islam). Syariat agama tidak membenarkan pantangan pernikahan antara warga desa Golan dan Mirah. Pandangan seperti ini menurut saya di lain pihak juga akan meruntuhkan keberadaan local genius daerah setempat. Tak ada yang salah dengan local genius yang lahir dimana pun juga. Sebab Desa itu mawa cara dan Negara mawa tata.Maksudnya, setiap masyarakat mempunyai hak hidup dan berbudi daya dengan caranya masing-masing di setiap wilayah. Satu dengan lainnya tidak bisa disamakan.
Menurut saya, warisan budaya dengan dogma agama tidak sepatutnya dibenturkan. Pertautan keduanya memerlukan sinkronisasi-solutif agar tidak menimbulkan salah pandang interpretasi. Pikiran konservatif-progresif dibutuhkan untuk menjaga warisan budaya, kukuhnya ajaran agama dan mewujudkan masyarakat yang adaptif sesuai dengan keadaan zaman. Dengan kata lain harus ada wacana solutif yang harus masif dimunculkan untuk mengimbangi narasi yang terhitung sensitif ini.Jangan sampai desa yang begitu tata, tentrem, kartaraharja jangan sampai digusur paradigma yang berusaha mengecilkan martabat kearifan masyarakat Desa.
——————-
Daftar Pustaka
De Graaf, H.J. 1985. Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa. Jakarta: Pustaka Grafitipers.
Knebel, J. 1909. Over de Plaatsen van de hogste vereering (poenden) en eenige andere bijzonderheden in de afdeeling Panaraga. Batavia: Albrecht & Co.
Margana, S. 2004. Pujangga Jawa dan Bayang-Bayang Kolonial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Purwowijoyo. 1984. Babad Ponorogo Jilid 1. Ponorogo: Depdikbud Kanwil.
Sukatman. 2011. Butir-butir Tradisi Lisan Indonesia Pengantar Teori dan Pembelajarannnya. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
*Penulis anggota Komunitas Sraddha Institute di Surakarta. Tengah menempuh studi di Pasca Sarjana Ilmu Susastra Universitas Diponegoro Semarang.





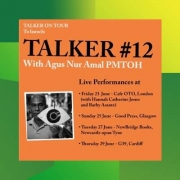




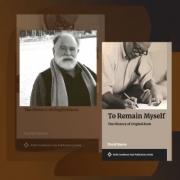


Golan-mirah, cinta yang tak bisa bersatu