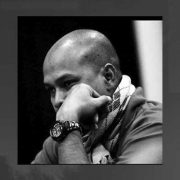Membaca Pesan, Mencermati Tanda: Literasi Budaya Ekologis dalam Musibah Banjir Bandang Minangkabau dan Tapanuli
Oleh: Gus Nas Jogja*
Pendahuluan: Kosmos yang Bicara dan Telinga Adat yang Membisu
Bencana hidrologis masif yang melanda Sumatera, termasuk wilayah yang secara kultural terikat pada Ekosistem Bukit Barisan (seperti tragedi di Batang Toru dan wilayah Minangkabau lainnya), bukan hanya anomali iklim, melainkan sebuah “Pesan” yang disampaikan oleh alam. Pesan ini muncul akibat rusaknya ekosistem penyangga kritis oleh aktivitas ekstraktif korporasi. Kegagalan menanggapi musibah ini menunjukkan krisis yang lebih dalam: kegagalan literasi budaya dalam membaca kearifan leluhur yang telah dikodifikasi dalam petatah petitih (pepatah dan petitih).
Masyarakat Minangkabau secara historis menempatkan alam sebagai guru— “Alam Takambang Jadi Guru”. Prinsip ini menciptakan “Ekosistem Kebudayaan” di mana aturan adat (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) berfungsi sebagai regulasi konservasi yang presisi. Esai ini akan mengelaborasi secara kritis tiga pepatah kunci Minangkabau sebagai kerangka filosofis untuk menganalisis dan merumuskan respons terhadap bencana, mengaitkannya dengan bukti empiris kerusakan lingkungan yang terstruktur.
Filosofi Kewaspadaan Struktural: Mandat Preventif dari Hutan Larangan
“Maminteh sabalun anyuik, malantai sabalun lapuak”
Berhati-hati sebelum terhanyut, menjaga rumah sebelum kayu lapuk.
Pepatah ini adalah inti dari prinsip konservasi berbasis budaya dalam Minangkabau. “Maminteh” (mencegah, memintal jaring) dan “Malantai” (memelihara lantai) secara ekologis merujuk pada pemeliharaan ekosistem penyangga. Bukti empiris dari kearifan ini terwujud dalam konsep tata ruang tradisional seperti:
1. Hutan Larangan Adat (HLA): Area hutan yang dijaga ketat oleh Niniak Mamak (pemimpin adat) dan hanya dapat diakses untuk kebutuhan ritual atau terbatas, berfungsi sebagai zona inti konservasi hidrologis dan penjaga keanekaragaman hayati. HLA adalah “lantai” yang tidak boleh dibiarkan lapuak [1].
2. Lubuk Larangan: Segmen sungai yang dilarang untuk ditangkap ikannya dalam periode tertentu, yang berfungsi sebagai bank gen dan memastikan keberlanjutan sumber daya perairan.
Secara filosofis, pepatah ini adalah penolakan terhadap Tragedi Kepemilikan Bersama (Tragedy of the Commons) di mana kepentingan individu merusak sumber daya kolektif. Kearifan Minang menetapkan sanksi sosial dan adat bagi perusak hutan, menahan laju entropi ekologis.
Namun, di era modern, “kayu lapuk” itu adalah rusaknya tutupan hutan Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru akibat izin eksploitasi korporasi (seperti PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, dan PTPN III). Kerusakan ini, yang secara empiris dikaitkan dengan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir dan longsor sejak Selasa (25/11/2025), membuktikan bahwa mandat preventif adat telah dikalahkan oleh kapitalisme ekstraktif [2]. Kegagalan malantai adalah kegagalan Niniak Mamak dan negara dalam mempertahankan integritas “Rumah Gadang” kolektif dari kepentingan modal.
Epistemologi Alam: Membaca Tanda Entropi di Hulu Sungai
“Cewang di langik tando ka paneh, gabak di ulu tando ka ujan”
Awan tipis adalah tanda akan cerah, awan hitam di hulu adalah tanda akan hujan.
Pepatah ini adalah ekspresi dari Literasi Tanda Alam—kemampuan untuk mendiagnosis keadaan ekosistem sebelum krisis terjadi. Dalam konteks bencana hidrologis, gabak di ulu (awan hitam di hulu) bukan hanya awan meteorologis, melainkan:
1. Sedimentasi dan Turbiditas: Peningkatan sedimen dan kekeruhan air sungai secara abnormal (turbidity) adalah gabak yang menunjukkan erosi lahan masif di hulu akibat pembukaan hutan.
2. Hilangnya Keanekaragaman Hayati: Punahnya spesies endemik seperti Orangutan Tapanuli atau Harimau Sumatera di wilayah Batang Toru adalah gabak yang menunjukkan hilangnya fungsi ekologis vital [3].
3. Monokultur Korporasi: Pergantian hutan heterogen menjadi monokultur perkebunan sawit (PT Sago Nauli, PTPN III) adalah gabak struktural yang mengurangi daya serap air tanah.
Filosofisnya, kearifan Minang menuntut pengakuan atas entropi yang mulai bekerja. Kita tahu bahwa ketika energi kerja alam –fungsi hutan sebagai penyangga– dieksploitasi dan diubah menjadi energi limbah (limbah pulp TPL atau limpahan air NSHE), kekacauan banjir bandang adalah keniscayaan termodinamika. Para leluhur mengajari kita untuk bereaksi terhadap tanda sekecil apa pun; namun, sistem modern justru buta terhadap tanda-tanda ekologis yang paling jelas, yaitu gabak korporasi di sekitar Batang Toru.
Konsekuensi dan Transformasi Ekologis: Geometri Alam yang Tak Terbalikkan
“Dek sakali aia gadang, sakali tapian barubah”
Sekali banjir besar, sekali pula tepian sungai berubah.
Pepatah ini adalah pengakuan filosofis atas prinsip ke-tak-terbalikkan (irreversibility). Banjir bandang yang menghancurkan dan mencatat 15 orang meninggal di Tapanuli Selatan, ribuan rumah dan hektare pertanian rusak adalah perubahan permanen pada tapian (tepian, sekaligus tatanan sosial).
Adanya perubahan geometri dan daya tahan ekologis. Secara empiris, hilangnya tapian berarti kerusakan yang melampaui ambang batas pemulihan alam (ecological resilience threshold). Sungai tidak akan kembali ke alur yang sama; lahan yang longsor tidak dapat secara instan menumbuhkan kembali hutan dewasa. Ini adalah peningkatan entropi yang permanen.
Pentingnya transformasi keadilan humaniter. Bencana ini memunculkan tuntutan untuk Transformasi Struktural dalam kerangka Keadilan Ekologis. Perubahan tapian harus direspons dengan perubahan hukum dan kebijakan. Pepatah ini mendesak agar kerangka Adat Basandi Syarak diaktifkan kembali untuk:
1. Akuntabilitas Korporasi: Menuntut pertanggungjawaban dari entitas yang secara empiris terindikasi sebagai pemicu kerusakan.
2. Restorasi Negentropi: Melakukan restorasi ekologis berbasis kearifan lokal dengan penanaman kembali dengan spesies asli, penetapan kembali HLA, serta berbagai tindakan pelestarian lingkungan lainnya.
Pepatah ini adalah penutup yang melarang kita kembali ke titik eksploitasi yang sama. Musibah ini adalah pesan bahwa masyarakat harus menyerap kesadaran ekologis ini dan menjadikannya dasar bagi revolusi termodinamika moral: mengubah energi serakah menjadi energi konservasi untuk menjamin masa depan.
Penutup: Merumuskan Kembali Literasi Budaya Ekologis
Musibah banjir bandang di Sumatera adalah epilog tragis dari narasi kegagalan MEMBACA PESAN, MENCERMATI TANDA yang tertuang dalam petatah petitih Minangkabau. Kearifan lingkungan yang berbasis Ekosistem Kebudayaan Minangkabau—terangkum dalam “Maminteh”, “Cewang”, dan “Tapian Barubah”—menawarkan kerangka kerja preventif, diagnostik, dan transformatif.
Kegagalan kita adalah menganggap petatah petitih sebagai folklor usang, padahal ia adalah panduan manajemen ekosistem yang paling canggih. Untuk mencapai Negentropi atau keteraturan dan keadilan sejati, masyarakat dan negara harus kembali pada literasi budaya ekologis ini. Hanya dengan demikian, kita dapat berubah dari menjadi korban Entropi menjadi Khalifah atau pengelola bumi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa Hutan Larangan tetap utuh dan tapian sungai dapat berfungsi kembali sebagai penyangga kehidupan.
Wallahu A’lam. ***
Catatan Kaki
[1] P. K. Nas, “The Power of Minangkabau: An anthropological approach to the social, political and economic organization of the Minangkabau people,” Universitas Leiden, 1993. (Membahas struktur Adat dan sistem pengelolaan sumber daya komunal).
[2] WALHI Sumatera Utara, Rilis Pers Mengenai Bencana Banjir dan Longsor Tapanuli, 2025. (Dokumentasi empiris yang mengaitkan aktivitas korporasi dengan kerusakan Ekosistem Batang Toru dan bencana).
[3] H. E. Daly, Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development, Beacon Press, 1996. (Karya fundamental dalam ekonomi lingkungan yang mengkritik pertumbuhan tak terbatas dan mendesak penerapan batas fisik—termodinamika—dalam kebijakan ekonomi).
[4] J. Rifkin, Entropy: A New World View, Bantam Books, 1989. (Menjelaskan bagaimana eksploitasi sumber daya secara fundamental meningkatkan entropi dan kekacauan, yang resonan dengan gabak ekologis).
[5] S. H. Nasr, Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man, Unwin Paperbacks, 1990. (Membahas bahwa krisis ekologi berakar pada krisis spiritual, sebuah pemutusan hubungan dari prinsip Tauhid, yang mencerminkan hilangnya kesakralan alam dalam petatah petitih).
Daftar Pustaka
Daly, Herman E. Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Boston: Beacon Press, 1996.
Nas, P. K. The Power of Minangkabau: An anthropological approach to the social, political and economic organization of the Minangkabau people. Universitas Leiden, 1993.
Nasr, Seyyed Hossein. Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man. London: Unwin Paperbacks, 1990.
Rifkin, Jeremy. Entropy: A New World View. New York: Bantam Books, 1989.
——
*Gus Nas Jogja, budayawan.