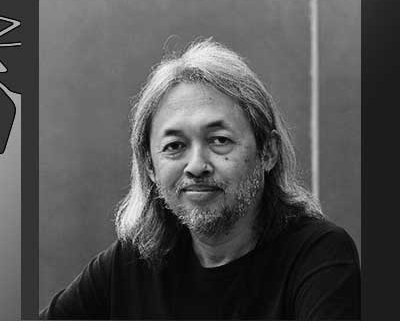“Tidak Ada Waktu bagi Nyonya Fatmah, Barda, dan Cartas”: Kriminalitas Filosofis
Tiga Drama Kuntowijoyo (2)
Oleh Seno Gumira Ajidarma
Skandal dan pembunuhan di perkebunan apel
yang menjadi rahasia 15 tahun. Terungkap
sebagai naratif filsafat eksistensi, berbalut
konsep waktu kualitatif Bergson. Praktik
berfilsafat Kuntowijoyo melalui naskah lakon.
Naskah drama Kuntowijoyo (1943-2005) kedua dalam seri perbincangan ini, “Tidak Ada Waktu bagi Nyonya Fatmah, Barda dan Cartas”, adalah salah satu pemenang Sayembara Penulisan Lakon Dewan Kesenian Jakarta pada 1972. Dengan segera tampak, betapa judulnya dapat menimbulkan pertanyaan, ketika dalam judul itu disebut tiga nama.
Lazimnya, “Tidak Ada Waktu bagi …” akan disusul satu nama atau subjek saja, seperti “Tidak Ada Waktu untuk Cinta” atau “Tidak Ada Waktu untuk Mati”. Dengan adanya tiga nama dalam judul tersebut, yang menjadi istimewa justru adalah ‘tidak ada waktu’, karena berlaku untuk tiga nama dan berarti ketiadaan waktunya ‘berlangsung’ sekaligus tiga kali: tidak ada waktu untuk Nyonya Fatmah, tidak ada waktu untuk Barda, dan tidak ada waktu untuk Cartas.
Apa artinya ‘tidak ada waktu’ dalam drama ini? Judul seperti itu membuat saya ingin menengok, bagaimana ‘tidak ada waktu’ berlaku bagi masing-masing peran, yakni peran Nyonya Fatmah, peran Barda, dan peran Cartas.
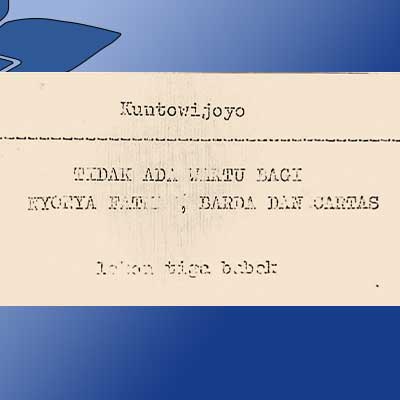
Lembar judul pada manuskrip stensil di Perpustakaan Jakarta, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Ruang yang menghadirkan waktu drama ini, sejauh tertulis dalam didaskalia (teks dalam naskah yang tidak diucapkan peran), adalah sebuah penginapan di dataran tinggi, tempat Nyonya Fatmah, pemiliknya, juga memiliki perkebunan yang menanam buah-buahan dingin. Nantinya, secara spesifik akan disebut buah apel.
Disebutkan tidak banyak orang menginap, karena menginap di sana merupakan suatu kemewahan. Penginapan itu berupa sebuah bangunan kayu dengan arsitektur yang bagus. Terletak di tengah hutan, orang dapat menikmati pemandangan cantik ke sekitar, memancing, atau berburu. Di bawah terdapat gudang, garasi untuk mobil sendiri dan tamu.
Dari beranda penginapan, tempat semua peristiwa dalam drama ini, gudang dan garasi itu tenggelam oleh pepohonan, tetapi karena tidak terlalu jauh juga, disebutkan orang cukup berteriak untuk memanggil seseorang di sana. Ruang di beranda itu beratap terbuka, dengan kursi-kursi rotan tempat memandang ke segala arah, pagar langkan di sekeliling beranda, kecuali di bagian yang menuju jenjang.
Pintu, dinding, atap, serba kayu, dengan hiasan kaca berwarna, kepala rusa bertanduk cabang. Siang hari sejuk, dengan cahaya matahari dari celah pohonan. Malam harinya dipercantik lampu-lampu gantung. Meski disebutkan burung-burung bermain di mana-mana, dinyatakan bahwa kesunyian adalah kesempurnaan tempat itu.
Lebih prosaik ketimbang petunjuk panggung dalam didaskalia, Kuntowijoyo membungkus teks penjelasannya sebagai berikut: Suara angin yang jauh, suara burung, bisik lebah di atas bunga-bunga.
Lima Belas Tahun Kerahasiaan
Pada babak pertama, terdapat dua tamu bapak-anak, Munib dan Leila, yang alih-alih sudah cukup lama berlibur di tempat itu, masih ingin terus memperpanjang masa tinggalnya. Pemilik penginapan, Nyonya Fatmah, digambarkan sebagai perempuan anggun usia 40-an, yang ‘menunjukkan gairah hidupnya’; sementara Cartas, laki-laki tua, disebut sebagai ‘semacam penganggur’, tetapi sebetulnya selalu membantu pada saat panen apel.

Perkebunan apel di dataran tinggi, latar misteri 15 tahun dalam drama “Tidak Ada Waktu Bagi Nyonya Fatmah, Barda, dan Cartas”, gubahan Kuntowijoyo pada 1972. ( https://nahwatravel.co.id/kebun-apel-malang)
Mereka berbincang tentang kedua tamunya, terutama Munib yang disebut Nyonya Fatmah sebagai ‘penganggur beruang’. Namun meski tak setuju dengan gaya hidup tamu-tamunya, Nyonya Fatmah menganggap sudah tugasnya melayani segala kebutuhan mereka, walau sempat digugatnya Cartas, yang menemani Munib bermain kartu sampai larut. Cartas memang jadi mengantuk untuk membantu panen apel. Cakapan menjadi serius, ketika Cartas mengaku suka bermain kartu dan bersahabat dengan Munib maupun Leila.
FATMAH: Baru sekarang aku mendengar kita perlu sahabat di sini. (kepada diri sendiri) Yang kita perlukan ialah diri sendiri. Kita boleh punya sahabat. Tetapi kalau kau tak punya dirimu sendiri, percuma saja.
CARTAS: Nyonya sudah belajar menipu diri sendiri selama ini.
FATMAH: Juga kau!
CARTAS: Ah, kita semua penipu di sini. Kita semua tidak jujur.
FATMAH: Tutup mulut. Hmm ya, kalau tuan itu nanti pergi, bikinkan tanda terima seperti biasa (dst…).
Cakapan berlanjut dengan keharusan bersikap sebagaimana pengusaha penginapan, agar tamu-tamunya merasa terpuaskan oleh pelayanan, dan karenanya dapat kembali lagi. Ini pun segera dipandang secara kritis.
FATMAH: Bagus. Belajar bertahun-tahun untuk mengucapkankalimat-kalimat yang menyenangkan para tamu.
CARTAS: Ya, dua puluh tahun sejak aku meninggalkan rumah orangtuaku. Dua puluh!
FATMAH: Sudah itu bersihkan kamar. Kita mesti selalu siap untuk menerima tamu. (menuding) Sudah dipetik apel di gunduk itu?
CARTAS: Akan kutanyakan. (beranjak pergi).
FATMAH: Jadi apa kerjamu selama ini? Mengawasi saja tidak.
CARTAS: Itu Barda punya kerja. Sesungguhnya Cartas seorang penganggur Nyonya. Itu sudah sama kita ketahui, bukan? Cartas tinggal di sini dikasih makan untuk menghabiskan waktu dengan caranya sendiri. Aku di sini untuk menanti kematian. Atau suatu perubahan.
FATMAH: Engkau sungguh tolol. Tidak mau belajar apa-apa dari umurmu.
CARTAS: Belajar ialah belajar untuk sesuatu. Sedang aku tidak punya lagi hak untuk mengidamkan sesuatu. Aku hanya diperkenankan menarik nafasku sendiri. Sambil menanti hari berhentinya jantungku.
FATMAH: (merenungi Cartas) Aku tahu Cartas. Setiap kali ada tamu di sini, semangatmu terganggu. Itu karena sebenarnya engkau penakut. Tidak punya keberanian untuk menyatakan Ya kepada nasib yang menimpamu. Engkau jadi pemurung, setiap kali tamu-tamu datang ke sini. Itu berarti kamu akan membunuh dirimu. Pelan-pelan. Yang kita perlukan ialah keberanian untuk hidup.
CARTAS: Keberanian, apakah itu?
FATMAH: (pelan) Untuk menyerah.
CARTAS: Menyerah bukan keberanian. Ini bukan hidup! Ini kematian, Nyonya! (dst.)
Lantas mereka berdebat tentang bagaimana harus hidup. Cartas menganggap kehidupan mereka yang terkungkung dan menyendiri itu menderita, tetapi pura-pura berbahagia. Menurut Fatmah, Cartas pun menciptakan kehidupan untuk dirinya sendiri, seperti yang saat itu mereka semua sedang menjalaninya. Cartas menyangkal, karena tidak menghendakinya. Perhatikan kalimat Cartas tadi:
“Cartas tinggal di sini dikasih makan untuk menghabiskan waktu
dengan caranya sendiri. Aku di sini untuk menanti kematian.
Atau suatu perubahan.”
Sudah lima belas tahun mereka berada di ketinggian, jauh dari dusun, apa lagi kota. Tidak pernah melihat dunia. Tanpa harapan kembali. Bagi Fatmah mereka beruntung tiba-tiba lahir dan berada di tempat itu, yang tenteram, damai, tiada keramaian dan kejahatan.
Namun bagi Cartas tiada artinya tanpa kebebasan, walau ia tak dapat juga mengetahui, ketika ditanya kebebasan itu apa. Cartas lantas menangis telah hidup. Kata Fatmah, mereka tak bisa memilih, dan hanya menerima. Tiada cara lain, “Kalau kau masih ingin punya umur.”
Sampai di sini, gagasan ‘waktu’ untuk kedua kalinya muncul.
CARTAS: Umur ialah hak mereka yang bebas. Sedangkan waktu saja kita tidak punya lagi.
FATMAH: Baiklah, mau apa kau kalau begitu?
CARTAS: (menatap kosong) Perkenanlah aku duduk sesukaku.
(sementara lengang, di bawah terdengar ribut lagi.
Fatmah memandang ke arah gudang. Cartas menyentik
burungnya. Kemudian terdengar laki-laki tua itu
mengeluh panjang pendek, mengucek mata).
FATMAH: Apa lagi?
CARTAS: Mengantuk (mengucek lagi). Aku benci mengantuk. Aku bosan tidur.
FATMAH: Kalau begitu kau boleh lari ke bawah. Ambillah beberapa butir apel. Aku mau lihat hasilnya. Dan suruh Barda segera ke kota.
CARTAS: Maaf. Aku lagi tidak suka Barda. Orang itu yang jadi biang keladi.
(Cartas bermain dengan burung betet. Ia menaruhkan burung itu di pagar langkan beranda. Menggodanya, meninggalkan di situ).
FATMAH: Cartas, buang burung itu! Ya, kalau tamu kita suka burung macam itu. Sedikit saja kita membuat kesalahan, hilang kesukaan orang. Mungkin putri Tuan Munib takut pada burung itu.
CARTAS: Baik atau buruk. Inilah satu-satunya kemerdekaan yang kupunya. Yang tersisa. Nikmatilah apa yang bisa kau nikmati. Bukan begitu Nyonya? Inilah juru penghiburku!
Fatmah mengancam, jika penginapan ditutupnya, Cartas akan kehilangan hak berbicara satu-satunya dengan orang luar. Cartas pun pergi sambil berteriak: “Baiklah aku akan lari dan lepas segalanya. Melemparkan hidup ke udara! Berhamburanlah! Berhumbalang! Berhamburan!”
Fatmah masih merenungi kepergian Cartas ketika Tuan Munib tiba, berpakaian untuk berburu dan membawa senapan. Mereka pun segera terlibat pertukaran pikiran, tentang apakah tempat liburan itu baik untuk liburan saja, dalam arti selingan hidup, ataukah untuk hidup selamanya, seperti Nyonya Fatmah yang sudah 15 bahkan tak pernah turun ke kota.
Tuan Munib dan Leila, anaknya itu, betah tinggal lama di penginapan bukan hanya karena lingkungan alamnya, melainkan kepribadian para pengurusnya. Termasuk ketika Fatmah mengucapkan ini:
FATMAH: Kalau aku boleh berpikir. Maka inilah pikiranku.
(sebentar …). Tuan, aku sudah di sini begitu lama.
Tidak pernah memikirkan akan mengubah hidupku.
Tuan tidak usah heran. Sebab, masa depan ialah kabut bagi kita. Semuanya masih gelap. Kita dihadapkan
kepada kerahasiaan yang diam. Tetapi yang selalu siap menelan kita. Aku tidak suka bertualang. Aku memilih tinggal di hutan ini. Di sini tidak ada rahasia. Tidak ada kecemasan. Sementara waktu berlalu.
Betapapun Tuan Munib mempertanyakan, mengapa setelah 15 tahun, Nyonya Fatmah tidak mempertimbangkan cara hidup lain. Nyonya Fatmah bukan tidak pernah turun ke kota, melainkan memilih untuk tetap berada di pebukitan itu sampai 15 tahun lamanya.
MUNIB: Berlibur di sini setengah bulan itu kegembiraan. Tetapi di sini 15 tahun tanpa melihat sesuatu yang lain, itu penjara.
Maka, tentu menjadi pertanyaan besar, apakah yang terjadi 15 tahun lalu itu, yang telah membentuk keniscayaan sekaligus kenisbian bagi mereka yang terlibat? Persoalan telah mengerucut sebagai kontradiksi: yang telah berlangsung di perbukitan itu adalah presentasi kebebasan, ataukah membuktikannya sebagai ketakutan menghadapi kebebasan? Keberanian atau penyerahan? Memang benar masalah pilihan hidup, atau terdapat peristiwa yang memaksakan pilihan itu?
Sedikit demi sedikit misteri itu diungkap, sebagai sesuatu yang tersembunyi dan barangkali memang ditutupi selama 15 tahun. Setelah pada awal babak ini Cartas bicara tentang menghabiskan waktu dua puluh tahun, peran yang diperlihatkan antara aneh tetapi manusiawi itu pun mengungkap lagi bersama kemunculan peran Barda.
CARTAS: Kalau aku mau cerita tentang burung, Tuan mau dengarkan?
LEILA : Aku suka. Asal jangan pelihara gagak. Aku tidak suka itu. Gagak bukan sebangsa burung jinak. Gagak kotor, makan bangkai, dan jahat.
MUNIB: Burung-burung tidak jahat. Itu sudah kerjanya. Burung tidak punya susila. Ia tidak baik atau jahat.
CARTAS: Betul, aku dapat tunjukkan kepada Nona. Yang lebih jahat dari gagak.
LEILA : Tidak ada. Elang, barangkali?
CARTAS: Dia adalah manusia! Tahukah Tuan dan Nona? Barangkali siapa juga yang kau jumpai di jalan, atau di rumah, sebenarnya adalah penjahat?
Tahukah Tuan dan Nona, sekarang kalian bergaul dengan pembunuh? Bukannya gagak yang pembunuh, tapi manusia! Gagak hanya mencakar dan itu kodratnya! Tak bisa lain. Tetapi manusia! Nona. Ia bisa tidak membunuh, namun ia membunuh juga! (semakin keras suaranya bersemangat dan tampak) Manusia itu! Pembunuh! Di sini ada pembunuh! Pembunuh! (berteriak-teriak,
Munib hanya diam. Tak mengerti. Di ujung beranda tiba-tiba Barda berdiri kaku. Menatap tajam Cartas. Fatmah bersandar di pintu. Cartas mengetahui kedatangan mereka. Menyurut semangat. Menyembunyikan keliarannya. Barda menghilang).
Cara Barda muncul dan menghilang, ketika gagasan tentang terdapatnya pembunuhan dinyatakan Cartas, menambah lapisan misteri baru bersamaan dengan tersingkapnya misteri lama: bahwa ada sebabnya mereka menutup diri sampai 15 tahun di situ.
Munib dan Leila tidak tampak mencurigai apapun. Sementara Leila masih terus bermaksud menikmati alam di sekitarnya, Munib yang seperti tertarik kepada Fatmah tampak berusaha mengajak perempuan itu turun ke kota, sebagai tamunya. Dalam perbincangan yang terus-menerus bernada filosofis, terbaca bahwa Fatmah mulai mengubah sikapnya, bahwa bukan tempat manusia tinggal, melainkan sikap manusia di mana pun tempatnya tinggal, yang menentukan keberadaannya.
Cartas yang menangkap perubahan itu mengingatkan, bahwa mereka yang tinggal di perbukitan itu, setelah 15 tahun, tidak mempunyai waktu lagi untuk mengubah kehidupan mereka. Mereka yang berada di sana telah memenjarakan diri mereka sendiri, atas suatu pembunuhan yang belum jelas duduk perkaranya. Hanya saja Barda yang muncul kembali berkata, bahwa seandainya ia dulu dihukum penjara, sekarang tentu sudah bebas; tidak terpenjara selamanya seperti yang mereka jalani.
Munib yang mendengarkan, bahkan terlibat dalam perbincangan, belum juga paham apa yang terjadi. Ia hanya minta Fatmah tidak menyerah, walau bagi Fatmah kemampuan menyerah itu suatu pencapaian. Betapapun Fatmah berpikir ia telah mengambil keputusan 15 tahun lalu dengan hasil yang dianggapnya final. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, seandainya mengambil suatu keputusan sekali lagi.
Rahasia yang Tersingkap
Babak Dua adalah sore hari di beranda penginapan. Mulai tersingkap apa yang terjadi 15 tahun lalu. Tidak langsung semuanya, melainkan selapis demi selapis, seperti diujarkan peran Barda yang paling jarang bicara.
BARDA : (memandang jauh pada yang di bawah–ke arah Fatmah dan Munib / sga) Mereka sebagai sedang bercintaan, Cartas. Apakah ini berarti kebebasanmu? Apakah mereka akan turun dan menikah?
CARTAS: (terkejut) Jawab dulu pertanyaan ini. Apakah orang dilarang bercinta?
BARDA : Di dunia yang lain, boleh. Di sini tidak.
CARTAS: Di dunia yang gila ini?
BARDA: Lebih dari itu, Cartas. Kita keracunan! Kita mabuk! Kita sudah mati! (menunjuk) Lihatlah bunga di tangan Tuan Munib itu, Cartas! Begitulah dulu (tertunduk dengan kenangan yang kacau) Ketika Nyonya mengirimkan bunga ke kamar. Ketika ia menyatakan kepadaku. Ketika bercintaan. Yang berakhir dengan pembunuhan. (menunduk dalam, terisak). Sudah itu, cinta itu terkubur. Berubah jadi neraka. Berubah jadi neraka. Penjara ini. Pembunuhnya, ialah dia. Hanya tangankulah yang berdarah. Sekarang ia akan keluar dari sini, sesudah ia menjerumuskan aku. Tanganku yang suci ketika naik ke bukit dengan cita-cita. Terbelenggu oleh darah yang tak habis amis baunya. Aku masih dapat menciumnya sekarang (sengsara). Bau bunga itu, bau darah itu. Cartas, mengapa kau tidak mengirimku ke penjara, ya?
CARTAS: (ikut sedih) Kukira dosa itu dapat dimaafkan, Nak. (mendekat, mengelus rambut Barda) ternyata tidak.
Justru engkau tidak memaafkan dirimu sendiri. Dan si pendosa bersama pengampun dimasukkan ke penjara Bersama. Seumur hidup, Barda, ya (mereka diam. Barda tegak kembali memandang ke bawah lagi. Tertunduk dan tegak, ia seperti kebingungan.
BARDA: Aku tidak akan sampai hati. Cukuplah kejahatanku. Tetapi aku harus membalaskan Tuan Sulaiman juga. Tuan Sulaiman yang telah menolongku, dan budiman itu. Aku berhutang budi padanya, untuk membalaskan pengkhianatannya.
Menjawab pertanyaan-pertanyaan Munib, dari Cartas akan diketahui bahwa Barda adalah mahasiswa yang 15 tahun lalu membantu Tuan Sulaiman membangun perkebunan. Sedangkan Fatmah, istrinya, saat itu adalah gadis cantik yang sangat dimanjakan Tuan Sulaiman. Namun pada suatu hari Fatmah meletakkan bunga-bunga di kamar Barda, yang kemudian berlanjut dengan terbunuhnya Tuan Sulaiman itu di padang perburuan. Pungggungnya luka tertembus peluru Barda.
“Ya, aku menggotongnya pulang. Tanganku masih bau darah. Sekarang ini seolah masih terjadi kemarin saja. Ciumlah darah ini,” kata Cartas sambil mengulurkan tangannya kepada Munib. Ia juga menunjukkan gundukan tempat Sulaiman dikubur.
Waktu seolah berhenti setelah itu. Tuan Sulaiman dikubur tanpa ada yang mempersoalkannya. Tidak ada saksi. Tidak ada hukum. Tidak ada polisi. Sedangkan ketiga orang itu tidak pernah membicarakannya. Selama 15 tahun, meski tidak ada yang melarangnya, mereka dengan suka rela tidak pernah turun ke kota. Seberapa jujur? Jika Cartas dan Barda sudah membocorkan apa yang mereka pikirkan, Leila bercerita kepada ayahnya, “Di mata Nyonya selalu kulihat air mata, Pap.”
Kedatangan Bapak-Anak ini memang mengubah keadaan, seperti terlihat dari akhir Babak Kedua.
FATMAH : Bagaimana pendapat Tuan tentang aku?
MUNIB : Tanyakanlah kepada putriku Nyonya! (Nyonya Fatmah melirik kepada Leila).
LEILA : Kami tidak akan mengurangi kemerdekaan Nyonya dengan berpendapat sesuatu tentang Nyonya. Nyonya merdeka dan utuh. Kami tidak berpendapat, tetapi berbuat. Atau pendapat kami adalah perbuatan kami.
FATMAH: (wajahnya berubah. Tersenyum. Seolah mau terjatuh dan Tuan Munib menyangganya). Tuan, oh, aku merindukan saat itu! Betapa aku menantinya!
MUNIB : Nyonya!
FATMAH: Tuan! Aku ingin menyatakan kemerdekaanku! Ingin. Mari kita berbuat! (dalam temaram mereka masuk, dan sebagai sejoli yang bercintaan. Malam merayap di beranda itu).
Di Balik Letusan Senapan
Dalam Babak Ketiga, pada pagi cerah Fatmah, Leila, dan Munib sedang bersiap-siap berangkat untuk pindah ke kota, berbincang tentang indahnya alam pegunungan, ketika Cartas dengan gaya kegila-gilaan seperti diperlihatkan sejak awal, kembali mengungkap masa lalu. Bahkan menyatakan bermimpi, bertemu dengan Tuan Sulaiman yang mengatakan akan menuntut balas. Menurutnya, harus ada keadilan bagi Tuan Sulaiman, yang dikhianati istrinya, dan dibunuh oleh pembantunya.
CARTAS: Dari jauh dosa makin tampak membesar. Dilupakan makin teringat. Disembunyikan makin jelas. Dicuci makin mengotori. Tidak bisa Tuan. Tidak. Tuan Sulaiman akan memburu ke mana saya lari.
MUNIB: Yang diburunya hanya Cartas. Bagi yang berani sunyi akan berubah jadi kegembiraan. Duka jadi bahagia. Dosa memutih seperti sediakala.
CARTAS: Tuan tidak akan berhasil. Kita bertaruh!
MUNIB: Aku tidak pernah menjanjikan hasil. Yang kujanjikan ialah perbuatan. Sejak pertama aku sudah menyatakannya. Semua hutang sudah dibayar. Dosa sudah ditebus. Tidak ada soal lagi. Kalau kau suka kau boleh ikut. Aku akan menunggumu. Kalau kau tak suka pergi, silahkan jangan
menghalangi kami.
CARTAS: (tertunduk menangis) Hanya Tuan Sulaiman berhak mengusirku. Aku datang di sini bersamanya, aku teringat kembali hari-hari pertama itu. Seorang yang suka bekerja keras untuk masa depannya. Luar biasa nasibnya. Nestapa yang sempurna. Tuan Sulaiman sekarang sudah hancur
dalam tanah, tapi rohnya! Akan menuntut balas. Para pembantunya harus di sini, Bersama Tuan Sulaiman. Tuan Sulaiman di kubur dalam tanah. Para pembunuhnya di atas tanah. Tak ada yang lebih sesuai kecuali itu. Keadilan yang sebenarya. Tidak ada lagi waktu.
Namun Munib justru membebankan kebersalahan kepada Cartas, sebagai saksi pembunuhan yang tidak lapor kepada polisi. “Engkau tidak bersalah, tapi engkau melakukan kesalahan,” katanya kepada Cartas–dan Cartas, maupun Barda, masih bisa menguburkannya, seperti yang telah dan selanjutnya akan dilakukan Fatmah.
Fatmah sendiri, yang sebelumnya sudah mantap untuk pindah, menjadi ragu dan menyatakan perasaan bersalahnya. Munib meyakinkan Fatmah, yang disebutnya sudah terbebas semenjak mengambil keputusan 15 tahun lalu untuk meniadakan kenyataan itu.
Demikianlah segala debat dalam perbincangan masih terus berlangsung, ketika Munib terpaksa membetulkan mesin mobil. Ini membuat keberangkatan Fatmah untuk meninggalkan dan mengubur masa lalu, menjadi tertunda. Dalam perdebatan, Cartas menyatakan Fatmah sebagai seorang pengkhianat jika pergi, karena bersama Barda telah bersepakat tetap tinggal di perbukitan dalam kerahasiaan–untuk itulah sebetulnya makna tidak ada waktu, karena perjalanan waktu dibekukan.
Namun Fatmah menegaskan bahwa dirinya telah bertanggungjawab dengan keputusannya 15 tahun lalu, dan kini pun ia telah mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan semua itu.
Munib sudah minta tangannya digandeng Fatmah untuk menuju mobil, ketika Cartas masih terus mengungkap ketidakpercayaannya, bahwa apa yang sebelumnya tampak akan abadi, bisa juga berubah. Saat itu Barda muncul membawa senapan.
BARDA: Nyonya! (mereka menoleh. Terdengar letusan. Dan jerit. Barda memandang mereka dengan kosong. Senapan itu terjatuh dari tangannya. Cartas mendekat ragu-ragu).
CARTAS: Barda! Benarkah telingaku? Mataku! Barda, gilakah aku? Atau mimpikah? Atau gilakah kau?
BARDA: (tenang) Antarkan aku ke penjara Cartas! Aku harus ke sana. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada tempat lagi bagiku. Aku telah menundanya lima belas tahun.
(Cartas bangkit menatap yang sedang mengurus Fatmah di jenjang bawah. Mereka tak tampak).
CARTAS: Barda, engkau Barda?
BARDA: (berjalan ke jenjang, menuruni sampai di hadapan Munib).
Jangan ganggu aku. Aku akan pergi ke rumahku yang baru. Lima belas tahun aku mengosongkannya. Ayolah Cartas! Bawa senapan itu! Berlumur darah (dua kata terakhir tak jelas dalam manuskrip, cakapan atau didaskalia – sga)
CARTAS: Barda!
BARDA: Ayolah, Cartas. Sekarang kau harus bicara!
CARTAS: (mengikuti) Aku tidak percaya. Aku tidak percaya! (Barda menuruni jenjang itu. Cartas mendekap burung dan berjalan mengikuti. Senapan di tangan. Munib membiarkan mereka pergi).
LAYAR
Dosa dalam Waktu dan Eksistensi Manusia
Latar lingkup perbukitan, di penginapan yang pengurusnya juga memiliki perkebunan apel itu, dalam didaskalia telah dibungkus dengan romantik melalui ungkapan keadaan alam pada awal drama ini: Suara angin yang jauh, suara burung, bisik lebah di atas bunga-bunga. Namun drama ini menolak godaan untuk menjadi romantik, seperti yang telah menjadi kesan dua tamu penginapan yang berlibur, bapak-anak, Munib dan Leila, selalu dalam perbandingannya dengan kota.
Saat kedua tamu ini memperpanjang masa tinggal mereka, sementara Leila terus membangun dunia idealnya berdasarkan suasana lingkungan dan karakter para peran, seperti Cartas dan Fatmah, melalui pertimbangan romantik pula; sebaliknya, Munib, juga melalui pergaulan dengan keduanya, justru romantisme itu tergugurkan, karena dipandangnya kehidupan para pengurus penginapan itu adalah semu, jika bukan pengingkaran kenyataan, atas kebersalahan mereka, yang dalam kenyataannya tidak terlupakan.
Namun Munib tetap mengagumi Fatmah, sebagai manusia yang mampu melakukan pilihan atas kemungkinan radikal dalam kebersalahannya: kuburkan (hanya ada gundukan, bukan kuburan) Sulaiman, lantas hidup dalam waktu yang tidak bergerak lagi, alias tetap tinggal di sana selamanya, dalam ikatan kerahasiaan abadi. Sebagai saksi, Cartas terlibat dalam ikatan itu.
Atas hubungannya dengan Fatmah, Barda menembak Sulaiman. Pembunuhan itu bukan kecelakaan, tetapi Fatmah menganggapnya sebagai peristiwa tak terduga, kecelakaan dalam hidup, yang bisa ditebus dengan kehidupan mereka selanjutnya. Bukan sekadar dalam penguburan kerahasiaan, melainkan sebagai kehidupan yang baru, tetapi kehidupan tanpa waktu, karena diandaikan tidak bergerak ke mana pun.
Dalam tafsir yang masih sama rupanya, Barda menembak Fatma, karena waktu mereka sudah tidak memberi kemungkinan lain. Namun penembakan itu mengembalikan keseimbangan batin Barda, yang tetap merasa bersalah, karena kali ini akan melapor ke polisi, sehingga dia bisa dihukum dan kebersalahan tertebus.
Walaupun tampak setimpal bagi Fatma, betapa ironis dan tetap tidak dapat dibenarkan, jika korban sebagai objek kebersalahan mesti bertambah demi kelegaan subjek kebersalahan yang sama. Tetap tidak ada waktu bagi Barda. Namun adalah twist dramatik bagi sang lakon teater.
Dapat diperhatikan bagaimana lakon kriminalitas ini tidak berurusan dengan komposisi alur misteri, untuk mencari jawab rasa penasaran: siapa pembunuhnya? Melainkan cakapan filosofis para peran atas tanggung jawab hidup masing-masing, yang setiap kali melibatkan pemahaman tentang ketiadaan waktu yang telah menjadi judul lakon Kuntowijoyo ini.
Dalam ranah filsafat, waktu menjadi pemikiran Henri Bergson (1859-1941), yang membaginya sebagai temps (“waktu” dalam bahasa Prancis) dan durée (duration., Eng.).
Temps adalah waktu yang terhubung dengan ruang, seperti berapa lamanya waktu dibutuhkan untuk pergi dari “sini” sampai ke “sana”–yakni waktu yang kuantitatif, dapat diukur secara objektif, seperti dalam fisika.
Durée adalah waktu sebagai hakikat kesadaran, dan karenanya tidak dapat diukur secara kuantitatif, karena merupakan kontinuitas yang selalu mengalir dan tiada terbagi–kesadarannya itulah durée, yang ukurannya subjektif, seperti dalam psikologi.
Maka dalam drama ini 15 tahun adalah temps, tetapi bahwa 15 tahun itu terasa “abadi” atau “seperti baru kemarin” adalah durée. Namun karena keadaan-kesadaran yang satu sulit dipisahkan dengan keadaan-kesadaran lain dalam penghayatan subjek, ketika yang kualitatif dimaknai berdasarkan yang kuantitatif, yakni lama atau sebentar berdasarkan ruang dan keluasan, timbul kerumitan psikologis maupun filosofis.
Menurut Bergson, adalah pemahaman atas durée sebagai hakikat kesadaran yang menjadi kunci pencapaian kebebasan, karena kebebasan hanya dapat dialami–bukan dibuktikan atau dianalisis. Gerak, perkembangan, dan peralihan terus-menerus, sebagai kesadaran dinamis dan kreatif, dialami subjek dalam kebebasannya–tetapi tidak berarti setiap perbuatan manusia itu bebas.
Disebut bebas, jika segenap perbuatannya bersumber dan mengungkap kepribadian. Namun, demikian Bergson, perbuatan manusia lebih sering tidak bebas. Inilah peran determinisme (pandangan manusia tertentukan), bahkan asosiasionisme (kesadaran tanpa peran kebebasan, karena determinasi), ketika yang kualitatif diperhitungkan secara kuantitatif (Bertens 1996, 12-4).
Keadaan inilah yang dihadapi manusia dalam perjuangan untuk menjadi bebas, sehingga dapat diketahui, mengapa cenderung gagal. Dalam drama ini Fatmah tampak secara kualitatif berhasil menjadi bebas dalam durée, karena terlepas dari beban perasaan berdosa, walau dalam temps hidupnya terdeterminasi kegagalan Barda, yang menghitung hari-harinya secara kuantitatif sebagai tumpukan kebersalahan abadi.
Tidak ada waktu bagi Fatmah karena waktu kuantitatif tidak bermakna lagi baginya. Tidak ada waktu bagi Bardas karena waktu kuantitatifnya baru akan berkualitas jika membunuh lagi, yang dengan begitu gagal sebagai pembebasan. Tidak ada waktu bagi Cartas, karena dalam kebebasan kepribadiannya, tidak memiliki kemampuan membangun kualifikasi bebas dalam durée.
Masih dalam ranah filsafat, peran manusia dalam drama ini bisa diuji dengan filsafat eksistensi, dalam hal ini Munib dan Leila, bahkan Sulaiman, berdasar perkacapan tentangnya, dapat dilibatkan.
Tentu boleh dicatat, bahwa eksistensialisme bukanlah aliran filsafat dengan kategorisasi yang ketat; bahkan tersebutkan pula sebagai bukan filsafat, melainkan suatu label bagi sejumlah pemberontakan meluas yang berbeda-beda melawan filsafat tradisional. Dalam keberbedaan itu terdapat persamaan, bahwa masing-masing dari kaum eksistensialis ini–begitulah mereka diberi nama–berbagi dalam individualisme mereka yang buruk.
Apakah yang dimaksud “buruk” ini memang buruk, ketika penjelasannya adalah penolakan terhadap aliran pemikiran apapun, penampikan atas kebercukupan setiap kepercayaan, khususnya sistem-sistem dan terutama tertandai oleh ketidakpuasan terhadap filsafat tradisional yang dangkal, akademik, dan terasing dari kehidupan? Eksistensialisme adalah suatu kepekaan abadi yang dapat dipahami terdapat di sana pada masa lalu; tetapi hanyalah kemudian, mengada sebagai protes maupun keasyikan (Kaufmann 1970, 11-2).
Dalam kombinasi kritik Bergson atas determinisme dan konseptualisasi eksistensialisme Kaufmann, jika menjadi instrumen pemahaman para peran dalam drama ini, dapatlah dikatakan tentang pemikiran filosofis mereka sebagai berikut:
Fatmah. Sikap dan pilihan-pilihannya menunjukkan sikap eksistensialis; bahwa seseorang hanya memerlukan dirinya sendiri, bahwa seseorang harus berani hidup meski bersikap menyerah, bahwa ia memilih dan bukan terpaksa tinggal di hutan, dan bahwa ia bercinta sebagai ungkapan kemerdekaannya. Pilihan eksistensial Fatmah membuat dirinya hidup dalam waktu kualitatif. Lima belas tahun adalah tanpa waktu baginya, dan artinya kematian tidak meniadakan apapun dari waktu kualitatif hidupnya yang eksistensial.
Cartas. Baginya setiap orang dalam kesepakatan itu tidak jujur dan menipu dirinya sendiri. Ia menyadari dirinya penganggur tapi mendapat makan, menghabiskan waktu dengan cara sendiri, menanti kematian–atau perubahan, tanpa usaha apapun. Kesadarannya tidak membuat hidupnya eksistensial, karena tetap menjalaninya secara kuantitatif, sehingga tidak dianggapnya sebagai pembebasan, bahkan merasa tidak berhak mempunyai keinginan. Menyerah adalah kematian katanya, tetapi dirinya hanya tubuh yang bernafas–hanyalah gumpalan perasaan bersalah, sebagai bentuk ketidakmampuannya membebaskan diri, alias tidak mampu menjadi diri sendiri.
Barda. Bersepakat atas kerahasiaan abadi, ia tidak pernah mengatasi waktu kuantitatif, dengan perhitungannya bahwa lolos dari hukum berarti terpenjara selamanya. Untuk mendapatkan hukuman penjara agar perasaannya tenang, ia menjadi pembunuh lagi, menampakkan ketidakmampuan membayar kebersalahannya sebagai penebusan. Padahal kedatangannya ke tempat terpencil, untuk membangun perkebunan apel, sebagai tenaga ahli Sulaiman, berpeluang menjadi tindak eksistensial–demikian pula hubungannya dengan Fatmah, tetapi itu tidak terjadi.
Munib. Pertimbangannya atas segenap peristiwa di perbukitan, menunjukkan kedudukan seorang realis sebagai lawan idealis, yang siap berkompromi atas apapun. Pengetahuan atas dibunuhnya Sulaiman, tidak membatalkan sama sekali penerimaannya atas Fatmah, yang sejak awal dipuja-pujinya karena bersikap mandiri. Pertimbangannya atas waktu jelas kuantitatif, maka baginya berlibur dua minggu adalah kegembiraan, tetapi 15 tahun tak ke mana pun adalah penjara. Ia bukan seorang eksistensialis, karena tidak mau menjadi siapapun, dan hanya mau mengambil keuntungan dari dunia ini.
Leila. Dari caranya membandingkan kota dan perbukitan, dirinya boleh dianggap romantik. Dalam romantisisme, rasionalisme dan empirisisme dihadapkan, jika tidak dilawan, dengan spiritualisme semesta, subjektivisme, dan individualisme yang memberi tempat emosi, serta memuja intuisi. Namun ketika ia berkata, “Kami tidak berpendapat, tetapi berbuat. Atau pendapat kami adalah perbuatan kami”, ia menjadi seorang eksistensialis; tetapi pemahaman waktunya sebatas kuantitatif.
Sulaiman. Hadir melalui kesaksian para peran, bahwa ia memanjakan Fatmah muda dengan segala kemewahan yang mampu diberikannya. Gejala ini berkategori romantik, dan karenanya sebagai idealis (tapi bukan dalam filsafat idealisme) maka dirinya berada di sana, membangun perkebunan apel yang sebelumnya hanya berada dalam kepalanya. Perkebunan itu menjadi representasi kehadirannya. Secara kualitatif dan eksistensial Sulaiman terus hidup. Bahkan perkebunan apel itu sendiri menjadi faktor determinan dalam alur lakon.
Sifat filosofis lakon ini kiranya menjelaskan proposisi etis di dalamnya, bahwa Fatmah tidak tewas tertembak sebagai orang berdosa, melainkan objek pendosa dalam pandangan Barda–yang membunuhnya bukan terutama demi keadilan, melainkan kepentingannya sendiri. Agar dirinya terhukum secara legal, kebersalahannya tertebus, dan jiwanya menjadi tenang.
Dihadapkan kepada filsafat tradisional, Fatmah tampak seperti mendapat hukuman semesta, tetapi kata “dosa” disebut dengan sangat minimal sepanjang lakon. Tiga kali kata “dosa” diungkapkan: sebagai dosa Barda (menembak Sulaiman), oleh Fatmah; dosa Cartas sendiri (saksi yang membisu) oleh Cartas sendiri; oleh Munib, dalam suatu konteks seperti berikut:
MUNIB: Barangkali kita salah memilih tempat berlibur di sini Leila.
LEILA: Tidak, Pap. Teruskanlah! Papi sedang menunjukkan keyakinan, bukan?
MUNIB: Engkau betul, Nona. Papimu sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Tidak kusangka. Sebagai dilempar dalam gelap di hutan itu.
Sendiri. Tidak tahu arah, tetapi harus berjalan juga. Kalau tidak, barangkali binatang buas sedang menunggumu. Atau justru kalau kau bergerak,
akan kau jumpai binatang itu. Di sinilah aku, di perbatasan antara keluasan dan kemerdekaan. Di batas dosa dan ampunan. Di batas kepastian dan
teka-teki. Harus ke mana?
CARTAS: (mengejek) Tuan jadi ragu-ragu!
LEILA. : Itu salah, Cartas!
CARTAS: Aku akan terlibat, Nona. Keputusan ayahmu akan melibat diriku. Seperti juga aku tiba-tiba saja
terlibat dengan hidup ini. Sama-sama terseret! Seseorang tak dapat melepaskan diri dari perbuatan bersama. Orang melangkah, aku melangkah.
LEILA: Orang yang kuat akan lebih dulu dari orang lain. Dan itulah papiku, Cartas!
MUNIB: (menatap anaknya lama) Aku sayang padamu Leila. Engkau terlalu suci untuk melihat kehidupan di sini. Kalau kau bisa menahannya,
jangan kau ingin tahu lebih banyak. Tidak patut bagi gadis macam kau, Leila.
LEILA: Aku sudah mengetahui semuanya, Pap.
Dengan menyebutkannya sebagai “di batas dosa dan ampunan. Di batas kepastian dan teka-teki” terjelaskan keberhinggaan manusia, yang berarti dalam keadaan apapun tidak dapat melampauinya–walau tetap dalam kepenuhan eksistensialnya.
Adalah Leila yang bicara, bahwa apel-apel ajaib dari bidadari Fatmah, kalau dimakan akan (membuat) jatuh cinta. Tentu bukanlah tabu, untuk merujukkannya kepada kisah kejatuhan manusia (the fallible man) gara-gara buah surgawi yang ditawarkan iblis itu–sebagai godaan yang menantang, dan barangkali disyukuri.
Hanya dengan terlempar ke bumi manusia mendapat harkatnya sebagai pejuang kehidupan, dan berpeluang mendapatkan pengetahuan dari titik nol, yang tak satu malaikat dan jin pun mendapat peluang tantangan serupa. Kemanusiaan adalah sumber iri hati iblis yang paling cerdas sekalipun.
Dosa tidak pernah definitif dalam lakon, tetapi lakon ini berada di tengah perkebunan apel, metafor buah dosa yang terlalu menggoda, seperti cinta, yang di balik daya tariknya, terlalu sering menjadi sumber tragedi manusia.

Apel merah, metafor buah cinta, sekaligus godaan bagi pendosa, yang telah ditafsirkan kembali sebagai buah (ilmu) pengetahuan yang godaannya menantang pembebasan. (https://nahwatravel.co.id/kebun-apel-malang)
Kuntowijoyo dan Drama Filsafat
Pada 1972, saat usianya 29 tahun, wacana filsafat eksistensi sedang mengecambah di sekitar Kuntowijoyo. Tahun itu pun bisnis apel lokal berada pada masa keemasan, antara 1970-1980, setelah pemerintah RI memperkenalkannya sejak 1953 (Widianto 2020, https://www.mongabay.co.id/2020/04/30/apel-malang-nasibmu-kini/).

Kuntowijoyo dalam paspor 1973.
Setidaknya dalam susastra Indonesia, filsafat ini selalu disebut-sebut dalam gubahan Iwan Simatupang (1928-1970) yang gaya absurdnya menjulang; dan eksistensialisme menjadi fashion wacana 1970-an, sama seperti dekonstruksi dalam pasca-modernisme pada 1990-an–yang sebagai gejala sosial-politik mendorong ke arah Reformasi 1998.
Di Eropa, walau sejak Nietzsche dan Kierkegaard eksistensialisme sudah melekat dalam pemikiran keduanya, dan bahwa berfilsafat itu bukan suatu profesi, melainkan kehidupan individual, baru setelah Sartre kembali dari Jerman tahun 1933 untuk mempelajari fenomenologi, dikembangkannya filsafat eksistensi yang bersumber dari kehidupan sehari-hari. Sejak 1950-an, eksistensialisme populer sebagai ‘filsafat kafe’ dengan pasangan penyebarnya, Jean-Paul Sartre (Being and Nothingness) dan Simone de Beauvoir (The Second Sex).
Eksistensialisme menjadi sexy melalui perbincangan Sartre atas kebebasan, Beauvoir atas mekanisme penindasan halus, Kierkegaard atas kecemasan, Camus atas pemberontakan, Heidegger atas teknologi, atau Merleau-Ponty atas ilmu pengetahuan kognitif, dengan rasa membaca berita mutakhir. Filsafat eksistensi tetap menarik bukan karena benar atau salah, melainkan karena peduli kehidupan (dunia), dan dalam penanganan atas dua pertanyaan besar manusia: apakah kita? dan apakah yang harus kita lakukan? Sedangkan jawabannya, sebagian besar, bersumber dari pengalaman terstruktur di sekitar filsafat (Bakewell 2016, 44).
Dalam filsafat eksistensi, manusia itu bebas, tapi kebebasannya bukan seperti kemerdekaan gemilang Pencerahan, bukan juga berkah Gusti Allah, melainkan bahwa manusia sendirian di alam semesta, bertanggungjawab atas kondisinya, kemungkinan tetap dalam kondisi rendah, tetapi bebas meraih bahkan yang berada di balik bintang.
Eksistensialisme telah mengembangkan filsafat yang non-politis, dan mereka yang dikenal sebagai eksistensialis telah menempuh arah yang berbeda-beda. Namun yang disebut eksistensialis ini ternyata bukan hanya para filsuf, melainkan juga para penulis susastra seperti Dostoyevski, Rainer Maria Rilke, Kafka, dan tentu saja Camus–yang bersama Sartre mendapat penghargaan Nobel untuk Kesusastraan (walau Sartre menolaknya).
Apa yang dilakukan Camus dan Sartre, dengan roman dan naskah drama, memang menimbulkan pertanyaan: mungkinkah, setidaknya sebagian, apa yang berusaha dilakukan kaum eksistensialis, paling baik dilakukan dalam seni dan bukan filsafat?
Mungkinkah dibayangkan bahwa Rilke dan Kafka, Sartre dan Camus dalam kerja imajinatif mereka mencapai ketinggian yang oleh para filsuf eksistensialis, termasuk Sartre, tapi tidak termasuk esai-esai Camus, tercapai cukup rendah sahaja dalam kegagalan dan kebingungan pada usaha keras mencapai puncak (pemikiran filsafat)? Iya atau tidak, ini merupakan pertanyaan penting yang tidak boleh dihindari pembelajar gerakan tersebut (Kaufman, op.cit., 49).
Sampai di sini, sudah jelas relevansi perbincangannya dengan drama-filsafat Kuntowijoyo. Namun lebih baik dituntaskan dengan persoalan konsep belajar yang diperiksa Deleuze dan Guatarri dalam What is Philosophy ?, ketika menyebut keberadaan otak-mikro (microbrains): Tidak setiap organisme punya otak, dan tidak setiap kehidupan itu organik, tetapi di mana pun terdapat daya-daya yang membentuk otak-mikro, atawa suatu kehidupan anorganik dari segala sesuatu (WP 213/QP 200).
Kehidupan anorganik ini jangan dikacaukan dengan hidup yang sudah digariskan pada spesies hewan, atau bahkan kehidupan organik itu sendiri; melainkan bahwa kehidupan ini adalah substansi problematik tak berhingga–Suatu Kehidupan (A LIFE-sic)–yang memperbolehkan sintesa-sintesa pasif dan kontraksi elemen-elemen bernama “kontemplasi-kontemplasi sunyi”–yang membuat kemunculan dan individuasi entitas tertentu dimungkinkan, organik atau tak organik, hidup atau tidak.
Otak-mikro, ringkasnya, adalah inti kehidupan segala sesuatu, kehidupan yang memungkinkan bagi eksistensi segala sesuatu yang sama sekali sangat menentukan. Dengan menghargai kehidupan sendiri, lebih jauh lagi, kehidupan manusia sebagaimana dihidupi bersama dengan konteks dan keadaan yang pasti; yang bertugas, seperti Deleuze dan Guattari melihatnya, untuk menyarikan Suatu Kehidupan dari kehidupan yang dihidupi manusia, dan ini perlu melibatkan kekacauan melalui retak-retak cakrawala.
Hasilnya adalah kehidupan yang direnungkan, kehidupan yang menyarikan “pemikiran dalam tiga bentuk besar” seperti filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni; atau seperti Deleuze dan Guattari merumuskannya, tugasnya adalah menyarikan “Otak-pikiran” (“Thought-brain”) dari kepastian hidup yang dihidupi:
Filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan bukanlah objek mental dari otak yang diobjektivikasi, melainkan tiga aspek di bawahnya (tempat) otak menjadi subjek, “Otak-pikir”. Ketiganya adalah tiga bidang datar, rakit-rakit tempat otak melompat (ke atasnya) dan melawan kekacauan (WP 210/QP 198).
Sumber-sumber konseptual yang terasosiasikan dengan pembelajaran, tempat kehidupan manusia dipikirkan, yang bukan terdiri dari koordinasi dan komposisi filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni, tetapi lebih sebagai kehidupan, tempat ketiga bentuk ini menjadi tidak dapat dibedakan, dan tempat hidup manusia tidak terpisahkan dari kreativitas, proses belajar yang memungkinkan munculnya bentuk-bentuk pemikiran yang bahkan belum pernah diantisipasi.
Dalam kata-kata Socrates, yang dicatat Plato dalam Apologia, masalahnya bukan sekadar menghidupkan hidup, tetapi membawa perubahan yang perlu untuk menghidupkan kehidupan dengan baik (Bell 2016, 244-6).

Sampul map naskah stensilan di Perpustakaan Jakarta, Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Kiranya menjadi jelas, dalam peta bumi kebudayaan macam apa “Otak-pikiran” Kuntowijoyo Anno 1972 berada. Seperti juga para filsuf yang menulis puisi, roman, atau naskah sandiwara sebagai bentuk pengungkapan filsafatnya, dalam “Tidak Ada Waktu bagi Nyonya Fatmah, Barda, dan Cartas”, Kuntowijoyo memang berfilsafat, sebagaimana tampak dari cakapan para peran, yang berdebat atas nama ideologi masing-masing, tentang kehidupan macam apa yang layak dihidupi dan dihidupkan.
Sangatlah menarik untuk menyadari, bahwa penggubah dalam wacana filsafatnya ini, terhindar untuk memberi penghakiman etis–bukan seperti menghindari tanggung jawab, tetapi dalam seni naratif yang mengalihkannya menjadi tanggung jawab para peran, tempat penghakiman yang dilakukan oleh para peran saling berkontestasi.
Drama ini seperti sengaja dilepaskan oleh penggubahnya, bagaikan peniup balon yang melepaskan balonnya ke langit, agar terbangun sebagai dunia mandiri–tapi tidak, dan memang tidak mungkin, otonom dari dunia di luar panggung itu sendiri.
Perhatikan sekali lagi didaskalia pada naskah:
(Cartas bangkit menatap yang sedang mengurus
Fatmah di jenjang bawah. Mereka tak tampak).
Masih terbuka kemungkinan tafsir, betapa kematian Fatmah tidak dapat dipastikan, sehingga konstelasi etiknya yang serba tak mapan itu pun kembali berubah. Sebagaimana filsafat, pembaca atau penonton terandaikan berpartisipasi dalam pemikiran, karena kata akhir memang tidak pernah dan tidak perlu diberikan.
Dalam iklim teater saat itu di Indonesia, yang mulai mengenal wacana “membebaskan teater dari penjajahan sastra” pada tahap awal, lakon Kuntowijoyo yang mengandalkan kata-kata, sarat dengan beban filsafat pula, dapat menjadi alasan keberjarakannya dari panggung–suatu persoalan yang semestinya menantang kreativitas pemanggungan.
Namun adalah khalayak ilmu filsafat yang akan bersituasi kelas kosong, jika dunia sandiwara ini tetap tinggal dalam ruang dan waktu membisu, bagaikan “Tidak Ada Waktu bagi Kuntowijoyo”.
Pondok Ranji-Kampung Utan,
Kamis, 21 Desember 2023. 20:09.