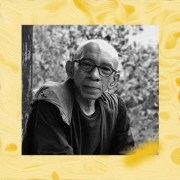Tuhankah Tuhan? The Saturated Phenomenon dan Iman
Oleh Tony Doludea
Manusia dalam kehidupan beriman dan beragamanya itu, pada satu sisi tidak hanya dituntut untuk taat dan setia terhadap Tuhan Allahnya saja. Tertullianus (160-222) mengatakan bahwa seorang beriman kepada Tuhan Allah karena hal itu tidak masuk akal (credo quia absurdum). Namun di sisi yang lainnya Anselmus (1033-1109) dari Canterbury mengatakan bahwa orang yang beriman itu juga memiliki keinginan mendasar untuk memahami imannya itu (fides quaerens intellectum). Salah satu bentuk dasar iman yang mencari pemahaman ini adalah pertanyaan, “Apakah yang dimaksud bahwa Tuhan Allah itu ada? Apa bukti nyata bahwa Tuhan Allah itu ada? Dapatkah manusia memahami fakta-fakta mengenai Tuhan Allah?”
Anthony Flew berusaha menjelaskan persoalan ini dalam suatu ilustrasi bahwa pada suatu hari, seorang filsuf dan seorang teolog yang memang telah lama tidak rukun, entah mengapa, mereka kali ini sepakat untuk berlibur bersama. Mereka mengadakan perjalanan tamasya ke daerah pegunungan. Sampailah mereka berdua itu di sebuah lembah dengan padang rumput hijau membentang dan ditumbuhi bunga-bunga berwarna-warni yang tertata rapih sekali. Sang teolog kemudian berkata, “Lembah ini pasti dirawat oleh seorang tukang kebun yang hebat.” Si filsuf dengan cepat menyergap, “Manalah mungkin ada seorang tukang kebun yang dapat mengurus padang seluas ini?”
Mereka kembali sepakat untuk membuktikan siapa dari antara mereka yang benar. Lalu mendirikan tenda di situ dan mengamati padang itu siang dan malam. Setelah berhari-hari, mereka tidak melihat apalagi menemukan tukang kebun itu. Maka mereka sepakat lagi untuk memasang pagar listrik mengelilingi taman bunga itu. Namun pagar itu tidak pernah bergetar dan terdengar teriakan orang yang tersengat listriknya, atau tanda-tanda sedikit pun bahwa seseorang pernah melompatinya.
Si teolog tetap bertahan, “Tidak mungkin tidak ada tukang kebun itu! Tukang kebun ini pastilah tukang kebun yang tidak dapat ditangkap oleh semua pancaindera manusia.” Suara terakhir yang terdengar dari perkemahan itu adalah jeritan si filsuf, “Apa perbedaan antara tukang kebun yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat diraba dan tidak dapat dirasa dengan tukang kebun yang memang benar-benar tidak ada?” Lembah itu kembali dalam kesunyian dan kedamaian abadinya yang semula.
Dalam konteks seperti itu jugalah Jean-Luc Marion melakukan suatu refleksi filosofis sebagai sebuah bentuk rasa ingin tahunya untuk dapat memahami Tuhan Allah yang diimannya itu. Jean-Luc Marion (3 Juli 1946) adalah seorang professor di Universitas Paris IV Sorbonne dan Universitas Chicago. Dari tahun 1972 sampai tahun 1980 Marion belajar di École Normale Supérieure, Universitas Paris IV Sorbonne dan Universitas Nanterre (University Paris Ouest Nanterre La Défense). Marion belajar Filsafat di bawah bimbingan Jacques Derrida, Louis Althusser dan Gilles Deleuze. Selain belajar Filsafat ia juga mendalami Teologi di bawah bimbingan Louis Bouyer, Jean Daniélou, Henri de Lubac dan Hans Urs von Balthasar. Buku-buku yang diterbitkannya antara lain: God Without Being (1991), Reduction and Givenness: Investigations of Husserl, Heidegger, and Phenomenology (1998), Cartesian Questions: Method and Metaphysics (1999), The Idol and Distance (2001), Being Given: Toward a Phenomenology of Giveness (2002), The Crossing of the Visible (2004), In Excess: Studies in Saturated Phenomena (2004), Descartes’ Grey Ontology (2006), The Erotic Phenomenon (2007), On the Ego and on God (2007), The Visible and the Revealed (2008) dan Descartes’ Grey Ontology (2012).
Dalam menjalankan usaha filosofisnya itu Marion mengajukan pertanyaan penting, yaitu apakah mungkin manusia itu sampai pada suatu fenomen yang bersifat otonom dan absolut tanpa terkondisi dan terreduksi oleh intuisi subjek. Apakah memang ada Fenomen Yang Utuh-Penuh (the saturated phenomenon), yang mandiri dan yang terlepas dari subjek sama sekali. Pertanyaan Marion ini diletakkan dalam kerangka Fenomenologi Edmund Husserl (1859-1938). Husserl berusaha untuk mengatasi dualisme dan dikotomi antara subjek (noesis) dan objek (noema) dan bertekad untuk mengatasi fenomenalisme Kant yang percaya bahwa manusia hanya bisa sampai pada fenomen saja dan tidak mungkin mencapai noumena (das Ding an sich/thing-in-itself). Husserl secara kritis melalui metode fenomenologis itu berusaha membawa manusia untuk sampai pada hakikat kenyataan, orang harus membiarkan objek itu berbicara langsung dengan sendirinya, kembali ke benda-benda itu sendiri (Zuruck zu den Sachen selbst!, To the things themselves!).
Bagi Fenomenologi pengetahuan itu selalu bersifat intensional, yaitu terjadi kerjasama dan interaksi antara subjek dan objek, bahwa objek kesadaran adalah fenomen, yaitu sesuatu yang menampakkan diri kepada subjek. Fenomenologi adalah filsafat yang bersifat deskriptif dan ketat (rigorous). Slogan Fenomenologi adalah kembali ke benda itu sendiri (Zu den Sachen! To the things themselves!) yang mengungkapkan tekad untuk keluar dari ilusi teoritis serta konsep idealisme dan rasionalisme. Keluar dari Filsafat yang bersifat redukstif dan masuk ke dalam intuisi langsung dan deskripsi fenomen sebagaimana ia menampakkan dirinya secara langsung melalui pengalaman lebenswelt (dunia kehidupan) manusia.
Pendekatan atau metode Fenomenologi menekankan pemahaman manusia sebagai mahluk yang ada di dalam dunia pengalaman hidup (lebenswelt) dan ada yang alamiah, bukannya berada hanya dalam pemikiran yang abstrak. Pendekatan fenomenologis ini sangat menjunjung tinggi segala pikiran, perasaan, keberadaan historis, kultural dan intersubjektifitas manusia dalam proses pembentukan struktur dan prosedur filosofis Filsafat. Husserl melalui Fenomenologinya itu tetap mendesak untuk kembali sampai kepada things themselves. Melalui suatu penundaan (epoché) fenomenologis Husserl berusaha menjelaskan perbedaan, kerumitan dan kekayaaan pemahaman pengalaman hidup manusia. Meskipun demikian, sesungguhnya penemuan Fenomenologi ini, yakni bahwa fenomen itu adalah self-manifestation, sebetulnya sudah ada dalam filsafat Yunani pada taraf yang lebih fundamental, yaitu bahwa Ada itu sendiri menampakkan diri. Ada itu tidak tersembunyi.
Melalui reduksi transendental fenomenologis itu, Husserl akhirnya tiba pada subjek yang menyadari kesadarannya tentang kesadarannya itu (noesis). Husserl meyakini bahwa ada hubungan intensional yang saling mengandaikan antara fenomen (noema), yaitu objek yang disadari dengan tindakan kesadaran subjek (noesis). Meskipun demikian bagi Husserl dari pengandaian ini tidak dapat disimpulkan adanya suatu interaksi dan kerjasama antara dua unsur yang sama pentingnya itu. Namun yang ada pada akhirnya hanya noesis saja, dan noema itu hanyalah suatu hasil ciptaan kesadaran subjek belaka. Husserl kembali kepada subjek yang substansial dan transendental sebagaimana diwariskan oleh para filsuf sebelumnya.
Namun Martin Heidegger (1889-1976) secara ontologis melihat bahwa Husserl telah mengabaikan noumena dengan memandang fenomena sebagai realitas apa adanya. Heidegger mentransformasi korelasi transendental Fenomenologi Husserl itu, yaitu bukan lagi korelasi antara noesis dan noema lagi, melainkan menjadi korelasi antara dunia kehidupan (lebenswelt) dan bentuk modalitas dunia (Umwelt, Mitwelt dan Selbswelt). Modalitas dunia ini dapat dimasuki hanya di dalam dan melalui fakta pengalaman hidup nyata (factical life-experience). Fakta pengalaman hidup nyata ini merupakan dunia kehidupan yang meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia dengan tidak membiarkan sedikit ruang pun tersisa.
Pada titik ini juga Marion menemukan adanya suatu kontradiksi dalam pikiran Husserl itu. Dalam pikiran Husserl fenomen tidak lagi memiliki cara asali untuk menghadirkan dirinya sendiri. Dalam reduksi ketiganya itu, yaitu reduksi transendental, Husserl tidak dapat menjelaskan secara tuntas mengenai struktur fenomenalitas. Menurut Marion, prinsip dasar Fenomenologi Husserl menciptakan suatu kontradiksi di dalam dirinya sendiri. Olen sebab itu Fenomenologi ini harus memikirkan ulang struktur fenomen dalam kaitannya dengan intuisi subjek.
Marion meradikalisasi lebih jauh lagi pandangan Husserl ini supaya membebaskan dan memulihkan fenomen sekaligus menolak unsur apriori bagi penampakan fenomen itu. Memang Husserl berpendapat bahwa Fenomenologi mengakui fenomen itu terberi kepada kesadaran (given to the consciousness) bukannya terberi oleh kesadaran (given by the consciousness). Melalui hal inilah Marion ingin menyelamatkan kemungkinan bagi fenomen untuk menampakkan dirinya sendiri dengan bebas secara utuh penuh tanpa sentuhan subjektif manusia sama sekali.
Dari sinilah Marion kemudian memungut dan mengangkat gagasan mengenai keterberian itu (Gegebenheit, givenness) dan memulai penyelidikannya atas peristiwa pemberian ini, di mana keberlainan itu (otherness) mampu melampaui subjek dalam bentuk fenomenalitas dari sesuatu yang sungguh-sungguh beda, sebagai yang sungguh-sungguh lain (absolutely other), misalnya Allah. Apabila Heidegger telah berjalan melampaui Husserl dengan mengatakan bahwa fenomen itu tidak menampakkan dirinya sendiri secara langsung, namun sebagai sasaran tindakan intensional kesadaran manusia. Heidegger telah berusaha melangkah melampaui konstitusi manusia.
Tetapi Marion ingin melangkah lebih jauh lagi, yaitu sampai pada suatu fenomen yang menampakkan dirinya sendiri secara maksimal dan sungguh-sungguh otonom. Marion mempertanyakan mungkinkah ada fenomen yang tak terkondisi sama sekali, tak terreduksi dan otonom. Suatu fenomen yang tidak dapat direduksi kepada ego dan tak terkondisi oleh intuisi, yang melampaui ikatan konseptual, kategori dan batasan intensonalitas. Fenomen ini oleh Marion disebut sebagai the saturated phenomenon, Fenomen Yang Utuh-Penuh.
Marion mencatat bahwa Fenomen Yang Utuh-Penuh itu melampaui intuisi dan transenden terhadap kategori atau konsep murni pengetahuan, bahkan berjalan jauh sampai kepada kontradiksi dengan intuisi manusia. Fenomen Yang Utuh-Penuh ini dapat dialami tetapi berada di luar segala bentuk pemahaman kategoris yang menjadi ukuran dan pembentuk intuisi. Namun Fenomen Yang Utuh-Penuh ini hanya dapat dikaitkan dengan kategori modalitas (mungkin atau tidak mungkin, aktual atau tidak aktual dan niscaya atau tidak niscaya) dan melampauinya.
Dalam pandangan Kant kategori-kategori ini tidak menentukan objek pikiran manusia, melainkan mengungkapkan hubungan objek tersebut dengan bagian-bagian pemikiran manusia. Kategori modalitas hanya menggambarkan keadaan pemahaman tentang fenomen (objek) dan membuat keputusan mengenai kemungkinan, aktualitas dan keniscayaannya. Fenomen itu aktual jika sesuai baik dengan keadaan formal dan material pengalaman manusia.
Namun Fenomen Yang Utuh-Penuh ini adalah suatu fenomen yang tidak dapat diobjektifikasikan, tetapi membuat dirinya menjadi mungkin melalui keterberian yang luar biasa melimpah (overwhelming givenness). Ia tidak dapat dipahami meskipun dapat dilihat. Bagi Marion, pewahyuan adalah pemenuhan dari pemenuhan ini. Pewahyuan ini secara kategorial dipusatkan menjadi empat kelompok, yaitu tidak terlihat secara kuantitas, tidak terpahami secara kualitas, absolut secara relasi dan tak terlukiskan (irregardable) secara modalitas. Fenomen Yang Utuh-Penuh ini adalah suatu bentuk pengalaman yang melampaui ikatan batas-batas konseptual, kategorial dan batasan intensional. Fenomen Utuh-Penuh ini adalah suatu pewahyuan dan bersifat paradoks.
Marion menyadari bahwa dalam struktur intensionalitas Husserl keberlainan absolut tidak dapat diterima, bukan karena cara berpikir Husserl yang menghubungkan antara kesadaran subjek dengan objek yang disadari sebagai sesuatu yang terberi bagi kesadaran itu. Namun karena keadaan keterberian itu (Gegebenheit) dianggap lebih rendah daripada reduksi.
Posisi Husserl ini tidak mampu melampaui pandangan Kant yang menyatakan bahwa manusia hanya mampu sampai pada pengenalan realitas fenomenal saja, dan tidak mungkin memahami hakikat noumenal suatu realitas. Jadi keterberian Husserl masih terkondisi oleh subjektifitas dan tidak bebas dari reduksi egologi, maka Husserl kehilangan otonomi keterberian itu di hadapan ego. Kesadaran manusia tentang fenomen terkait erat dengan pemahamannya tentang hakikat fenomen itu sejajar dengan kemungkinan fenomen itu sendiri terberi sebagai sesuatu yang terberi kepada ego, yaitu sesuatu yang diterima ego dari luar dirinya sendiri, yang ada secara mandiri dari bentuk-bentuk pikiran subjek yang menangkapnya. Oleh sebab itu Marion ingin memikirkan ulang struktur fenomenalitas dalam kaitannya dengan intuisi subjek.
Di sini Marion sudah mengandaikan bahwa the saturated phenomenon itu ada dan hadir sebagai suatu fenomen yang luar biasa (extraordinary) yang bersifat tidak dapat direduksi (irreducibility). Untuk mengatasi masalah ini Marion masih menggunakan ulang gagasan Husserl tentang keterberian (Gegebenheit). Bagi Husserl intuisi langsung adalah prinsip segala prinsip dan kriterium terakhir Filsafat. Intuisi ini adalah kesadaran langsung yang terberikan kepada subjek. Karena hanya apa yang secara langsung terberikan kepada subjek dalam pengalamannya dapat dianggap benar sejauh terberikan.
Melalui konsep keterberian ini Marion berusaha melepaskan fenomen dari pengkondisian subjek, supaya subjek tidak dapat memiliki dampak atas fenomen lagi, sehingga fenomen dapat mewujudnyatakan dirinya sendiri. Hal ini berarti subjek menghargai hak suatu fenomen untuk mengungkapkan dirinya secara bebas, dan mempersilahkan transendensi keterberian bebas dari imanensi subjek (let it flows).
Jika fenomen itu mampu mengungkapkan dirinya sendiri, hal ini berarti bahwa intuisi menjadi miskin dan kurus, tanpa suatu konsep yang memadai untuk merepresentasi secara konseptual dan benar juga bahwa setiap fenomen itu hadir sebagai kenyataan yang berbentuk keberlaian yang mendasar (radical otherness). Hanya jika subjek mampu menjaga jarak dari keberlainan itu, maka hal ini menjamin kemampuan fenomen itu untuk mengungkapkan dirinya sendiri.
Melalui refleksinya ini Marion ingin mengajukan pilihan bahwa pengetahuan manusia tentang Tuhan Allah itu pada satu sisi adalah sebuah Keterberian (Gegebenheit) melalui pembatasan pewahyuan Diri Allah itu sendiri, sementara itu di sisi yang lain manusia memang memiliki keterbatasan pengetahuan, bahasa dan sejarah untuk memahami Tuhan Allah, namun sekaligus memiliki iman yang merupakan tanggapan pembatasan Diri Tuhan Allah yang terberi itu, yang bersifat melampaui keterbatasannya tadi.
Pengetahuan manusia tentang Tuhan Allah itu merupakan bentuk Keterberian (Gegebenheit) berupa pembatasan Diri Allah sendiri. Pengetahuan manusia tentang Allah itu adalah suatu hal yang terberikan (Geben), yang melampaui reduksi kognitif dan jangkauan intuisi manusia. Oleh sebab itu, usaha manusia untuk merepresentasikan Allah melalui pikiran, Ada (Being) dan moralitas, yaitu membatasi Allah dengan hal yang bukan Diri-Nya adalah suatu bentuk pemberhalaan Allah. Menurut Marion, manusia tidak menentukan Allah melalui pemahamannya, namun Allah-lah yang menentukan Diri-Nya melalui pandangan ikonik-Nya itu kepada manusia.
Dalam bukunya God Without Being, Marion menantang tradisi metafisika secara umum dan teologi secara khusus. Bagi Marion sejauh ini baik Teologi maupun Filsafat sama-sama telah jatuh ke dalam penyembahan berhala (idolatry) konseptual, yaitu dengan cara memahami Tuhan Allah itu sebagai Ada (Being). Pada saat yang sama, di titik ini Marion juga sedang mengusahakan cara berpikir tentang Allah yang bebas dari pemberhalaan tersebut (idolatry). Berpikir tentang Tuhan Allah yang sungguh-sungguh menghormati Allah, mengakui keberlainan-Nya yang absolut.
Marion berusaha terlepas dari cara berpikir metafisis dan onto-teologis yang bersifat idolatry itu. Berhala (idol) adalah suatu bentuk tiruan, gambar palsu tentang Allah. Karena berhala tidak mampu menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin dia hasilkan. Berhala adalah suatu pengganti yang bersikap seolah-olah dan berpura-pura seperti apa yang sebenarnya bukan dirinya sendiri yang diwakilinya itu. Berhala adalah suatu reduksi pikiran manusia tentang Allah. Sementara itu di sisi yang lainnya, ikon (icon) mampu mempertahankan jarak yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Namun jarak dan pemisahan transendental ini tidak berarti bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk bertemu dan mengalami Allah. Dalam melampaui tradisi onto-teologi dan fenomenologi yang masih mengikat ontologi, Marion berusaha membebaskan Tuhan Allah dari paksaan pemberhalaan ontologis, yaitu Allah sebagai substansi (ousia).
Marion ingin menarik Allah keluar dari cakrawala ontologis dan menyatakan bahwa Allah tanpa Ada itu adalah suatu Pemberian Kasih. Marion berusaha menyelamatkan Tuhan Allah dari reduksi subjek-objek Husserl dan reduksi pemberian Ada dalam Ereignis Heidegger, yang sesungguhnya bukan pemberian asali karena ia masih tunduk kepada keadaan sebelumnya, yaitu perbedaan ontologis yang tidak dapat direduksi ke dalam hubungan antara Ada (Being/Sein) dan Mengada (being/Seiende). Teologi dan Filsafat akhirnya harus bekerja sama satu dengan yang lainnya sedapat mungkIn supaya saling melengkapi dalam mengatasi persoalan mengenai apa yang tidak dapat diketahui oleh masing-masing pihak.
Marion membedakan antara idol (Kualitas) dan icon (Modalitas). Meskipun baik idol dan icon itu sendiri sama-sama bukan Ada (Being) tetapi hanya menunjuk kepada suatu cara beradanya Ada (Being). (1) Suatu idol (berhala) berkaitan dengan penglihatan dan hal yang dapat dilihat. Idol berusaha menangkap sesuatu yang lain dan unik dari Yang Ilahi. Idol itu menjadi nyata terlihat bukan karena diri idol itu sendiri, melainkan oleh pandangan manusia terhadap idol itu. Seperti patung di kota Athena sesungguhnya hanya sebagai objek untuk dipandang saja. (2) Tindakan sadar manusia terhadap idol yang dipandangnya itulah yang memberi kekuatan yang membuatnya berkuasa. Yang Ilahi diantropomorfiskan oleh pandangan manusia atas idol, karena manusia itu sendiri yang memutuskan bahwa idol yang dilihatnya itu lain dan unik. Manusia menciptakan keilahian idol itu. Tuhan Allah jadi terperangkap oleh pandangan manusia. Allah menjadi hanya suatu konsep di mana seseorang itu dicengkeram dan dikurung oleh pemahamannya sendiri. Allah dikerdilkan ke dalam kategori konseptual dan pemahaman manusia. Allah tidak menjadi sebagai Diri-Nya sendiri lagi. Pikiran dan gagasan manusia tentang Allah telah menjadi berhala. Tuhan Allah dibuatnya menjadi suatu gagasan, suatu Allah. (3) Tidak seperti idol, icon tidak memiliki asal-usul, karena keberadaan dirinya itu berasal dari ketiadaan asal-usul. Icon tidak dicengkeram oleh pandangan manusia. Icon berusaha menghadirkan apa yang secara hakiki tidak dapat dihadirkan, ia berusaha membuat terlihat apa yang tidak dapat dilihat. (4) Melalui icon, Yang Ilahi itu memandang manusia dan manusia dipandang-Nya atasnya. Yang Ilahi memandang kerahasiaan manusia yang tak terukur dan melampaui pemahaman konseptual. Manusia terrahmati oleh suatu hadirat Yang Ilahi. Seperti suatu gambar icon (ikonografi), sang seniman hanya menjadi suatu alat Yang Ilahi untuk mengungkapkan Diri-Nya. Si seniman hanya suatu alat penyataan (wahyu) Ilahi yang berusaha mengungkapkan Diri-Nya dalam gambar-gambar tersebut. Bagi Marion penyembahan berhala itu (idolatry) bukannya manusia memahami salah atau berilusi tentang Allah. Justru sebaliknya, ia menganggap diri sebagai terang yang sungguh memantulkan Allah. Berhala membekukan Tuhan Allah dalam pemahaman, kepentingan dan tujuan manusiawi, sehingga ia selalu merupakan cermin di mana manusia melihat dirinya sendiri. Dalam berhala itu manusia tidak akan pernah meraih dan sampai kepada Allah kekal yang tak terbatas itu. Marion dengan menggunakan pendekatan fenomenologis mengajak Filsafat dan Teologi untuk memahami Allah tanpa suatu pengkondisian, untuk memahami Allah bukan sebagai sesuatu yang ada (being), bahkan tanpa Ada (Being) sekalipun.
Oleh sebab itu bagi Marion Tuhan Allah itu tidak dapat dipahami dalam arti kategori tradisional Ada, karena hal ini telah mereduksi Allah ke suatu konsep terlalu manusiawi yang disebut ilahi. Reduksi ini merupakan suatu kekerasan terhadap Tuhan Allah. Ia menyatakan bahwa Tuhan Allah itu harus dipahami di luar perbedaan ontologis (the ontological difference) dan di luar pertanyaan tentang Ada (Being) itu sendiri. Manusia telah membatasi Allah melalui konsep pemahamannya (ego transendental Kant).
Karena itu AlIah tidak dapat diperlakukan dengan membatasi-Nya dengan konsep pengetahuan seperti itu. Allah “telah terlebih dahulu ada” dan terberi bagi pemahaman manusia melalui pewahyuan/penyataan/pengilhaman. Bagi Marion Tuhan Allah tanpa Ada itu (God Without Being) adalah bukannya bahwa Allah itu tidak ada, melainkan Allah yang tanpa kondisi (the saturated phenomenon). Allah itu tidak ada untuk manusia (God is not “there” to us), namun Allah ada demi manusia itu sendiri (God is “there” for us).
Pada “keadaan asalinya” Allah itu tidak terkondisi oleh pikiran manusia. TUHAN Allah itu terberi (Geben). Dengan memahaminya seperti ini maka manusia membebaskan diri dari penyembahan berhala konseptual yang mereduksi Allah ke dalam konsep pikiran manusia yang sempit ini. Beberapa dari antara teolog dan juga filsuf ada yang yakin bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk memahami Allah secara pasti (apodiktis) dan total (absolut), misalnya Hegel. Sementara yang lainnya menemukan bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk dapat memahami Allah, misalnya Kant, Heidegger dan Derrida.
Pelajaran yang dapat diambil dari Keterberian Marion ini adalah bahwa apabila manusia ingin dapat memikirkan Keterberian itu, yaitu Fenomen Yang Utuh-Penuh itu, ia harus mampu keluar dari kekuatan subjektifitasnya. Fenomen ini memberikan dirinya kepada subjek tanpa disadari oleh subjek melalui batasan apriori yang terberikan atau juga oleh tindakan-tindakan yang mendahuluinya. Hal ini berarti bahwa manusia harus keluar dari pandangan dan arahan subjektif yang sudah ada. Hanya dengan cara ini sajalah Fenomen Yang Utuh-Penuh ini menampakkan diri oleh dan dalam dirinya sendiri sebagai dirinya sendiri. Hanya dengan demikian kemungkinan untuk memahami Keterberian itu sebagai pemberian yang asali menjadi mungkin.
Proses pemahaman ini tidak bergantung pada hukum ego, bahkan pada ego murni yang menjalankan epoche fenomenologis itu. Kesadaran itu memberikan dirinya sendiri oleh dirinya sendiri kepada kesadaran dan menampakkan dirinya di hadapan segala sesuatu yang lain, bukan sebagai kesadaran, namun sebagai rahmat bagi kesadaran, sebagai suatu kemungkinan bagi kesadaran itu sendiri, sebagai kesadaran di dalam tindakan kesadarannya sendiri.
Berkaitan dengan Teologi, Marion menyatakan bahwa TUHAN Allah merupakan keterbukaan kepada umat manusia. Pewahyuan Diri Allah kepada manusia selalu lolos dari segala bentuk kesadaran egologi manusia. Semakin banyak dan semakin lebih fenomenalitas dan pemberian yang disediakan oleh Allah yang melampaui ruang pemahaman manusia akan menciptakan tirai bagi konsep Allah dalam pemahaman manusia yang merupakan pemenuhan fenomenalitas-Nya. Pewahyuan Allah itu sungguh-sungguh terlepas dari kesadaran intensional manusia. Manusia selalu mencari Allah, namun ia tidak dapat menemukan-Nya hanya karena memang Dia adalah Allah, bahkan dalam keheningan sekalipun, dalam ketiadaan-Nya, dalam jarak yang absolut, Dia selalu sudah “ada di sana” bagi manusia, mendatanginya, mambuat Diri-Nya nyata.
Kenyataan yang terasa aneh adalah bahwa pemahaman manusia tidak dapat berhenti di hadapan Pewahyuan itu, mata manusia tidak akan bertahan menatap TUHAN Allah, karena sinar manifestasi-Nya itu terlalu kuat bagi manusia. Dari sudut pandang ini maka hanya imanlah yang dapat menyatakan apa yang tidak dapat dicandra oleh kesadaran manusia. Sampai di sini lalu Marion rela membiarkan Teologi untuk tetap mengaitkan dirinya pada Wahyu Ilahi, sementara dirinya yang adalah seorang Fenomenolog hanya ingin menggambarkan cara yang memungkinkan bagi Allah sebagai Fenomen Yang Utuh-Penuh.
Pandangan Marion ini tentu saja tidak baru sama sekali dan tidak jauh bedanya dengan pemikiran Karl Rahner (1904-1984) sebelumnya. Rahner dalam usaha Teologinya yang mengalir dari Antropologi itu didasarkan atas keyakinan bahwa sesungguhnya umat manusia itu secara hakiki memang terarah kepada Yang Ilahi. Manusia secara alamiah memiliki keterbukaan kepada pengalaman tentang Allah. Oleh sebab itu tidak keliru apabila di sini diterapkan Fenomenologi Agama, yaitu suatu kajian tentang tindakan-tindakan religius yang dilakukan manusia sebagai tanggapannya terhadap penyataan Yang Ilahi itu.
Tindakan-tindakan religius seperti ritus, kultus, beribadah, sakramen, bertobat, berdoa, bersyukur, memohon, berkesenian dan hidup etis. Dari kajian ini kemudian secara tidak langsung akan menjawab pertanyaan tentang hakikat, sifat Yang Ilahi, yaitu sebagai Yang Absolut dan Yang Kudus, dan cara bagaimana Yang Ilahi itu menyatakan Diri-Nya.
Dasar Antropologi Rahner ini adalah Vorgriff, yaitu bahwa manusia itu memiliki pemahaman tentang Allah dalam bentuk pra-pengetahuan yang ada di dalam diri setiap orang. Vorgriff ini melekat dalam sifat dasar manusia yang membuatnya dapat menanyakan dan mempermasalahkan tentang Yang Ilahi itu meskipun dalam bentuk yang kabur dan belum bersifat refleksif. Allah yang tersembunyi dan tak terpahami itu dialami sebagai cakrawala yang tak terbatas dan secara sepintas nyata dalam pengetahuan tentang realitas yang konkret. Kemampuan manusia untuk dapat menerima penyataan Yang Ilahi itu termeterai di dalam dirinya sebagai rahmat/anugerah.
Rahmat ini bersifat dinamis dan merupakan pengomunikasian diri pribadi TUHAN Allah. Rahner menyebut rahmat ini oleh sebagai pengalaman langsung tentang Allah, meskipun pengalaman ini dengan cara yang implisit dan tidak bertema/berjudul/bernama. Rahner menekankan pengalaman tanpa tema dan pra-pengetahuan yang asali itu sebagai pengalaman dasariah tentang Allah yang mendasari semua pengalaman lainnya tentang Allah. Pengalaman ini adalah sebuah pengalaman hidup biasa yang terkubur dalam di dalam kegiatan manusia sehari-hari dan karena tidak bertema, ia seringkali tak terlihat dan tak teramati. Pengalaman ini tidak disadari secara objektif. Pengalaman ini merupakan suatu misteri yang tak terselami dan bermukim di dalam kebisuan. Pengalaman ini membuat TUHAN Allah tetap menjadi Allah, menjadi Allah yang memberikan suatu pemberian misterius yang tidak lain adalah Diri Allah Sendiri.
Vorgriff selalu mencari kepenuhan dirinya dan tidak akan pernah berhenti meskipun ketika hakikat -sebagai suatu konsep manusia yang tertinggi- memenuhi dan melampauinya. TUHAN Allah tetap tinggal menjadi suatu rahasia yang murni, yang tidak pernah diketahui dan terungkapkan. Manusia harus memelihara supaya rahasia ini selalu tetap aman sebagai rahasia yaitu dengan cara mengakui bahwa sebenarnya tidak ada rahasia apa-apa tentang Allah, agar rahasia ini tetap tak diketahui sehingga terus menjadi suatu rahasia murni. Demikian juga dengan TUHAN Allah yang tidak ada, yang tidak bernama dan yang tidak hadir itu untuk tetap terus menjadi Allah.
Tentu saja pandangan Rahner ini berasal dari pemikiran Heidegger tentang fakta pengalaman hidup (factical life-experience). Fakta Pengalaman Hidup ini meliputi: (1) melakukan tindakan yang dialami (aktif), (2) yang dialami melalui tindakan (pasif). Mengalami tidak berarti menyadari sesuatu hal (taking-cognizance-of) tetapi berhadapan dengan (confrontation-with). Fakta Pengalaman Hidup di sini tidak berarti harus sungguh nyata ada dan terjadi, melainkan suatu bentuk pengalaman yang berada di dalam wilayah berbahaya, yaitu di luar pra-anggapan epistemologi dan ilmu pengetahuan.
Fenomenologi Marion memiliki suatu karakter teologis yaitu bahwa Penyataan /Pewahyuan itu adalah suatu bentuk pertama dan utama fenomenalitas yang absolut dan tak terkondisi, yang memperlihatkan rahmat Tuhan Allah kepada umat manusia. Melalui paradigma kemungkinan formal saturated phenomenon tak bernama ini Marion mengajak orang untuk menyadari bahwa Penyataan Allah itu bukan suatu objek tetapi sebagai rahmat, pemberian (Gegenstand) dan hal ini menghindarkan orang untuk membuat Allah sebagai suatu objek atau berhala (idol).
Oleh sebab itu tidaklah heran jika Marion berusaha mendesak Heidegger untuk keluar dari kerangkeng tradisi cerita tentang Ada. Marion menolak kesimpulan Heidegger bahwa peristiwa (event/Ereignis) yang mengungkap Ada juga membuka dimensi penyingkapan Allah, meskipun hal ini tidak dapat diidentifikasikan dengan Allah sendiri. Ada dan peristiwa yang mengungkap Ada itu bersifat tidak niscaya sehingga tidak mampu mengungkap Allah Yang Tak terbatas. Tetapi bagi Marion peristiwa ini tetap mengandung suasana teologis yang mengungkap bahwa peristiwa ini ditafsirkan sebagai penciptaan ilahi.
Bagi Marion Filsafat itu bersifat memberhalakan (idolatrous), yaitu ketika Filsafat memastikan suatu konsep sebagai dasar pemikiran. Heidegger telah membongkar kesalahan ini dengan mengakui bahwa tidak ada yang lain di luar pemahaman tentang Ada. Namun Marion mendesak kemungkinan pemikiran tentang Allah sebagai rahmat tanpa kondisi. Justru Heidegger berusaha menolak berpikir di luar dan keluar jangkauan apa yang ada dan muncul untuk menghormati ketersingkapan yang tidak dapat direduksi ke dalam bahasa.
Marion berusaha membebaskan agama dari pengkondisian filosofis dengan meletakkan agama itu di atas pengandaian bahasa dan Ada dan kembali kepada peristiwa rahmat itu sendiri. Namun kelihatannya justru Marion nampak tidak cukup radikal daripada Heidegger karena dia hanya kembali dan mengulang lagi asumsi filosofis bermasalah sebelumnya yang telah berhasil dijungkirbalikkan oleh Heidegger itu. Seperti seekor anjing yang kembali berputar-putar mengejar ekornya sendiri, sementara Heidegger telah berhasil menyadarkan manusia bahwa itu hanya pikiran (ekor)-nya sendiri saja.
Rupa-rupanya usaha fenomenologis Marion ini hanya mengulang kembali skandal Kant, yang menyelundupkan klaim-klaim teologis ke dalam metode ketat Husserlian yang diterapkannya itu. Agama manusia ini belum berhasil membebaskan dirinya sendiri dari penindasan dan belenggu perbudakan dikotomi ilusif antara iman dan rasio. Dikotomi ilusif ini merupakan hasil dari proses Helenisasi pengalaman hidup Yudeo-Kristenitas tentang Yang Ilahi oleh Bapa-Bapa Gereja sejak paruh kedua Abad II Masehi sampai pada Abad Pertengahan.
Meskipun Marion telah sempat mengatakan bahwa Allah itu tidak dapat dinamai, dipredikasi dan diungkapkan dengan kata-kata. Namun Marion dan para pemikir ini mungkin harus belajar ulang kepada Lao Tzu (604-500 SM). Di dalam Tao Te Ching, Lao mengatakan bahwa, “Jalan yang dapat dijalani bukanlah jalan. Nama yang dapat dinamai bukanlah nama.” Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa orang yang dapat membicarakan dan menjelaskan tentang seluk beluk Allah itu justru telah berhasil membuktikan ketidaktahuannya sama sekali tentang Allah.
Pada masa Dinasti Sung (960-1279), saat itu Perdana Menteri Chang Shang-Yin sangat dikenal sebagai orang yang mati-matian menentang Buddhisme. Shang-Yin banyak menulis untuk menolak agama itu dan menghabiskan tiap malam untuk menyempurnakan usaha luhurnya ini. Istrinya yang telah lama mengamati usaha keras dan perjuangan obsesif suaminya itu, bertanya, “Apa yang sedang engkau lakukan?” Shang-Yin menjawab, “Buddhisme ini sangat menjengkelkan sekali. Aku sedang berusaha membuktikan bahwa Buddha itu tidak ada!” Istrinya itu lalu berkata, “Aneh sekali engkau ini! Jika engkau mengatakan bahwa tidak ada Buddha, mengapa repot-repot menentang Buddha? Seperti memukul udara kosong saja.” Ucapan istrinya itu kemudian membuatnya sadar.
Kitab Dhammapada mengatakan, “Pikiran adalah pelopor segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya.” Sehingga tidak begitu meleset jika kemudian film Being There (1979) mengatakan bahwa, “Life is a state of mind.” Sementara itu dalam kumpulan tulisan Ki Dalang Sri Mulyono di situ disebutkan bahwa mencari kasunyatan itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka. Kasunyatan yang dicari dan diusahakan oleh seseorang itu hanyalah merupakan kasunyatan yang palsu, yang semu, yang merupakan pantulan citra diri manusia itu sendiri saja. Mencari dan mengusahakan pengertian tentang Yang Ilahi itu adalah sebuah kesia-siaan karena manusia mencarinya dengan menggunakan sebuah alat, yaitu pikirannya yang penuh dengan amarah, dengki, dendam, ambisi, keserakahan, sekakar, kecongkakan dan kesombongan. Yang Ilahi, yang dicari oleh manusia ini sesungguhnya tidak ada bedanya sama sekali dengan mengingini kesenangan, keselamatan dan keamanan. Jaminan batiniah akan kenyamanan itu tentu saja bukan kasunyatan. Untuk itu Kabir (1440-1518) membagikan pengalamannya tentang Yang Ilahi itu melalui bait syair:
Ke manakah engkau mencari-Ku wahai manusia
Aku sangatlah dekat, dekat sekali kepadamu
Tidak juga di tempat kudus, Aku
Juga tidak di kuil ilah-ilah
Tidak juga di tempat terpencil Aku tinggal
Aku sangatlah dekat, dekat sekali kepadamu
Aku tidak diam di bait atau di masjid
Tidak juga di Ka’bah atau di Kailash
Aku tinggal sangatlah dekat, dekat sekali kepadamu
Tidak di dalam pengasingan diri atau meditasi, Aku
Tidak dalam perayaan atau puasa, Aku
Tidak dalam penyembahan seperti yang tertera dalam Kitab Suci
Tidak dalam yoga, Aku
Aku katakan kepadamu manusia, bila engkau tulus mencari-Ku
Aku sudah ada di sisimu
Kabir berkata, Oh Shadu dengarlah baik-baik
Di mana imanmu berada di situ Aku ada
(D. N. Das, Mystic Songs of Kabir. Shakti Malik Abhinav, New Delhi, 1996, 17.)
Oleh sebab itu, mengenai masalah pemahaman manusia tentang TUHAN dan iman kepada TUHAN sebagai Allah ini, Marion dan para pemikir lainnya itu kiranya mampu bersama dengan Lao Tzu mengatakan bahwa, “Yang tahu tidak bicara. Yang bicara tidak tahu.” Seperti Wittgenstein juga mengatakan bahwa, “Apa yang seorang tidak dapat katakan, harus dibiarkan dalam diam.” (Ludwig Wittgenstein. Tractatus Logico-Philosophicus. Kegan Paul, London, 1922, 111.)
Tao adalah keheningan
kata-kata
tidak dapat menangkapnya.
Tao adalah kekosongan
tidak juga
keheningan
dapat meraihnya.
Kata yang benar
tidak ada
karena Tao
tidak memiliki
nama.
Bagi Si Bestari
makna tidak hakiki
dan kebodohan tidak ada.
Orang Bodoh berdebat dengan semangat.
Si Bestari tersenyum dan menikmati tehnya.
Si Bestari
makan aprikot di musim panas
dan duduk dekat perapian di musim dingin.
Si Bestari menggunakan keheningan
untuk mengungkapkan keheningan.
Si Bestari
berpikir ketika berpikir itu perlu,
namun dia tidak pernah memecah keheningan.
Si Bestari
tidak bersandar bahkan
pada keheningan
dan kekosongan,
karena itu mengalihkannya dari Tao.
(Jos Slabbert. http://www.taoism.net/theway/taoistao.htm)
Bahkan menjelang ajalnya, Sönam Namgyal, ayah Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö dan saudara Lama Tseten itu, mengatakan bahwa ia telah melupakan semuanya dan tidak ada sesuatu untuk diingat. Segala sesuatu ini adalah mimpi, baginya. Namun ia pasti bahwa semua ini baik-baik saja sebagaimana adanya. Namgyal merupakan wujud nyata sidik jari dan bukti hidup ajaran Buddha kepada Subhuti dalam Diamond Sutra yang mengajarkan bahwa orang harus menyadari bahwa segala kenyataan hidup ini sama seperti sebuah mimpi, sebuah ilusi, gelembung busa, bayangan, seperti embun atau kilasan kilat. Oleh sebab itu kepada Sariputra dalam Prajna Paramita Heart Sutra Buddha mengajarkan bahwa karena tidak ada penderitaan dan duka maka pada akhirnya tidak ada pencerahan dan tidak ada sesuatu untuk dicapai. Tidak ada ketakutan karena semua mimpi itu telah lama berlalu dan sudah jauh ditinggalkan di belakang.
Tsele Natsok Rangdrol seorang guru Tibet abad ke tujuh belas menjelaskan bahwa samsara adalah pikiran manusia dan nirwana adalah juga pikiran seseorang saja. Segala kesenangan dan penderitaan berada tidak di luar pikiran. Bahkan kehidupan ini dan kematian pun ada di dalam pikiran bukan di tempat lain. Pikiran mewujud sebagai dasar pengalaman dan menciptakan kebahagiaan dan kesengsaraan, menciptakan hidup dan mati. Samsara tidak dapat membuatnya bertambah parah dan nirwana pun tidak akan membuatnya jauh bertambah lebih baik juga.
Apabila mungkin, ada baiknya pencarian pencerahan dan pencapaian ke-buddha-an itu harus segera diakhiri saat ini juga. Karena semuanya itu hanya permainan pikiran. Seorang guru Zen pernah menasihati muridnya bahwa apabila dalam perjalanannya bertemu dengan Buddha, maka dia harus langsung membunuhnya saja. Albert Einstein pernah menyinggung bahwa umat manusia merupakan satu bagian dari keseluruhan jagad raya ini, namun yang mengalami dirinya dalam sebuah delusi optikal, yaitu merasa dan berpikir sebagai sesuatu yang terpisah dari keseluruhan semuanya tadi itu. Delusi ini adalah sebuah penjara bagi manusia, yang membatasinya untuk hanya mengalami beberapa orang terdekat di sekelilingnya saja. Tugas manusia adalah membebaskan diri dari kerangkeng ini dengan memperluas lingkaran kasih sayang yang merangkul seluruh mahluk hidup dan segala semesta dalam keindahannya itu.
Kalaupun pada akhirnya dengan sangat terpaksa harus disebutkan juga. Maka Pencerahan, Nirwana, Keselamatan, Buddha, Tao atau Yang Lain-nya itu bukanlah perolehan yang dapat digapai serta diraih dan pencapaian yang dapat diusahakan serta diperjuangkan. Melainkan hilangnya segala yang paling hakiki, yang terluhur, yang terpenting, yang paling bernilai dan yang paling dicintai oleh seseorang. Bahkan hikmat dan kebenaran, kesucian dan Yang Ilahi sekalipun itu juga harus rela lenyap. Biarlah yang tersisa hanyalah kesederhanaan keheningan dan kehinaan kekosongan.
Pengalaman hidup Sönam Namgyal seperti itu oleh Pyrrho of Elis (365-270 SM) disebutnya sebagai ataraxia, yaitu kedamaian jiwa dan ketenangan batin yang membuat seseorang tidak tergoyahkan dalam segala kekacauan situasi kehidupan. Ataraxia ini merupakan suatu akibat dari pandangan skeptis, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat mengenali dan mengakui keterbatasan dan ketidaktahuannya serta menghidupi kesadarannya yang sedemikian itu. Orang yang hidup dalam ketentraman jiwa ini adalah orang yang hidup mandiri dan swasembada (autarkia) karena bermental dan bertekad kuat. Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengganggu dan menggoyahkannya. Orang ini bebas dari kebingungan, keresahan, kegalauan dan ketakutan.
Iman sejati
adalah
kepercayaan penuh
tanpa pemahaman:
Menerima
keheningan
diam.
Hanya keheninganlah
yang dapat menjelaskan
yang tak terjelaskan.
Si Bestari
memilih
kehinaan keheningan
daripada
kecongkakan kata-kata.
Bahasa
merusak
pikiran luhur,
tetapi pikiran yang luhur
merusak
kemurnian keheningan.
Keheningan
Tao
hanya dapat didengar oleh
diam.
Si Bestari
selaras dengan Tao
tidak memerlukan kata-kata ataupun kebenaran,
karena dia menerima
kekosongan
dan merangkul
keheningan.
Si Bestari
tidak akan ragu
membayar harga keheningannya.
Orang Bodoh
dikendalikan oleh pikiran.
Orang Bijak
mengendalikan pikiran.
Si Bestari
hidup
dalam keheningan.
Pikiran
membentuk
orang bodoh.
Si Bestari
dibentuk
oleh keheningan.
Si Bestari
hidup tanpa harapan
dan tidak pernah dikecewakan.
Ucapan syukurnya
beralasan.
(Jos Slabbert. http://www.taoism.net/theway/taoistao.htm)
Selama ini Teologi dan Filsafat baru hanya mampu menawarkan kesengsaraan dan keputusasaan dalam hidupnya yang saling bertentangan, terus berada dalam ketegangan, terpecah-pecah, galau, kaku, dingin dan gelap. Meskipun demikian, gaya hidup kegila-gilaan ini dinilai sebagai suatu hidup yang filosofis, etis, teologis bahkan estetis. Marion masih mewarisi dan tidak mampu mengenali serta tidak dapat keluar dari padangan patologis semacam ini dan masih mau mengawetkannya lagi. Tidak berlebihan apabila sajak Epitaph, yang dikaitkan dengan Martinus von Biberach, yang meninggal pada tahun 1498 berbunyi,
Aku datang – entah dari mana,
aku ini – entah siapa,
aku pergi – entah ke mana,
aku akan mati – entah kapan,
aku heran bahwa aku bergembira.
(Harry Hamersma. Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat. Kanisius, Yogyakarta, 1992, 9.)
Rasul Yohanes juga mencatat dalam Injilnya bahwa Yesus pernah berkata: “Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya.” (Yohanes 20: 29). Karena apabila orang telah melihat, mengerti dan memahami maka di situ tidak lagi diperlukan kepercayaan dan iman. Orang yang percaya dan beriman adalah orang yang diberkati, orang yang berbahagia, orang yang bergembira. Orang yang hati dan jiwanya tentram serta damai.
————————
*Penulis adalah Peneliti di Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia.
Kepustakaan
Babbitt, Irving. The Dhammapada. Oxford University Press, New York, 1965.
Bornemark, Jonna and Ruin, Hans. (Ed.). Phenomenology and Religion: New
Frontiers. Södertörn University, Huddinge, 2010.
Conze, Edward. Buddhist Wisdom: Containing the Diamond Sutra and the Heart Sutra. Vintage Books, New York, 2001.
Das, D. N. Mystic Songs of Kabir. Shakti Malik Abhinav, New Delhi, 1996.
Hamersma, Harry. Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat. Kanisius, Yogyakarta, 1992.
Heidegger, Martin. Being and Time. Basil Black Well, Oxford, 1973.
Heidegger, Martin. The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude, Solitude. Indiana University Press, Bloomington, 1995.
Heidegger, Martin. Ontology: The Hermeneutics of Facticity. Indiana University
Press, Bloomington, 1999.
Heidegger, Martin. Introduction to Metaphysics. Yale University
Press, New Heaven, 2000.
Heidegger, Martin. The Phenomenology of Religious Life. Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis, 2010.
Hua, Hsüan. The Vajra Prajna Paramita Sutra: A General Explanation.
Buddhist Text Translation Society, California, 2003.
Kuzminski, Adrian. Pyrrhonism. How the Ancient Greeks Reinvented Buddhism. Lexington Books, Lanham, 2008.
Magnis-Suseno, Franz. 13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19. Kanisius, Yogyakarta, 1997.
Magnis-Suseno, Franz. Menalar Tuhan. Kanisius, Yogyakarta, 2006.
Marion, Jean-Luc. God Without Being. The University of Chicago Press, Chicago, 1991.
Marion, Jean-Luc. Reduction and Givenness: Investigations of Husserl, Heidegger, and Phenomenology. Northwestern University Press, Illinois, 1998.
Marion, Jean-Luc. Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness.
Stanford University Press, Stanford, 2002.
Mitchell, Basil. The Philosophy of Religion. Oxford University Press, Oxford, 1986.
Mulyono, Sri. Wayang dan Filsafat Nusantara. Penerbit Gunung Agung, Jakarta,
1982.
Pine, Red. The Diamond Sutra. Counterpoint Press, California, 2001.
Rahner, Karl. Spirit in the World. Shead & Ward, London, 1968.
Rahner, Karl. Hearers of the Word. Sheed & Ward, London, 1969.
Rinpoche, Sogyal. The Tibetan Book of Living and Dying. HarperCollins Publishers Inc., New York, 2002.
Tzu Lao. Tao Te Ching. Wordsworth, Hertfordshire, 1997.
Van Der Weij, P.A. Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia. Gramedia, Jakarta,
1988.
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Kegan Paul, London, 1922.
Sumber Internet
http://www.buddhanet.net/pdf_file/scrndhamma.pdf
http://www.buddhanet.net/pdf_file/damapada.pdf
http://www.buddhanet.net/pdf_file/prajparagen2.pdf
http://www.buddhanet.net/pdf_file/heart_s2.pdf
http://www.fodian.net/world/ps.vajra.02.020503.screen.pdf
http://www.taodirectory.co.uk/phocadownload/tao-te-ching.pdf
http://www.taoism.net/theway/taoistao.htm