Tari dan Tubuh Kenyataan
Oleh Fitri Setyaningsih
“Tari bukan semata-mata peristiwa gerak. Tari menuju sebagai peristiwa media dengan tubuh tetap sebagai poros utamanya”.
Apakah tari itu? Apakah koreografi itu? Saya merasa diri saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawabnya. Atau saya mungkin tidak amat terlalu berminat untuk menjawabnya. Saya bukan bagian dari pekerja seni yang suka berpikir. Saya melihat hidup saya bergerak dari peristiwa satu ke peristiwa lainnya, bukan dari pikiran satu ke pikiran berikutnya. Peristiwa-peristiwa itu lalu menjadi cerita. Mungkin cerita-cerita ini jadi rumah untuk proses kreatif saya ketika mulai melakukan kerja koreografi. Mungkin dalam cerita ada emosi, sementara pikiran tidak. Saya tidak tahu. Tapi dia selalu datang. Kadang-kadang waktu berlalu begitu saja, tanpa peristiwa yang cukup berarti. Itu pun untuk saya tidak apa-apa. Saya termasuk orang yang hidup tanpa target.
Kalau saya diminta menjawab pertanyaan di atas, saya seperti ikan yang dikeluarkan dari air dan disuruh menjawab pertanyaan: “apa itu air?” Rasanya saya mau sakit perut. Saya lebih tertarik dengan kenyataan bahwa tubuh kita adalah tubuh yang setiap harinya tidak sendirian. Tubuh selalu bersama dengan berbagai benda dan peralatan di sekitarnya.
Tubuh membuat gerak bersama benda-benda dan peralatan itu. Saya sering terpukau melihat bagaimana gerak itu muncul berbeda bukan karena tubuh yang bergerak itu, melainkan karena benda-benda atau peralatan yang digunakan tubuh itu. Ada keterampilan. Ada intensitas. Ada ketegangan kalau terjadi kecelakaan atau kegagalan. Ada tubuh yang bekerja keras, atau rasa malas yang tiba-tiba datang. Ada tubuh yang rasanya tidak jujur terhadap pekerjaannya sendiri. Ada aura, ada suara dan ada energi.
Saya merasa tubuh penari harus mampu membaca dan memiliki dasar-dasar kenyataan itu, karena itu adalah tubuhnya sendiri dan hidupnya sendiri. Itu pula sebabnya dari kerja koreografi saya untuk menyiapkan sebuah pertunjukan tari, pada tingkat awal saya sebenarnya bekerja dengan biografi masing-masing penari. Ekplorasi awal dilakukan dengan cara lebih banyak bercerita tentang diri masing-masing, pekerjaan masing-masing. Lalu mulai muncul tema, mulai muncul gagasan-gagasan kecil, bayangan-bayangan yang masih kabur.
Eksplorasi awal seperti ini membuat saya tidak membawa saya kepada kesadaran apakah saya sedang melakukan eksperimen atau tidak dalam kerja koreografi itu. Tubuh penari sendiri sudah merupakan sebuah tantangan untuk saya bisa mengenalinya. Apalagi kalau saya bisa menemukan bahasanya. Pusing sekali rasanya kalau saya berhadapan dengan tubuh yang tidak memiliki bahasa. Sakit perut. Sumpek. Bete. Apa yang dilakukan selalu gagal, kecuali tubuh itu dibentuk dan diberi bingkai. Tapi dia jadi robot atau hanya jadi model yang mati.Saya curiga tubuh yang tidak memiliki bahasa adalah tubuh yang mungkin banyak tidak jujur terhadap apa yang dikerjakannya sendiri, atau tidak punya fokus.
Semua catatan-catatan di atas tidak datang begitu saja. Sebelumnya saya adalah bagian dari dunia tari dimana tari dibaca sebagai kecanggihan teknik dan perbendaharaan gerak yang dimilikinya. Tidak mudah untuk bertemu dengan cara kerja di atas. Karena sejak usia 6 tahun saya sudah mengenal tari tradisi Surakarta. Kebetulan saya juga tinggal dan hidup di lingkungan kampus ISI surakarta, yang pada waktu itu masih bernama ASKI. Ketika SD kelas 2, keluarga saya pindah ke sebuah desa di hutan. Belum ada listrik, walau pal pal listrik sudah bertahun-tahun berdiri. Sampai saya selesai SMP pun listrik belum juga masuk. Di desa itu ada ruangan yang akhirnya oleh saudara saya dibuka sanggar gratis untuk orang di kampung yang mau belajar tari, setiap minggu kami anak-anak latian tari. Kadang buat pentas hari kemerdekaan atau perkawinan di desa. Mewakili sekolah untuk ngikuti lomba-lomba tari.
Tamat SMP keluarga saya pindah lagi ke solo, hubungan saya dengan tari sebagai teknik menari semakin kuat, karena saya melanjukan ke SMKI [sekolah menengah karawitan indonesia] surakarta. Belajar teknik tari, olah tubuh, komposisi tari, dan koreografi. Dan berlanjut ke STSI [kini ISI] jurusan tari jalur koreografi.
Kehidupan saya terus-menerus bertemu penari. Mata saya buta oleh adanya tubuh yang lain. Wuih, saya tidak menyadari ada yang hilang dari tubuh saya atau tubuh penari di sekitar saya, yaitu tubuh sehari-hari saya sendiri, tubuh sehari-hari para penari. Lembaga pendidikan kesenian yang besar justru bisa membutakan kita terhadap dunia di sekitar kita, karena otomatis dalam lembaga itu kita sudah merasa sudah berada dalam dunia kesenian dan bergaul dalam komunitas seniman. Seakan-akan tidak ada lagi dunia lain. Saya lupa bahwa semua gerak yang saya pelajari dari tradisi justru didasari oleh lingkungan pekerjaan dari seniman-seniman yang menciptakan gerak itu. Entah pekerjaan petani, abdi dalam keraton, selir-selir istana atau dari pencapaian spiritual tertentu. Saya mempelajari tari, tapi saya kehilangan sejarah tubuh dari tari itu. Bagaimana caranya saya harus kembali?
Saya tidak bisa kembali melalui eksperimen atau keinginan untuk melakukan pembaruan. Saya merasa tidak dekat dengan jargon-jargon kesenian yang serba wah seperti “eksperimen” atau “pembaruan” itu. Karena tubuh itu tidak pernah sendirian, selalu bersama dengan benda-benda dan peralatan di sekitarnya, saya menggunakan ini untuk bisa kembali bertemu dengan tubuh sehari-hari, tubuh biasa, bukan tubuh penari yang hebat. Untuk tidur saja, tubuh kita memerlukan alas, kasur, bantal atau selimut. Untuk mandi memerlukan handuk. Juga memerlukan aksesoris dan kosmetik, entah pakaian dan seterusnya. Jadi tubuh itu bekerja dan menghias dirinya juga.
Saya belum bekerja dengan cerita atau biografi yang ada dalam tubuh. Saya mulai bekerja dengan benda sehari-hari itu: mengibaskan kain, melipat, meletakkan kain. Rasanya bukan tarian yang hebat, mungkin tidak akan melahirkan tarian yang hebat. Bagaimana melipat kain bisa menghasilkan tarian yang hebat? Untuk saya ini merupakan ketegangan baru yang langsung menusuk ke dalam diri saya, karena saya harus berhadapan dengan kemungkinan munculnya kritik: wah tarianmu miskin sekali. Atau gugatan: mana tarinya? Saya merasa tidak lagi belajar tari, tetapi belajar sabar, belajar bertemu dengan kemungkinan lain yang tidak terduga.
Kerja saya pada tahap awal itu, adalah menjaga agar penari tidak memperlakukan benda-benda hanya sebagai alat atau aksesoris untuk memperindah dirinya sendiri. Saya menjaga agar kecanggihan teknik para penari tidak memperlakukan benda-benda untuk mereka taklukkan hanya untuk menghasilkan teknik yang canggih dalam menggunakan benda-benda itu sebagai hiasan tarinya. Saya menjaganya agar penari berhubungan seimbangan dengan benda-benda itu, saling membuka diri. Tetapi itu tidak mudah. Saya merasa tidak semata-mata berhubungan dengan teman-teman penari. Tetapi lebih dari itu saya sebenarnya sedang berhadapan dengan tubuh penari yang sudah diprofesikan dan kehilangan tubuh kesehariannya. Sampai sekarang saya belum terlalu yakin memiliki cara lain untuk menghadapinya.
Lalu saya mulai mencoba pekerja dengan teman-teman yang bukan penari. Disinilah saya mulai bertemu dengan tubuh biasa, bukan tubuh penari. Tubuh biasa itu saya sebut sebagai “tubuh tari”, istilah yang sering digunakan Afrizal Malna. Tubuh yang tidak memiliki identitas kepenarian. Tubuh tari bisa ada dalam diri siapa saja, tukang becak dengan kayuhan kakinya, tukang batu dengan pukulan palunya untuk memecahkan sebongkah batu menjadi berkeping2. Saya juga seperti ini, kadang harus pecah kemana-mana. Di sini saya mulai banyak berhadapan dengan hal-hal yang terus-terusan membut saya heran. Mendorong, menggoda saya, mencoba untuk berjalan bareng, merusaknya, merontokanya lagi, membangunya. Dan saya rasa pelan-pelan saya mulai menemukan tema-tema personal dalam berkarya.
Di sini juga saya tambah menyadari begitu pentingnya bekerja dengan kawan-kawan seniman dari berbagai disiplin. Bertemu dengan cara melihat yang lain, merasa lebih dewasa dengan belajar saling menghormati, saling mengerti batas masing-masing.Komunikasi dan keterbukaan menjadi begitu penting. Kalau komunikasi tidak berjalan baik, saya bisa langsung macet. Solusinya jalan-jalan, kadang hanya masak bareng atu ngobrolin yang jorok-jorok.Saya juga mulai membuka diri dengan tubuh yang bukan tubuh manusia. Saya pakai belut, daging atau usus ayam dalam karya-karya saya. Tubuh ikut bergetar dengan pertemuan seperti ini. Tubuh belut yang licin dan menjijikkan. Daging yang amis yang digigit penari. Usus yang cepat sekali berbau busuk dan berlendir. Pertemuan ini begitu tidak terduga, begitu membuka kemungkinan dan kesadaraan lain.
Kerja saya menjadi kian mirip dengan kerja visual. Menggunakan sansak tinju atau botol-botol plastik, membawa berbagai imaji yang membuat ceritanya sendiri. Imaji-imaji itu rasanya begitu membebaskan saya dalam eksplorasi yang saya lakukan. Kadang menjadi seperti performance art ketika saya memasukkan jarum ke dalam lubang anting telinga saya. Dan menyadari saya bahwa tubuh kita memiliki banyak lubang.Apakah artinya lubang-lubang yang dimiliki tubuh kita untuk tari atau kerja koreografi? Kadang-kadang saya tidak ingin menari. Saya ingin diam saja. Biarkan yang lain yang menari. Yang bukan tubuh kita.
***
*Penulis adalah seorang penari dan koreografer



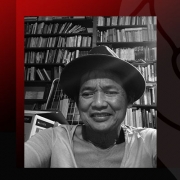



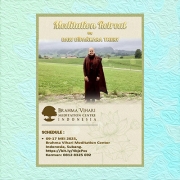


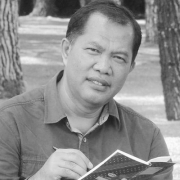


Assalamuallaikum
mbakyuuuu
Sangat inspiratif sekali, sangat membangun disaat atau pada zaman seperti ini, banyak segi pandang ataupun aspek dalam pembahasannya yang dirasa seperti curahan hati yang enteng tapi berbobot yang bisa digunakan seniman2 muda sekarang terus belajar mengenai nilai atau makna dalam hidup yang sebenarnya ( sebagai seniman maupun sebagai manusia ) hahaha….tapi emang keren hehe….kesungguhan hati dalam melaksanakannya yang insyaallah menjadikan semua bisa lebih baik secara umum maupun personal….
Ingin rasanya mengingatkan dan tidak ada kata yang lebih baik dari itu mbak fitri hahaha….semoga masih ingat saya karena saya sendiri pernah menjadi penari mbak fitri sendiri hehehe….yaitu, menurut saya akan lebih baik disertakan bagaiman secara spiritual agama yang dianut yang tanpa kita sadari menjadikan sebuah panutan dalam mencapai semuanya juga….karena mungkin juga itu bisa menjadi lebih berarti karena dengan mengingat segalanya tentang sang Pencipta semua bisa menjadikan lebih barokah aamiin….
Terima kasih
Wassalamuaallikum…
Semangad aku nang mburimu jooosssss…..