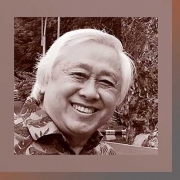Si Gurita: Dan Setelahnya
Oleh Nirwan Dewanto
—untuk Ketut Putrayasa
Jika saya mencoba masuk ke dalam pikiran bung, jika saya menyatukan irama langkah saya yang lambat dengan langkah bung yang cepat, jika saya terheran-heran kenapa bung membuat sebuah “patung” gurita berukuran raksasa di Pantai Berawa, Canggu, Bali Selatan, pada bulan April lalu, maka saya berpikir tentang tiga jenis kesenian yang hendak bung imbangi.
Yang pertama adalah karya-karya seni yang hanya dipajang di ruang pamer dengan pendingin udara, dengan kebersihan dan kerapihan yang tak biasa, karya-karya yang hanya boleh dipandang dengan sikap terlalu berhati-hati dan kepala mendongak pura-pura mencintai. Ini bukan melulu karya-karya di dalam aneka galeri atau museum, tapi bisa juga yang terpasang di pelbagai hotel, restoran, kafe, mal, bahkan rumah.
Yang kedua adalah karya-karya di ruang luar, yang menjulang tinggi dan menjadi tanda akan kebesaran tertentu, misalnya saja “patung-patung publik”. Karya-karya “monumental” yang dimaksudkan untuk jadi kekal abadi, untuk menandakan siapa yang punya uang dan kuasa, siapa yang sudah merasa sudah berbuat berbuat besar untuk rakyat.
Yang ketiga adalah kesenian yang hidup di lingkungan “tradisi”, dalam berbagai upacara, yang tidak lagi dikenali sebagai kesenian karena sudah begitu menyatu dalam keseharian hidup di Bali. Berbagai karya “instalasi” (atau “pepasang”, jika saya boleh meminjam istilah Sudjoko) yang sangat hidup di satu momen singkat: penjor, banten, bade, dan seterusnya.
Mengimbangi bukanlah melawan, namun merangkul apa yang layak dari ketiganya. Bung hendak membuat, katakanlah, kesenian lingkungan, di mana para pemirsa bisa dengan suka hati terlibat dengan si karya—menyentuhnya, meremasnya, memeluknya, bahkan memasukinya bila mungkin, menjadi bagian daripadanya. Karya yang masih mengandung unsur “ekspresif”, tapi yang tidak lagi “agung”. Yang bersifat publik, tapi tidak berjarak dengan mereka. Karya pepasang yang kolektif, tapi bukan lagi relijius, melainkan sangat melekat ke dunia yang penuh keringat dan noda.
Gurita raksasa anggitan bung itu tegak menjulang tinggi mencoba mengimbangi terang siang dan gelap malam. Barangsiapa melihatnya sudah pasti ingin mendekatinya, tidak sabar hendak menyentuhnya, memeriksanya, dan “menduduki”-nya. Si pemirsa tak hendak mengambil jarak daripadanya.
Dan itulah “kesenian lingkungan” yang saya maksud. Si gurita mengambil posisinya secara tepat-ruang: ia tidak menjadi angkuh, ia tahu bagaimana “bertanding” dengan luas pantai dan bentang laut. Ia sangat besar di dalam kisaran indera penglihatan (yaitu bila kita berdiri di antara kaki-kakinya), tapi ia kecil belaka dalam bentangan lanskap tepian samudera yang mahabesar itu (terutama bila kita bisa mewakilkan diri ke dalam pesawat drone yang terbang berkitaran di atasnya, mengambil gambarnya dan gambar alam sekitar).
Sesungguhnya ungkapan “tegak menjulang” untuk si gurita tidak tepat. Sebab lebih sering si “makhluk bambu” dengan tinggi 20 meter dan delapan tentakel yang masing-masing 300 meter itu terlihat merunduk atau melata: kepalanya seperti hendak lunglai ke bawah, mengikuti tentakel-tentakelnya yang menjulur masuk ke dalam hamparan pasir dan hendak mencapai ujung sana. Si gurita hendak merayap memeluk si pemirsa di satu pihak dan di pihak lain memayungi panggung yang menyajikan tontonan setiap malam selama sepekan itu.
Dan persis di sinilah pengertian “seni lingkungan” yang kedua. Yaitu sebagai penghidup rasa hayat komunitas. Si gurita hadir sebagai anasir belaka, sebagai semacam wadah, yang membuat pengunjung betah berada di situ, di bentangan pasir pantai, menikmati pasar siang, pasar malam dan berbagai pertunjukan di panggung. Satu faset baru dalam kehidupan banjar dan turisme yang memang sudah berlangsung di situ. Katakanlah sebuah nilai tambah.
Pengertian “seni lingkungan” yang ketiga adalah bahwa si gurita di kawasan desa Tibubeneng itu sekadar makhluk seni, dan bukan makhluk biologis, dan justru oleh itulah ia menjadi sejenis simbolisme yang membuat kita harus memperhitungkan ekosistem laut dan pantai di sekitarnya, atau secara lebih luas lagi, ekosistem di sepanjang pantai timur Samudera Hindia di Bali Selatan, yang kian hari kian terpincang-pincang mendukung turisme. (Lihatlah Canggu yang dulu persawahan hijau permai itu, kini sudah jadi wilayah 1001 vila dan bungalo yang tumpang tindih tak terkendali.)
Si gurita raksasa tampil bersama karya-karya patung dan instalasi yang lain—misalnya karya-karya Hedi Hariyanto, I Gede Sarantika, dan Aditya Chandra—dalam Berawa Beach Arts Festival yang kedua pada akhir Mei lalu. Festival tahunan yang digagas dan dikerjakan oleh bung, Wayan Seriyoga Parta, Made Dwijantara ini ialah sebuah pesta rakyat yang menggabungkan pameran seni rupa di alam terbuka, panggung seni pertunjukan, dan pasar malam.
Bung pasti tahulah bahwa pada malam penutupan itu saya menyaksikan sekitar lima ribuan orang—sebagian besar adalah masyarakat di Kabupaten Badung dan sebagian lain adalah turis mancanegara—berduyun-duyun menonton pentas-pentas, antara lain duo pegitar I Wayan Balawan dan peseruling Gus Teja sambil memuaskan diri di kios-kios makanan di sisi timur gelanggang atau seraya mondar-mandir ke pantai di sisi barat menikmati debur ombak. Si gurita raksasa seperti memayungi mereka semua.
Esok paginya, selepas matahari terbit, saya berjalan ulang-alik dari hotel saya di selatan lokasi Berawa Beach Arts Festival ke arah si gurita raksasa sambil senantiasa menenengok ke sekeliling, mencoba “mencerna” garis pantai yang melengkung leluasa utara-selatan. Langit biru cerah dengan gumpal-gumpal awan putih; dengan para peselancar di tengah ombak dan para turis menyusuri pantai dengan berlari atau berjalan saja. Nun di selatan sana tampaklah sayup-sayup patung Garuda Wisnu Kencana di Jimbaran, patung yang kiranya akan terus berdiri hingga akhir zaman. Ke arah utara, tampaklah satu jendul kecil kepala si gurita yang kian lama jadi kian besar, kian besar lagi, seiring makin dekatnya saya ke lokasi festival bung itu.
Gurita raksasa itu akan dibongkar dua minggu lagi. Festival yang mewadahinya sudah selesai. Namun festival ini tampaknya mengandung cita-cita besar ke depan, jika saya boleh merangkum percakapan kita yang berselang-seling itu. Pameran seni rupa di udara terbuka di sepanjang pantai: bisakah itu berlangsung dengan skala yang lebih besar, yaitu mengambil tempat, misalnya, di sepanjang pantai di antara Legian dan Canggu-Berawa?
Bung, beserta I Wayan Seriyoga Parta, telah mengatakan kepada saya bahwa kawasan Kuta-Legian-Seminyak-Petitenget-Canggu sudah semestinya mengembangkan “seni rupa kontemporer yang lain”, yang tidak mungkin dikembangkan di Ubud (dan sekitarnya), Sanur, dan Nusa Dua. Seperti kita tahu, kawasan-kawasan yang terakhir ini sudah “terikat” dengan kultur galeri dan museum, yang “memingit” terutama seni lukis dan seni patung dan segala jenis seni dan desain yang “tinggi” itu.
Bali, sebagai tujuan wisata yang tak tertawar bagi seluruh dunia, layak memiliki peristiwa seni rupa yang besar yang menginternasional, yang bisa menyajikan “Bali yang lain”, Bali yang bisa memperbaharui diri seraya tetap terhubung dengan kekayaan masa lampaunya. Barangkali tak ada salahnya mengikuti Venezia, yang memiliki La Biennale, biennale seni rupa kontemporer terbesar di dunia? Seni rupa kontemporer menumpang kepada turisme: kenapa tidak? Apalagi jika ia bisa memperbaharui turisme itu sendiri?
Jika Venezia punya kawasan-kawasan Arsenale dan Giardini untuk La Biennale, Bali bagaimana pula? Tampaknya bung punya jawaban jitu: pameran “seni rupa kontemporer yang lain”—yang di kemudian hari bisa saja menjadi biennale, misalnya—mesti mengambil tempat di sepanjang pantai Kuta hingga Canggu-Berawa, bahkan lebih ke utara lagi, ke arah Tanah Lot. Pameran seni rupa di ruang terbuka, di tepi pantai, kurang-lebih versi yang jauh lebih besar daripada yang sudah ada di Berawa Beach Arts Festival yang sudah saya saksikan ini.
Dan saya memberanikan diri berkata bahwa mimpi bung, dan mimpi Wayan Seriyoga Parta, itu tampak jitu untuk beberapa alasan. Yang pertama, bahwa kawasan pantai yang bung maksud itu sungguh luas-lebar. Bentangan pasir pantai di antara tubir laut dengan garis sempadan bangunan sungguh-sungguh sangat berarti untuk karya-karya berukuran besar (seperti si gurita raksasa), tak seperti pantai Sanur, misalnya, yang sama sekali mustahil untuk itu maupun untuk pesta rakyat pada umumnya. (Dua malam itu, ketika berkeliaran di tepi samudera di sekitar hotel tempat saya menginap, saya sungguh merasa bahwa kekosongan dan keluasan itu benar-benar nyata dan mencekam. Maka pantai Sanur, yang sering kusinggahi, hanyalah semacam pematang belaka di antara laut dan halaman hotel-hotel di situ.)
Yang kedua, turisme sudah berlimpah ruah di pantai matahari terbenam dan bersifat lintas-kelas itu; dan di samping itu, juga industri kreatif meledak (banyak desainer internasional yang membuka bengkel di Canggu, misalnya). Dengan demikian, seperti Venezia, kawasan pantai pantai barat di Bali Selatan ini sesungguhnya tidak perlu bersusah payah mengiklankan seni rupa kontemporer. (Tidak seperti kawasan Nusa Dua, kantung turisme yang sangat tersembunyi dan eksklusif, yang sampai kini sungguh bersusah payah mendatangkan kaum pemirsa ke perhelatan seni rupa kontemporer seperti Art Bali, misalnya.)
Yang ketiga, dukungan dari banjar-banjar setempat, serta dukungan lain dari industri turisme (hotel-hotel dan kelab-kelab) dan Kabupaten Badung (yaitu kabupaten terkaya di Bali) yang sudah terbukti dalam penyelenggaraan Berawa Beach Arts Festival kali ini. Segala dukungan ini tentu tak terpisah dengan faktor pribadi, yaitu bung sendiri, yang lahir dan besar di kawasan itu (dan dengan begitu bung bisa punya daya dan wibawa untuk menggerakkan jejaring kerja sama); bung menyaksikan turisme berkembang hingga ke titik jenuhnya sekarang ini. Katamu, turisme akan habis jika tak merangkul kreativitas baru.
Yang keempat, adalah faktor teknis, atau mungkin lebih tepat disebut faktor pembelajaran. Bung adalah pematung yang sudah membuat banyak patung publik. Dengan segala kempuan teknik dan pengetahuan tentang bahan, bung banyak “tergoda” untuk membuat atau mendukung karya-karya di ruang terbuka. Gurita raksasa itu, misalnya, bung kerjakan dengan rancangan yang tepat, dengan 200 perajin-pekerja dan 25 ribu batang bambu. Saya percaya bahwa mimpi besar bung untuk membuat pameran besar instalasi di ruang terbuka di sepanjang pantai yang saya panas-panaskan tadi “hanyalah” ekstrapolasi dari segenap kerja bung untuk Berawa Beach Arts Festival. Tentulah bung sangat sadar bahwa “sifat interaktif dari sebuah karya” satu menyatu dengan aspek bentuk dan tekniknya, serta lingkungan di mana ia tertancap.
Untuk mulai mengamalkan impian besar itu Wayan Seriyoga Parta dan bung tentulah harus berhati-hati, meski kalian juga tidak mulai dari nol. Berawa Beach Arts Festival itu mestinya mengandung efek bola salju. Khazanah seni rupa Indonesia kontemporer kaya dengan tenaga dan mimpi untuk menyebarkan karya-karya instalasi berukuran besar yang tak biasa, yang tak monumental, di ruang luar.
Sebut saja, misalnya, Joko Dwi Avianto dan Eko Prawoto yang sudah leluasa membuat karya-karya instalasi bambu di ruang terbuka di berbagai gelanggang nasional dan internasional. Sebut saja berbagai karya pepasang dari berbagai khazanah Nusantara: para pencipta dari aneka lingkungan tradisi itu akan girang jika diberi gelanggang pameran seperti yang bung impikan. Sebut saja ogoh-ogoh yang luar biasa itu di pulaumu, kesenian “eksperimental” yang bagi saya perlu gelanggang pamer tersendiri.
Di tahun 2016 Asosiasi Pematung Indonesia pernah menyelenggarakan pameran patung dan instalasi di berbagai ruang terbuka Yogyakarta. Anusapati, pematung utama Indonesia yang menggagas pameran itu, tentulah tahu bahwa khalayak harus mendapatkan apa-apa yang lain daripada pameran di ruang-ruang tertutup maupun patung-patung publik yang “begitu-begitu saja”.
Berbagai amalan di atas tentu bukan sekadar contoh, tapi juga tonggak-tonggak ancangan untuk mengokohkan gagasan perihal pameran besar seni instalasi di pantai Samudera Hindia yang bung impikan itu.
Berhati-hati dengan impian besar semacam itu adalah juga bermain wacana. Membangun jejaring nasional dan internasional sambil mengerahkan aneka sumberdaya lokal, menegakkan organisasi yang siap untuk memberesi lapangan dari menit ke menit, menghayati lokasi sebagai jantung peristiwa seni, memadukan industri turisme dengan kekuatan banjar-banjar setempat, berselancar dalam gelombang opini “akhir seni”, membarengi kesadaran ekologis yang sedang pasang di berbagai kalangan, adalah kerja dari hulu hingga hilir yang pasti memerlukan landasan konsep yang kuat.
Dengan “sederhana”, misalnya, patutlah bung bersitegas bahwa gagasan tentang pameran besar di tepi Samudera Hindia itu adalah juga untuk mengisi ruang yang tidak diisi oleh berbagai pameran “akbar” di tanah air, misalnya saja berbagai biennale di Jawa, Art Jog, Art Bali, dan sebagainya; pada saat yang sama ia juga mesti melampaui segala yang nasional itu untuk mewajarkan diri sebagai sajian yang layak bagi penonton dari berbagai penjuru. Inilah yang saya sebut bermain wacana tersebut. Saya yakin bahwa bung, bersama Seriyoga Parta, yang sudah banyak berjejaring dengan para kurator dan direktur artistik di tanah air, sangat menyadari laku peta-memetakan ini.
Di kaki-kaki gurita raksasa itu, barangkali saya mulai belajar membaca kembali peta seni rupa kontemporer Indonesia di bawah sinaran yang berbeda.
(21 Juli 2019)
*Penulis adalah seorang Sastrawan