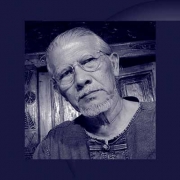Rekontruksi Sejarah, Identitas Dan Dialektika Budaya Melayu: Telaah Novel Bulang Cahaya Karya Rida K Liamsi
Oleh Tjahjono Widijanto
Berdasarkan klasifikasi Ricoeur, sastra dapat diklasifikasikan ke dalam sistem lambang verbal. Di sisi lain, sepanjang sejarah keberadaanya sastra terbukti dapat menunjukkan diri sebagai karya artistik-estetik sekaligus karya intelektual (ideasional-kognitif).Dengan demikian secara proporsional teks sastra dapat dipandang sebagai seni, sebagai lambang verbal sekaligus sebagai lambang ekspresif-kognitif atau intuitif-intelektual.
Sebagai lambang seni verbal yang intuitif-intelektual atau rasa-pikir yang terjadi secara serempak, teks sastra merupakan hasil dari persenyawaan atau persatupaduan penghayatan dan pemikiran, gabungan antara kecerdasan hati dan kecerdasan otak. Dalam teks sastra selalu melekat kualitas gagasan, pikiran dan cara pandang di samping memuat pula kualitas hayatan, renungan dan ingatan tentang realitas. Hal ini mengimplikasikan bahwa sebuah teks sastra dapat dipahami sebagai sulingan, saringan, endapan, penghayatan, pemikiran, serta penggagasan sastrawan atas pelbagai peristiwa, pengalaman budaya, serta realitas hidup dan kehidupan yang dilakoninya.
Bedasarkan hal tersebut maka teks sastra dapat diperlakukan sebagai sejarah mentalitas manusia, apa yang ditinggalkan dan dihasilkan oleh kegiatan jiwa atau mental dalam rentangan kesejarahannya sendiri (Brinton, 1985: 201). Catatan-catatan dalam sejarah mentalitas ini selalu bersifat hermeneutis atau interpretatif yang merupakan kesatuan realitas atau fakta dengan tafsiran yang dilekatkan oleh imajinasi sejarah.
Di dalam sebuah teks sastra (baik prosa atau puisi) antara realitas dan imajinasi tidak dapat ditentukan mana yang lebih penting karena kedua-duanya bercecabang, berkelindan dan berpagutan menjadi satu. Fakta dan fiksi, faktual dan imajinatif bersenyawa dalam teks sastra, —meminjam istilah A. Teeuw (1995), hal ini dikatakan sebagai realitas hulu dan realitas hilir. Karena mempunyai realitas hulu dan realitas hilir, teks sastra hadir sebagai kisah sekaligus berita pikiran. Sebagai kisah teks sastra menyajikan narasi atau penceritaan tertentu, dimana pembacanya dapat bersimpati dan berempati. Sebagai berita pikiran, teks sastra menampilkan hayatan, renungan, pandangan serta gagasan tentang kontruksi realiatas budaya sastrawannya.
Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, berhadapan dengan teks (novel-novel) sastrawan Indonesia berlatar Melayu, pembaca tidak saja dapat menikmati cerita dalam novel tersebut namun dimungkinkan dapat pula menelusuri “berita pikiran” tentang rekontruksi budaya dan penggambaran dialektika budaya Melayu dengan budaya-budaya lainnya. Terkait dengan latar budaya Melayu, dalam karya sastra Indonesia paling tidak ada dua dua novel karya sastrawan dari Melayu (Sumatera) yang berbicara tentang sejarah dan identitas Melayu, yakni novel Bulang Cahaya(JP. Book, Juli 2007) karya Rida K Liamsi, dan novel Tambo (Grasindo, 2000) karya Gus tf. Sakai. Sedangkan dalam genre puisi, muncul puisi-puisi berlatar Melayu dengan segala kompleksitasnya dari para pengarang semisal Marhalim Zaini,dan Fahrunas M. Jabbar.
Kalau diamati sepintas kilas, kedua novel tersebut diatas dapat dianggap mewakili dua hal. Pertama, kedua novel ini dianggap penulis mewakili dua kutub kebudayaan Melayu di Indonesia, yakni Melayu tua dan Melayu muda. Melayu tua bersumber dari kerajaan Pagarruyung Minangkabau (abad 14) yang dianggap cikal bakal Melayu, dan Melayu muda atau Melayu Riau yang berada di wilayah bekas kerajaan Riau-Lingga dan Johor (abad 19) .Melayu muda diwakili novel Bulang Cahaya, sedangkan Melayu Tua diwakili oleh novel Tambo. Kedua, kedua novel ini sarat dan kental dengan sejarah dan warna budaya Melayu yang ditulis oleh sastrawan-sastrwan Indonesia terkini yang hidup dan mencipta pada zaman globalisasi, meskipun bisa jadi menghadapi problematika yang berbeda-beda.
Tulisan pendek ini mencoba menelaah dan mengritisi novel Bulang Cahaya dengan mefokuskan pada persoalan rekonturuksi sejarah Melayu dan dialektika budaya di dalamnya. Dalam pembahasan ini penulis juga sesekali membandingkannya dengan novel Tambo, meskipun penulis sama sekali tidak bermaksud meletakkan kajiannya pada telaah sastra bandingan. Novel Tambo hanyalah sekedar sebagai penguat kajian terkait dengan Melayu dan fokus serta obyeknya adalah novel Bulang Cahaya.
Sejarah dalam Novel Sebagai Titik Pijak
Sudah semenjak awal kelahiran sastra Indonesia modern banyak sastrawan yang memanfaatkan peristiwa kesejarahan sebagai sumber inspirasi kreatifnya. Dimulai dengan Abdoel Moeis pada masa Balai Pustaka, ditulislah dua buah roman berlatar sejarah: Surapati dan Robert Anak Surapati. Setelah dua roman ini segera diikuti dengan roman atau novel berlatar sejarah lain mulai dari Hulubalang Raja (Nur Sutan Iskandar) hingga era yang lebih modern seperti novel Roro Mendut (Ajip Rosidi), Roro Mendut, Genduk Duku, Lusi Lindri (J.B Mangun Wijaya) dan novel-novel sejarah Pramoedya Ananta Toer seperti Bumi Manusia, Anak semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, Panggil Aku Kartini Saja, dan Arus Balik.
Dalam mengolah peristiwa kesejarahan tersebut sastrawan sebagai sang kreator dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama pengarang berada atau mengambil posisi yang “linear” dengan sejarah yang dianggap “resmi”.. Sedangkan pilihan kedua pengarang mengambil posisi berseberangan dengan sejarah “resmi”. Pada pilihan pertama, pengarang lebih berperan sebagai tukang cerita masa silam. Sedangkan pilihan kedua memposisikan penulisnya untuk mengkritisi sejarah yang resmi atau bahkan menciptakan versi lain dari sejarah sebagai sebuah tandingan dari sejarah itu sendiri.
Berhadapan dengan novel: Bulang Cahaya, dengan jelas terlihat upaya pengarang-pengarangnya dalam memanfaatkan sejarah untuk melakukan rekonstruksi ulang tentang sejarah dan identitas budaya Melayu. Dalam Bulang Cahaya dilakukan rekontruksi ulang tentang sejarah dan identitas budaya kerajaan Melayu Raiu Lingga. Tentu saja rekontruksi sejarah dan identitas budaya yang dilakukan pada novel ini tidak seperti apa yang dilakukan oleh para ahli sejarah dari sudut akademi sejarah ansich, tetapi lebih cenderung seperti apa yang dikatakan sejarawan Taufik Abdullah (1983) sebagai ‘nothing but story’, sejarah yang menekankan gaya literer. Dalam hal ini novel dan sejarah saling mempengaruhi sebagai suatu narasi yang harus dapat dinikmati tapi tak terlepas dari kenyataan empiris.
Sebagai kisah-kisah narasi yang dapat dinikmati, novel Bulang Cahaya menyuguhkan suatu cerita manusia yang di dalamnya penuh dengan tematik-tematik kehidupan. Di dalamya terdapat tragedi, penderitaan, kekuasaan, cinta dan konflik-konflik internal psikologis seperti lazimnya sebuah kehidupan. Dalam hubungannya dengan sejarah, cerita atau naratif itu dipusatkan pada suatu pusaran waktu atau periode tertentu, yang di dalam pusaran waktu yang tertentu itu terkait peristiwa-peristiwa yang mungkin secara lahiriah hanya terjadi atau ditemukan pada periode masa itu.
Sebagai pengarang, Rida K Liansi memberi referensi imajinasi ke dalam sejarah sehingga novel yang mereka sajikan tetap memiliki sifat simbolik karena itu ketika bersinggungan dengan sejarah menyebabkan sejarah (dalam novel-novel tersebut) menjadi suatu problematik. Karena sifat simbolis yang menyediakan medan luas yang kaya dengan interprestasi, bagaimanapun juga novel akhirnya memang tidak dapat dijadikan sumber utama sejarah meskipun sebenarnya ia ‘mempertanyakan’ sejarah itu sendiri.
Pertanyan-pertanyaan elementer dalam disiplin ilmu sejarah tentang “apa, siapa, di mana dan apabila” tidak bisa mendapatkan jawaban yang mutlak dengan menggunakan novel sebagai sumber. Tetapi dengan memanfaatkan sejarah, Rida K Liamsi melalui novel Bulang Cahaya melalui novel Tambo dapat memberikan ‘pantulan-pantulan’ tertentu tentang perkembangan pikiran, perasaan dan orientasi masa silam yang bermanfaat pada masa sekarang dan mungkin yang akan datang, atau bisa jadi secara substansial dapat terulang dalam sejarah berikutnya.
Rekontruksi Sejarah dan Identitas Budaya dalam Bulang Cahaya
Novel Bulang Cahaya karya Rida K Liamsi merupakan sebuah teks sastra yang terinspirasi sekaligus mencoba mengolah sejarah kerajaan Riau-Lingga yang membentang dari kepulauan Riau sampai ke pantai timur semenanjung Malaysia. Sebagai sebuah novel yang mengolah sejarah, novel ini mencoba menafsirkan sejarah dengan caranya sendiri. Meskipun tentu saja karena memang diniatkan sebagai sastra sejarah, pengarangnya mempelajari berbagai sumber sejarah Kerajaan Riau Lingga seperti Tuhfat an Nafis karya Raja Ali Haji, Silsilah Melayu Bugis, dan Sejarah Riau.
Dalam mengolah sejarah menjadi sebuah teks sastra, Rida K Liamsi menghadirkan novel Bulang Cahaya sebagai kisah sekaligus berita pikiran. Sebagai kisah, novel Bulang Cahaya bercerita tentang suatu masa dalam sejarah Riau dan kisah tragedi percintaan tokoh-tokohnya, dan sebagai berita pikiran novel ini mencoba menyampaikan gagasan, pemikiran dan pendapatnya sendiri tentang realitas (termasuk realitas sejarah). Meskipun realitas yang ditampilkan dalam novel ini tentu bukan merupakan realita sui generis, namun semuanya diolah berdasarkan fakta dan data-data.
Dalam novel Bulang Cahaya ini pengarang mengisahkan masa transisi pemerintahan kerajaan Riau-Lingga sepeninggal Sultan Mahmud yang wafat pada 12 Januari 1812 M dimana kerajaan diperebutkan oleh kedua putera tirinya yakni Sultan Husin dan Sultan Abdurrahman. Hal ini merupakan turning point kemunduran kebudayaan dan kekuasaan kerajaan Riau. Menurut data sejarah, akhirnya kedua saudara tiri yang berseteru ini melibatkan pihak-pihak asing yang justru membelah kerajaan.Sultan Husin meminta bantuan pihak Inggris sedangkan kelak Sultan Abdurrahman meminta bantuan pemerintah Hindia Belanda. Novel Bulang Cahaya ini memang berakhir tidak sampai pada peristiwa terbelahnya kerajaan Riau dan masuknya Inggris dan Belanda di Kerajaan Riau, tetapi hanya sampai pada saat Sultan Abdurrahman dinobatkan sebagai Sultan oleh Raja Jaafar yang menjabat wali negara. Namun ending novel sudah menyiratkan kepada pembaca bahwa kelak akibat penobatan ini kerajaan Riau menjadi runtuh.
Secara struktur novel dikembangkan dengan sangat sederhana menggunakan pola cerita berbingkai seperti dalam cerita Kisah 1001 Malam. Dimulai dengan bagian “Prolog” sebagai bingkai awal dimana tokoh pencerita bernama Raja Ihsan mendapatkan kiriman naskah kuno dari sahabatnya dari negeri Belanda. Isi naskah kuno inilah yang menjadi isi novel Bulang Cahaya, tentang kisah asmara tokoh Raja Jaafar dengan puteri Tengku Buntat yang tak berkesampaian karena faktor politik dan kekuasaan, sampai Jafaar menjadi Yang Dipertuan Muda hingga “berhasil” membalaskan dendam cintanya dengan menggagalkan suami mantan kekasihnya menjadi Sultan dengan cara mengangkat adik tirinya menjadi Sultan. Jadilah novel ini berbicara tentang tragedi cinta yang berkelindan, bersilang sengkarut bahkan berbenturan dengan kekuasaan dengan akhir yang sangat dahsyat: runtuhnya sebuah imperium besar bernama kerajaan Riau-Lingga.
Dalam novel ini pengarangnya seakan-akan membuat versi lain tentang Sejarah Melayu Lingga yang berbeda dengan versi yang sudah ada. Hal ini tampak ketika pengarang justru menempatkan tokoh Raja Djaafar sebagai tokoh utama sekaligus hero cerita. Dipilihnya tokoh Raja Djaafar sebagai hero dan tokoh utama dalam novel menjadi sangat menarik karena hampir semua versi sejarah dari buku-buku sejarah temtang Riau peranan Raja Djaafar (Jaafar) sebagai Yang Dipertuan Muda tidak dianggap dominan. Peranan Raja Djaafar dalam kitab Tuhfat al-Nafis —yang dianggap sejarah “resmi” kerajaan Riau—- yang tampak menonjol dan “dipuji” hanya tampak ketika tokoh ini berhasil melaksananakan perintah Yang Dipertuan Besar (Sultan) Sultan Mahmud untuk menagkap dan memenggal kepala seorang tokoh agama bernama Lebai Kemat yang berasal dari Minangkabau yang mengajarkan ajaran sesat bahwa ia adalah Tuhan.
Pemilihan tokoh Raja Djaafar sebagai tokoh utama, hero dan protagonis juga merupakan keberanian pengarang menentang arus sejarah resmi kerajaan Melayu mengingat selama ini dalam berbagai versi tentang sejarah Melayu, Raja Djaafar lebih dianggap sebagai tokoh antagonis penyebab keruntuhan kerajaan Raiu-Lingga. Sedangkan yang selalu dianggap sebagai tokoh protagonist dan hero dalam sejarah “resmi” Melayu adalah Engku Putri Hamidah adik tiri dan saudara seayah Raja Djaafar yang merupakan isteri keempat Sultan Mahmud Marhum Besar. Dalam novel pengarang dengan transparan menempatkan posisinya yang berseberangan secara politis denga Raja Djaafar. Bahkan dalam kitab-kitab babon sejarah Melayu,–misalnya Tuhfat al-Nafis, Raja Djaafar disebut-sebut sebagai biuang keladi runtuhnya kerajaan Riau Lingga karena menobat Sultan Abdulrahman putera tiri kedua Sultan Mahmud tanpa meminta persetujuan Engku Puteri sebagai pemegang regalia kerajaan.Hal inilah yang menjadi perhatian utama dalam kaitannya dengan identitas budaya yang sebenarnya merupakan persoalan marwah dan martabat Melayu. Marwah merupakan kunci identitas kebudayaan Melayu sekaligus merupakan trade mark budaya Melayu yang tak lekang oleh zaman. Marwah yang berkaitan dengan kebesaran kedaulatan (kerajaan) sering disimbolkan dengan alat-alat upacara yang dipakai dalam ritual kenegaraan.
Menurut berbagai sumber dari sejah Melayu, regelia kerajaan atau alat-alat kebesaran adat istiadat dalam adat istiadat Melayu dianggap sakral dan keramat karena melambangkan kebesaran dan kekuasaan yang berpengaruh pada kosmologi kesemestaan merupakan puncak simbolisasi dari marwah kebudayaan kerajaan Riau Lingga. Semua benda-benda regelia menjadi sangat penting pada saat pelantikan seorang raja atau Sultan. Penabalan atau penobatan seorang raja dianggap tidak memenuhi syarat, tidak bermartabat dan tak bermarwah apabila tidak disertai oleh kebesaran regelia ini. Dan Engku Puteri sebagai pemegang regelia kerajaan tidak bersedia melantik Sultan Abdurrahman atau Tengku Jumat sebagai Sultan.
Namun dalam novel Bulang Cahaya Raja Djaafar yang menjabat sebagai Yang Dipertuan Muda berani mengabaikan peranan alat-alat regelia kerajaan, seperti ditunjukkan pada kutipan berikut:
“Baiklah kalau begitu. Sebagai saudara tua dan sebagai Yang Dipertuan Muda, kakanda sudah sampaikan apa yang patut kakanda katakana. Kakanda telah memutuskan akan tetap menabalkan Tengku Jumat sebagai Sultan Riau, meskipun hanya dengan sehelai bulu ayam yang diletakkan di belakang kepalanya. Sekarang kita bersurai!” Suara Djaafar keras dan tajam. Belum pernah dia sekasar itu pada adiknya Engku Puteri (hal 283).
Kutipan di atas menunjukkan bagaimana identitas kebudayaan dicoba untuk direduksi dengan memasukkan nilai-nilai, konsep, dan pandangan baru. Tentu saja hal ini bukan berarti tanpa konflik dan tanpa resiko. Pandangan Raja Jaafar dalam novel seakan-akan menyuarakan arus jaman “baru” yang senatiasa siap untuk bernegoisasi dengan segala perubahan.
Sebaliknya pula, tokoh Engku Puter Raja Hamidah sangat mengagungkan marwah kerajaan. Pelantikan seorang raja tanpa kebesaran relegia kerajaan sama dengan mempermalukan kerajaan, membuat kerajaan kehilangan marwah dan martabatnya, seperti terkutip di bawah ini. Tokoh ini seakan-akan tampil mewakili arus “tua” yang ingin terus menggegam identitas kebudayaan yang sudah diraihnya tanpa kompromi, seprti tampak pada kutipan berikut:.
Pulang ke Penyengat. Biarkan beta yang menanggung akibatnya. Hanya ini lagi yang menjadi marwah kerajaan. Kalau regelia inipun sudah digunakan untuk yang salah, tak ada lagi gunanya. Tak ada lagi marwah.Tak ada lagi adat kerajaan. Biarkan Raja Djaafar yang menanggung beban hinaan itu” katanya kepada para hulubalang, pengawalnya. Suaranya melengking tinggi. Penuh kemarahan. Air matanya meleleh di sudut matanya … (hal. 311).
Sejarah memang akhirnya mencatat bagaimana perseteruan Sultan Husin (Tengku Long) bversama Engku Puteri Hamidah berhadapan dengan adiknya, Sultan Abdulrahman (Tengku Jumat) bersama Raja Djaafar akhirnya melibatkan pihak-pihak asing. Tengku Long meminta bantuan Inggris dan memisahkan Tumasek (Tumasik) dan Johor dari Kesultanan Riau, sedangkan Abdulrahman meminta bantuan Belanda. Dengan pihak Inggris Tengku Long (Sultan Husin) yang tetap berambisi menjadi Sultan Riau menerapkan money politic dengan mengkompensasikan regelian kerajaan dengan uang sebesar 50.000 ringgit Spanyol. Di pihak lain, Sultan Abdulrahman meminta bantuan Belanda menerapkan paksaan untuk merrebut regalia kerajaan dengan mengepung istana Engku Puteri di Pulau Penyengat. Dan sejarah mencatat pada tanggal 13 Oktober 1822 regelia kerajaan dapat direbut dan digunakan melantik ulang Abdulrahman sebagai Sultan Riau. Setahun kemudian terjadilah perjanjian Trakat London yang membelah kerajaan Riau Lingga menjadi dua. Tumasik menjadi wilayah dalam pengaruh Inggris dan Riau di bawah pengaruh Belanda. Kelak kemudian hari Tumasik jatuh seutuhnya di tangan Inggris dan di Riau pun Sultan takluk di bawah kaki Belanda.
Dalam novel ini dalam kaitannya dengan sejarah pengarang ingin menunjukkan bahwa sejarah yang meskipun merupakan masa lampau terpisah dari “masa kini”, namun bukan berarti tidak berhubungan. Pada satu fihak memang ada keterpisahan antara keduanya dimana masa lalu tidak mungkin dikembalikan atau digantikan, namun di pihak lain masa lampau sebenarnya tetap hidup dalam diri kita. Sesuatu yang terjadi pada masa lampau secara substansial dapat saja terjadi dan dialami pada saat ini atau masa yang akan datang.Dengan begitu, masa lampau sebenarnya tidak pernah terpisah secara mutlak dari masa kini. Ada benang halus yang dapat menjembataninya, yang mungkin saja benang halus ini dapat berubah menjadi tali besar sehingga masa lampau itu berubah menjadi sesuatu yang kembali konkrit pada masa kini.
Rekontruksi identitas yang dilakukan Rida K Liamsi melai Bulang Cahaya ingin menunjukan kepada pembacanya bahwa dalam menilai masa lampau selalu ada dua hal yang saling mempengaruhi. Pertama, hubungan kita dengan masa kini, dan kedua, tanggapan kita terhadap masa lampau itu sendiri. Kekecewaan terhadap masa kini dapat menyebabkan seseorang untuk mengidealkan masa lampau, dengan kata lain kita dapat kembali melancong ke masa lampau untuk menyadarkan kan kebobrokan damn ketidaksempurnaan masa kini. Masa lalu dapat menjadi cermin atau mematut diri di masa kini sekaligus menjadi “kitab referensi” menghadapi masa yang akan datang, meskipun tentu saja referensi ini tidak bersifat formal atau kaku tetapi lebih cenderung menghadirkan subtansial masalah yang mungkin terulang dalam bentuk atau wujud material yang berbeda.
Dalam merekontruksi sejarah dalam novel tersebut, pengarang tidak mendekati sejarah melalui pendekatan monumental tetapi lebih cenderung pada pendekatan
antikurian dan pendekatan kritis. Melalui pendekatan antikurian, pengarang tidak memandang sejarah semata-mata sebagai penyimpan peristiwa-peristiwa besar kemanusiaan dari masa lalu supaya tidak ditelan oleh waktu, namun lebih terfokus untuk memandang sejarah sebagai sebuah kesadaran identitas lampau yang berkesinambungan dan memberikan arah masa depan. Sedangkan dengan pendekatan kritis, pengarang membuka kemungkinan untuk menguji, mengkaji ulang, dan menafsirkan kembali peristiwa masa lampau untuk kepentingan masa datang. Sejarah diperlakukan sebagai suatu organesme yang berkembang dan lahir kembali atau sebagai sebuah siklus alamiah peradaban manusia yang dapat menjadi persoalan abadi bagi manusia sebagai pembentuk peradaban.
Dengan demikian secara kreatif melalui novel Bulang Cahaya sejarah tidak dibeberkan sebagai fakta telanjang seperti halnya kelompok annals dari Perancis yang memandang sejarah terbatas pada hubungan waktu dan kronologis semata-mata. Tidak hanya memandang sejarah sebagai past significane (hanya penting untuk peristiwa masa lampau), tetapi secara kreatif mencoba memandang sejarah dengan hubungannya dengan masa kini (present meaning), bahkan masa yang kelak datang (future meaning). Sejarah mejadi sebuah medan yang selain membuka tafsir baru ia juga menyimpan potensi-potensi yang signifikan untuk lahirnya sejarah baru sekaligus juga berfungsi sebagai tengara untuk mengingatkan manusia atas berbagai kemungkinan baik atau buruk pada masa silam dan masa datang.
Upaya pengarang dalam melakukan rekontruksi identitasnya ini dapat dilihat sebagai cara untuk menyampaikan dua hal. Pertama, pengarang mencoba memungut realitas sejarah karena menganggap identitas masa lampau berhubungan dengan perubahan social budaya yang dapat diamati berdasarkan pemikiran dialektika budaya. Kedua, melalui realitas sejarah tersebut pengarang ingin mengajak pembacanya untuk melakukan comparative dan pengkajian ulang (intropeksi diri) dengan realitas yang dialaminya kini.
Dialektika Budaya Dalam Novel Bulang Cahaya
Kebudayaan atau cultur merupakan konsep yang sangat tua. Pada mulanya kebudayaan dipandang sebagai sistem makna secara sinkronik dan a-historis. Kemudian kebudayaan dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan konsistensi dan integrasi antar unsurnya, dan kemudian kebudayaan dipahami sebagai semacam konsesus sosial tentang kepercayaan, sikap dasar, dan disposisi yang tepat. Namun akibat dari pergeseran paradigma kini lebih strategis memandang kebudayaan sebagai proses pertukaran dan proses pengaruh-mempengaruhi dalam sejarah secara komplek. Kebudayaan merupakan gambaran sementara dan imajinatif tentang persilangan-persilangan dari berbagai aliran.
Dengan demikian kebudayaan selamanya ditandai dengan inkonsistensi, inkoherensi, serta sisi-sisi yang maknanya bagi daya kognisi kita masih dalam proses menjadi. Kebudayaan adalah suatu proses dialektika yang dinamis, kebudayaan bukan sesuatu yang given yang dengan sendirinya ada dan tidak akan berubah. Kebudayaan justru akan selalu berubah dan bergeser, namun mencairkan kemapanan sosok kebudayaan akan tergantung dari ramuan dialektika berbagai sistem dan nilai.
Dalam novel Bulang Cahaya selain tergambar upaya rekontruksi sejarah dan identias budaya, juga diperlihatkan bagaimana sebuah sistem budaya lahir melalui dialog dan proses pertukaran dan pengaruh-mempengaruhi antara budaya-budaya yang berlainan.Dalam Bulang Cahaya tampak bagaimana terjadinya pertemuan budaya Bugis dan Melayu yang mempengaruhi kekuasaan di kerajaan Riau Lingga. Pertemuan sekaligus dialektika budaya Bugis-Melayu menandai dinasti baru dalam kerajaan Riau yakni dinasti Abdul Jalil Riayatsyah sebelum akhirnya 100 tahun kemudian terbelah karena perjajnjian Trakat London. Dialektika budaya Bugis-Riau ini akhirnya membuahkan sistem ketatanegaraan Melayu menjadi dua sistem penyelenggara pemerintahan, yakni jabatan Yang Dipertuan Besar dan jabatan Yang Dipertuan Muda. Yang Dipertuan Besar merupakan puncak pimpinan pemerintahan atau Sultan yang mengurusi masalah agama, adat dan pemerintahan umum dan jabatan ini senantiasa menjadi hak keturunan Melayu. Jabatan kedua disebut Yang Dipertuan Muda yang memegang kendali pemerintahan dalam bidang pertahanan dan keamanan yang menjadi hak Bugis.
Dalam Bulang Cahaya juga ditemukan pandangan bagaimana sebuah perkawinan merupakan sesuatu yang sakral namun juga dapat dimanfaatkan sebagai jalur diplomatik budaya untuk melanggengkan kekuasaan dan menjalin silaturahmi budaya dan politik sekaligus.Untuk menjalin silaturahmi budaya antara Bugis dan Melayu dilakukan pernikahan “silang” antara tokoh-tokoh Bugis dengan bangsawan Riau. Daeng Marawa dan Daeng Celak dikawinkan dengan Tengku Tengah dan Tengku Mandak, saudara muda Sultan. Pada titik inilah persoalan seksual tidak saja sekedar diperlakukan dan dianggap sebagai sebuah “kenikmatan” tetapi lebih dari itu selalu dikaitkan dengan persoalan kekuasaan. Hal ini oleh Foucault dikatakan sebgagai agregasi hubungan-hubungan sosial yang secara historis dan berkelindan dengan rezim kekuasaan. Motif seks sebagai pintu menuju kesepakan kekuasaan ini tidak saja terjadi di kerajaan Riau-Lingga tetapi juga oleh wanita-wanita di kerajaan-kerajaan nusantara laiinya.
Di Jawa misalnya, dalam kitab Pararaton, tokoh Ken Arok pendiri kerajaan Singasari yang menjadi cikal bakal kerajaan Majapahit untuk melenggang ke kursi kekuasaan memperistiri Ken Dedes isteri dari rival politiknya, Tunggul Ametung. Perkawinan politik yang merupakan perwujudan kuasa seksual terhadap kepentingan kekuasaan sebagai sesuatu yang sah dan formal juga tampak pada masa pemerintahan Raja Kameswara II di Kediri (1104-1222). Untuk menyelesaikan perang saudara yang berlarut-larut antara Kediri (Daha), Kahuripan (Jenggala) dan Gegelang, Raja Kameswara II yang berasal dari Kahuripan menikahi puteri Sekar Tadji (Candra Kirana) dari kerajaan Daha. Pernikahan politis seperti ini juga dilakukan oleh Raja Majapahit pertama Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana yang untuk membendung invasi kerajaan Cina (Tartar) menikahi dua puteri asing dari kerajaan Campa dan Cina yang bernama puteri Dara Petak dan puteri Dara Jingga. Demikian pula pada masa yang lebih muda, pada masa pemerintahan Mataram Islam dibawah kekuasaan Sultan Agung, untuk memadamkan pemberontakan Surabaya Sultan Agung menikahkan puterinya yang bernama Wandan Wangi dengan Pangeran Pekik penguasa Surabaya sekaligus memanfaatkan pelabuhan Surabaya sebagai pangkalan armada laut untuk memadamkan pemberontakan di sepanjang pesisir utara.
Dialektika budaya Bugis dan Melayu dalam Bulang Cahaya ini juga nampak dalam novel Tambo yang juga berlatar Melayu tetapi berdialetika dengan Jawa.. Melalui dua tokoh utamanya, yakni Sutan Balun dengan kakaknya Sutan Marajo digambarkan pertemuan dua paham kebudayaan yang bertolak belakang. Sutan Marajo atau Adityawarman, yang karena sejak kecil di besarkan di Jawa (Majapahit) menganut paham kekuasaan sentralistik, otoriter, dengan tumpuan pada pemujaan kekuatan perang berhadapan dengan Sutan Balun yang karena pengembaraannya yang luas lebih condong pada paham yang berpola desentralistik dan lebih egaliter.
Perbedaan pola budaya yang berbeda tersebut pada dasarnya menggambarkan khazanah perbendaharaan budaya Indonesia yang memang diwakili dua kutub yang saling bertolak belakang. Kutub Jawa yang berpola sentralistik, sentripetal, dan feodalistik berhadapan dan bersinggungan dengan kutub budaya Melayu yang berpola desentralistik, sentrifugal, dan lebih egaliter. Pilar budaya Jawa secara par excellence diwakili budaya Mataram (Mentaraman) yang berakar dari kebudayaan Majapahit, dan budaya Melayu yang secara par excellence pula diwakili Minangkabau..
Dalam novel Bulang cahaya terlihat ada tandingan konsepsi pola kepemimpinan Jawa dan pola kepemimpinan Melayu. Pola kepemimpinan Jawa, raja selalu dipandang sebagai pusat kekuasaan dan kekuatan bahkan pusat kosmologi semesta. Konsep ini tercermin dengan doktrin kekuasaan dan gelar-gelar raja Majapahit dan selanjutnya menurun pada dinasti kerajaan Mataram sebagai penguasa-penguasa besar di tanah Jawa.
Doktrin seperti misalnya: sabda pandhita ratu, ratu gung binathara bau dhendha anyakrawati, Rajasanagara Sang Amurwabhumi) (Maharaja Negara Pemelihara Bumi) yang kemudian berlanjut pada gelar-gelar raja Mataram (Mentaram Islam): Pakubuwono, Hamengkubuwono, Sayidin panatagama khalifatullah serta konsep patrilineal, menunjukan bagaimana kekusaan seorang raja (pemimpin) bersifat mutlak dan tergugat. Dengan gelar-gelar kebesaran itu kekuasaan Raja-raja atau pemimpin Jawa tidak saja sebagai pusat kekuasaan sosial tetapi juga menjadi pusat kosmos atau semesta, bahkan menjadi wakil Tuhan di bumi. Raja sebagai Tuhan dan rakyat sebagai titah atau mahluk yang tergantung sepenuhnya pada tangan kekuasaan Raja.
Paham dan konsep kepemimpinan Jawa yang cenderung otoriter, patrilineal, dan feodal ini berhadapan dengan konsep dan pola kepemimpinan Melayu yang lebih demokratis dan egaliter dimana raja bukan merupakan pusat kekuasaan apalagi pusat semesta. Hal ini diperlihatkan dalam Bulang Cahaya ketika Raja Jaafar mengangkat Sultan Abdulrahmansyah sebagi Sultan. Faktor geneologi atau “trah” dan garis keturunan raja tidak memiliki kebenaran yang mutlak tapi dapat juga dikritik atau dikontrol. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan Melayu senantiasa bersifat lentur terhadap pengaruh budaya-budaya lainnya.
Dalam novel Bulang Cahaya juga terdapat dialog-dialog antar tokoh-tokohnya terkait dengan ketegangan suksesi pemerintahan, sengketa dan perselisihan kekuasaan dan martabat.. Namun nampak ditonjolkan bagaimana diaolog-dialog panjang terkait dengan musyawarah, kebijakan bersama, perundingan, dan dialog budaya dapat lebih efektif bagi perkembangan kekuasan, peradaban dan keseimbangan semesta daripada peperangan dan kekerasan yang hanya menyisakan kesewenangan dan penderitaan apapun motif dari peperangan itu.
Secara tersirat melalui novel tersebut pengarang dengan halus ‘menyindir’ dan mengritik (otokritik) peradaban dan sejarah kekuasaan Melayu (juga daerah Nusantara lainnya) yang penuh dengan penaklukan, peperangan dan kekerasan. Sejarah memang menunjukkan bahwa sejarah peradaban kerajaan-kerajaandi Nusantara tidak lepas dari peperangan, penindasan, dan penaklukan. Kerajaan Singasari di Jawa misalnya, kerajaan cikal-bakal Majapahit ini membangun imperium kekuasaannya lewat pertumpahan darah antara Tumapel, Singasari, dan Kediri. Kerajaan terbesar di Jawa bahkan Nusantara, Majapahit, lahir dari serangkaian pertumpahan darah yang dimulai dengan pengkhianatan Jayakatwang Raja Kediri yang menghancurkan Kartanegara, Raja terakhir dari Singasari, yang kemudian berbalas dengan tampilnya menantu Kartanegara yakni R. Wijaya yang ganti menaklukan Jayaktwang dan menghancurkan Kediri lalu mendirikan Majapahit. Majapahit kemudian menjadi besar dan menjelma imperium raksasa karena ekspansi Gajahmada dengan kekuatan armada lautnya (Jaladry mantri) di bawah pimpinan laksamana laut Mpu Nala dan akhirnya Majapahit runtuh juga karena perang saudara (perang Paregreg) dan balas dendam Girindawardhana dari Kediri.
Di Melayu sendiri kekerasan dan peperangan telah terjadi semenjak awal Sriwijaya hingga terjadi pula perebutan kekuasaan dan konflik politik di kerajaan Johor antara Tengku Sulaiman keturunan Sultan Abdul Jalil Riayatsyah yang berkuasa di Johor dengan Raja Kecik keturunan Sultan Mahmud yang dibesarkan di Istana Pagarruyung Minangkabau. Sultan Mahmud merupakan Sultan Johor sebelum Sultan Abdul Jalil Riayatsyah yang tewas dibunuh Megat Sri Rama panglimanya sendiri yang berasal dari Bintan. Sampai pada puncaknya perselisihan antara Raja Husen dan Sultan Abdurahman, antara Raja Jaafar dengan kakanya Engku Hamidah, yang melibatkan pihak asing Belanda dan Inggris yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Riau-Lingga.
Sentuhan Imaji, Romantisme,Tragedi dan Ironi.
Dengan sentuhan imajinasi pengarangnya, novel Bulang Cahaya ini seakan-akan memberikan lakon carangan baru sekaligus penafsiran tentang runtuhnya kerajaan Raiau-Lingga. Tokoh-tokoh dalam sejarah yang cenderung selalu ditampilkan secara mutlak hitam-putih, dalam novel dihadirkan sebagai sosok manusia utuh yang memiliki kompeksitas jiwa dan watak.
Tokoh-tokoh seperti Raja Djaafar, Engku Puteri, Sultan Mahmud Syah, juga tokoh-tokoh lain dihadirkan selain sebagai tokoh berwatak tegar juga dihadirkan sebagai manusia pada satu titik dapat menjadi lemah, merana dan putus asa. Dengan membaca novel ini pula pembaca dapat menyelami dan menilai tokoh Raja Djaafar tidak saja semata-mata sebagai tokoh penentu sejarah runtuhnya kerajaan Riau-Lingga, namun juga dapat menyelami keterbelahan jiwanya, beban status dan kewajibannya, serta bagaimana rumitnya posisinya sebagai keturunan Bugis-Melayu dalam konstelasi politik Raja-raja Melayu.
Di dalam Bulang Cahaya ini pula tergambar bagaimana tragedi dan ironi hadir sebagai kisah yang menrenyuhkan sekaligus mengasyikan untuk dilihat didengar dan dibaca. Novel ini juga memperlihatkan bagaimana dalam peristiwa-peristiwa besar, di balik tokoh-tokioh besar penentu sejarah, di belakangnya baik secara terang-terangan atau tersembunyi hadir sosok wanita-wanita yang turut menjadi penentu sebuah sejarah. Di balik nama mahsyur Napoleon Bonaparte, ada baying-bayang perempuan bernama Maria Josephine. Di balik keperkasaan Antonius muncul lirikan tajam Cleopatra. Dalam dunia fiksi dan mitologi pun di balik sosok tokoh Yudistira yang jujur namun peragu ada perempuan tegar bernama Drupadi. Sebaliknya pula di balik tokoh Destarata yang lemah hati ada sosok Gendari yang penuh ambisi.
Dalam novel Bulang Cahaya ini dapat pula ditemukan dua citra wanita yang bertolak belakang. Yang pertama adalah citra wanita perkasa, tabah, kuat dan pantang menyerah, Sedang citra kedua adalah sosok perempuan lemah, pasrah dan tidak berdaya dalam pusaran nasib. Citra pertama diwakili oleh tokoh Engku Puteri Hamidah, citra yang kedua diwakili oleh Engku Buntat, kekasih Raja Djaafar.
Tokoh Engku Puteri adalah sosok gigih, tak kenal kompromi dan penuh dinamika. Tokoh ini merupakan tokoh perempuan paling disegani dan dihormati pada masa akhir kerajaan Raiu-Lingga. Engku Putei merupakan isteri keempat Raja Mahmud Marhum Besar, sekaligus pula salah satu puteri Raja Ali Haji dari isterinya yang bernama Raja Perak binti Yang Dipertuan Muda Riau III Daeng Kamboja. Karena keteguhan hatinya Engku Puteri diberi kepercayaan sebagai pemegang regalia kerajaan dan selalu meletakkan kepentingan adapt dan tradisi Negara di atas segala-galanya. Sedangkan tokoh Engku Buntat adalah citra wanita yang tak berdaya, tak mau melawan, dikalahkan oleh cinta dan akhirnya tergerus oleh putaran politik dan kekuasaan.
Dalam novel, Engku Buntat mendapatkan nasib malang dimana cinta kasihnya bersama Raja Djaafar gagal akibat kepentingan politik dan kekuasaan. Nasib malang tokoh ini merupakan pengulangan cerita lama nan malang tentang nasib wanita-wanita di tengah pergolakan kekuasaan dan intrik politik kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ihlas atau tak ihlas, Engku Buntat harus bersedia menjadi tumbal intrik dan strategi politik kekuasaan, harus bersedia melakoni sebuah pernikahan politis untuk menyelesaikan sengketa dan perang saudara antara bangsawan Melayu asli dengan Melayu Bugis.
Dengan latar pernikahan politis ini pengarang mencoba menyiratkan bahwa cerita novel Bulang Cahaya ini tak sekedar kisah kasih tak sampai, tetapi juga ingin menyampaikan kepada pembacanya bagaimana seksualitas sejak masa silam merupakan bagian dari scenario politik dan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu berada. Dalam bahasa novel Bulang Cahaya, ini dikatan sebagai “pernikahan adalah bagian dari siasah, dan pemerintahan adalah siasah itu sendiri.
***
Membaca Bulang Cahaya memang cenderung lebih mengasyikan ketimbang mengerutkan kening. Pengarang memang tidak bermaksud mengajak pembaca berpusing-pusing mencerna isi novel namun lebih cenderung membetot perasaan, simpati dan empati pembaca dengan menyuguhkan sebuah kisah cinta di balik wiracarita. Dengan kata lain baik secara struktur maupun gaya bercerita novel ini tampil dengan sederhana dan tak mau berumit-rumit, juga tak begitu memperhatikan eksplorasi literer. sehingga mudah untuk dicerna dan dihayati oleh pembacanya.
Membaca novel ini mengingatkan penulis pada cerita-cerita bersambung S.H Mintaredja yang sangat populer di harian Kedaulatan Rakyat Yogjakarta, yakni serial Api di Bukit Menoreh atau Keris Nagasasra-Sabuk Inten. Baik novel Bulang Cahaya dan Api di Bukit Menoreh hadir dengan struktur yang sederhana namun ceritanya lancar mengalir, memikat, membetot dan mengasyikan. Yang membedakan keduanya adalah stting ceritanya, kalau Api di Bukit Menoreh mengambil latar sosial budaya kerajaan Mataram Islam Jawa di era Panembahan Senopati (raja Mataram pertama), Bulang Cahaya bersetting sosial budaya kerajan Riau menjelang keruntuhan kerajaan Riau.
Dengan membaca novel Bulang Cahaya ini, lamat-lamat pembaca dapat menangkap bagaimana pengarang mengingatkan bahwa sejarah masa lalu dapat menjadi cermin tempat kita mematut diri di masa kini. Masa lalu dapat dijadikan referensi untuk menghadapi masa yang akan datang, meski tenntu saja referensi ini tidak bersifat formal, kaku dan absolut tetapi lebih cenderung menghadirkan substansial maslah yang mungkin terulang dalam bentuk atau wujud material yang berbeda.
Membaca novel ini, pembaca dapat lebih arif menyikapi sejarah. Tidak ada kemutlakan dan ketunggalan dalam sejarah, sejarah dapat hadir sebagai sebuah medan yang senantiasa menyimpan peluang untuk membuka tafsir baru. Seajarah akan senatiasa menyimpan potensi-potensi signifikan untuk lahirnya sejarah baru sekaligus berfungsi sebagai tengara mengingatkan manusia atas berbagai kemungkinan baik atau buruk pada masa silam dan masa datang.
Dari uraian-uraian di atas pula, melalui dialektika budaya yang terdapat di dalamnya, novel Bulang Cahaya mencoba memberikan gambaran bagaimana Melayu senatiasa berproses untuk terus membetuk “ke-Melayuannya” dengan mengakomodasi, berdialog dan bersilangan dengan pola-pola kebudayaan laiinya. Sekaligus pula novel ini menunjukan bagaimana Melayu tetap mampu memberikan sumbangan bagi kekayaan sastra Indonesia modern.
Novel itu juga mengingatkan kepada kita bahwa bipolarisme budaya dan warna lokal budaya merupakan sebuah kewajaran. Bipolarisme dan warna lokal budaya mestinya tidak ditanggapi secara subyektif, emosional dan politis dan dianggap sebagai “sara”, tetapi harus ditanggapi secara rasional, kritis dan intelektual. Dengan menanggapi bipolarisme secara kritis-intelektual-rasional justru dapat dikaji sisi-sisi kelemahan dan keunggulan kutub-kutub budaya bangsa sekaligus dapat dilihat sejauh mana validitas dan signifikansinya bagi sebuah pertemuan dan dialektika antar budaya yang fair dan balance.
Dengan dialektika budaya di dalamya, novel Bulang Cahaya juga membuka mata kita bahwa budaya dan kebudayaan tidak harus selalu disikapi sebagai sesuatu yang “harus harmoni”, tetapi budaya dan kebudayaan selain mengandung unsur harmoni juga menyimpan unsur “konflik” yang justru berguna bagi keberlangsungan kebudayaan selama “konflik” itu terjadi secara fair, sehat, dan alamiah. Spektrum Indonesia (budaya Nusantara) yang luas dan beraneka sehingga secara ‘kodrati’ selain menyimpan keharmonisan juga menyimpan konflik budaya yang dapat bersifat konstruktif bagi kebangsaan dan kenegaraan. Konflik budaya yang fair akan membuka pintu terciptanya dialektika budaya dan pada gilirannya dapat membawa ke arah proses tranformasi budaya etnik ke budaya negara-kebangsaan serta transformasi sosial-politik yang lebih egaliter.
Melalui upaya rekontruksi sejarah dan dialektika budaya di dalamnya, novel ini menyiratkan bahwa konsep bhineka tunggal ika perlu dihidupkan kembali tetapi dengan lebih menekankan kepada ke-bhineka-annya, kepada keberagamannya, bukan pada ika-nya secara sempit. Pemahaman kesatuan dan bangunan nasionalisme justru harus mencerminkan secara transparan keanekaragaman berbagai sistem budaya di nusantara yang saling melengkapi. Masing-masing keanekaragaman itu harus disikapi sebagai produk-produk budaya yang sama-sama memiliki potensi yang berimbang dan sederajat untuk membentuk kebudayaan Indonesia.
***********
*Penulis adalah penyair dan esais. Doktor sastra lulusan UNS Solo. Tinggal di Ngawi Jawa Timur.
_________________
- Ada bermacam-macam klasifikasi lambang budaya dalam kehidupan manusia. Riceour (1991;117) membagi lambang budaya menjadi lambang verbal dan lambang piktorial. Cassirer (1987), Soedjatmoko (1994), dan Kuntowijaya (1987; 1994; 1995) membagi lambang budaya menjadi lambang seni, bahasa, mitos, religi, musik, sejarah, dan pengetahuan.. Pada umumnya pula paraahli ilmu sosial atau humaniora membagi lambang menjadi lambang ekspresif, lambang konstitutif, lambang penilaian moral, dan lambang kognitif (Bachtiar, 1985: 66). Perbedaan-perbedan klaifikasi ini disebabkan oleh perbedaan perspektif dan paradigma menangkap fenomena budaya. Oleh karena itu, perbedaan-perbedan yang muncul lebih bersifat epistimologis dan metodologis bukan substansif.
- Berkaitan dengan perpaduan antara otak dan hati ini, banyak sastrwan misalny STA, Chairill Anwar, dan Subagio Sastro Wardoyo pernah menyatakan bahwa sastra (baik prosa atau puisi) merupakan filsafat dengan penjelasan seni (Rosidi, 1987). Demikian juga para ahli sastra seperti Budi Darma dan Suripan Sadi Hutomo menyatakan bahwa sastra mula-mula adalah otak sehingga pada mulanya sastramerupakan dunia pemikiran.
- Rida K Liamsi dilahirkan di Dabosingkap Kep. Riau. Pendiri Yayasan Sagang Melayu yang bergiat dalam pengkajian budaya Melayu, dan sejak th 1996 Yayasan ini memberikan penghargaan seniman-budayawan yang karya-karyanya dianggap mengangkat budaya Melayu.
- Lahir di Payakumbuh, Sumatera Barat. Mendapat penghargaan Sea Writte Asean.
- Ijnformasi tentang Melayu Tua dan Melayu Muda ini diperoleh dari sastrawan Gus Tf. Sakai. Dari buku klasik Sejarah Melayu karya Tun Srilanang juga dapat ditemukan bermulanya keturunan Melayu dari bukit Siguntang.
- kisah ini secara panjang lebar diulas oleh Taufik Ikram Jamil dalam tulisannya “Penggalan Kepala untuk Sultan Melayu, Membolak-balik “Tuhfat al-Nafis. Lembar Bentara Kompas, Jumat 1 Agustus 2003.
- St. Sunardi. 2003. Opera Tanpa Kata. Yogyakarta: Buku Baik.
- Bambang Sugiharto. Kebudayaan, Filsafat dan Seni. Bentara, Kompas, Periksa Mochtar Naim, Demokrasi dalam Dialektika Kebudayaan Nusantra, dalam buku Pembebasan Budaya-budaya Kita. 1999. Jakaerta: Gramedia.
- Sabda atau perintah Raja adalah perintah Tuhan
- Konsep kebesaran kekuasaan kedewatan. Konsep ini merupakan konsep kekuasaaan Jawa yang berujung menuntut kepasrahan abdi (Jw: nderek kersa dalem).
- Gelar ini pertama kali dipakai oleh Ken Arok pendiri kerajaan Singasari, yang bermakna Raja sang Penguasa Negara Pemelihara Bumi. Selanjutnya gelar ini dipakai oleh Hayam Wuruk raja terbesar Majapahit.
- Pusat alam semesta.
- Yang memangku dunia.
- Raja pemuka agama dan pemimpin kawula.
- Dalam kitab Pararaton diceritakan Ken Arok menjadi raja setelah mengalahkan Tunggul Ametung, kemudian menaklukan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran di Ganter. Pertumpahan darah terus terjadi sampai tiga generasi keturunannya.
- Sartono Kartodihardjo, dkk. 1974. sejarah Nasional Indonesia II..Depdikbud.
————–
DAFTAR RUJUKAN
Alfian. 1984. Transformasi Sosial Budaya Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Awuy, Tommy F. 1996. 27 Juli. Masyarakat Rasional dan Retorika Ilmiah. Dalam Kompas, hlm. 5.
Berger, Peter L. dan Thomas Luckman (Terjemahan oleh Hasan Basari). 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES.
Cassirer, Ernst (Terjemahan Alois A. Nugroho). 1987. Manusia dan Kebudayaan: Sebuah Esei tentang Manusia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
Damono, Sapardi Djoko. 1999.Politik Ideologi dan Sastra Hibrida.. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Foucault, Michel. 1972. The Archeology of Knowledge and the Discourse on Language. New York: Pantheon.
Habermas, Jurgen (Terjemahan Hassan Basari). 1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Kartodirdjo, Sartono. 1988. Modern Indonesia: Tradition and Transformation. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Kayam, Umar. 1988. Memahami Roman Indonesia Modern sebagai Pencerminan dan Ekspresi Masyarakat dan Budaya Indonesia: Suatu Refleksi. Dalam Esten, Mursal (Penyunting). 1988. Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan (hlm. 118 — 131). Ban-dung: Penerbit Angkasa.
Kayam, Umar. 1989. Transformasi Budaya Kita. Horison, XXIV (08, 09, 10): 256 — 269;292 — 298;328 — 335.
Kleden, Ignas. 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.
Mahayana, Maman S. 2001. Akar Melayu. Magelang: Indonesia Tera.
Mahayana, Maman. S. 2005. 9 Jawaban Sastra Indonesia. Jakarta: Bening Publishing.
Newton, K.M. (Terjemahan Dr. Soelistia, ML.). 1994. Menafsirkan Teks: Pengantar Kritis kepada Teori dan Praktek Penafsiran Sastra. Semarang: IKIP Semarang Press.
Ricour, Paul (Penyunting Mario J. Valdes). 1991. Reflection and Imagination: A Ricour Reader. New York: Harvester Wheatsheaf.
Rosidi, Ajip. 1995. Sastra dan Budaya Kedaerahan dalam KeIndonesiaan. Jakarta: Pustaka Jaya.
Said, Edward W. 1994. Orientalisme. Bandung: Penerbit Pustaka.
Said, Edward W. (Terjemahan Rahmani Astuti). 1995. Kebudayaan dan Kekuasaaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat. Bandung: Penerbit Mizan.
Soedjatmoko. 1994. Menjelajah Cakrawala. Jakarta: PT Gramedia bekerja sama dengan Yayasan Soedjatmoko.
Sugiharto, I. Bambang. 1996. Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Sumaryono, E. 1993. Hermeneutik. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Widijanto, Tjahjono. 2011.dari Zaman Kapujanggan Hingga Kapitalisme: Segugusan Esai dan Telaah Sastra. Surabaya: Buku Kita.