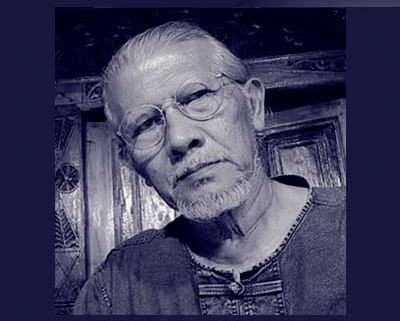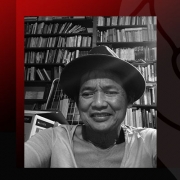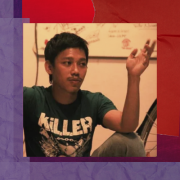Tutup Ngisor, Sitras Anjilin dan Komunitas Seni Tradisi
Oleh Riwanto Tirtosudarmo
Nama Tutup Ngisor pertama kali saya dengar dari Bung Hairus Salim. Mendengar nama itu, ”Tiuup Ngisor”, entah kenapa ada yang terasa magistical di telinga saya. Saat itu, tahun 2000 saya menjadi koordinator tim penelitian cukup besar Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI tentang kebijakan kebudayaan masa Orde Baru. Jennifer Lindsey yang menjadi program officer Ford Foundation melalui Bung Bisri Effendy (almarhum) memberi dana cukup besar untuk melakukan penelitian itu. Karena kompleks dan luasnya isu yang hendak diteliti, kami membaginya.menjadi enam tim yang menangani enam isu: agama, pendidikan, sastra, seni pertunjukan, bahasa dan etnisitas. Hairus Salim menjadi anggota tim peneliti seni pertunjukan yang dipimpin Bisri Effendy. Rupanya di Tutup Ngisor, Harus Salim yang tinggal di Jogya itu menemukan sebuah komunitas yang memiliki wayang orang yang secara rutin dipentaskan.
Tutup Ngisor secara administratif hanyalah salah satu Dukuh dari Desa Sumber, Kabupaten Magelang. Dalam sebuah kesempatan saya memutuskan untuk mencari Tutup Ngisor. Seingat saya, tahun 2003 itulah pertemuan pertama dengan Mas Sitras Anjilin yang telah memimpin Padepokan Tjito Budojo sebuah komunitas seni tradisi di Tutup Ngisor. Ketika itu saya sedang menjadi anggota tim penelitian tentang perkembangan ilmu-ilmu sosial di Jawa Tengah. Saat itu saya berkeliling menemui dan mewawancarai para narasumber yang saya anggap dapat menceritakan pengalamannya dalam berkiprah sebagai ilmuwan sosial. Di Semarang misalnya saya sempat mewawancarai Profesor Satjipto Rahardjo (almarhum) guru besar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) yang mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebaga Mazhab Peleburan. Peleburan adalah lokasi Kampus UNDIP saat itu, tidak jauh dari Simpang Lima, sebelum dipindahkan ke Tembalang sekarang.
Di Yogyakarta, cukup banyak yang saya wawancarai, antara lain Profesor Mohtar Mas’ud, saat itu Dekan Fisipol Universitas Gajah Mada; dan Dr. St. Sunardi, staf pengajar program Pasca Sarjana Universitas Sanata Dharma. Selain para akademisi saya juga menemui orang-orang yang menurut pengamatan saya aktif dalam menggerakkan masyarakat, dan secara idak langsung berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora secara luas. Mereka bisa digolongkan sebagai kaum intelektual organik Diantara mereka yang saya sebut sebagai kaum intelektual itu adalah Mas Sitras Anjilin dari sebuah desa yang dekat dengan puncak Merapi. Saya ingat, saya mengunjungi dengan naik mobil menjelang sore dari arah Muntilan naik ke atas. Selain mengunjungi Mas Sitras di Tutup Ngisor malam itu saya juga menemui Romo Kirjito seorang pastor Jesuit yang memimpin gereja katolik kecil di Desa Sumber, sedikit dibawah Tutup Ngisor. Saat itu Romo Kirjito bersama warga desa sedang melawan penambangan pasir yang merusak lingkungan di lereng Merapi.
Tutup Ngisor adalah sebuah dukuh yang matapencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Karena letaknya yang cukup tinggi, selain padi tanahnya yang subur itu menghasilkan berbagai jenis “poliwijo” seperti kentang, wortel, kobis kacang panjang dan cabe. Bekas lava yang setiap saat digelontorkan dari puncak Merapi menjadi berkah karena menyuburkan tanah di desa-desa di sekeliling puncak Merapi. Menurut sebuah penelitian dari Pusat Penelitian dan Sudi Kependudukan UGM yang saat itu dipimpin oleh Pak Masri Singarimbun, penduduk seputar puncak dan lereng-lereng Merapi enggan mengikuti program transmigrasi yang ditawarkan pemerintah meskipun mereka menempati wilayah yang dianggap rawan bencana karena tingginya ancaman erupsi gunung Merapi. Selain memang membuat tanah-tanah menjadi subur, oleh orang Jawa disekitarnya, termasuk para pewaris kraton Jogya, gunung Merapi dianggap sebagai gunung yang keramat. Oleh kraton Jogya di puncak gunung Merapi selalu ditempatkan seorang penunggu (kuncen) salah seorang yang kita kenal adalah Mbah Marijan.
Dalam seting dan lanskap geo-sosio-spiritual seperti itulah komunitas Tutup Ngisor yang berpusat pada Padepokan Tjipto-Budojo itu tumbuh dan berkembang. Didirikan oleh Romo Yoso Sudarmo, ayahanda Sitras Anjilin, pada tahun 1937 Tjipto-Budojo mampu bertahan hingga hari ini. Romo Yoso telah membangun reputasinya sendiri sebagai empu seni tradisi sekaligus guru spiritual. Sebuah panggung wayang orang lengkap dengan seperangkat gamelan menandai sebuah kompleks yang tidak terlalu besar dari komunitas seni tradisi Tutup Ngisor. Ketika saya pertama kali mengunjungi Tutup Ngisor sekitar tahun 2003 keadaan fasilitas keseniannya terlihat kurang terawat. Pada kedatangan saya yang kedua kalinya di tahun 2010 keadaannya jauh lebih baik, bahkan seperti terlihat baru.

Foto 1: Panggung untuk pementasan seni Tjipto Budojo (Koleksi pribadi penulis)
Menurut penuturan Mas Sitras Anjilin, sekitar tahun 2005 gubernur Jawa Tengah saat itu, Mardiyanto, menyumbangkan dana pemerintah untuk merenovasi fasilitas kesenian Tutup Ngisor. Sitras Anjilin, putra terkecil dari almarhum Romo Yoso Sudarmo memiliki andil terbesar dalam upaya merenovasi fasilitas kesenian di Tutup Ngisor dan mengembangkannya sebagai pusat kesenian tradisi yang berbasis komunitas.

Foto 2: Pak Sucoro (kaos putih) dan Mas Sitras Anjilin (kaos hitam) (Koleksi pribadi penulis)
Komunitas kesenian Tutup Ngisor, meskipun terlihat seperti sebuah pulau tersendiri ditengah hamparan ladang-ladang dan kampung-kampung masyarakat Jawa, terbukti tidak bias dipisahkan dari lingkungan geografi-kultural yang lebih luas. Romo Yoso sendiri, menurut penuturan Mas Sitras Anjilin dalam kunjungan terakhir saya pertengahan Desember 2022 yang lalu, semasa mudanya berguru pada Ndoro Purbokusumo, paman Hamengku Buwono IX di kraton Yogyakarta. Romo Yoso lahir tahun 1887 dan wafat tahun 1990 dalam usia 103 tahun. Menurut Mas Sitras sejak usia 70 tahun Romo Yoso selalu mengenakan baju jubah yang berwarna putih, sampai wafatnya.
Sutanto Mendut, penggerak Komunitas Seni Lima Gunung dan pemilik Studio Mendut, menurut penuturan Mas Sitras ketika muda sering menyambangi Romo Yoso di Tutup Ngisor. Mas Tanto Mendut sendiri kepada penulis menceritakan bahwa selain Romo Yoso sendiri, pada tahun 1990-an di sekitar Borobudor Magelang ada lima “jenius-alami-akomodatif-magelangan”, istilah yang dipakai Mas Tanto untuk menggambarkan mereka, yaitu Kyai Mangli, Kyai Hammam, Mbah Dalhar dan Kyai Sirat. Seperti merindukan masa lalu yang penuh kedamaian karena hadirnya tokoh-tokoh kebudayaan itu, Sutanto melalui berbagai kegiatan seni komunitasnya, antara lain Festival Lima Gunung yang telah berusia 20 tahun dan pementasan-pementasan yang di fasilitasinya di Studio Mendut miliknya, seperti ingin menggedor kesadaran penontonnya akan pentingnya membangun kembali kebudayaan yang bersifat holistik tanpa sekat apapun.

Foto 3: Sutanto Mendut (kanan berjaket) di Studio Mendut (Koleksi pribadi penulis)
Adalah sangat menarik mengamati muncul dan menggeliatnya berbagai ekspresi seni komunitas di sekitar kompleks percandian Bororobudur-Pawon-Mendut yang merupakan warisan peradaban besar Budha-Jawa dari Wangsa Syailendra dari abad 8-9 Masehi. Pada tahun 2014-2015 saya memimpin sebuah tim penelitian Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI untuk mengetahui bagaimana masyarakat sekitar Candi Borobudur memandang dan memanfaatkan kehadiran Candi Budha itu. Masyarakat sekitar Candi Borobudur yang sebagian besar telah beragama Islam itu umumnya melihat keberadaan Candi Borobudur itu sebagai sebuah berkah bagi kehidupan ekonomi mereka. Borobudur memang kemudian lebih dilihat sebagai pusat pariwisata meskipun disana-sini unsur kaegamaan atau spiritualitas masih sedikit ikut mewarnainya. Jika ada sebuah kegiatan dari komunitas sekitar Candi Borobudur yang masih berusaha menunjukkan arti penting Borobudur sebagai pusat spiritualitas, salah satunya adalah Ruwat Rawat Borobudur (RRB) yang selama 20 tahun dipimpin oleh Pak Sucoro (Lihat Foto 1).

Foto 4: Penulis dan beberapa kawan saat berkunjung ke Padepokan Tjipto Budojo pertengahan Desember 2022 (Koleksi pribadi penulis).
Meskipun tidak terletak di lingkaran dalam Borobudur Padepokan Tjipto Budojo yang saat ini dipimpin oleh Sitras Anjilin itu seperti berusaha untuk meneruskan seni tradisi Jawa dengan kesadaran yang kuat bahwa unsur filosofis dan spiritualitas Jawa merupakan bagian yang menjadi intinya. Sitras Anjilin juga sangat menyadari bahwa salah satu tantangan utama dari komunitas seni tradisi adalah ekonomi pasar yang dibawa oleh pariwisata. Oleh karena itu dengan tegas Mas Sitras menolak Tutup Ngisor dijadikan sebagai desa wisata seperti telah melanda hampir seluruh desa-desa di sekitar Candi Borobudur. Bagi Sitras berkesenian adalah seperti halnya bertani, keduanya tidak bias dipisahkan. Ekonomi desa harus didukung oleh pertanian dan berkesenian adalah bagian dari kehidupan sehari-hari warga desa.
Kampung Limasan Tonjong, 9 Januari 2023.
*Riwanto Tirtosudarmo adalah peneliti