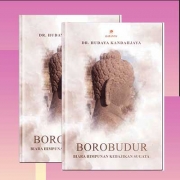Dramaturgi dalam Film: Bollywood Vs. Hollywood
Oleh Panji Wibowo
Intro
Sinema India dalam wacana perfilman dunia seringkali dipandang sebelah mata. Sebuah wahana yang tersisih dari tilikan estetik dibanding dengan Hollywood atau sinema Eropa. Bahkan seringkali sinema India digeneralisasi dengan sebutan “Bollywood”, sebuah sebutan yang pada awalnya merupakan sebuah lelucon yang ditujukan bagi film-film berbahasa Hindi yang diproduksi sebuah studio di Mumbai (Bombay). Sebutan Bollywood kemudian tertanam kedalam lingua franca sinema dunia dan secara salah dianggap sekedar sebuah genre yang melingkupi seluruh film produksi sinema India. Anggapan semacam ini sama halnya dengan mengatakan film-film produksi Warner Brothers sebagai representasi keseluruhan sinema Amerika. Faktanya, sinema India juga kaya akan beragam genre, dan Bollywood semata-mata hanya sebuah area produksi film di India, yang merujuk pada genre spesifik dengan karakter produksi yang mewah, mengelaborasi tontonan, lagu dan tari (seringkali kolosal) serta cerita yang berpusat pada kehidupan dan ritual-ritual keluarga. Penyematan karakteristik generik semacam ini seringkali mengabaikan elemen-elemen budaya India yang intrinsik dan menggantikannya dengan elemen-elemen dari masyarakat berbahasa Inggris. Meskipun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Madhava Prasad dalam buku Ideology of the Hindi Film: A Historical Construction, bahwa peran Hollywood (bahkan Hollywood yang memberi nama Bollywood) pada sejarah mula sinema India sangat dominan, namun sinema India memiliki pendekatan estetik yang berakar pada tradisinya sendiri.
Dalam tulisan ini saya akan mencoba mengungkapkan satu sisi penting yang secara intrinsik melandasi cerita dan struktur dramatik sinema India (teori rasa) dimana pergerakan dramatik terletak pada empati karakter, membedakan dengan struktur dramatik sinema Hollywood (Aristotelian) yang mendasarkan pergerakan dramatik pada plot. Sementara untuk urusan karakter (akting, performance) Hollywood sangat mengandalkan teknik yang diusung oleh Konstantin Stanislavky (1863-1938) yang mengembangkan metode akting realisme sehingga dapat diterima secara luas baik untuk panggung maupun film.
Struktur dramatik Aristotelian dalam Sinema Hollywood
Naratif dan struktur dramatik dalam sinema Hollywood merupakan salah satu faktor penentu yang mengikat orang untuk terus datang ke bioskop dan menonton film. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kristin Thompson dalam buku Story Telling in New Hollywood, prinsip dasar sinema Hollywood adalah bahwa naratif wajib memuat hubungan sebab-akibat yang mudah untuk diikuti oleh penonton (Thompson, hal.10). Lantas apa hubungan pernyataan Kristin Thompson ini dengan Aristiotle? Sekitar 2300an tahun yang lalu, Aristotle menulis buku berjudul Poetics, sebuah buku tentang teknik bercerita (drama) dan hubungannya dengan pengalaman emosional. Pengalaman emosional ini disebut oikeia hedone (‘proper pleasure’). Pada era film bersuara, dimana ketrampilan menulis skenario mulai diajarkan, pengaruh Aristotle menjadi semakin kuat. Pengaruh ini dapat kita lihat secara lebih jelas melalui tiga persoalan yang selalu ada dalam cerita; pertama, struktur tiga babak (begining, middle, ending), kedua, plot lebih utama daripada karakter dan ketiga, keharusan akan adanya ‘katarsis’ pada bagian akhir. Hingga kini tiga perkara tersebut menjadi pola baku yang selalu ada di hampir semua genre film Hollywood.
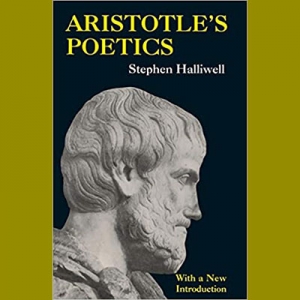
Buku Aristotle’s Poetics (Sumber foto Amazon)
Prinsip drama tiga babak ala Aristotle secara jelas memang memberi tekanan lebih pada plot daripada karakter. Lajos Egri, mengutip Aristotle dalam The Art of Dramatic Writing, pertimbangan pertama adalah plot, karena plot adalah jiwa dari tragedi. Karakter menjadi pertimbangan kedua (Egri, hal. 92). Pengaruh ini dapat dengan mudah kita lihat dalam sinema Hollywood, permainan plot dalam berbagai bentuk lebih banyak dipergunakan, dan hanya sedikit film yang menitik beratkan pada perkembangan karakter. Ari Hiltunen dalam introduksi buku Aristotle in Hollywood : The Anatomy of Successful Story-Telling, mengatakan bahwa cara bercerita film Hollywood sesungguhnya mendaur ulang kesuksesan strategi dari kisah-kisah kuno. Orang ingin mengalami beragam emosi dan Hollywood dapat memberikan pengalaman tersebut. Hiltunen menambahkan, bahwa pengalaman ini disebut ‘proper pleasure’ dari hiburan modern (Hiltunen, XV). Secara Aristotelian, Proper pleasure atau oikeia hedone, merupakan kesenangan yang dialami pada momen yang tepat (dari sisi penonton atau pembaca) sebagai hasil dari tripartit phobo (fear, kecemasan, ketakutan), eleos (pity, iba, simpati) dan catharsis (Katarsis, pelepasan ketegangan).
Pengaruh Aristotle tidak hanya diungkapkan dalam ulasan-ulasan yang berupa kajian. Dalam buku-buku screencraft penulisan skenario yang banyak dipakai sebagai diktat utama pengajaran pembuatan film, seperti Screenplay: The Foundations of Screenwriting karangan Syd Field, pengaruh Aristotle jelas terlihat. Dalam buku tersebut Syd Field bahkan menggunakan aturan tiga babak secara lebih terperinci. Babak I (beginning) harus diakhiri pada halaman 30, babak II (middle) harus berakhir pada halaman 90, dan babak III (ending) harus berakhir pada halaman 120 dan harus disertai dengan sebuah resolusi yang menghasilkan katarsis (Field, hal. 8). Menggunakan film China Town (Roman Polanski, 1974) Syd Field menjabarkan bahwa Babak I berakhir ketika detektif Jake Gites (Jack Nicholson) harus sudah mengetahui apakah Mrs. Mulwray (Faye Dunaway) adalah Mrs. Mulwray tulen, orang yang menyewa jasanya untuk menyelidiki perselingkuhan dan pembunuhan suaminya. Babak II merupakan babak konflik dimana Jake Gites harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang menghalangi dan tidak menghendaki orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Mulwray terungkap. Terakhir, Babak III, Field menjelaskan bahwa dalam film ini dan setiap film, harus sanggup menggiring penonton untuk menuju sebuah akhir yang kuat (strong ending) dengan tujuan untuk menjadikannya “dapat dipahami secara menyeluruh” (comprehensible) dan “tuntas” (complete). Field menyimpulkan, bahwa ending yang ambigu sudah berakhir masanya (Field, hal. 10). Hal ini sejalan dengan prinsip katarsis, pelepasan ketegangan, pembersihan emosi-emosi yang membuncah yang terakumulasi dari keberhasilan drama, dan penontonpun memperoleh proper pleasure.
Secara sederhana, kita dapat melihat pengaruh atau penerapan struktur dramatik Aristotelian dihampir semua film Hollywood dari periode klasik hingga kontemporer. Sebutlah dari The Wizard of Oz, Gone With the Wind, Psycho, Lawrence of Arabia hingga Star Wars, E.T, Batman, Lord of the Rings dan lain-lain. Meskipun tetap ada film yang tidak mengikuti struktur dramatik semacam itu seperti, Inception (Chritopher Nolan, 2010), Birdman (Gonzales Innaritu, 2014) film-film semacam itu merupakan pengecualian.
Teori Rasa dalam Sinema India
Bharata Muni (200 SM), atau yang biasa disebut Sage Bharat, seorang teoritikus dan filosof India yang pertama kali memformulasikan konsep seni pertunjukan (performing arts) dan teori rasa. Ia juga ditasbihkan sebagai bapak seni pertunjukkan India. Dalam buku Natyasastra, Sage Bharat berargumen bahwa sensasi yang paling tinggi bergantunng pada emosi yang dirasakan oleh penonton dengan bimbingan aktor. Meskipun aktor dan karakter yang mempertunjukkan emosi dengan cara dikdaktik, namun penontonlah yang mengolah, penontonlah yang menyaksikan dan mengalami emosi yang diusung dan dipertunjukkan diatas panggung. Richard Schechner dalam sebuah esai berjudul Rasaesthetics mengatakan bahwa, rasa merupakan akumulasi dari vibhava (stimulus), anubhava (aksi yang diarahkan-involuntary) dan vyabhichari bhava (reaksi langsung-voluntary). Sebagai contoh, ketika bermacam bumbu, saus, rempah dan bahan-bahan makanan lainnya dicampur maka akan memunculkan pengalaman atas cita rasa (Schechner, hal. 29).
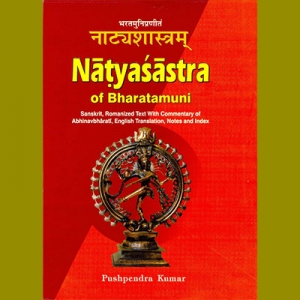
Buku Nātyaśāstra of Bharatamuni (Sumber foto Amazon.com)
Sederhananya, rasa adalah emosi yang berlangsung dalam diri penonton, kenikmatan sebuah pertunjukkan. Ketika seorang aktor memainkan sebuah peran dalam sebuah pertunjukkan untuk kemudian sang aktor merasakan emosi yang khusus atau rasa tertentu, maka penonton akan merasakan rasa yang kurang lebih sama. Dalam sebuah esai berjudul Rasa Theory and Dharma Theory: From The Home and the World to Bandit Queen, Patrick Colm Hogan menjelaskan, jika karakter sedang merasakan cinta, maka penonton juga merasakan sesuatu semacam cinta. Penonton tidak merasa marah, atau jijik. Dengan demikian, Implikasi dari klaim ini adalah bahwa rasa merupakan versi empatik dari emosi (bhava) (Hogan, hal. 39). Saya tidak takut pada Rahwana, tapi saya cemas melihat apa yang dapat ia lakukan pada Sita. Dibawah pengaruh teori rasa, penonton menikmati pertunjukkan melalui penampilan aktor. Menurut Natyasatra, sebagaimana dikutip oleh Matthew Jones dalam sebuah esai berjudul Bollywood, Rasa and Indian Cinema: Miscoception, Meanings and Millionaire, terdapat delapan rasa yang fundamental:
Shringara – cinta
Hasya – humor
Karuna – iba, derita
Raudra – marah
Vira energi – energi, semangat
Bhayanaka – takut, cemas, malu
Bibhasta – jijik
Abdhuta – kejutan
Masing-masing rasa merepresentasikan sebuah emosi khusus yang diusung oleh aktor pertunjukkan dan kemudian dirasakan oleh penonton (Jones, 37). Dapat saja kita memperbandingkan masing-masing rasa dengan genre. Namun keduanya akan saling mereduksi, karena konsep dasarnya berbeda dan cara kerjanya juga berbeda. Kita mungkin hanya dapat memperlihatkan korespondensi antar keduanya, misalnya genre horor dapat berkorespondensi dengan bhayanaka, mengingat tujuan film horor adalah untuk membangkitkan emosi ketegangan atau kecemasan. Genre romance dapat berkorespondensi dengan shringara dan lain sebagainya.
Sebagai tambahan, pada abad ke-10, Abhinavagupta, seorang filosof India menambahkan rasa kesembilan yaitu shanta atau kebahagiaan (bliss). Rasa kesembilan ini bukanlah sesuatu yang baru, shanta muncul ketika delapan rasa bergabung bersama, memberikan kepenuhan puncak dalam diri penonton. Menurut Richard Schechner, sebuah pertunjukan yang sempurna, semestinya sanggup memunculkan shanta, namun bukan dengan mengekspresikannya, melainkan dengan cara memberi jalan bagi shanta untuk dialami secara simultan dan absolut oleh aktor dan orang-orang yang turut mengambil bagian di dalamnya. (Schechner, hal. 32). Tuntutan akan kesempurnaan ini mengakibatkan sangat jarang sebuah pertunjukkan dapat mencapai shanta. Sinkronisitas setiap aspek pertunjukkan harus secara ketat bekerja dan aktor harus mampu membawakan setiap rasa secara sempurna. Aktor rasic (yang menerapkan teori rasa) harus mampu memperagakan emosi lebih dari karakter aktual yang ia perankan, dengan demikian penonton akan ikut merasakan emosi tersebut. Dari sudut ini, maka shanta dapat diperbandingkan dengan ‘proper pleasure’, hanya tekanannya lebih pada aktor bukan pada plot, dengan suntikan faktor spiritual yang sangat terasa.
Dalam buku Natyasastra, akting bukan hanya persoalan aksi (action), namun melibatkan aktivitas yang tak terhitung. Sebagaimana dijabarkan oleh Shechner, dalam Natyasastra terdapat empat jenis akting, pertama Angika Abhinaya, gerak tubuh, gestur, tatapan, cara berjalan dan gerak tubuh yang melibatkan anggota tubuh utama; kepala, dada, tangan dan kaki serta ekspresi wajah; mata, hidung, bibir, dagu, leher. Kedua vachik abhinaya, cara pengucapan atau ekspresi melalui kata-kata; tempo, aksen, intonasi, interval, pitch hingga cara melafalkan konsonan dan vokal. Tujuannya adalah untuk mengarahkan penonton dalam mengalami rasa melalui kekuatan bahasa. Ketiga aharya abinaya, ini menyangkut dandanan aktor; rias, tata rambut, busana, hand props, perhiasan, pelengkap peran hingga dekorasi ruangan. Dan yang keempat sattyika abhinaya, representasi mood internal dan temperamen sang karakter melalui akting. Kualitas tertinggi akting dapat tercapai jika inner feelings dari seorang karakter yang diekspresikan dengan subtil; gerak bibir, tubuh yang bergetar, wajah yang memerah, tetes air mata, tarikan nafas termasuk respon terhadap cuaca, terang-gelap, sinar matahari (Schechner, hal 18-19). Sinema India mempergunakan teknik ini untuk menyampaikan emosi kepada penonton secara melodramatik.

Richard Schechner (Sumber foto NYU,Tisch)
Karena penekanan teori rasa lebih pada aktor dan karakter, maka akting (abhinaya) menjadi hal yang utama. Berbeda dengan rata-rata film Hollywood yang menerapkan metode akting Stanislavkian dimana penjiwaan karakter lebih utama. Penjiwaan karakter yang bertujuan supaya aktor tampil meyakinkan. Pervis Sawoski dalam The Stanislavki System: Growth and Methodology, menjelaskan bahwa, aktor yang memiliki kemampuan untuk membuat penonton percaya apa yang ia ingin penonton percayai akan mencapai scenic truth (kebenaran filmis) (Sawoski, hal. 7). Stanislavski menjabarkan scenic truth sebagai kebenaran yang berasal dari wahana imajinatif dan fiksi artistik. Ia membedakannya dengan kebenaran yang tercipta secara otomatis dari wahana fakta aktual (Sawoski, hal. 8). Dari sudut ini perbedaanya menjadi tegas, teori rasa bertujuan membuat orang merasa, metoda Stanislavski bertujuan membuat orang percaya. Bagi Stanislavski, seorang aktor harus mampu menghuni secara total spirit dari karakter yang diperankannya. Dengan cara ini intepretasi aktor atas karakter bisa saja mengubah pengejawantahan emosi dari konsep asalnya. Bagi Stanislavski, menubuh dalam karakter, memberinya hidup dan nafas lebih penting daripada sekedar mengusung emosi, karena emosi dengan sendirinya akan lahir dari seorang karakter yang telah diberi nyawa oleh seorang aktor. Seperti Al Pacino menghidupkan karakter Michael Corleone, seorang gembong mafia dalam The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972), ia menubuh dalam karakter itu, dan ia tampil sangat meyakinkan. Sementara bagi seorang aktor rasic seperti Amitabachan dalam film Coolie (Manmohan Desai, 1983), yang pada waktu itu berusia hampir 40 tahun, memerankan seorang kuli angkut yang berusia 20 tahun tidak menjadi masalah. Bagi seorang aktor rasic, menubuh ke dalam spirit karakter bukan persoalan penting, karena tujuan utamanya adalah mengusung emosi dengan tepat dan sempurna.
Dalam kaitan dengan penulisan skenario, sinema India juga sangat patuh pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku Natyasastra, sebagaimana dikutip oleh Richard Schechner, bahwa tujuan dari seni pertunjukan adalah Tontonan (Spectacle) (Shechner, hal. 36). Sebagai sebuah tontonan, sinema India mencoba untuk menciptakan percampuran organik antara teori rasa dan segala bentuk skenario. Sutradara besar India, Satyajit Ray percaya bahwa untuk menciptakan sebuah tontonan, penulisan skenario film secara ketat harus sejalan dengan teori rasa. Sebagaimana yang dinyatakan Darius Cooper dalam buku The Cinema of Satyajit Ray: Between Tradition and Modernity, dalam sejarah setiap orang terdapat emosi (bhava) atas segala macam hal. Emosi tersebut terumuskan kedalam delapan rasa : cinta, humor, iba, marah, semangat, cemas, jijik, kejutan. Masing masing rasa, dalam konteks puitik, berubah menjadi suasana hati yang sepadan dan bersamanya terbawa ekspresi fisik, ikatan perasaan, dominasi dan konsekuensinya dalam perilaku emosional. Perangkat-perangkat inilah yang menjadi dasar dari pertunjukan yang dramatik (Cooper, hal. 3). Meskipun tidak ada hirarki dalam kedudukan masing-masing elemen rasa, tak dapat dipungkiri bahwa sinema Populer India didominasi oleh genre romance dan melodrama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hogan, mungkin rasa yang paling umum dan akrab dalam sinema India adalah cinta (shringara) dan iba (karuna), sebagai perwujudan emosi yang paling mudah diakses dan dialami oleh manusia (Hogan, hal.40). Satu hal yang harus diperhatikan adalah, bahwa tidak ada sebuah film yang hanya menerapkan satu elemen rasa. Dalam sebuah film romance misalnya, rasa yang paling utama adalah shringaya (cinta), elemen rasa yang lainnya tetap saja masih dibutuhkan sebagai pendukung yang memperkuat.
Film Rang De Basanti (Rakeysh Omprakash Mehra, 2006) dapat menjadi contoh dalam kaitan dengan teori rasa. Film ini berkisah tentang Sue McKinley, seorang pembuat film dokumenter asal Inggris yang hendak membuat film tentang pejuang kemerdekaan India yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, kemudian di hukum mati. Sesampai di India ia bertemu dengan sekelompok anak muda. Sue mengajak mereka untuk terlibat sebagai pemain dalam film yang akan ia buat. Sue jatuh cinta dengan salah satu pemain yang bernama DJ yang memiliki kakak bernama Ajay, seorang pilot Angkatan Udara India. Pada suatu hari, pesawat tempur Ajay mengalami kecelakaan dan ia meninggal. Beredar spekulasi bahwa penyebab kecelakaan adalah korupsi yang dilakukan Kementerian Pertahanan India dengan cara menjual kontrak pada sebuah perusahaan. Perusahaan itu kemudian membuat peralatan murah dan dibawah standar. Merasa marah kepada pemerintah, DJ, Sue dan kelompoknya turun ke jalan untuk melakukan protes kepada pemerintah India. Sepanjang aksi protes tersebut, DJ, Sue dan kawan-kawan mulai merasakan adanya kesamaan mereka dengan para pejuang yang hendak mereka filmkan. Pejuang yang mengangkat senjata untuk melawan ketidak adilan. Mereka akhirnya menjadi sama-sama revolusionernya.
Setengah bagian pertama film ini, secara jelas mengusung rasa vira (Semangat), hasya (humor), Shringara (Cinta) dan abdhuta (surprise). Memasuki setengah bagian berikutnya, mulailah perubahan rasa terjadi. Film mulai mengusung rasa karuna (iba, sedih), bibhasta (jijik, muak), bhayanaka (cemas, malu) dan raudra (marah). Dan yang tak kalah penting, perubahan karakter yang sebelumnya hanya memikirkan bagaimana caranya bersenag-senang, berangsur-angsur menjadi keras dan revolusioner. Penonton merasakan perubahan ini melalui emosi-emosi yang menghubungkan mereka dengan tema film. Pesan akhir dari film ini adalah melalui pemunculan angka korban akibat kegagalan mesin pesawat Angkatan Udara India. Hal ini menjadi semacam ajakan pada penonton untuk ikut protes atas korupsi yang dilakukan pemerintah. Disini menjadi jelas bahwa sinema India, mengikuti Natyasastra, menjalankan fungsi didaktiknya, melahirkan empati yang dapat merubah persepsi penonton atau menambah pengetahuan atas peristiwa-peristiwa tertentu. Hogan menyatakan, karya-karya didaktik di India cenderung menggunakan estetika rasa, bukan sekedar hiburan ringan belaka. Melalui kreasi-kreasi yang terus berlanjut sehingga dapat meningkatkan perasaan empatik , yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah komitmen etika sosial dari pembaca atau penonton (Hogan, hal. 41). Dampak apapun yang ingin dicapai oleh pembuat film, sangat tergantung pada penggunaan rasa yang tepat untuk merengkuh empati sehingga penonton melanjutkan progresi sosialnya. Kebutuhan sebuah film untuk dapat dinikmati sebagaimana Rang De Basanti merupakan hal yang universal dalam sinema. Sebuah tema yang sulit akan jauh lebih mudah untuk dicerna jika secara keseluruhan mengandung unsur-unsur yang menghibur.

Poster Film Rang De Basanti (Sumber Wikipedia)
Sinema India secara umum sangat ekspansif, memiliki lapisan-lapisan peristiwa, dengan durasi sekitar tiga sampai empat jam. Bagi penonton rasic, masing-masing rasa memiliki cukup ruang untuk dinikmati seperti dalam sebuah perjamuan dengan aneka hidangan, setiap hidangan memiliki rasa–nya masing-masing, tetamu mencicipi secukupnya tanpa tergesa-gesa untuk kenyang, hingga semua rasa menyatu dalam puncak kenikmatan emosional yang sempurna. Analogi antara makanan dan rasa sangatlah tepat. Rasa dalam bentuknya yang paling murni diusung oleh seorang aktor, kemudian dibagi kepada penonton untuk dicicipi dan dinilai. Penilaian tidaklah rumit, jika penonton dapat menikmati berarti pertunjukkannya bagus, rasa telah dipergunakan dengan kuat dan baik, sebaliknya jika penonton tidak atau kurang dapat menikmati maka dapat dikatakan pertunjukkannya buruk, yang berarti pendemonstrasian rasa nya tidak atau kurang berhasil.
Sinema India banyak yang berdurasi lebih dari tiga jam, cerita mengalir keluar-masuk dengan naratif yang kadang berganti-ganti. Bagi penonton yang tidak terbiasa, hal ini bisa membosankan. Terlebih penonton yang terbiasa dengan cara bertutur Hollywood dengan struktur beginning-middle-end, seperti yang sudah saya jelaskan dibagian awal tulisan ini. Formula sinema India memang tidak berdasarkan struktur cerita atau perkembangan plot, melainkan berdasar pada penyajian rasa yang diperlama, memberi penonton cukup waktu untuk merasakannya. Schechner menegaskan, pertunjukkan rasic bertujuan untuk memperlama kesenangan, bukan untuk memisahkan yang menang dari yang kalah. Pertunjukan rasic lebih menghargai kedekatan daripada keberjarakkan, paradigma aktivitasnya adalah berbagi antara aktor dan siapapun yang turut mengambil bagian di dalamnya (Shechner, 31).
Kesimpulan
Aristotle dan Bharata Muni barangkali memang tak pernah saling mengenal. Mereka sama-sama melahirkan teori drama dan seni pertunjukkan yang sumbernya dari kisah-kisah kuno. Faktor geografis lah yang menjadi pembeda, yang satu bersandar pada logika yang lain bersandar pada spiritualitas. Ketika masing-masing teori di terapkan dalam sinema tentu memunculkan perbedaan-perbedaaan. Yang satu memberi tekanan lebih pada plot yang lain memberi tekanan lebih pada karakter. Yang satu berpuncak pada proper pleasure yang lain berpuncak pada shanta. Namun menjadi jelas bahwa pengaruh seni pertunjukkan sangat melekat pada sinema India. Penerepan teori rasa yang tertuang dalam buku Natyasastra kedalam medium baru, sinema, tidak menghilangkan kekentalan karakteristik seni pertunjukkan. Jika kita mencabut teori rasa dari sinema India, maka kita seperti mencabut sesuatu yang paling mendasar yang menciptakan keunikannya. Mengabaikan sinema India dan teori estetika pertunjukkan yang menjadi landasannya, membuat kita keliru dengan melabeli sinema India sebagai Bollywood. Teori rasa adalah sebuah cara yang indah untuk mengalami sebuah film. Terlepas dari itu, sinema India telah menemukan konsep estetiknya sendiri, estetika sinema yang telah menyejarah dalam rupa produksi maupun cara menonton. Apa kabar dengan estetika sinema Indonesia?
*Penulis adalah peneliti dan sutradara film
——————–
Daftar Pustaka,
Bharata Muni (1995). The Natyasastra (Manmohan Ghosh, Trans.) (3rd ed). West Bengal, WB: Miscellany Incorporation.
Darius Cooper. (2000). The Cinema Of Satyajit Ray: Between Tradition and Modernity. Cambridge, UK: Cambridge university press.
Hogan Colm Patrick. (2003). Rasa Theory and Dharma Theory: From The Home and the World to Bandit Queen. Quarterly Review of Film and Video, 20(1), 40, 37-52
Matthew Jones. (2009). Bollywood, Rasa and Indian Cinema: Misconceptions, Meanings and Millionaire. Visual Anthropology, 23(1), 38, 33-43. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/08949460903368895
Richard Schechner. (2001). Rasaethetics. The Drama Review, 45(3), 29, 27-50. Diambil dari http://www.jstor.org/stable/1146911
Pervis Sakowski, http://homepage.smc.edu/sawoski_perviz/Stanislavski.pdf