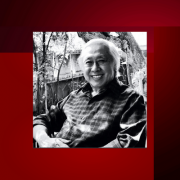Pawitra,Pradaksinapatha dan Parwatarajadewa
Pawitra, Pradaksinapatha dan Parwatarajadewa
(Sebuah refleksi tentang Gunung Penanggungan)
Oleh: Anapana
Air yang keluar dari kedua tetek (payudara) arca Dewi Lakshmi dan Dewi Sri di Patirtan Belahan, sebelah timur Gunung Penanggungan, Kabupaten Pasuruan masih tak henti-hentinya mancur. Air itu bersih. Jernih. Bening. Sudah lebih 1000 tahun mungkin sejak patirtan itu didirikan Airlangga pada 1009 M air menyegarkan itu terus menerus keluar. Bahkan tatkala desa-desa sekitar Gunung Penanggungan dilanda musim kemarau berkepanjangan dan kekeringan, air yang mancur dari buah dada Dewi Laksmi Dewi Sri itu menyelamatkan penduduk.
Seperti Juni siang itu. Kami melihat banyak penduduk desa silih berganti datang ke Sumber Tetek (penamaan masyarakat untuk menyebut Patirtan Belahan) membawa jerigen-jerigen. Mereka bergantian menadahkan jerigennya menampung air yang keluar dari kedua susu sang dewi. Satu warga bisa membawa dua jerigen. Selain untuk kehidupan mereka sendiri, air juga dibutuhkan warga untuk air minum ternak.
Ketika musim panas, Patirtan Belahan juga menjadi tempat “suaka” yang menyejukkan. Kolam Patirtan Belahan sendiri sesungguhnya tergolong kecil. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6,14 meter dan lebar 6,14 meter kolam itu menjadi tempat untuk sekedar mencelup-celupkan kaki atau meraup wajah, di kala udara terasa gerah. Seperti siang itu juga. Kami melihat banyak anak-anak laki desa sepulang sekolah yang menyempatkan diri untuk berendam mandi dan bermain-main di kolam Belahan. Mereka bersendau gurau membawa bekas-bekas ban sebagai pelampung. Bahkan –seorang remaja madrasah berjilbab mengambil air wudhu dari pancuran air kedua payudara sang dewi. Terasa menggetarkan menyaksikan bagaimana seorang muslim mengambil air wudhu dari pancuran arca-arca Hindu kuno yang berumur lebih dari 1000 tahun.

Seorang remaja tengah wudhu di Sumber Tetek
Studi tentang Gunung Penanggungan sampai sekarang masih terus dilanjutkan oleh para arkeolog. Gunung Penanggungan di masa Jawa Kuno dikenal bernama Pawitra. Bagi masyarakat Jawa kuno Gunung Penanggungan dianggap gunung suci. Negarakertagama menyebut Gunung Pawitra merupakan salah satu dari beberapa karsyan tempat tingal kaum pertapa atau kaum rsi. Karsyan lain yang disebut di Negarakertagama: Sumpud, Rupit, Butun, Pilan, Pucangan, Jagaditta sampai sekarang belum bisa didentifikasi oleh para arkeolog lokasinya di mana.
Menarik unttuk mengkaji anatomi Gunung Penanggungan. Gunung itu sekarang – hanya gunung kering yang tak menarik wisatawan, kecuali mungkin para arkeolog yang mengetahui memang banyak terdapat bekas-bekas situs kepurbakalaan dari era abad 10-14 Masehi di sepanjang tubuh gunung itu. Pada zaman lampau dari kaki, tubuh dan puncak Gunung Penanggungan memiliki makna kosmologis tertentu. Petirtaan adalah bagian paling bawah dari Gunung Penangungan. Ia berada di lokasi kaki Gunung Penanggungan. Petirtaan Belahan atau Sumber Tetek berada di kaki sebelah timur. Sementara Petirtan Jalatunda,yang umurnya lebih tua daripada Patirtan Belahan (dibangun 991 M oleh Udayana, ayah Airlangga) berada di kaki barat Gunung Penanggungan. Petirtan Jalatunda berbahan batu andesit. Panjangnya 16,85 meter, lebar 13,5 meter dan kedalaman sekitar 5 meter. Sebagaimana Patirtaan Belahan sampai kini airnya pun masih jernih. Bahkan disbanding Patirtan Belahan, di sana ikan-ikan masih banyak berkeliaran di dasar kolam.
Berbagai buku dan tulisan tentang Gunung Penanggungan akhir-akhir ini banyak bermunculan. Kelompok Bol Brutu, suatu kelompok penulis dari Yogya yang anggotanya terdiri dari arkeolog, antropolog, sastrawan sampai pelukis dan pemusik misalnya menerbitkan buku: Jelajah Candi-Candi Gunung Penanggungan (2017) . Arkeolog UGM Dr Daud Aris Tanudirja pernah di Borobudur Writers and Cultural Festival 2014 menyajikan makalah berjudul: Sejarah Ratu Adil pada Jawa Kuno: dari Kediri ke Penanggungan. Ia mengasumsikan Penanggungan zaman dulu adalah tempat gagasan-gagasan atau pandangan eskatologi mengenai Ratu Adil atau Mesianisme berkembang. Paling mutakhir adalah penelitian yang dilakukan Hadi Sidomulyo (Nigel Bullough )bersama Tim Ubaya.
Dalam ceramahnya di Borobudur Writers and Cultural Festival 2015 Hadi Sidomulyo alias Nigel Bulough mengajukan makalah berjudul: Eksplorasi Gunung Penanggungan: Pusat rohani masa akhir Majapahit. Dalam kesempatan itu, Hadi mengatakan setelah Gunung Penanggungan mengalami kebakaran pada Agustus sampai Oktober 2015 terjadi hal di luar dugaan. Terbakarnya rumput-rumput dan ilalang menyebabkan banyak tersingkapnya bekas-bekas bangunan candi yang tadinya tertutupi alang-alang. Yang menarik beberapa dari bekas candi itu sebelumnya belum terdata atau tidak diketahui. Bahkan menurut Hadi Sidolmuyo, kebakaran itu membuat munculnya kembali jejak rute jalanan kuno atau jalur pendakian kuno dari masa Majapahit. Rute jalanan kuno ini memang sudah diketahui sebelumnya tapi jalurnya tidak jelas karena tertimbun sana sini.
Hadi Sidolmuyo memaparkan dengan menggunakan kamera drone ia berusaha memotret jalur pendakian kuno itu dari atas. Hasilnya fantastis. Tampak dari atas dua lapis jalan yang berbentuk memutar atau melingkar dari mulai bagian bawah gunung sampai puncak gunung. Dua lapis jalan itu semuanya jalan makadam atau jalan yang terbuat tumpukan batu. Menurut Hadi Sidomulyo di samping dua jalan itu terdapat sebuah jalan lagi berbentuk zig zag yang menghubungkan dua lapis jalan melingkar di atas. Dalam kesempatan BWCF di atas, Hadi mempresentasikan dengan proyektor hasil foto-foto dan rekaman kamera drone yang ia buat.

Panorama Gunung Penanggungan dari sisi timur
Hadi bercerita, dia bersama tim Ubaya mencoba berjalan di jalur pendakian kuno tersebut. Jalur pendakian kuno itu berbeda dengan jalur pendakian yang selama ini digunakan oleh para pendaki. Jalur yang digunakan pendaki cenderung lurus menanjak dan mencapekkan serta berbahaya. Itu dikarenakan jalur yang selama ini digunakan pendaki memotong jalur pendakian kuno. Sementara itu menurut Hadi, jalur kuno yang zig zag itu meskipun lebih lama, sangat aman dan bisa digunakan siapapun yang ingin mencapai puncak gunung. Lebar jalan kuno itu sendiri dari 1,5 sampai 2 meter. “Saya membayangkan melalui jalan melingkar kuno ini andai ada orang cebol atau kereta berkuda pun naik ke Penanggungan di zaman Majapahit tak akan kesulitan dari bawah mendaki sampai ke atas. Karena jalannya cukup lebar dan mudah. Ini menakjubkan ,” kata Hadi saat itu.
***
Buku Arkeologi Pawitra karya Dr. Dr Agus Aris Munandar yang berangkat dari thesisnya di UI tahun 1990 adalah salah satu buku yang lengkap mengenai kepurbakalaan Gunung Penanggungan. Dalam buku tersebut ia mengemukakan hipotesis orisinil yang menarik tentang kehidupan dan cara kematian Rsi di Gunung Pananggungan atau fungsi Gunung Pananggungan bagi para Maha Rsi. Buku itu kiranya bisa menjelaskan anatomi Gunung Penanggungan di masa lalu.Buku itu bisa menjelaskan makna kaki, tubuh dan puncak Gunung Penanggungan di masa silam. Penemuan kembali rute kuno pendakian ke puncak Penanggungan oleh Hadi Sidomulyo di atas menurut hemat saya dapat memperkuat analisa anatomi Gunung Penanggungan yang dikemukakan Agus.
Agus berpendapat Gunung Penanggungan adalah tempat tinggal para maha pertapa atau Maha Rsi pemuja Parwatarajadewa, dewa yang merupakan dewa utama di Majapahit. Dewa ini merupakan dewa asli Majapahit bukan dewa Siwa atau Wisnu.Agus berpendapat Gunung Penanggungan tidak bisa didaki sembarangan oleh peziarah masyarakat biasa. Para peziarah yang datang hanya bisa sampai di tingkat paling bawah yaitu di pemandian kuno Jalatunda dan Belahan.

Panorama Gunung Penanggungan
Bagian tengah Gunung Penanggungan hanya boleh dimasuki oleh para pertapa. Dilereng-lereng tengah gunung, para petapa ini membuat pertapaan-pertapaan di gua-gua atau tempat sunyi lainnya. Di lereng tengah itu mereka juga membuat punden-punden berundak di mana mereka sehari-harinya membuat ritus-ritus keagamaan untuk memuja Parwatarajadewa. Agus berpendapat puncak Gunung Penanggungan adalah tujuan utama para pandita yang tinggal di lereng tengah ini. Mereka yang merasa telah mendekat ke ajal dan siap menyongsong ajal kemudian akan meninggalkan pertapaan mereka di lereng tengah dan mengarahkan diri untuk berjalan menuju ke puncak Gunung. Puncak Gunung Penanggungan dalam tesis Agus dengan kata lain adalah obsesi eskatologis terakhir para pandita. Puncak Gunung Pananggungan adalah klimaks dari perjalanan kehidupan mereka. Tempat para Maha Rsi menganggap bisa menyatukan rohnya ke alam lebih tinggi.
Untuk mendukung tesisnya ini Agus membaca ulang banyak temuan para arkeolog sebelumnya yang meneliti Gunung Penanggungan dan juga menafsirkan kembali berbagai kitab atau mitos. Pendapat Agus bahwa puncak Gunung Penanggungan di masa Majapahit oleh para pandita dianggap sebagai puncak tersuci dibanding puncak gunung-gunung Jawa lainnya misalnya berdasarkan penafsiran dia terhadap kitab Tantu Panggelaran. Dalam kitab ini dikisahkan terjadinya pemindahan Gunung Maha Meru dari India ke tanah Jawa. Saat proses pemindahan terjadi bagian-bagian Gunung Maha Meru jatuh menjadi berbagai gunung di Jawa. Sementara puncak atau pucuk utamanya jatuh menjadi Gunung Pananggungan.
Agus terutama juga membaca ulang penelitian arkeolog Belanda VR Van Romont. Seperti diketahui Van Romont adalah arkeolog pertama yang memetakan kepurbakalaan Gunung Penanggungan. Bertolak dari peta jalan-jalan kuno kawasan Gunung Penanggungan yang dilampirkan Van Romont dalam laporannya tahun 1951 lah, Agus berani menampilkan pemikiran orisinil bahwa para maha pertapa yang berniat menyongsong ajalnya akan melakukan sebuah – dalam istilah Agus Mahameru Pradaksinapatha atau berjalan memutar mengelilingi Pananggungan sampai puncaknya.
Seperti dikatakan di atas Agus berpendapat puncak Penanggungan adalah tujuan eskatologis bagi pandita yang menjelang ajal ingin menyatukan rohnya dengan dewa tertinggi. Para pandita yang mendekati ajal menurut Agus akan melakukan perjalanan ke puncak Penanggungan yang dianggap Puncak Mahameru. Dalam bayangan Agus, para rsi ini akan mendaki dengan tidak membawa apapun. Cara mendaki itu ditempuh dengan berjalan mengelilingi gunung searah dengan gerak jarum jam (gerak pradaksina). Sepanjang perjalanan itu berarti para pandita akan senantiasa berjalan dengan cara menganankan gunung. Dalam perjalanan berkeliling menuju puncak itu kemungkinan besar menurut Agus di samping ada yang berhasil menuju puncak dan mati di puncak, banyak pendita yang meninggal terlebih dahulu
Peta jalan kuno Penanggungan 1951 yang dilampirkan Van Romont menjadi pegangan bagi Agus untuk menyajikan pemikiran demikian .Peta itu di tahun 1951 masih menampilkan bahwa di Gunung Pananggungan terdapat jalur pendakian tua mengitari (melingkar) dari sisi tengah lereng selatan-timur-barat sampai akhirnya sampai puncak . Menurut Agus jalur melingkar selatan-timur-barat itu dibentuk dengan jalan memapras lereng sehingga terdapat sebuah ruang cukup lebar untuk dapat dilalui dua orang untuk berjalan bersebelahan.
Lebar jalan pada lereng tengah menurut Agus berkisar 3-3,5 M. Sementara mendekati puncak lebar jalankuno berkisar 1,5-2 M. Jalur rute tua pendakian ke puncak sebagaimana terdapat dalam peta Van Romont 1951 menurut Agus bisa digunakan sebagai bukti sebagai jalur yang di zaman Majapahit dipakai oleh para pandita melakukan Mahameru Pradaksinapatha. Jalur jalanan kuno itu landai, lebar dan bahkan sampai puncak tidak memunculkan jalan yang menanjak curam ke atas. Jalur melakukan Mahameru Pradaksinapatha tersebut mudah dilalui bahkan oleh para pandita yang sepuh walau waktu tempuhnya lebih lama dan harus banyak istirahat.
Menurut Agus dari Laporan Survey yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi nasional tahun 1976 jalur tua itu telah tertutup sebagian. Ketika Agus di tahun 1983 dan 1985 melakukan pendakian ke Gunung Penanggungan sebagian jalan kuno itu juga masih ada. Sementara sebagian lainnya sudah tersembunyi oleh rumputan, ilalang dan pepohonan. Pemotretan drone dan perjalanan di jalur jalan tua yang dilakukan Hadi Sidomulyo pada 2015 setelah Gunung Pananggungan terbakar yang menyingkapkan kembali adanya jalan tua melingkar di lereng timur-barat-selatan dalam hal ini bisa memperkuat tesis Agus tentang adanya Mahameru Pradaksinapatha.
***
Secara keseluruhan Agus dalam buku Arkeologi Pawitra menjelaskan bahwa secara konsep ruang, topografi Gunung Pananggungan terbagi atas pembagian triloka: bhurloka–bhuwarloka–swarloka. Masyarakat penziarah yang bukan pendeta hanya boleh menginjak Gunung Penanggungan di wilayah bawah atau kaki gunung yaitu areal Bhurloka – yang dalam hal ini hanya boleh sampai pemandian Jalatunda dan Belahan – yang sampai kini airnya masih mancur dan kolamnya masih bening itu.

Sumber Tetek
Akan halnya areal tengah- kawasan Bhuwarloka khusus menjadi area sakral yang hanya boleh dihuni oleh para pandita. Sementara puncak Gunung Penanggungungan dianggap sebagai areal Swarloka—yang menjadi kawasan tujuan akhir-para pandita yang akan melakukan tahapan kehidupan sanyasin. Tahapan sanyasin adalah tahapan bagi para pandita yang sudah tinggi ilmunya dan merasa ajalnya sudah dekat untuk melakukan pradaksina menuju puncak Swarloka. Konsep ini hemat saya mampu memberikan gambaran yang sangat jelas dan clear tentang anatomi kesucian Gunung pananggungan di masa lalu.
Yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi adalah pendapat Agus tentang pemujaan Parwatarajadewa. Benarkah yang dipuja para pandita di Gunung Pananggungan adalah Parwatarajadewa yang merupakan dewa asli zaman Majapahit yang bukan merujuk pada pantheon Hindu: Siwa atau Wisnu? Agus mengambil kesimpulan bahwa yang dipuja di Gunung Pananggungan di masa Majapahit adalah Parwatarajadewa setelah membaca disertasi S. Soepomo: Arjunawijaya an Kakawin of Mpu Tantular. Dalam disertasinya S. Soepomo menyebut Parwatarajadewa adalah bukan dewa dari kebudayaan India, bukan dewa Hindu atau Buddha melainkan dewa yang dikonsepkan oleh masyarakat Majapahit sendiri. Parwatarajadewa adalah dewa raja gunung (Lord of Mountain) atau menurut Agus adalah gunung sendiri yang diperdewa. Parwatarajadewa artinya adalah Raja gunung yang diperdewa. Parwatarajadewa menurut Soepomo sebagaimana dikutip Agus adalah dewa “nasional” bagi masyarakat Majapahit.
Persoalannya pendapat Soepomo mengenai adanya dewa asli Majapahit bernama Parwatarajadewa akhir-akhir ini telah dipertimbangkan kembali dan mengalami kritik akademis. Disertasi filolog I Made Supartha di tahun 2016 berjudul: Teks Putri Kalepasan Merapi-Merbabu (Kajian Filologis dan Konsep Eskatologis Jawa Kuno Abad ke-16 Masehi) menyebutkan apa yang disebut Parwatarajadewa sebetulnya juga merujuk kepada Siwa. Dalam disertasinya – yang juga dikopromotori Dr.Dr Agus Aris Munandar, I Made Supartha menyebutkan Sri Parwatarajadewa – yang merupakan istadewata bagi pengarang kakawin Arjunawijaya sesungguhnya sama dengan Sri Parwatanatha yang menjadi istadewata bagi Mpu Prapanca. Made Supartha menyebut menurut H.Kern dan Zoetmulder, nama Parwataraja atau Parwatanatha dalam karya-karya Jawa kuno merupakan epithet Siwa.
I Made Supartha sendiri untuk mengukuhkan pendapat bahwa Parwatarajadewa sebetulnya adalah Siwa mengajukan argumentasi berdasar analis atas pemikiran di dalam kitab Bramanda-Purana. Menurut I Made Supartha, dalam kitab Bramanda-Purana secara tegas disebut Bhattara Rudra atau Bhattara Paresmawara atau Bhattara Nilahota yang semuanya adalah nama lain dari Bhattara Siwa dalam kenyataannya adalah Bhattara Gunung. Dalam mantra-mantra pemujaan di Bali pun, khususnya mantra Panca Giri, Siwa atau Rudra dipuja sebagai Giripati atau penguasa gunung, dewa gunung. Menurut I Made Supartha maka dari itu tafsir S.Soepomo yang memaknakan Parwatarajadewa sebagai dewa gunung berdasar semata-mata kakawin Arjunawijaya tak dapat lagi dipertahankan. Dari berbagai bukti teks, Parwatarajadewa menurut I Made Supartha adalah nama lain dari Siwa.

Anak-anak mandi di Sumber Tetek
Demikianlah ada pendapat Parwatarajadewa adalah Siwa. Dalam perspektif ini maka, para rsi yang menetap di Gunung Penanggungan pada dasarnya melakukan ritual-ritual terhadap Siwa. Para rsi yang menjelang ajal melakukan Pradaksina atau perjalanan melingkar ke arah puncak Penanggungan pada dasarnya juga ingin meleburkan rohnya kepada Siwa. Tapi sesungguhnya apabila memang yang disembah dan dipuja para Rsi dan pertapa di Gunung Penanggungan zaman Majapahit itu adalah Siwa juga diperkuat oleh analisis Agus Aris Munandar sendiri tentang temuan-temuan arca di Gunung Penanggungan.
Hanya sedikit arca yang ditemukan dari lereng Penanggungan sampai saat ini. Dalam buku Arkeologi Pawitra, disebut Agus dari tujuh arca yang diketemukan di Penanggungan dua diantarannya bisa diidentifikasi sebagai arca Siwa. Satu arca setinggi 147 cm menggambarkan Siwa dengan empat tangan. Dua tangan dii depan dalam posisi meditasi di depan perut. Dua tangan di belakang memegang benda-benda yang memang biasa menjadi laksana Siwa yaitu camara (pengusir lalat) dan aksamala (tasbih).
Hal yang ”aneh” menurut Agus, arca Siwa ini mengenakan mahkota berupa topi tinggi (kiritamukuta). Sebab kiritamukuta dalam ikonografi pantheon Hindu biasanya dipakai oleh Wisnu. Sementara Siwa biasanya memakai jatamukuta, yaitu mahkota dari rambut sendiri yang dipilin meninggi di kepala. Arca Siwa kedua setinggi 150 cm. Arca ini juga mengenakan mahkota kiritamuka bukan jatamukuta. Kedua mata Siwa setengah terpejam dan rambutnya meski mengenakan mahkota tergerai di samping kanan kiri kepala. Postur tubuh Siwa tampak kaku. Hal yang menarik menurut Agus seluruh tubuh arca secara tegas menampilkan tanda garis-garis sinar.
Garis-garis bersinar adalah tanda khas ikonografi Majapahit. Tanda ini melambangkan sinar kadewatan. Kita bisa membayangkan kedua arca Siwa ini di Gunung Penanggungan masa lampau itu oleh para rsi apabila mereka memang memuja Siwa diletakkan di altar-altar lereng atau punden berundak sebagai bagian obyek peribadatan utama.
Fotografer: Yono ndoyit