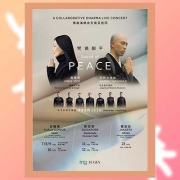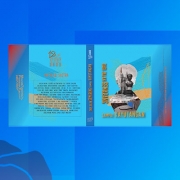Putu Wijaya, Sebuah Transkip Wawancara Tentang Teror Mental dan lain lain oleh Jose Rizal Manoa
PUTU WIJAYA:
Usaha untuk, mencoba untuk melawan larangan-larangan itu dan memanfaatkan segala kendala-kendala itu sebagai batu loncatan sebagai challenge, bahkan sebagai tambahan juga untuk membuat tenaga kita meloncat sama dengan seperti seorang pencuri yang sebetulnya badannya ringkih, tapi ketika dia dikejar oleh masyarakat mau dibunuh tiba-tiba disudut dia bisa meloncat dua meter. Padahal meloncat satu meter pun dia bisa sakit pinggang.
Ini menunjukkan bahwa ada tenaga simpanan yang ada pada orang ketika dia berada dalam satu situasi yang terjepit, dan situasi terjepit itu kalau dimanfaatkan bisa menambah tenaga kita.

Putu Wijaya (Sumber foto: https://hanaivanaya812.medium.com)
Ini saya ceritakan penting sekali karena pada beberapa tahun kemudian ketika saya berada di Jakarta, saya sampai kepada konsep ‘bertolak dari yang ada’.
Jadi apa yang ada itu dipakai, disyukuri, diterima. Jadi kita selalu melihat dari apa adanya. Menerima apa adanya. Kelebihannya, kekurangannya, semua diterima dulu, lalu memanfaatkan seoptimal mungkin apa yang ada itu.
Tidak dimulai dengan meminta ini dan itu, menyesali ini dan itu. Tapi menerima apa adanya. Bahwa kita miskin, bahwa kita kurang dan sebagainya, itu diterima dulu lalu kemudian kita manipulasi, kita maksimalkan, kita optimalkan menjadi sesuatu.
Jadi bukan nrimo dalam berarti pasrah, tapi menerima untuk memakainya sebagai modal untuk bekerja. Jadi mensyukuri seluruh kekurangannya dan kemudian membalikkan kekurangan itu menjadi kekuatan, menjadi kelebihan.
Sehingga ketika kita mencapai sesuatu kita tidak akan mencapainya dengan unsur-unsur sebagaimana orang yang lain yang dalam keadaan yang lengkap mencapainya. Dia menjadi unik. Dan ini akan menimbulkan sesuatu yang khas.
Dan ini kemudian, ini kemudian membuat saya sampai kepada, ketika kemudian saya berada di Jakarta, sampai kepada konsep ‘bertolak dari yang ada’.
Tentang Teror Mental
Nah, untuk membiasakan diri, untuk menerima sesuatu yang tadinya kita tidak sukai dan kemudian mencoba akrab dengan hal itu, lalu mencintainya, lalu kemudian menguasainya.
Karena kita tidak bisa mempergunakannya kalau kita belum mencintainya dan menguasainya. Setelah kita mencintainya dan menguasainya, baru kita benar-benar dapat mempergunakannya.
Tapi untuk menerima segala sesuatu, termasuk yang tidak kita kehendaki, termasuk yang tadinya berlawanan dengan diri kita, itukan berarti kita mesti mengubah konsep yang ada dalam diri kita sebetulnya.
Keinginan-keinginan kita yang ada dalam diri kita sebelumnya. Ide-ide kita, idealisme-idealisme kita terpaksa kita ubah karena kenyataannya berbeda. Dan ini distorsi. Distorsi ini adalah merupakan satu gangguan, gangguan ini merupakan teror. Teror kepada diri kita sendiri.
Jadi, misalnya, saya ingin ke Jakarta, tapi orang tua saya tidak boleh saya ke Jakarta. Kakak saya tidak boleh saya ke Jakarta. Uang untuk ke Jakarta juga tidak boleh. Jadi saya mesti berani menerima bahwa saya tidak bisa ke Jakarta dan saya harus menerima tinggal di Yogya saja.
Jadi saya mesti men-teror diri saya dulu, berkelahi dengan diri saya sendiri dulu untuk sampai kepada suasana jiwa yang menerima apa adanya di Yogya.
Nah, setelah menerima tidak berarti kalah, tapi kompromi. Dan baru kemudian tiba-tiba mulai mengakali. Bagaimana caranya untuk nanti pada suatu ketika akan sampai juga ketempat itu.
Jadi teror kepada diri sendiri ini berkesinambungan dengan konsep bertolak dari yang ada. Dimulai dari diri sendiri. Membiasakan diri, men-teror diri dulu. Men-teror diri maksudnya adalah mengalahkan, mengalahkan diri sendiri untuk menerima keadaan, kemudian pada suatu ketika nanti bisa kembali kepada diri yang kita harapkan.
Jadi, teror dalam hal ini adalah pengertian, bagaimana kita menyergap sesuatu, memperkosanya, sehingga kita memasuki sesuatu yang lain. Mengubah.
Kemudian pada saat-saat itu, tahun tujuh-puluhan kalau saya tidak salah, sudah mulai ada teror-teror. Pembajakan pesawat dan sebagainya sudah mulai ada seperti itu.
Teror itu adalah satu upaya untuk menerobos sesuatu dengan cara, secara fisikal. Secara fisikal mempengaruhi sesuatu. Sehingga apa yang kita kehendaki terjadi. Sesuatu yang tidak kita kehendaki, tetapi kemudian kita teror, kita paksa supaya berubah, untuk sampai kepada apa yang kita kehendaki. Tapi dilakukan dengan fisik.
Saya tidak tertarik kepada itu, tapi saya tertarik kepada caranya. Caranya, kita sampai kepada sesuatu dengan cara menerobos sesuatu dengan teror. Dan itu kalau dilakukan kepada jiwa sama saja.
Itu sebabnya kemudian saya sampai kepada apa yang dinamakan teror mental. Mengganggu, mengganggu satu keadaan yang kita inginkan tadinya, karena memang keadaannya sudah terganggu dan gangguan itu hanya sifatnya gangguan batin, sehingga kita sampai kepada satu pemahaman baru, menerima, dan sesudah itu kita kemudian kita meng-optimal-kannya.
Teror mental adalah satu usaha untuk mengganggu jiwa. Agar kemudian yang terganggu jiwanya itu bergolak. Sehingga dia mencoba kembali menafsirkan, mencoba kembali memikirkan, mencoba kembali mempertimbangkan, apa yang sudah merupakan keputusan-keputusannya.
Misalnya, seperti ini, istri saya ingin membeli mobil, lalu saya Tanya: “Kamu benar mau membeli mobil?” “Ya”. “Kan kita sudah punya mobil?” “Tapi saya ingin punya mobil yang ketiga”, “Tapi untuk apa mobil ketiga? Kan karena kita tidak memerlukan mobil ketiga? Dua saja sudah cukup.” Terus-menerus begitu dipertanyakan. Sampai kepada pertanyaan yang ke seratus barangkali.
Waktu pertanyaan pertama jawabannya tetap membeli mobil. Pertanyaan ke lima puluh tetap membeli mobil. Tapi sampai pertanyaan ke seratus tiba-tiba dia terkejut: “O,ya, ngapain membeli mobil?” Dia kebingungan. Seakan-akan itu baru pertanyaan yang baru, lalu dia mulai berpikir … nah itu!
Suasana berpikir itu yang saya sukai. Perkara kemudian dia ingin membeli mobil, bahkan ingin membeli mobil ke empat juga tidak apa-apa. Tapi pertanyaan itu membuat dia berpikir kembali, berpikir kembali untuk mengevaluasi seluruh pikiran-pikirannya dia. Membuka seluruh bagasi pikirannya, menpertimbangkan sekali lagi apa yang sudah dia putuskan.
Apapun keputusannya nanti itu akan berbeda, karena dia sudah mulai dengan pertimbangan yang baru. Bahwa dia ingin membeli mobil lagi ndak apa-apa, tapi suasana jiwanya sudah berbeda. Dia bertambah yakin … yak!
Seluruh yang saya lakukan, baik dalam pementasan, maupun penulisan-orang untuk mempertimbangkan sekali lagi apa yang sudah diputuskannya. Bukan untuk memberikan dia satu resep baru, bukan untuk mengajak dia berpikir lain, tapi hanya untuk mengganggu saja. Sehingga dia berada dalam situasi yang chaos, berpikir lagi, nah, terserah mau kemana.
Karena itu akhir dari cerita pendek, novel, pementasan yang saya buat, saya senang sekali dengan akhir yang mengapung. Akhir yang tidak memberikan solusi, karena saya takut solusi itu akan menjebak orang, seperti harus mengikuti jalan itu.
Saya tahu apa yang saya, jawaban saya, saya tahu. Dan saya tidak ingin orang menjawab seperti saya. Setiap orang bebas untuk menjawabnya. Menurut latar belakangnya, tuntutannya sendiri, keyakinannya sendiri, apa yang berguna buat dia, seperti itu.
Jadi ‘teror mental’ dengan ‘bertolak dari yang ada’ adalah dua konsep yang sampai sekarang saya pakai. Sebagai dasar saya bekerja. Strategi saya bekerja. Bahkan juga tujuan saya bekerja. Tidak untuk memberikan resep, tidak untuk mengobati, tapi justru menyakiti. Untuk membuat orang menyembuhkan dirinya sendiri, menurut kebutuhan dan kepentingan masing-masing, sesuai dengan keadaan masyarakat, masyarakat yang kita yang heterogen.
Kita kan hidup dalam masyarakat plural, yang sangat berbeda satu sama lain. Ada beberapa suku, ada ratusan bahasa. Di Bali sendiri, ada macam-macam orang Bali. Jangan dikira orang Bali itu cuma satu. Ada orang Bali utara, Bali selatan, Bali timur, Bali barat. Dan ada orang Bali kuno, orang Bali sekarang, ada orang Bali yang murtad, dan sebagainya. Seperti orang Jawa juga seperti itu.
Saya sudah menceritakan tadi tentang bertolak dari yang ada kemudian terror mental, yang bagaimana sampai terjadinya, kemudian hubungannya satu sama lain, yang mungkin juga kita ceritakan lebih jauh lagi nanti.
Tentang Anekdot
Lalu ada hal yang lain lagi, yang menarik. Yang bisa dibicarakan adalah tentang anekdot. Kenapa anekdot itu, kenapa, kenapa, kenapa kita mesti membicarakan anekdot.
Dari kecil saya memang senang sekali kepada hal-hal yang lucu. Kalau lihat majalah itu, yang pertama kali saya lihat adalah komik-komik strip-nya, yang dari, ada tiga kotak, ada satu kotak, gitu. Cerita-cerita bergambar, cerita-cerita bergambar itu selalu menangkap moment yang lucu, unik, dari sesuatu yang, dari satu hal yang kadang-kadang di belokkan.

Putu Wijaya. (Sumber foto: FB Putu Wijaya)
Misalnya, waktu SD kan sering sekali ada empat gambar di mana kita harus bercerita. Antara lain, yang saya ingat itu misalnya, ada seekor burung bertengger di atas sumur, lalu ada kemudian kucing ingin maumenangkapnya, gitu. Ketika ingin menangkapnya, ketika burung itu lepas, kucing itu jatuh ke sumur. Tapi ada juga, ketika burung lepas, kucing mau jatuh ke sumur, kucing itu melompat ke atas garis pembatas, pembatas dari garis komik strip itu. Yang tadinya kita menganggap sebagai garis pembatas saja ternyata, ternyata dipakai oleh kucing itu untuk berpegangan. Misalnya seperti itu.
Hal-hal ini kan mengejutkan sekali. Sesuatu yang tidak terduga, tapi menimbulkan satu yang rangsangan di dalam batin kita. Ada penyegaran, gitu. Kemudian cerita-cerita tentang orang Batak, tentang orang Padang, cerita tentang orang Bali, cerita tentang orang Cina, dan sebagainya, yang lucu-lucu.
Kalau dikumpulkan anekdot-anekdot di masa penuh keterbatasan ini banyak sekali dan lucu-lucu sekali. Bahkan orang yang kena, kena lempar oleh anekdot itu pun bisa ketawa karena lucu. Karena lucu sekali. Tapi di balik kelucuan itu kita melihat satu kecerdasan, satu kemampuan untuk memaket seluruh keinginan yang mau disampaikan itu dengan satu bentuk-bentuk yang lucu, yang seperti kadang-kadang menyesatkan, membelokkan, tapi sebenarnya kalau dipikirkan itu merekam seluruh pikiran-pikirannya.
Itu di belakangan saya coba evaluasi diri saya, kenapa kok saya suka anekdot. Dari awal memang saya suka sekali anekdot. Saya kira semua orang suka anekdot. Semua orang sebenarnya ingin sekali berbincang, ingin sekali mengutarakan pikiran, ingin sekali mengeritik, tetapi masyarakat, di mana harmoni sangat penting artinya untuk membuat kita bisa hidup masih di dalam saling hormat-menghormati dengan segala perbedaannya.
Ini menyebabkan aturan-aturan ketat sekali. Sehingga kita tidak bisa ngomong frontal. Kita tidak bisa ngomong seperti orang Amerika, kalau dia suka langsung dia bilang suka. Kalau dia tidak suka dia langsung bilang tidak suka. Dan tidak ada permusuhan. Kalau kita kan sulit sekali. Kita, rasa sangat penting. Sehingga kalau ada orang bilang tidak suka, meskipun kita tahu dia benar, tapi kita, karena menimbulkan permusuhan yang lama. Karena rasa buat kita sangat penting.
Ini, perbedaan culture ini menyebabkan anekdot itu menjadi subur sekali ditempat kita, sebagai jalan pelepasan untuk menggemboskan perasaan-perasaan, untuk menyalurkan pikiran-pikiran yang tidak bisa disalurkan dengan saluran-saluran formal yang biasa. Sehingga lahirlah anekdot-anekdot itu.
Dan anekdot-anekdot ini sering sekali dianggap oleh banyak orang sebagai hanya lelucon saja. Tapi saya selalu melihat apa yang ada di balik itu.
Jadi saya seakan-akan punya microscop di mata saya. Atau di telinga saya ada suatu cara menangkap yang berbeda, karena begitu mendengar satu anekdot, jelas terbayang apa yang ada di belakangnya itu.
Sehingga kemudian saya merasa, nah, ini satu lapangan yang tidak terlalu banyak digarap. Karena orang lebih senang kepada tema-tema besar. Kepahlawanan, semangat kebangsaan, kemerdekaan, cinta kasih, dan sebagainya. Yang kemudian diceritakan dengan bagusnya di dalam karya-karya seni. Banyak hal-hal yang remeh-temeh yang kemudian dianggap hanya sebagai seloroh saja, dibuang begitu saja dalam tong sampah.
Lalu saya mencoba menjadi pemulung yang pergi ke tong-tong sampah itu, mengambil segala lelucon, segala sindiran-sindiran. Segala hal-hal, guyonan-guyonan, yang nampaknya sambil lalu dilontarkan, tapi yang saya lihat menyimpan sesuatu yang sangat penting di baliknya,. Yaitu, dia menyimpan pesan-pesan, pemikiran-pemikiran, saran-saran dari orang banyak terhadap situasi yang ada.
Itu sebabnya kemudian saya menjadi seperti pemulung anekdot, tetapi tidak menceritakan anekdot itu kembali. Karena kalau sebuah anekdot sudah diceritakan oleh orang lain, dia sudah menjadi hak, milik bersama. Jadi kalau kita ulangi lagi itu, ya, sudah klise.
Bagaimana membuat anekdot itu? Jadi, kalau dalam keadaan sehari-hari orang banyak mengumpulkan anekdot kemudian menceritakannya kembali untuk bergaul. Saya mencoba untuk melihat anekdot-anekdot itu, mengumpulkannya dan belajar dari anekdot-anekdot itu bagaimana meng-compose-nya.
Bagaimana membuat anekdot, bagaimana untuk melemparkan pikiran-pikiran kita yang membuat orang merasa itu sebagai anekdot, tetapi sebenarnya itu adalah semacam pemikiran-pemikiran yang diberikan bingkisan agar selamat sampainya. Karena apa? Karena banyak sekali larangan-larangan.
Adanya sara di masa lalu menyebabkan kita tidak mungkin melakukan sebebas-bebasnya apa yang apa yang ingin kita lakukan. Ada batas-batasnya. Tapi kalau kita paketkan di dalam anekdot, maka tiba-tiba sara itu tertembus.
Ini juga salah satu upaya saya, ketika saya tadi sebelumnya mengatakan bahwa berikan saya seribu atau lebih larangan-larangan, saya akan bisa menerobosnya. Anekdot! Adalah satu package, adalah satu bungkus yang sangat memungkinkan hal itu. Yang bisa memungkinkan hal itu. Yang bisa menembus apa saja.
Karena orang, orang menganggapnya sebagai sampah. Orang menganggapnya sebagai satu guyonan yang tidak serius. Ah, nggak penting, tidak berbahaya, tidak perlu terlalu dimasukkan ke dalam hati. Ini seloroh saja. Ketika dibungkus seperti itu maka dia selamat masuk ke mana.
Ini seperti passport, seperti password yang bisa menembus semua, apa namanya, sandi-sandi, sehingga bisa masuk. Lalu saya menyerap anekdot itu, lalu masuk ke dalamnya, mempelajarinya dan kemudian mencoba melihatnya sebagai sebuah senjata.
Sebagai sebuah kenderaan untuk terapy terhadap suatu keadaan yang begitu banyak pressure-nya. Begitu banyak larangannya. Begitu banyak yang tidak boleh, sehingga kita mesti menyulap sesuatu.
Kita mesti menjadi tukang sihir, kita mesti mesti menjadi seorang pemain sulap. Menyulap sesuatu, membungkus sesuatu dalam satu kemasan tertentu, sehingga dia tetap bisa berjalan namun mengandung isi itu, buat orang yang benar-benar ingin mengetahuinya. Tapi kalau buat orang yang tidak mau mengetahuinya, ya, mungkin hanya akan sampai sebagai seloroh saja. Nah, hanya sampai sebagai sampah saja.
Jadi saya menulis cerita-cerita sampah, menulis novel-novel sampah, membuat pementasan-pementasan sampah, yang membuat orang memperlakukannya sebagai sampah juga. Saya kira ini sebabnya, sejauh ini, sampai sekarang ini saya tidak memiliki hambatan di dalam berkreasi dari pemerintah.
Begitu banyak teman-teman yang merasa gerah sekali karena terhambat berekspresinya. Tapi dari dulu sampai sekarang saya merasa, saya bebas sekali melakukan apa pun yang ingin saya lakukan. Cuma dalam melakukan apa pun yang ingin saya lakukan, saya kemas sedemikian rupa, sehingga orang, sering orang terkecoh. Tidak tahu apa sebenarnya isinya. Kecuali kalau dia sungguh-sungguh. Salah satu contoh misalnya, saya membuat drama yang judulnya Front.
Pada waktu itu ada peristiwa di Tanjung Priok, di bawah pemerintahan orde baru, yang menyebabkan ada orang meninggal segala macam. Lalu saya renungkan peristiwa itu. Saya tidak berpihak ke mana-mana. Saya hanya berpihak kepada saya sebagai orang Indonesia. Saya melihat peristiwa ini adalah peristiwa yang harus diperingati.
Saya ceritakan tentang sebuah kerajaan yang mencoba untuk mengurangi pahlawan-pahlawannya. Karena pahlawan-pahlawannya sudah menjadi tua, memang jasanya besar, tapi ketika dia sudah menjadi tua dia menjadi beban. Dan bebannya kalau terlalu banyak kerajaan ini menjadi sulit, karena pahlawan-pahlawan ini minta prioritas yang lebih dari orang-orang biasa. Sementara dia melakukan hal-hal yang bukan kepahlawanan lagi. Karena itu, kerajaan itu ingin menyeleksinya.
Untuk menyeleksinya, dibuatlah pura-pura ada satu pertempuran baru, sehingga kita memerlukan pembela-pembela. Lalu keluarlah para pahlawan-pahlawan itu. Tentu saja mati dalam pertempuran itu karena dia tak sanggup lagi berkelahi.
Sementara itu anak-anak muda pun dipanggil keluar. Anak-anak muda yang terlalu keras, yang agak berbeda pemikirannya dengan kerajaan itu, disuruh untuk, diberi keleluasaan, diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, sehingga begitu mereka keluar lalu kemudian dihajar. Jadi perang itu dibuat untuk membunuh orang-orang tua juga kemudian menyunat orang-orang, anak-anak muda ini.
Ini kemudian sebabnya, saya kemudian tinggal kepada anekdot itu. Karena ketika dibungkus sama anekdot, maka dia bisa selamat jalannya. Bisa smooth jalannya. Kemana saja.
Jadi anekdot buat saya adalah senjata. Anekdot buat saya adalah kemasan. Anekdot buat saya adalah satu kekayaan yang memungkinkan saya untuk menerobos sesuatu dengan selamat. Tetapi juga bisa dinikmati oleh orang banyak, gitu.
Anekdot itu sampai sekarang tetap saya pertahankan. Tapi sebagai akibatnya memang, kalau kita menulis anekdot orang merasa, ini sesuatu yang tidak penting. Sesuatu yang remeh-temeh saja. Sesuatu yang tidak serius. Sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Sesuatu yang, ya, boleh dibaca, boleh nggak. Boleh dilihat, boleh nggak, seperti itu. Itu resikonya. Artinya, besar kemungkinan tidak akan popular. Besar kemungkinan orang tidak akan tahu tepat pada saatnya apa yang kita mau katakan. Jadi kita mesti bersabar.
Bersabar berarti, ekspresi, baik itu berupa novel atau cerita pendek atau apa saja, itu adalah satu investasi cultural yang buahnya itu tidak sekarang langsung bisa kita nikmati, mungkin lama sekali.
Bahkan siapa tahu barangkali terlalu lama sehingga kita sendiri tidak bisa menikmatinya. Generasi ini tidak bisa menikmati, generasi nanti bisa menikmati. Ada orang lain yang bisa menikmatinya.
Masalahnya sekarang, rela nggak, mau nggak, tidak bisa menikmati apa-apa sekarang? Saya nggak pernah berpikir untuk, untukmempertimbangkan ini, karena saya, saya terima saja. Saya tidak peduli apakah itu akan, sampai sekarang, sampai nanti, atau tidak akan sampai, tidak terlalu menjadi masalah buat saya. Yang penting saya mencoba untuk menitipkannya.
Karena jauh dalam pikiran saya, saya sadar bahwa satu pemikiran, apa pun, apa pun bungkusnya, bagaimana pun kita menyembunyikannya, pada suatu ketika sejarah akan membukanya. Seperti anggur, makin lama, mungkin dia makin matang makin enak. Kalau sekarang diminum dia memang fresh, tapi seperti fastfood juga, sekarang, untuk memuaskan sekarang saja, setelah itu nggak ada apa-apanya.
Berbeda dengan sesuatu yang ditanam, makin lama makin matang dan pada suatu ketika sejarah membukanya, mereka baru tahu, ”…..ah, ternyata begini!” Saya senang sekali surprise-surprise seperti itu.
Karena itu saya tidak terlalu memforsir bahwa apa pun yang saya buat didalam kesenian itu tidak harus langsung ada reaksinya, akibatnya, ada kegunaannya, karena dia merupakan satu tabungan. Tabungan moral, tabungan batin. Siapa tahu tidak berharga, juga tidak apa-apa.
Karena seorang yang bekerja untuk kesenian tidak selamanya mampu untuk menghasilkan yang berharga. Tidak selamanya bisa menciptakan sesuatu yang luhur. Mungkin dia hanya kerajinan-kerajinan biasa, mungkin hanya ekspresi-ekspresi yang biasa, yang tidak ada pentingnya, tidak ada gunanya untuk sekarang , bahkan nanti, tidak apa-apa. Tapi minimal, karena, itulah tempat saya, itulah kemampuan saya, jadi itulah yang saya bisa berikan.
Putu Wijaya di Mata Caerul Umam :
Saya melihat Putu pertama kali itu di Yogya. Ketika sama-sama di Asdrafi (Akademi Seni Drama dan Film).
Cuma barangkali waktu di Asdrafi itu Putu tidak mengenal saya, saya mengenal dia karena dia tingkatnya sudah lebih tinggi waktu itu. Dia sudah kelas tiga waktu itu, saya baru masuk.
Kemudian ada pementasan-pementasan di Asdrafi, setiap bulan itu ada pementasan, saya melihat Putu bermain bersama, dia satu kelas atau di atas, enggak, satu kelas dengan Maruli Sitompul waktu itu. Bermain, wah! Kemudian saya juga melihat pementasannya dia, waktu itu di sana, belum kenal, ya? Waktu, di Yogya waktu itu.
Ketemu di Bengkel Teater dan sama-sama di sana. Kita latihan bersama, kemudian menyatu di sana. Kesan saya pada Putu ini, sangat energik. Orangnya sangat energik sekali. Dan kata Rendra ini Putu memang, dekat sekali ini gayanya dengan lingkungannya, dengan lingkungan Balinya. Yaitu, penuh fisikal, gitu lho. Serba besar, serba berkeringat, serba, serba otot, gitu lho. Dan sesuai dengan orangnya yang tinggi besar waktu itu, ya?

Almarhuim budayawan WS Rendra memberi sambutan saat pemberian penghargaan kepada Putu Wijaya. (Foto: ANTARA/FANNY OCTAVIANUS. (Sumber: https://www.antaranews.com)
Kemudian kira-kira setahun apa, setahun deh kayaknya, setahun lebih, gitu, sempat kami mementaskan, yang paling mengesan itu ‘Waiting for Godot’ bersama beliau. Dan dia sungguh-sungguh sangat menghayati perannya waktu itu, jadi Pozzo. Sampai konsentrasinya begitu tinggi, persiapannya begitu, sampai dia sempat, sempat histeris, nangis gitu lho. Belum ketemu perannya sampai nangis gitu. Saya melihat dia serem sekali waktu itu. Kita bermain bersama.
Sehabis itu, ya, sebelumnya, sebelum ‘Waiting for Godot’, ya, pementasan-pementasan ‘Mini Kata’. Dia banyak membuat nomor-nomor ‘Mini Kata’ yang bagus-bagus waktu itu. Sempat kami pentaskan juga di Yogya, kemudian ke mana-mana waktu itu, ya? Ke kota-kota kecil.
Kemudian akhir dari, akhir dari, di Bengkel Teater, kita sama-sama tergoda rupiah, waktu itu. “Gimana, Put? Kita pergi aja ke Jakarta ini. Amak Baldjun sudah pergi ke Jakarta, gitu, ya? Sju’bah Asa sudah pergi ke Jakarta”. “Terus gimana? Di sana mau ngapain nih?”. “Ya, udah, ke ini aja, anda punya kemampuan menulis, saya mau coba-coba jadi wartawan”. Kita semuanya meninggalkan, meninggalkan dunia teater waktu itu.
Masuklah kita ke majalah Ekspres, namanya. Sebab di sana banyak teman-teman. Waktu itu ada, teman-teman Pekalongan ada di sana. Ada Sju’bah Asa, ada Amak, ada ini, Goenawan Mohamad, ya, waktu itu yang bosnya, ya? Kita langsung saja diterima. Putu sebagai penulis, saya sebagai reporter. Tapi baru berjalan satu bulan, rupa-rupanya, majalah itu bubar. Majalah itu bubar, mereka berantem, yang, siapa, yang punya uang berantem, bubar.
Akhirnya kami menggelandang lagi, masuk ke Teater Populer. Kita bertamu ke Teater Populer yang dipimpin oleh Teguh Karya. Sempat kami berdua itu bermain di sana. Bertamu sebagai pemain tamu. Di repertoar ‘Jayaprana’, ‘Jayaprana’. Putu jadi, siapa itu nama perannya, lupa saya, saya jadi rajanya waktu itu.
Di situlah kami berkenalan dengan Slamet Rahardjo, Riantiarno, Silvia Nainggolan, Dewi Matindas, ya? Setelah itu, bubar. Setelah itu kita kembali masing-masing menggelandang lagi. Tidak punya kerjaan lagi. Kemudian saya masuk ke Teater Kecil. Masuk ke Teater Kecil, kalau nggak salah bersama Putu juga masuk ke sana.
Apa, tengah-tengah kita bermain di Teater Kecil, tiba-tiba ada panggilan untuk masuk lagi ke mana, majalahnya eee “Goenawan punya majalah baru namanya Tempo” katanya. Kami semuanya alumni-alumni diundang, Ekspres, saya sudah malas, saya sudah malas, saya bilang: “Put, kamu saja ke sana deh, ke sana deh?”
Akhirnya Putu tetap menjadi penulis di Tempo, saya nggelandang lagi bersama ke Teater Kecil. Saya melihat Putu luar biasa. Ini orang sangat energik dan serba bisa gitu lho. Heran. Dan cukup mengagumkan. Teman-teman, bukan hanya saya, jadi teman-teman cukup kagum terhadap dia. Terhadap energinya gitu lho. Dia sekaligus bisa nulis novel, kemudian novel, kemudian menulis cerita pendek-cerita pendek, kemudian naskah drama, sekaligus juga nyutradarai dan dia kadang-kadang main juga. Lima hal dia rangkep jadi satu dalam satu waktu. Apa lagi kalau cara mencari uangnya waktu itu. Kalau ada lomba-lomba penulisan selalu ngikut dia. Ada lomba penulisan novel, dia ngikut. Ada lomba penulisan cerita pendek, dia ngikut. Dan selalu menang. Selalu menang itu.

Putu Wijaya saat menjadi wartawan Tempo di Jakarta, 1977. (Foto: dok. Tempo/Ed Zoelverdi). (Sumber: https://majalah.tempo.co)
Di Majalah Femina juga menang. Di Dewan Kesenian Jakarta menang. Dan itu dengan cepatnya dia bikin. Dua minggu satu novel. Dua minggu itu dia bisa melahirkan satu novel, satu naskah drama, kemudian menyutradarai dan bekerja sebagai writer di Majalah Tempo. Luar biasa waktunya, dan dia bisa membagi waktu. Heran saya. Di rumah itu cuma, kerjanya cuma, habis itu nulis, habis nulis ya, tidur, makan, nulis lagi, tidur, makan, nulis lagi. Mandi sebentar, ke kantor. Itu istimewanya.
Saya kira belum ada tandingannya, sampai detik ini belum ada tandingannya orang seenergik Putu Wijaya ini. Kemudian saya numpang di rumah dia sampai dia berhasil punya rumah, ya, di sebuah kampung kecil di Pramuka, gitu. Dia beli rumah. Saya numpang sama dia. Numpang situ. Dan ketika dia ada, apa? Ada grand ke Jepang waktu itu, ya? Itu, saya nungguin rumah itu. Diapulang dari sana dan mendirikan teater Mandiri. Nah, saya ikut mendirikan itu teater Mandiri waktu itu.
Pementasan bersama dia, mungkin di teater Mandiri saya cuma sekali- sekali saja, ikut di program-program televisinya. Sehabis itu kita berpisah, berpisah. Putu dengan Teater Mandirinya sampai detik ini. Sampai detik ini. Dan memang ciri khas dia itu memang energik. Semua dengan kekuatan fisik, gitu lho.
Teaternya itu sangat terpengaruh dengan lingkungan Balinya. Tidak lepas dari Balinya itu. Selalu dengan properti-properti boneka yang, model patung-patung. Bayangan saya itu patung-patung Bali, gitu ya? Diterjemahkan dalam boneka-boneka raksasa.
Sampai kemarin waktu dia mendapat hadiah, e, apa? Dewan Kesenian Jakarta, pementasannya masih begitu. Judulnya saya lupa itu, a, bukan hadiah Dewan Kesenian, hadiah Akademi Jakarta. Hadiah Akademi Jakarta dia tetap pementasannya seperti itu.
Teman-teman juga mengatakan, “mesti ada patung ini, mesti ada boneka ini, mesti ada boneka”, betul boneka. Dan karya-karyanya sangat spesifik dia, selalu dia membela keadilan. Dia selalu protes kepada ketidak-adilan. Kejujuran itu selalu dikemukakan. Bagaimana dia , e, memprotes terhadap e, apa, e, pemerkosa-pemerkosa keadilan, gitu ya, itu selalu. Tapi dengan secara halus, dan, dan malah beberapa pengamat mengatakan kurang nyata gitu lho. Hanya orang-orang dekat saja tahu, ini, wah ini maksudnya ini, maksudnya ini, dia ada semacam ketidak beranian untuk menyatakan untuk protes. Atau memang gaya dia memang begitu.
Gaya dia itu, protes dia itu memang halus, ya? Ditutupi, gitu lho. Ditutupi dengan budaya-budaya Bali, gitu. Sekarang bukan hanya menyutradarai, membuat, membuat novel dan sebagainya. Sekarang ditambah dengan membuat skenario. Jadi tambah novel, skenario, menyutradarai, bikin, bikin apa, bikin naskah teater, main juga, keliling dunia juga, gitu, luar biasa!
Saya kira belum ada tandingannya. Rendra kalah dalam hal ini, dalam soal, ini ya, produktifitas. Dia itu produktifitas sangat tinggi, kwalitasnya juga tidak terlalu jelek. Istimewa juga enggak. Tapi tidak terlalu jelek lah dibandingkan dengan produktifitas dan kwalitas lumayan tinggi.
Putu Wijaya di Mata Michael H. Bodden :
Baru-baru ini saya nonton, kalau nggak salah ‘Merdeka’. Dan dia sepertinya sering pakai properti yang agak mirip. Ada layar besar putih, kadang-kadang makan orang, kadang-kadang orang dibalut di dalamnya, berusaha keluar, atau apa, seperti itu. Dan itu bisa, itu bisa menyinggung banyak persoalan. Paling tidak banyak persoalan yang bisa tersirat dengan properti-properti seperti itu. Tapi pada saat yang sama seperti ada perubahan dalam penulisan cerpen Putu. Sekarang jadi lebih blak-blakan kalau menangani persoalan sosial Indonesia atau politik Indonesia.
Nah, saya kurang jelas, apakah gaya yang lama itu lebih tajam atau gaya yang baru yang lebih tajam. Kadang-kadang saya merasa gaya yang lama, memang bisa kita pikir lebih dalam. Tapi itu tidak dibawa ke dalam pementasan-pementasannya.
Kalau saya, saya lihat, ya, mungkin pementasannya baru-baru ini tidak sekuat dulu. Dan saya nggak tahu mengapa? Itu mungkin perlu penelitian atau satu orang yang agak dalam kelompoknya, seperti Cobina mungkin lebih tahu. Mungkin nanti bisa bicara sama dia, kenapa itu terjadi perubahannya, dan kenapa kadang-kadang pementasannya, memang terasa lebih, lebih apa, lebih seadanya. Tapi kalau saya lihat, ya, untuk zamannya, Putu, khususnya sejak tahun 70-an, 80-an, teater Putu termasuk teater naskah, yang paling naskah dan improvisasi ‘Lho’ dan ‘Nol’, itu merupakan perintisan yang cukup penting untuk perkembangan teater Indonesia ke depan. Atau paling tidak untuk dua atau tiga dasawarsa sesudahnya.
Saya kira ada pengaruh dari karya-karya itu pada beberapa penulis. Mungkin mereka tidak akan setuju dengan penafsiran saya, tapi saya lihat pengaruh itu di dalam satu-dua naskah dari Makasar. Misalnya satu naskah Aspar, ‘Perahu Nuh II’ . Dia merasa itu sebenarnya terpengaruh oleh gaya Arifin. Tapi kalau saya lihatnya, itu mungkin Putu. Saya kira ada mengaruh itu, ada juga pengaruh dari nomor-nomor yang tidak pakai naskah, yang sangat mengesankan bagi pemain-pemain dan penulis teater, seperti dari Teater Sae.
Afrizal Malna baru kemarin itu bicara tentang kesan dari pementasan-pementasan Putu. Dia anggap itu paling tidak puncak pencapaian Putu, karena bisa membebaskan teater dari pola-pola lama. Boedi Otong juga terkesan dengan pementasan-pementasan itu. Jadi saya kira pengaruh Putu cukup luas dan gayanya khas waktu itu, saya kira nggak ada duanya di Dunia, yang bisa bikin naskah seperti dia juga ada tahun-tahun 70-an, 80-an, dengan tokoh yang nggak ada watak yang jelas. Bisa berubah tergantung arus perdebatan, kemudian, ya, naskah sendiri nggak didasarkan atas alur cerita yang linier, tapi lebih didasarkan atas perdebatan bisa berubah-berubah setiap saat menurut tokoh-tokoh yang merupakan peran saja daripada individu dan pola, apa, melingkar mulai dengan persoalan tertentu dan berakhir dengan persoalan yang mirip, tapi mungkin ditahap yang lebih tinggi atau, jadi gaya dia sangat khas, dan saya, saya belum ketemu, ada mungkin unsur-unsur satu atau dua yang mirip di teater absurd atau bagaimana, tapi sebagai keutuhan itu tidak ada dua yang seperti Putu.
Jadi baik dari perintisan dia sebagai penulis naskah dan gaya, menulis naskah maupun dari segi menciptakan bersama pemain-pemainnya, karya-karya tidak pakai naskah, saya kira dia cukup merintis banyak hal.
Putu Wijaya di Mata Afrizal Malna :
Generasi baru di teater Indonesia, ya, yang mengubah cara penulisan naskah sebelumnya, ya, Goenawan menyebut itu sebagai naskah yang ditulis oleh sutradara. Yang sebelumnya tidak terjadi, ya. Yang muncul generasi yang belakangan, hampir bersamaan antara Putu dan Arifin.
Dan strategi narasinya oleh Putu sendiri banyak disebut sebagai teror. Ini menurutku stategi narasi Putu, karena lebih mirip dengan silat, ya? Ada salto-salto yang dilakukan ditingkat pikiran. Dan yang tidak diketahui publik, pembaca naskah-naskahnya Putu, bahwa strategi narasi yang dilakukan Putu, sebenarnya seimbang dengan strategi narasi visual yang dilakukan Putu di pertunjukan-pertunjukan teater Mandiri.
Nah, itu yang tidak terbayangkan pembaca. Antara strategi visual dan strategi narasi itu. Misalnya bagaimana tubuh aktor dibalut-balut, sehingga tubuh jadi benjol-benjol. Jadi nggak jelas, jadi distorsi. Semacam ada kubisme di teater Mandiri, ya?
Dan aku sendiri bisa mengerti, ya, bahwa penulis naskah yang menulis di luar teater akan sulit membayangkan, bagaimana waktu bergerak di panggung. Bagaimana ruang tumbuh di panggung, ya? Dan sutradara yang menulis naskah, dia menulis naskah dengan suatu pemahaman bagaimana nafas bergerak di panggung. Sehingga putu mengerti speed di pertunjukannya.
Bagaimana gerak tumbuh lewat dialog itu, ya? Yang mungkin tidak terbayangkan oleh penulis-penulis yang di luar teater. Kira-kira seperti itu ya, apa yang aku sebut dengan Putu adalah awal munculnya narasi baru di dalam teater Indonesia tahun-tahun 70-an dan tahun 80-an.
Putu Wijaya di Mata Benny Yohanes :
Putu itu adalah seniman teater yang secara fisik melakukan migrasi dari ranah budaya lokal Bali ke budaya kota Yogyakarta, lalu kemudian ke budaya urban Jakarta.
Migrasi fisik itu kemudian juga melahirkan bentuk-bentuk migrasi estetik, ya, migrasi pemikiran. Nah, teater-teater putu Wijaya, baik dalam bentuk teks atau pun dalam bentuk visual pertunjukan itu menunjukkan upayanya untuk memperlihatkan identitas barunya. Dari ranah budaya lokal ke ranah budaya urban.
Nah, pergeseran dari lokalitas Bali ke wilayah budaya yang lebih profan seperti Jakarta itu melahirkan sejumlah bentuk-bentuk teater yang mengetengahkan, ya? Pertama, munculnya bentuk-bentuk kontradiksi di dalam teks itu. Kontradiksi ini bisa dipahami karena memang Putu hidup juga di dalam dunia yang kontradiktif itu. Bahwa dia masih memiliki memori tentang dunia lokal Bali, tetapi memori tentang dunia lokal Bali itu sekaligus juga menjadi beban ketika dia harus mengekspresikan identitas barunya sebagai bagian dari masyarakat urban Jakarta.
Nah, di dalam teks-teks Putu Wijaya kontradiksi itu kemudian melahirkan bentuk-bentuk teks yang memunculkan anonimitas tokoh, lalu pengasingan atau alienasi latar, ya? Atau setting peristiwa, juga kemudian memunculkan bentuk diksi dramatik yang sifatnya lebih oral begitu daripada literal. Nah, bentuk-bentuk inilah yang kemudian melahirkan juga sebuah strategi baru di dalam mengungkapkan tema-tema, ya?
Dan strategi baru itu saya sebut sebagai bentuk dekonsentrasi nilai. Artinya, dalam teks-teks Putu Wijaya, ketika dia menggambarkan tema maupun peristiwa, nilai-nilai itu selalu disuguhkan dalam konsep tesis dan antitesis secara bersamaan.
Dan Putu seringkali tidak mengakhiri kontradiksi antara tesis dan antitesis itu menjadi sebuah sintesis. Artinya, bahwa penonton atau pembaca teks drama Putu Wijaya itu memang dibiarkan untuk menggelandang, ya, antara pilihan untuk percaya pada tesis atau pun juga kepada bentuk-bentuk antitesisnya.
Dan kegelisahan itulah yang kemudian mewujudkan atau menimbulkan efek teror mental ini, gitu.
Putu Wijaya di Mata Ucok Hutagaol :
Seorang Putu Wijaya bagi saya, saya menganggap dia seorang yang jenius. Orang yang pintar. Karena apa, teman-teman saya itu banyak yang tidak sekolah, banyak yang bukan orang teater, tapi dipegang oleh mas Putu itu menjadi, bisa menjadi aktor, bisa menjadi pintar, gitu, bisa menyampaikan sesuatu kepada penonton, gitu.
Contohnya saya lihat, pernah saya lihat Kamsudi Merdeka. Kamsudi Merdeka saya lihat tidak begitu pintar, tapi kalau Putu Wijaya megang dia, Kamsudi Merdeka menjadi pintar sebagai aktor. Termasuk Amin, ada Amin yang pernah masuk sama saya, termasuk teman saya juga, Edi Pantat, itu tidak bisa bicara. Kalau bicara itu gap-gap-gap, tapi begitu dipegang mas Putu, mas Putu mengerti benar orang itu gimana, lekak tubuhnya bagaimana, kelemahannya di mana, sehingga justru bagi saya mas Putu itu menciptakan aktor-aktor, cuma tanpa disadari, teman-teman saya yang menghina saya masuk di Mandiri, mereka tidak, tidak terjun langsung bagaimana mengenal mas Putu.
Waktu saya main di Jepang, orang Jepang itu tidak tahu bahwa teater kita itu seperti itu, gitu. Begitu kami belum main, mereka sedikit menganggap enteng kepada kami, gitu. Tapi begitu mas Putu, teater Mandirinya mengenalkan teater Mandiri dengan, dengan pementasannya, itu sambutannya sangat luar biasa sekali. Mereka itu mendapatkan imajinasi-imajinasi yang sangat berkembang, apalagi orang Jepang, ya? Mereka itu sampai mengambil filmnya berulang-ulang-ulang-ulang-ulang-ulang, itu sangat luar biasa sekali, mereka mendapatkan ide-ide baru, bahwa teater ini ada teater seperti ini, gitu, di Indonesia. Mereka menganggap di Indonesia itu tidak ada teater yang seperti ini, ternyata mas Putu mengenalkan teater seperti ini. Maka kami tahun berikutnya diundang lagi, tahun berikutnya diundang lagi, tahun berikutnya diundang lagi. Ternyata mereka ingin mempelajari, bagaimana cara kita membikin teater seperti itu, gitu. Jadi, bertolak dari yang ada. Nah, bagaimana kami memakai kostum dengan apa adanya. Dengan Koran, dengan kardus. Properti juga seperti itu. Itu yang menjadi penasaran bagi mereka. Karena di Jepang tehnologi sangat canggih, tapi teater Mandiri sama mas Putu, itu, dengan kami bertolak dari yang ada, kami memakai tehnologi yang sangat rendah. Waktu itu saya mainkan lampu. Terus saya pegang lampu, termasuk di Jerman ini, di mana-mana itu selalu di protes saya. “Tidak boleh memainkan lampu seperti itu”, katanya, “apalagi lampu jelek seperti itu”. Lalu saya bilang, “inilah model kami”, saya bilang. “Kalau lampu ini tidak saya pakai pertunjukan kami tidak maksimal”, saya bilang. “O, nggak”, di Jepang itu sama di Jerman, mereka mencarikan saya lampu yang bagus-bagus. Dipilihkan, suruh pilih sebagus-bagusnya. Ternyata satu pun lampu itu tidak ada yang cocok. Jadi akhirnya diskusi-diskusi, dibolehkanlah saya memakai lampu yang saya bawa dari Gedung Kesenian. Nah, setelah saya pakai,saya hidupkan, saya main latihan, baru mereka mengerti, “o, ini maksudnya, ini motivasinya”, seperti itu. Jadi, dan mereka juga, perbandingan-perbandingannya, ya, memang ini suatu teater yang baru bagi mereka, di Jepang termasuk di Jerman, termasuk di Hongkong, di Taiwan, di Mesir. Apalagi di Mesir, di Mesir itu kami festival diikuti oleh 43 negara. Dan kebetulan kami main, dan mereka sangat aneh, kok ada teater seperti ini, gitu lho. Begitu kami main, itu orang-orang Mesir, waktu itu kami memainkan War,a, Perang. Begitu kami main itu penontonnya mengerti apa yang kami mainkan. Gerak dan musik itu. Sampai itu, siapa, keamanannya, panitianya, katanya sangat luar biasa sekali, dan mereka menangis, katanya. Mereka mengerti apa yang disampaikan oleh teater Mandiri tentang ketidak-adilan, tentang, tentang HAM perempuan, tentang apa, semua yang kita sampaikan sangat komunikasi sekali dengan penonton, gitu, walau pun itu dengan gerakan dan musik dan siluet. Jadi teater Mandiri di luar itu, suatu hal yang baru bagi Negara-negara lain dan belum ada seperti itu, gitu lho.
Saya ikut Teater Mandiri dari tahun tujuh puluh lapan sampai sekarang hampir 32 tahunlah. Jadi, selama saya di Mandiri itu sangat, saya sangat, kadang-kadang saya menangis. Kenapa Tuhan begitu baik memberikan saya masuk ke Teater Mandiri. karena di situ saya banyak mendapatkan pelajaran spiritual yang sangat luar biasa sekali. Yang tidak saya dapatkan di teater lain atau dikehidupan yang lain. itu yang saya dapatkan di teater Mandiri.
Putu Wijaya di Mata Yanto Kribo :
Kalau pola latihan Teater Mandiri itu, ya, memang prinsipnya adalah bertolak dari apa yang ada. Apa yang ada pada tubuh kita, apa yang ada pada lingkungan kita, apa yang ada di batin kita. Jadi bertolak dari apa yang ada. Dan prosesnya itu, pencarian. Terutama sekarang ini kita Teater Mandiri itu sudah bergerak kepada, seperti Teater Seni Rupa. Bukan lagi teater-teater yang dikenal seperti konvensional atau modern lainnya, tapi kita sudah melanglang kepada penemuan baru, yaitu Teater Seni Rupa. Jadi prosesnya adalah pencarian , pencarian bentuk, di mana kita membuat bentuk yang sesuai apa pada diri kita, apa yang ada pada naluri kita, tinggal sang sutradara mengedit.
Putu Wijaya, terus terang saja, dia orangnya disiplin, ya? Dia royal terhadap ilmu. Jadi siapa pun yang ingin berguru atau bertanya kepada beliau, dia akan buka selebar-lebarnya apa yang ada di kepalanya dia. Apa yang ada dibenaknya dia. Asal orang itu serius. Kalau dia tidak, atau orang yang berguru tidak serius dia paling sebel, dia paling benci hal-hal seperti itu. Karena dia orangnya penuh dengan disiplin dan bekerja keras.
Yang saya dapat dari teater Mandiri itu adalah kebebasan berpikir. Di mana kita, kalau kita menderita suatu tekanan, gitu, ya, kita cepat mengambil alih tekanan-tekanan itu menjadi buyar, menjadi lepas. Dan tidak terkungkung oleh pemikiran-pemikiran yang menteror kita. Karena itu, jadi, cepat sekali kita melakukan perubahan-perubahan di dalam hidup ini, di mana kita kalau tertekan kita harus cepat-cepat merubahnya. Karena, itulah dalam proses latihan itu selalu ada yang tidak kita rasakan secara langsung, tapi kemudian hari kita akan merasakan langsung, begitu.
Dia orangnya pemarah, kenapa dia, saya bilang dia orangnya pemarah? Karena dia orangnya disiplin, makanya dia pekerja keras, karena disiplin, pekerja keras itu harus tetap menjaga barisan. Dia kalau melihat satu hal yang melenceng, apa yang dia lihat, dia akan timbul marah. Tapi kemudiannya dia akan guyup kembali. Jadi marah dia itu tidak akan terbawa sampai ke mana-mana, gitu.
*Jose Rizal Manua, anggota Teater Mandiri, Teaterawan dan Penyair.