Putu Wijaya: Sastra di Antara Nasionalisme Kita

Oleh Panji Gozali
Wawancara berlangsung di Kediaman Putu Wijaya (Astya Puri II/A09, Jl. Kertamukti, Cirendeu, Tangerang Selatan) pada hari Kamis, 31 Januari 2019, pukul 11.06 s/d 12.30 WIB. Wawancara oleh Panji Gozali ini mengulas tentang biografi, pemikiran dan pandangan kebangsaan Putu Wijaya.
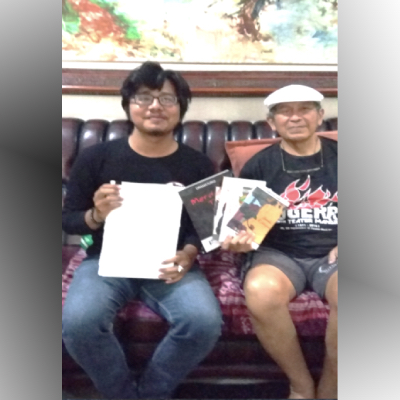
Panji Gozali dan Putu Wijaya paskah wawancara di kediaman Putu Wijaya. (Foto: Dokumentasi Milik Panji Gozali)
Dari membaca Achmad Fedyani Saifuddin (Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia—UI), ada tiga pilar yang membentuk rasa nasionalisme di Indonesia. Satu adalah kesadaran kolektif identitas, yang kedua adalah kesadaran kolektif historis dan yang ketiga adalah gerakan sosial bersama dalam melawan ancaman dari luar.
Saya mencoba menemukan tiga pilar itu dalam cerita-cerita pendek pak Putu dan itu setelah saya baca di buku-buku seperti; Tidak, Blok, Jreng, Kroco, Yel, Es, Protes, Bom dan Gres. Tapi dari semua buku itu bila saya kaji yang lebih masuk—pada tiga pilar yang membentuk rasa nasionalisme—ada di cerpen berjudul “Indonesia” dalam buku Blok.
Sebagai sebuah awalan, ada beberapa pertanyaan klarifikasi awal, jadi ini belum masuk ke pertanyaan intinya. Untuk pertanyaan pertama, apakah betul ayah pak Putu seorang punggawa?
Ya, bekas punggawa. Jadi saya tidak tahu apa jabatan punggawa itu, sekarang apa ya? Sekarang tidak tahu kita apa punggawa itu, punggawa itu bukan wali kota apa ya? Semacam itulah, yang menata kota zaman dahulu. Dia dulu bekas punggawa, kemudian digantikan oleh anaknya, kakak tiri saya itu. Pegawai pemerintah dulu. Cuma punggawa itu dalam Bahasa Indonesia sekarang saya tidak tahu. Harus dicari saja punggawa itu apa. Itu yang menata kota. Kalau di Bali itu jabatan pemerintah, ya tidak ada hubungannya dengan kasta. Punggawa itu jabatan pemerintah, jadi pegawai negeri itulah. Zaman sekarang pegawai negeri, zaman dulu tidak tahu saya apa, tapi kalau di Bali itu ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, kalau kasta saya Ksatria, jadi makanya pakai nama I Gusti Ngurah Raka, itu nama ayah saya. Kalau saya, I Gusti Ngurah Putu Wijaya. I Gusti itu kasta kalau di Bali. Seperti juga Ngurah Rai, kan I Gusti Ngurah Rai yang nama bandara di Bali, itu kasta Ksatria, kasta Ksatria itu adalah orang pemerintahan. Kalau Brahmana itu orang yang mengurus agama. Waisya, orang yang berdagang. Sudra itu rakyat kebanyakan.
Oke. Kemudian, waktu pada masa Orde Baru, apa pernah pementasan pak Putu diberedel?
Belum, belum pernah. Jadi selama perjalanan saya dalam kesenian, saya tidak pernah berhubungan dengan sensor pemerintah. Karna saya, satu hal yang sangat saya pikirkan adalah bagaimana caranya agar tidak menyinggung apa yang tidak boleh, tanpa mengurangi maksudnya gitu. Jadi di semua massa, saya pelajari apa yang tidak boleh, kalau itu bertentangan, kalau ada yang tidak boleh tapi bertentangan dengan maksud saya, maksud saya itu saya carikan jalan. Maksudnya tetap pada tujuan, tetapi caranya mengatakan itu berbeda sehingga bisa lolos sensor.
Karna saya mempelajari hukum, jadi saya tidak ingin melanggar hukum. Saya lebih senang menyiasati hukum, mengelak atau menipu hukum. Sehingga maksudnya tercapai tapi tidak perlu melanggar. Nah itu yang saya lakukan. Jadi dalam seluruh disiplin saya, dalam bekerja apa pun sampai pada tahun 1991 saya ikut dalam KIAS, membawa sebuah pertunjukan namanya Yel di sebuah tempat seorang profesor yang bisa berbahasa Indonesia bertanya, “Apakah anda sudah diizinkan oleh negara?” Saya bilang, “Ini misi negara. Saya mewakili Teater Indonesia ke KIAS.” KIAS itu pameran Indonesia setahun penuh di Amerika, saya keliling di beberapa kota. “Kenapa anda menanyakan begitu? Saya ini dibiayai oleh pemerintah,” kata saya. “Oh anda mestinya dilarang,” katanya sambil tertawa. Kenapa? Ini keras sekali gitu. Tapi di Indonesia orang tidak mengerti apa yang saya katakan. Malah orang luar justru merasakan seperti itu, tapi itu interpretasi, jadi boleh saja ya. Seperti misalnya kata YA dan kata ya dan TIDAK YA kalau di Indonesia, orang Jawa misalnya, kamu orang mana?
Saya Jawa.
Jawa kalau misalnya kamu ya-ya-ya kadang-kadang artinya bukan iya kan? Ya bahwa kamu sudah mendengar, mungkin maksudnya tidak. “Eh kamu sudah makan? Eh kamu datang nda besok?” Ya. Padahal dia tidak datang. Kalau buat orang barat ini kacau, tapi buat orang Indonesia ini biasa. Karna kata itu mendua, tergantung daripada situasinya, ya itu maksudnya saya sudah mendengar pertanyaan kamu dan saya bilang ya tapi mungkin besok saya berhalangan dan tidak bisa datang. Tapi tidak ada penjelasan seperti itu, jadi di Indonesia ambigu. Kata-kata kita ambigu. Nah ambigu ini penting sekali untuk kita berhadapan dengan penguasa, dengan sensor yang membuat mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mencegah kita. Itu yang saya lakukan.
Kemudian saya sempat nonton sinetron None yang Nike Ardila perankan. Kemudian waktu itu di buku yang saya baca pak Putu pernah mendirikan Putu Wijaya Mandiri Production. Tapi di buku yang saya baca itu tahunnya tidak dicantumkan pak. Itu kira-kira tahun berapa ya pak?
Saya mulai bikin sinetron sepulang dari tahun 1974 (International Writing Program di Iowa, Amerika Serikat). Saya mulai bikin sinetron itu mungkin tahun 1975. Itu syutingnya sinetron None bukan produksi saya. Saya hanya jadi sutradara dan penulisnya, kemudian saya bekerja dengan sebuah production house setelah bikin None, kemudian saya berniat untuk bikin produksi sendiri. Ya produksi itu harus membuat production house dan itu judulnya yang pertama adalah Intrik. Intrik itu produksi saya, naskah saya, sutradara saya, produksi Putu Wijaya Mandiri Production (1995), artinya uangnya dari kita. Kalau yang None itu uangnya dari production house, saya hanya sutradara.
Kemudian berakhirnya itu tahun berapa ya pak?
Oh ada dua yang kita buat, Intrik sama Warteg (Warung Tegal) tapi setelah itu di televisi-televisi kita bikin production house sendiri. Lebih senang begitu, production house dari luar dikurangi, jadi mereka bikin sendiri in house, istilah mereka in house misalnya seperti RCTI, SCTV bikin in house production sendiri di dalamnya. Kalau tidak keluar dia sudah potongin segala macam jadi kita kehilangan ini, kehilangan hubungan, sedangkan pajak terus jadi kalau kita bikin production house. Bayar hukum, terus bayar pajak, akhirnya saya bekukan karna lebih baik saya bekerja di production house yang lain. Pilih punya orang gitu. Jadi tahun 1997, punya kita tidak berproduksi lagi. Saya ikut production house lain akhirnya kira-kira tahun 2000-an, karna itu bahaya sekali untuk pajak, saya bekukan. 2000-an saya lupa berapa, setelah saya kemari. Saya pindah kemari tahun 1998, setelah beberapa tahun di sini saya bekukan. Mungkin tahun sekitar 2000-an lah. Artinya dibekukan. Dibekukan itu tidak berproduksi, berarti tidak wajib pajak gitu. Kalau dihidupkan lagi, bisa saja.
Betulkah teror mental itu awalnya sejak pak Putu merasa terteror oleh salah seorang Yakuza di Jepang, waktu tinggal bersama masyarakat Ittoen?
Bukan. Kalau teror itu artinya kita secara batin dikena kepotlah. Kena dikecewakan, kena sindir atau apa pokoknya, ada sesuatu yang membuat kita jadi aware kepada sesuatu. Sesuatu yang sangat mempengaruhi kita, sesuatu yang dahsyat. Macam-macam, itu bisa terjadi kapan saja. Teror mental itu mulai saya rumuskan tahun 1980. Ya sekitar 1980. Waktu itu saya jadi Ketua Komite Teater di Dewan Kesenian Jakarta, ya pada waktu itu Ketua Dewannya antara lain ibu Toeti Heraty, Doktor Profesor. Waktu itu dewan membuat sebuah buku yang isinya adalah konsep-konsep penulisan. Beberapa orang diminta. Rendra, segala macam, diminta untuk menulis konsepnya. Saya juga diminta untuk menulis konsep. Saya menulis dua konsep, konsep tentang teater itu saya beri label “Bertolak dari yang Ada: Jalan Pikiran Teater Mandiri” sampai sekarang masih ada. Tetapi untuk cerpen saya beri label “Teror Mental” karna cerita-cerita saya tidak bermaksud untuk menghibur orang, tidak bermaksud juga untuk memotret peristiwa tapi saya berusaha untuk menggugah orang, mengejutkan orang dengan cerita itu agar dia bimbang, bimbang maksudnya terkejut ya. Nah, ketika dia terkejut, dia mulai berpikir sekali lagi, memikirkan apa yang sudah terjadi, memikirkan apa yang dia lihat, memikirkan kesimpulan dia dan akhirnya memutuskan sesuatunya. Keterkejutan itu saya perlukan untuk membuat mereka berpikir sekali lagi, ini cerita saya mengganggu, misinya mengganggu.
Cerita saya meneror, mengganggu orang, bukan untuk mencelakakan dia. Untuk membuat bimbang sehingga dia berpikir sekali lagi terhadap keputusan-keputusannya. Karna itu ceritanya kadang-kadang tidak menyenangkan. Kadang-kadang membuat orang jadi tidak nyaman, tapi sebetulnya buat orang yang suka berpikir, ini peluang untuk mengingatkan dia kepada sesuatu yang harus dia pikirkan kembali. Jadi teror dalam cara penulisannya maupun akhirnya. Akhirnya banyak yang menggantung, mengambang karna saya ingin pembacanya itu ikut serta mencipta. Buat orang yang biasa disuguhi sesuatu dan ingin menelan saja tidak akan suka. Dia akan marah membacanya, “Lah ini apa? Kok digantung?” Digantung maksudnya supaya dia ikut mengalami dan membukanya.
Saya tidak mulai dengan intro misalnya, pagi apa suasana tapi langsung “Tiba-tiba orang itu memotong leher saya,” misalnya seperti itu. Jadi langsung kepada persoalannya, nanti diterangkan belakangan atau tidak pernah diterangkan. Kenapa? Karna orang sudah bisa menyimpulkan itu. Bahasanya juga agak berbeda, bukan bahasa lumrah. Misalnya, “Aku melemparkan mataku ke luar.” Maksudnya aku melihat ke luar. Itu kan kalau orang biasa, “Mata kok dilempar?” Dicoba untuk dibikin baru gitu. Orang berpikir, tapi ini apa namanya, simbol bahasa isyarat, bahasa imajinasi. Jadi temanya teror, cara penulisannya teror, bahasanya juga teror, penyelesaiannya juga teror. Seperti itu, tapi tidak maksudnya untuk merusak. Teror justru untuk membangun tapi ya resikonya adalah belum tentu orang senang, tidak menghibur ada juga yang menghibur, yang biasa membaca terhibur, yang tidak terbiasa mungkin tidak mau lagi membaca tulisan saya. Karna itu buku-buku saya seperti Blok yang kamu baca itukan, dicetakkan sekali. Tidak pernah dicetak lagi, malah penerbitnya mati sudah.
Seperti Pabrik itu juga ya pak?
Iya, Pabrik. Pustaka Jaya yang menerbitkan, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tidak pernah diterbitkan lagi. Akhirnya, lama-lama saya cabut. Telegram juga begitu, Stasiun. Semua yang di Pustaka Jaya tidak pernah diterbitkan lagi saya cabut, saya kirim ke Kompas. Ada beberapa yang dimuat, diterbitkan misalnya Pabrik. Stasiun juga ada penerbit yang menerbitkan tapi tidak ada kabarnya, akhirnya saya cabut setelah hampir lima tahun kemudian. Basabasi Jogja itu mau lagi kencang menerbitkan. Yel terbit lagi. Stasiun terbit lagi. Telegram terbit lagi. Pabrik mau terbit lagi. Nyali mungkin akan terbit lagi, seperti itu.
Saya merumuskan ada beberapa pertanyaan inti. Pertama, bisa tolong diceritakan pak, waktu pengalaman di ASRI dan Asdrafi? Secara singkat saja.
Saya suka kepada drama, saya juga suka melukis. Waktu kecil saya ingin jadi pelukis dan main drama, itu memang dari kecil senang tontonan, tapi kemudian saya bandingkan diri saya dengan yang lain-lain. Misalnya melukis, itu ada orang pintar bilang, “Kita itu berpijak di atas punggung orang-orang besar, jadi kalau kamu tidak lebih besar dari mereka, tidak akan eksis.” Pelukis ini banyak sekali. Di Indonesia saja untuk melewati Affandi sulit sekali, belum lagi di luar. Jadi ketika saya masuk Asdrafi, saya juga mulai masuk Fakultas Hukum karna saya suka hukum, karna saya juga ingin menyenangkan hati orangtua saya. Karna pada waktu saya kecil orangtua itu tidak ingin kalau anaknya bukan dokter, insinyur, ya meester in de rechten. Tapi kemudian begitu masuk Fakultas Hukum, meester in de rechten diganti gelarnya jadi SH. Saya kecewa sekali, tapi ya apa boleh buat, sudah masuk ke sana.
Kemudian kalau zaman dulu itu kuliahnya tidak seperti mahasiswa sekarang, tiap hari kuliah. Kadang iya, kadang tidak. Gampang sekali. Juga waktunya tidak terbatas, ada orang berpuluh-puluh tahun tidak lulus-lulus jadi tidak ada DO (Drop Out), jadi santai sekali. Karna santai itu saya gerah. Saya masuk Asdrafi masih banyak waktu. Saya masuk ASRI juga masih bisa bagi waktu. Kemudian di ASRI pada tahun pertama itu saya sudah mau melukis, tapi diajari ABC-nya banyak sekali, jadi saya pikir sudah tidak cocok gitu. Satu tahun dari sana saya berhenti. Kemudian tidak lama dari situ di Asdrafi saya kuliah, tapi itu ilmunya kuno sekali. Misalnya ilmu jiwa. Saya mengharapkan akan mendapatkan froint itu segala macam tapi yang diajarkan adalah pelajaran kebatinan, luamah segala macam itu, saya sudah tanyakan kepada gurunya, gurunya marah. Kalau pelajaran filmnya, pelajaran aktingnya oke, tapi banyak pelajaran yang sudah kuno karna memang pendirinya orang lama itu. Nah akhirnya saya selesaikan sampai kelas tiga terakhir, tapi saya tidak ikut ujian, saya selesaikan hukum.
Oh, waktu di Asdrafi gagal di penulisan skripsinya?
Tidak, saya tidak ikut. Saya ikut ujiannya tapi dulu tidak pakai skripsi. Karna akademinya tidak begitu teratur maksudnya, tidak tahu kalau sekarang ya. Jadi saya tidak teruskan, saya lebih kepada hukum saja. Karna saya pikir drama saya bisa pelajari sendiri, kalau seni rupa bisa saya pelajari sendiri.
Berarti yang Asdrafi tidak diteruskan, kalau yang ASRI juga tidak?
ASRI tidak diteruskan, Asdrafi selesaikan pelajarannya tapi tidak ikut ujian. Ujian teorinya sudah, tapi tidak saya selesaikan karna saya merasa tidak berguna gitu.
Kalau saya lihat di salah satu rekaman wawancara acara televisi, apa betul bapak merasa dongkol ketika, misalnya waktu di ASRI itu disuruh melukis dengan warna A, tapi pak Putu menolak?
Nah begini, itu juga mau saya jelaskan. Di tingkat satu memang akademi itu belajar dari awal ya, saya sudah ingin jadi pelukis, jadi untuk menggambar misalnya gambar bentuk harus persis atau apa harus pakai areng segala macam. Nah, sekarang komposisi membuat pemandangan saya warna hijau seperti lukisan ini (menunjuk lukisan di salah satu dinding rumahnya). Ini warna pohon, warna macam-macam semua itu yang saya mau, tapi gurunya bilang, “Tidak bisa begini, warna hijau itu bermacam-macam nuansanya. Tidak seenaknya gitu.” Jadi patokannya realis, saya merasa tersiksa di situ. Saya tidak mau melukis apa yang mau dia lukis. Saya mau melukis apa yang mau saya lukis gitu loh. Saya tidak melukis pohon, ini pohon apa saya tidak tahu, tapi saya ingin pohonnya seperti ini. Apa salahnya kalau pohon itu berdaun warna, pohon apa saya tidak tahu karna saya tidak melukis pohon apa gitu loh. Seperti itu, itu bertentangan dengan akademi yang memberikan basic kita. Yasudah kalau sudah begitu, tapi memang saya tidak akan mampu untuk menjadi akademis dalam melukis.
Bagi pak Putu, apa itu sastra?
Sastra itu adalah alat untuk berekspresi dengan bahasa sebagai basisnya. Kalau kita lihat di buku-buku pelajaran, sastra itu tulisan. Susastra tulisan yang indah. Tapi secara letter itu sudah bukan tulisan yang indah, tidak semuanya indah dan tidak semuanya ditulis. Bagaimana kita menamakan sastra lisan? Itu bukan sastra karna itu bukan tulisan? Jadi buat saya sastra itu alat, media untuk berekspresi dengan bahasa sebagai basisnya. Itu yang di definisi saya.
Loh bagaimana dengan bahasa tubuh? Itu bahasa juga. Jadi bahasa itu bukan hanya oral ya, bukan hanya vokal, tubuh pun memiliki bahasa. Peristiwa ada di bahasa isyarat, ada bahasa tubuh, ada bahasa imajinasi, ada bahasa rahasia dan bahasa pun macam-macam. Ada bahasa resmi, ada bahasa prokem, ada bahasa hukum, ada bahasa dagang, macam-macam sekali. Jadi kalau saya bilang bahasa sesuai basisnya masih belum salah, semuanya masih kena, bukan tulisan. Kalau tulisan, di bahasa lisan sudah hancur habis. Bahasa tubuh hancur, jadi karna itu kalau orang bilang sastra itu ada dalam peristiwa, iya. Dalam suatu peristiwa ada aspek sastranya, ada. Misalnya, usaha untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan, aspek sastranya ada karna ada intrik-intriknya, ada dramatiknya segala macam, ada persiapan-persiapannya, ada adegan tindakan-tindakannya, kemudian ada benturan-benturannya, ada konflik-konfliknya di dalam. Jadi, pengertian sastra sudah keluar dari pengertian yang baku kalau di saya. Karna perbuatan pun seperti berbau sastra, kalau kita bilang berbau sastra tidak me-refer kepada tulisan, tapi bahwa di situ ada plotnya, ada perencanaannya, ada keindahannya, ada konfliknya, seperti itu loh. Jadi saya membuat arti sastra itu melebar. Jadi lebih luas, lebih leluasa karna saya memukul ratanya dengan semau saya, tidak harus menulis untuk menjadi sastrawan, tidak harus bikin plot saja, bergerak pun sudah sastra. Ini bahasa tubuh, bahasa peristiwa.
Berarti bagi pak Putu, seseorang dikatakan sastrawan apabila dia?
Apabila dia memakai, berekspresi dengan bahasa sebagai basisnya. Berekspresi!
Termasuk bahasa tubuh?
Semua, semua bahasa. Lalu mungkin pertanyaannya, apakah seorang sejarawan itu seorang sastrawan? Tidak, karna dia tidak berekspresi. Jadi ada dua gen yang sangat penting, bahasa sebagai basisnya dan berekspresi. Jadi sastra adalah ekspresi, kalau tidak berekspresi bukan sastra. Surat apa? Surat iya. Surat-surat Kartini itu sastra karna dia berekspresi. Esai? Iya. Pendapat? Iya. Lamaran? Iya. Cuma ada yang bagus, ada yang tidak, kan begitu ya.
Kemudian, fungsi dari sastra itu sendiri bagi pak Putu itu apa?
Fungsi dari sastra itu kalau kita terima bahwa sastra adalah ekspresi dengan bahasa sebagai basisnya, lalu fungsi ekspresi itu apa? Ekspresi itu antara lain untuk berkomunikasi, untuk memberitahukan, untuk memancing komunikasi, untuk jalan mengutarakan pikiran, menyampaikan pikiran, untuk melawan juga, segala macam. Kalau ekspresi itu ada dan bahasa sebagai basisnya, dalam bahasa pengertian bukan hanya oral, maka bisa untuk apa saja, bisa untuk pendidikan. Ya, segala macam jadinya bisa apa saja, multifungsi.
Menurut pandangan pak Putu terhadap dunia sastra di Indonesia seperti apa ya pak?
Nah, kalau sastra diberikan arti sempit seperti itu maka manfaatnya pun jadi sempit, tapi kalau diberikan definisi seperti yang saya berikan tadi itu sangat luas, sangat memungkinkan apa saja. Tadi apa pertanyaannya?
Pandangan terhadap dunia sastra di Indonesia?
Oh yang tadi? Penghargaan kepada sastra itu sangat kurang, karna sastra dihubungkan dengan kelanganan kesenian, jadi sikap umumnya yang formal bukan sikap mendasar dari orang Indonesia, bukan dibedakan dengan sikap tradisi. Sikap tradisi kepada sastra itu sangat tinggi karna buat dia sastra itu ilmu pengetahuan. Tapi, sikap formal orang Indonesia sekarang terhadap sastra itu hiburan, kelanganan, ya jadi bukan cuma sastra, kesenian itu dianggap sebagai kelanganan, hiburan. Jadi, kalau orang ingin menghibur diri ya bersering-sering dia membaca sastra, itu sebabnya kemudian sastra itu dituntut menyenangkan, membahagiakan, dia tidak dipelajari. Kecuali dia menjadi sebuah fenomena, misalnya pemberontakan berbasis sastra.
Pada suatu ketika ada pertemuan antara Sastrawan Perancis dan Sastrawan Indonesia di Bentara Budaya. Orang Perancis ini mengatakan, “Saya agak risih, kenapa? Karna di Indonesia penghargaan kepada sastra berbeda dengan Perancis. Di Perancis sastra itu ilmu pengetahuan.” Jadi ilmu dipelajari karna bukunya juga banyak sekali. Sejarah juga begitu. Dulu sejarah kita anggap adalah hal-hal tertulis tapi kemudian ilmu sejarah berkembang. Surat-surat, sastra pun bagian dari sejarah karna itu menunjukkan dokumentasi dari beberapa peristiwa. Jadi sekarang ini ilmu sejarah yang baru. Itu begitu, tidak hanya kepada prasasti-prasasti itu yang dianggap sejarah. Tapi, sastra pun dianggap bagian dari sejarah karna itu ekspresi manusianya.
Di Cornell, Belanda, di luar negeri saya ketemu sama orang-orang ahli sejarah yang memulai sebuah uraiannya dengan cerita pendek, dimulai dengan sebuah cerita pendek. Seperti misalnya, Ben Anderson. Ben Anderson itu Guru Besar di Cornell, sudah meninggal kemarin, di Batu meninggalnya, karna dia orang yang cinta Indonesia tapi tidak boleh tinggal di Indonesia waktu zaman Soeharto, kemudian datang lagi. Dia adalah orang yang pertama mengapresiasi buku saya yang namanya Nyali, itu terbitan Balai Pustaka. Saya waktu itu ada di Jogja, saya mendengar ceritanya, cerita orang bahwa Ben datang lagi ke Indonesia dan berceramah di UI. Dia mengatakan bahwa buku Nyali itu adalah karya sastra terbaik sesudah Pas yang menggambarkan peristiwa G-30-S. Saya ngikutin selama dia di UGM pada waktu itu, diulangi lagi jadi saya mendengar sendiri. Sementara, buku Nyali itu kalau di review, saya baru sekali membaca review-nya dan itu disamakan dengan cerita-cerita silat.
Kho Ping Hoo?
Ya semacam itu. Jadi versi pukul-pukulan, banyak berantemnya, banyak darahnya. Itu kalau kamu baca Nyali, itu berdarah-darah sekali. Meskipun maksud saya bukan itu, tapi sampainya kepada pembaca Indonesia ini adalah rekaman dari peristiwa itu jadinya saya ingin mengatakan kepada kamu, bahwa seorang ahli sejarah tertarik kepada sastra karna kaitannya dengan sejarah. Nah, saya menjawab pertanyaan kamu sekarang bahwa di Indonesia penghargaan kepada sastra itu kurang, masih dianggap sebagai hiburan.
Waktu saya SMA, sastra itu dipelajari di seluruh jurusan. Dulu jurusan A Sastra, B Pasti, C Sosial, semuanya mempelajari sastra, ada pelajaran sastra. Dulu ujian itu ada dua tingkat di kelas dua ujian separuhnya, di kelas tiga ujian, sastra diuji juga. Pelajaran mengarang juga ada dulu. Sekarang tidak ada karna dianggap mengarang itu membuat-buat sesuatu, mengkhayal. Itu salah sekali. Mengarang itu usaha untuk mencoba melatih berpikir secara sistematis agar dimengerti oleh orang. Anak kecil diajar mengarang bukan mengkhayal. Tapi merumuskan pikirannya. Orang-orang politik yang pintar-pintar, mengarangnya nol jadi waktu dia ngomong itu kacau, tidak mampu dia menceritakan apa yang dia maksudkan. Jadi seperti kamu datang kemari ingin mendengarkan sesuatu, kamu akan mengarang dulu apa yang mau kamu tanyakan supaya efektif.
Jadi, kembali kepada penghargaan kurang. Salah tembak gitu loh dan itu memperbaikinya susah sekali. Karna perhatian orang hanya kepada politik dagang saja sekarang di Indonesia ini. Ketika Reformasi sudah selesai, muncul pertanyaan, “Apa yang harus dilakukan?” Jawabannya hanya dua. Stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, stabilitas budaya tidak ada. Padahal kalau kita lihat, ujung-ujung dari korupsi misalnya yang tidak habis-habisnya, itu budaya. Orang anggap itu kiat yang mampu untuk menggandakan uangnya tanpa bekerja, enak-enakan saja mengambil, itu dianggap sebagai kiat dan kiat dibenarkan oleh perdagangan sekarang. Dulu menipu orang dengan menganggap barang jelek itu bagus adalah penipuan, sekarang sudah sah. Dulu iklan-iklan yang mengejek barang lain tidak boleh, rokok satu mengejek rokok lain dia tidak boleh, sekarang kayanya boleh, jadi sudah dilanggar, sudah jadi kiat sekarang. Bagaimana mencapai tujuan asal tercapai dengan menaikkan produksi tanpa peduli jalannya, mungkin seperti itu sekarang.
Jadi seperti kiat, kalau kita ikuti kiat-kiat ekonomi di beberapa tempat, di hotel-hotel itu pelajaran penipuan. Belajar menipu orang, lihatlah semua iklan sekarang, hampir semuanya menipu. Dia mengiklankan sebuah real estate hanya lima menit dari Monas. Lima menit apa? Lima menit kamu keluar dari komplek ini saja belum tentu lima menit, mesti ngomong sama satpam segala macam, belum jalanan. Saya dari sini pergi ke TIM (Taman Ismail Marzuki) bisa sama dengan saya pergi ke Bandung loh, tiga jam bisa begitu. Jadi dia enak saja lima menit dari Monas, gampang sekali, penipuan semua. Nah, sebetulnya kita hidup itu terapinya adalah melalui sastra. Ekspresi dengan bahasa sebagai basisnya. Itu sudah tidak ada upaya untuk ke arah situ sampai sekarang, jadi posisinya rentan dan kekuatannya pun menjadi tumpul, tidak ada kekuatannya.
Dengan Kongres Kebudayaan kemarin pak?
Oh, Kongres Kebudayaan. Sebentar lagi Kongres Kebudayaan ke berapa? Sudah sekian puluh Kongres Kebudayaan. Saya ikut dalam dua Steering Committee Kongres Kebudayaan sebelumnya, tahun 2003 dan tahun 2008. Apa yang terjadi? Rekomendasi dan Kongres Kebudayaan itu yang entah berapa biayanya diikuti oleh semua orang-orang pintar dari seluruh Indonesia, rekomendasinya itu hanya menjadi dokumentasi. Tidak pernah terealisasi karna rekomendasinya saja harus disampaikan kepada presiden, pemerintah, pemerintah menyampaikannya kepada DPR, DPR harusnya membuat sebagai bahan untuk membuat peraturan.
Antara lain yang kami usulkan dalam Kongres Kebudayaan 2003 misalnya reinterpretasi terhadap kearifan lokal, reposisi dan revitalisasinya kearifan lokal. Seluruh Indonesia ini kearifan lokalnya luar biasa dan sangat-sangat berguna kalau direinterpretasi. Setelah direinterpretasi disesuaikan dengan keadaan sekarang, direposisi-reposisi dan diberikan kekuatan hukum, harusnya begitu. Tapi, dua Kongres Kebudayaan itu berhenti jadi dokumentasi saja, dokumentasi bahwa pernah dilakukan Kongres Kebudayaan. Sekarang saya tidak tahu, mudah-mudahan ada gunanya nanti. Ya mudah-mudahan ya. Karna kita tidak boleh begini terus-menerus.
Tentang pengertian cerpen itu sendiri pak. Menurut pak Putu sendiri sebagai orang yang sudah banyak sekali menulis karya cerpen, apa pengertian cerpen menurut bapak?
Iya, semua definisi-definisi itu adalah upaya untuk menjelaskan cerpen yang sudah ada ya. Jadi dari cerpen yang sudah ada dirumuskan untuk pegangan, ke depannya dia tidak bisa, tidak diketahui dan kalau dilakukan itu hanya meramalkan, apalagi kalau yang meramalkan itu adalah bukan pelakunya itu sulit sekali. Cerpen itu tidak bisa dibatasi—jumlah katanya—karna dia berkembang terus, cuma barangkali bisa dibandingkan, yang membedakan cerpen dengan novel dan kemudian dulu ada istilahnya roman.
Roman kemudian sudah diganti jadi novel, di bawah novel ada yang namanya novelet yang lebih kecil. Kalau semua definisi itu mungkin ada benarnya tapi tidak perlu dijadikan satu patokan, apalagi dibatasi dengan sepuluh ribu kata, dua belas ribu kata. Itu mungkin persyaratan dari sebuah penerbit atau publisher untuk mengumumkan kepada orang yang mau menyumbangkan karya, jadi tahu batasnya. Seperti misalnya ada majalah baru, kemarin. Majalah sastra, “Berapa panjangnya?” saya tanyakan begitu. Oh dia bilang, “Ya maksimal dua belas ribu kata.” Ada yang bilang, “Tolong lima belas ribu kata.” Misalnya kalau tulis di koran berapa? Maksimal dua ribu lima ratus kata atau tiga lembar komputer, itu batasan untuk media yang ingin menampungnya.

Panji Gozali dan Putu Wijaya paskah peluncuran buku “Seribu Cermin” di Galery Indonesia Kaya, 19 September 2018. (Foto: Dokumentasi Milik Panji Gozali)
Ada cerita pendek yang panjang sekali. Jadi dia tulis lebih banyak pengalaman-pengalaman. Ada juga cerita pendek yang sangat pendek, ada yang panjang sekali. Saya berikan contoh ke puisi ya. Sitor Situmorang pernah menulis sebuah puisi namanya Malam Lebaran, hanya satu baris. “Malam lebaran. Bulan di atas kuburan,” itu saja. Itu menjadi terkenal karna menjadi contoh sebuah puisi satu baris. Nah cerpen bisa. Saya sekarang bikin cerpen-cerpen mini yang saya sebut cermin, cerita pendek mini. Pendek-pendek sekali. Kadang-kadang hanya satu alinea, tapi saya juga bisa bikin cerpen yang sangat panjang. Ya cuma yang bisa membedakan cerpen dengan novel adalah, bahwa cerpen beberapa saat yang penting dalam hidup seseorang.
Beberapa saat yang penting?
Iya beberapa peristiwa. Kalau novel itu bermacam-macam peristiwa dalam hidup seseorang yang kemudian memberikan kita pada kesimpulan tentang sebuah fenomena. Jadi lebih meluas ini. Lebih bukan panjangnya ya tetapi kontennya, lebih kepada kontennya. Kalau panjangnya novel bisa pendek. Misalnya ada ya, novel Indonesia mungkin seratus halaman bisa disebut novel. The Old Man and The Sea itu bukan cerpen, itu novel, tapi benar-benar pendek. Tentang seorang yang ke laut membawa ikan dan ikannya habis. Pendek sekali, tapi novel.
Hemingway?
Hemingway! Jadi isinya yang lebih mendalam mengenai banyak hal. Kalau cerpen mendalam tapi kepada satu peristiwa tertentu saja, tidak bercabang-cabang seperti itu, kalau sudah bercabang-cabang itu sudah mulai. Kalau lebih bercabang-cabang mungkin lebih dekat kepada roman, ada trilogi, tetralogi gitu, seperti itu. Jadi pengertian saya seperti itu ya, saya tidak mengklaim itu, tapi tidak ingin dibatasi oleh definisi-definisi, cuma isinya seperti tadi.
Menurut pak Putu sendiri, definisi dari nasionalisme itu apa?
Saya sebetulnya tidak terlalu terbiasa untuk membuat definisi, karna definisi itu membatasi, saya lebih banyak memberontak kepada batasan-batasan itu. Jadi agak sulit buat saya untuk membuat definisi. Kalau saya terpaksa, definisinya itu agak terbuka buat saya. Kalau nasionalisme itu ada kesadaran untuk merasa dirinya satu bangsa, satu negara. Bukan hanya kesadaran, di samping kesadaran adalah sebuah pengakuan, kesadaran dan pengakuan bahwa merasa dirinya satu bangsa dan satu negara. Kalau Indonesia itu bukan hanya satu bangsa sebetulnya. Etnik kita itu seribu seratus etnik. Ya, majemuk. Bangsa Indonesia itu me-refer bahwa kita adalah India Barat dulu, inilah Indonesia dan orang Batak, orang Bali segala macam itu menjadi orang Indonesia tapi isinya adalah orang Bali, orang Batak.
Kemudian menurut pak Putu, apakah nilai-nilai nasionalisme itu bisa digali melalui karya sastra, khususnya cerpen?
Sangat bisa. Sangat bisa karna seperti saya katakan tadi, banyak sejarawan yang memulai tinjauannya dari sebuah cerpen bahkan dari judul juga bisa. Dipakai sekarang jadi sangat bisa karna itu justru menggambarkan peristiwa nyata sebuah dokumen historis dari seseorang. Ya seseorang itu pasti dia mempunyai akar kemana, apa, dia anggota sebuah komunitas apa, etnis, itu akan sangat bisa menolong. Tapi tidak bisa dijadikan patokan. Jadi referensi iya, bisa membawa kita ke sana tapi bukan identik ya, tidak bisa.
Dalam melihat gejala-gejala fenomena di zaman sekarang ini di Indonesia, apa masyarakat kita dalam memandang nasionalisme itu? Dalam kasatmata?
Saya menilai ada krisis kebangsaan. Semacam angkatan 45’ karna dia secara fisik berjuang untuk memerdekakan dirinya. Jadi isolasi yang diakibatkan adanya agama, akibat adanya perbedaan etnis itu hilang, karna ada musuh bersama. Musuh bersamanya itu kolonial, jadi musuh semua perbedaan itu dilupakan. Karna adanya musuh bersama. Setelah itu hilang, maka keberagaman itu mulai menukik ke dalam dirinya sendiri dan ini dipacu lagi oleh beberapa orang khususnya dari luar negeri yang sebetulnya lebih menyarankan kalau kita, kalau menurut istilahnya Ben Anderson kita seperti kue yang mau dibagi gitu loh.
Sama dengan Timur Tengah ya, Timur Tengah kalau bersatu luar biasa. Power-nya dia mempunyai minyak, tapi kalau sudah dipecah-pecah begitu gampang dikeruk uangnya oleh luar. Jadi karna satu, karna kita sudah kehilangan musuh bersama. Tapi karna itu, setiap saat penguasa atau mereka yang berusaha untuk menyatukan kembali mengadakan usaha musuh bersama. Misalnya seperti tiba-tiba hak cipta batik, hak cipta kita diaku oleh Malaysia. Pada waktu itu kita bersatu lagi. Di depan—rumah—saya ini ada Pom Bensin Malaysia, besar, bagus, tapi tidak laku sama sekali. Tidak ada orang yang mau belanja di situ, akhirnya tutup, rusak. Itu di zaman-zaman ketika batik diaku. Rakyat marah dan semenjak itu membuat semua orang memakai batik. Anak saya memakai batik, saya pun menjadi mulai suka batik dan batik menjadi mahal dan berkembang di Indonesia, karna musuh bersama.
Adanya musuh bersama, jadi ketika musuh bersama hilang, maka ego masing-masing itu muncul dan mulai timbul intrik-intrik. Ditambah dari luar masuk juga segala macam itu paham. Dulu saya ingat kalau tidak salah, tahun akhir 1959, awal tahun 1960 pernah terjadi hari raya yang sama. Idul Fitri dan Hari Nyepi, Hari Raya Hindu satu hari itu kontras. Hari Raya Idul Fitri orang ramai-ramai hari kemenangan. Hari Raya Nyepi orang hening, sepi. Listrik dimatikan, orang naik kendaraan tidak boleh. Tapi, tidak ada masalah. Waktu itu saya masih SMA kelas satu, baru masuk SMA.
Di Singaraja itu?
Iya, itu saya belum pernah lagi mengalami satu hari itu. Terkejut saya pada waktu itu, semuanya aman. Padahal orang Bali kalau lagi Nyepi, ada orang yang menyalakan api dilempari batu, ada orang naik kendaraan dihajar. Pada waktu kedua hari raya itu berjalan tidak ada juga yang membangga-banggakan, biasa saja, jadi berjalan wajar. Jadi damai dalam perbedaan itu tidak muncul karna slogan, tapi memang sudah dihayati dari dulunya.
Kenapa sekarang hal-hal kecil saja jadi masalah, kenapa? Tentu ada yang menyulutnya. Satu, kita seakan-akan kehilangan musuh bersama, padahal tentunya masih ada. Kedua, ada usaha-usaha dari luar mengajak orang kembali pada teritorialnya yang terisolir itu. Jadi, ada kemerosotan dalam pembinaan nasionalisme. Ada sikap tak acuh anak-anak muda sekarang pada sejarah. Tak diajarkan sejarah antara lain Pancasila pemersatu, tidak diajarkan lagi. Nah, sekarang baru mulai mau diajarkan lagi. Yah, jadi kenapa? Karna kita alpa sedikit. Negara kita besar sekali, persoalan kita besar. Kalau peta-peta Indonesia itu ditaruh di atas peta Amerika, sama loh dari ujung timur ke barat besarnya. Laut kita luas, daratan kita juga banyak, banyak sekali, kita lupa bahwa negara kita ini bukan hanya Jakarta saja. Bukan hanya Jawa saja. Kita ini negeri kelima penduduk terbesar di dunia. Orang-orang itu berpikir hanya satu juta, dua juta, lima juta. Kita ini 250 juta yang sebentar lagi bertambah jadi 300 juta, itu membuat mereka bahagia. 300 juta besar sekali kan? Tapi yang saya tahu, yang saya lihat orang-orang itu ingin membagi-bagi kita menjadi dua juta, tiga juta orang saja. Gila, karna adanya krisis nasionalisme. Kurang besar skupnya, kita ini negara besar kecuali kalau kita memang mau bikin negara kecil-kecil saja.
Jadi kita mengalami krisis itu. Itu persoalan besar yang harus kita pelan-pelan benarkan juga kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kecil dan kita tidak punya waktu untuk itu, kenapa? Karna orang lebih senang berpikir untuk memperbaiki kehidupannya. Dulu orang punya sandang pangan sudah cukup. Kebutuhan-kebutuhan sandang, pangan, papan, sekarang lebih lagi. Kamu lihat kebutuhan orang-orang Indonesia sekarang kalau libur musti ke luar negeri. Kalau tidak ya ke tempat wisata, ke Bali, ramai sekarang. Itu menimbulkan hal yang positif bahwa ekonomi kita membaik, masyarakat mobilitasnya jadi lebih tinggi, tapi di tingkatan yang lebih atas lagi ada kesenangan untuk ke luar negeri, untuk pameran kepada kawan-kawannya, “Oh saya ke Jepang dan lain-lain.” Itu buang uang ke sana juga, seperti itu. Kalau kesadaran, banyak orang bilang bahwa di negeri kita ini apa yang tidak ada? Ke Jepang hanya melihat bunga sakura, di Indonesia padahal banyak sekali yang belum dilihat, bunga bangkai. Apa-apa banyak sekali loh. Di Irian, ada taman laut segala. Jadi itu bagian dari krisis kebangsaan.
Pak Putu tadi bilang karna kita kehilangan musuh bersama, kalau saya bilang bahwa kita kadang juga tidak tahu musuh kita siapa. Itu bagaimana pak?
Seakan-akan kita kehilangan musuh. Saya bilang tadi bahwa adanya musuh bersama itu membuat kita satu pikiran. Kita seakan-akan tidak punya musuh bersama sekarang. Seakan-akan dibuat begitu. Karna apa? Karna musuhnya banyak sekali. Ada yang musuhnya agama lain, ada yang musuhnya komunitas lain, ada yang musuhnya korupsi, ada yang musuhnya partai lain dan itu sebab musuh bersamanya tidak ada, padahal ada. Penjajahan pikiran masih ada pada kita hari ini. Barat masih menjajah kita karna apa? Persepsi barat itu lebih diutamakan, tetap. Jadi musuh kita ada sebetulnya, tapi seakan-akan tidak ada, kenapa? Karna pikiran kita terpecah-pecah. Nah itu harus ada orientasi baru lagi. Komunitas harus berusaha mengajaknya, pemerintah harus bisa mengajaknya.
Karna kita seakan-akan kehilangan. Lupa bahwa musuh bersama itu masih ada, tapi kita lupakan karna kita punya musuh sendiri-sendiri. Musuh-musuh komunitas, musuh-musuh agama, skupnya dikecilkan. Kesadaran bernegara itu kurang diprioritaskan. Kesadaran berkomunitas, kesadaran bersuku, itu yang lebih dikemukakan sekarang.
Kemudian kalau seperti yang tadi saya kemukakan di awal mengenai tiga pilar yang membentuk rasa nasionalisme menurut Achmad Fedyani Saifuddin: satu adalah kesadaran kolektif identitas, yang kedua adalah kesadaran kolektif historis dan yang ketiga adalah gerakan sosial bersama dalam melawan ancaman dari luar. Kalau dari ketiga pilar itu, apa kiranya pak Putu sepakat? Atau mungkin ada sedikit pandangan yang berbeda?
Saya setuju. Ketiga-tiganya benar dan itu yang melemah, tapi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Itu ada tiga, jangan dikurangi, kalau dikurangi ya saya katakan kurang. Ketiga-tiganya harus jadi satu. Kesadaran nasional itu pilarnya ada tiga. Saya setuju itu, yang tidak saya setuju adalah ketika itu dipisah-pisah. Karna sebagai contohnya begini, Pancasila ada lima sila, kalau dipisah-pisah aneh. Bukan Pancasila. Kalau Ketuhanan Yang Maha Esa saja tidak cukup, Ketuhanan dan Perikemanusiaan tidak cukup, harus lima-limanya. Itu dasar kita dan ini juga harus tiga-tiganya.
Pernah terjadi waktu Nurcholis Madjid dicalonkan oleh Golkar untuk jadi presiden. Waktu itu beliau masih hidup, ada sebuah rembukan di hotel. Saya lupa nama hotelnya, beberapa ahli politikus, ekonomi, macam-macam berbicara tentang bagaimana caranya untuk menyehatkan keadaan. Semuanya betul, cuma dia sektoral. Orang ekonomi melihatnya dari aspek ekonomi saja, orang politik dari aspek politik saja. Jadinya lucu. Harus semuanya jadi satu, baru dirumuskan. Nah, tiga pilar itu kalau masih dirumuskan menjadi satu bagus sekali. Saya setuju, yang tidak saya setujui dan akan berbahaya kalau itu dilepas—dipisah.
Kemudian yang terakhir. Bisa tolong diceritakan pak, mungkin secara singkat saja tentang teror mental dan bertolak dari yang ada?
Sebelum saya lupa, saya kebetulan sedang merumuskan sesuatu, ya itu ditulis. Saya ngomong, istri saya yang mencatatnya. Mungkin ada gunanya, nanti saya kirim ke kamu, kasih saya email kamu. Pikiran-pikiran saya ada di sana. Itu tentang bertolak dari yang ada dimuat di sana tapi yang ini saya jawab sekarang.
Bertolak dari yang ada itu bukan berarti memakai sesuatu seadanya, tidak. Jadi dasar pikirannya adalah pertama-tama kita harus menerima dulu apa yang ada, kemudian mengoptimalkan itu sesuai dengan apa tujuan kita. Kalau ada yang kurang dengan kreativitas kita, kita olah dia supaya menjadi sesuatu yang dapat menuju ke sasaran meski jalan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini, saya membuat contoh di teater ya.
Saya membuat produksi, pemain saya kira-kira ada dua puluh orang, uang produksinya untuk membuat setting, untuk membayar mereka, untuk latihan, tidak cukup. Lalu apa yang saya lakukan? Uang itu semuanya saya fokuskan kepada honor mereka, saya bagi untuk mereka, karna mereka akan latihan sebulan, jadi mereka harus menyewa untuk transport, juga bisa untuk membantu keluarganya. Lalu untuk kostum bagaimana? Kostum tidak usah kita belikan. Orang lain itu banyak menghabiskan uangnya untuk bikin kostum, untuk bikin setting dan tidak ada untuk pemain. Saya justru pemain yang diperlukan. Untuk kostumnya apa? Saya putar otak, saya lihat di gudang TIM, pada waktu itu spanduk-spanduk bekas, spanduk banyak sekali bertumpuk dan itu saya minta, gratis! Lalu spanduk-spanduk itu saya pakai untuk membalut badan

Panji Gozali dan Putu Wijaya paskah Technical Meeting Monolog Putu Wijaya di kediaman beliau, 6 Agustus 2017. (Foto: Dokumentasi Milik Panji Gozali)
Nah, itu dilakukan semua dan mencipta. Setelah jadi disuruh naik ke panggung, dikasih cahaya, itu fantastis jadinya, mewah sekali. Kreatif dan mewah, tidak masuk akal karna aneh sekali kaya baru gitu loh. Tidak meniru siapa-siapa, jadi original. Original, murah dan fantastis, karna baru. Itu menyengat, meneror orang juga. “Apa ini? Ini pakaian mana?” Tidak ada. Itu bukan masalah. “Ini menarik tidak?” Menarik! Sudah cukup. “Ini bisa mengantar ke cerita tidak?” Bisa! Karna sudah menarik gitu. Nah ini maksud saya apa yang ada. Kita gunakan jadi berharga dan saya tidak memainkan sebuah cerita yang tidak sesuai, artinya tidak penting. Karna bukan itu masalahnya, yang saya inginkan adalah ingin menggambarkan sebuah peristiwa.
Waktu itu saya memainkan Gerr. Tentang seorang suami yang meninggal. Semua keluarga bersedih, mau dikuburkan. Semua orang memberikan orasi di depan keranda itu. Tapi tiba-tiba lelaki itu hidup lagi, ya dia mati suri. Ketika dia hidup lagi semua bingung, seluruh konsep yang sudah ada di kepala mereka jadi rusak. Hartanya sudah dibagi, istrinya sudah punya pacar lagi, segala macam, jadi buyar. Mereka bingung. Akhirnya laki-laki itu diburu, mau dibunuh, lebih baik mati saja. Kalau dia mati, selesai sudah. Ini kok hidup lagi? Jadi bikin persoalan baru. Akhirnya laki-laki itu dikejar, lari kemana-mana tidak ada yang menolong, akhirnya penggali kuburnya menolong, “Sudah! Mereka itu maunya kamu mati. Pura-pura saja mati, jadinya selesai. Biarkan mereka meneruskan konsepnya dan kamu hidup dengan cara lain.” Pada waktu itu dia ambil bendera merah putih, diselimutkan di diri dia dan jadi orang lain.
Maksud saya di Indonesia pada waktu itu, orang di dalam sebuah kelompok telah kehilangan hak-haknya sebagai individu. Dia menjadi anggota kelompok ya tidak punya lagi kepentingan individu. Tapi kalau kita tinjau semua kelompok itu unsurnya individu, yang tidak mungkin dia tiadakan karna pasti ada. Jadi compare, akan ada antara kebutuhan individu dan kebutuhan sosial, dalam antropologi itu juga ada manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial, itu kontras dan selalu bercakaran. Orang sebagai individu bisa menuntut macam-macam, tapi ketika dia sudah masuk komunitas dia tidak bisa apa-apa. Itu yang mau saya katakan, jadi lokasinya dimana, pakaiannya apa tidak masalah, bukan itu masalahnya. Itu sebabnya, dengan bertolak dari yang ada apa pun jadi. Kita punya uang bisa, tidak punya uang bisa juga.
Jadi ya pernah ingin bekerjasama dengan orang, dia sebagai art director tapi dia minta ini-ini-ini, tidak bisa saya bilang, kita tidak punya uang. Itu lebih baik kita tidak usah bekerja. Saya bekerja dengan orang yang mampu bekerja dengan apa saja. Tidak berarti bahwa kemudian yang dikerjakan itu seadanya. Cerita tadi yang saya mainkan di TIM selama sepuluh hari, penuh penontonnya dan review-nya bagus. Saya bawa ke Amerika, saya mainkan orang-orang Amerika. Saya ajak mereka berbuat seperti saya, tadinya mereka bingung, lama-lama mereka terkejut jadi begitu. Seseorang bilang, “Ini kalau kita main di New York, bisa jadi terkenal karna jadi fashion cara berpakaian seperti ini.” Karna buat mereka itu baru. Jadi bertolak dari yang ada, esensinya seperti itu dan dalam segala aspek saya melakukannya.
Misalnya berhubungan dengan teater sekarang, kalau tidak ada pemain ya saya pakai yang ada, kalau tidak ada barang ya saya pakai yang ada, kita berangkat dan main di Jepang. Sampai di Jepang saya tidak membawa apa-apa, dari sini ke sana membawa seadanya. Sampai di sana kemudian minta izin pagi-pagi memilih tong sampah orang-orang Jepang. Itu kita dapat bermacam-macam barang. Orang Jepang itu buat kita sih isi tempat sampahnya masih banyak yang berharga, itu kita kumpulkan untuk bikin properti. Jadi mereka bingung melihat kita. Kalau dilihat waktu kita bekerja itu jorok, tapi setelah jadi baru mereka terkejut. Jadi saya berani mengatakan itu karna sudah mengalami. Itu menjadi satu kekuatan kami di Mandiri.
Kami bisa bekerja tanpa ada apa-apa, dengan satu orang bisa, dengan seribu orang juga bisa, banyak uang bisa, tidak punya uang juga bisa. Jadi bukan seadanya. Tapi untuk itu kita harus berani dulu menerima apa adanya lalu dioptimalkan. Dengan apa? Dengan kreativitas, itu harta yang luar biasa kreativitas itu. Tak perlu teknologi, tak perlu apa-apa. Kenapa saya bilang begitu? Penonton itu ikut mencipta. Kamu lihat pertunjukan-pertunjukan tradisional? Tidak pakai apa-apa di lapangan. Dia bilang, “Aku sekarang berada di Jakarta, aku mau pergi ke bulan.” Dia berjalan dua langkah, “Aku ada di bulan!” Penonton langsung membayangkan bulan, tidak perlu ada bulan. Jadi penonton ikut mencipta, itu konsep lokal, kearifan lokal, mengajak penonton ikut serta mencipta.
Upacara bersama tidak ada penonton, semua penonton ikut bermain dalam imajinasinya sehingga tidak perlu ada apa-apa, karna orang mengadakannya. Seperti kamu mendengar cerita hantu di radio ya. Itu lebih seram ketimbang hantu dalam sinetron atau film. Lucu kadang-kadang ya? Kalau di sandiwara radio kamu tidak lihat, tapi lebih seram dari apa yang ada. Setiap orang macam-macam, abis nonton itu kamu bisa tidak enak tidur, seakan-akan muncul di dalam bayangan, bisa begitu ya? Itu bertolak dari yang ada, kuat sekali.
Kalau teror mental itu usaha untuk mengajak orang ngeh. Ngeh itu ya Bahasa Jawa. Aware kepada fokus, tapi bukan fokus ke satu titik. Kearifan lokal kita bilang fokus itu 360 derajat, seluruh titik itu fokus. Jadi kalau orang fokus itu tidak berarti lupa kepada yang lain-lain, justru harus sadar kepada yang lain-lain. Contoh kasatmatanya begini: Ada orang-orang tidur, padahal seharusnya waktu mereka untuk bekerja. Dibangunkan, mereka tidur saja terus. Dipukul, tetap tidur. Ya akhirnya kamu ambil karet atau cabang kayu, kamu lempar dan jatuh ke mereka, “Ular!” Langsung mereka bangun, “Mana? Tidak ada ular!” Tapi mereka bangun, setelahnya mereka bekerja. Jadi, itu teror.
Teror itu pernah dikritik, setelah Reformasi tidak ada lagi teror yang bisa mengagetkan orang. Karna pengertian terornya salah. Ada teror waktu malam sepi sekali, tapi kurang sepi. Kalau ada gong-gongan anjing lama-lama di kejauhan itu baru bertambah sepi. Atau ada tetes air di kamar mandi, tes-tes-tes itu sudah jadi konsep logika. Bukan sepi ada bunyinya, tapi justru bertambah sepi sekali. Saat kamu pergi ke mall yang ramai sekali, tapi kamu baru kehilangan pacar, sepi sekali pasti rasanya. Jangankan di kamar, di mall yang begitu ramai pun sepi karna kamu baru kehilangan pacar. Nah itu teror mental. Teror mental itu maksudnya mentalnya, bukan fisiknya. Batinnya dan maksudnya positif. Dicabik orang, tapi dibuat ngeh.
Oke pak. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan.
Iya nanti akan saya email.
Muhammad Panji Gozali, lahir di Buaran pada 14 Mei 1997. Lulusan S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (2019) dan S2 Pascasarjana Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (2022). Mengajar Sejarah di SMA Islam Al Azhar 1, aktif dalam dunia kesenian sebagai penulis, pimpinan/sutradara Teater Moksa, pendiri Pustaka Pandawa, tergabung dalam Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia dan Majelis Sastra Asia Tenggara.
Buku terbit; novel Srimuni (2017), dramaturgi Merdeka Tanda Tanya (2018), dramaturgi Mati Konyol (2019), kumpulan sajak Abstraksi Kehidupan (2019), kumpulan sajak Balada Buaran (2019), kumpulan sajak Sukma Mawar (2019), kumpulan cerita Mati Suri Seorang Seniman (2020), dramaturgi KE.LUH (2021), Putu Wijaya: Sejarah Pemikiran dan Nasionalisme Cerpen ‘Indonesia’ (2021), dramaturgi Cilaka (2022) dan dramaturgi Itu! (2023).
Karya teaternya yang dipentaskan; Merdeka Tanda Tanya (2018), Mati Konyol (2019), Reunian (2019), Bisikan Jiwa (2020), Fragmen Pandemi (2020), KE.LUH: Parade Monolog Problematika Pendidikan Indonesia Masa Pandemi (2021), Among: Retrospeksi Satu Abad Taman Siswa (2022), Kau Belum Teruji: Sebuah Monolog untuk Rudy Masinambouw (2022), Cilaka (2023) dan Kalap: Di Balik Kebahagiaan (2023).













