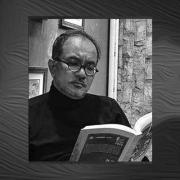Dari Death of Salesman Sampai Badak-Badak
(Catatan Singkat Pementasan FTJ 2022)
Oleh Seno Joko Suyono
FTJ (Festival Teater Jakarta) 2022 yang diselenggarakan dari 1-9 Oktober 2022 baru saja usai. Tahun ini adalah tahun ke 49 FTJ dihitung dari tahun dimulainya Festival Teater Remaja yang diinisiasi oleh almarhum Wahyu Sihombing di Taman Ismail Marzuki. Tahun depan adalah tahun ke 50 FTJ. Sebuah tahun “magis” yang harus dirayakan betul oleh seluruh ekosistem teater Jakarta dengan pertunjukan-pertunjukan berkualitas.
FTJ mungkin adalah salah satu festival teater tertua di Asia Tenggara. Daya tahan dan kekonsistenan segenap insan perteateran di Jakarta (bersama Dewan Kesenian Jakarta yang sejak tahun 1973 berperan sebagai stake holder pelaksana FTJ) secara kontinu mampu menyelenggarakan FTJ sampai umur 50 tahun adalah sebuah pencapaian tersendiri.

Foto poster Festival Teater Jakarta 2022
Selama 8 hari, 15 grup dari berbagai wilayah Jakarta berkompetisi di FTJ 2022. Setelah dua tahun, FTJ dilaksanakan dengan penonton terbatas kini FTJ kembali lagi terbuka luas untuk dihadiri publik teater. FTJ menggunakan dua lokasi yaitu Teater Luwes milik Institut Kesenian Jakarta dan Teater Kecil Taman Ismail Marzuki. Masing-masing grup teater bisa memilih lokasi panggung mana yang cocok dengan pementasannya.
Berbeda dengan pelaksanaan FTJ tahun-tahun sebelumnya, salah satu prasyarat FTJ kali ini adalah sutradara yang ikut dari mulai babak penyisihan di wilayah-wilayah Jakarta sampai final di Taman Ismail Marzuki adalah sutradara di bawah usia 40 tahun. Ini adalah strategi DKJ untuk melakukan pembinaan terhadap jagad perteateran Jakarta.

Para Juri Festival Teater Jakarta 2022 di lobby Teater Kecil TIM (1). (dari kiri ke kanan: Joseph Ginting, Seno Joko Suyono, Sri Qadaratin, Elly Luthan, Dindon W.S).(Foto: Seketi Tewel)
Tiga grup pemenang final (tanpa rangking) selanjutnya akan diundang untuk pentas kembali di acara besar: Lebaran Teater yang diadakan DKJ pada bulan Desember. Pada acara itu selain tiga pemenang FTJ akan dipentaskan kembali, juga ditampilkan tiga grup senior dari Jakarta yang akan dipilih melalui jaur kurasi. Yang dimaksud grup senior adalah grup-gup yang diipimpin oleh sutradara-sutradara di atas 40 tahun. Selain itu juga akan dipentaskan juara-juara Festival Teater Kampus, juara-juara Festival Teater Pelajar sampai juara-juara Festival Teater Anak. Juga akan ditampilkan grup-grup teater dari luar yang berkolaborasi dengan teaterawan dari Jakarta termasuk grup teater dari Belanda dan Jepang. Sistem yang baru ini diharapkan akan mampu menambah gairah, kesemarakan dan mensolidkan ekosistem perteateran Jakarta, dengan hasil-hasil pencapaiannya yang bisa lebih terukur.

Para dewan juri Festival Teater Jakarta 2022 di lobby Teater Kecil TIM (2). (Foto: Seketi Tewel)
Balik kepada FTJ 2022 sendiri, bila kita cermati komposisi naskah yang diangkat selama FTJ 2022 ini adalah: 7 kelompok teater memilih menggunakan naskah-naskah lama yang telah mapan (baik naskah terjemahan maupun naskah dramawan Indonesia sendiri yang telah dikenal luas publik teater) dan 8 grup teater memilih menggunakan naskah-naskah baru yang dibuat sendiri. Yang memilih menggunakan naskah terjemahan dan naskah karya dramawan Indonesia yang telah teruji kualitasnya adalah: Sun Community (Psychosis karya Sarah Kane), Rawamangun Concept (Death and The Maiden karya Ariel Dorfman), Teater Laut (Nyanyian Angsa karya Anton Chekov), Teater Sapta (Orkes Madun 2 atawa Umang Umang karya Arifin C Noer), Teater Petra (Death of Salesman karya Arthur Miller), Kelompok Sandiwara Mantaka (Badak-Badak karya Eugene Ionesco), Teater Jannien (Bui karya Akhudiat).
Adapun yang menggunakan naskah sendiri adalah: Teater Diri (Ranggalawe karya Ayak M.H), Teater Ciliwung (Panjar karya Yoga Mohammad), Teater Anala (Wayang Garok karya Muhammad Habib Koenady), D’Lakon Aktor Panggung (Kausal karya F. Bachtiar Bak), Teater K (Renshu ! karya MMAl Muhtadi MD), Teater Cahaya (Langit Biru Darahku Biru karya Mohammad Syukron Amrulloh), Madilog Act (Legenda Anak Negri karya Anca Takdir), Teater Confeito (Gelembung, Gelombang, Lumbung karya Heri Purwoko).

Para dewan juri Festival Teater Jakarta 2022 di lobby Teater Kecil TIM (3). (Foto: Seketi Tewel)
Dilihat dari pemilihan naskah-naskah terjemahan rata-rata yang diangkat para peserta adalah terjemahan naskah-naskah lama. Naskah terjemahan paling baru yang tampil di forum FTJ 2022 ini adalah Psychosis karya Sarah Kane. Sarah Kane adalah penulis teater dari Inggris yang mati muda pada usia 28 tahun di tahun 1999. Ia mati karena bunuh diri. Pada 17 Februari 1999 di apartemennya di Brixton Sarah Kane menenggak 50 pil obat tidur dan 150 tablet anti deresi. Ia dilarikan ke London’s king’s College Hospital dan dirawat di sana. Tapi saat dirawat, pada tanggal 20 Februari Kane ditemukan mati. Ia menjerat lehernya sendiri di pojok toilet menggunakan taki sepatunya sendiri.
Naskah-naskah yang ditulis Sarah Kane kemudian dikenal luas oleh kelompok-kelompok teater Inggris dan dianggap dari bagian generasi baru naskah-naskah Inggris tahun 2000-an. Sepanjang hidupnya Sarah Kane menulis 4 naskah teater yaitu: Blasted, Phaedra’s Love, Cleansed dan Crave. Naskahnya rata-rata bertema kekerasan, depresi dan keterombang-ambingan psikologi. Naskah Blasted misalnya bercerita tentang seorang wartawan setengah baya yang memperkosa seorang dan kemudian memutilasinya. Naskah ini kontroversial dan mengundang kritik yang tajam dari media karena adegan-adegan brutal namun naskah ini dikagumi oleh penulis naskah dan dramawan besar Inggris Harold Pinter. Selain Psychosis, naskah Kane yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Phaedra’s Love. Phaedra’s Love diterjemahkan oleh Yudi Aryani di Yogja menjadi Cinta Phaedra. Dan pada tahun 2013 pernah dipentaskan oleh Saturday Acting Club Yogja dengan sutradara Rukman Rosadi.

Rapat dewan juri di kantor Dewan Kesenian Jakarta (1). (Foto: Budi Yasin Misbach)
Selain naskah Sarah Kane namun jarang atau belum ada naskah terjemahan dari dramawan-dramawan Eropa ternama generasi tahun 2000-an yang beredar luas dalam publik teater kita. Itu menunjukkan bahwa memang terdapat “krisis” terjemahan naskah-naskah terbaru yang berbobot – yang dewasa ini diperbincangkan luas di Eropa atau Amerika. Kita juga tidak tahu sama sekali misalnya naskah mutakhir –terkini dari Rusia. Naskah-naskah Russia yang beredar di kalangan perteateran kita masih sebatas naskah-naskah “jadul” seperti Chekov , Nikolai Gogol (Hal yang sama juga terjadi dengan terjemahan sastra Rusia yang belum menyentuh sastrawan-sastrawan Rusia terkini, baru sampai ke karya-karya klasik seperti Dostoyevsky, Ivan Turgenev, Leo Tolstoy, Solzhenitsyn). Padahal tentunya di kala perang Russia dan Ukrainia seperti sekarang, dramawan-dramawan Russia tak tinggal diam melahirkan karya-karya yang merespon situasi genting itu dari perspektif personalnya. Kita juga sama sekali tidak tahu kondisi naskah-naskah drama Eropa Timur. Bahkan naskah-naskah lama Vaclav Havel dramawan yang menjadi presiden Cekoloswakia dari 1993-2003 pun seperti Garden Party, The Memorandum dan lain-lain sama sekali belum pernah diterjemahkan di sini.
Pada tahun 60 sampai 70 an kita memiliki sastrawan-sastrawan yang aktif menerjemahkan naskah-naskah barat klasik dan kontemporer seperti almarhum Asrul sani, Rendra, Sapardi Joko Damono, Toto Sudarto Bachtiar, Trisno Juwono, Arif Budiman dan sebagainya. Mereka menerjemahkan karya-karya dari Samuel Beckett, Ibsen, Strindberg, Albert Camus sampai tragedi-tragedi Yunani. Mereka dikenal memiliki antusiasme untuk memonitor perkembangan naskah-naskah di barat dan lalu menerjemahkan naskah-naskah babon yang dianggap penting. Di tahun 70 an memang secara menarik DKJ memiliki progam penerjemahan naskah.
Dalam buku Asrul Sani 70 tahun yang pernah diterbitkan Pustaka Jaya misalnya disebutkan Asrul sudah menerjemahkan kurang lebih 100 naskah drama asing meski semua tidak pernah dipentaskan. Pada tahun 1980 an kemudian atas ide almarhum Tuti Indra Malaon juga dilanjutkan progam penerjemahan naskah-naskah standart barat kontemporer. Salah satunya adalah naskah terkenal Sweeney Todd : Tukang Cukur Haus Darah (diterjemahkan oleh almarhum perupa Candra Johan ,saat itu anggota komite Seni Rupa DKJ) karya Christopher Bond dan Rumah Yang Dikuburkan karya Sam Shepard (diterjemahkan oleh Akhudiat).
Jarak-jarak penerjemahan naskah-naskah kontemporer barat dengan kemunculannya di sini memang bervariasi. Naskah Buried Child misalnya ditulis Sam Shepard tahun 1978 dan meraih Putlizer tahu 1979. Pada tahun 1988 terjemahan Akhudiat atas naskah ini yang kemudian disadur lagi oleh Afriza Malna dipentaskan oleh Teater SAE di TIM. Artinya hanya dalam jarak 10 tahun terjemahan Buried Child sudah sampai dan dimainkan di Indonesia. Masih banyak lagi naskah Sam Shepard yang belum diterjemahkan di sini. Masih banyak naskah-naskah dramawan Amerika lain generasi Shepard seperti David Mamet atau Tom Stoppard yang tidak pernah diterjemahkan di sini dan makanya belum dikenal di sini. Hanya sebuah naskah dari Edward Albee: Zoo Story (Kisah Kebun Binatang) yang juga pernah ditransliterasian ke bahasa Indonesia.

Rapat dewan juri di kantor Dewan Kesenian Jakarta (2). (Foto: Budi Yasin Misbach)
Melongok lebih jauh lagi, naskah Huis Clos misalnya ditulis Sartre pada tahun 1944. Dan tahun 1946 terjemahan Inggrisnya: No Exit sudah dipentaskan di Broadway dan London. Pada tahun 1958 naskah itu dipentaskan oleh Mahasiswa ATNI di Solo dan tahun 1961 disajikan ulang pada Pekan Teater ATNI. Penerjemah dan sutradara pementasan itu adalah Asrul Sani. Artinya hanya dalam jarak 14 tahun naskah Sartre itu telah diterjemahkan dan dipentaskan di Indonesia. Akan halnya naskah Badak-Badak karya Ionesco diadaptasi oleh Jim Adilimas ke bahasa Indonesia sangat cepat. Badak-Badak diciptakan oleh Ionesco pada tahun 1959. Pementasan pertama Badak-Badak di Paris disutradarai oleh Jean Louis Barrault pada 25 januari 1960 di Odeon Theatre. Dan pementasan pertama Badak-Badak di London disutradarai oleh Orson Wellesdi Royal Vourt Theatre paa 28 April 1960. Sementara Badak-Badak telah diadaptasi oleh Jim Adhi Limas dari STB (Studi Teater Klub Bandung) sebelum keberangkatannya ke Paris 1967. STB semasa Jim masih berada di Bandung memang terlihat tendensi ingin mementaskan naskah-naskah yang juga sedang dipentaskan di Eropa.
Sesunguhnya munculnya terjemahan atas naskah Sarah Kane lumayan cepat. Naskah Phaedra’s Love dipentaskan pertama kali di Inggris tahun 1996. Dan Psychosis pertama kali dipanggungkan tahun 23 Juni 2000 di Royal Courtsd Jerwood Theatre Upstairs Inggris –setahun sesudah kematian Sarah Kane. Bila dihitung dari tahun pementasan Phaedra’s Love dan Psychosis di Inggris pementasan Phaedra Love di Indonesia yang muncul pada tahun 2013 dan Psychosis di FTJ 2022 (sebelumnya pada Maret 2015 naskah ini juga pernah dipentaskan oleh Riset Teater Jakarta di Teater Salihara), berkisar 15 sampai 17 tahun. Artinya ia lebih lama rentangnya dari penerjemahan Badak Badak dan Buried Child tapi hampir bersamaan rentang waktunya dengan para mahasiswa ATNI saat mementaskan Pintu Tertutup terjemahan Asrul Sani di Solo.
Beberapa tahun terakhir juga muncul terjemahan naskah-naskah dramawan sepuh Jepang Tadashi Suzuki yang terkenal dengan prinsip prinsip pelatihan tubuh dan kaki. Naskah-naskah Suzuki yang diterjemahkan di sini adalah naskah-naskah tafsir Suzuki atas tragedi-tragedi Yunani terutama yang ditulis Euripides, antara lain: Bacchae (yang dibuat Suzuki tahun 1978), Electra (yang dibuat Suzuki 2007), Clytemnestra (yang ditulis Suzuki 1983). Pada tahun 2018, Bacchae diterjemahkan oleh tim dari Bali Purnati pimpinan Restu Imansari untuk keperluan kolaborasi para aktor Indonesia dengan Tadashi Suzuki baik di Jepang, Singapura maupun Indonesia. Pada tahun 2021 Electra juga diterjemahkan oleh tim Restu Imansari untuk pementasan bersama aktor-aktor Indonesia dengan Tadashi Suzuki di Jepang. Restu meminta sastrawan Nirwan Dewanto menerjemahkan Electra versi Suzuki. Adapun Clytemnestra karya Suzuki pernah diterjemahkan oleh Fathul Husein dari Neo Theater Bandung. Ia mementaskan naskah itu pada tahun 2012 di Bentara Budaya Jakarta. Fathul sendiri kemudian diundang pentas di Toga, sarang Tadashi Suzuki di Jepang. Ia mementaskan Rumah Boneka (A Doll’s House) karya Ibsen. Seharusnya dengan begitu banyaknya network dan kolaborasi yang dilakukan para teaterawan kita dengan dedengkot-dedengkot teater dari luar, terjemahan naskah-naskah asing bisa lebih banyak. Saya melihat berlimpahnya penerjemahan naskah-naskah terkini dari luar justru akan membuat bergairah medan perteateran kontemporer.
Sebuah penerjemahan akan menantang seorang sutradara untuk membumikan, mengadaptasi, menyadur dan mencari konteks relevansi naskah-naskah tersebut dengan persoalan yang ada di dalam negri sendiri. Apalagi bila memang naskah-naskah itu kuat dan menantang. Munculnya naskah-naskah babon yang disebut di atas sampai naskah-naskah seperti Woyzeck dari George Buchner, Lady Machbeth dari Ionesco, Caligula dari Albert Camus, Waiting for Godot dari Samuel Beckett Indonesia, pada tahun 70-80 an sangat mampu meramaikan jagad pementasan kita.
Satu hal lagi yang penting menurut saya adalah banjirnya terjemahan naskah-naskah berbobot dengan sendirinya akan memicu lahirnya naskah-naskah sendiri yang juga berkualitas. Munculnya naskah-naskah Arifin C Noer dan Putu Wijaya yang khas Indonesia dalam penglihatan saya sebetulnya secara tidak langsung merupakan bentuk “kontestasi”, “rivalitas”, “persaingan”, “kompetisi” untuk “melawan” bentuk-bentuk pemanggungan yang ditawarkan rata-rata naskah terjemahan barat. Dalam dunia tari pun begitu. Munculnya pemberontakan-pemberontakan, penafsiran atau pembacaan ulang tradisi dalam koreografi kita seperti yang dilakukan Sardono W Kusumo, almarhum Gusmiati Suid sesunguhnya adalah kerja koreografi yang sadar akan konstelasi peta tari kontemporer dunia mulai dari Pina Bausch, Martha Graham, gelombang Butoh dan lain sebagainya.
Demikianlah sedikit penglihatan saya tentang naskah terjemahan yang di FTJ masih porsinya lebih banyak mengandalkan terjemahan-terjemahan lama, kecuali Sarah Kane. Bagi saya untuk membentuk ekosistem perteateran ke depan menjadi segar dan menantang, DKJ harus mengupayakan kembali proyek-proyek penerjemahan atau pengadaptasian naskah-naskah luar mutakhir. Di banding dunia seni rupa, jagad perteateran kita mungkin ketinggalan dalam menempatkan diri dalam peta internasional.
Terpilihnya Ruangrupa menjadi kurator Documenta 2022 di Kassel Jerman dan bagaimana kurasinya menggoncangkan dunia seni rupa dengan lebih menampilkan komunitas-komunitas seni non main stream dari Afrika, Amerika Latin, Asia, Timur tengah daripada perupa-perupa mapan Eropa-Amerika menunjukkan bahwa seni rupa kita telah memiliki kekuatan di blantika internasional. Upaya dunia seni rupa untuk terus berusaha mengikuti dan mengamati perkembangan-perkembangan seni di kawasan-kawasan lain dunia juga tampak lebih maju daripada dunia teater. Bienalle Yogja tahun depan – setelah tahun-tahun sebelumnya bekerja sama dengan perupa Brazil dan Afrika kini misalnya berancang-ancang untuk bermitra denga para perupa negara-negara eks Yugoslavia di Eropa Timur.
Sementara untuk naskah-naskah yang dibuat sendiri di FTJ 2022 saya melihat banyak yang belum matang penulisannya. Kita melihat – pada naskah-naskah yang realis ada keinginan untuk menjelajahi kemungkinan tema-tema namun struktur dramaturginya kurang bisa membuat penonton terserap ke dalam sebuah peristiwa dramatik yang memiliki sebab akibab ketat dan logis. Akan halnya pada naskah-naskah yang mengandalkan eksprimen lebih-lebih lagi. Pada titik ini menurut saya – apakah itu teater realis atau physical theater, naskah yang baik tetap merupakan sebuah hal yang vital. Pertunjukan yang bagus – bahkan teater tubuh bisa bertolak dari naskah yang jelas. Kita bisa melihat contoh kasus Teater Payung Hitam.
Salah satu pertunjukan terbaik dan terkuat Rahman Sabur dan Teater Payung Hitam adalah pertunjukan Kaspar Hauser yang mereka pentaskan tahun 1994. Pertunjukan ini cenderung non verbal dan tanpa dialog. Namun demikian sangat menghunjam penonton. Saya melihat pertunjukan ini di teater arena Taman Budaya Surakarta. Kekuatan aktor utamanya Tony Broer saat itu sangat memukau dan membekas. Pertunjukan ini mengangkat Teater Payung Hitam menjadi sangat diperhitungkan sampai sekarang. Yang banyak orang tidak tahu pertunjukan ini adalah tafsir Rahman Sabur terhadap naskah dramawan Austria Peter Handke. Dari naskah yang bagus itu, Sabur memiliki imaji-imaji radikal untuk menampilkan sebuah physical theater yang tentu sangat berbeda dengan apabila naskah itu disajikan secara realis. Pada kasus ini ini terlihat sebuah pertunjukan physical theater yang dasyat pun bisa bertolak dari tafsir atas naskah-naskah yang cenderung realis.

Para dewan juri Festival Teater Jakarta 2022 di lobby Teater Kecil TIM setelah pementasan terakhir. (Foto: Imanuela Dyan Indriyani)
Hal lain yang menonjol yang saya catat pada FTJ 2022 ini adalah perbedaan karakter ruang pertunjukan yang sangat mempengaruhi bentuk pementasan. Teater Kecil dan Teater Luwes. yang digunakan di FTJ adalah dua gedung yang memiliki karakteristik tak sama. Teater Kecil cenderung merupakan gedung teater konvensional yang tiap pertunjukannya senantiasa dipertontonkan di panggung proscenium. Sementara Teater Luwes- sebagaimana namanya Luwes bisa digunakan untuk format pertunjukan apapun. Di Teater Luwes orang bisa menggunakan panggung proscenium sebagaimana teater konvesional. Namun lantai di bawah proscenium yang tidak memiliki kursi-kursi yang tertanam fix bisa dimaksimalkan sebagai sebuah teater arena. Bahkan sebuah komunitas teater bisa saja melakukan pementasan dengan sekaligus menggunakan proscenium dan lantai bawah. Format Teater Luwes yang bisa menampilkan banyak kemungkinan pementasan ini saya amati membuat beberapa grup teater melakukan eksplorasi ruang yang menarik, penuh main-main dan tak terduga.
Sesungguhnya beruntung TIM memiliki banyak aneka rupa format gedung teater. Sekarang TIM memiliki format panggung proscenium di Graha Bakti Budaya, Teater Jakarta dan Teater Kecil. TIM juga memiliki Teater Arena dan Teater Luwes (milik IKJ di belakang TIM). Pada tahun 70 an sedikit banyak berbagai ragam format panggung teater ini mampu membuat para sutradara teater dan penulis naskah saat menyusun naskahnya sudah menyusun dialog-dialog dan suasana dramatiknya yang dibayangkan cocok dengan salah satu format panggung. Juga tatkala melakukan latihan-latihan sudah bisa megimajinasikan lebih cocok dipentaskan di gedung mana. Beragam format panggung membuat beragam ide tentang pemanggungan bisa muncul. Maka dari itu saya juga menyarankan pada FTJ tahun depan, gedung Teater Arena yang baru juga dipergunakan sebagai salah satu tempat pertunjukan.
Tapi apapun apakah pertunjukan itu dipentaskan di proscenium atau format teater arena, apakah pertunjukan itu pementasan realis atau physical theater tetap kunci utama pementasan adalah kematangan tubuh. Tubuh adalah unsur utama dalam teater. Teater mula-mula adalah tubuh. Yang jadi soal banyak pementasan di FTJ 2022 ini kemampuan tubuh aktor beserta cara mengucapkan kalimat-kalimat naskah kurang tergarap meyakinkan. Sudjojono salah satu maestro seni rupa Indonesia pernah memiliki istilah Jiwa ketok (jiwa tampak) untuk menyebut apakah sebuah lukisan telah memiliki karakter atau tidak. Sesungguhnya jiwa tampak itu juga yang harus muncul dalam keaktoran. Khusus untuk final FTJ, seharusnya yang tampil adalah pementasan-pementasan yang tubuh-tubuh aktornya sudah mampu mengatasi persoalan-persoalan teknis dan elementer kebertubuhan. Sehingga dalam menonton pentas final, penonton tinggal melihat bagaimana tubuh-tubuh para aktor yang matang itu terlibat dalam kompetisi penafsirkan naskah yang tepat dan pembaruan artistik. Namun sayangnya – dalam ajang final FTJ 2022 ini beberapa pementasan masih menampilkan tingkat keaktingan yang sangat permukaan. Jangankan memukau. Cara mengucapkan kalimat-kalimat dan ekspresi tubuh masih seperti cenderung stereotype drama-drama sekolahan tingkat SMA. Di satu sisi juga ada beberapa pertunjukan yang bagus-tapi menjadi sangat terganggu saat dari awal sampai akhir seorang aktornya cenderung over, ekspresi dan lengkingan suaranya dibuat-buat dan itu anehnya dibiarkan oleh sang sutradara.
Berikut adalah catatan singkat (snapshot-snapshot) saya atas 15 pertunjukan yang selama 8 hari di FTJ 2022 saya tonton. Sebagai salah satu dari anggota dewan juri (juri lain adalah Joseph Ginting, Dindon W.S, Elly Luthan, Sri Qadaratin) tentu saja catatan saya mungkin berbeda dengan catatan anggota juri lain. Tiap juri memiliki perspektif penilaiannya sendiri-sendiri. Tiap juri memiliki pandangan argumentasinya sendiri-sendiri. Foto-foto yang menjadi ilustrasi dari catatan saya ini adalah jepretan dari fotografer dan aktivis teater Suketi Tewel, fotografer Imanuela Dyan Indriyani dan sutradara teater Budi Yasin Misbach.
Ronggolawe, produksi Teater Diri
Pementasan ini ingin menampilkan sosok Ronggolawe yang merasa tak puas dengan kebijakan politik Raden Wijaya, penguasa Majapahit. Raden Wijaya sesungguhnya adalah sahabat dekat Rongolawe. Mereka berjuang bersama-sama mendirikan Majapahit. Ronggo Lawelah yang beserta Lembu Sora, Nambi, Gajah Pagon melindungi Raden Wijaya saat Singosari dihancurkan Jayakatwang dari Kediri hingga membuat Kertanegara tewas. Dan melarikan Raden Wijaya ke Sumenep menemui ayah Ronggolawe, Arya Wiraraja untuk meminta bantuan pasukan. Raden Wijaya kemudian kembali ke Jawa Timur berpura-pura mengabdi ke Jayakatwang namun kemudian bersama pasukan baru dan pasukan Mongol Raden Wijaya kemudian bisa menghancurkan Kediri. Tapi juga kemudian mengusir pasukan Mongol.

Foto pementasan Ronggolawe oleh Teater Diri (1). (Foto: Imanuela Dyan Indriyani)
Apabila pentas ini fokus mengulik pergulatan kejiwaan Ronggo Lawe yang berani menantang Wijaya – sahabat akrab dan sekutunya sendiri tentunya menarik. Problemnya pengadegan kurang konsisten menampilkan persoalan Ronggolawe dan lebih banyak menampilkan sub-sub adegan yang tidak menguatkan problem politik yang hendak diangkat. Penulisan naskah drama Ronggolawe ini bertolak dari novel. Agaknya pengalih wahanaan dari novel ke naskah drama belum mampu mengangkat pertautan adegan satu dengan adegan lain menjadi satu kesatuan kohesif.
Konteks persoalan politik mengapa Ronggolawe sampai marah terhadap Wijaya kurang dimunculkan. Apa sesungguhnya yang terjadi di Trowulan? Kebijakan politik apa yang dikeluarkan Raden Wijaya? Bagaimana sahabat-sahabat Ronggolawe lain, Lembu Sora, Kebo Anabrang? Penonton yang belum mengetahui sejarah Ronggolawe tentu membutuhkan dialog-dialog yang sedikit banyak menyinggung hal itu.
Dalam pementasan ini dimunculkan tokoh Jejaran (diperankan Assa Musa) sebagai semacam narator. Porsi permainannya hampir sebesar porsi permainan Teguh Pryono yang bermain sebagai Ronggolawe. Betapapun demikian, sosok Jejaran ini tidak ditempatkan sebagai seorang “dalang” yang memberi penjelasan sejarah tapi lebih ditempatkan sebagai sosok yang menampilkan simbolisasi peristiwa secara artistik. Ia misalnya muncul membawa sapu lidi. Di atasnya terdapat sebuah sangkar atau kurungan kosong tergantung. Ia memasukkan kepalanya di sangkar itu. Ia kemudian juga menghantam-hantamkan sapu lidi ke sangkar hingga lidi-lidinya tertancap.
Di adegan lain, ia masuk panggung sambil membawa manekin a setengah torso. Kepala manikin berwarna merah seolah berdarah. Setelah itu muncul secara sepintas manusia-manusia bertopeng dari balik pintu. Adegan ini menarik secara artistik namun kurang ada kaitannya dengan peristiwa besar yang dipersoalkan. Adegan ini lebih seperti seperti sebuah fragmen lepas yang tidak menguatkan persoalan yang hendak dibicarakan. Hal yang sama juga terjadi pada adegan rakyat kecil. Para rakyat kecil ini berdialog kecil hanya kurang menginformasikan. Baik tokoh Jejaran dan para rakyat kecil tidak menyebut nama-nama tokoh seperti Lembu Sora, Kebo Anabrang, Nambi- yang nota bene tokoh-tokoh yang amat berkaitan dengan pusaran peristiwa Ronggolawe.

Foto pementasan Ronggolawe oleh Teater Diri (2). (Foto: Imanuela Dyan Indriyani)
Ending pementasan ini menggantung. Ronggolawe diperlihatkan bermaksud menghadap Raden Wijaya. Sang istri membasuh kaki Ranggalawe. Secara simbolis ia bersumpah melakukan sati – atau bunuh diri bila sang suami mati. Penonton yang tidak tahu sejara Jawa Timur pasti tidak mampu menangkap apa yang terjadi selanjutnya karena cerita tiba-tiba selesai. Kita tahu dalam dalam teks Pararaton dikisahkan Ronggolawe tewas di tangan sahabat-sahabatnya sendiri seperti Kebo anabramg. Ronggolawe menghadang pasukan Majapahit yang merupakan sahabat-sahabatnya sendiri. Tapi dia kalah.
Di akhir, ada adegan Jejaran membawa anak kecil kesana kemari oleh. Sang anak menirukan kalimat Jejaran yang suka mengatakan: weleh weleh. Anak ini seolah diposisikan sebagai anak cucu keturunan Ronggolawe di masa kini. Ia adalah Satria Piningit. Adegan masa kini itu disimbolkan denga musik blues yang tiba-tiba menguar di panggung. Betapapun demikian –karena heroisme Ronggolawe tidak dipaparkan secara jelas dalam dramaturgi, adegan anak kecil sebagai Satria Piningit ini terasa sebagai tempelan belaka.
4.48 Pyschosis produksi Sun Community
Pertunjukan teater ini pekat sedari awal sampai akhir. Tatkala penonton masuk di Teater Luwes dan duduk di trap-trap yang penataannya disusun membentuk format teater arena suara tik tak tik tak seperti detak jam atau jantung sudah menguar. Begitu lampu remang, muncul suara gaung elektrik seperti gaung bowl meditatif. Makin lama gaung ini makin dalam.
Bunyi ini langsung bisa membawa kita masuk ke atmosfer “dunia bawah sadar” yang diinginkan. Pementasan ini menonjolkan pemakaian format teater arena namun proscenium Teater Luwes juga digunakan. Mula-mula terlihat di pojok kanan proscenium seorang perempuan muncul meringkuk. Lampu kemudian disorotkan dengan posisi diagonal ke gelanggang permainan berformat arena. Seseorang laki-laki (diperankan Irfan Hakim) dengan menggunakan wheelchair lalu meniliti garis diagonal tersebut. Sebuah pembukaan yang kuat. Laki-laki itu adalah pasien. Perempuan di proscenium lalu seperti melihat seluruh kejadian yang akan berlangsung pada pasien-pasien.

Foto pementasan Pyschosis produksi Sun Community (1). (Foto: Seketi Tewel)
Naskah kontroversial Sarah Kane ini berbicara tentang halusinasi dan depresi. Sutradara Irfan Hakim yang merangkap aktor utama memilih menggunakan wheel chair sebagai properti utama para aktor meski dalam naskah tidak ada petunjuk mengunakan kursi roda. Wheel chair itu digunakan Irfan untuk mendukung aura pasien-pasien di rumah sakit yang terobsesi bunuh diri. Pertunjukan menggunakan wheel chair sendiri bukan hal yang baru. Teater-teater di Jepang sering menggunakan prop wheel chair.
Salah satu yang termasyhur adalah pentas Electra karya Tadashi Suzuki yang mengadaptasi naskah tragedi Euripides. Pentas Electra menggunakan elemen utama wheel chair. Pentas ini beberapa tahun lalu disajikan Tadashi Suzuki bersama aktor-aktor Indonesia. Boleh jadi sebagai sutradara, Irfan banyak melakukan riset pembacaan atas Electra (yang secara lengkap sudah ditayangkan di Youtube). Dan lalu mengilhami dia untuk memasukkan dan mengimplementasikannya sebagai elemen utama naskah Sarah Kane. Hal itu tak menjadi soal, karena mentraformasikan gagasan di sebuah tempat menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda di tempat lain justru menunjukkan kecerdasan. Apalagi memang bila penggunaan wheel chair tersebut memang orisinil gagasan Irfan.
Lepas dari adanya keterpengaruhan atau tidak, penggunaan wheel chair memang mampu menjadi tenaga utama pertunjukan ini membangun “estetika” depresi”. Wheel chair tidak menjadi sekedar prop statis namun menjadi wahana kesakitan tubuh. Dikisahkan pada tiap pukul 4.48 halusinasi pasien-pasien memuncak. Bisikan-bisikan kuat muncul dari dalam pikiran pasien sendiri untuk mengerat nadi dan menjerat atau menggantung leher sendiri.
Bisikan-bisikan itu menginjeksikan rangsangan bahwa dengan mengerat urat nadi tangan sendiri pasien akan mengalami kesakitan tapi sekaligus kenikmatan luar biasa. Kenikmatan tiada duanya. Tiga aktor merepresentasikan halusinasi tersebut. Irfan sebagai poros dan dua aktor lain (dimainkan oleh Banyu Setiawan dan Ilman Bahri) sebagai pendamping cukup kuat saling menciptakan dimensi kelam kerapuhan jiwa manusia dan suasana psikologi dalam yang hitam.
Irfan sebagai sutradara, mampu membuat pergerakan tiga wheel chair mengeksplorasi berbagai arah ruangan sehingga dinamis dan tak membosankan. Mobilisasi kursi roda diperhitungkan. Percakapan-percakapan overdosis dan sakauw antara Banyu Setiawan dan Ilman Bahri juga ditakar intonasinya. Ada adegan dialog di mana salah seorang dari mereka mengajukan interograsi dengan pertanyaan-pertanyaan bernada lambat tapi menghunjam dan menggiring sementara yang satu menjawab dengan cara bicara yang menghentak-hentak keras.
Kemampuan Irfan Hakim sendiri menampilkan dirinya sebagai pasien lumpuh yang mengalami visoner-visioner penglihatan dan ganguan-gangguan suara-suara aneh cukup kuat. Tubuhnya dan wheel chair seolah sudah menyatu padu. Ia memutar-mutar kursi roda keliling ruangan sampai menghentak-hentakkan wheel chair. Di awal ada adegan ia menutup kuping dengan kedua telapak tangannya seolah ia tak tahan dengan bisikan-bisikan yang berdengung di kepala dan merasuk pikirannya. Ia menangkupkan kaos yang dipakainya menutupi kepalanya seolah bisikan-bisijan secara liar dan bertenaga merayap seluruh syarafnya. Ia sampai berdiri merentangkan tangan di atas kursi roda saat mengucapkan : Aku takut obat-obatan. Aku tak bisa ngentot…”

Foto pementasan Pyschosis produksi Sun Community (2). (Foto: Seketi Tewel)
Acap para aktor menjalankan kursi roda dengan kaki-kaki menghentak-hentak lantai. Di sini terlihat ada kesadaran menjadikan tubuh bagian dari permainan bunyi yang melengkapi suasana musik elektrik. Para aktor sadar menjadikan tubuhnya masuk dalam permainan irama. Kursi roda sendiri ke sana kemari digerakkan para aktor tidak dengan tangan memutar roda-roda, tapi dengan kaki-kaki berderap di lantai. Ini membuat dramatika sendiri. Kaki-kaki yang menghentak lantai sangat memperhatikan koreografi. Bunyi derit besi kursi roda menciptakan sensasi tersendiri. Pertunjukan ini juga menciptakan adegan-adegan di mana para aktor mendekat kepada penontong, seolah ingin melibatkan penonton sebagai bagian dari dunia rumah sakit. Beberapa kali aktor mengarahkan wheel chair dekat ke wajah penonton dan mengucapkan kalimat-kalimat ke arah muka penonton.
Pertunjukan ini berakhir dengan klimaks yang tak terduga. Tiga aktor melakukan adegan bunuh diri dengan menjerat lehernya dengah tali. Mereka seolah menjerat leher sendiri kuat-kuat. Adegan bunuh diri ini diawali dengan tiba-tiba dari arah proscenium disorotkan belasan lampu ke arah penonton. Suasana pementasan yang tadinya suram mendadak silau oleh belasan sorot lampu. Bersamaan dengan itu mengumandang ke dalam ruangan komposisi musik orkestra yang megah : Carmina Burana dari Carl Off. Adalah tak terduga adegan menjerat leher diiringi dengan komposisi Carmina Burana. Sepanjang pertunjukan musik elektronik yang cenderung minimalis kontemporer (termasuk suara sirene, suara koor yang saling menumpuk, elemen-elemen gaung, gema, echo) tiba-tiba berpuncak kepada Carmina Burana yang kolosal secara bunyi. Dan itu untuk mengiringi adegan bunuh diri.
Teater ini telah mampu mengatasi persoalan teknis dasar. Dan membawa penonton ke dalam lapisan-lapisan psikologi manusia yang hitam. Bagian paling lemah mungkin adalah saat sang perempuan yang sedari awal duduk di proscenium memperhatikan seluruh adegan turun ke lantai. Perempuan tersebut merupakan personifikasi dari kesadaran Sarah Kane. Tatkala turun ia dikelililingi oleh para pasien di kursi roda. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh sang perempuan dan kehadiran ekspresi tubuhnya kurang terintegrasi dengan intensitas suasana yang telah diciptakan ketiga aktor. Kehadiran sang perempuan seperti adegan tempelan yang bisa dibuang.
Bagi yang berusaha kritis, tentu ada pertanyaan mengapa pertunjukan ini seolah menampilkan glorifikasi bagi sikap-sikap yang menguatkan bunuh diri. Tak terelakkan pertanyaan itu mencuat karena nasib Sarah Kane sendiri setelah membuat naskah ini lalu memang betul-betul bunuh diri. Namun dari sisi lain- pertunjukan yang ditampilkan Sun Community ini mampu bagi saya pribadi menghasilkan refleksi betapa progam-progam healing medis yang menggunakan obat-obatan modern di rumah sakit di sana sini ternyata tak selalu sukses menerapi pasien-pasien over dosis. Seperti ditunjukan pementasan Sun Community, perawatan-perawatan pasien-pasien di rumah sakit justru makin membuat mereka didominasi oleh halusinasi-halusinasi yang mereka tidak mampu mengatasinya. Pentas ini seolah menyodorkan tesis Michel Foucault dalam bukunya the Birth of Clinic bahwa kegilaan atau penyakit mental bisa makin merasuk ke dalam diri pasien makin akibat penanganan dan metode instrument-instrumen rumah sakit cenderung eksploitatif.
Death And The Maiden produksi Rawamangun Concept
Naskah Death And The Maiden karya penulis Chile, Ariel Dorfman sudah beberapa kali dipentaskan di sini. Paling tidak ada empat grup teater yang memanggungkan: Teater Kami, Teater Satu Lampung, Teater Aristokrat dan Teater ISBI Bandung. Semua memiliki strategi dan siasat-siasat dramatiknya sendiri. Pertunjukan Teater Satu Lampung yang disuradarai oleh Iswadi Pratama di Teater Salihara pada 12-13 Juli 2013 misalnya untuk membuat penonton tidak jenuh dengan dialog-dialog dan perdebatan-perdebatan politik di panggung menambahkan karakter tambahan (peran kecil). Dalam naskah asli Dorfman tokoh hanya berjumlah tiga orang: Paulina, Gerardo Escobar, dokter Robert Miranda. Oleh Iswadi ditambah kemunculan singkat ibunda Paulina, Jane (perempuan yang berselingkuh dengan Gerardo Escobar), tukang kebun dan pemerah susu.

Foto pementasan Death And The Maiden produksi Rawamangun Concept (1). (Foto: Seketi Tewel)
Pertunjukan Rawamangun Concept setia pada teks asli. Tokoh tetap hanya tiga orang. Dialog-dialog panjang mengenai politik cenderung dipertahankan. Duduk perkara persoalan penculikan aktivis dan pemerintahan Chile baru yang berusaha melakukan investigasi terhadap kasus-kasus kekerasan Hak asasi Manusia di zaman Diktatorial Jendral Augusto Pinochet yang berkuasa antara tahun 1973-1990 – yang dalam pertunjukan teater-teater sebelumnya cenderung diperpendek bisa kita dapatkan dalam dialog antara Gerardo Escobar (dimainkan Muhammad Thoriq) dan tamunya Robert Miranda (diperankan Aldiansyah Azura).
Paulina (diperankan oleh Adinda Rahmawati) cenderung ragu bahwa pemerintahan baru di era reformasi mampu membongkar kejahatan di masa rezim Pinochet. Sebagai korban pemerkosaan aparat, dia menyangsikan suaminya yang baru dipilih presiden menjadi anggota termuda Komisi Rekonsialisasi mampu membongkar dan menyeret pelaku-pelaku kekerasan. Sepanjang 15 tahun, dia tidak bisa lepas dari trauma dan kecurigaan terus menerus. Sebagai aktivis kiri pada masa rezim Pinochet dia dipenjara dan di dalam penjara dia diperkosa berulang kali serta disetrum terus menerus. Paulina tidak bisa memaafkan semua penyiksaan itu.
Secara konteks cerita semua itu bisa kita dapatkan saat menonton pertunjukan ini. Yang menjadi persoalan sedari awal pembagian ruang skenografi terasa kurang pas atau agak kurang proporsional. Lokasi peristiwa ini di naskah disebutkan terjadi di sebuah villa di tepi laut. Untuk format panggung Teater Kecil yang tidak begitu luas, sutradara Fajrin Yuristian membagi set permainan menjadi ruang luar (outdoor) yang berada di tebing laut dan ruang tamu. Walhasil ruang tamu cenderung sempit. Padahal seluruh adegan inti berada di sana terutama adegan pemukulan, pengikatan, penyanderaan dan penodongan pestol kepada dokter Roberto Miranda oleh Paulina.
Ruang tamu yang sempit itu dipenuhi kursi, meja dan sofa sehingga membuat mobilasi bloking Paulina saat mengintiidasi dokter Miranda kurang variatif. Adegan Paulina mendengarkan pembicaraan suaminya dengan dokter Miranda dari ruang bersantai outdoor di gigir jurang itu juga terasa agak janggal. Karena sesungguhnya antara ruang outdoor dan ruang indoor tertutup dinding tebal- meski di panggung dinding tebal itu hanya imajiner. Tak masuk di akal dihalangi dinding tebal itu Paulinan mampu memastikan suara dokter Miranda adalah suara orang yang dulu memperkosanya di penjara.
Tatkala adegan penyiksaan terhadap dokter Miranda dilakukan Paulina tensi pertunjukan memang meningkat meski adegan pengikatan sendiri berlangsung kurang dramatik. Pada pementasan Teater Satu Lampung, dokter Miranda (yang diperankan Iswadi) tangannya “dipalu” lebih dulu oleh Paulina (yang dimainkan Ruth) hingga terasa kepada penonton sang dokter benar-benar lumpuh dan tidak berdaya. Terasa Paulina energinya begitu kuat dan mampu melakukan “kesadisan”. Hal itu yang kurang menguar pada pertunjukan Rawamangun Concept. Akting aktig para aktornya mampu menunjukkan kelancaran cerita tapi tidak menunjukkan daya pukau atau karisma pemeranan. Cara mengikat tali Paulina ke kaki dan tangan Miranda kurang meyakinkan. Tatkala tiba-tiba Paulina melepas celana dalam merahnya dan menyumpalkan ke mulut dokter Miranda –adegan itu membuat penonton lebih tersenyum daripada merasakan ketegangan.
Karakter tokoh utama Paulina sedari awal cenderung terisak-isak hingga membuatnya terlihat sebagai perempuan yang lemah. Pada titik ini menarik untuk mendiskusikan apakah logis karakter yang terus terisak dan terlihat renta tersebut kemudian tiba-tiba berubah menjadi kuat dan seperti “kesetanan” mampu mengikat, menyiksa dan menodongkan pestol ke seorang laki-laki. Mungkin sebuah kelompok teater yang hendak mementaskan adegan ini perlu lebih dulu berkonsultasi dengan psikolog untuk meraba bagaimana sesungguhnya ingatan seseorang yang penah diperkosa dalam penjara militer. Apakah ia cenderung dingin, berupaya menyembunyikan perasaan tapi tiba-tiba dapat melakukan tindakan-tindakan yang mustahil dan tak terduga atau cenderung tiap mengingat kekejian itu selalu terisak-isak meski peristiwa yang terjadi padanya sudah berlangsung 15 tahun?

Foto pementasan Death And The Maiden produksi Rawamangun Concept (2). (Foto: Seketi Tewel)
Bagian paling penting dan menjadi klimaks dari keseluruhan adegan adalah saat Paulina menggeret dokter Miranda keluar, menodongkan pestol dan mendekatkannya ke pagar (yang diimajinasikan di tepi jurang itu). Paulina memaksa dokter Miranda melakukan pengakuan dan ia akan merekam seluruh pengakuannya. Dokter Miranda dalam adegan terakhir pementasan ini diperlihatkan mengaku ia melakukan pemerkosaan berkali kali terhadap Paulina. Ia mengaku teah menyetrum Paulina berulang-ulang untuk melakukan eksprimen terhadap daya tahan tubuh perempuan apakah tetap memiliki rangsangan seksual sesudah tubuhnya lemah dialiri listrik.
Tapi dalam pengakuan itu, dokter Miranda juga menyatakan sesuatu yang mengejutkan. Eksprimen penyetruman dan pemerkosaan itu menurut dokter Miranda justru dilakukan untuk menyelamatkan Paulina. Semua tahanan perempuan yang tak dijadikan kelinci percobaan akan langsung dibunuh militer. Dengan memilih Pauluna menjadi obyek eksprimen seksual, Miranda mengaku berusaha menyelamatkan Paulina. Di situlah kisah ini berakhir dengan dilema dan paradoks.
Paulina akhirnya melepaskan tembakan. Penonton mengira dokter Miranda mati. (Dan tertawa karena tatkala bagian panggung outdoor belum gelap benar terlihat aktor yang memerankan Miranda bangkit merangkak). Ternyata dalam kisah dokter Miranda memang dibiarkan Paulina hidup. Tembakan Paulina tidak diarahkan benar ke tubuh sang dokter. Sang dokter tertatih-tatih keluar melewati Paulina yang tengah berpelukan dengan suaminya. Paulina seolah mengalami katarsis karena telah melakukan keputusan yang berat. Di sini Rawamangun Concet tidak memotong klimaks yang sangat penting – dan menjadikan problem moral menjadi dilematis dan tak hitam putih – sebagaimana dilakukan oleh teater lainnya.
Nyanyian Angsa produksi Teater Laut
Hal yang mengherankan dalam pementasan ini adalah sepanjang adegan monolog tokoh komedian tua – pementasan diiringi sayup-sayup musik gamelan Bali. Mula-mula musik yang diperdengarkan di panggung adalah iringan instrumental lagu Pink Floyd: Hey You dan baru kenudian disusul samar-samar gamelan Bali.

Foto pementasan Nyanyian Angsa produksi Teater Laut (1). (Foto: Seketi Tewel)
Adalah terasa janggal iringan tersebut, karena dalam pementasan ini nama-nama aktor masih berbau nama Rusia. Aktor tua yang melakukan monolog di ruang teater yang telah kosong dan tertutup itu masih dipanggil dengan nama Vasili Svietlovidoff. Lebih masuk akal apabila Teater Laut menampilkan pementasan Nyanyian Angsa ini dengan menampilkan kisah seorang maestro tradisi Bali yang kesepian, menjelang ajal dan merasa ditinggalkan penggemarnya. Dia bisa seorang penari sepuh topeng Arja Bali atau aktor sepuh drama Gambuh atau yang lainnya. Tafsir demikian akan lebih cocok dengan iringan musik Bali dan mungkin akan terasa lebih kuat adaptasinya karena monolog Nyanyian Angsa ini sendiri sudah sangat sering dipentaskan di manapun.
Vasili Svietlovidoff, aktor tua berusia 68 tahun itu dikisahkan tak pernah merasa mengalami detik-detik menakutkan seperti hari itu. Ia baru mabuk. Ia merasa sangat kesepian. Ruang teater kosong yang sehari-hari memang menjadi tempat tinggalnya tiba-tiba seperti dipenuh ancaman maut. Dengan masih mengenakan kostum totol totol badut, ia merasakan ajalnya mendekat. Vasili adalah komedian ternaman. Di ruangan ganti gedung teater itu tampak dicantelkan berbagai kostum badut.
Untuk membunuh kesepian yang akut, ia mengajak pembisik panggung yang tiba-tiba muncul di ruang ganti arena ia juga terkunci di gedung teater – dan tak bisa keluar memainkan potongan-potongan naskah yang pernah dia mainkan. Petilan-petilan naskah yang menghantarkan dia ke puncak ketenaian. Yang janggal petilan-petilan naskah yang mereka mainkan bukan naskah-naskah Rusia atau barat tapi naskah Malin Kundang. Dan lagu yang mereka dendangkan bersama adalahbseperti bait-bait lagu Broery Pesolima. Vasili Svietlovidoff adalah aktor gaek yang malang melintang dalam pementasan akbar. Petilan-petilan drama seharusnya adalah petilan naskah Rusia atau naskah-naskah standartpapan atas seperti Shakespeare. Pilihan menampilkan adegan Vasili memainkan cuplikan adegan Malin Kundang sama sekali terasa tak nyambung dan menurunkan kelas Vasili.

Foto pementasan Nyanyian Angsa produksi Teater Laut (2). (Foto: Seketi Tewel)
Pentas yang ditata sutradara Muhammad Esa Gilang Anugrah ini sangat pendek. Dinding kanan kiri areal penonton di Teater Luwes ditutupi kain hitam. Namun itu tidak sampai menciptakan efek dramatis atau kesunyian akut. Pementasan di proscenium juga tak mampu menyajikan suasana aura kesedihan aktor tua menjelang ajal. Pementasan ini tidak kurang dari 30 menit. Tiba-tiba selesai. Tanpa meninggalkan bekas apapun.
Panjar produksi Teater Ciliwung
Mereka adalah kumpulan orang-orang mati. Mereka ditempatkan dalam “dunia sementara” sebelum mereka betul-betul pulang entah kemana, sorga atau neraka. Mereka “menunggu” untuk menuju alam yang final. Dalam “dunia sementara” dan dimensi lain itu para arwah orang mati ini – masih berperi laku selaiknya orang hidup. Menyanyi, berdebat, berkelahi, membunuh. Hanya saja mereka sadar bahwa mereka sudah mati. Dalam “dunia sementara” itu mereka mengalami “kesakitannya” masing-masing sesuai panjar atau tabungan kebaikan yang telah mereka kumpulkan dalam kehidupan.
Konsep tentang kematian dan kehidupan setelah mati yang “rumit” dari penulis naskah dan sutradara Yoga Mohamad ini ingin diwujudkan pada cerita sekelompok mantan seniman yang mati dan mereka tertahan – menunggu dalam “dunia sementara” berupa sebuah pondok dengan interior perabotan-perabotan klasik cukup mewah. Mereka adalah Billie, seorang diva jazz , Gotti penyair, Hans pemusik, Lana penari, Bong sutradara, Ashmir seseorang mati yang kemudian menjadi pengelola pondok. Dalam pondok itu mereka mengenang masa lalunya saat kejayaan masa-masa hidup. Mereka juga berkonflik satu sama lain dengan pembawaan emosi-emosi yang berbeda.

Foto pementasan Panjar produksi Teater Ciliwung (1). (Foto: Seketi Tewel)
Problemnya adalah seluruh pemain bersama-sama sedari eksposisi – adegan pengantar awal sampai akhir, belum bisa secara kuat memberi keyakinan kepada penonton bahwa cerita yang mereka hamparkan adalah kisah mengenai dunia orang mati. Sutradara kurang mampu membuat keseluruhan ansambel permainan semenjak awal menunjukkan suasana bahwa sesungguhnya percakapan-percakapan yang terjadi adalah percakapan antara orang mati. Struktur dramaturgi, pengkarakteran masing-masing tokoh yang terlalu ingin menonjolkan cerita-cerita tentang kesenimanan mereka justru menutupi persolaan inti yang hendak disampaikan dan tidak menggulirkan peristiwa peristiwa yang dapat dinikmati dengan lancar. Gagasan soal Panjar yang menjadi judul tontonan ini walhasil tidak muncul kuat dalam alur rangkaian sebab akibat peristiwa.
Hal ini berbeda misalnya dengan naskah Sartre: Pintu Tertutup. Sejak sedari awal teks telah kuat menampilkan dialog-dialog yang segera membuat penoton langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa tokoh Garcin, Estelle, Inez adalah orang-orang mati. Adegan-adegan awal dalam Pintu Tertutup adalah baik Garcin, Estelle, Inez terkejut bahwa neraka tidak seperti yang mereka bayangkan saat mereka masih hidup di bumi. Di dalam neraka ternyata tidak ada alat-alat penyiksaan seperti yang sering mereka dengar.
Sementara dalam naskah Panjar tidak ada dialog kuat yang sejak awal menunjukkan dunia kematian yang mereka alami. Penonton, akibatnya bisa salah terka bahwa naskah ini adalah semacam naskah yang melulu menceritakan seniman-seniman tua yang saling mengelus-elus masa keemasannya dulu di sebuah villa. Apalagi yang ditonjolkan adalah kemampuan Billie (dimainkan Margareta Marisa) menyanyikan lagu-lagu jazz dengan tingkat kesulitan vokal yang lumayan. Iringan lagu-lagu jazz yang dipentaskan langsung dalam pertunjukan ini – meski enak namun malah bisa mengalihkan perhatian penonton terhadap persoalan yang hendak dikemukakan. Tidak ada tokoh sentral dalam percakapan-percakapan, semua bermain dengan porsi adegan yang sama membuat alur cerita seperti sebuah ping pong percakapan terus menerus. Beberapa pemain aktingnya sangat over (terlalu bersemangat) dengan ekspresi dan gesture tangan yang dilebih-lebihkan sehingga cenderung malah makin mengaburkan persoalan Panjar.
Beberapa adegan yang sesungguhnya hendak dijadikan clue bahwa peristiwa di pondok itu adalah peristiwa orang mati adalah adegan perkelahian antara Hans dan tamu baru pondok Bong, sang sutradara. Hans mengusir, menyeret, memukul dan meminta Bong agar tidak masuk ke pondok. Hans menganggap “dunia sementara” adalah tempat terkutuk. Hans maka dari itu tidak ingin ada tamu tamu baru yang akan makin sengsara. Tapi perkelahian tersebut terkesan menjadi perkelahian biasa yang kehilangan duduk perkaranya. Demikian juga tatkala dalam adegan tiba-tiba terdengar jeritan suara Gina – sosok yang tidak muncul di panggung. Tangisan itu merupakan ekspresi dari penderitaan yang diakibatkan oleh panjarnya. Sesungguhnya bila semenjak awal tangisan-tangisan dan jeritan para penghuni pondok itu dimunculkkan – diseling-selingkan dengan peristiwa musikal jazz yang dipertontonkan Billie – mungkin – suasana dunia kematian itu lebih terasa.
Yang juga membuat logika kita berpikir keras adalah adegan Hans mengeluarkan pestol dan membunuh Ashmir. Ini adalah bagian yang bisa makin membingungkan penonton. Penonton yang mungkin di tengah pertunjukan mulai bisa meraba bahwa yang sesungguhnya peristiwa di panggung adalah adegan orang-orang mati, bisa kembali sangsi – mengapa dalam dunia orang mati masih terjadi adegan-adegan pembunuhan. Pestol itu bahkan dikatakan Ashmir kepada Hans telah digunakan membunuh 27 kali di pondok yang mereka tempati. Dan mengapa Ashmir yang sudah mati juga terkesan takut kepada ancaman nyawa yang dilakukan kepadanya oleh Hans.

Foto pementasan Panjar produksi Teater Ciliwung (2). (Foto: Seketi Tewel)
Konsep kematian yang diusung oleh sutradara agaknya ; seseorang bisa mati berkali-kali (mungkin diambil sutradara dari menafsirkan sebuah puisi Jallaludin Rumi). Setelah mati dia bisa mati lagi – dan berada di dunia-dunia sementara sebelum akhirnya mati paling akhir yang menjadikannya pulang ke surga atau neraka. Adegan mati seluruh pemain “yang sudah mati itu” diperlihatkan saat ending saat para pemain musik pun naik ikut menyanyi di atas panggung. Para aktor dan musisi sama-sama menyanyikan lagu We’ll Meet Again yang kerap dilantunkan Vera Lynn. Semarak. Lalu mereka semua satu persatu jatuh mati.
Sebuah ending yang lain daripada yang lain. Pemilihan lagu We’ll Meet Again jelas ingin mengalegorikan bahwa setelah kematian ini mereka akan berjumpa dengan kehidupan lain di alam kematian lain. Pementasan dengan iringan yang memainkan lagu-lagu Jazz disisipi choir sesungguhnya adalah sebuah pementasan yang langka. Apalagi ketrampilan musik tim penata musik (Michael rumondor dan kawan-kawan) bukan asal-asalan. Para musisi pertunjukan ini jelas bukan musisi abal-abal. Harmoni 7 orang anggota tim musik saat melantunkan choir adalah bukti mereka vokalis-vokalis paduan suara yang terlatih. Namun adegan terakhir yang segar pun tak mampu membuat ending menjadi pamungkas sebuah pertunjukan yang clear secara narasi. Pementasan ini walhasil lebih menonjol kulitnya daripada isi yang hendak disampaikan.
Orkes Madun II Atawa Umang-Umang produksi Teater Sapta
Unsur teater rakyat menjadi jiwa pertunjukan Teater Sapta. “Teater tanpa batas” sekaligus “aktor tanpa batas” yang meleburkan penonton dan pemain memang cocok dengan semangat dasar naskah Umang Umang. Pemilihan format berupa teater arena di Teater Luwes mampu menampilkan roh teater keliling yang bisa pentas di lokasi manapun dan pada tiap pentas berusaha melakukan interaksi dengan penonton secara intim tanpa jarak.
Sedari awal, suasana cair, suasana guyub, suasana komunitas, suasana lebur sangat mewarnai pertunjukan Teater Sapta. Set sederhana- pemain dan pemusik dengan areal akting dibatasi cuma pembatas bambu yang dipasang rendah. Pemain satu persatu keluar meloncat ke arena permainan. Format demikian memang sudah sangat sering digunakan oleh banyak teater tradional namun terasa masih aktual dan segar di tangan Teater Sapta.

Foto pementasan Orkes Madun II Atawa Umang-Umang produksi Teater Sapta (1). (Foto: Seketi Tewel)
Yang sangat menonjol memang adalah permainan M. Fahmi A.R, sebagai pemeran tokoh Waska. Ia memainkan secara bergantian sosok Waska dan Semar, sang dalang. Sebagai aktor yang memerankan Waska sang pemimpin besar para bajingan dan masyarakat tersisih, Fahmi mampu menunjukkan karakter karismarik yang bisa menyedot daya hormat dan kesetiaan gerombolan maling. Ia mampu menghidupkan suasana komunitas. Kemampuan menghidupkan komunitas ini penting. Karena keguyuban komunitas marginal adalah jantung dari naskah Umang-Umang.
Banyak kelompok teater yang telah menampilkan Umang-Umang. Mereka masing-masing menafsirkan lapisan-lapisan komunitas marginal apa yang menjadi pengikut Waska. Selain pembunuh-pembunuh dan preman seperti Borok, Ranggong, Debleng, Gustav ada kelompok teater yang menambahkan pengikut Waska dari komunitas punk ronk sampai laskar gembel. Kelompok pasukan Waska untuk merampok di tangan Teater Sapta menunjukkan kemampuan berbagai keragaman maling ini untuk saling mengisi. Banyolan-banyolan bermunculan sepanjang pertunjukan namun tidak jatuh ke banyolan yang norak namun betul-betul banyolan yang bertolak dari komunitas yang anggotanya beraneka ragam latar belakang.

Foto pementasan Orkes Madun II Atawa Umang-Umang produksi Teater Sapta (2). (Foto: Seketi Tewel)
Bagi saya, pertunjukan Teater Sapta mampu menunjukkan bahwa naskah-naskah Arifin sesungguhnya penuh kekocakan. Kejenakaan yang muncul bukan dari humor murahan tapi muncul dari atmosfer naskah yang secara lintas batas campur baur mempertemukan dari para maling, perampok, anak kecil, tukang pijat, dajjal sampai nabi-nabi dengan setara dan rileks. Dari kejenakaan itulah kedalaman filosofis Arifin sesungguhnya adalah sebuah sub ex yang harus digali.
Death of Salesman produksi Teater Petra
Naskah Death of Salesman dibuat oleh Arthur Miller untuk mengkritisi mimpi-mimpi kapitalisme Amerika atau American Dream. American Dream menjadi jargon umum pemerintah Amerika di tahun 40 an. Masyarakat dijejali oleh mimpi mimpi cepat menjadi sukses, kaya dan makmur apabila masyarakat giat bekerja dan memanfaatkan sistem pasar yang berkembang.
Miller melihat American Dream mengandung aspek-aspek halusinasi dari kapitalisme yang berbahaya. Ia ingin menunjukkan bagaimana masyarakat kebanyakan Amerika terseret kepada mimpi-mimpi instan menjadi kaya dan sejahtera tapi kenyataannya kandas. Miller menampilkan kegagalan American Dream pada kisah seorang salesman tua. Ujung tombak kapitalisme saat itu untuk mendistribusikan aneka rupa barang dagangan adalah salesman atau penjaja keliling. Seorang salesman tua bernama Willy Loman dalam naskah Miller dikisahkan memiliki khayalan-khayalan sebagai orang sukses. Padahal ia tidak dipergunakan lagi sebagai pegawai dan dipecat di mana-mana. Willy bekerja keras. Hampir tiap hari keluar kota. Tapi ia sesungguhnya tetap gagal. Betapapun demikian ia masih optimis (cenderung halusinasi tepatnya) anak-anaknya juga akan mengikuti kesuksesan dirinya, padahal dua orang anaknya adalah pengangguran dan juga pencuri.

Foto pementasan Death of Salesman produksi Teater Petra (1). (Foto: Seketi Tewel)
Teater Petra yang disutradarai oleh Sultan Mahadi Syarif ini mampu menangkap duduk persoalan kepedihan apa yang dinginkan Miller sehingga percakapan-percakapan yang panjang dari naskah bisa dikuti secara logis. Naskah Miller dipenuhi percakapan-percakapan kecil seputar keluarga, yang kadang seolah melantur kemana-mana padahal semua mengarah kepada satu persoalan yaitu tentang masyarakat yang berkompetisi keras mencari pekerjaan dan pendapatan dan banyak kelas masyarakat yang kalah. Susah memainkan kerapuhan keluarga Willy apabila sutradara tidak secara cermat mampu menganalisa kalimat kalimat per dialog dan mengungkapkan sub teksnya. Teater Petra cukup lancar menampilkan bagaimana kesadaran palsu tertanam pada diri keluarga Willy. Kesadaran bagaimana mereka bagian dari arus orang-orang sukses.
Yang menggelayut menjadi pertanyaan sampai pementasan ini berakhir adalah mengapa Teater Petra memilih jenis skenografi non realis. Dalam pertunjukan, Petra tidak menampilkan sebuah interior rumah dengan sofa atau perabotan, atau set tangga yang menuju ruang atas dan lain-lai sebagaimana pentas teater realis pada umumnya. Set yang dihadirkan hanya berupa dua bingkai besar kotak bujur sangkar yang didirikan sebagai background areal permainan. Bidang-bidang ini memberi aksen selera kubuistik pada panggung. Kursi-kursi juga bukan kursi dalam pengertian sebenarnya. Adegan awal dimulai dengan disorotkan video berupa kolase gambar perumahan dan urbanisitas kepada kedua bidang itu.

Foto pementasan Death of Salesman produksi Teater Petra (2). (Foto: Seketi Tewel)
Penempatan set “seni rupa ala kubuistik” yang diletakkan agak di tengah panggung membuat membatasi ruang akting dan membuat para aktor tidak leluasa bergerak sampai sudut sudut belakang. Para aktor tidak bisa mengeksplorasi komposisi bloking yang variatif dan berubah-ubah dari bagian belakang sampai depan. Pergerakan pemain seolah hanya berada di sebuah garis lurus di depan. Tapi resiko demikian tentu disengaja oleh sutradara. Tampaknya sutradara ingin menghindari set yang klise berupa interior sebuah ruang tamu. Dan menggantikannya dengan set yang lebih minim tapi imajinatif- bisa menjadi apa saja.
Kekuatan pentas ini adalah akting dari pemain utama Ahmad Rifqi sebagai Willy Loman dan Dina Amalina sebagai Linda, istri Willy. Rifqi memainkan Willy dengan karakter yang tidak meledak-ledak. Ia hampir tidak melakukan gerak-gerak besar yang menteaterikalkan geturkulasinya. Aktingnya berusaha wajar. ia lebih seperti menjadi orang biasa. Bila ia bicara keras, membentak istrinya atau memarahi anaknya bukan marah dengan ekspresi yang dibesar-besarkan. Tapi marah kecil yang sebentar kemudian lunak lagi. Willy sesungguhnya putus asa dalam berkompetisi menjadi salesman di pasar yang demikian keras namun ia berusaha menutup-nutupi. Ia masih berusaha menegakkan kebanggaan terhadap keluarga. Akan halnya permainan Dina Amalia , mampu meyakinkan kita bahwa Linda adalah sosok istri yang demikian sabar. Ia adalah istri yang berusaha mengerti dengan sikap-sikap suaminya yang tak reaslistis. ia berusaha berdamai dengan kekecewaan-kekecewaan keluarga.
Bagian paling menarik adalah tatkala Willy mengalami halusinasi berbicara dengan kakaknya, almarhum Ben. Ben adalah panutan Willy. Ia ingin menunjukkan prestasi kakaknya bisa menjadi acuan anak-anaknya. Bens adalah seorang pengelana yang banyak bepergian untuk bekerja di tambang-tambang emas dan berlian. Ia seseorang yang berani dan karena keberaniannya ia cepat menjadi sukses dalam kapitalisme. Di sini suara-suara dari Ben diperdengarkan melalui rekaman. Suara-suara tak terlihat itu terus mengikut Willy dan makin menjadi Willy seseorang yang tersuruk dalam delusi akan kesuksesan.
Sebuah drama watak yang bagus akan menghasilkan akhir yang liris. Di akhir adegan, Willy membawa dua koper besar. Ia ke sana kemari mendatangi perusahaan-perusahaan menawarkan diri sebagai salesman. ia ditolak dimana-mana. Di penghujung pertunjukan, sebuah kopernya ditinggal. Dan koper itu secara artistik kemudian diberi gundukan tanah menjadi sebuah nisan. Sebuah ending yang halus namun kuat. Kematian Willy terasa sebagai kematian seseorang yang terlalu letih, kecewa, dan putus asa. Ada perasaan simpati terhadap sosok yang tragis.
Wayang Garok produksi Teater Anala
Suasana chaos, riuh, dan perpindahan tempat yang ekstrem menjadi estetika utama teater ini. Pentas ini mengisahkan seorang siswa perempuan bernama Ayona yang memimpin para pelajar memberontak pada para guru yang konservatif. Para guru yang dipimpin oleh Pak Balul dan asistennya Garok dipandang hanya menaati rezim saja. Kisah kudeta para pelajar ini tidak diangkat ke panggung dengan perhitungan seni keaktoran dan ruang yang lazim.

Foto pementasan Wayang Garok produksi Teater Anala (1). (Foto: Seketi Tewel)
Akting dan suasana dramatikal yang terjadi lebih cenderung ke sebuah happening art street underground yang hiruk pikuk. Liar dan seolah tak terkendali. Ungkapan-ungkapan gerak para aktor lebih menekankan ke ekspresi-ekspresi grostek dan suasana yang dibentuk adalah suasana karnaval jalanan. Kostum dan tata rias make up para guru ditampilkan serupa joker, clown, joker, pantomimer yang dominasi busana warna merah. Gerak yang disajikan adalah gerak banal keseharian sampai campuran dengan gerak gerik teaterikal verbal. Sementara busana Ayona dan pasukannya mirip dengan busana yang bertolak dari dunia cos play, dunia manga dan anime. Mereka membawa senapan-senapan, ketapel, pestol dompis, panah-panahan dan siap melontarkan ke arah para badut. Ayona sendiri berkostum ala punk, dengan tangan berbalut besi-besi runcing.
Memanfaatkan lantai bawah ruang Teater Luwes, penampilan Teater Anala betul-betul mengacak acak ruang. Properti utama yang menjadi motor pertunjukan adalah semacam kotak meja beroda empat yang bisa didorong ke sana kesini. Properti ini bisa menjadi ruang metafor apa saja. Bisa menjadi kelas para guru tapi juga bisa menjadi sel atau jeruji. Konflik antara pasukan Ayona dan para badut membuat terjadi perebuatan kotak ini. Kotak di dorong ke segala sudut. Permainan dan percecokan bisa dari arah mana saja, bahkan membelakangi penonton.

Foto pementasan Wayang Garok produksi Teater Anala (2). (Foto: Seketi Tewel)
Para pelajar pemberontak merebut kotak beroda itu dan membawanya membelah penonton. Menerjang penonton sehingga penonton yang duduk di lantai segera buru-buru berdiri menyingkir. Suasana happening yang ramai mengagetkan penonton. Para aktor melakukan okupasi ke ruang penonton. Suasana kacau. Kita melihat Teater Luwes yang selama ini identik dengan tempat latihan-latihan mahasiswa IKJ yang realis dengan naskah well made play menjadi” didesakralisasi” oleh Teater Anala. Proscenium yang elitis ditingalkan. Format teater arena pun juga ditabrak. Ruang dan medan pertunjukan menjadi “dimana” saja.
Saya melihat ada semangat besar untuk berekesprimen pada Teater Anala. Ada keberanian untuk menumpahkan unsur-unsur street art ke pertunjukan. Pada jenis tontonan seperti ini memang susah mengharapkan adanya perwatakan tokoh yang kuat. Naskah yang ditampilkan Teater Anala miskin dari segi cerita, plot dan kalimat. Hanya mengulang-ngulang soal ketidaklulusan. Dialog-dialog para aktor bukan dialog yang kritis mengenai sistem pendidikan tapi teriakan-teriakan dangkal. Gaya akting Ultah Kumalasari yang memerankan Ayona yang memimpin gerakan mirip gaya dan tipikal seorang mahasiswa demonstran yang berdiri di atas kap mobil lalu dengan corong menggelorakan massa.
Seperti juga pemeran sosok Waska dalam Umang-Umang yang diproduksi Teater Sapta tapi akting Ultah Kumalasari sedikit banyak —mampu menghidupkan dan mensolidkan “massa kolektif” seluruh pemain yang hadir di panggung . Terutama saat ia berdiri di atas kotak dan didorong ke sana sembari menggelorakan yel-yel: ”Batalkan kelulusan, batalkan kelulusan..” Bagi mereka yang melihat pertunjukan ini strict dengan takaran-takaran akting yang “baik dan betul” dan tak melihat sisi happening seni rupa dan eksprimen ruang teater ini, tentu akan berpendapat bahwa pentas teater ini hanya memamerkan keanehan-keanehan bentuk belaka yang isinya kurang mendalam. Teater ini hanya berani tampil beda untuk menutupi kelemahan akting para aktornya. Pemilihan gaya ekspresi badut-badut hanya main-main artifisial belaka.

Foto pementasan Wayang Garok produksi Teater Anala (3). (Foto: Seketi Tewel)
Betapapun demikian bagi saya pribadi, pemilihan gaya bermain seperti itu namun bukan tanpa konsep yang jelas. Pertunjukan ini mengingatkan pertunjukan-pertunjukan Sutanto Mendut dengan warga desa Lima Gunung yang liar. Tanto membiarkan puluhan warga desa mengenakan kostum seaneh-anehnya. Norak, tidak match, tak masalah. Para warga gunung itu dibiarkan Tanto bergerak, menari apa adanya– campur baur, tak masalah saling “bertabrakan” satu sama lain tanpa sebuah desain yang baku. Tanto hanya memberi ruang agar terjadi “chaos”. Dalam “chaos” itu akan muncul benturan-benturan yang menimbulkan ketidakterdugaan estetis.
Saya kira sikap-sikap seperti ini di barat pun digaungkan oleh para seniman Fluxus dan Dada, sebuah gerakan untuk mendobrak kemapanan seni yang macet. Seni dalam manifestasi Fluxus tidak harus diekspresikan orang-orang dengan pengalaman yang matang, tapi justru bisa digedorkan oleh kolektivitas orang-orang biasa. Dalam konteks ini, menarik melihat bagaimana Teater Anala menciptakan ruang-ruang permainan. Kotak beroda itu digeret membuat kelompok-kelompk penonton menjadi “berantakan”. Adegan terakhir penghukuman Garok dan Balul membuat medan permainan dari tengah bergerak ke samping kiri lalu berpindah ke samping kanan.
Para guru sekolah dihukum. Mereka dimasukkan ke kotak seperti sebuah sel. Mereka seperti disekap dalam kurungan terali besi. Kotak dibalikkan menjadi vertikal. Dan di pojok kiri areal permainan disitu tangan Garok diikat lalu ditarik-tarik leh “massa”. Kotak didiorong lagi melewati penonton dan areal permainan menjadi di kanan. Di situ Pak Balul tangannya direntangkan seperti disalib lalu “disetrum” oleh massa pelajar. Setiap “setruman” yang membuat Pak Balul “kejet-kejet” disambut meriah. Anarkis. Saya menjadi agak mengerti mengapa pertunjukan ini disebut sebagai wayang. Peristiwa yang terjadi mirip adegan goro-goro yang riuh .
Di ending, suasana yang sangat hiruk pikuk ini tiba-tiba berakhir hening. Tiba-tiba dari arah proscenium muncul layar besar yang menampilkan visual video lorong seperti sebuah time tunnel. Para massa yang ribut berhenti bersorak dan dalam kegelapan menatap lorong panjang yang bergerak itu . Pementasan teater Anala meski serebral, memperhitungkan ending yang menarik. Keriuhan diakhiri dengan sunyi reflektif. Sesuatu yang sungguh tidak terduga. Ending yang bagi saya cukup memperlihatkan bahwa pertunjukan Teater Anala meski terkesan hanya permukaan bukan jenis pertunjukan asal-asalan yang hanya mempertontonkan kesemrawutan. Pertunjukan mereka bukan hanya sekedar “everything goes” tapi memiliki konsep pemanggungan “lain” yang cukup dipikirkan dan berani dieksekusikan.
Kausal produksi Teater D’Lakon
Dinding-dinding di sisi kiri, tengah, dan kanan panggung Teater Kecil ditata dengan hiasan ornamen pola abstrak geometrik berupa garis-garis warna warni yang saling bertumpuk dan silang menyilang. Melihat panggung yang lumayan artistik awalnya pementasan ini cukup mengundang rasa ingin tahu.

Foto pementasan Kausal produksi Teater D’Lakon (1). (Foto: Seketi Tewel)
Dinding dinding berpola geometrik ini menampilkan sebuah ruangan tempat dua sahabat Gema dan Genta (yang dimainkan Halim Kusuma dan F Bachtiar Bak) hidup. Mereka saling membutuhkan. Mereka saling melengkapi. Tubuh mereka kontras: gemuk dan kurus. Karakter mereka berbeda. Yang satu penuh perasaan tapi kurang logis. Yang lain memiliki kemampuan berpikir tapi cenderung kurang peka.
Mereka tinggal bertahun-tahun dalam ruangan itu. Sepanjang pertunjukan namun tidak jelas apa yang ingin disampaikan pementasan ini. Tempat apakah itu? Apakah bunker bawah tanah? Apakah sebuah tempat persembunyian? Apa yang membuat mereka bertahan di situ? Adakah ancaman dari luar? Sepanjang pertunjukan, kita diperlihat cek cok antara mereka tapi hanya cek cok ringan yang dari dialognya sama sekali tak menampilkan persoalan penting “hidup dan mati”
Beberapa adegan segera mengingatkan pada End Game karya Samuel Beckett. Di ruangan itu terdapat sebuah kotak, tempat salah satu dari mereka sering masuk ke dalamnya. Ini mengingatkan properti tong dalam End Game, tempat Nag dan Nell sehari-hari tidur. Adegan lain, si gemuk memanggul si kurus dan si kurus membawa teropong untuk melihat suasana di luar. Jelas ini mengadosi adegan di dalam End Game karya Samuel Becket ketika Clov disuruh Hamm untuk melaporkan suasana di dunia luar. Hamm adalah sosok buta yang lumpuh dan hanya bisa duduk di kursi. Dia selalu menginstruksikan Clov sang pelayan.

Foto pementasan Kausal produksi Teater D’Lakon (2). (Foto: Seketi Tewel)
Tapi tentu pementasan ini jauh sekali dari End Game. Suasana yang dibangun sama sekali tidak pekat dan sublim. Interaksi kedua aktor lebih seperti persahabatan dua remaja ingusan yang saling merajuk karena tidak diperhatikan satu sama lain. Apalagi nada logat suara salah seorang aktor selalu dikekanak-kanakan. Adegan si gemuk yang suka menggambar angka-angka dan garis-garis di papan kertas, serta selalu percaya matematika hanya adegan ilustrasi yang tak dikembangkan menjadi materi masalah yang menjadi motor dramaturgi. Juga adegan-adegan si gemuk memanggul si kurus keliling ruangan tak bisa membuat suasana dramatis.
Terlihat seorang aktor (Halim Kusuma) memiliki kemampuan yoga. Sebuah adegan di awal memperlihatkan dia melakukan posisi asana yoga dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Sesungguhnya kalau kemampuan ini dieksplorasi menjadi jantung adegan-adegan lain, mungkin pertunjukan ini agak berbeda-dan bisa menawarkan sesuatu. Di akhir pertunjukan kedua sahabat itu memutuskan pergi. Mereka ingin melakukan perjalanan jauh. Meninggalkan tempat yang sudah mereka diami bertahun-tahun. Namun saat mereka pergi – sama sekali pada kita tidak membekas sesuatu tragedi atau keabsurdan.
Renshu produksi Teater K
Puluhan Stick Light berwarna merah dibagikan kepada penonton. Tiga penyanyi remaja perempuan bergaya penyanyi idol Jepang di proscenium mengomando para penonton untuk ikut menyanyi. Dalam kegelapan para penonton langsung bersama-sama mengacung-ngacungkan, menggelombang-gelombangkan Stick Light merah tersebut mengikuti irama musik. Para penonton (yang sebagain besar penonton pendukun) ikut menimpali nyanyian dengan suara koor bersama :”Ho ho Ho…” ,

Foto pementasan Renshu produksi Teater K (1). (Foto: Seketi Tewel)
Pementasan Teater K yang disutradarai Al Muhtadi ini menampilkan gaya dan selera anak-anak yang tengah gandrung dengan industri musik pop Jepang dan Korea. Backdrop panggung didesain dengan model pintu geser Jepang plus hiasan lampion. Unsur-unsur pop anime dan cara pemanggungan yang bernuansa amat remaja mendominasi panggung. Cerita yang dibuat Al Muhtadi ini sesungguhnya menarik.
Seorang sutradara sebuah kelompok teater sekolah bernama Dru Sensei (dimankan Daffa Mulla) dituntut para donatur harus cepat cepat menyelesaikan skenario, agar mereka bisa berangkat pentas ke Jepang. Ia lalu bersama sorang rekannya bernama Syasya (Ausy Syahdilla) mencoba membuat naskah dari yang berbau kriminal, horor sampai naskah action. Di panggung kemudian muncul sosk-sosok dari seorang misterius bertopi tinggi, berjubah hitam namun berparuh burung sampai sosok-sosok samurai. Mereka semua adalah bayangan-bayang imajinasi naskah mereka. Tapi kemudian Dru Sensi menola mereka semua membuat imaji-imaji itu protes.

Foto pementasan Renshu produksi Teater K (2). (Foto: Seketi Tewel)
Dru Sensei kemudian memutuskan untuk membuat naskah mengenai idol. Dia menyuruh seorang anak buahnya menculik Maria Ozawa seorang tokoh idol. Adalah lucu, sebab nama ini merukan nama salah satu tokoh film panas Jepang. Maria Ozawa lalu ikut dalam pemantasan Dru Sensei (yang ternyata hanya mimpi). Dia yang bernyanyi dan meminta para penonton menirukan nyanyian dengan mengacung-acungkan Stick Light merah.
Persoalannya eksekusi pertunjukan Teater K ini – mulai gaya akting dan bobot pementasannya lebih mirip pentas inaugurasi atau acara-acara Pensi (pentas seni) di sekolahan-sekolahan. Sang sutradara seharusnya menyadari untuk kebutuhan final festival harus lebih dari itu.
Badak Badak produksi Kelompok Sandiwara Mantaka
Beberapa orang yang tengah mengobrol di sebuah kafe dikejutkan oleh suara gemuruh melintas dari luar. Bunyi yang serupa bunyi binatang erat dan besar berderap lari cepat melewati jalanan menimbulkan café itu bergetar seolah hendak rubuh. Bunyi tersebut diwarnai lengkingan suara bak terompet. Para pengunjung café spontan bersama-sama melongok di jendela. Dan terkejut tatkala melihat ada sekawanan badak besar tengah menyerbu kota kecil mereka.

Foto pementasan Badak-Badak produksi Kelompok Sandiwara Mantaka (1). (Foto: Seketi Tewel)
Adegan suara gemuruh kawanan badak yang melintas ini diwujudkan oleh Kelompok Sandiwara Mantaka dengan rekaman suara gerombolan badak-badak. Pilihan tipe jenis bunyi badak-badak yang diperdengarkan, meyakinkan imajinasi kita bahwa memang ada gerombolan badak bercula yang tengah berlari bersama menerjang kota. Sepanjang pementasan suara badak-badak ini dimunculkan terus menerus pada titik-titik adegan yang dianggap pas. Suara badak seolah berfungsi sebagai leitmotif atau pokok bunyi yang menjaga dramatika suasana agar tetap konstan.
Badak-badak karya Ionesco bagi beberapa penamat sesungguhnya sebuah naskah “politik”. Kritikus teater Martin Esselin menyebutnya sebagai naskah post-war. Munculnya secara tiba-tiba segerombolan badak-badak liar dan buas memporak-porandakan sebuah kota kecil di Perancis sesungguhnya adalah satir Ionesco tatkala Nazi Jerman menduduki wilayah Perancis. Badak-badak yang berkulit tebal, bercula, ganas, menyeruduk sana sini tanpa bisa kompromi, membuat ketakutan serta kepanikan seluruh kota itu sesungguhnya adalah metafor Ionesco untuk serdadu-serdadu Nazi.
Badak adalah binatang bermuka tebal adalah juga parodi bagi Nazi yang tak tahu malu. Naskah Ionesco menggambarkan seluruh warga kota sedikit demi sedikit berubah bermetamorfosis menjadi badak. Itu sesungguhnya untuk melukiskan bagaimana Nazi berupaya keras dengan segala sepak terjang kekerasannya menundukkan warga-warga Perancis. Nazi berusaha keras mengubah cara berpikir warga agar menaati pikiran fasis. Akibat tekanan dan intimidasi Nazi banyak warga Perancis yang menyerah namun banyak juga warga yang tak mau tunduk dan melakukan perlawanan terhadap Nazi.

Foto pementasan Badak-Badak produksi Kelompok Sandiwara Mantaka (2). (Foto: Seketi Tewel)
Bila ditafsirkan dari sudut perspektif politik yang kuat, maka dari itu pemanggungan naskah ini bisa dimainkan dengan penekanan suasana serius, meminimalisir adegan-adegan dan akting berbau komedi yang dibuat-buat. Tafsir politik akan mengakibatkan suasana adegan demi adegan mungkin akan lebih menonjolkan kegentingan-kegentingan dan ketakutan-ketakutan akan masyarakat yang satu persatu berubah menjadi badak. Tapi apabila roh naskah ini dilepaskan dari kesadaran politik dan semata-mata ditempatkan pada sebuah “peristiwa absurd” maka bisa saja dimainkan dengan banyak memasukkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih cair.
Pada titik ini memang sebuah kelompok teater diberikan kebebasan memilih. Semuanya sah. Lagi pula memang banyak situasi-situasi dalam naskah Badak Badak yang memiliki potensi diartikulasikan dengan akting dan suasana setengah komedi. Sebuah kelompok teater yang ingin banyak menggaet penonton umum tentu mempertimbangkan hal ini karena tontonan kemudian akan menjadi sebuah pentas yang serius tapi juga menghibur.
Agaknya pilihan kedua itulah yang menurut saya dijalankan oleh Kelompok Sandiwara Mantaka. Dalam banyak adegan, saat warga merespon suara-suara badak, akting dibubuhi suasana komikal. Kepanikan-kepanikan yang muncul akibat ancaman badak tidak menjadi peristiwa yang betul-betul dramatis – menegangkan tapi diselipkan ekspresi-ekspresi yang bisa membuat penonton tertawa. Bahkan beberapa aktor cenderung di sana sini menggunakan kesempatan untuk melucu. Terutama tokoh Dewi yang sepanjang adegan berakting dengan suara yang dibuat-buat. Suara dan akting yang cenderung dipola melengking itu sampai pentas akhir dibiarkan oleh sutradara.
Persoalannya memang mungkin sulit untuk mengkontekstualisasikan naskah Badak Badak ini ke situasi sosial-politik Indonesia. Syahdan tatkala karya Ionesco ini dipanggungkan di Perancis akhir tahun 50 an semua penonton saat itu langsung mengerti bahwa idiom badak badak sesungguhnya menyasar kepada agresi pasukan Nazi dan tank-tank Nazi.
Semerntara saat naskah ini diadaptasi ke bahasa Indonesia oleh Jim Adhi Limas di Bandung tahun 60 an (yang dipakai sebagai teks rujukan oleh Kelompok Sandiwara Mantaka) sama sekali tak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa politik yang ada. Naskah ini seolah diadaptasi dengan steril. Namun toh bukannya tanpa peluang. Dalam ucapan salah satu tokoh yang ketakutan disebut orang-orang pertama di kota yang bertransformasi menjadi badak justru adalah para pejabat dan para tokoh-tokoh elite kota. Para pejabatlah yang kulitnya menjadi tebal dan kemudian bercula. Bila suasana ini diberi nada besar dalam pementasan, pertunjukan bisa menjadi sangat aktual dan sangat satir, karena problem pejabat yang bermasalah karena berbagai hal adalah problem kita hari-hari ini. Tapi kemungkinan satir sosial seperti ini dilewatkan oleh Kelompok Sandiwara Mantaka.
Bui produksi Teater Jannien
Upaya melakukan tafsir berbeda dicoba dilakukan oleh Teater Jannien saat mementaskan Bui karya Akhudiat di Teater Luwes. Umumnya kelompok yang memanggungkan naskah ini akan membagi panggung menjadi dua “sel penjara” yang berhadapan. Dua sel itu adalah ruang pengap bagi dua tahanan. Sementara ruang di tengah sel itu akan menjadi areal permainan dan konflik dua tahanan tersebut dengan sipir-sipir penjara.

Foto pementasan Bui produksi Teater Jannien (1). (Foto: Seketi Tewel)
Teater Jannien yang disutradarai Heri Jambul tak menghadirkan sebuah set yang menampilkan dua aktor di dalam jeruji. Tak ada adegan-adegan dimana dua aktor dikesankan berada dalam kerangkeng atau berdialog antar sesama napi dari balik jeruji. Begitu memasuki Teater Luwes kita melihat konsep pemanggungan yang lain. Proscenium yang biasanya menjadi tempat permainan menjadi lokasi meja para juri. Dan di situ digeletakkan palu martil pengadilan seolah para juri ditempatkan sebagai hakim yang memvonis kasus. Sementara bagian belakang Teater Luwes yang biasanya menjadi tempat meja juri dipasang sebuah bidang lebar yang mengesankan jeruji-jeruji tahanan, pagar penghalang atau pagar kawat berduri.
Kursi-kursi penonton diposisikan di kanan kiri antara bidang kawat penghalang dan proscenium. Sementara areal akting berada di tengah. Adegan awal cukup menjanjikan. Dari atas video digital disorot membentuk sebuah image bergerak berupa arus lingkaran yang memutar-memutar di areal akting. Seorang aktor yang memerankan tahanan berdiri di atas arus pusaran itu. Ia seolah terseret dalam pusaran. Terlihat Teater Jannien ingin memasukkan unsur-unsur mapping digital untuk mengolah pementasan.
Persoalannya sepanjang adegan baik olahan digital maupun konsep ruangan yang berbeda hanya cenderung ditempatkan sebagai asesoris belaka. Akting kedua pemain yang menjadi tahanan kurang mampu menjadikan ruang sebagai sebuah simbol penjara yang penuh ”kekerasan”. Dua tahanan itu adalah seorang guru yang baru masuk tahanan melalui proses pengadilan dan satu tanpa proses pengadilan. Sayang kedua aktor ini kurang mengesplorasi situasi di sekitarnya. Bidang berupa kawat penghalang yang dipasang di Teater Luwes sesungguhnya potensial sekali dieksplorasi karena dapat menimbulkan imaji tentang kamp-kamp tahanan dan kekerasan di dalamnya. Benda ini sama sekali tidak disentuh oleh kedua aktor. Kawat hanya menjadi pajangan saja.
Naskah Akhudiat memang bukan naskah realis betul. Banyak adegan dipenuhi cerocosan kalimat yang lebih mirip permainan bunyi. Tapi naskah Akhudiat memiliki kemungkinan besar bagi sebuah kelompok teater untuk melakukan eksprimen dan permainan tubuh aktor dengan benda-benda yang biasanya ada dalam penjara. Elemen-elemen dan benda-benda yang ada dalam penjara seperti: sepatu lars, rantai tanga, gembok sel, terali, peluit-peluit pemeriksaan, sapu-sapu pel, piring rangsum, lonceng, tong air, suara pestol semua ada dalam naskah Akhudiat. Semuanya itu bisa dijadikan adegan yang kaya dan mencekam. Memang dalam pertunjukan Teater Janin terdapat adegan piring-iring yang dilemparkan para napi, air yang diguyurkan dari ember para sipir tapi itu hanya sepintas lalu dan tak menjadi irama pertunjukan.
Interaksi antara dua tahanan dengan para sipi yang menguasai alat-alat kekerasan dalam penjara dengan kata lain kurang dimaksimalkan. Dalam naskah dapat dibaca sang sipir selalu melakukan dominasi. Sipir adalah penguasa rangsum. Jam jam makan ditentukan oleh sipir. Sipir mempermainkan para tahanan dengan membuat mereka saling berkelahi berebutan piring rangsum. Sipir pun bisa seenaknya menggebuk tahanan dengan sapu pel. Dalam pemanggungan Teater Jannin, simbol intimidasi sipir ini tak begitu tampak. Dalam naskah Akhudiat sang sipir kemudian mempermainkan kedua tahanan dengan seolah melepaskan tikus ke dalam sel hingga membuat ribut para tahanan sampai berkelahi. Adegan tikus itu memang ada dalam pementasan Teater Jannin namun seolah lepas konteks dari persoalan kekuasaan sang sipir.

Foto pementasan Bui produksi Teater Jannien (2). (Foto: Seketi Tewel)
Sebaliknya sutradara menonjolkan adegan homo seksual antara tahanan yang nota bene guru. Adegan homo dimulai dengan adegan tahanan lama memanggul sang guru. Mereka kemudian bergumul dan kemudian terengah-engah menandakan ada hubungan seksual. Mereka berdansa. Tak cukup berhenti di situ. Agaknya sutradara hendak menjadikan hubungan seksual itu sebagai hal utama. Sang guru yang berkostum putih-putih lalu mngenakan BH dan celana dalam merah . “Jadi konak nih. Bang pelan-pelan…” BH dan CD memang ada dalam naskah Akhudiat tapi hanya sekilas. Adalah sah-sah saja menafsirkan seks dalam penjara. Dalam naskah Akhudiat saat kedua tahanan itu berimaji mereka berdua adalah kucing jantan dan betina yang tengah mengejar tikus memang disyaratkan adanya adegan main-main percintaan itu. Namun eksekusinya di sini terasa berlebihan dan banal.
Pada bagian akhir berbagai sorot video bergambar mobil luks, rumah-rumah mewah, gambar-gambar kasus-kasus di televisi tentang korupsi sampai patung dewi keadilan Athena disorotkn dari atas ke areal akting. Namun yang sampai ke kita semua itu hanya sekedar ilustrasi indah-indahan saja. Persoalan penjara, kekerasan dan keadilan sampai pertunjukan ini selesai terasa kurang menggumpal.
Langitku Biru Darahku Biru produksi Teater Cahaya
Tempo permainan berjalan lambat. Tuturan-tuturan pengucapan bergerak lamban. Ini seputar kisah cinta yang klise. Dimainkan oleh empat aktor (plus dalang) yang semua nama-namanya diinisialkan dengan nama-nama warna. Biru (Lulu) adalah seorang gadis yang cantik dari keluarga sederhana. Ia dicintai oleh seorang pemuda dari kalangan berada bernama Mamat (hijau). Sang ibu (Putih) yang janda amat mengharapkan anaknya menerima cinta Mamat. Namun Biru menolak, bahkan ia lebih bisa berdialog dengan seorang buruk lelaki tua yatim piatu (Tanpa warna).

Foto pementasan Langitku Biru Darahku Biru produksi Teater Cahaya (1). (Foto: Seketi Tewel)
Pengadegan di panggung tidak menonjolkan adanya sebuah “peristiwa nyata” di sebuah set panggung. Masing-masing seperti lebih menampilkan “monolog” suara hati atau percakapan percakapan diri sendiri yang kecil. Kalaupun ada dialog senantiasa lalu disusul dengan suara-suara “solilokui” kecil. Percakapan antara Biru dan Hijau. Percakapan Putih dan hijau. Percakapan Biru dan tanpa warna – namun semuanya tak ada yang istimewa.

Foto pementasan Langitku Biru Darahku Biru produksi Teater Cahaya (2). (Foto: Seketi Tewel)
Kalimat-kalimat dalam dialog tak nampak dikaitkan dengan esensi warna-warna. Tak jelas mengapa mengaitkan nama-nama tokoh dengan biru, hijau, putih. Adegan dimulai dengan adegan dalang topeng yang bertutur tentang percintaan sejoli yang berbeda kelas. Lalu tarian Tumenggung ditarikan disajikan semua pemain apa adanya. Meski diawali dengan tari topeng sepanjang adegan sama sekali tidak ada roh kekuatan teater rakyat yang rancak, dinamik dan bertenaga. Cara dalang mengintervensi adegan juga tak menunjukkan hal baru. Banyolan-banyolan sang dalang juga “garing.” Ungapan-ungkapan hati para tokoh cenderung berperetensi melankolis. Bila dengan cara dimaksudkan oleh sutradaranya Syukron ingin menimbulkan sensasi puitis – hal itu tak sampai.
Legenda Anak Negri produksi Teater Madilog Art
Gagasan dasar pementasan kelompok ini menarik. Para tokoh utama dongeng-dongeng nusatara muncul mendatangi seorang pendongeng. Mereka memprotes dan menginginkan sang pendongeng meluruskan jalan cerita. Selama beratus-ratus tahun mereka menganggap jalan cerita mengenai diri mereka salah dan merugikan mereka. Malin Kundang, Joko Tarub, Dewi Nawang Wulan bersama rombongan bidadari kahyangan dan sebagainya yang selama ini dalam dongeng pun tak pernah ketemu tiba-tiba bisa berkumpul bersama.

Foto pementasan Legenda Anak Negri produksi Teater Madilog Art (1). (Foto: Seketi Tewel)
Mulanya pertunjukan teater ini lebih mirip teater anak-anak. Sekelompok anak-anak duduk setengah melingkar mendengar seorang pendongeng bercerita. Anak-anak ditempatkan dengan porsi besar, mereka saling mengomentari dongeng. Pengadegannya juga cenderung seperti pengadegan teater anak-anak. Tapi kemudian saat rombongan kahyangan dan barisan Minang mulai muncul, kita tahu orang dewasa pun ikut bermain.
Menarik mencermati bagaimana satu persatu tokoh tokoh fiktif foklor nusantara itu muncul dan mengekspresikan gerak geriknya. Malin Kundang memprotes mengapa ia disebut anak durhaka dan memperagakan ketrampilan silek atau silat Minang. Adegan ibu-ibu tua berusaha berebutan menyambut hangat dirinya oleh Malin Kundang diperlihatkan untuk menunjukan justru ia disayangi seluruh ibu-ibu di Minang dan bukannya ibu-ibu malah mengutuk dirinya jadi batu. Loro Jonggrang juga memprotes mengapa dia dalam dongeng kemudian dijadikan arca matu. Sosok berkostum raksasa wayang wong dalam kisah Bandung Bondowoso yang membantu Bandung Bondowoso membangu Prambanan juga menolak keras disebut sebagi jin dalam dongeng. Adegan cukup seru tatkala tiba-tiba tokoh Pitung dari Betawi masuk dan melakukan perkelahian dengan Malin Kundang. Silat Betawi melawan Silek Padang.

Foto pementasan Legenda Anak Negri produksi Teater Madilog Art (2). (Foto: Seketi Tewel)
Sesungguhnya pentas ini berpotensi sebagai tontonan yang “bermind set” kontemporer. Munculnya berbagai tokoh wayang, tokoh silat, tokoh bidadari-bidadari kahyangan, tokoh tokoh legenda nusantara dalam satu ruangan dengan kostumnya sendiri-sendiri berpeluang menjadi suatu cerita yang tidak klise. Membenturkan aneka fiksi, foklor nusantara dan antar tokoh dalam dongeng saling berkelahi sendiri atau merencanakan sesuatu adalah gagasan segar. Tatkala para tokoh dongeng akhirnya bersama-sama mengangkat tubuh pendongeng karena ia tetap bersikeras mempertahankan dongengnya sesunguhnya pentas ini bisa menjadi sebuah kisah pemberontakan yang lain daripada lain.
Pementasan ini tapi kemudian cenderung memberikan nasehat-nasehat. Pementasan ini terlihat lebih berorientasi sebagai teater pendidikan atau teater didaktik yang sarat pesan-pesan moral. Pesan agar kekayaan bangsa terjaga dan senantiasa dipelihara. Pada titik ini walaupun menampilkan banyak aktor orang dewasa namun pertunjukan tetap berspirit untuk ditujukan kepada anak-anak. Pementasan teater ini lebih seperti dalam kerangka teater pengajaran atau pertunjukan paedagogik.
Gelombang Gelumbung Lumbung produksi Teater Confeito
Pentas yang disutradari Heri Purwoko ini lebih menampilkan fragmen-fragmen yang terkesan tidak berhubungan satu sama lain. Tiap fragmen berusaha menonjolkan kekuatan visual. Unsur-unsur seni rupa dan gerak kuat dalam fragmen-fragmen itu.

Foto pementasan Gelombang Gelumbung Lumbung produksi Teater Confeito (1). (Foto: Seketi Tewel)
Fragmen pertama menampilkan tiga manusia yang bergerak dalam bungkus-bungkus seperti plastik. Mereka adalah manusia-manusia gelembung. Mereka bergerak perlahan. Bersamaan dengan itu backdrop menampilkan visual muti media berupa tetes tetes air. Muncul kemudian sesok laki-laki mondar mandir ke sana kemari mencai Uma.Dia mendekati manusia-manusia plastik itu. “Uma, Uma kamu bukan Uma,”teriaknya. Siapa Uma kita tak tahu.
Fragmen ini kemudian disusul fragmen adegan seorang nenek di sebuah kawasan berbatu padas yang menaburkan pakan bagi ayam-ayamnya. Angin menderu kencang membuat pakan-pakan ayam tersapu. Seseorang dengan ikatan kain yang melambai-lambai bergerak menyimbolkan deru angin. Sang nenek menyalahkan angin.
Fragmen berikutnya menampilkan seorang laki-laki terseret ganasnya laut. Tiga kain putih panjang direntangkan dan digelombang-gelombangkan membentuk imaji laut. Hal demikian bukanlah sesuatu yang asing dalam tata artistik pentas-pentas tari kita. Dalam dunia pementasan tari sering diciptakan imaji gelombang laut melalui medium kain panjang .Dari pementasan sendra tari klasik Ramayana di Prambanan sampai pentas kontemporer Sardono W Kusumo pernah menggunakan idiom-idiom seperti itu. Pada fragmen tampak seorang aktor membawa miniatur sebuah perahu. Ia seperti terombang ambing, timbul tenggelam – hilang muncul dalam air. Tata cahaya cukup menimbulkan efek estetis pada adegan itu.

Foto pementasan Gelombang Gelumbung Lumbung produksi Teater Confeito (2). (Foto: Seketi Tewel)
Pada fragmen terakhir terlihat seorang lelaki duduk di bongkahan batu padas memainkan jerami kering. Seseorang datang memangul padi. Anak laki-laki itu berdialog mengenai lumbung dan memperhatikan petani itu bergerak ke arah lumbung dan kemudian pergi. Tapi kemudian datang serbuan ayam-ayam yang diperankan beberapa aktor. Teriakan bencana, bencana disuarakan. Ayam-ayam itu menotoli dan merusak padi-padi. Terasa tidak ada koneksi langsung antara fragmen ini dengan fragmen pertama sampai ketiga meski di fragmen terakhir itu anak-anak lelaki tersebut meneriakkan kata Uma sebagaimana laki-laki di fragmen pertama dan ayam-ayam juga diperlihatkan menyerang gelembung-gelembung yang ada di fragmen pertama hingga gelembung pecah dan membuat penari di dalamnya keluar.
Satu-satunya tanda semiotik yang bisa mengaitkan ketiga fragmen secara “konsisten” adalah rekaman suara tatkala transisi. Di tiap transisi – dalam kegelapan menguar rekaman suara percakapan antara sepasang suami istri yang membicarakan persoalan-persoalan domestik dari problem di kantor, susahnya pekerjaan sehari-hari, masa depan anak-anak sampai tarif parkir naik. Percakapan itu menyambung dari transisi satu ke transisi lain. Sutradara agaknya ingin mempertautkan tiga fragmen di atas dengan situasi aktual yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Mungkin begitu. Tapi kita masih tetap susah mencari kaitan logis antara narasi rekaman percakapan dengan pertunjukan “teater visual” di panggung.
-----SJS-----