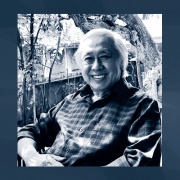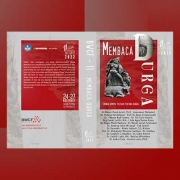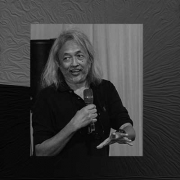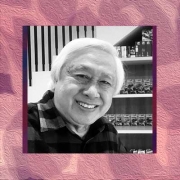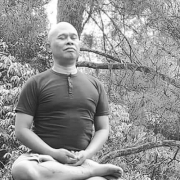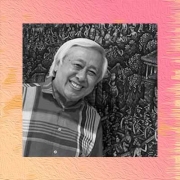Membaca Nisan-nisan Tua Nusantara: Menggali Harta Karun Arkeologi, Filosofi, dan Sanad Tarekat Masa Lampau
Menyambut Borobudur Writers and Cultural Festival 2025
Oleh: Gus Nas Joga*
Nisan—batu penanda peristirahatan terakhir—seringkali dilihat sekadar sebagai penanda kubur, batas fisik antara dunia fana dan keabadian. Namun, bagi seorang arkeolog sejarah dan seorang penempuh spiritual, nisan-nisan tua Nusantara adalah lebih dari itu. Mereka adalah arsip statis peradaban, menyimpan data epigrafi, ornamen artistik, dan yang terpenting, sanad spiritual yang tersembunyi. Membaca nisan adalah upaya epistemologis: menggali pengetahuan dari materi yang diam.
Nisan di Nusantara terbagi dalam berbagai tradisi, dari batu tegak khas tradisi megalitik hingga nisan pasai dan nisan Aceh yang mewah dengan kaligrafi indah. Mereka merefleksikan ekosistem kebudayaan yang dinamis di mana Islam tidak datang sebagai tabula rasa (lembaran kosong), tetapi berdialog intens dengan pra-kondisi kultural lokal.
Secara filosofis, nisan mewakili batas eksistensial manusia. Ia adalah titik di mana waktu—sejarah yang dicatat pada batu—bertemu dengan keabadian—janji eskatologis yang tertulis pada kaligrafi. Dalam konteks Nusantara, nisan adalah jembatan antara Arkeologi Sejarah –kapan Islam tiba, siapa yang memimpin– dan Arkeologi Spiritual –bagaimana tasawuf mengakar–.
Arkeologi Sejarah: Batu Nisan sebagai Kronik Peradaban
Studi mengenai nisan-nisan tua, seperti yang dilakukan oleh J.P. Moquette pada nisan Malikussaleh (w. 1297 M) di Pasai, membuktikan kehadiran Islam jauh lebih awal dari dugaan sebelumnya. Nisan-nisan ini, terutama yang bergaya Gujarat atau Persia, tidak hanya mencatat tanggal wafat, tetapi juga jabatan (Sultan, Syekh, Malik) dan nasab (keturunan).
Namun, nilai tertinggi nisan bukan pada materialnya, melainkan pada inskripsi yang terukir. Kaligrafi tsuluts atau kufi yang sering memuat ayat suci, hadis, atau untaian syair tasawuf, adalah bukti keras bahwa Islam yang masuk adalah Islam yang akrab dengan tradisi intelektual dan seni tinggi.
Nisan membantah narasi linear sejarah. Mereka menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara adalah fenomena yang multisentris dan berlapis. Keberagaman gaya nisan—dari yang sederhana di pedalaman Jawa hingga yang megah di pesisir Aceh—menjelaskan bahwa Islam dianut melalui berbagai jalur sosial, ekonomi, dan politik. Nisan adalah dokumen perjumpaan antara identitas lokal (ditunjukkan oleh bentuk batu atau ornamen flora) dan identitas universal (ditunjukkan oleh kaligrafi Arab).
Nilai Spiritual Keagamaan dan Sanad Tarekat
Di balik inskripsi formal, nisan-nisan ulama dan sufi Nusantara menyembunyikan sanad—rantai transmisi pengetahuan spiritual dan tarekat. Dalam tradisi tasawuf, sanad adalah vitalitas dan keabsahan ajaran.
Banyak nisan ulama besar, terutama yang berasal dari abad ke-16 hingga ke-18, tidak hanya mencantumkan nama dan gelar, tetapi terkadang juga isyarat keanggotaan tarekat. Misalnya, penggunaan istilah tertentu seperti al-arif billah (yang arif dengan Allah) atau kutipan dari Kitab al-Hikam yang mengindikasikan koneksi dengan Tarekat Syattariyah atau Qadiriyah.
Melalui Nisan kita bisa menziarahi Pemikiran Ulama dan Manuskrip berikut:
1. Syekh Abdul Rauf Singkil (w. 1693 M), salah satu ulama kunci dalam Tarekat Syattariyah di Aceh dan Nusantara. Meskipun nisannya mungkin tidak mencantumkan sanad secara eksplisit, keberadaan makamnya menjadi pusat ziarah yang menegaskan barakah (keberkahan) dan silsilah tarekat. Ajaran Martabat Tujuh –kosmologi sufistik– yang ia kembangkan melalui manuskripnya, seperti Kitab Daqā’iq al-Hurūf, menunjukkan kedalaman pemikiran metafisik yang menjembatani alam fisika dan hakikat. Nisan beliau adalah penanda geografis dari pusat transmisi Syattariyah.
2. Syekh Yusuf al-Makassari (w. 1699 M), ulama yang berlayar jauh ke Yaman dan Damaskus untuk mendapatkan sanad Tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, dan Naqsyabandiyah. Nisannya di Makam Pa’baeng-Baeng, Makassar, adalah penanda fisik dari globalisasi spiritual Nusantara. Ia adalah contoh nyata bagaimana ulama Nusantara secara aktif mencari dan membawa pulang sanad mu’tabarah –sahih. Karyanya, Tuhfat al-Mustafid, membahas penyatuan eksistensi, menegaskan ajaran wahdat al-wujud –kesatuan wujud– yang dikemas secara etis.
3. Haji Hasan Mustapa (w. 1930 M), pujangga Sunda yang pemikirannya tentang Wujudiyyah –esensi wujud– dan Filsafat Sunda terekam dalam naskah-naskah berbahasa Sunda-Pegon. Meskipun hidup lebih modern, makamnya di Bandung menjadi simbol sintesis antara keulamaan tradisional dan pemikiran modernitas. Pemikirannya sering mengutip Al-Ghazali, Rumi, dan Hamzah Fansuri.
Nisan-nisan ini secara kolektif membentuk peta spiritual Nusantara, membuktikan bahwa tarekat bukan sekadar ajaran ritual, melainkan sebuah jaringan intelektual yang mengikat ulama dari Aceh hingga Sulawesi dalam satu silsilah guru-murid yang tidak terputus.
Ekosistem Kebudayaan: Nisan dalam Perspektif Filsafat Sejarah
Nisan tidak berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari ekosistem kebudayaan yang meliputi masjid tua, pondok pesantren, dan tradisi ziarah (berkunjung). Makam para ulama besar sering menjadi cikal bakal permukiman dan pusat pendidikan keagamaan.
Dari sudut pandang Filsafat Sejarah –seperti yang ditawarkan oleh Toynbee atau Ibnu Khaldun, nisan mencerminkan respons peradaban terhadap krisis dan perubahan. Ketika Kerajaan Hindu-Buddha mengalami transisi, Islam masuk melalui medium kultural yang tidak konfrontatif, dan nisan menjadi penanda permanen dari transisi identitas ini.
Nisan, dengan inskripsi kematian (inna lillahi wa inna ilaihi raji’un), mengajarkan filosofi transiensi –ketidakabadian dunia. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu. Bagi komunitas di sekitarnya, nisan bukan objek yang menakutkan, melainkan sumber keberkahan (barakah) dan pengingat moral (ma’izhah).Hal ini sejalan dengan konsep Kosmologi Nusantara yang sering memandang garis vertikal (pohon, gunung, nisan) sebagai penghubung antara dunia bawah (bumi/makam) dan dunia atas (langit/ilahi). Islam berhasil mengislamisasi simbol-simbol kosmologis ini, mengganti kepercayaan lama dengan keyakinan tauhid, tetapi mempertahankan bentuk dan fungsi ritualnya (seperti penghormatan terhadap leluhur).
Membaca Diri di Batu Nisan
Membaca nisan-nisan tua Nusantara adalah sebuah proyek reflektif. Ini memaksa kita untuk melihat sejarah bukan hanya dari catatan istana atau kronik kerajaan –seperti Nagarakretagama atau Pararaton, tetapi dari suara sunyi yang diukir pada batu. Nisan adalah bukti bahwa penyebaran Islam adalah gerakan yang bersifat populis dan sufistik, didorong oleh para ulama yang membawa ajaran dengan sanad yang kuat dan integritas spiritual yang tinggi.
Setiap nisan adalah titik henti, meminta kita merenungkan pertanyaan eksistensial yang sama dengan yang direnungkan oleh ulama yang terkubur di bawahnya: Apa itu Wujud? Apa itu Cinta Ilahi? Bagaimana aku menyelaraskan syari’at (hukum) dengan hakikat (kebenaran)?
Dengan demikian, nisan-nisan tua bukan sekadar harta karun arkeologi; mereka adalah harta karun spiritual yang menyimpan warisan filosofis dan sanad keulamaan yang menjadi fondasi bagi ekosistem keagamaan Indonesia modern. Mereka adalah pengingat abadi bahwa di Nusantara, spiritualitas selalu terikat pada akar sejarah, tertulis abadi pada batu yang diam.
Deskripsi Reflektif: Nisan, Sanad, dan Peta Intelektual Nusantara
1. Epistemologi Nisan: Jejak Gujarat dan Persia
Deskripsi kita tentang nisan-nisan tua Nusantara dimulai dari kajian pionir arkeolog Belanda, J.P. Moquette. Pada awal abad ke-20, Moquette melakukan telaah mendalam terhadap nisan Pasai, khususnya Nisan Malikussaleh (raja pertama Samudra Pasai). Ia bukan sekadar mencatat keberadaan batu, tetapi ia menerapkan epistemologi nisan: mencari pengetahuan dari bentuk dan ukiran.
Moquette dengan cermat mencatat kemiripan bentuk nisan-nisan tersebut dengan gaya arsitektur pemakaman di Gujarat, India, dan Persia. Penemuan ini memberikan bukti kuat bahwa Islam tidak datang melalui jalan yang sunyi, melainkan dibawa oleh jaringan perdagangan dan intelektual yang terhubung erat dengan Samudra Hindia. Nisan-nisan ini, dengan bentuknya yang mewah dan kaligrafi yang anggun, adalah dokumen fisik yang menggeser kronologi kedatangan Islam di Nusantara dan menggarisbawahi peran pedagang-sufi dari Barat. Mereka adalah harta karun arkeologi yang berbicara tentang kosmopolitanisme Islam awal di Asia Tenggara.
2. Sanad Tarekat Syattariyah dan Kosmologi Martabat Tujuh
Nisan-nisan juga mengarah pada pusat-pusat spiritual. Salah satu figur paling berpengaruh adalah Syekh Abdul Rauf Singkil, ulama besar dari Aceh abad ke-17. Meskipun kita tidak selalu menemukan nisan yang secara eksplisit mencantumkan silsilah tarekat, makamnya menjadi penanda geografis dari pusat transmisi ajaran sufi.
Seperti yang ditelaah oleh Martin van Bruinessen dalam karyanya tentang Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Syekh Abdul Rauf adalah pilar utama penyebaran Tarekat Syattariyah di Nusantara. Ajarannya yang fundamental, terutama konsep Martabat Tujuh (seven grades of existence), yang tertuang dalam manuskripnya seperti Kitab Daqā’iq al-Hurūf, merupakan upaya filosofis untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan (Ahadiyyah) dan dunia ciptaan (Af’āl). Makam Syekh Singkil adalah simbol keberlanjutan sanad spiritual yang vital—rantai guru-murid yang mengikat ulama-ulama di seluruh kepulauan, memastikan keabsahan ajaran tasawuf yang mengakar di bumi Nusantara.
3. Globalisasi Spiritual dan Sanad Multinasional
Kajian tentang nisan juga mengungkap globalisasi spiritual yang terjadi ratusan tahun lalu. Sosok Syekh Yusuf al-Makassari adalah contoh sempurna. Makamnya di Pa’baeng-Baeng, Makassar, adalah titik akhir dari sebuah perjalanan intelektual dan spiritual epik. Syekh Yusuf tidak hanya menimba ilmu di Makkah, tetapi melintasi Yaman dan Damaskus untuk mendapatkan sanad Tarekat Khalwatiyah, di samping Qadiriyah dan Naqsyabandiyah.
Melalui manuskripnya, terutama Tuhfat al-Mustafid –Hadiah bagi Pencari Manfaat, Syekh Yusuf membahas konsep wahdat al-wujud dengan pemahaman yang mendalam, dikombinasikan dengan etika syari’at. Makam beliau, beserta karya-karyanya, adalah bukti bahwa ulama Nusantara bukanlah penerima pasif; mereka adalah agen aktif yang membawa pulang berbagai silsilah dan mengawinkannya dengan tradisi lokal. Nisan Syekh Yusuf adalah dokumentasi arkeologi dari jaringan ulama global Abad ke-17.
4. Nisan sebagai Dokumen Perjumpaan Kultural
Hasan Muarif Ambary, dalam telaahnya mengenai jejak arkeologis Islam, memandang nisan sebagai dokumen perjumpaan kultural. Nisan-nisan di Jawa, misalnya, seringkali mempertahankan bentuk dasar lingga-yoni atau memiliki ornamen flora dan fauna yang diserap dari tradisi pra-Islam, namun dihiasi dengan kaligrafi Arab yang tegas.
Nisan-nisan ini menunjukkan bahwa Islam di Nusantara mengalami sinkretisme seni yang halus. Proses islamisasi berjalan secara damai melalui medium kultural. Batu penanda kubur menjadi titik temu di mana identitas lokal (rasa estetika dan penghormatan terhadap leluhur) bernegosiasi dengan identitas universal Islam (tauhid dan bahasa Arab). Dengan demikian, nisan bukan sekadar penanda kematian, melainkan monumen hidup dari strategi budaya Islam Nusantara yang berhasil mengakar.
5. Filsafat Wujudiyyah dalam Konteks Lokal Sunda
Nisan tidak hanya milik pesisir. Di Jawa Barat, pemikiran filosofis terekam pada sosok Haji Hasan Mustapa, pujangga dan ulama Sunda modern. Meskipun hidup pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemikirannya adalah kelanjutan dari tradisi wujudiyyah –esensi wujud dan tasawuf yang mendalam.
Dalam naskahnya yang berbahasa Sunda-Pegon, Adat Pasundan Sareng Agama Islam, Haji Hasan Mustapa berupaya menyelaraskan adat istiadat Sunda dengan ajaran Islam. Ia menunjukkan bagaimana konsep-konsep lokal dapat dipahami melalui lensa tasawuf. Nisan beliau adalah simbol sintesis antara keulamaan dan kearifan lokal, menunjukkan bahwa filsafat spiritual di Nusantara bersifat inklusif, merangkul epistemologi setempat tanpa mengorbankan prinsip tauhid.
6. Nisan dan Kosmologi Transisi: Jaringan Ulama
Dari perspektif sosiologis, Azyumardi Azra menyoroti peran makam dan nisan dalam membentuk jaringan ulama Nusantara. Makam-makam besar menjadi simpul kekuasaan spiritual dan pusat ziarah yang menghubungkan masyarakat dari berbagai pulau.
Nisan, dalam konteks ini, menjadi bagian dari kosmologi transisi. Tradisi ziarah, yang merupakan adaptasi dari penghormatan terhadap roh leluhur, diislamisasi menjadi upaya mencari barakah (keberkahan) dan mengingat akhirat (ma’izhah). Nisan ulama-ulama abad ke-17 dan ke-18 adalah titik-titik jangkar bagi jaringan yang meluas hingga ke Timur Tengah, membuktikan bahwa identitas keagamaan Nusantara dibangun di atas silsilah intelektual yang terorganisir.
7. Nisan dan Epigrafi Abad Awal
Terakhir, kontribusi arkeolog Uka Tjandrasasmita sangat penting dalam memvalidasi kronologi. Melalui penelitian epigrafi, ia mengumpulkan data tentang nisan-nisan tertua di Indonesia.
Nisan-nisan ini, seringkali dengan ukiran yang minimalis namun tegas, memberikan bukti konkret dan penanggalan pasti mengenai awal mula Islam. Nisan adalah artefak yang membantu memverifikasi kronik lisan atau manuskrip yang mungkin mengandung bias. Mereka berfungsi sebagai validasi arkeologis yang kritis terhadap sejarah lisan, memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman kita tentang Islam sebagai peradaban yang berakar kuat dan terdokumentasi secara material di kepulauan ini.
Seluruh kajian ini menunjukkan bahwa nisan-nisan tua Nusantara adalah harta karun berlapis. Mereka adalah arsip batu yang tak hanya menyimpan data sejarah (Moquette, Tjandrasasmita), tetapi juga peta spiritual (Singkil, Syekh Yusuf), dokumen dialog budaya (Ambary, Mustapa), dan simpul jaringan sosial (Azra). Membaca nisan berarti membaca filsafat ketidakabadian yang diukir pada batu fana.
—
*Gus Nas Jogja, budayawan.