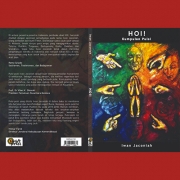Koperasi Seniman: Membangun Sanggar Bersama di Era Ekonomi Keserakahan
Oleh: Gus Nas Jogja*
Di sebuah Sanggar yang remang dan sunyi, seorang seniman duduk sendiri menyusun imajinasi. Wajahnya diterangi bukan oleh cahaya ilham, melainkan oleh pendar dingin layar gawai. Di layar itu, angka-angka menari—jumlah likes, views, shares. Angka-angka itu adalah hakim sekaligus juri bagi karyanya, menjadi takaran absah bagi eksistensinya. Ia merasa bebas, seorang kreator independen di era disrupsi, namun kebebasan ini terasa seperti ilusi. Ia adalah raja di kerajaan seluas layar sentuh, namun sekaligus budak dari algoritma tak berwajah yang menuntutnya untuk terus berproduksi, terus relevan, terus menjadi konten.
Inilah potret paradoks seniman di abad ke-21: seorang individualis agung yang terperangkap dalam mesin kolektif raksasa bernama Ekonomi Kerakusan. Sebuah sistem yang memuja “passion” hanya untuk mengeksploitasinya, yang menjanjikan panggung global namun hanya memberikan etalase digital yang sempit, yang mendorong seniman untuk menjadi merek pribadi (personal brand) hingga mereka lupa cara menjadi manusia. Jiwa mereka, yang seharusnya menjadi sumber karya, kini menjadi komoditas utama.
Dalam lanskap yang brutal ini, di manakah sang seniman bisa menemukan rumah? Di manakah ia bisa berlindung dari badai metrik dan tuntutan pasar yang tak pernah tidur? Jawaban itu mungkin datang dari arah yang paling tak terduga, dari sebuah konsep yang sering dianggap usang dan berdebu: Koperasi. Bisakah sebuah gagasan yang berakar pada kolektivitas—sesuatu yang tampak antitesis bagi jiwa seniman yang individualistis—menjadi bahtera penyelamat?
Jawabannya, secara mengejutkan, adalah sebuah “ya” yang tegas. Namun, ini bukanlah koperasi yang kita kenal. Ini adalah visi baru: sebuah Koperasi Merah Putih untuk para seniman, sebuah sanggar bersama di tengah cakrawala digital.
Anatomi Kerakusan: Penjara Emas Sang Seniman
Untuk memahami mengapa koperasi menjadi relevan, kita harus terlebih dahulu membedah anatomi penjara yang tak terlihat yang mengurung para seniman. Ekonomi Kerakusan di era disrupsi beroperasi melalui tiga tirani utama:
Pertama, Tirani Algoritma. Dulu, seorang seniman berdialog dengan kemanusiaan, dengan sejarah, dengan Tuhan. Kini, ia dipaksa berdialog dengan algoritma. Platform digital—baik itu layanan streaming musik, galeri NFT, atau media sosial—adalah kurator agung yang menentukan apa yang akan dilihat dan didengar. Algoritma tidak peduli pada kedalaman, kebaruan, atau kejujuran sebuah karya. Ia hanya peduli pada engagement. Seni yang “baik” adalah seni yang viral. Akibatnya, proses kreatif yang seharusnya merupakan sebuah penjelajahan spiritual (laku) direduksi menjadi kalkulasi pasar (laku jual).
Kedua, Tirani Individualisme Toksik. Mitos tentang seniman sebagai jenius penyendiri—sang serigala tunggal yang berjuang melawan dunia—adalah narasi yang paling disukai oleh Ekonomi Kerakusan. Mitos ini memecah belah para seniman, menempatkan mereka dalam arena kompetisi yang abadi untuk memperebutkan perhatian, dana, dan validasi yang terbatas. Mereka diajarkan untuk melihat sesama seniman sebagai rival, bukan sebagai kawan seperjuangan. Perpecahan ini membuat mereka lemah, tanpa daya tawar kolektif, mudah dieksploitasi oleh platform raksasa, galeri, atau label yang memegang kuasa.
Ketiga, Tirani Prekariat. Seniman adalah poster utama dari gig economy. Mereka adalah pekerja lepas abadi, hidup dari satu proyek ke proyek berikutnya tanpa jaring pengaman sosial, tanpa asuransi kesehatan, tanpa dana pensiun. “Passion” mereka dijadikan dalih untuk menormalisasi upah rendah dan kondisi kerja yang tidak pasti. Di dalam sistem ini, seniman tidak punya waktu untuk bereksperimen, untuk gagal, untuk merenung. Mereka harus terus “berkarya” hanya untuk bertahan hidup, mengubah studio mereka menjadi pabrik konten pribadi.
Pemberontakan Sunyi: Gotong Royong sebagai Filsafat Perlawanan
Di tengah krisis eksistensial ini, Koperasi untuk Seniman hadir bukan sekadar sebagai model bisnis, melainkan sebagai sebuah pemberontakan filosofis. Ia adalah sebuah deklarasi bahwa seni lebih dari sekadar konten, dan seniman lebih dari sekadar produsen. Ia adalah sebuah upaya sadar untuk menenun kembali jiwa Gotong Royong yang telah dicerabut oleh individualisme pasar.
Ini adalah sebuah kepulangan. Jauh sebelum ada galeri seni modern, para empu di Nusantara berkarya dalam sebuah ekosistem komunal. Ada sanggar, ada padepokan—ruang-ruang di mana pengetahuan diwariskan, kritik diberikan dalam semangat persaudaraan, dan karya diciptakan bukan untuk ketenaran pribadi semata, tetapi sebagai persembahan bagi komunitas atau Yang Ilahi. Koperasi untuk Seniman adalah upaya untuk membangkitkan kembali ruh sanggar ini dalam konteks abad ke-21.
Visi ini terangkum dalam konsep Koperasi Merah Putih: sebuah sintesis antara idealisme murni dan aksi yang berani, sebuah jawaban otentik Nusantara terhadap tantangan global.
Aspek “Putih”: Koperasi sebagai Benteng Jati Diri
Aspek “Putih” adalah tentang kemurnian tujuan, tentang jiwa, tentang mengapa kita berkarya. Bagi seniman, Koperasi Merah Putih berfungsi sebagai benteng spiritual yang melindungi esensi dari kerja kreatif mereka.
1. Mendefinisikan Ulang “Nilai”: Di dalam koperasi, nilai sebuah karya tidak lagi semata-mata diukur oleh algoritma atau pasar. Komunitas inilah yang menjadi kuratornya. Koperasi menjadi ruang aman untuk kritik yang membangun, dialog yang mendalam, dan apresiasi yang tulus. Ia mengembalikan validasi dari tangan mesin ke tangan manusia, dari likes ke empati.
2. Kedaulatan Proses Kreatif: Dengan sumber daya yang dimiliki bersama—studio, alat rekaman, ruang pamer, dana produksi—seniman dibebaskan dari tekanan untuk selalu menciptakan produk yang “pasti laku”. Koperasi melindungi hak seniman untuk bereksperimen, untuk mengambil risiko, untuk menciptakan karya-karya yang mungkin tidak populer namun penting. Ia menjaga kesucian proses, bukan hanya mengomersialisasi hasil.
3. Jaring Pengaman Kemanusiaan: Semangat Gotong Royong diwujudkan dalam bentuk dana kolektif untuk asuransi kesehatan, bantuan hukum, atau bahkan dana darurat saat seorang anggota menghadapi kesulitan. Ini adalah pengakuan bahwa untuk berkarya, seorang seniman harus terlebih dahulu bisa hidup sebagai manusia yang utuh dan terjamin.
Aspek “Merah”: Koperasi sebagai Pedang Aksi Kolektif
Jika “Putih” adalah jiwanya, maka “Merah” adalah tubuhnya—tindakan berani dan dinamis untuk merebut kembali kedaulatan di tengah pasar yang buas.
1. Daya Tawar Kolektif: Bayangkan sebuah koperasi yang beranggotakan ratusan musisi independen. Mereka tidak lagi bernegosiasi satu per satu dengan platform streaming raksasa. Koperasilah yang maju sebagai sebuah entitas tunggal, menuntut royalti yang lebih adil, transparansi data, dan perlakuan yang setara. Kekuatan individu yang kecil menjadi kekuatan kolektif yang dahsyat.
2. Membangun Ekosistem Sendiri: Koperasi Merah Putih tidak hanya bermain di platform orang lain; ia membangun platformnya sendiri. Sebuah layanan streaming musik milik para musisi, di mana algoritma dirancang untuk penemuan (discovery) dan keadilan, bukan eksploitasi. Sebuah galeri virtual milik para perupa, yang memotong rantai perantara yang mencekik. Sebuah penerbitan kolektif milik para penulis. Ini adalah aksi merebut kembali infrastruktur produksi dan distribusi.
3. Kedaulatan Data sebagai Aset Bersama: Di era digital, data adalah minyak baru. Koperasi seniman akan mengelola data pendengar, pembaca, dan penikmat seni sebagai aset kolektif. Data tersebut digunakan secara demokratis untuk memahami audiens, membangun komunitas, dan menciptakan model bisnis baru yang berkelanjutan—semuanya untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk dijual kepada pengiklan.
Paradoks Sang Individualis Kolektif
Lalu, bagaimana dengan ketakutan terbesar: apakah kolektivitas tidak akan membunuh individualitas, percikan jenius yang unik dari setiap seniman? Justru sebaliknya. Ekonomi Kerakusanlah yang membunuh individualitas dengan memaksa semua seniman untuk mengikuti tren yang sama yang didikte oleh algoritma.
Di dalam Koperasi Merah Putih, seniman bukanlah sekrup dalam mesin. Ia adalah simpul dalam jejaring. Kekuatan jejaring—infrastruktur, keamanan finansial, dukungan komunitas—justru membebaskan setiap simpul untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan tidak lagi menghabiskan 80% waktunya untuk administrasi, promosi, dan kecemasan finansial, seorang seniman memiliki kemewahan yang paling berharga: waktu dan kebebasan mental untuk benar-benar mencipta.
Koperasi tidak menuntut keseragaman gaya, melainkan menyediakan fondasi yang sama agar setiap gaya yang unik bisa mekar sepenuhnya. Tujuannya bukanlah kepasrahan pada kolektivitas, melainkan interdependensi yang memberdayakan.
Sanggar Baru di Cakrawala Digital
Koperasi untuk Seniman bukanlah sebuah utopia, melainkan sebuah keniscayaan logis bagi siapa pun yang peduli pada masa depan seni dan kemanusiaan. Ia adalah evolusi dari sanggar tradisional, sebuah rumah bersama yang kini dibangun dengan bata digital dan semen gotong royong.
Di dunia yang memaksa kita untuk membangun istana pasir individual yang rapuh di tepi pantai data yang ganas, koperasi menawarkan sesuatu yang radikal: sebuah ajakan untuk membangun dermaga batu bersama-sama. Dermaga itu mungkin tidak semegah istana-istana para raksasa teknologi, tetapi ia kokoh. Ia adalah tempat di mana setiap seniman bisa melabuhkan kapalnya dengan aman, memperbaiki layarnya yang sobek, dan bersiap untuk kembali menjelajahi samudra kreativitas yang tak terbatas.
Pada akhirnya, ini adalah sebuah pilihan eksistensial. Terus menjadi atom yang kesepian dan mudah dihancurkan dalam reaktor pasar, atau menjadi molekul yang stabil dan kuat dalam sebuah ikatan kebersamaan. Bagi seniman Indonesia, pilihan ini seharusnya tidak sulit. Jiwa Gotong Royong sudah ada dalam darah kita. Kini saatnya menenunnya kembali, bukan sebagai artefak masa lalu, melainkan sebagai cetak biru untuk masa depan yang lebih adil, lebih berdaulat, dan lebih manusiawi.
Gitu aja kok rumit!
——
*Gus Nas Jogja. Budayawan.