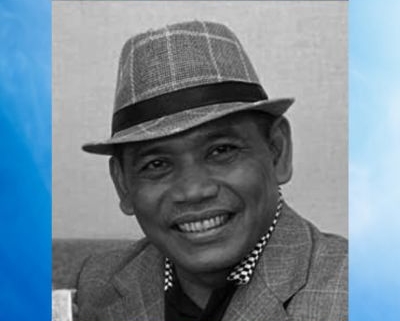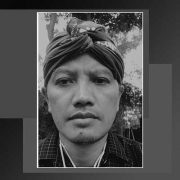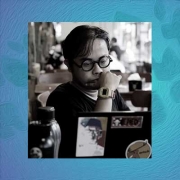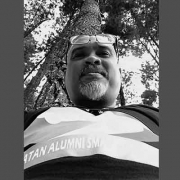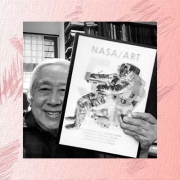Hari Kebudayaan: Antara Seremoni, Konspirasi dan Selebrasi
Oleh: Gus Nas Jogja*
Proyeksi Eksistensial Atas Penentuan Tanggal, Beban Bhinneka, dan Kiamat Budaya Digital
Seremoni: Kelahiran Sebuah Tanggal dan Ironi Pengakuan
Pada sebuah senja di tahun 2025, melalui SK Menteri Kebudayaan Nomor 162/M/2025, sang Menteri, Dr. H. Fadli Zon, secara seremonial menandatangani kelahiran sebuah tanggal: 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
Penetapan ini, pada tingkat permukaan, adalah sebuah tindakan afirmasi yang elegan, sebuah anggukan resmi dari Negara kepada Roh yang selama ini telah menghidupinya. Namun, bagi mata filsafat yang reflektif, muncul pertanyaan yang membayangi: Mengapa kebudayaan, sebuah entitas yang secara hakiki bersifat organik, abadi, dan melampaui waktu, harus dibatasi, dilingkari, dan diresmikan oleh sebuah angka kalender?
Seremoni adalah tindakan formalisasi. Ia menciptakan batas, menentukan awal dan akhir. Kebudayaan, sebagai Dasein kolektif—keberadaan kita yang terpapar dan terlempar ke dalam dunia—adalah sebuah sungai yang mengalir tanpa henti, mewarisi pasir dan lumpur dari setiap generasi. Ketika Negara, melalui birokrasi dan Surat Keputusan (SK), memutuskan untuk “memperingati” sungai itu, maka sungai itu seketika menjadi obyek, bukan lagi subyek yang mengalir bebas.
Ironi eksistensial pertama terletak pada kebutuhan untuk diakui. Kebudayaan Nusantara telah berdenyut selama ribuan tahun, dari ukiran candi hingga lantunan macapat di tengah malam, dari rempah-rempah Maluku hingga tarian Hudoq Kalimantan. Kehidupan sehari-hari adalah perayaan kebudayaan yang tak terputus. Tetapi, kita harus menunggu hingga tahun 2025, hingga sebuah kursi kekuasaan bergerak, untuk memberikan “pengakuan nasional” kepada dirinya sendiri. Ini adalah ironi kesadaran diri yang terderiva: Kebudayaan, sang ibu pertiwi, harus meminta izin kepada anaknya (Negara) untuk bernapas secara resmi.
Pilihan 17 Oktober, yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara Garuda Pancasila dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, adalah sebuah usaha untuk menambatkan perayaan kebudayaan pada jangkar historis yang paling kokoh: identitas politis. Ini bukan lagi sekadar perayaan tari dan lagu, melainkan perayaan Kontrak Sosial yang telah berumur puluhan tahun. Dan di sinilah, antara Seremoni dan sejarah, benih-benih Konspirasi mulai bersemi.
Konspirasi: Arkeologi Tanggal dan Dialektika Bhinneka
Konspirasi di sini tidak merujuk pada rencana jahat, melainkan pada konspirasi makna yang melekat pada setiap keputusan politik. Dalam filsafat politik, setiap formalisasi adalah tindakan untuk mengamankan narasi. Penetapan 17 Oktober adalah sebuah operasi arkeologi yang cerdas: menggali kembali tanggal penetapan simbol persatuan (Garuda dan Bhinneka) untuk menguatkan relevansi kebudayaan di masa kini.
Siapa yang berkonspirasi? Para seniman, budayawan, dan yang lebih penting, Menteri Kebudayaan. Ini adalah konspirasi untuk mewajibkan ingatan.
Konflik Antara Ritual dan Revolusi
Kebudayaan, dalam makna aslinya, adalah revolusi batin—sebuah tindakan kreatif yang terus-menerus mendobrak bentuk lama. Namun, Seremoni Hari Kebudayaan berisiko menjadikannya ritual rutin. Konspirasinya adalah ini: Negara menyukai ritual karena ia dapat diatur, dianggarkan, dan dievaluasi. Negara khawatir pada revolusi batin karena ia menghasilkan pertanyaan.
Audit Budaya, sebuah anekdot. Seorang auditor dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pernah datang ke Kementerian Kebudayaan. “Bapak Menteri,” tanyanya, “Bagaimana kami mencatat nilai estetika Tari Saman dalam neraca keuangan? Apakah barakah dalam keris pusaka termasuk aset non-moneter?” Sang Menteri menjawab, “Nilainya ada pada SK yang saya tanda tangani. Jika SK itu ada, berarti anggarannya sah. Budaya itu mahal, Tuan, karena ia harus mampu menjustifikasi biaya rapat di hotel bintang lima.”
Anekdot ini menyindir kegagalan wacana politik dalam menjangkau kedalaman spiritual kebudayaan. Kebudayaan menjadi ‘biaya tinggi’, bukan karena biaya produksinya, tetapi karena biaya justifikasi politiknya.
Beban Ganda Bhinneka Tunggal Ika
Pemilihan 17 Oktober secara eksplisit menambatkan Hari Kebudayaan pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Secara filosofis, semboyan ini adalah pisau bermata dua:
1. Mandat Eksistensial (Bhinneka): Pengakuan atas perbedaan yang tak tereduksi. Kebudayaan Jawa harus tetap Jawa, Minang harus tetap Minang. Ini adalah wilayah otentisitas Sartrean: Saya bebas memilih identitas kultural saya.
2. Kewajiban Politik (Tunggal Ika): Tuntutan untuk bersatu. Ini adalah wilayah struktur yang meminta agar perbedaan-perbedaan itu tunduk pada satu payung narasi kebangsaan.
Konspirasi di balik penetapan tanggal adalah upaya untuk mengendalikan dialektika ini. Negara ingin memastikan bahwa Bhinneka tidak menjadi terlalu liar hingga mengancam Tunggal Ika. Hari Kebudayaan menjadi semacam Katarsis Nasional Tahunan di mana perbedaan diizinkan meledak dalam perayaan selama 24 jam, hanya agar keesokan harinya, Tunggal Ika dapat menegakkan kembali ketertiban.
Menatap Cermin Abad Digital dan Krisis Karakter
Empat pertimbangan utama dalam penetapan Hari Kebudayaan—memperkuat karakter bangsa, modal pembangunan, pelestarian peradaban, dan pengakuan nasional—adalah empat janji profetik yang kini harus dihadapkan pada cermin dingin abad ke-21.
A. Karakter dan Pelarian Eksistensial
Pertimbangan pertama, memperkuat karakter bangsa, adalah janji yang paling berat. Dalam filsafat eksistensial, karakter adalah pilihan otentik yang diambil individu dalam menghadapi kehampaan. Apakah perayaan satu hari setahun mampu menambal erosi karakter yang terjadi 364 hari lainnya oleh arus disrupsi digital?
Di masa depan, kebudayaan yang paling terancam bukanlah bahasa daerah, melainkan bahasa keheningan (the language of silence). Budaya digital menuntut kita terus-menerus terhubung dan berproduksi. Jeda kultural—seperti ritual sunyi dalam meditasi Jawa atau duduk diam mendengarkan petuah adat—telah tergantikan oleh scroll tanpa akhir.
Hari Kebudayaan, jika gagal, akan menjadi sekadar kosmetik—memakai baju adat selama sehari untuk selfie di media sosial, lalu kembali tenggelam dalam anonimitas global keesokan harinya. Karakter tidak dibentuk oleh baju, melainkan oleh ketegasan batin untuk menolak in-otentisitas global.
B. Modal Pembangunan atau Proyek Museum?
Pertimbangan kedua, warisan budaya sebagai modal pembangunan, adalah pernyataan yang sarat optimisme futuristik. Kebudayaan diharapkan menjadi soft power Indonesia, mata uang yang diperdagangkan di pasar peradaban global.
Namun, ada risiko komodifikasi massal. Ketika budaya dijadikan “modal,” ia berisiko kehilangan jiwanya dan menjadi barang dagangan. Apakah Gamelan harus diubah menjadi ringtone agar dianggap “berharga”? Apakah Wayang harus diadaptasi menjadi augmented reality game agar dianggap “relevan”?
Di masa depan yang futuristik, tantangan terbesar adalah menjaga integritas seni. Ketika seorang dalang diminta mempersingkat lakon Mahabharata menjadi 15 menit agar sesuai dengan durasi TikTok, maka kebudayaan telah diserahkan kepada tirani algoritma. Hari Kebudayaan harusnya menjadi hari untuk menolak kecepatan, hari untuk kembali menghormati durasi yang panjang, rumit, dan mendalam.
Menatap horizon tahun 2100, Hari Kebudayaan 17 Oktober 2025 tampak seperti sebuah prasasti kuno yang penuh harapan. Bagaimana kebudayaan Nusantara bertahan di tengah peradaban kuantum?
Pelestarian di Blockchain dan Kiamat Arsip
Pertimbangan ketiga, perlunya pelestarian budaya untuk memengaruhi arah peradaban dunia, menuntut langkah futuristik. Di masa depan, kebudayaan akan hidup di dua tempat: dalam blockchain (sebagai arsip digital yang tidak dapat diubah) dan dalam ingatan neuro-digital (melalui implan memori).
Lelang NFT Naskah Kuno, sebuah anekdot. Dalam sebuah lelang futuristik di Metaverse Jakarta, Naskah Kuno Negarakertagama dilelang sebagai Non-Fungible Token (NFT). Sang pemenang, seorang kolektor asing, memamerkan hak kepemilikannya. Namun, ketika ada budayawan lokal yang ingin membacanya, ia harus membayar fee transaksi kripto. Ironinya, kebudayaan telah dilestarikan secara sempurna dalam kode, tetapi di saat yang sama, ia telah diasingkan secara sempurna dari pemilik spiritualnya. Arsip telah diselamatkan dari api, tetapi dibakar oleh firewall ekonomi.
Pengakuan Nasional vs. Otoritas Global
Pertimbangan keempat, pentingnya pengakuan nasional terhadap kebudayaan, akan menjadi usang di masa depan. Pengakuan sejati tidak datang dari SK Menteri, melainkan dari pilihan bebas manusia di seluruh dunia untuk mengadopsi atau merayakan nilai-nilai Nusantara.
Hari Kebudayaan sejati adalah ketika seorang anak di Tokyo menari tarian Sunda bukan karena tugas sekolah, melainkan karena ia memilih secara bebas (otentik) untuk menjadi bagian dari tradisi itu. Pengakuan nasional hanyalah langkah awal; tujuan futuristik adalah Pengakuan Universal, di mana Bhinneka Tunggal Ika menjadi model etika global.
Selebarasi: The Poetic Mandate dan Pilihan Otentik
Seremoni menetapkan tanggal. Konspirasi mengamankan narasi. Tetapi, hanya Selebarasi—perayaan yang tulus dan otentik—yang dapat menyelamatkan kebudayaan dari kekosongan makna.
Selebarasi adalah momen di mana individu melompat keluar dari kekangan SK dan algoritma, dan memilih untuk menjadi kebudayaan itu sendiri.
Mandat Puitis Budaya ialah:
• Jangan biarkan kebudayaan menjadi fosil yang dicium sekali setahun.
• Biarkan ia menjadi Darah yang Mendesak,
• Menuntut kita untuk menari di tengah kemacetan,
• Untuk berbahasa daerah di tengah rapat global,
• Untuk memilih gotong royong di atas profit individu.
Perayaan sejati adalah ketika Hari Kebudayaan tidak lagi menjadi kewajiban, melainkan sebuah kerinduan kolektif untuk kembali kepada sumber. Ia adalah sebuah tindakan melawan lupa, sebuah proyeksi diri ke masa depan sambil membawa seluruh beban dan keindahan masa lalu.
Kita, sebagai pewaris, memiliki beban eksistensial: menghidupkan kembali roh yang telah diresmikan. Jika kita gagal, 17 Oktober akan menjadi Hari Seremoni dan Konspirasi yang sepi, sebuah penanda tanggal mati di kalender. Jika kita berhasil, setiap hari akan menjadi Hari Kebudayaan, dan 17 Oktober hanyalah sebuah hari di mana kita berhenti sejenak, bersyukur, dan menegaskan kembali:
Kami Ada. Kami Berbeda. Kami Satu. Dan Kami Memilih untuk Abadi dalam Tari Kami.
Penutup: Ritual Abadi Kebudayaan
Hari Kebudayaan Nasional, 17 Oktober 2025, adalah sebuah paradoks. Ia adalah sebuah tanggal resmi yang menuntut kita untuk merayakan sesuatu yang seharusnya tidak pernah membutuhkan tanggal resmi.
Antara Seremoni formal birokrasi, Konspirasi politik narasi, dan potensi Selebarasi eksistensial, terletak pertarungan abadi jiwa Nusantara. Tugas kita adalah menembus Seremoni, memahami Konspirasi, dan kemudian, dengan tulus, merayakan Pilihan Otentik kita untuk menjadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika—bukan sebagai paksaan politik, melainkan sebagai takdir filosofis yang indah dan tak terhindarkan.
Kebudayaan adalah perjalanan pulang yang tak pernah berakhir. Selamat Hari Kebudayaan, hari di mana kita diingatkan bahwa kita bukan sekadar homo economicus di pasar global, melainkan homo culturalis yang berakar pada bumi yang kaya akan lagu, tari, dan makna.
Selamat Hari Kebudayaan Indonesia.
——-
*Gus Nas Jogja. Budayawan.