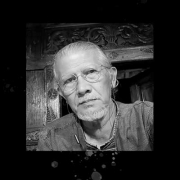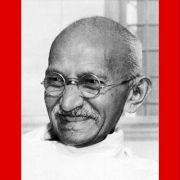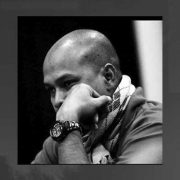“Happy Rain”, Satire, dan Etika Publik
Oleh Purnawan Andra*
Banjir yang kembali menggenangi Jakarta dalam beberapa hari terakhir tidak lagi datang sebagai kejutan. Ia hadir seperti tamu rutin yang sudah dikenal tabiatnya. Warga pun telah menyesuaikan jam berangkat, menghindari rute tertentu, menyiapkan sepatu cadangan, dan melanjutkan hidup dengan sedikit keluhan.
Tidak ada kepanikan kolektif, tidak ada kegentingan yang benar-benar terasa. Dalam konteks kebudayaan, absennya rasa kaget ini penting dibaca. Ketika sebuah gangguan besar berhenti mengejutkan, ia berhenti diperlakukan sebagai masalah. Ia berubah menjadi bagian dari keseharian.
Di titik inilah banjir tidak lagi berfungsi sebagai bencana, tapi sebagai rutinitas sosial. Sesuatu yang mengganggu, tetapi diterima. Bukan karena sudah selesai ditangani, tapi karena terlalu sering hadir tanpa penyelesaian.
Normalisasi ini bukan tanda kedewasaan, tapi tanda kelelahan kolektif. Masyarakat tidak lagi berharap banyak, dan dari situlah bahasa baru lahir untuk menamai keadaan.
“Happy Rain”
Salah satu bahasa itu muncul dalam bentuk satire ringan di media sosial: “happy rain”. Ungkapan ini tampak sederhana, bahkan jenaka. Ia menjadi semacam penghiburan di tengah hari yang macet dan basah.
Tapi jika dibaca secara kultural, “happy rain” bukan sekadar lelucon. Ia adalah bahasa pengganti. Bahasa yang muncul ketika harapan terhadap sistem sudah terlalu rendah untuk diekspresikan secara serius.
“Happy rain” bukan pernyataan bahwa hujan itu menyenangkan. Ia adalah cara aman untuk mengatakan bahwa kita sudah lelah mengeluh. Daripada marah dan kecewa berulang kali tanpa hasil, masyarakat memilih menertawakan situasi.
Tawa ini bukan tanda bahagia, tapi bentuk penghematan emosi. Sebuah mekanisme bertahan agar frustrasi tidak terus-menerus menggerogoti kehidupan sehari-hari.
Di sinilah pergeseran makna kebahagiaan jadi terlihat. Dalam wacana publik, kebahagiaan sering dipahami sebagai keadaan emosional positif. Tapi dalam praktik sosial hari ini, kebahagiaan lebih dekat dengan kemampuan untuk tetap berjalan meski kondisi tidak ideal.
Bahagia tidak lagi berarti hidup tertata, tapi tidak tumbang meski hidup semrawut. Dalam definisi seperti ini, bertahan menjadi prestasi, dan keluhan dianggap kelemahan.
Klaim Bahagia
Pergeseran makna ini menemukan momentumnya ketika klaim bahwa Indonesia adalah salah satu negara paling bahagia di dunia terus diulang. Klaim tersebut bukan sekadar data statistik, tetapi telah berubah menjadi narasi simbolik.
Ia menawarkan gambaran bahwa semua baik-baik saja, atau setidaknya cukup baik untuk tidak dipersoalkan terlalu jauh. Tapi ketika klaim ini berhadapan dengan pengalaman tubuh sehari-hari—berdiri berjam-jam di kemacetan, menerobos genangan, menata ulang rencana karena hujan—terjadi ketegangan makna.
Ketegangan ini bukan berarti masyarakat berbohong tentang perasaannya. Yang terjadi justru lebih rumit. Kebahagiaan telah didefinisikan ulang agar sesuai dengan kondisi yang ada.
Kita disebut bahagia bukan karena sistem bekerja dengan baik, tapi karena kita tidak memberontak meski sistem sering gagal. Dalam logika ini, kebahagiaan menjadi indikator ketahanan warga, bukan kualitas tata kelola.
Negara yang Sakit
Di titik inilah kita bisa mulai berbicara tentang negara yang sakit. Bukan negara yang represif, bukan negara yang penuh konflik terbuka, tapi negara yang terlalu santai menghadapi kegagalannya sendiri.
Negara yang tidak lagi menunjukkan rasa malu ketika masalah yang sama terulang. Banjir datang, lalu pergi, dan siklus ini tidak melahirkan rasa darurat yang nyata. Tidak ada bahasa krisis yang sungguh-sungguh mencerminkan kegentingan.
Ketidakhadiran rasa malu ini penting dicatat. Dalam budaya politik, rasa malu terhadap kegagalan adalah motor perubahan. Ia memaksa evaluasi, koreksi, dan perbaikan. Ketika rasa malu menghilang, kegagalan bisa diterima sebagai hal biasa. Dan ketika kegagalan menjadi biasa, warga didorong untuk menyesuaikan diri, bukan menuntut perubahan.
Dalam situasi ini, warga secara kultural diposisikan sebagai peredam sistem. Ketangguhan, kesabaran, dan keluwesan warga sering dipuji sebagai kekuatan bangsa.
Tapi pujian ini menyimpan problem. Ketika warga selalu bisa bertahan, sistem mendapat ruang untuk terus tidak siap. Ketika warga selalu bisa menyesuaikan diri, kegagalan struktural kehilangan urgensinya.
Banjir, dengan demikian, bukan sekadar soal curah hujan atau saluran air. Ia adalah ujian etika publik. Sejauh mana negara merasa gagal ketika kota lumpuh oleh hujan yang bisa diprediksi? Sejauh mana warga merasa pantas menuntut kehidupan yang lebih tertata? Ketika banjir tidak lagi memicu rasa gagal di tingkat kebijakan, persoalannya bukan teknis, tapi etos.
Satire “happy rain” menjadi penting karena ia berdiri di persimpangan ini. Ia bisa dibaca sebagai humor, tetapi juga sebagai gejala kebudayaan. Sebuah tanda bahwa masyarakat sedang berada di antara dua pilihan yaitu marah tanpa hasil, atau menertawakan keadaan agar tetap waras. Pilihan kedua memang lebih ringan, tetapi ia juga berisiko melanggengkan keadaan.
Esai ini tidak mengajak untuk menolak humor atau memusuhi tawa. Yang dipertanyakan adalah apa yang kita korbankan ketika humor menjadi respons utama terhadap kegagalan yang berulang. Jika setiap gangguan ditertawakan, kapan kita memberi tekanan agar ada perubahan? Jika bertahan hidup terus dipuji, kapan hidup yang layak diperjuangkan?
Pada akhirnya, persoalan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Bukan lagi soal apakah kita bahagia atau tidak, tapi sejak kapan kegagalan berulang berhenti terasa memalukan. Sejak kapan kemampuan bertahan menggantikan kewajiban untuk membenahi.
Jika hujan yang datang setiap tahun saja cukup melumpuhkan kota, dan kita menanggapinya dengan candaan yang ringan, mungkin yang perlu ditinjau ulang bukan cuaca, tapi cara kita memahami normalitas, tanggung jawab, dan makna kebahagiaan itu sendiri.
—-
*Purnawan Andra, pegiat Kelompok Kajian Kebudayaan “Wanyabala” Jakarta, penerima fellowship Humanities & Social Science di Universiti Sains Malaysia