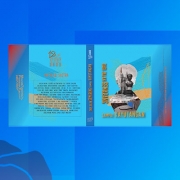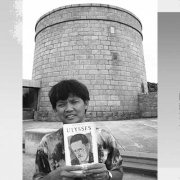Film, Pohon, dan Logika Ekologis Kita
Oleh: Purnawan Andra*
Dalam banyak kebudayaan Nusantara, pohon bukan sekadar benda hidup yang berdiritegak. Ia adalah penanda moral, ruang komunal, sekaligus representasi dari cara manusiamemahami posisinya di dalam jagat.
Namun dalam imajinasi pembangunan modern, makna ini perlahan disisihkan. Pohondipindahkan dari ranah kultural ke ranah statistik, dari ruang hidup menjadi kolom produksi, darientitas relasional menjadi sumber daya yang bisa diambil kapan saja.
Salah satu cara membaca perubahan imajinasi ini adalah melalui film. Ia menjadi media yang dapat memetakan ketegangan antara pengetahuan lama dan cara pandang baru yang dibangun negara maupun pasar.
Relasi yang Retak
Film tidak hanya merekam hubungan manusia dan pohon. Ia memperlihatkan bagaimanarelasi itu retak. Di dunia animasi, Nausicaä of the Valley of the Wind (1984) karya HayaoMiyazaki menunjukkan betapa rapuhnya peradaban yang memutus kaitannya dengan “pohon” sebagai penyeimbang dunia. Hutan beracun dalam film itu bukan musuh, melainkan mekanismealam untuk memurnikan tanah yang dirusak manusia.
Pohon dihadirkan sebagai agen ekologis, bukan objek. Representasi semacam inisejatinya dekat dengan pandangan kosmologis masyarakat Nusantara yang melihat pohonsebagai penjaga batas – antara tanah dan manusia, antara ruang hidup dan ruang sakral.
Imajinasi tersebut bukan mitos belaka. Ia berfungsi sebagai sistem pencegahan bencanasebelum istilah “mitigasi” dikenal dalam kebijakan negara.
Di banyak komunitas adat, pohon menentukan ritme kehidupan. Ia menjadi penandamusim, penunjuk arah air, sekaligus pengingat kapan manusia harus berhenti mengambil darialam. Namun film-film kontemporer sering menunjukkan bagaimana logika itu patah ketikapembangunan tak lagi menghitung daya dukung ekologis.
Film animasi The Lorax (2012) yang diisi suaranya diantaranya oleh Zack Efron, Taylor Swift dan Danny de Vito misalnya, menceritakan dunia yang kehilangan seluruh pohonnyaakibat kerakusan industri. Film ini memang dikemas sebagai cerita anak, tetapi substansimoralnya sangat jelas. Ketika pohon hilang, bukan hanya lanskap yang berubah, tetapi juga struktur moral masyarakat. Kehilangan pohon berarti kehilangan batas etis tentang bagaimanamanusia harus berperilaku.
Dari perspektif cultural studies, representasi pohon bukan semata ornamen visual. Iaadalah teks budaya yang memperlihatkan relasi kuasa. Bukan kebetulan bahwa film-film yang bertema lingkungan sering menempatkan korporasi atau negara sebagai pihak yang mengekstraksi pohon, sementara masyarakat lokal menjadi korban.
Ini tampak dalam Semesta (2018), film dokumenter Indonesia yang menampilkan tokoh-tokoh dari berbagai daerah yang mempertahankan pohon dan hutan mereka dari tekananekonomi. Film itu mengungkap satu hal penting yaitu bahwa bencana ekologis tidak pernahnetral. Ia lahir dari pertarungan antara dua model pengetahuan—pengetahuan lokal yang berorientasi keberlanjutan, dan pengetahuan modern yang berorientasi produksi.
Sisi Emosional
Film menjadi medium penting untuk memperlihatkan sisi emosional dari krisis ini. Banyak film menempatkan pohon sebagai simbol ingatan. The Tree of Life (2011) karya Terrence Malick menghadirkan pohon sebagai jangkar kosmik yang menghubungkan manusia denganmasa lalu dan masa depan.
Malick sendiri adalah sutradara yang kerap menempatkan tetumbuhan sebagai fokusvisual dalam film-filmnya. Makbul Mubarak (2011) mencatat bahwa dalam Badlands (1973), pelarian Kit (Martin Sheen) dan Holly (Sissy Spacek) membawa mereka melewati padangrumput di sepanjang mata memandang. Meskipun sepenuh tenaga menyelimpat, merekaakhirnya tertangkap di padang rumput itu juga.
Days of Heaven (1978) memeragakan ladang gandum yang bercengkerama sepanjangwaktu dengan para tokoh. Kejahatan jualah yang menyebabkan ladang gandum itu terbakarmemilukan.
Juga hampir semua adegan pertempuran dalam The Thin Red Line (1998) terjadi di tengah kepungan ilalang. Bahkan bisa dibilang bahwa para prajurit ini hanya bertempur kontrabatalyon ilalang mengingat musuh mereka tak pernah diperlihatkan.
Film The New World (2005) mematahkan hati pasangan sejoli Smith (Colin Farrell) danPocahontas (Q’orianka Kilcher) lalu menguburkannya di delta tepi hutan perawan Virginia.Pohon menjadi representasi kontinuitas, sesuatu yang lebih panjang umur dari manusia, tetapijuga mudah hilang karena satu keputusan manusia.
Dalam konteks Nusantara, ini mengingatkan kita pada beringin di alun-alun, pohon randudi tengah desa, atau pohon-pohon besar yang diperlakukan sebagai ruang musyawarah. Ketikafilm memperlihatkan pohon sebagai penanda memori, ia sedang mengarsipkan kehilangankultural yang sebenarnya juga sedang terjadi di dunia nyata.
Pergeseran Makna
Pergeseran makna pohon dalam film dapat dibaca sebagai bagian dari perubahan nilaimasyarakat. Film-film Indonesia generasi lama, mulai dari drama desa, komedi Betawi, hinggasinema Jawa, sering menempatkan pohon sebagai latar penting bagi dinamika sosial. Pohonmenyediakan tempat menunggu, berteduh, bermain, atau memulai percakapan yang menentukanalur cerita.
Kita nyaris tak menyadari bahwa pohon dalam film-film itu adalah ruang sosial. Namundalam sinema Indonesia masa kini, representasi semacam itu semakin jarang muncul. Ruangsosial bergeser ke kafe, kantor, atau ruang dalam bangunan—menandai perubahan cara kitabertemu dan bernegosiasi. Hilangnya pohon dalam sinema menggambarkan hilangnya pohondalam kehidupan.
Dalam film-film bertema bencana, pohon sering muncul sebagai korban pertama. Badaimenghancurkan hutan, banjir bandang membawa batang-batang kayu, tanah longsor menyeretakar-akar besar ke sungai. Namun film jarang memberi ruang untuk bertanya: mengapa pohonitu tumbang?
Representasi bencana yang menyalahkan cuaca atau alam sesungguhnya menutupi akarmasalah berupa eksploitasi ekologis yang berlangsung terus-menerus. Pohon digambarkansebagai “yang tersapu”, padahal pohon adalah “yang disapu setelah ditebang”. Representasi inipenting untuk dikritik agar film tidak memproduksi imajinasi keliru tentang siapa pelakusesungguhnya dalam bencana ekologis.
Relasi manusia-pohon dalam film memperlihatkan apa yang hilang dalam cara kitamemahami lingkungan. Ketika film menempatkan pohon sebagai pusat kehidupan seperti dalamfilm Avatar (2009, sutradara James Cameron), kita diingatkan bahwa keseimbangan ekologistidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu merupakan relasi, yaitu relasi spiritual, relasi sosial, relasiekologis.
Di Nusantara, relasi semacam ini pernah menjadi fondasi. Kini, ia menjadi arsip yang tersimpan dalam tradisi, cerita rakyat, dan film-film tertentu, tetapi tidak lagi menjadi basis pengambilan keputusan publik.
Karena itu, membaca film tentang pohon bukan sekadar membahas cerita. Ini adalahupaya memahami bagaimana budaya memaknai alam, bagaimana nilai-nilai ekologis digeseroleh logika ekonomi, dan bagaimana representasi visual dapat membantu kita mengkritik arahpembangunan.
Film memberi kita cermin: apakah kita masih melihat pohon sebagai bagian dari diri kita, atau hanya sebagai salah satu komoditas yang bisa disingkirkan atas nama pertumbuhan danpembangunan?
Film mengajarkan relasi manusia dengan pohon adalah relasi manusia dengan masa depannya sendiri. Ketika pohon hilang dari layar, hilang pula sebagian dari imajinasi ekologiskita. Dan ketika imajinasi itu padam, bencana tidak lagi terlihat sebagai peringatan, melainkansebagai normalitas baru.
Film-film yang menghadirkan pohon sebagai pusat narasi mengajak kita memulihkanimajinasi yang hilang, sebelum bencana menjadi satu-satunya bahasa yang mengingatkan kitabahwa pohon pernah menjadi bagian terdalam dari kearifan hidup kita.***
—-
*Purnawan Andra, lulusan Jurusan Tari ISI Surakarta, penerima fellowship Governance & Management of Culture di Daegu Catholic University, Korea Selatan.