Kerja Penghadiran dalam Medan Pasca-Sentuh Undisclosed Territory 13
Oleh Afrizal Malna
I Made Yogi Sugiartha memunculkan istilah “pasca-sentuh” pada karyanya “Ice See You”. Berlangsung dalam program Undisclosed Territory 13. Istilah ini digagas Sugiartha untuk memantulkan tema program, yaitu “Jarak” (Performing Distance), dengan konteks pandemi Covid-19.
Untuk saya, istilah ini membuat bentangan antara “jarak” dan “gerak” sebagai hukum dasar fisika: “Sebuah benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, selama tidak ada gaya yang bekerja terhadap benda itu (Newton)”. Kalau kita menyentuh benda itu, mendorong atau melemparnya, maka ada “gaya-sentuh” yang bekerja dan mengubah posisi benda. Di sisi lain, bila ada medan listrik, medan magnit atau gravitasi yang bekerja di sekitar benda, maka ada “gaya-tak-sentuh” yang bekerja dan mengubah kondisinya (Marga Surya: “Gerak Berbagai Benda di Sekitar Kita,” Kemendikbud, 2018).
Gerak, jarak, ruang, tubuh, objek, jeda dan durasi merupakan instrumen-instrumen primer yang banyak dibahas sejak Undisclosed Territory diluncurkan Melati Suryadarmo dari Studio Plesungan di Solo tahun 2007. Kelompok performance art “Black Market International” dari German ikut berkontribusi pada pembentukan awal Undisclosed Territory (terutama Boris Nieslony). Program ini, yang di dalamnya terdapat Pala (Performance Art Laboratori) digagas sebagai ruang riset kreatif dan sarana pengembangan bagi seniman yang menggunakan tubuh sebagai wahana utama berkarya. Saya mengikuti program ini sejak awal, dan untuk saya sudah seperti kampus dimana saya belajar banyak hal di sekitar praktik-praktik performance art yang beragam.
Instrumen-instrumen primer itu juga bukan sesuatu yang definitif. Mereka bekerja dalam banyak sudut pandang maupun pendekatan, dan membuatnya selalu dinamis dilihat dari luar maupun dilihat sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Pada tahap awal, program ini menggunakan model kurasi yang inklusif, cair, melihat siapa pun bisa berkonstribusi dalam performance art. Sambil menggunakan performance art sebagai evaluasi atas model-model penciptaan yang biasa dilakukan oleh masing-masing seniman dari berbagai disiplin yang terlibat. Dan sebaliknya, model-model penciptaan itu mendapatkan ruang alternatif dalam performance art. Pada tingkat ini, kurasi yang dijalankan secara inklusif mulai bergeser menjadi eksklusif, yaitu ketika produksi pengetahuan mulai mendapatkan momen pertemuan antar masing-masing seniman peserta sebagai lintas disiplin dan pemetaan pengetahuan mulai dilakukan.
Setiap pertemuan, dilakukan secara intim, seperti curhat, sebuah kesaksian, evaluasi, maupun sebagai dugaan-dugaan penuh keraguan. Ini membuat forum-forum pertemuan yang diproduksi Undisclosed Territory sering saya rindukan. Berlangsung antar bahasa-ibu (di samping Indonesia-Inggris), sambil duduk bersila atau nongkrong. Dan aksi performance selalu berlangsung di ruang outdoor. Alam terbuka memberikan ruang yang dinamis dan tidak defenitif atas perforrmance yang berlangsung.
Apakah yang terjadi dengan Undisclosed Territory 13, yang berlangsung di tengah-tengah pembatasan ruang akibat pandemi Covid-19?
Kali ini Undisclosed Territory mengundang 9 seniman dari berbagai disiplin (Senirupa, Tari, Teater, Musik, Film) dari berbagai kota (tanpa melibatkan seniman luar). Satu-satunya genre yang tidak dilibatkan adalah Sastra. Program laboratorim (Pala) sepenuhnya berlangsung secara online dalam beberapa pertemuan sejak 11 Desember 2021 hingga 8 Februari 2022. Di antaranya mengundang narasumber Martin Suryajaya dan Alia Swastika. Setiap pertemuan difasilitasi Melati Suryodarmo. Aksi performance berlangsung 16 Februari 2022 di Solo (Galeri Taman Budaya Jawa Tengah), 19 Februari 2022 di Yogyakarta (Galeri Kafe Ada Sarangan).
Jarak dan Imajinasi Struktur Ruang
Saya ingin memunculkan dua titik tolak yang menjadi kerangka dasar tulisan ini. Pertama dari tema “jarak” itu sendiri. Beberapa kata kunci yang mungkin diturunkan dari tema “Jarak”:
pengamatan
batas
posisi
ukuran
skala
sudut pandang
pantulan
meretas
evakuasi
di luar atau di dalam
Dan kedua, bagaimana para seniman melihat tema ini. Beberapa kata kunci yang diproduksi oleh 9 seniman peserta:
“pasca-sentuh” (I Made Yogi Sugiartha)
“Di Antara” (Ragil Dwi Putra)
“Pengepungan” (Densiel Prisma Yanti Lebang)
“Jembatan” (Flourish Sekarjati)
“Follow me” (Syska La Veggie)
“Saling tembus hitam putih” (Monica Hapsari, Gilang Anom Manapu Manik)
“Mematuhi / tidak mematuhi” (Abdi Karya)
“Pecah dan menjahit” (Arsita Iswardhani)
“Penyusup” (Fitri Setyaningsih)
Kedua kata kunci itu diproduksi berdasarkan tema “Jarak”. Jarak selalu mengandaikan batas dan tempat. Keduanya bersifat fisik. Namun ketika keduanya ditempatkan dalam kerangka “ruang”, akan memantulkan banyak kemungkinan imajinasi di sekitar struktur ruang. Apakah ruang berubah ketika kita memasukkan sebuah benda, atau ketika terjadi sesuatu yang bergerak? Ragil Dwi Putra dalam karyanya “Bergerak Di Antara / Moving in Between” (berdurasi 70 menit), menggunakan material tumpukan cermin ukuran sekitar 10 X 10 CM. Dengan mata tertutup kain hitam, Ragil mulai bergerak memindahkan satu-persatu cermin ke sebuah tempat yang dibatasi oleh kamera. Ketika cermin berhasil di tempatkan di bawah kamera, maka kamera akan merekam gerak di sekitar cermin.
Pada tahap awal, Ragil tersesat. Dengan mata yang tidak bisa melihat, dia gagal menemukan batas, dan melewati batas. Kemudian memunculkan imajinasi ruang sebagai “medan tersesat” dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Namun medan yang mulai terbuka ini dibatalkan sendiri oleh Ragil. Dia melepas kain hitam yang membalut matanya, melihat dua titik yang harus dilaluinya bolak-balik, lalu memasang kembali kain pembalut di matanya, dan memulai lagi langkah baru.

Karya Ragil Dwi Putra “Bergerak Di Antara / Moving in Between” (Sumber Foto: Tangkapan layar kanal YouTube Studio Plesungan)
Langkah baru ini kemudian menjadi usaha untuk memetakan sekaligus membekukan jalur lintas yang dilalui untuk membawa satu-persatu cermin dan memindahkannya di bawah kamera. Pembekuan ruang dilakukan Ragil dengan cara mengikuti garis ubin melalui rabaan tangannya. Dia berjalan jongkok untuk sampai ke batas kamera. Ragil bergerak. Tapi ruang membeku. Dan yang tersisa di luar batas kontrolnya, adalah posisi kamera yang terus bergeser, karena sering tersentuh kepala Ragil saat menempatkan cermin di bawa kamera. Dan kamera mulai meleset untuk bisa merekam cermin. Kamera justru menjalankan fungsi melepaskan kembali ruang dari pembekuannya.
Ada dua peran kamera yang menjalankan fungsi secara berbeda dalam performance Ragil. Kamera internal sebagai bagian dari pertunjukan, dan kamera eksternal yang merekam pertunjukan. Keduanya memposisikan ruang secara berbeda, dan keduanya akan menentukan ruang pertunjukan virtual untuk penonton yang menyaksikannya melalui kanal Youtube Studio Plesungan. Kemudian memunculkan problem “ruang-pasca-sentuh” melalui pembatasan mobilitas kamera.
Imajinasi struktur ruang mendapatkan pantulannya dalam performence Densiel Prisma Yanti Lebang (“Barricade”) yang berdurasi 87 menit. Pertunjukan ini bergerak mengubah bingkai menjadi konten, menggunakan material police-line. Densiel tidak bisa hadir dalam program ini, dan meminta Eyik Lesar (seorang penari dan koreografer) untuk menggantikannya sebagai performer. Pertukaran ini berlangsung dalam batas waktu yang darurat, lalu memunculkan pertanyaan: apakah perbedaan yang bisa ditemukan bila performence dilakukan oleh Densiel sendiri? Atau kemungkinan Dansiel menggunakan video-call bersama Eyik yang dibocorkan ke publik untuk bagaimana performence ini dijalankan?
Performance Ragil berlangsung di bagian dalam Galeri Senirupa Taman Budaya Solo. Pilihan untuk ruang yang sebenarnya sudah didefinisikan (dibekukan) oleh tipologi maupun fungsi ruang. Sementara performance Eyik berlangsung di luar, diapit antara bangunan galeri dan bangunan kantor yang berkontur beton marmer. Bagaimana seorang seniman performance art melakukan kurasi atas pilihan ruang dan material yang digunakan, akan sangat menentukan kerja organik pada karyanya.
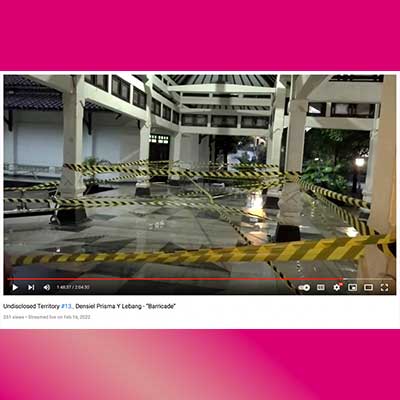
Karya Densiel Prisma Yanti Lebang “Barricade” (Sumber Foto: Tangkapan layar kanal YouTube Studio Plesungan)
Dengan material police-line, kostum orange mirip para pekerja infrastruktur fisik kota, medium laser pada kepala yang memproduksi garis hijau cahaya digital pada dinding-dinding ruang, dan kamera G-pro yang tersemat di dadanya, Eyik berjalan mundur. Police-line yang biasanya digunakan sebagai bingkai pembatas untuk sebuah lokasi yang tidak boleh dimasuki oleh publik (karena bencana maupun kecelakaan), justru dibuat menjadi konten itu sendiri. Dengan berjalan mundur, selama satu jam lebih, Eyik membebatkan police-line itu pada tiang-tiang, dinding, kursi, meja, tanaman maupun objek apa pun yang ada dalam lokasi performance.
Di tengah hujan yang turun deras dan angin kencang, Eyik terus bergerak, dan memproduksi ruang yang menjadi kian masiff oleh layar-layar police-line. Ketika Eyik berhenti, membuat jeda, memproduksi tatapan ke seluruh ruang, posisi diam ini menjadi semacam “pengukuhan” atas ruang yang sudah berubah. Ruang terus tumbuh ketika performer diam. Kesadaran atas praktik “jeda”, memang tidak terlalu banyak digunakan atau disadari dalam performence yang lain dalam program ini. Berkisar pada bagaimana praktik ini memiliki fungsi pengukuhan atas perubahan ruang, maupun ruang yang tetap tumbuh dalam keheningan atau dalam batas underscore.
Pertunjukan Dansiel yang diperagakan oleh Eyik itu, akan tampak jauh berbeda ketika penonton menyaksikannya melalui kanal youtube Studioplesungan. Karena yang ditampilkan dalam video, sebagian besar merupakan rekaman melalui kamera yang disematkan pada dada Eyik, dan ruang berubah sebagai latar belakang dari gulungan police-line yang dibebatkan Eyik ke benda-benda yang berada di sekitar pertunjukan. Performer yang bergerak mundur merupakan posisi utama dari mata penonton.
Dalam performence Abdi Karya, “To Obey or Not To Obey”, yang berlangsung dua sesi (sesi pertama berdurasi 1 jam dan sesi kedua 2 jam), Abdi menggunakan banyak performer dalam karyanya yang berbasis instruksi. Imajinasi akan struktur ruang di sini lebih banyak hadir sebagai imajinasi di sekitar struktur adegan. Menurut Abdi, masing-masing performer tidak saling mengenal satu sama lainnya, dan berarti performence berlangsung tanpa latihan. Memunculkan banyak kemungkinan di sekitar adegan-adegan organik yang akan mereka hasilkan.
Salah satu bunyi instruksi yang ditayangkan melalui pengeras suara dan bisa didengar oleh penonton adalah “gerakmu akan berubah setiap pikiranmu berubah” sebagai order utama dalam performence. Instruksi ini ditayangkan berulang-ulang sepanjang pertunjukan. Ia kemudian menjadi rutin, dan gerak maupun adegan kian tumbuh di luar order utama. Ini menjadi inti dari “To Obey or Not To Obey” (Mematuhi atau Tidak-Mematuhi).
Dalam sesi kedua, penonton tidak bisa mendengar instruksi yang sama, karena instruksi dipindahkan melalui HP yang diikatkan pada tubuh performer (terutama pada tangan), dan hanya bisa didengar oleh para performer. Wawasan pengetahuan performer di sekitar dunia seni pertunjukan, perlahan-lahan mulai bocor, dan pada gilirannya diproduksi oleh masing-masing performer. Menggeser order utama pertunjukan.
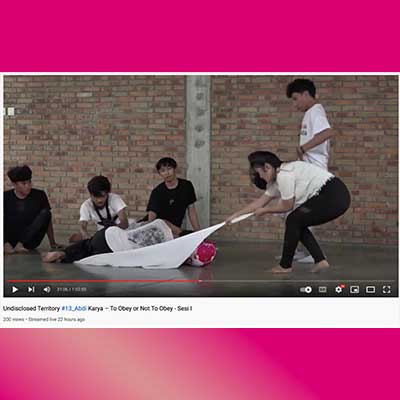
Abdi Karya, “To Obey or Not To Obey” (Sumber Foto: Tangkapan layar kanal Youtube Studio Plesung)
Wawasan pengetahuan pertunjukan itu di antaranya muncul dalam adegan performer yang melakukan gerak akrobatik seperti melompat, atau mendelikkan bola mata menjadi putih. Masuknya material seperti, kain, guling, sarung atau tongkat bambu ke dalam ruang pertunjukan, oleh sebagian performer diterima sebagai order membuat bentuk-bentuk adegan orang tua yang berjalan dengan tongkat; atau dua performer saling berpelukan, memproduksi drama kesedihan.
Produksi adegan-adegan itu pada gilirannya beresiko mempropokasi tim kamera yang merekam pertunjukan ini. Kamera mulai melakukan pilihan atas adegan-adegan tertentu. Dan dengan sendirinya ikut memproduksi atau mengkonstruksi pilihan itu. Seolah-olah pilihan ini adalah adegan utama yang perlu disampaikan secara lebih dekat kepada penonton yang menyaksikannya melalui kanal youtube. Padahal pertunjukan berlangsung tanpa fokus tertentu.
Metode “mematuhi dan tidak-mematuhi” yang digunakan Abdi dalam pertunjukan ini, beresiko menjadi peristiwa latihan dalam eksplorasi mencari-cari adegan. Dan peristiwa organik yang disasar juga beresiko menjadi pseudo-argonik. Kian jauh dari harapan Abdi untuk para penonton bisa bebas masuk jadi bagian dari pertunjukan. Karena adegan yang diproduksi oleh sebagian performer, pada gilirannya membuat batas tegas antara ruang pertunjukan dan ruang penonton.
Drama dan Godaan Spektakel
Flourish Sekarjati biasa bekerja sebagai seorang pelukis yang menghadapi ruang dua dimensi. Dalam karyanya “Breath Bridge” yang berdurasi 40 menit, Flourish tidak semata-mata bekerja dalam ruang tiga dimensi. Tapi juga dalam dua layer antara aksi performence dan sensor video yang ditayangkan melalui proyektor. Keduanya ditempatkan secara paralel, bersebelahan.
Untuk penonton yang menyaksikan langsung performancenya di Galeri Taman Budaya Solo, dapat menyaksikan paralitas karyanya antara aksi performance dengan video sensor yang mengubah informasi gerak Flourish menjadi data-data digital yang baru. Namun yang menyaksikan pertunjukan melalui kanal youtube, melihat keduanya secara bergantian dan hilangnya keserentakan dari paralelitas itu.
Dalam performancenya, Flourish menggunakan sebuah karung besar dari bahan yang elastis, sebagian besar berisi bola-bola kecil. Elastisitas ini membuat bentuk karung mudah berubah setiap terjadi tekanan berbeda ketika Flourish menyentuh atau memeluknya. Dalam video sensor, ketika Flourish mengambil jarak dengan karung, melahirkan dua bentuk yang sama anehnya antara tubuh Flourish dan tubuh karung. Kadang tubuh karung menyerupai binatang.
Namun ketika Flourish membiarkan dirinya mulai memproduksi drama, atau terjebak dalam drama, ke dua tubuh itu kehilangan dinamikanya dalam membentuk posisi. Keduanya jadi bentuk bertumpuk ketika ditransfer sebagai data-data baru oleh video sensor. Dan Flourish kian memproduksi peran hubungan seorang ibu dengan sesuatu (seperti bayi) yang disayanginya, dimana video sensor tidak bisa menstransfer data-data emosi seperti ini.
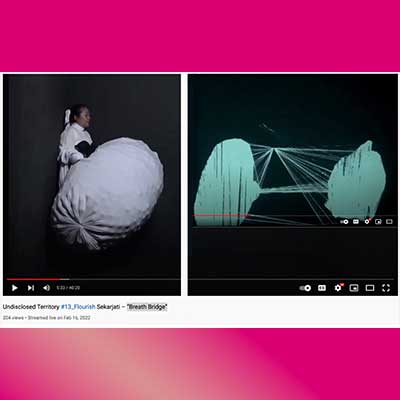
Karya Flourish Sekarjati “Breath Bridge” (Sumber Foto: Tangkapan layar kanal YouTube Studio Plesungan)
Tubuh sebagai wahana dalam performance art dan tubuh sebagai drama yang biasa digunakan dalam teater, merupakan dua hal yang berbeda. Kultur seni pertunjukan di Indonesia, yang memang lebih banyak dirayakan melalui teater sebagai drama, cenderung terus terbawa dalam performance art. Dan hingga kini menjadi bagian yang ikut menentukan salah satu ciri performance art yang tumbuh di Indonesia.
Dalam fenomena yang lain, beban drama lebih ditemukan sebagai “beban penafsiran” pada performance Monica Hapsari dan Gilang Anom Manapu Manik. Keduanya awalnya akan melakukan performance secara terpisah: Monica Hapsari dengan judul “Tandur Tampah” dan Gilang Anom Manapu Manik dengan judul “Sawang Sawasih Jagad Jati”. Menjelang program akan berlangsung, keduanya mengambil keputusan untuk menjadikannya sebagai karya bersama. Keduanya ditempatkan dalam ruang terpisah, saling berhadap-hadapan dengan durasi 56 menit.
Keduanya dilihat sebagai medan Yin-Yang. Monica Hapsari dengan tubuh dilamuri material hitam, dinding hitam dan lingkaran hitam. Sementara Gilang Anom Manapu Manik dengan dominan warna putih. Pertunjukan mereka berbasis ritual dengan beban penafsiran yang tinggi dalam pantulan kosmologis dan mitologis.
Ruang hitam sebagai basis performance Monica mengalami semacam gangguan, karena menggunakan tampah yang memperlihatkan warna asilnya (warna rajutan bambu) yang tampak masih baru. Tampah muncul sebagai judul dan sebagai objek. Sementara Monica bergerak di sudut belakang lingkaran hitam yang dibentuk dengan material arang. Lingkaran hitam ini sejatinya bisa menjadi semacam transformasi tampah, sehingga tampah lebih mungkin digunakan dalam penghadiran imajinasi kosmologi dibandingkan tampah dalam bentuknya yang masih baru. Sementara Gilang menggunakan jubah dan tongkat, memunculkan gambaran pendeta dari kepercayaan-kepercayaan tua. Dan cenderung menjadi tubuh spiritual yang terbekukan, tidak mendapatkan ruang organiknya untuk tumbuh.

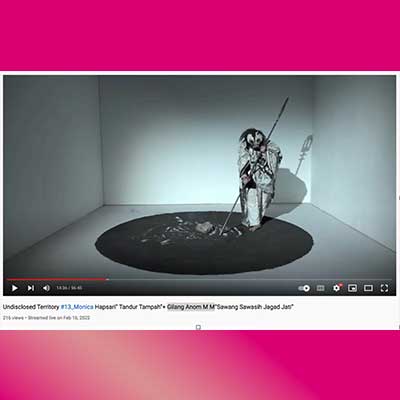
Karya Monica Hapsari “Tandur Tampah” dan Gilang Anom Manapu Manik dengan judul “Sawang Sawasih Jagad Jati” (Sumber Foto: Tangkapan layar kanal YouTube Studio Plesungan)
Ikon-ikon pertunjukan atas nama spiritualitas maupun kosmologi, cenderung menghasilkan masalah pada medan representasi, terutama karena keterbatasan material untuk menghadirkannya. Biasanya selalu menggunakan dupa maupun mantra (atau semacam mantra) dan memunculkan “beban tafsir” yang serius. Tubuh spiritual yang digerakan melalui beban penafsiran sebagai akting, juga beresiko memunculkan masalah komunikasi. Gilang sendiri membawa tubuh-mitos ini di berbagai banyak program yang diikutinya, berganti latar kota yang berbeda-beda. Seolah-olah membawa dialog tentang identitas spiritual di tengah munculnya gerakan fundamentalis berbasis agama.
Beban penafsiran ini menjadi berlipat ganda dengan peran musik yang sangat menentukan struktur performance Monica dan Gilang. Dan beresiko dimana musik membuat posisi pertunjukan bergeser menjadi ilustratif. Ketika menjelang akhir performance, Monica dan Gilang saling bergerak berganti ruang, momen ini tidak terekam oleh tim kamera video yang memang disetup merekam keduanya secara terpisah. Dan penonton melalui kanal youtube, ikut tidak bisa menyaksikan momen ini.
Godaan yang datang dari drama, sama kuatnya dengan godaan membuat pertunjukan dengan tujuan menghasilkan spektakel. Pertunjukan Fitri Setyaningsih, “Penyusup dalam Tubuh (Kucing dalam Karung)”, berdurasi 34 menit. Fitri menggunakan ruang dan pencahayaan yang kompleks dan tidak mudah diwujudkan sebagai pertunjukan virtual melalui kamera video.
Ada berlapis layar performer yang dihadirkan: performer yang kepalanya menggunakan handuk, tubuh performer dalam karung, performer dengan tubuh normal yang melakukan mobilitas lebih cair, dan performer dengan siluet tubuh perempuan antara rambut dan sorotan cahaya dari belakang sebagai hightlight pertunjukan. Model pencahayaan seperti ini banyak digunakan di panggung-panggung tari maupun teater dalam memproduksi ruang dramatik. Dan satu layar lain yang diperankan oleh musik. Pertunjukan Fitri sepenuhnya hadir sebagai performing art.

Karya Fitri Setyaningsih, “Penyusup dalam Tubuh (Kucing dalam Karung)” (Sumber Foto: Tangkapan layar kanal YouTube Studio Plesungan)
Ruang Galeri Kafe Ada Sarangan di Yogyakarta yang digunakan Fitri, dengan dinding pemisah jendela dan pintu kaca, merupakan ruang yang memang tidak mudah dipetakan oleh kamera yang bekerja dalam momen pertunjunkan. Pilihan ruang yang kompleks ini mungkin berpeluang lebih terpetakan bila dilakukan melalui kerja kamera untuk dokumentasi.
Tema “Penyusup” yang dibawa Fitri, lepas dari muatan makna yang dibawa pertunjukan ini di sekitar kucing dalam karung dalam dimensi sosial-politik, berpeluang sebagai peretas dalam mendekati tema “jarak” yang ditawarkan program Undisclosed Territory 13. Namun tema penyusup ini mendapatkan makna lain ketika dipadankan dengan kucing dalam karung.
Kerja Representasi dalam Medan Pasca-Sentuh
I Made Yogi Sugiartha memiliki lapisan-lapisan tubuh penuh warna. Tubuh yang terkesan modis, fotografis dan transpuan. Pertunjukan menggunakan lantai yang terbuat dari balok-balok es. Suhu dingin mulai menyeruak di sekitar ruang pentas. Sugiartha bergerak di atas lantai balok es itu, mengenakan mantel dan sepatu ankle boots.
Kostum yang dikenakan Sugiartha, sekilas terkesan disiapkan untuk menghadapi dinginnya balok es. Namun yang terjadi sebaliknya: Belahan kancing pada mantelnya memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang hanya menggunakan celana dalam. Dan bersama sepatu ankle boots yang terbuat dari material kulit, rambutnya yang panjang, celana dalam yang dikenakan, semuanya merupakan material yang justru menyimpan dingin dan cairan es.

Karya I Made Yogi Sugiartha “Ice See You”(Sumber Foto: Tangkapan layar kanal youTube Studio Plesungan)
Sepanjang pertunjukan, Sugiartha menggunakan palu besi untuk memecah balok es, dan memunculkan percikan es setiap palu menghantam balok es. Palu dengan ukuran kecil itu, tidak mampu digunakan untuk membelah balok es. Balok es baru terbelah ketika dibiarkan jatuh terhempas di lantai. Aksi ini terus memproduksi tubuh feminim yang dimiliki Sugiartha, namun dengan tenaga yang maskulin. Dalam momen tertentu, Sugiartha berhenti bergerak. Tubuhnya berubah jadi patung. Dalam momen ini, dia mengirim informasi kepada penonton tentang kualitas dingin yang sedang dialami oleh tubuhnya. Bibirnya bergetar antara informasi sebagai data dingin, pada sisi lain sebagai data estetika yang sedang diproduksi dalam pertunjukannya.
Seluruh pertunjukan itu sepenuhnya merupakan medan sentuh yang mengubah balok es jadi pecahan-pecahan batu es melalui aksi palu besi. Namun di balik ini semuanya, juga sedang berlangsung medan-tak-sentuh di mana momen dingin bertransformasi ke dalam berbagai emosi di sekitar tubuh yang tersingkir, tertindas, dirapuhkan, dan terlempar ke dalam medan trauma sosial. Semakin tinggi tubuhnya menyerap dingin dari balok es, medan-tak-sentuh itu kian dalam dan kian tebal dalam memproduksi persoalan yang dihadapi oleh para penyitas yang transpuan.
“Ice See You”, pertunjukan I Made Yogi Sugiartha itu, berlangsung selama 2 jam 10 menit. Durasi yang cukup mencemaskan untuk melihat ketahanan tubuh dalam menghadapi dinginnya balok es, tanpa data-data medis untuk penonton bisa ikut mengukurnya. Sugiartha termasuk performer dengan pilihan material yang kompak dan ekstrim dengan tema yang diusungnya.
Dalam pertunjukan Syska La Veggie, “light, like, life (follow me)”, medan-tak-sentuh itu dihadirkan melalui medan listrik. Ia menggunakan LED Tumblr berupa ribuan cahaya mata kucing yang melapisi tubuhnya dan membuat bentuk-bentuk tertentu pada dinding maupun di tengah ruang pertunjukan.
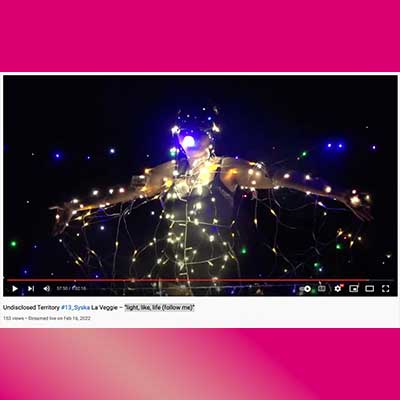
Karya Syska La Veggie, “light, like, life (follow me)” (Sumber Foto: Tangkpan layar kanal YouTube Studio Plesungan)
Pertunjukan yang berlangsung selama satu jam itu menggunakan ruang hitam di Galeri Taman Budaya Solo. Sebuah kursi yang juga hitam. Syska mulai memasang lampu-lampu LED Tumblr ke bagian tubuhnya dan ruang pertunjukan, sehingga tubuhnya membentuk semacam galaksi cahaya. Ia menggunakan alat gun-tacker untuk menempelkan lampu-lampu LED Tumblr pada dinding. Setiap alat gun-tacker digunakan, suaranya yang menembus dinding tripleks, bergema dan memproduksi ruang melalui suara. Aksi ini, antara yang terlihat dan terdengar, saling memproduksi ruang dalam medan-tak-sentuh.
Suara gema dari gun-tacker dan gerak Syska yang natur dan non-gender, memunculkan maskulinitas dari kesetaraan gender yang diusung dalam pertunjukan ini. Pertunjukannya menjadi dunia “kelap-kelip” antara gelap dan terang, visual dan suara, gender dan non-gender, jarak dan batas yang saling berkelindan satu sama lainnya. Dalam momen yang lain, ia menjadi dunia peri yang puitis dan minimalis.
Arsita Iswardhani dengan pertunjukan paling panjang dalam program ini, memakan waktu 3 jam lebih, merupakan pertunjukan yang memunculkan ketegangan antara arsip dan data arsip yang seksis. Pertunjukannya, “Pecah dan Celana Dalam Ibu”, menghadirkan paradoks antara lantai ruang yang dipenuhi oleh pecahan cangkir, dan sebuah level tempat Arsita duduk bersimpuh menjahit, menyatukan sekian banyak celana dalam bekas ibunya selama 3 jam lebih.

Karya Arsita Iswardhani “Pecah dan Celana Dalam Ibu” (Sumber Foto: Tangkapan layar kanal YouTube Studio Plesungan)
Pecahan cangkir, yang bisa menjadi rujukan untuk pecahnya ruang domestik bagi peran perempuan dalam budaya patriarki, hampir tidak pernah dijadikan sebagai informasi utama oleh kamera video yang bisa dinikmati penonton melalui kanal youtube. Kamera tetap membiarkan pecahan cangkir itu sebagai serakan di lantai ruang pertunjukan, tanpa tergoda memperlihatkan teksturnya sebagai data.
Begitu juga celana dalam bekas ibunya yang digunakan Arsita, kamera dan Arsita tidak pernah memperlihatkan bentuk celana dalam itu sebagai arsip keluarga yang bisa dikenali penonton. Sehingga penonton tidak mendapatkan data yang lebih lengkap tentang spesifikasi celana dalam bekas itu. Pilihan ini memunculkan ketegangan celana dalam bekas sebagai arsip keluarga, dan kemungkinan kesan seksis yang dibawanya. Jadi, celana dalam, pada pertunjukan ini lebih hadir sebagai informasi, dan bukan sebagai data arsip.
Pertunjukan ini, yang pada akhirnya merupakan pertunjukan yang biografis dan privat, pada gilirannya memunculkan cara-cara bagaimana arsip dihadirkan dalam ruang pertunjukan sebagai medan-tak-sentuh. Bahwa tidak seluruh arsip, data-datanya pantas untuk dijembrengkan dalam pertunjukan. Antara “yang-pecah” dan “yang-dijahit-kembali” dalam pertunjukan ini, pada gilirannya merupakan respon evaluatif dan puitis dalam mempersoalkan ruang domestik dalam budaya partriarki; walau budaya patriarki tidak mendapatkan rujukan yang cukup vokal dalam pertunjukan Arsita. Namun samar-samar, budaya patriarki ini kian terbentuk melalui posisi bersimpuh yang dilakukan Arsita sepanjang pertunjukan. Bahwa yang berdiri adalah lelaki.
Dramaturgi Kamera dan Kerja Penghadiran
Menurut Melati Suryodarmo, Undisclosed Territory 13 memang menghadapi persoalan bagaimana kamera ditempatkan dalam peristiwa performance art sebagai peristiwa virtual. Pembatasan wilayah akibat pandemi, membuat untuk pertama kalinya program ini menghadapi kamera sebagai problem penghadiran dan distribusi karya yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya.
Pertemuan antara seniman peserta dengan tim teknis dan tim kamera, tetap meninggalkan ruang penuh dugaan bagaimana produksi kerja kamera pada gilirannya bisa mendistribusi pertunjukan sebagai pertunjukan virtual. Problem ini muncul, karena kamera bekerja di tengah momen pertunjukan yang tidak bisa diulang, dan bukan bukan bekerja sebagai dokumentasi yang bisa diulang.
Dramaturgi kamera dalam program performance art, alih-alih tidak bisa ditempatkan sama dengan praktik cinematografi. Kamera menghadapi dua kerja penghadiran, yaitu produksi pertunjukan dan bagaimana produksi mendapatkan distribusinya sebagai penghadiran virtual. Ruang virtual, sebagai bentuk dari praktik pasca-sentuh, memunculkan tantangan tidak terduga dalam kolaborasi medium dengan teknologi.
Di sisi lain, kerja penghadiran ini juga memunculkan pergaulan baru antara performance art dan performing art. Saya masih menduga-duga apakah pergaulan baru ini terjadi karena masing-masing seniman memiliki peluang membawa karya dari luar, dan menjauh dari praktik site-spesifik. Karena karya sudah diproses dari tempat masing-masing, dan tidak berada di ruang yang sama. Hal yang juga mungkin terjadi, karena pilihan ruang indoor, baik di Galeri Taman Budaya Solo, maupun Galeri Kafe Ada Sarangan di Yogyakarta, untuk memudahkan pengambilan video.
Lepas dari dugaan-dugaan itu, untuk saya, Undisclosed Territory 13 menjadi khas, karena ia mulai melepaskan ketegangan lanten antara performance art dan performing art. Keduanya dibiarkan tumbuh, mendapatkan ruang pergaulan barunya dalam program ini. Mendekatnya tubuh dan teknologi sebagai tubuh baru dalam performance, dan dunia digital di sisi lainnya. Memunculkan hari esok yang lain dalam seni pertunjukan antara performance art dan performing art. Mungkin ini terasa aneh. Tapi untuk saya terasa asyik.***
Sidoarjo, 18 Maret 2022
*Afrizal Malna. Penyair dan Pengamat Seni.













