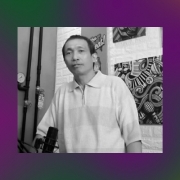Melampaui Hijab Gerhana
(Catatan tambahan untuk Aminudin TH Siregar, Hendro Wiyanto, Yuswantoro Adi, dan Asmudjo J. Irianto)
Oleh: Hajriansyah*
Membaca polemik yang diawali ketakjuban terhadap peristiwa “gerhana” seni rupa Indonesia belakangan ini, saya jadi ingat model penyingkapan yang pernah disampaikan Ibnu Arabi, seorang sufi dan filsuf besar dari Damaskus, negeri terakhir ia tinggal. Model penyingkapan dimaksud membayangkan sebuah hijab (dinding) yang membuat seseorang gagal melihat “realitas” yang sesungguhnya. Hanya dengan melihat semua yang “nyata” itu pada dasarnya imajinasi (khayyal) belaka, seseorang bisa mengalami ke-”nyata”-an dengan sesungguh-sungguhnya.
Apa yang diimajinasikan Aminuddin TH Siregar (Ucok) soal kesan “kemunduran” atau stagnasi dari pernyataan gerhana Joebar Ajoeb, saya kira beberapa bagiannya telah dikoreksi oleh Hendro Wiyanto. Yang ditambahkan oleh Yuswantoro Adi (Yus) makin memperjelas bukti kelalaian melihat realitas yang lain itu karena terhalang “subjek” gerhana. Mesti ada kesungguhan untuk melihat fenomena dan dinamika seni rupa Indonesia secara menyeluruh, dari barat, tengah, hingga ke timur negeri kepulauan yang besar ini. Dan ini saya maklum, tak mungkin bisa dilakukan dan dipanggul sendiri oleh Ucok dengan “imajinasi” tunggalnya.
Saya kira contoh Yogyakarta yang dikemukakan Yus hanya satu bagian saja dari keindonesiaan ini. Dan sah-sah saja ia mengklaim daerahnya sebagai “ibukota”, karena diasumsikan di sana keramaiannya terasa agak lebih jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Jawa.
Bicara soal seni rupa Indonesia mestinya tak harus melulu melihat pusat-pusat perayaan di Pulau Jawa. Okelah, pada tataran tertentu, dalam hal pencapaian boleh kita berorientasi pada satu sampai sekian titik kulminasi kreatif di beberapa daerah yang dianggap sebagai “pusat”’ tersebut dalam konteks tertentu. Tapi kreativitas yang berlangsung bukannya berkutat di situ-situ saja, bukan? Belum lagi jika kita bicara “pusat”, bukankah wacana semacam ini sudah lewat? Postmodernisme, sebagai landasan wacana seni rupa kontemporer, yang disinggung Asmudjo J. Irianto, merupakan titik tolak menisbikan kuasa tunggal dan menyemaikan relasi yang dibangun oleh kuasa-kuasa yang jamak dan terbagi.
Sebagian besar perupa yang nangkring di “puncak” seni rupa Indonesia itu awalnya datang dari daerah dan kepulauan lain Indonesia ini? Sebagian yang kurang sreg, atau punya kecenderungan lain, pulang ke daerah dari studinya di Jogja, Bandung dan Jakarta, dan berkontribusi mengisi kekosongan wacana di daerah, dan mereka juga berkontribusi pada pameran-pameran kecil maupun besar di (sekali lagi) pusat sana.
Galeri Nasional Indonesia (GNI), lebih dari dua dekade sudah, menyelenggarakan Pameran Seni Rupa Nusantara (PSRN) secara reguler. Ini suatu upaya diseminasi yang baik saya kira, yang oleh Citra Smara Dewi diamati secara fokus, bersamaan dengan peran GNI, dalam disertasinya di Universitas Indonesia.
Catatan Citra ini (sengaja saya kutip secara melompat-lompat untuk memberi gambaran umumnya saja) saya kira penting untuk dibaca oleh para pengamat berkacamata kuda, yang terhijab oleh citra besar seni rupa Indonesia melalui imajinasi tunggal mereka.
Ironisnya, sejalan dengan perkembangan seni rupa kontemporer global, terjadi kesenjangan dalam perkembangan seni rupa modern dan kontemporer Indonesia, khususnya dalam memaknai eksistensi seni rupa yang berkembang di luar Jawa dan Bali. Sebagai negara kepulauan, bangsa Indonesia selain memiliki sumber geografi dan sejarah yang tinggi, juga sumber daya demografi, yaitu para perupa seluruh Nusantara. Keterlibatan perupa Nusantara memang belum terlihat signifikan pada era 1980-an dan 1990-an, salah satunya karena keterbatasan akses dan kesempatan untuk menampilkan karya di tingkat nasional. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui sentralisasi, sehingga belum dapat menjangkau potensi-potensi seniman di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan… Lahirnya gerakan seni rupa terutama di kawasan luar Jawa dan Bali membuktikan bahwa potensi perkembangan Seni Rupa Indonesia bukan hanya berpusat di Jawa dan Bali…. Melalui PSRN itu terjadi interaksi dan komunikasi yang intens antara perupa Jawa dan Bali dan luar Jawa dan Bali sehingga mereka terdorong untuk berbagi pengalaman satu sama lain.
Pada bulan Desember 2020 yang lalu juga telah diadakan diskusi online, yang menyertai pameran Komunitas Seni Torang Sulawesi Utara. Pameran ini menyoal wacana semacam ini, dengan tema “Arus Timur: Sebuah Proposal tentang Sejarah Seni Rupa dari Sulawesi Utara”. Kurator pameran, sekaligus penyelenggara diskusi, memberi catatan berikut:

Poster Pameran “Arus Timur: Sebuah Proposal tentang Sejarah Seni Rupa dari Sulawesi Utara”
Dalam pameran ini, selain kiprah dan karya para anggota komunitas Torang, juga dikaji soal linimasa sejarah seni rupa di Sulawesi Utara. Karya, kiprah, dan soal linimasa historis ini kemudian memantik pemikiran mengenai perlunya menelisik secara khusus alur sejarah seni rupa di wilayah timur Indonesia. Apakah mungkin, Sulawesi Utara secara khusus, dan Indonesia Timur secara lebih umum, dapat menyumbang narasi sejarah seni rupa yang baru bagi kita semua?
Ya, tentu sangat niscaya (meski juga bukan hal baru)!
Saya ikut terlibat dalam rangka perbandingan wacana seni rupa di Kalimantan Selatan. Sekian narasumber dan penanggap memberi “kesaksian” sekaligus catatan tentang apa yang terjadi di daerah mereka, dan itu masih di wilayah Indonesia. Sejarah dan dinamika masing-masing daerah terbukti andal dan bertahan, meski berada di bawah cakrawala amatan para kritikus dan kurator di “sana”. Di sini, mereka melek wacana, baik yang terjadi di pusat sana maupun di pusat sini. Seni rupa modern, serta kontemporer, yang mereka geluti berkelindan dengan tradisi seni rupa lain (baca: tradisional) yang tumbuh dan juga tetap bertahan di sekitar mereka. Alih-alih itu juga jadi “bahan” mereka berkarya untuk diakui di pusat sana. Oh, naasnya!
Seperti juga halnya kajian Citra, saya meyakini bahwa seni rupa Indonesia tidak sesempit yang dibayangkan beberapa pemerhati yang sibuk dengan wacana pasar dan pasar wacana saja. Wilayah yang luas, faktor demografis, dan seterusnya, me-”nyata”-kan keniscayaan yang lebih luas. Tokoh dan gerakan, ragam tema kebudayaan beserta pandangan dunia yang mengitarinya, dan persoalan suprastruktur serta infrastruktur seni rupa Indonesia meniscayakan wilayah luas kajian yang—alangkah sayangnya (!)—jika hanya dilihat atas capaian beberapa daerah yang diasumsikan sebagai “pusat” tersebut.
Di Kalimantan Selatan Misbach Tamrin, eksponen Sanggar Bumi Tarung, berkarya secara kontinyu dan konsisten demi “bertahan-hidup” dan mengikuti undangan pameran di Banjarmasin, Jakarta dan Yogyakarta. Pameran terakhir yang diselenggarakan kawan-kawan komunitas Sanggar Sholihin (diambil dari nama pelukis Sholihin, yang mengikuti Biennale Sao Paulo II Brazil bersama Affandi dan Kusnadi di tahun 1953) didedikasikan untuk “membaca” Misbach, kiprah dan gagasannya untuk Indonesia. Pameran ini, meski dikurasi secara longgar (tak terlalu berorientasi pada kualitas “sepihak” khas para kurator), memperlihatkan regenerasi perupa Kalimantan Selatan terkini.

Foto Misbach Tamrin di pameran “Membaca Misbach”

Foto pameran “Membaca Misbach”

Foto Misbach Thamrin saat pameran “Membaca Misbach”
Saya kira begitu pula yang terjadi di Balikpapan, Palangkaraya, Pontianak, dan daftar panjang daerah lainnya, dengan beragam wacana pameran dan kegiatan yang sudah dibagikan secara meluas melalui media sosial, dan dapat diakses beritanya dengan mudah melalui internet. Alangkah naifnya melihat seni rupa Indonesia secara terbatas, melalui imajinasi segelintir pemerhati populer!
Saya senang sekali ada upaya rekreatif semacam ini, yang “mengundang” para pemerhati seni rupa Indonesia untuk bicara terkait polemik yang sudah-sudah. Sudah saatnya melihat ke cakrawala yang lebih luas, yang tak dibatasi media terbatas semacam Kompas (dengan keterbatasan ruangnya yang hanya mampu menayangkan empat tulisan saja). Ujug-ujug, saya bisa melihat sesuatu di luar imajinasi “besar” seni rupa Indonesia beberapa orang saja. Dan demikian, saya terbayang pernyataan Ibnu Arabi (yang dalam pernyataannya memiliki maksud berbeda), saya kutip dari Toshihiko Izutsu, “Karena kau hanya membayangkan (imagine) bahwa ia adalah realitas otonom …, padahal sebenarnya tidaklah demikian.”
Vita brevis ars (non) longa!
*Penulis adalah pengajar dan pengamat seni rupa di Banjarmasin.