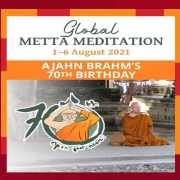Fasisme dan Buku
Oleh Joss Wibisono
Tiga perkara melatarbelakangi penulisan esai ini. Pertama, perbandingan yang tidak begitu tepat pada salah satu tulisan terdahulu, jadi ini semacem revisi. Kedua, hasrat mencari perspektif bagi karya sastra Indonesia yang ditulis oleh mereka yang hidup di pengasingan, dan ketiga, di tanah air berkali-kali terjadi razia terhadap apa yang dicap sebagai buku komunis/kiri. Moga-moga ketiga dorongan itu dapat teramu dengan baik, sehingga karangan ini tidak terlalu rumit sehingga terlalu sulit dipahami.
Ada perbandingan yang sebenarnya meleset pada bab dua buku pertama saya Saling Silang Indonesia Eropa (Marjin Kiri, 2012). Bab berjudul “Sejarah Musik Bejat” itu secara tidak tepat membandingkan para komponis Jerman yang karya musik mereka dicap oleh rezim nazi sebagai “entartete Musik” (musik bejat) dengan para penulis Indonesia anggota Lekra, organisasi penulis kiri-kerakyatan onderbouw PKI, Partai Komunis Indonesia. Komponis jelas bukan penulis. Walaupun tidak sepenuhnya salah (karena kedua kelompok seniman merupakan korban rezim otoriter kanan), harus ditemukan perbandingan lain yang lebih pas. Hal ini baru saya sadari tahun 2017 selesai membaca sebuah buku tentang peran penerbit-penerbit Belanda dalam menyebarkan buku-buku karya penulis-penulis Jerman yang terpaksa hidup dalam pengasingan tatkala Hitler menguasai negara mereka. Indonesia juga punya penulis-penulis yang hidup di pengasingan! Demikian kesadaran itu sampai pada benak saya. Tentu lebih cocok membandingkan penulis Indonesia dengan penulis Jerman. Segera saya pelajari apa yang di Jerman dikenal sebagai die deutsche Exilliteratur alias Sastra Eksil Jerman.
Sebelum itu, dalam membacai pelbagai tulisan mengenai Sastra Eksil Indonesia, termasuk mendalami karya-karya yang ditulis dalam pengasingan itu, saya merasakan perlunya semacam pegangan atau perspektif yang bisa mengkaitkan pengalaman Indonesia dengan pengalaman negeri lain. Pendekatan wayang Mahabharata dengan episode Pandawa diasingkan (digunakan oleh beberapa penulis) terasa terlalu spesifik Jawa, tidak begitu cocok untuk Indonesia yang jelas tidak hanya terdiri dari orang Jawa. Tatkala berakhirnya zaman diktator disambut dengan terbitnya lumayan banyak tulisan bahkan buku —fiksi maupun non-fiksi— oleh dan mengenai mereka yang terhalang pulang kampung karena sang diktator merebut kuasa, maka tampaknya yang masih perlu dilakukan adalah memberi wawasan, acuan atau perspektif untuk bisa mengapresiasi karya-karya itu. Maklum fenomena eksil bukan cuma dikenal di Indonesia. Perspektif internasional ini juga diperlukan untuk menunjukkan bahwa juga dalam perkara karya sastra yang ditulis di pengasingan, kasus Indonesia bukanlah unik. Kalau begitu, kalangan eksil negara mana yang kira-kira cocok dengan eksil Indonesia? Di sini segera saya dapati bahwa ternyata seorang penyair Indonesia yang terpaksa hidup dalam pengasingan pernah menyinggung-nyinggung soal Sastra Eksil Jerman!
Sementara itu, pada bulan juli 2019 di tanah air kembali terjadi penyitaan buku, setelah tujuh bulan sepi. Sabtu malam minggu 27 juli 2019, di Probolinggo, Jawa Timur, dua orang pemuda pegiat Vespa Literasi, ditahan dan diinterogasi polisi. Walau mereka akhirnya dibebaskan, tapi empat buku mereka disita, tiga buku tentang D.N. Aidit (pemimpin PKI) dan satu buku tentang Bung Karno, sang proklamator. Diawali akhir desember 2018, inilah untuk keempat kalinya terjadi penyitaan buku dalam setahun. Pertama terjadi di Pare (Kediri, Jawa Timur), sesudah itu penyitaan terjadi pada hari yang sama (8 januari 2019) di Padang (Sumatra Barat) dan Tarakan (Kalimantan Timur). Pada 23 januari 2019, seusai rapat dengan DPR, Jaksa Agung bahkan usul untuk melakukan razia besar-besaran terhadap buku-buku komunis. Tapi sampai pertengahan juli 2019, belum juga dibentuk satgas razia itu. Seminggu setelah insiden di Probolinggo, pada akhir pekan pertama agustus 2019, kembali terjadi insiden perampasan buku. Kali ini menimpa sebuah toko buku besar di Makassar dan pelakunya menyebut diri brigade muslim Indonesia. Mereka jelas bukan pihak berwajib, tapi bisa dipastikan mereka belum pernah membaca buku-buku yang mereka bawa begitu saja, tanpa bayar.
Razia dan penyitaan buku adalah salah satu bentuk pembatasan kebebasan berpikir dan berpendapat warisan zaman diktator. Di sini segera muncul kesempatan untuk mengkaitkan ketiga dorongan untuk menulis yang diuraikan di atas. Sekarang jelas bahwa Exilliteratur, Sastra Eksil dan razia atau penyitaan buku merupakan wujud ketidakbebasan berpikir dan berpendapat. Ketidakbebasan zaman diktator antara lain telah membuahkan apa yang disebut Sastra Eksil. Indonesia tampaknya memang tidak mau kalah dengan Jerman, karena di bawah nazi Hitler, mereka sudah punya apa yang disebut die deutsche Exilliteratur. Adakah keterkaitan antara Jerman dengan Indonesia dalam perkara sastra eksil ini, atau keduanya hanya berjalan paralel belaka, tanpa ada sentuhan tertentu?
Membelokkan arah tulisan
Sebelum benar-benar menyandingkan Indonesia pada zaman diktator dengan Jerman di bawah nazi Hitler, perlu terlebih dahulu ditinjau bentuk sastra eksil lain. Apa lagi karena fenomena eksil sendiri sudah terjadi sejak zaman purbakala, misalnya orang-orang Israel yang pada zaman nabi Musa diasingkan ke Mesir. Mungkinkah ada eksil lain yang lebih cocok dengan Indonesia? Pada abad 20 silam ada dua fenomena yang menonjol, pertama eksil yang terjadi di Cekoslowakia menyusul merangseknya tank-tank Soviet pada agustus 1968 untuk mengakhiri apa yang disebut Pražské jaro (musim semi Praha) yaitu demokratisasi komunisme di bawah Alexander Dubček. Salah satu penulis negeri itu yang kemudian kabur ke Paris adalah Milan Kundera. Kundera banyak dibaca di Indonesia, beberapa pendapatnya juga sering dikutip. Sayangnya, mereka yang mengutip Kundera tidak juga membandingkan penulis dalam pengasingan ini dengan seniman Ceko lain yaitu Václav Havel, seperti dilakukan orang di Eropa. Kundera pernah berdebat sengit dengan Havel, antara lain soal protes dan manfaat pengasingan.
Fenomena eksil kedua terjadi di Jerman, tatkala partai NSDAP yang beraliran national sozialismus (disingkat nazi) berkuasa pada awal 1933. Waktu itu juga banyak orang kabur ke luar negeri, termasuk dua nama yang dalam berkarya berkaitan dengan Indonesia. Jelas fenomena kedua lebih cocok, dan bukan hanya karena dua penulis yang karyanya akan dibahas di bawah nanti. Alasan utamanya: musim semi Praha yang terjadi di bawah rezim komunis tidak cocok untuk Indonesia. Walaupun diperintah oleh Sukarno yang kekiri-kirian, Indonesia pada zaman Demokrasi Terpimpin itu jelas bukan negeri komunis. Alhasil Sastra Eksil Indonesia tampaknya memang lebih mirip dengan istilah serupa yang ada dalam bahasa Jerman, itulah istilah die deutsche Exilliteratur alias Sastra Eksil Jerman.
Die deutsche Exilliteratur mencakup pelbagai karya sastra dalam bahasa Jerman yang terbit (dan ditulis) di luar Jerman, antara 1933 sampai 1945, tatkala negeri berpenduduk terbanyak benua Eropa itu diperintah oleh rezim fasis beraliran nazi. Sastrawan yang terpaksa berkarya dalam pembuangan itu diusir keluar negeri karena mereka dianggap menghasilkan karya sastra yang bukan Jerman lagi. Walaupun karya-karya itu ditulis dalam bahasa Jerman, tetapi karena penulisnya orang Yahudi, keturunan Sinti dan Roma (diejek sebagai gipsi), pemeluk Saksi Yehova, penganut komunisme, penyuka sejenis, pasifis (anti perang), pendek kata tergolong Untermensch (belum lagi manusia) sehingga merupakan musuh rezim kanan berliran nazi, maka karya mereka dianggap tidak layak dibaca lagi. Para penganut aliran nazi menyebut diri sebagai Übermensch alias manusia kelas atas.
Razia buku yang berlangsung di Pare (dekat Kediri), Padang, Tarakan dan kemudian Probolinggo, serta Makassar memaksa saya membelokkan arah tulisan ini. Ada perkara yang lebih mendesak lagi ketimbang ‘cuma’ mencari perspektif bagi Sastra Eksil alias membandingkannya dengan Exilliteratur Jerman. Menekuni ideologi kanan para pelaku razia buku jelas jauh lebih menarik dan mendesak ketimbang lagi-lagi menggambarkan korban tindakan mereka atau menulis tentang penderitaan para penulis kiri yang hidup terlunta-lunta di pengasingan. Selain orang tidak pernah (paling sedikit jarang) menyoroti pelaku, lebih dari itu saya sangat ogah meringankan ulah mereka yang jelas-jelas tidak (pernah) membaca buku yang mereka sita. Karena itu saya memutuskan untuk tidak membahas karya-karya yang tergolong Sastra Eksil ini. Bisa-bisa dengan membahas penulis eksil Indonesia buku-buku karya mereka akan terciduk razia pula! Tak pelak lagi, walaupun tindakan memusuhi buku bukan hal baru di Indonesia (semasa penjajahan Belanda dan Jepun serta pada zaman Bung Karno juga sudah banyak buku yang dikorbankan), tindakan terhadap buku-buku yang dianggep kiri adalah warisan zaman diktator yang paling murni.
Alhasil berikut bisa disimak ideologi dan pelbagai langkah yang ditempuh kalangan yang memusuhi buku, kemudian juga akan diambil contoh-contoh yang membuktikan kaitan Jerman dengan Indonesia. Contoh itu juga mencakup Pramoedya Ananta Toer, penulis ternama Indonesia yang begitu dimungsuhi rezim diktator. Seperti Pramoedya, tokoh-tokoh lain yang ditampilkan di sini juga sudah tutup usia, sehingga pengungkapan jati diri itu tidak akan membahayakan mereka. Selain itu tentunya juga tidak ada lagi karya baru yang akan mereka terbitkan. Dengan sengaja tulisan ini tidak akan menyebut penulis-penulis yang masih hidup dan berkarya di pengasingan, supaya tidak mempermudah ulah para pelaku razia buku.
12 dalil kebohongan
Tindakan paling dramatis bahkan disebut-sebut langkah awal partai NSDAP yang beraliran nasional sosialis begitu mengambilalih kekuasaan di Jerman pada awal 1933, adalah apa yang disebut die Bücherverbrennung alias pembakaran buku. Walau begitu peristiwa bersejarah di musim semi ini sebenarnya tidaklah direncanakan, tidak pula diselenggarakan oleh si rezim fasis Jerman. Seolah terlalu sibuk mengurusi kekuasaan yang baru tiga bulan digenggamnya, rezim ekstrim kanan ini kemudian hanya mengaku-aku peristiwa bersejarah ini sebagai langkahnya. Dalam hal ini perlu dibedakan dua pihak, pertama kelompok penyelenggara pembakaran dan kedua, tokoh si pembuat daftar buku-buku yang dilempar ke bara api. Pembuat daftar ini adalah seorang pustakawan beraliran nazi yang bernama Wolfgang Herrmann. Namun Herrmann tidaklah menyusun daftar itu atas perintah para pentolan NSDAP, partai fasis yang waktu itu barusan berkuasa. Sebagai pustakawan di Berlin, daftar buku yang dianggap tidak berjiwa Jerman ini disusun atas inisiatifnya sendiri. Buku-buku yang masuk daftar tidak boleh dipinjam lagi pada perpustakaan tempatnya bekerja. Begitu pikiran awalnya.
Pada saat yang kira-kira sama, organisasi mahasiswa Jerman Deutschen Studentenschaft (disingkat DSt) yang kepengurusannya diambil alih oleh kalangan pro NSDAP, mengeluarkan pernyataan berisi 12 dalil untuk melawan apa yang mereka sebut undeutschen Geist alias jiwa non-Jerman. Mengagung-agungkan nasionalisme Jerman dan apa yang mereka sebut ‘deutschem Volkstum’ (watak kejermanan), pernyataan ini mencerca orang-orang Yahudi dan mereka yang tergolong ke dalamnya. Orang Yahudi hanya bisa berpikir Yahudi, begitu tertera pada dalil kelima. Kalau mereka menulis dalam bahasa Jerman, maka mereka berbohong. Sebaliknya, kalau ada orang Jerman yang menulis dalam bahasa Jerman tetapi berpikir tidak secara Jerman, maka dia adalah seorang pengkhianat. Tentu saja tak secuilpun akal sehat dapat menjelaskan dalil-dalil yang hanya berlatar belakang kebencian ras ini.
Patut dicatat baik 12 dalil DSt maupun daftar buku yang disusun oleh Herrmann adalah konsekuensi logis langkah-langkah yang diambil Hitler begitu berkuasa. Pertama-tama der Führer (gelar kehormatan Hitler yang berarti pemimpin) mengeluarkan dekrit untuk melindungi bangsa dan negara yang pada intinya menghapus kebebasan pers. Dekrit ini segera diikuti dengan penyerangan kantor partai komunis Jerman dan perusakan perpustakaannya. Menyusul pembakaran Reichstag (gedung parlemen) pada 27 februari 1933 yang menurut partai NDSAP dilakukan oleh seorang komunis (akhirnya beberapa gembong NSDAP mengaku melakukan sendiri pembakaran itu), Hitler mengeluarkan dekrit yang lebih ketat lagi. Akibatnya lenyaplah kebebasan berpendapat, berserikat dan kebebasan pers.
DSt sementara itu tidak tinggal diam, segera mereka umumkan rencana aksi yang akan berlangsung selama empat minggu, mulai 12 april sampai 10 mei 1933. Selama itu mereka bersiap-siap untuk melakukan pembakaran terbuka buku-buku yang dianggap tidak berjiwa Jerman, karena ditulis oleh, misalnya, kalangan-kalangan Yahudi atau komunis. Menggunakan daftar buku buatan Herrmann, DSt tidak hanya mengarahkan aksinya dalam pelbagai universitas tetapi juga dunia di luar pendidikan tinggi, pendeknya Jerman secara keseluruhan.
Maka begitulah, pada rabu malam tanggal 10 mei 1933 di Berlin, bertempat di Opernplatz, yang terletak persis bersebelahan dengan gedung opera Unter den Linden dan berseberangan dengan gedung utama Humboldt Universität, dilakukan pembakaran buku. Joseph Goebbles, sang menteri penerangan dan propaganda, datang untuk memberi sambutan, dan ia berpidato dengan berteriak-teriak anti Yahudi, anti komunis dan anti musuh rezim itu. Sekitar 70 ribu orang hadir dan sekitar 20 ribuan buku dibuang ke dalam bara api. Pembakaran tidak hanya berlangsung di ibukota Berlin, melainkan juga di 20 kota Jerman lain. Dari München di selatan sampai Hamburg di utara; dari Kleve di barat sampai Rostock di timur.
Buku-buku yang dibakar mencakup karya 251 orang penulis, akibatnya sebagian besar penulis itu sekarang tidak dikenal orang lagi. Siapa mereka, seperti juga pemikiran mereka yang tertuang dalam buku-buku yang dibakar itu tidak lagi diketahui orang. Dan memang itulah tujuan utama nazi melakukan pembakaran buku. Walau demikian, tetap harus diakui ada pula nama-nama penulis yang sampai sekarang tetap terkenal, misalnya Albert Einstein, Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Engels dan Rosa Luxemburg (penulis buku-buku non-fiksi), serta Heinrich Heine, Franz Kafka atau Joseph Roth yang menulis karya-karya fiksi. Jangan salah duga, bukan cuma penulis-penulis Jerman yang kena sasaran. Penulis-penulis Prancis Victor Hugo dan André Gide juga kena; begitu juga buku-buku penulis Amerika seperti Ernest Hemingway dan Upton Sinclair; termasuk karya-karya penulis Inggris D.H. Lawrence dan Joseph Conrad; penulis Irlandia James Joyce; penulis Soviet seperti Fyodor Dostoevsky dan Leo Tolstoy; penulis Jepang Tokunaga Sunao. Diiringi sorak-sorai hadirin, buku-buku mereka musnah dilalap si jago merah. Di pelbagai perpustakaan (baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan umum) dan toko buku Jerman tidak tersedia lagi buku-buku para penulis itu. Sebagai gantinya di pelbagai toko buku orang Jerman bisa membeli dua buku yang berisi ideologi nazi, masing-masing Mein Kampf (perjuanganku) karya Hitler dan Kampf um Berlin (perjuangan merebut Berlin) karya Goebbles. Pasti tidak butuh waktu lama untuk membaca buku-buku ini, lalu bagaimana dengan hasrat membaca khalayak ramai Jerman?
Di sini terlihat pula manfaat kerja Wolfgang Herrmann si penyusun daftar buku maupun langkah DSt, organisasi mahasiswa Jerman, penyelenggara pembakaran. Sebagai kaki tangan mereka jelas ikut-ikutan dalam upaya si rezim kanan menghapus pelbagai gagasan progresif dari khazanah pengetahuan orang Jerman. Sebagai cecunguk mereka juga pelaku kerja kotor si rezim, sehingga seandainya saja upaya mereka gagal, maka si rezim dengan mudah akan memaklumkan mereka sebagai oknum belaka. Mengoknumkan orang yang sebenarnya sudah bekerja sesuai amanat serta dalam cakupan ideologinya adalah juga pola kerja rezim diktator Indonesia.
Sementara itu, langkah rezim fasis Jerman tidak berhenti pada pembakaran buku. Mereka berlanjut terus menindak kalangan yang mereka musuhi. Tak lama kemudian mereka umumkan apa yang disebut Ausbürgerung, yaitu pencabutan kewarganegaraan kalangan yang dianggap musuh Jerman. Akibatnya banyak orang melarikan diri, meninggalkan Jerman, termasuk penulis-penulis yang buku mereka sudah terlumat api.
Penyelamatan dan perlawanan
Menariknya, tatkala di Jerman waktu itu praktis tidak ada lagi penerbit yang berani menerbitkan karya-karya para penulis ini, di Belanda (sebelum diduduki Jerman aliran nazi pada mei 1940) ternyata paling sedikit ada tiga penerbit yang justru begitu bernyali untuk menerbitkan karya-karya mereka. Dengan demikian buku-buku karya Lion Feuchtwanger, Heinrich Mann, Klaus Mann, Josep Roth, Vicki Baum dan banyak lagi penulis Jerman lain yang hidup di pengasingan bisa terus terbit dan dibaca orang. Pada awalnya, di Amsterdam, baik penerbit Querido-Verlag maupun penerbit Verlag-Allert de Lange, serta penerbit De Gemeenschap di Bilthoven (Belanda tengah) mungkin menerbitkan karya-karya penulis Jerman dalam pengasingan itu cuma berdasarkan pertimbangan keuntungan belaka. Penulis-penulis yang dibungkam rezim beraliran nazi itu sudah cukup terkenal, mestinya banyak orang yang ingin terus membaca karya mereka, jadi menerbitkan buku mereka pasti akan menghasilkan keuntungan. Tetapi kini penerbitan karya-karya para penulis Exilliteratur itu dielu-elukan sebagai langkah penyelamatan sastra Jerman dari cengkeraman fasisme.
Inilah makna Exilliteratur yang sebenarnya, karya sastra dalam bahasa Jerman tapi terbit di luar Jerman. Artinya sebelum diusir, para penulis yang tergabung dalam Exilliteratur sudah menghasilkan karya sastra. Mereka sudah punya nama sebagai penulis.
Tak pelak lagi, di sini segera terlihat aspek Exilliteratur yang paling menarik, karena tampak titik temu antara fasisme Jerman dengan rezim serupa di Indonesia. Itu berarti bahwa Exilliteratur dengan Sastra Eksil tidak melulu paralel belaka. Titik sentuh atau titik temu itu berpasangan dalam bentuk prosa dan puisi, seperti terlihat pada karya penyair Bertolt Brecht dan novelis Vicki Baum. Maklum, Brecht menulis puisi berjudul Das Lied vom Surabaya-Johnny (lagu Surabaya-Johnny) dan Baum menghasilkan novel Liebe und Tod auf Bali (cinta dan maut di Bali) yang diterbitkan pada 1937 di Amsterdam oleh Querido-Verlag. Akibat puisi dan prosa sentuhan ini penggunaan Exilliteratur sebagai perspektif dalam membahas Sastra Eksil Indonesia bukanlah kebetulan belaka. Bahkan perspektif Exilliteratur itu merupakan langkah logis yang tidak terhindar lagi. Kalau begitu bagaimana sebaiknya kita harus memaknai sentuhan Indonesia dalam Exilliteratur ini? Mengapa Frau Baum menulis novel tentang Bali dan Herr Brecht memasang judul Surabaya untuk salah satu sajaknya? Benarkah mereka tidak lagi berkarya tentang Jerman, seperti tuduhan rezim nazi yang mengusir mereka?
Rangkaian pertanyaan itu kira-kira bisa merupakan ancer-ancer untuk meneliti pertemuan antara Exilliteratur dengan Sastra Eksil. Yang jelas, setelah pembakaran buku dan pencabutan warga negara, Brecht maupun Baum (dan banyak penulis lain) meninggalkan Jerman. Mereka ke Amerika, penulis-penulis lain sementara itu ada yang ke negara Eropa lain. Di sana mereka terus berkarya. Brecht memang suka memasang judul kota-kora asing bagi pelbagai puisinya, tanpa maksud khusus. Walaupun memasang Havana, Mandalay atau Surabaya sebagai judul pelbagai sajaknya, tidaklah berarti puisi itu berkisah tentang kota-kota di Kuba, Birma atau Indonesia. Tidak pernah bertandang ke tiga negara itu, Das Lied vom Surabaya-Johnny malah berkisah tentang jalur kereta api Birma yang dibangun Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Ini merupakan salah satu puisi yang ditulis Brecht untuk drama musik berjudul Happy End, diciptanya bersama komponis Kurt Weill. Baum lain lagi. Sesampai di Amerika dia tertarik untuk menengok temannya yang bermukim di Bali. Maka teman itu, seniman Walter Spies, merupakan sumber utama novel Liebe und Tod auf Bali yang ditulisnya ketika berada di Bali pada 1935. Inilah salah satu novel etnografis pertama yang juga berkisah tentang perang Puputan, yaitu bagaimana penjajah Belanda menaklukkan pulau Dewata.
Tidak kalah menarik juga adalah bahwa kalau di satu pihak nazi Hitler dengan rezim diktator Indonesia berjalan paralel atau sejajar dengan pelbagai persamaan, maka di lain pihak sentuhan antara Exilliteratur dengan Sastra Eksil justru ada pada pihak yang melawan keduanya. Dengan terus menulis puisi dan prosa di pengasingan, baik Baum maupun Brecht (serta banyak penulis lain) sama-sama melakukan perlawanan terhadap rezim fasis yang menguasai negeri mereka. Begitu pula orang-orang Indonesia yang walau terhalang pulang tapi di luar negeri terus menulis tentang negeri mereka, sampai sekarang.
Melarang tanpa membaca
Harus diakui, berbeda dengan nazi Hitler, rezim diktator Indonesia memang tidak melakuken ‘daripada’ pembakaran buku. Selama 32 tahun berkuasa rezim tangan besi ini juga tidak terang-terangan melancarkan Ausbürgerung alias pengumuman kepada dunia bahwa telah melakukan pencabutan kewarganegaraan. Tapi itu tidaklah berarti bahwa semua warga negara Indonesia di luar negeri bisa pulang kampung, tidak pula berarti bahwa Indonesia bebas sensor. Rezim diktator Indonesia jelas takut pada PBB yang dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia melarang pencabutan kewarganegaraan seseorang, apalagi kalau akibat pencabutan itu seseorang menjadi tak berwarga negara (bahasa Inggrisnya stateless). Karena itu si rezim diktator tidak bernyali untuk memberi istilah khusus bagi langkahnya tidak memperpanjang paspor warga Indonesia yang berada di luar negeri. Orang Indonesia di luar negeri yang kebanyakan mahasiswa itu memang harus menjalani screening untuk akhirnya menghadapi kenyataan bahwa paspor mereka tidak diperpanjang. Tapi si rezim diktator tidak bernyali untuk memberi nama langkahnya itu, apalagi mengumumkannya kepada dunia internasional. Hitler jelas lebih leluasa ketika memaklumkan politik Ausbürgerung, karena jangankan maklumat semesta hak-hak asasi manusia, pada zaman itu PBB saja masih belum ada.
Rezim kanan tangan besi Indonesia memang tidak perlu membakar buku, cukup mengganti ejaan, karena dampaknya sama: generasi muda tidak berniat lagi membaca buku zaman dulu karena ditulis dalam ejaan lain. Dengan membakar buku, maka bukan saja buku itu musnah, tetapi —dan ini yang terpenting— gagasan yang terurai dalam buku itu tidak lagi dikenal orang. Dengan mengganti ejaan terlihat betapa rezim diktator Indonesia lebih cerdik sekaligus lebih licik lagi, karena dia telah menutup sejarah Indonesia bagi generasi muda. Mana mungkin generasi milenial tertarik membacai buku-buku yang tidak ditulis dalam ejaan yang sekarang berlaku? Gagasan yang terurai dalam buku-buku lama itu jelas terlupakan orang.
Di samping pelbagai paralel alias persamaan antara rezim diktator Indonesia dengan nazi di atas, juga jelas bahwa pelaku perampasan buku yang terjadi di Indonesia tidak bekerja sesistematis pelaku Jerman. Ini mungkin perbedaan terpenting di antara keduanya. Pelaku Indonesia tidak punya daftar seperti pelaku Jerman. Pembuatan daftar di Jerman zaman fasis dipastikan bukan hanya telah terjadi klasifikasi, tetapi besar kemungkinan sebagai pustakawan Wolfgang Herrmann, si pembuat daftar, juga sudah benar-benar membacai buku-buku yang kemudian dimasukkannya ke dalam daftar hitam sebagai buku yang “tidak berjiwa Jerman”. Beda sekali dengan Indonesia. Pelaku Indonesia (baik polisi maupun sipil yang sebenarnya preman berkedok agama) jelas-jelas tidak terlebih dahulu membaca buku-buku yang mereka rampas. Paling jauh mereka hanya membaca judul buku-buku itu.
Buku Peter Kasenda berjudul Sukarno, marxisme dan leninisme yang dirampas polisi di Probolinggo (termasuk dua buku lain tentang Aidit) lebih berkisar tentang Bung Karno ketimbang tentang dua ideologi kiri itu. Di sini tampak sesuatu yang ganjil: kelompok pegiat literasi yang bertujuan membuat orang gemar membaca harus berhadapan dengan aparat kekuasaan yang justru tidak membaca buku. Niat mulia untuk menyebarkan bacaan dan membuat orang gemar membaca telah secara tidak masuk akal dihalang-halangi oleh kekuasaan sewenang-wenang, sisa-sisa rezim diktator. Di sini jelas betapa polisi maupun kalangan sipil yang melakukan perampasan buku malah memamerkan diri (bisa-bisa dengan bangga pula) sebagai pihak yang tidak membaca, apalagi paham isi buku-buku yang mereka ambil tanpa bayar
Lebih lucu lagi adalah razia dua buku karya Franz Magnis-Suseno, masing-masing berjudul Pemikiran Karl Marx dan Dalam bayangan Lenin. Keduanya diambil begitu saja oleh para anggota brigade, bersama setumpuk buku-buku lain yang mereka cap komunis di Makassar. Rohaniwan katolik keturunan Jerman Magnis-Suseno termasuk salah satu pengecam keras ideologi kiri tanah air. Inilah alasan utama mengapa bukunya diterbitkan oleh penerbit terbesar Indonesia.
Dalam pendahuluan buku Dalam bayangan Lenin, Franz Magnis-Suseno menulis bahwa pada april 2001 bukunya Pemikiran Karl Marx “dibakar di depan umum oleh sekelompok orang yang khawatir bahwa komunisme di Indonesia mau dibangkitkan lagi” (Magnis-Suseno, 2003: xviii). Sesudah itu rohaniwan ini marah besar, karena buku ini sebenarnya ditulis untuk mengkritik marxisme dan leninisme. Kedua aliran itu menurut Magnis-Suseno harus dilawan, dan untuk itu orang harus mengetahuinya dulu. Ia tidak setuju kalau orang cuma mengutuk tanpa mengerti. Hal itu, demikian Magnis-Suseno, “bukan hanya memalukan, melainkan juga berbahaya, karena membuat kita tidak mengetahui kekuatan lawan”.
Justru alasan Magnis-Suseno menulis kritik terhadap Lenin dan Marx itulah yang patut dipertanyakan. Apa perlunya mengkritik kedua pemikir kiri itu dalam buku berbahasa Indonesia di negeri yang sudah melarang penyebarannya? TAP MPRS nomer 25 yang melarang penyebaran ajaran Lenin dan Marx menyebabkan buku-buku kedua pemikir kiri tidak boleh dibaca lagi di Indonesia, sehingga kritik terhadap pemikiran mereka jelas tidaklah bermanfaat. Bahkan kritik itu bisa-bisa juga pengecut, tidak ksatria, tidak lebih dari mengkritik orang yang sudah dibungkam. Layaknya bertinju melawan seseorang yang diikat kedua tangannya. Jangankah memprotes, dalam bukunya Franz Magnis-Suseno sama sekali tidak menyinggung TAP MPRS nomer 25. Padahal bukankah seharusnya TAP ini dicabut dulu, sehingga buku-buku karangan Lenin dan Marx boleh beredar, baru sesudah itu Magnis-Suseno pantas menerbitkan buku yang berisi kritik terhadap pemikiran kedua tokoh komunisme. Dengan demikian pembaca bisa menilai sendiri bagaimana kritik itu setelah mereka membaca sendiri buku-buku Marx atau Lenin. Tapi sekarang buku-buku yang dikritik tidak boleh beredar, sementara buku yang mengkritiknya boleh. Betapa timpang!
Sekedar usul: sebaiknya Magnis-Suseno diminta menyusun daftar buku-buku berbahasa Indonesia yang memuat ajaran Marx dan Lenin, seperti yang dilakukan oleh Wolfgang Herrmann pada zaman Hitler berkuasa di Jerman dulu. Dengan demikian akan ada daftar yang bisa dipakai sebagai pegangan oleh para preman berkedok agama untuk beraksi. Dan pasti dalam melakukan razia itu mereka tidak akan merampas buku-buku karya Franz Magnis-Suseno. Moga-moga sang rohaniwan ini bersedia untuk berperan sebagai Wolfgang Herrmann, bukankah mereka berdua sama-sama kritis dan mengecam ideologi kiri?
Razia dan penyitaan buku di Makassar juga berbuntut menggelikan. Tindakan main sita yang dilakukan preman berkedok agama (berarti bukan kalangan resmi penegak hukum) membuat baik polisi maupun kejaksaan setempat (yang adalah pihak resmi penegak hukum) merasa kecolongan. Segera mereka bertindak, seolah-olah selalu aktif mengadakan razia dan penyitaan buku. Pihak polisi yang mengaku berupaya melancarken razia menghimbau gerombolan itu untuk menyerahkan buku yang disitanya. Sementara itu kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan menggunakan jejaring sosial pertama-tama untuk unjuk gigi sebagai pihak yang paling tahu hukum. Caranya dengan mendaftar pelbagai peraturan dan undang-undang yang menurutnya melandasi pelbagai larangan penyebaran paham komunisme, termasuk, ini telunjuk berkait, penyebaran radikalisme dan terorisme. Jelas kejati merasa perlu menyebut keduanya karena sekalian untuk menuding para preman berkedok agama yang begitu berani mendahului mereka melakukan razia. Istilah razia memang tidak digunakan, tapi untuk menutupi rasa kecolongan itu kejati Sulawesi Selatan mengaku aktif mengadakan pemantauan terhadap buku-buku terlarang, dan itu dilakukannya dengan menyertakan apa yang tampaknya seperti foto-foto pemantauan pada jejaring sosial.
Seperti peran Wolfgang Herrmann yang menyusun daftar buku-buku yang dianggap berlawanan dengan ideologi nazi, pelarangan buku tidak bisa dilepas dari peran pegiat buku. Polisi, kejaksaan atau preman yang menggunakan kedok agama jelas tidak menekuni buku, sehingga upaya mereka bergerak sendiri melakukan razia dan peyitaan (sebenarnya perampasan), tanpa melibatkan pihak buku, pasti akan gagal, bahkan menggelikan, karena mereka melakukan razia tanpa terlebih dahulu membaca buku-buku yang jadi sasaran. Tindakan mereka gagal karena menyita buku karangan Franz Magnis-Suseno yang justru mengkritik leninisme.
Pertanyaannya: adakah seorang Wolfgang Herrmann dalam dunia buku Indonesia masa kini? Zaman sudah berganti, sebagian besar aktivis buku sekarang yakin bahwa buku hanya bisa dilawan dengan buku, bukan dengan larangan atau pembakaran. Kalau orang masih beranggapan buku bisa dilarang dan dibakar, dan pasti ada saja kalangan yang berpandangan primitif seperti ini, maka dia sudah amat-sangat ketinggalan zaman. Bagaimana pula bisa melarang atau membakar buku pada zaman digital ini, ketika buku tidak hanya ada dalam bentuk fisik dengan sampul dan halaman-halaman, melainkan juga dalam bentuk elektronik? Tahukah polisi di Pare, di Padang, di Tarakan dan di Probolinggo, serta preman berkedok agama di Makassar, termasuk polisi dan kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan akan apa yang disebut e-book? Dalam hitungan detik, buku elektronik ini bisa disebar ke mana saja, termasuk ke negara atau wilayah yang memberlakukan larangan terhadap buku tertentu. Bagaimana bisa melarang buku elektronik, bagaimana pula bisa merazia buku modern yang tak punya bentuk fisik buku ini?
Pengasingan tak kunjung berakhir
Jelas razia buku dilatarbelakangi ideologi anti kiri warisan zaman diktator. Di lain pihak, tetap bercokolnya ideologi anti kiri si diktator, walaupun rezim kanan ini sudah dua dekade lebih terguling, membuktikan bahwa dari segi ideologi Indonesia masih tetap dalam cengkeramannya. Tersingkirnya rezim diktator tidak serta merta berarti lenyapnya ideologi rezim kanan ini. Kalau rezim itu dulu punya hari kesaktian Pancasila, maka tidak ada hari nasional yang memperingati jatuhnya rezim ini. Tahun baru Imlek yang sesudah rezim diktator bubaran merupakan hari libur nasional —berkat keputusan bernyali Gus Dur— jelas bukan pengganti hari kesaktian Pancasila. Upaya Gus Dur menghapus diskriminasi terhadap kalangan Tionghoa, terutama pencabutan Inpres 14/1967, berlangsung dalam momentum tepat karena kalangan Tionghoa termasuk korban kerusuhan massal di beberapa kota yang menyebabkan sang diktator turun tahta dan rezimnya bubaran. Berita perkosaan terhadap gadis-gadis dan perempuan-perempuan Tionghoa yang kemudian dibunuh menimbulkan kaget nasional yang lumayan besar, sehingga keputusan Gus Dur untuk mencabut larangan merayakan tahun baru Imlek yang dikeluarkan oleh si diktator, praktis tidak diprotes. Tetapi ketika Gus Dur berupaya mencabut TAP MPRS nomer 25 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran komunisme, marxisme dan leninisme maka dia harus berhadapan dengan militer yang begitu perkasa. Tak pelak lagi, inilah salah satu alasan penting mengapa tentara berada di belakang kejatuhan Gus Dur yang sebenarnya berupaya mengembalikan Indonesia seperti ketika didirikan, Indonesia yang lengkap karena terdiri dari Indonesia kanan dan Indonesia kiri.
Ketika menjabat presiden, Megawati tidak (berani?) mengambil keputusan tegas untuk menyingkirkan warisan rezim diktator. Misalnya dia tidak memaklumkan 21 mei (hari jatuhnya si diktator) sebagai hari reformasi, untuk menggantikan 1 oktober yang sampai sekarang tetap diperingati, walaupun ketika itu Megawati tidak pernah hadir pada upacara hari kesaktian Pancasila. Jangankan mengubur rezim diktator, memulihkan nama baik ayahnya saja tidak dilakukan oleh Megawati. Alhasil ideologi anti kiri zaman diktator tetap kokoh bercokol. Ini berarti tersingkirnya rezim itu bukan akibat perlawanan lawan-lawan politiknya, melainkan karena pemerintahan otoriter itu busuk dari dalam, terutama akibat korupsi. Krismon yang melanda Asia Tenggara pada 1997-1999 merupakan faktor penting pendorong kejatuhan si diktator dan rezimnya. Tapi tetap si diktator jatuh bukan karena lawan politik yang menjadi kuat, rezim itu bubaran bukan karena kalah oleh kekuatan politik alternatif.
Di Jerman, begitu nazi kalah Perang Dunia II, orang segera mengubur ideolog rezim fasis ini. Berlaku larangan terhadap NSDAP dan ideologi national sozialismus, bahkan hal-hal yang berbau nazi segera dianggap tabu dan dicurigai. Yang penting adalah faktor kekalahan nazi. Betapa berbeda dengan Indonesia begitu si diktator enyah. Rezim otoriter itu tidak dikalahkan oleh kekuatan alternatif lain, yang misalnya menghendaki perubahah menyeluruh di Indonesia (termasuk pencabutan TAP MPRS No 25). Perbedaan inilah yang tampaknya juga akan bisa menjelaskan akhir pengasingan yang dialami baik oleh para penulis Jerman setelah kalahnya rezim Hitler maupun penulis Indonesia menyusul tergulingnya si diktator.
Di antara pelbagai keputusan yang diambil oleh para penulis Jerman yang hidup dalam pengasingan menyusul runtuhnya rezim fasis Hitler, bisa diambil dua pola. Pertama kembali ke Jerman dan kedua tetap di Amerika. Menariknya kedua contoh itu ternyata juga pas bagi Bertolt Brecht maupun Vicki Baum, dua penulis yang menghasilkan karya yang menyinggung-nyinggung Indonesia atau bahkan karya tentang Indonesia. Brecht memutuskan kembali ke Jerman, terutama karena dia muak terhadap gelombang anti komunisme yang melanda Amerika akibat ulah Senator Joseph McCarthy. Di kampung halaman Brecht mendapati tanah air yang pecah: Jerman Timur yang komunis dan Jerman Barat yang kapitalis, dengan ibu kota Berlin yang juga terbelah yaitu Berlin Timur yang tetap merupakan ibu kota Jerman Timur dan Berlin Barat sebagai kota kapitalis di tengah-tengah wilayah komunis Jerman Timur. Ibu kota Jerman Barat adalah Bonn.
Pada 1947 Bertolt Brecht kembali ke Berlin Timur, ibu kota Jerman Timur. Bersama istrinya, Helene Weigel dia kemudian mendirikan das Berliner Ensemble (disingkat BE), gedung teater yang semula bernama Theater am Schiffbauerdamm, tempat dia pada 1928 untuk pertama kali mementaskan die Dreigroschenoper, drama musik satiris yang terkenal sampai sekarang, dengan Kurt Weil yang menggubah musiknya. Di BE itu dia mementaskan pelbagai karya baru, dan bekerjasama dengan dua komponis Jerman Timur: Paul Dessau dan Hanns Eisler yang juga sempat mengungsi ke Amerika.
Memperoleh kewarganegaraan Amerika pada 1938, Vicki Baum memutuskan tidak kembali ke Jerman. Sejak itu dia juga menerbitkan karya-karya lain dalam bahasa Inggris. Baru pada 1949 dia menjenguk ke Eropa, berkunjung ke Portugal, Prancis, Italia, Swiss dan Belgia, tapi pada kunjungan itu dia tidak singgah di Jerman maupun Austria. Dia tutup usia tahun 1960 di Los Angeles, empat tahun kemudian terbit otobiografinya, berjudul It was all quite different.
Bagaimana dengan para penulis eksil Indonesia? Adakah yang tergolong pada pola Brecht yang pulang kampung atau pola Baum yang terus menetap di luar negeri dan memperoleh kewarganegaraan asing? Memang ada penulis Sastra Eksil yang pulang kampung, tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar tetap tinggal di luar negeri dan memperoleh kewarganegaraan asing pula. Bahkan, seperti Utuy Tatang Sontani dan Agam Wispi, tidak sedikit pula yang tutup usia dan dimakamkan di pengasingan. Berakhirnya rezim kanan tangan besi tanah air memang membuat mereka lebih mudah pulang kampung menjenguk handai taulan, tapi tidak untuk menetap. Alasannya mudah diduga: di tanah air masih kuat bercokol politik anti kiri warisan rezim diktator.
Sebenarnya perbedaan Exilliteratur dengan Sastra Eksil sudah terlihat pada diri para penulis kedua sastra pengasingan ini. Kalau penulis yang tergolong dalam Exilliteratur adalah mereka yang sudah punya nama, maka alih-alih penulis bernama, Sastra Eksil sejatinya tidak melulu beranggotakan penulis. Mereka baru menulis ketika mendapati diri tidak bisa lagi pulang kampung. Waktu itu penulis Indonesia yang terdampar di luar negeri tidaklah banyak, Utuy Tatang Sontani salah satunya, kemudian juga penyair Agam Wispi. Dalam wawancara dengan Hersri Setiawan tahun 1992, Agam Wispi sebenarnya sudah menyinggung-nyinggung soal Exilliteratur yaitu Sastra Eksil Jerman ini, bahkan dia mengangkat contoh Anna Segher dan Bertolt Brecht, penulis dan penyair Jerman Timur. Sayang tidak ada yang tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut seruan Agam Wispi ini. Tapi untungnya orang-orang Indonesia lain yang senasib dengan Agam dan Utuy tidak tinggal diam. Mereka menulis dan kebanyakan memang berisi pengalaman hidup dalam buangan di luar negeri. Sebagian besar (kalau tidak semua) orang Indonesia yang terhalang pulang ini adalah kalangan terdidik, bagi mereka menulis jelas bukan sesuatu yang sulit. Alhasil kalau Exilliteratur semata-mata berisi fiksi, maka ke dalam Sastra Eksil seharusnya bisa digolongkan semua karya tulis yang dihasilkan oleh mereka yang terhalang pulang. Itu jelas mencakup fiksi maupun non-fiksi, juga prosa maupun puisi.
Manus Amici
Buku pasti tidak terpisah dari penerbit. Kalau Exilliteratur dimungkinkan antara lain karena peran tiga penerbit Belanda di atas, bagaimana dengan Sastra Eksil? Perlu ditegaskan bahwa orang-orang Indonesia yang terhalang pulang tidak henti-hentinya mengupayakan publikasi karya-karya mereka dengan menerbitkan banyak macam berkala. Tetapi ada satu upaya yang menonjol. Itulah penerbit Manus Amici di bilangan de Jordaan Amsterdam pusat yang menerbitkan buku-buku Pramoedya Ananta Toer dalam terjemahan bahasa Belanda. Manus Amici digagas dan dikelola oleh Soeraedi Tahsin, wartawan pendiri harian Bintang Timur yang pada 1964 diangkat Bung Karno menjadi dutabesar Indonesia untuk Mali (Afrika barat daya). Tidak berlebihan kalau dicatat bahwa juga berkat Manus Amici karya-karya Pramoedya dikenal dunia internasional. Pramoedya sendiri mencipta Tetralogi Buru dalam pengasingan (bahkan dalam kondisi yang sangat tidak kondusif untuk menulis), bukan pengasingan di luar negeri, melainkan pengasingan di pulau Buru. Menariknya dalam soal penerbit, Amsterdam ternyata punya makna sama, baik bagi Exilliteratur maupun Sastra Eksil. Dalam menghadapi sensor dan pembungkaman rezim diktator, jelas Manus Amici berada pada peringkat yang sama dengan Querido-Verlag, Verlag-Allert de Lange, maupun penerbit De Gemeenschap yang pada 1930an kucing-kucingan menerobos sensor Hitler nazi. Seperti ketiga penerbit Belanda itu, Manus Amici dan terutama Eddy Tahsin berhasil menyebarkan karya Pramoedya yang justru mati-matian ingin disensor oleh orde bau.
Peran penerbit ini belum pernah diungkap oleh pelbagai tulisan yang membahas Sastra Eksil Indonesia. Itu memang baru terlihat kalau orang membandingkan Sastra Eksil dengan Exilliteratur. Tak pelak lagi Exilliteratur memang merupakan perspektif jitu tidak hanya untuk menekuni Sastra Eksil, tapi juga untuk menyorot peran pelaku sensor dan penghalang kebebasan berpendapat yang sempat begitu ngebet kembali nongol di tanah air, seolah-olah kita masih ditongkorongin oleh rezim otoriter kanan jahanam itu.
Ringkasan Tiga Larik
Di Berlin, pada tempat pembakaran buku di Opernplatz (sekarang ganti nama menjadi der Bebelplatz), sejak maret 1995 dipasang monumen peringatan pembakaran buku 10 mei 1933. Terdiri dari dua plakat di atas dan rak buku di bawah tanah, monumen ini dirancang oleh seniman Israel Micha Ullman. Rak buku bawah tanah cukup bagi sekitar 20 ribuan buku, sesuai jumlah buku yang dibakar pada malam jahanam di musim semi itu. Rak itu sengaja dibiarkan kosong untuk menekankan bahwa buku-buku yang seharusnya ditaruh di situ sudah dibakar habis.
Ada dua plakat besi tertanam di alun-alun der Bebelplatz. Pada plakat kedua tertera bahwa monumen ini dipasang untuk mengenang pembakaran buku yang dilakukan oleh mahasiswa Jerman beraliran nazi. Sedangkan plakat pertama di sebelah kiri memuat cuplikan tiga larik puisi Heinrich Heine, penyair Jerman zaman Romantik abad 19, keturunan Yahudi yang buku-buku kumpulan puisinya ikut dilumat api pada malam terkutuk itu. Tiga larik itu berbunyi:
Das war ein Vorspiel, nur
dort wo man Bücher verbrennt
verbrennt man am Ende auch Menschen
Ini barulah awal belaka
di sana tatkala orang membakar buku
pada akhirnya orang juga membakar manusia (terjemahan Joss Wibisono)
Larik-larik di atas yang dicuplik dari drama liris berjudul Almansor ditulis Heine pada 1820, maka dibutuhkan kebencian selama 125 tahun sebelum larik-larik ngeri itu akhirnya berubah menjadi kenyataan keji. Kehebatan Heine tampak pada kejituannya meringkas sebuah rezim bengis hanya dalam tiga larik. Siapa berani menyangkal bahwa pembakaran buku pada musim semi 1933 itu hanya permulaan bagi Holocaust, genosida, pembunuhan massal yang tidak lain adalah industri maut dalam skala fantastis. Pada awalnya rezim nazi memang membakari buku, tetapi akhirnya rezim ini juga membakari jenazah para korban setelah sebelumnya mati digas dalam pelbagai kamp pemusnahan, terutama Auschwitz. Hebatnya lagi Heine menulis larik-lariknya itu pada zaman romantis, tatkala dia sendiri juga menghasilkan kumpulan puisi berjudul Lyrische Intermezzo (intermezzo liris), dengan salah satu larik berbunyi “Was will die einsame Träne” (apa kehendak linangan merana). Jelas saat itu tak pernah terbayangkan akan muncul satu rezim keji dengan korban sampai enam juta jiwa.
Kapankah Indonesia memiliki monumen untuk mengenang korban-korban rezim diktator yang menurut salah satu algojonya mencapai tiga juga orang? Walaupun jumlah itu hanya separuh korban nazi, tapi PKI sendiri memang pernah menyatakan bahwa anggotanya mencapai tiga juta orang. Sang algojo, dengan kata lain, menyatakan bahwa Genosida 65 telah berhasil mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya.
*Joss Wibisono, penulis dan mantan redaktur senior siaran Indonesia, Radio Nederland, Hilversum, Belanda.
Versi awal esai ini dengan judul “Fasisme, pelarangan buku dan sastra eksil” pernah dimuat di situs Tirto.id. Ini adalah pengembangan yang lebih rinci lagi dan lebih disesuaikan dengan perkembangan yang berlangsung di tanah air.
————-
Referensi
Buku/artikel
1. Alex Supartono, “Rajawali tak bisa pulang: karya-karya eksil Utuy Tatang Sontani” dalam Kalam (nomer 18 2001, ISSN 0854-7866), halaman 133-159.
2. Bettina Baltschev, Hölle und Paradies: Amsterdam, Querido und die deutsche Exilliteratur, (Berlin: Berenberg Verlag, 2016 ISBN 978-3-946334-08-8).
3. Bertolt Brecht, Brecht Liederbuch, Herausgegeben und kommentiert von Fritz Hennenberg, (DDR Berlin: Suhrkamp, 1984 ISBN 3-518-37716-7).
4. Vicki Baum, Liebe und Tod auf Bali, (Amsterdam: Querido-Verlag, 1937).
5. Henri Chambert-Loir, “Locked out: Literature of the Indonesian Exiles Post-1965” dalam Archipel Études interdiscipinares sur le monde insulindien (nomer 91, 2016), halaman 119-145.
6. Henri Chambert-Loir, “Bibliography of Exile Literature (Sastra Eksil)” dalam Archipel Études interdiscipinares sur le monde insulindien, (nomer 91, 2016), halaman 177-183.
7. Robert Cribb, “How Many Deaths? Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980)” dalam Ingrid Wessel dan Georgia Wimhöfer (editor), Violence in Indonesia (Hamburg: Abera Verlag, 2001 ISBN 3-934376-16-9), halaman 82-98.
8. Vanessa Hearman, “The last man in Havana: Indonesian exiles in Cuba” dalam Review of Indonesian and Malaysian Affairs, (volume 44, no. 1, 2010), halaman 83-109.
9. Heinrich Heine, Buch der Lieder, (Frankfurt am Mein: Insel Verlag, 1975 ISBN 3-458-31733-3).
10. Joss Wibisono, Saling Silang Indonesia-Eropa dari diktator, musik hingga bahasa (Jakarta: Marjin Kiri, 2012 ISBN 978-979-1260-16-9).
11. Joss Wibisono, “Fasisme, Pelarangan Buku dan Sastra Eksil,” dalam Tirto.id (30 juli, 2019).
12. Jeroen C.M. Linsen, “Boekverbrandingen in Duitsland: reden voor verontwaardiging?” skripsi bachelor, (Nijmegen: Radboud Universiteit, 2017).
13. Franz Magnis-Suseno, Dalam bayangan Lenin: enam pemikir marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2016 GM 204 03 061).
14. Helmut F. Pfanner, Exile in New York, German and Austrian Writers after 1933, (Detroit: Wayne State University Press, 1983 ISBN 0-8143-1727-8).
15. Dick van Stekelenburg, “Een paradijs verdwenen? Vicki Baums Liebe und Tod auf Bali” dalam Indische Letteren, (jaargang 11, 1996), halaman 163-178.
16. Koos van Weringh/Toke van Helmond, Joseph Roth in Nederland, (Amsterdam: De Engelbewaarder, 1979).
Situs web (internet)
1. “Die 12 Thesen ‘Wieder den undeutschen Geist’” dalam http://www.buecherverbrennung33.de/zwoelfthesen.html (dirujuk pada ahad 4 agustus 2019).
2. Hersri Setiawan “Menjadi Eksil, Puisi Eksil dan Indonesia: wawancara dengan Agam Wispi” dalam https://indoprogress.com/2013/08/menjadi-eksil-puisi-eksil-dan-indonesia-wawancara-dengan-agam-wispi/ (dirujuk pada rebo 7 agustus 2019).
3. “Schwarze Listen” dalam http://www.buecherverbrennung33.de/schwarzelisten_3.html (dirujuk pada ahad 4 agustus 2019).