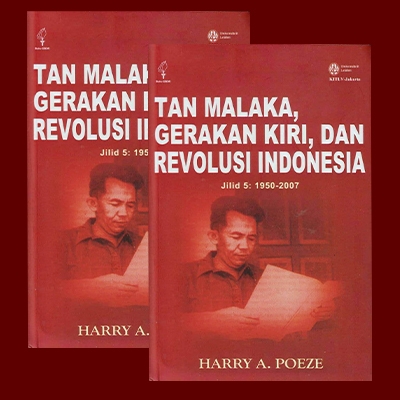Di antara Gunung dan Samudra: Sebuah Ziarah ke Kham-Tibet
Oleh Arahmaiani
Pagi itu sebelum matahari terbit dan suasana masih terasa gelap aku dan asistenku Li Mu sudah berdiri didepan hotel darurat yang bentuknya seperti kotak barang di pelabuhan. Karena bangunan hotel sebelumnya hancur dilanda gempa lalu untuk sementara digantikan kotak-kotak berbahan metal dengan konstruksi sederhana. Dengan tenang walau terasa masih lelah karena tidur yang tidak lelap kami menanti jemputan yang akan membawa ke desa terpencil di daerah Kham-Tibet. Yang merupakan bagian dari wilayah yang diistilahkan sebagai“atap dunia” karena memang terletak di ketinggian diatas 4000 meter dari permukaan laut. Kawan baru kami bernama Nimarinchen orang Khampa akan mengantar ke desa Lab yang konon lumayan jauh letaknya dari kota Yushu dimana kami menginap. Ya aku ataupun Li Mu berkunjung ke wilayah Kham untuk pertama kalinya. Dan tentunya belum pernah mengunjungi desa itu selama hidup kami. Memang ini pengalaman pertama mampir di wilayah Plateau Tibet yang terasa seperti memasuki alam mimpi. Namun sekaligus nyata. Alamnya memang berbeda dengan tempat kelahiranku atau tempat-tempat yang pernah aku kunjungi. Seperti memiliki keunikan dan kekhasan suasana tersendiri.
Gempa besar yang melanda wilayah yang diisolasi ini telah memakan korban ribuan orang meninggal, terluka dan kehilangan tempat tinggal. Kota Yushu maupun desa-desa di wilayah Kham hancur berantakan. Sebagai aktifis lingkungan hidup yang pernah berurusan dengan korban gempa di Yogyakarta aku merasa terpanggil. Dan assistenku Li Mu begitu mantap menyanggupi untuk menemani. Li Mu adalah seniman muda Cina yang kreatif dan cerdas – dan saya menaruh rasa percaya padanya. Seperti umum diketahui wilayah Tibet yang sudah dikuasai Cina sejak tahun 1959 tampaknya tetap masih bermasalah. Dan menjadi semakin rumit dimasa gempa melanda. Memang pengetahuanku tentang dinamika politik di Tibet waktu itu masih sangat sedikit. Kemudian secara bertahap seiring dengan kegiatan yang aku kerjakan disana akupun perlahan memahaminya. Setelah melakukan diskusi dengan kurator Biljana Ciric dari Museum Seni Kontemporer Shanghai kami diminta menandatangani perjanjian bahwa kami akan menanggung segala resiko sendiri. Sekalipun kami tak mempunyai kontak atau orang yang kami kenal disana – aku dan Li Mu memutuskan untuk berangkat. Itulah awal perjalananku ke Tibet pada tahun 2010. Dan kemudian berlanjut dengan kegiatan untuk menangani permasalahan lingkungan hidup, bekerjasama dengan para biksu dan penduduk disana hingga saat ini.
Sepertinya Li Mu dan aku memiliki kemiripan karakter: menyukai tantangan dan petualangan. Maka dengan yakin dan mantap kami terbang ke kota Yushu (kota kecil diwilayah Kham). Lalu secara kebetulan bertemu orang-orang Tibet yang ramah dan terbuka di bandara sesudah kami mendarat. Yang membantu kami untuk bertemu dengan pimpinan biara di kota itu dan mendapatkan informasi lengkap tentang dampak bencana yang melanda. Juga sang pimpinan yang biasa disebut Lama itu menyarankan aku untuk pergi ke dusun yang jauh dari kota demi keamanan. Pada saat itu aku memang tidak terlalu paham situasi dan kondisi politik di wilayah tersebut. Baru sesudah sampai disana dan mendengar penjelasan aku mulai mengerti bahwa wilayah Kham ini merupakan area khusus yang diisolasi dan diawasi mengingat situasi dan kondisinya yang dianggap penting dan istimewa. Orang Kham terkenal sebagai “warrior” atau ksatria dan ketika wilayahnya mulai diduduki pihak China, mereka melakukan perlawanan intensif dan menewaskan banyak tentara Cina.

Photo 1 – Biara Jergu di Yushu (setelah dibangun kembali)
Pagi itu jemputan tiba sebelum matahari terbit dan Nimarinchen datang sendirian menyetir mobilnya. Suasana masih terasa gelap ketika kami meninggalkan area kota. Sambil menyetir dan menyusuri jalan aspal yang masih sepi ia berbicara kepada Li Mu dan menjelaskan sedikit rencana dan arah perjalanan serta waktu yang akan ditempuh. Hingga di tempat dimana mobil menyebrangi sebuah jembatan yang panjang Nimarinchen berhenti berbicara dan kemudian membelokan mobilnya diujung jembatan. Lalu memasuki jalanan berbatu dan agak sempit disamping sebuah sungai yang besar dengan suara arus air yang menderu. Nimarinchen kemudian mengaktifkan audio mobil dan memperdengarkan suara mantra yang dilantunkan para biksu – yang belum pernah kudengar sebelumnya dan terasa magis, bahkan sakral. Sementara mobil berjalan perlahan aku yang duduk didepan disampingnya, merasakan laju mobil seperti agak bergoyang-goyang karena jalan berbatu yang kami lalui bukan jalan yang mulus dan rata. Pandangan matapun terbatas pada area yang disinari lampu mobil. Langit terlihat masih gelap saat itu namun udara terasa sangat segar dan melegakan.
Sambil menyusuri jalan kecil berbatu dipinggir sungai Yangtze dan mendengarkan mantra, perlahan langit mulai terlihat berubah warna. Dan alam sekitarnya mulai memperlihatkan bentuk dan konturnya sekalipun dimulai dengan nada warna hitam dan kelabu kemudian secara perlahan menjadi semakin terang dan mulai menampakan detilnya. Bukit terjal berbatu disamping jalan sebelah kanan tampak penuh lekukan yang dihiasi bebatuan beragam ukuran yang diselingi rerumputan hijau. Juga kulihat sungai yang sangat lebar dan curam disisi lainya. Jalan yang kami lalui awalnya tampak datar tetapi kemudian menanjak dan berkelok-kelok. Disisi bebukitan terjal lalu tampak batu-batu besar bertonjolan yang membuat aku terpana melihatnya. Dan ketika cahaya matahari mulai terbit maka pemandangan terlihat menjadi sangat dramatis – membuat aku begitu terpesona. Sebab tak pernah dalam hidup ini kulihat pemandangan begitu luar biasa indahnya! Namun sekaligus juga seperti berbahaya – karena posisi bebatuannya seperti rentan untuk jatuh dan meluncur kebawah. Lalu bagian pinggir jalan di sisi sungai tak ada pagar atau pembatasnya! Yah, agak menakutkan memang sebab posisi mobil seperti berada di antara “gunung dan samudra”. Diiringi mantra para biksu yang sangat menyentuh kedalaman rasa dengan visualisasi dramatis yang menyentuh rasa keindahan yang kuat – entah kenapa suasana itu lalu menyebabkan airmataku berjatuhan.

Photo 2 – Sungai Yangtze, Kham, Tibet
Kuhapus airmata dengan bagian jaket yang menutupi kedua belah tanganku karena airmataku berjatuhan dengan derasnya seiring dengan lantunan mantra dan perubahan cahaya. Nimarinchen yang sedang menyetir mobilpun menyadari apa yang kualami dan ia sempat memperhatikan untuk beberapa saat. Tapi ia tidak mengucapkan sepatah katapun atau bertanya. Dan dari pandangan matanya ia seperti memahami apa yang sedang aku alami. Aku tidak merasa sedih – tapi entah mengapa aku seperti mengalami rasa terharu yang mendalam – yang sangat sulit untuk aku jelaskan. Hanya bisa aku rasakan. Apa yang kulihat dan kudengar telah menggugah sesuatu dikedalaman hatiku. Akupun terisak untuk beberapa saat dan terhanyut dalam aliran rasa haru yang gelombangnya bergejolak bagai aliran sungai Yangtze di musim panas itu. Dan suara mantra para biksu seperti bergema secara berulang-ulang di relung-relung hatiku. Menggugah kedalaman rasa yang memantik suasana khidmat dan meditatif. Aku tak tahu berapa lama hal ini berlangsung persisnya karena aku seperti memasuki alam lain yang menggugah rasa di kedalaman bathin yang begitu mengharukan.
Begitulah pengalaman pertama yang luar biasa dan takkan pernah bisa aku lupakan ketika menyusuri sungai Yangtze dan menaiki bebukitan terjal menuju Biara Lab di sebuah desa terpencil Plateau Tibet. Yang akan membuka jalan lebar kearah pemahaman hidup dimana sebelumnya aku sering merasa bingung, tegang dan kuatir. Selain merasa terisolasi dan hidup di tempat sepi. Pengalaman unik ini kemudian menjadi awal dari cerita kehidupan penuh makna didalam keheningan jiwa yang ingin mengabdi dan memberi. Merindukan kehidupan berwarna-warni didalam kedamaian abadi. Seraya menggenggam bebungaan cinta kasih yang akan diserahkan kepada semua mahluk penghuni planet bumi. Sambil melantunkan nyanyian do’a untuk keselamatan kehidupan didalam mengarungi segala tantangan hidup lahir dan bathin ketika menyelami kedalaman makna. Membuka kesadaran tentang “kekosongan” dan memberikan pencerahan. Yang membimbing aku untuk memahami maksud dan tujuan hidup yang fana ini. Kearah yang lebih terang, mencetuskan harapan dan menjanjikan kebahagiaan.
Pertemuan dengan pimpinan biara Lab (Lab Gompa) yang dipanggil Kadheng Rinpoche yang ramah dan bersikap terbuka memberi semangat untuk aku melaksanakan keinginanku melakukan riset seputar masalah lingkungan hidup. Beliau juga memberikan informasi penting dan sangat berharga yang membuka ruang hidup baru. Kemudian mendorong aku untuk secara serius mempelajari kembali warisan budaya leluhur yang sepertinya terlupakan ditempat asalnya sendiri. Setelah mendengar pemaparan sejarah budaya dan tradisi biaranya yang ternyata berasal dari negriku (yang membuat aku terperanjat dan terbengong!). Karena memang selama hidupku aku tak pernah memahami fakta ini. Sekalipun aku sangat tertarik dengan sejarah budaya dan mencoba untuk mempelajarinya sejak mulai kuliah di Seni Rupa ITB di Bandung (dimulai tahun 1979). Demikianlah, Kadheng Rinpoche adalah orang yang telah membukakan tirai pengetahuan leluhur yang hilang atau tersembunyi. Kemudian membangkitkan semangat hidup yang belum pernah kualami sebelumnya. Dan memberikan semacam kekuatan untuk terus menggali makna kehidupan yang terkadang tampak sulit dan menyedihkan. Diwarnai kekelaman penderitaan hidup manusia maupun makhluk lainnya.

Photo 3 – Bersama Kadhheng Rinpoche dan Geshe Sonam Lobsang
Didalam waktu singkat selama 10 hari dengan dibantu Li Mu dan seorang penterjemah bernaman Sonamdawa, serta biksu bernama Sonamrinchen aku melakukan riset intensif. Selain berdiskusi dengan para biksu lainya dan tentunya Kadheng Rinpoche serta kepala biara yang dipanggil Geshe Sonam Lobsang – yang juga menjadi bagian penting dari proses riset ini. Lagi-lagi aku merasa mendapat kejutan ketika berdiskusi dengan mereka karena cara berkomunikasinya yang terbuka dan kritis! Pembawaanku yang cenderung suka melontarkan pertanyaan dan kritis direspon dengan sangat positif oleh mereka. Sehingga membuat aku bukan saja merasa lega dan nyaman tetapi tentunya juga membangkitkan semangat dan merangsang imajinasi kreatifku. Ya, setelah beberapa hari tinggal disana dan mendapat kesempatan untuk mengamati kegiatan sehari-hari para biksu, aku bisa menyaksikan bagaimana mereka berlatih berdebat serius selama berjam-jam mengasah kemampuan logis dan rasional secara intensif setiap harinya. Selain bermeditasi dan melakukan ritual-ritual.
Ketika petang hari tak ada kegiatan – biasanya sesudah makan malam aku akan berdiskusi dengan Li Mu atau membuka catatan dan merenungkanya. Pada suatu kesempatan berdiskusi petang hari dengan Li Mu, ia mengakui kalau sebetulnya ia terpesona dengan praktek debat para biksu. Mulanya ia mengira bahwa kegiatan para biksu hanya fokus di meditasi dan berdo’a saja – yang membuat dia sebelumnya cenderung berkomentar sinis atas kehidupan mereka. Karena bagi dirinya kegiatan seperti itu tak ada manfaatnya. Dan ketika aku merenungkan acara kegiatan berdebat itu, memang membuat aku berpikir dan juga merangsang imajinasiku: melayang ke masa lalu. Membayangkan tradisi budaya biara yang dipraktekan di Biara Muara Jambi di Sumatra dimasa kerajaan Sriwijaya. Membayangkan para biksu yang sedang melakukan perdebatan seru dengan gaya khas. Dan para biksu itu bukan hanya berasal dari wilayah Nusantara saja – tetapi juga banyak yang datang dari Cina maupun India! Ya, bayangan tersebut bukan hanya khayalan saja tapi didasari oleh fakta.

Photo 4 – Para biksu sedang berdebat
Tercatat dalam sejarah bahwa biara Muara Jambi yang dibangun sekitar abad ke 7 hingga kini masih bisa disaksikan reruntuhan peninggalannya. Dimana bisa dilihat candi-candi berundak tempat peribadatan yang terbuat dari bata merah. Bahkan 8 candi dari jumlah keseluruhan sebanyak 82 buah – kini sudah direnovasi. Memang wilayah biara ini sangat luas dan konon merupakan biara terbesar di Asia Tenggara. Dengan model bangunan candi yang unik dengan tata ruang lingkungan yang alami. Dan didasari oleh falsafah keyakinan sebagai dasar konstruksinya, desain keseluruhannya tampak tertata dengan baik. Selain itu ada tambahan informasi yang lebih mencengangkan lagi adalah soal keterhubungannya dengan candi Budha terbesar di dunia – yaitu candi Borobudur di pulau Jawa. Ternyata di masa itu kerajaan Sriwijaya dan Medang Kamulan di Jawa bersatu dalam ikatan kekeluargaan dan budaya keyakinan yang pada dasarnya sama. Yaitu apa yang diistilahkan sebagai keyakinan “Siwa-Budha” atau dulu diistilahkan sebagai Tantrayana Budhisme. Yang tentu saja merangsang imajinasi dan fantasiku. Dan semakin tetarik untuk mempelajari sejarahnya.

Photo 5 – Candi Muara Jambi

Photo 6 – Candi Borobudur
Namun disisi lain aku juga mulai memikirkan situasi lingkungan hidup yang tampak sangat bermasalah. Dari hal yang kasat mata saja aku bisa melihat betapa sampah plastik mengotori hampir seluruh bagian desa. Saluran sungai-sungai kecilnya penuh dengan sampah-sampah berbahaya ini, bahkan tampak hampir menyumbat! Selain airnya tampak keruh dan tentunya tak layak untuk dimanfaatkan. Ternyata masalah ini timbul dari laku konsumsi pangan maupun minuman produk industri. Nah, ini kejutan lainya lagi: mereka umumnya sudah tidak memproduksi bahan pangan sendiri. Bahan pangan yang sudah diproses dan digemari itu datang dari Cina – dan kebanyakan menggunakan kemasan plastik. Begitu pula dengan air minum, mereka juga sudah mengkonsumsi air ‘galonan’ atau botolan (yang tentu saja menggunakan wadah berbahan plastik). Aku betul-betul heran kok mereka malah minum air ‘galonan’ padahal wilayah mereka adalah sumber mata air benua Asia! Waktu itu aku betul-betul merasa kaget dan heran mengapa di daerah terpencil dan jauh dari kota bisa terjadi hal seperti itu. Dan aku menjadi sangat penasaran ingin memahami apa sebetulnya yang terjadi.
Ya, wilayah Kham ini adalah bagian yang istimewa dari Plateau Tibet. Selain merupakan tempat kelahiran 5 orang Dalai Lama dan tempat pertemuan 3 sungai besar: Yangtze, Mekong dan Sungai Kuning, hal lain yang mungkin dianggap paling penting dimasa sekarang adalah kenyataan tentang kekayaan sumber daya alamnya yang luar biasa. Bahkan oleh kalangan ilmuwan wilayah ini diberi julukan “the future of China” (“masa depan Cina”). Selain juga kondisi keberagaman hayatinya yang memang sangat kaya. Plateau Tibet sendiri sering istilahkan sebagai “Kutub Ketiga” – yaitu salah satu bidang es terluas dimuka bumi, disamping Kutub Utara dan Kutub Selatan. Sisi penting lainya lagi juga dikenal sebagai “Tower Air Asia” karena merupakan sumber mata air dari sungai-sungai besar di Benua Asia seperti sungai Yangtze, Mekong, Sungai Kuning, Gangga, Indus, Brahmaputra, Salween, Irrawadi & Lena yang menghidupi lebih dari 1,5 milyar penduduk benua ini. Jadi tempat ini merupakan wilayah penting yang akan mempengaruhi situasi lingkungan hidup global.
Dengan kondisi bumi yang kini dilanda “pemanasan global” sebagai dampak dari kerusakan lingkungan hidup dimana suhu udara meningkat dan menjadi semakin panas, telah menyebabkan es-nya meleleh dengan cepat! Menimbulkan bencana banjir dan longsor yang terjadi secara rutin di seluruh benua Asia. Yang tentu saja menyebabkan penderitaan dengan korban dalam jumlah yang tidak sedikit setiap tahunnya. Bahkan sebuah kota bisa seperti ditenggelamkan (petaka seperti ini pernah terjadi di Bangladesh). Atau jutaan orang harus mengungsi seperti yang pernah terjadi di Thailand. Bersamaan dengan timbulnya malapetaka ini juga telah menyebabkan penguapan permafrost yang menambah peningkatan suhu udara! Dan menyebabkan gangguan keseimbangan ekologi yang menjadi semakin parah. Sehingga dampak buruknya tidak saja terjadi dan bisa dirasakan di wilayah lokal dan regional, namun juga di tataran global. Keluhan cuaca atau musim menjadi tidak menentu selain suhu udara meningkat atau ditempat yang dingin cuacanya makin dingin, menjadi hal yang terjadi diberbagai tempat di dunia. Semua penghuni planet bumi sepertinya sekarang sudah bisa merasakan dan mengalami dampak perubahan iklim ini.

Photo 7 – Bencana Banjir di Bangladesh
Tak terasa waktu berlalu dengan cepatnya, setelah hampir 2 minggu berada di “atap dunia” dan mencoba memahami situasi dan kondisinya kamipun harus kembali ke Shanghai. Pekerjaan lain yaitu persiapan pameran bersama seniman-seniman Indonesia lainya sudah menanti. Maka sekalipun aku sangat menyukai pengalaman bertemu teman-teman orang Tibet dan menikmati keheningan malam ataupun langit biru dihiasi awan putih disiang hari dengan padang rumput yang luas terhampar. Ataupun merenung dipinggir sungai besar yang tampak seperti tak ada ujungnya. Maka dengan berat hati akhirnya aku harus mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Hari terahir di desa Lab kami diundang makan siang di rumah Kadheng Rinpoche yang dihadiri beberapa biksu-biksu senior lainnya. Kamipun sempat berdiskusi cukup lama sesudah aku ungkapkan poin-poin penting hasil penelitian dan aku jelaskan beberapa permasalahan yang kutemukan. Mereka menanggapi dengan antusias dan serius. Sehingga akupun menjadi berani untuk menyampaikan gagasan penataan lingkungan.
Usulan pertama yang kusampaikan saat itu adalah menyangkut masalah yang gamblang, yaitu pengelolaan sampah. Karena memang ini masalah kasat mata yang bisa disaksikan langsung oleh siapapun yang tinggal di desa itu. Yang juga berkaitan erat dengan persoalan air dan sumbernya, maupun pemanfaatannya. Respon yang positif dan bersemangat menanggapi usulan ini seperti muncul serentak dari semua yang hadir. Bahkan mereka seperti langsung punya ide tentang pelaksanaannya yaitu dengan membayar tukang sampah. Sedangkan aku punya ide agak berbeda: untuk mengajak semua penduduk desa bekerjasama dengan para biksu mengelola persoalan sampah ini. Karena keterlibatan semua pihak ini penting dan sekaligus akan menjadi program pendidikan serta ungkapan rasa tanggung-jawab individu didalam kebersamaan. Tapi mereka menjadi seperti agak kaget dan tergagap ketika mendengar saranku untuk mengajak para biksu ikut dalam kegiatan ini. Yang membuat aku merasa agak bingung dan merasa tak paham dengan apa sebetulnya yang terjadi.
Ya itulah cerita awal pengalaman yang menarik dalam hal kerja bersama dengan para biksu. Sehubungan dengan aturan dan disiplin ketat kehidupan mereka yang didasari dengan ajaran dan keyakinannya. Yang pada mulanya aku tak pahami samasekali. Seperti dalam kasus penglolaan sampah ini misalnya, ternyata mereka kaget sekali dengan usulan untuk bekerjasama dengan orang biasa. Apalagi mengurusi sampah! Karena didalam kebiasaan hidup dan tradisi mereka ternyata ada aturan untuk tidak mengurusi kehidupan duniawiah. Apalagi bekerja bersama orang biasa mengurusi sampah akan dilihat sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan dan bahkan mungkin dianggap menyimpang dari tata aturan kehidupan biara. Namun Kadheng Rinpoche menanggapi dengan tenang dan positif mengatakan bahwa beliau paham usulan dan argumenku. Dan beliau akan mencoba untuk berdiskusi lalu berunding dengan para biksu. Katanya nanti kalau sudah ada kejelasan aku akan dikabari.

Photo 8 – Diskusi di rumah Kadheng Rinpoche
Demikianlah perjalanan pertama dan singkat ke Tibet Plateau yang tak bisa kulupakan. Begitu sangat mengesankan dan menyentuh. Selain seperti memasuki alam mimpi yang indah juga aku melihat dan merasakan beberapa hal yang seperti terasa tak asing bagi diriku. Atau bahkan aku kenali. Selain keramahan, tata-krama dan tradisi berdebat sebetulnya ada hal lain lagi yang begitu membuat aku terpana, yaitu tradisi bendera do’a. Berdera-bendera do’a berwarna-warni bagai pelangi dan dikibarkan di alam terbuka memang mengejutkan karena mengingatkan diriku akan karya “Proyek Bendera” ku sendiri. Yaitu karya seni berbasis komunitas yang dimulai pada tahun 2006 ketika bekerjasama dengan komunitas para santri dari Pesantren Amumarta di Yogyakarta sesudah dilanda gempa.Yang juga telah membawa atau mengantarkan aku ke Tibet! Sebab karya berbasis komunitas dengan ekspresi berupa bendera-bendera warna –warni yang dihiasi kata kunci adalah karya yang akan dipamerkan di Museum Seni Kontemporer Shanghai. Dan memberi kesempatan padaku untuk mengunjungi Tibet. Memang terasa aneh – tapi juga sangat nyata dan tak terbantahkan hubungannya.

Photo 9 – Bendera Doa di Area Kuil Whencheng Koncho di Yushu

Photo 10 – Proyek Bendera ditampilkan di Candi Borobudur
Semenjak meninggalkan Tibet dan pulang ke Yogyakarta – aku tak pernah bisa melupakan pengalaman kunjungan singkat itu. Yang mendorong aku untuk menelusuri dan mempelajari jejak warisan budaya leluhur yang seperti terlupakan itu. Selain juga mencari informasi tentang Plateau Tibet yang lebih mendetil khususnya dari sisi yang kuanggap paling penting yaitu aspek lingkungan hidup maupun sosial-politik. Dan teknologi di era digital telah sangat membantu aku untuk mengakses buku-buku maupun kontak-kontak teman yang mempelajari ragam bidang pengetahuan yang berhubungan dengan tema-tema tersebut. Namun yang paling membuat aku bersemangat adalah terbukanya kemungkinan untuk mempelajari warisan budaya leluhur di biara bergaya Tibet (Sera Jey) di India. Diawali dengan kedatangan Tashi-la (Ven Tenzin Dakpa) – seorang biksu asisten pribadi Dalai Lama – mengunjungi tempat tinggalku di Tempuran Elo-Progo dan melakukan ritual disana. Selain menemui Kyai Masrur di pesantren Al-Qodir di Cangkringan Yogyakarta. Maka akupun lalu berangkat ke India. O, ya Tempuran Elo-Progo dimasa lalu adalah tempat pelatihan meditasi atau semedhi para biksu.

Photo 11 – Tempuran Elo-Progo, Magelang, Jawa Tengah
Keinginan mempelajari tradisi budaya leluhur itu kemudian akan membuka kesadaran tentang pentingnya “penyelarasan antara pikiran-ucapan-tindakan” yang merupakan salah satu prinsip dasar ajaran dari tradisi budayanya. Selain prinsip dasar lain yang tak kalah pentingnya yaitu memahami “keseimbangan antara kekuatan berlawanan di alam semesta”. Dan didalam prosesnya, selama bekerja di Plateau Tibet aku mendapat kemungkinan mendalami pengetahuannya karena diberi kesempatan untuk mempraktekan penerapan ajaran dan pemikiranya kedalam tindakan/aksi nyata. Situasi kondisi masyarakat di desa Lab waktu itu, khususnya di ranah ilmu pengetahuan umumnya agak bermasalah, karena mereka belum mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan modern. Dan kondisi ini telah membantu aku untuk lebih memahami tradisi budaya mereka dan bagaimana menghubungkanya dengan science dan teknologi. Untungnya ketika belajar di biara Sera Jey aku bertemu dengan biksu-biksu yang juga merangkap sebagai ilmuwan modern. Aku juga sering diundang menghadiri acara-acara pertemuan ataupun konferensi dengan para biksu dan biksuni yang berasal dari Barat. Yang pada umumnya juga berprofesi rangkap sebagai ilmuwan dan/atau filsuf.
Dimasa itupun aku mendapat kesempatan untuk mempelajari sejarah tradisi biara yang dimulai di India (Biara Nalanda) dan kemudian dikembangkan di Muara Jambi. Melahirkan ajaran kesadaran yang luhur dan khas yang disebut sebagai ajaran Bodhisatwa. Yaitu ajaran yang menekankan pencarian ilmu pengetahuan dan praktek kebajikan untuk supaya bisa menjadi bijak dan mampu menolong siapapun yang dilanda masalah dan penderitaan. Maka pada saat itu banyak biksu dari Cina dan India yang datang belajar di Biara Muara Jambi ataupun berlatih meditasi di Tempuran Elo-Progo. Tersebutlah nama seorang biksu yang kelak membawa ajaran warisan leluhur kita ke Tibet, bernama Atisha Dipankara Srijnana yang berasal dari India. Seorang pangeran yang memutuskan untuk menjalani kehidupan spiritual ini berguru para Mahaguru lokal bernama Dharmakirti (atau kalau di Tibet dikenal dengan sebutan Lama Serlingpa). Di Tibet Atisha mendirikan sekolah Kadampa dan menjadi pelopor pembaharuan ajaran baik di Tibet maupun di dunia Budhis pada umumnya. Sekolah ini adalah cikal bakal dari sekolah sekte Gelugpa yang dipimpin langsung oleh Dalai Lama.

Photo 12 – Belajar di Biara Sera Jey, India
Lalu pada tahun 2011 aku mendapat undangan dari Prof Rudiger Korff ketua Departmen Asia Tenggara, Fakultas Filsafat Universitas Passau di Jerman untuk mengajar disana. Tentu saja aku menerimanya dengan senang hati. Walaupun aku hanya sanggup untuk mengajar satu semester saja setiap tahunnya (pada semester musim panas), mengingat banyaknya pekerjaan lain yang harus kutangani. Pengalaman mengajar (dan juga belajar) yang masih berlangsung hingga saat ini telah banyak membantu aku didalam memahami masalah maupun tantangan dalam cara pikir modern maupun sistem pendidikannya. Khususnya di lembaga pendidikan tinggi seperti universitas. Juga dalam hubunganya dengan pengetahuan “spiritual” atau kemampuan manusia untuk memahami wilayah pengetahuan “metafisik” yang merujuk pada teori modern. Dengan penerapan pendekatan “transdisiplin” (istilah yang digunakan di Jerman untuk istilah “interdisiplin”) praktek berkesenianku diakui dan diapresiasi oleh para akademisi: dianggap sebagai contoh nyata praktek kerja yang tidak hanya dibatasi tataran teori – namun sekaligus dilengkapi penerapannya di dalam kehidupan.
Dukungan luar biasa atas praktek yang kukerjakan baik oleh lembaga tradisi biara Budha di Tibet dan India maupun lembaga pendidikan tinggi modern di Jerman ini tentu saja mendorong semangatku untuk lebih jauh mengeksplorasi kreatifitas yang tidak hanya dibatasi di wilayah seni saja. Dan interaksi dengan mereka yang mengajar dan yang belajar atau para murid, juga memberi stimulasi pada pengembangan imajinasi dan fantasi. Utamanya untuk menemukan solusi inovatif dan kreatif dari berbagai permasalahan yang dihadapi manusia (khususnya komunitas-komunitas yang bekerjasama denganku). Dengan praktek di lapangan semacam ini maka akupun makin memahami bahwa seni sebagai media memiliki fleksibilitas luar biasa. Menjadi penghubung berbagai disiplin ilmu maupun tradisi filsafat, keyakinan dan kebudayaan. Membuka kemungkinan penemuan ilmu pengetahuan dan gagasan baru atau yang bersifat alternatif. Selain pendalaman pengetahuan lama dan pengembangan metodanya. Juga dalam kaitanya dengan strata sosial, seni bisa melebur “pemisahan” yang inklusif ataupun “pengkelasan”. Walau disisi lain juga bisa dijadikan simbol eksklusifitas.
Maka proyek dengan fokus utama masalah lingkungan hidup di Tibet pun berjalan dengan lancar. Didalam jangka waktu 5 tahun pertama kami berhasil melaksanakan beberapa proyek dasar seperti: mengelola sampah dan mendaur ulang, menanam pohon, menghidupkan kembali pertanian organik, mengaktifkan kembali budaya dan gaya hidup nomadik, dan membuat sistem enerji alternatif (solar panel dan hidro-power). Dan dipraktekan oleh penduduk dari 16 desa. Sehingga di tahun 2015 pemerintah Cina menyetujui dan mendukung gerakan lingkungan hidup ini. Dimasa awal sebelum pekerjaan ini dimulai – tentu saja aku harus mendapat izin dari pemerintah. Dan aku mendapatkannya sekalipun dengan persyaratan yang tidak ringan: tidak boleh mendapat bantuan dari luar, atau khususnya dari organisasi internasional. Yang tentu saja pada mulanya membuat aku agak bingung. Namun dengan semangat dan dorongan para pimpinan Biara Lab yang antusias, membuat aku merasa cukup optimis. Dan memang dalam pelaksanaanya mereka sangat bisa diandalkan. Begitu pula dengan kelompok orang biasa yang kemudian bergabung kedalam gerakan secara konsisten.

Photo 13 – Para biksu sedang menyiapkan pepohononan untuk ditanam

Photo 14 – Seorang biksu mendo’akan pohon yang baru ditanam
Nah, jadi untuk urusan pekerjaan lingkungan hidup di Plateau Tibet boleh dikatakan berhasil dan terus berkembang hingga saat ini. Yang menjadi masalah dan tantangan yang masih merupakan “pe-er” (pekerjaan rumah) adalah persoalan warisan budaya leluhur yang sepertinya hilang dari ingatan bangsa Indonesia. Kalaupun masih ada sisa pemahaman dan prakteknya dibeberapa kelompok tertentu seperti di Jawa & Bali, ini juga bukan tanpa masalah. Mengingat orientasi kehidupan modern yang cenderung mengutamakan sisi material. Yang ditegaskan lewat ideologi “pembangunan” yang diterapkan rezim Orde Baru sejak mereka berkuasa di negri ini. Dan sepertinya masih terus berlanjut sekalipun rezim Orde Baru sudah jatuh pada tahun 1998. Maka akibatnya ranah budaya tidak pernah dianggap penting! Kecuali jika bisa dimanfaatkan demi kepentingan kekuasaan dan modal maka aspek ini akan seperti dihidupkan kembali. Namun biasanya hanya dijadikan objek eksotis penunjang sistem kuasa atau untuk dijual di wilayah industri pariwisata. Didalam konteks kegiatan seperti ini produk budaya tidak perlu terkait dengan makna ataupun nilai-nilainya.

Photo 15 – Dengan perempuan Nomad
Keterputusan dengan pengetahuan budaya memang bisa terjadi seiring perubahan zaman. Tapi juga bisa di ”desain” dengan sengaja untuk melancarkan agenda kekuasaan sebagai upaya kendali ataupun penaklukan. Yang bisa dilakukan oleh penguasa lokal maupun asing – seperti yang terjadi dimasa penjajahan. Dengan hilangnya pengetahuan akan akar budaya orang akan mengalami “krisis identitas” dan ini bisa menjadi peluang untuk penguasa atau kelompok yang berkepentingan menanamkan “ideologi” atau agendanya. Di ranah politik dan bisnis memang hal ini biasa terjadi. Dan ketika manusia tak memperdulikan nilai-nilai serta etika kehidupan maka kecenderungan manipulatif seperti ini bahkan bisa dianggap hal yang wajar saja. Contoh kongkrit tragedi budaya yang nyata akibat penjajahan di negri ini berhubungan dengan penjarahan artefak budaya maupun naskah tua oleh pihak Belanda dan Inggris. Belanda menjajah dalam kurun waktu yang panjang (sekitar 300 tahun) dan menjarah banyak sekali artefak maupun naskah. Yang membawa dampak traumatis hingga saat ini.
Menurut info terbaru yang kudengar ketika diundang berbicara didalam konferensi dengan tema “penjarahan” di Stadelijk Museum di bulan Maret lalu (2021), artefak yang masih tersisa berjumlah lebih dari 10.000 dan naskah jumlahnya bahkan mencapai ratusan ribu. Direncanakan untuk dikembalikan oleh pemerintah Belanda. Namun tentunya program repratriasi ini akan memerlukan waktu dan persiapan. Agar kumpulan artefak dan manuskrip itu bisa terawat dan aman di tempat asalnya. Kelihatannya ini bukan hal mudah khususnya untuk artefak-artefaknya. Memang dengan menggunakan teknologi digital imejnya bisa disimpan. Begitu pula dengan naskah sepertinya pengamanannya tidak sulit. Ini tugas khusus lembaga-lembaga negara untuk mengurusinya dan tentunya bukan hal yang mudah. Aku sendiri lebih tertarik untuk mempelajari lebih lanjut fungsi dan makna artefak yang erat berhubungan dengan ilmu pengetahuan, filsafat maupun nilai-nilai budayanya (yang banyak ditulis didalam naskah-naskahnya). Lalu melanjutkan kerja yang sudah aku lakukan selama ini: merevitalisasi dan memaknai ulang warisan budaya atau peradaban luhur nenek moyang.
Sehingga peninggalan berharga ini tidak hanya dilihat sebagai objek antik dan mahal harganya semata. Tetapi dipahami makna dan fungsinya lalu dihubungkan dengan ilmu pengetahuan modern dan juga dengan kenyataan hidup hari ini. Supaya budaya masa lalu dengan segala perangkatnya tidak akan dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Yang dalam kenyataannya sebetulnya samasekali tidak “ketinggalan zaman”! Malah bahkan sangat relevan dengan situasi dan kondisi hari ini. Dimana berbagai permasalahan perlu diatasi. Dan yang diistilahkan sebagai“kearifan lokal” peninggalan leluhur ini bisa memberikan petunjuk dan jawaban. Terutama didalam menghadapi permasalahan manusia modern yang pada dasarnya mengalami cara pandang yang terdistorsi didalam memahami hubunganya dengan alam. Dimana ia cenderung melihat dirinya sebagai mahluk superior dan penguasa alam. Sehingga alam hanya dilihat sebagai objek untuk dieksploitasi. Dan manusia lain serta mahluk berbeda dianggap inferior (lebih rendah) dan boleh dijajah serta dipelakukan dengan semena-mena!

Photo 16 – Patung Pradnyaparamita
Manusia cenderung tak memahami lagi kenyataan bahwa dirinya dan semua aspek kehidupan di alam semesta ini saling berhubungan. Padahal di dalam budaya tradisional hal ini dipahami dan ditegaskan dalam falsafah serta praktek kehidupannya. Dan khususnya didalam tradisi budaya di masa Kerajaan Sriwijaya dan Medang Kemulan prinsip hidup yang selaras dengan alam didalam kebersamaan ini dicatat di dalam kitab-kitab ajarannya. Juga diukirkan pada panel-panel batu di candi Borobudur. Panel-panel di dinding candi yang berjumlah 2672 ini menjadi medium pemaparkan ajaran tentang kebajikan dan ilmu pengetahuan yang akan menjadikan manusia bijak dan rendah hati. Suka menolong dan berbagi, tanpa memandang posisi didalam strata hierarkhi yang diciptakan untuk semata-mata kepentingan kekuasaan. Ajaran kearifan dan kebijaksanaan hidup ini juga ditata didalam format konstruksi Mandala dengan tingkatan lantai dan tangga naik keatas dan turun kebawah. Yang mencerminkan kemampuan dan pemahaman manusia akan potensi dirinya (baik sisi kekuatan positif maupun negatif) dalam hubunganya dengan semesta. Untuk didaya-gunakan demi kemaslahatan hidup bersama atau untuk “membebaskan semua mahluk dari penderitaan”.
Tempuran Elo-Progo, 2021
*Penulis adalah seorang Perupa