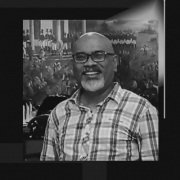Wahib Dan Eksistensialisme
Oleh Ramdan Malik
Di Mesjid
Kuseru saja Dia
Sehingga datang juga
Kami pun bermuka-muka
Seterusnya Ia bernyala-nyala dalam dada
Segala daya memadamkannya
Bersimpuh peluh diri yang tidak bisa
diperkuda
Ini ruang
Gelanggang kami berperang
Binasa-membinasa
Satu menista lain gila
(Chairil Anwar, 29 Juni 1943)
1
40 tahun silam, LP3ES menerbitkan catatan harian seorang intelektual muda muslim, Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam. Dua tahun kemudian, penerbit yang sama membukukan diary Soe Hok Gie, Catatan Seorang Demonstran. Kedua buku yang ditulis dua aktivis yang mati muda ini mendapat sambutan luas, bahkan cendekiawan Daniel Dhakidae “membaptis” keduanya sebagai “humanistic intellectual yang tidak pernah disukai karena melakukan pembongkaran dan penelanjangan paradigmatik terhadap masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi”. (Dhakidae, 2015:98). Yang unik, keduanya beberapa kali mengutip karya-karya para filsuf eksistensialis dalam catatan harian mereka.
Studi tentang eksistensialisme di Indonesia tak terbatas di bidang filsafat, tapi juga merambah disiplin lain yang karib dengannya, seperti psikologi dan sosiologi. Dari skripsi Arief Budiman di Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, pada akhir 1960-an, Chairil Anwar: Sebuah Pertemuan, hingga skripsi Wahyu Budi Nugroho di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, empat dekade kemudian, Orang Lain Adalah Neraka: Sosiologi Eksistensialisme Jean Paul Sartre. Sebelumnya, di wilayah sastra, dramawan, sastrawan, serta sutradara Asrul Sani menerjemahkan naskah teater Albert Camus, Caligula, pada 1965, yang disusul skenario sandiwara Sartre, Pintu Tertutup, pada 1976. Kemudian, pada 1983, terbit terjemahan dua novel Camus sekaligus, Sampar (yang diterjemahkan prosais NH Dini) dan Orang Asing (oleh penerjemah Apsanti D).
Esay singkat ini berusaha melihat Ahmad Wahib dari sisi eksistensialesme. Terutama bagaimana upaya Ahmad Wahib menjadi diri yang otentik, di tengah absurditas kehidupan berbangsa pasca kejatuhan diktator Orde Lama, Soekarno, yang tak lama kemudian ternyata bersalin rupa dengan otoriter Orde Baru, Soeharto. Dalam diary-nya pada 26 Oktober 1969, Wahib menulis: “teori kaum eksistensialis sangat tepat bahwa sesungguhnya manusia itu adalah individual dan tak bisa dikotak-kotakkan dalam skema-skema tertentu. Manusia itu menghadapi persoalan-persoalan sendiri dalam bereksistensi dengan lingkungannya, yang membuat tiap manusia itu memiliki masalah-masalah sendiri yang tidak dimiliki manusia lainnya” (Wahib, 1981:52).
Usai menyaksikan drama Pelacur karya Sartre di Yogyakarta, ia juga menulis kekagumannya kepada filsuf dedengkot eksistensialisme itu, dengan agak melupakan Camus yang juga menulis naskah drama dan novel serta menawarkan modus pemberontakan (rebellion) di tengah absurditas: “Problema manusia memang merupakan problema yang menarik. Ragu, ketidaktentuan, merupakan salah satu unsur yang melekat pada kehidupan seorang manusia. Cemas, ragu-ragu, kecewa, keunikan-keunikan pribadi, terjepit oleh pilihan-pilihan yang semuanya jelek, merupakan keadaan yang sering tak bisa kita hindarkan. Apa-apa yang diungkap oleh falsafah eksistensialisme itu tercermin dengan jelas dalam drama Pelacur karya JP Sartre. Inilah kelebihan Sartre daripada filsuf-filsuf eksistensialisme lainnya. Dia bisa menyalurkan falsafahnya lewat novel-novelnya. Alangkah hebatnya karya Sartre yang satu ini dan betapa rumitnya manusia itu. Karena itu tidak mungkin kita mengenal dengan tepat kawan kita yang paling akrab sekalipun, sebab untuk manusia tidak ada ukuran obyektif yang sepenuhnya bisa dipakai dengan berhasil. Manusia itu unik dan penuh dengan subyektivitas. Dan ini tidak bisa dihindarkan selama kita bernama manusia. Kita boleh memberontak dan meradang terhadap nasib, tapi pemberontakan dan peradangan itu sendiri adalah buah dari subyektivitas. Pengetahuan kita tentang hakekat manusia menyebabkan dua hal: 1. Sikap toleransi, harga menghargai; 2. Sikap memberontak terhadap belenggu-belenggu kebersamaan, seperti organisasi” (Wahib, 1981:225-226).
2
Berdasarkan tulisan Djohan Effendi, sahabat almarhum yang bersama Ismed Natsir menyunting 17 jilid buku tebal tulisan tangan mendiang dan menulis “Pendahuluan” Pergolakan Pemikiran Islam (Wahib, 1981:1-16), Ahmad Wahib dilahirkan di Sampang, Pulau Madura, Jawa Timur, pada 9 November 1942. Ayahnya seorang pemuka Islam di kotanya, sehingga tak heran bila Wahib sempat mengecap kehidupan pesantren. Setamat SLTA di SMA Pamekasan pada 1961, ia kuliah –meski tak sampai meraih gelar sarjana– di Fakultas Ilmu Pasti dan Alam (FIPA), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kendati aktivis Himpunan Mahasiswa Islam di Yogya, ia tinggal di sebuah asrama mahasiswa Katholik, Realino. Di luar HMI, Ahmad Wahib aktif dalam Lingkaran Diskusi Limited Group yang dipimpin Prof. Dr. Mukti Ali, kelak menjadi Menteri Agama semasa Orba. Pada 1971, Wahib hijrah ke Jakarta. Selain kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, ia juga aktif dalam diskusi-diskusi di rumah Dawam Rahardjo, sahabatnya di HMI Yogya yang Sarjana Ekonomi UGM, bersama antara lain Nurcholish Madjid, Ketua Umum Pengurus Besar HMI yang Sarjana Sastra Arab IAIN Jakarta. Ahmad Wahib wafat pada 31 Maret 1973, setelah ditabrak sebuah sepeda motor yang pengemudinya melarikan diri di simpang jalan Senen Raya-Kalilio, selepas bekerja malam sebagai calon reporter majalah Tempo. Beberapa gelandangan membawa jasadnya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.
Semasa mahasiswa di Yogya hingga bekerja sebagai wartawan di Jakarta, Wahib merupakan salah satu tokoh “di balik layar” gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang digaungkan Nurcholish Madjid. Transisi politik dari Orla ke Orba menuntut pergulatan ide kaum muda muslim, seperti Ahmad Wahib, untuk menyembuhkan “trauma” negara Islam dan sejarah Masyumi –partai Islam yang tokoh-tokohnya terlibat dalam Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat semasa Soekarno berkuasa–, dengan slogan “Islam bukan ideologi dan Islam Yes, partai Islam No”. Kritiknya terhadap kaum muslimin Indonesia yang di matanya lebih berkomitmen kepada organisasi atau tokoh Islam daripada nilai-nilai Islam, mengundang pro dan kontra. Kendati gagasan pembaharuan pemikiran Islam berawal dari “Tiga Serangkai” HMI Yogya –Ahmad Wahib, Djohan Effendi, dan Dawam Rahardjo– pada akhir 1960-an, nama mereka kerap dilupakan setelah Nurcholish Madjid berpidato “Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam” di Jakarta pada 1970.
Kritik Bapak Eksistensialisme, Kierkegaard, terhadap kepalsuan, ketidakotentikan hidup, serta publik yang abstrak (Tjaya, 2010:xv) didedahkan Wahib dengan komitmennya terhadap kebebasan berpikir ala Aristoteles, Hegel, atau Immanuel Kant: “manusia pada hakikatnya adalah pengada yang rasional (rational being) yang ingin tahu dan berusaha menggapai kebenaran (rational being)” (Tjaya, 2010:16). Dalam catatan hariannya pada 17 Juli 1969, Ahmad Wahib menulis: “Sebagian orang meminta agar saya berpikir dalam batas-batas Tauhid, sebagai konklusi globalitas ajaran Islam. Aneh, mengapa berpikir hendak dibatasi. Apakah Tuhan itu takut terhadap rasio yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri? Saya percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan bukanlah daerah terlarang bagi pemikiran… Sesungguhnya orang yang mengakui ber-Tuhan, tapi menolak berpikir bebas, berarti menghina rasionalitas eksistensi Tuhan. Jadi dia menghina Tuhan, karena kepercayaannya hanya sekadar kepura-puraan yang tersembunyi… Pada hemat saya, orang-orang yang berpikir itu, walaupun hasilnya salah, masih jauh lebih baik daripada orang-orang tidak pernah salah karena tak pernah berpikir” (Wahib, 1981:23).
Sebagai manusia yang membuka diri terhadap berbagai kemungkinan, Ahmad Wahib bereksistensi secara otentik yang, menurut Heidegger, “hidup dalam kesadaran akan kemungkinan untuk mati (sorge).” (Hardiman: 2017:8). Dalam diary-nya, 1 Desember 1969, Wahib menulis: “Aku bukan Hatta, bukan Soekarno, bukan Sjahrir, bukan Natsir, bukan Marx, dan bukan pula yang lain-lain. Bahkan, aku bukan Wahib. Aku adalah me-Wahib. Aku mencari, dan terus-menerus mencari, menuju dan menjadi Wahib. Ya, aku bukan aku. Aku adalah meng-aku, yang terus-menerus berproses menjadi aku. Aku adalah aku, pada saat sakratul maut!” (Wahib, 1981:55).
Walau masih percaya kepada Tuhan, Ahmad Wahib memahami risiko kebebasan berpikirnya yang radikal. Seperti Sartre yang mengakui betapa “penuh susah payah” hidup sebagai atheis, dengan mengibaratkan dirinya sebagai “orang yang bepergian tanpa tiket kendaraan”. Doktrin Sartre bahwa “karena manusia bebas, maka Allah tidak ada”, harus ditanggung konsekuensinya. Karena jika Tuhan ada, maka manusia tidak akan berhasil merealisasikan dirinya secara sungguh-sungguh, dalam arti ia tidak dapat secara total dan penuh kedaulatan menentukan dirinya sendiri (Thahjadi, 2017:5-6). Dalam catatan panjangnya tentang pembaharuan pemikiran Islam, Ahmad Wahib menulis pada 14 Juli 1972, “Djohan dan saya tidak khawatir untuk ragu-ragu atau kafir karena kami yakin bahwa Tuhan menolerir hamba-Nya untuk meragukan atau tidak mempercayai ajarannya sebelum taat sepenuh hati. “Bagaimana saya disuruh percaya atau menaati kalau tidak diberi hak untuk tidak percaya atau ingkar?” Demikian kata-kata yang sering kami berdua lontarkan dalam diskusi-diskusi dan training HMI.” (Wahib, 1981:156).
Sebagaimana Kierkegaard yang berpaling kepada subyektivitas, yakni diri manusia sendiri yang mengalami berbagai gejolak dalam kehidupannya, sehingga eksistensi otentik dapat dicapai, Ahmad Wahib mengkritik “publik” yang bagi Kiekegaard “merupakan entitas abstrak dan tempat persembunyian bagi orang banyak orang yang takut untuk menyatakan diri atau menghidupi eksistensinya secara berani dan tegas” (Tjaya, 2010:68-69). Dalam “puisi” panjangnya nan melankolis kepada sobatnya, Djohan Effendi, pada 14 Agustus 1969, Wahib menulis perpisahannya dengan HMI: “kehadiran kita sebagai muslim/ kita nilai sebagai kebetulan/ untuk itu kita cari/ Islam menurut kita sendiri/ Islam menurut kamu/ dan Islam menurut aku sendiri//… sebagaimana prinsip kita/ warna yang beraneka rona kita hormati/ bentuk yang beraneka ragam kita terima/ pluralisme, itulah prinsip kita/… bagi kita/ theis dan atheis bisa berkumpul/ muslim dan kristiani bisa bercanda/ artis dan atlit bisa bergurau/ kafirin dan muttaqin bisa bermesraan/ tapi/ puralis dan antipluralis tak bisa bertemu/ dia menyangkut milik manusia yang paling tinggi/ awal dan akhir/ pribadi/ dia menyangkut keterbukaan dan ketertutupan/ dia menyangkut adanya pribadi atau lenyapnya pribadi/ bagi kita/ tak ada pribadi, tak ada manusia/ kemerdekaan adalah hakekat eksistensi manusia/ ini masalah dasar kita/ apalagi bagi organisasi kader/ yang sasarannya: manusia dengan kepribadiannya//… kita tengadahkan muka ke atas/ ke alam bebas dan lepas/ di mana pluralisme bisa hidup/ dan antipluralisme tak menemukan ruangnya/ di mana perkawinan pendapat bukan pengkhianatan/ di mana pertentangan pendapat bukan pengacauan/ di mana pembaharuan sikap bukan kejelekan//… kita cari ruang bebas/ di mana warna yang beraneka adalah Rahmat/ di mana bentuk yang beragam adalah Hidayat/ di mana konflik menjadi pertanda kemajuan/ di mana untuk masuk tak usah bayar terlalu mahal, pribadi// ke sanalah, Han, kita menengadah/ di mana pendapat-pendapat bisa saling bertentangan/ di mana pendapatku, pendapatmu bersaingan/ dalam kompetisi yang mengasyikkan/ di mana pendapatmu, pendapatnya, dan pendapatku/ dimungkinkan bercanda dan bercumbuan/ dalam saling penghormatan// walaupun begitu/ kita kaum pluralis yang konsekuen/ perlu tundukkan kepada sebentar/ mengusap mata sekali/ mengheningkan hati sejenak/ buat menerima/ sebuah perpisahan/ dengan roh kita sendiri/ HMI/ (Wahib, 1981:37).
3
Ahmad Wahib memang bukan seorang atheis. Ia seorang muslim yang senantiasa gelisah. Namun, Wahib mencari kebenaran religiusitasnya mirip dengan atheisme yang dimaksud Sartre: “Ide tentang Tuhan dihilangkan, sehingga ide bahwa esensi mendahului eksistensi ditolak… Eksistensialisme atheistik, yang saya wakili ini, menyatakan dengan sangat konsisten bahwa jika Tuhan tidak ada, sekurang-kurangnya ada kehidupan yang eksistensi mendahului esensinya, kehidupan yang hidup sebelum ia dapat didefinisikan dengan konsepsi apa pun… Apa yang kita maksudkan dengan eksistensi mendahului esensi? Yang kita masuk adalah bahwa, pertama-tama, manusia ada, berhadapan dengan dirinya sendiri, terjun ke dalam dunia, dan barulah setelah itu ia mendefinisikan dirinya… Manusia adalah bukan apa-apa selain apa yang ia buat dari dirinya sendiri. Itulah prinsip pertama eksistensialisme.” (Sartre, 2002:43-45).
Hidup Ahmad Wahib mungkin absurd, yang menurut Camus, “adalah konfrontasi antara keadaan tak rasonal itu dan hasrat tak terbendung akan kejelasan yang gemanya bergaung di relung hati manusia yang paling dalam” (Camus, 1999:25). Dan, seperti mitos Sisifus yang ditulis Camus, “para dewa telah menghukumnya untuk terus-menerus mendorong sebuah batu besar sampai ke puncak gunung, meski akhirnya batu itu jatuh ke bawah lagi karena beratnya sendiri” (Camus, 1999:154). Tapi Sisifus mengajarkan komitmen hidup untuk terus melakukan pemberontakan: “perjuangan ke puncak gunung itu sendiri cukup untuk mengisi hati seorang manusia. Kita harus membayangkan Sisifus berbahagia.” (Camus, 1999:159)
Akhirnya. sejak 2003, Ahmad Wahib Award menjadi nama kompetisi penulisan esai. Sayembara ini untuk mendorong anak-anak muda agar menulis gagasan kritisnya mengenai agama, bangsa, serta kemanusiaan. Meski telah tiada pada usia relatif muda, 31 tahun, catatan hariannya yang dibukukan dalam Pergolakan Pemikiran Islam melanggengkan eksistensi ide-idenya, sehingga dapat melahirkan Wahib-Wahib baru.
*Penulis adalah Jurnalis