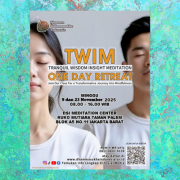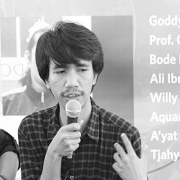Hari yang Berbahaya: Krisis Makna dan Kehidupan yang Menjadi Biasa dalam Puisi Beno Siang Pamungkas
Oleh Abdul Wachid B.S.*
1. Ketika Hidup Terasa Baik-Baik Saja
Ada masa dalam hidup ketika segalanya tampak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada tragedi yang memaksa kita berhenti. Tidak ada kehilangan besar yang membuat dunia runtuh seketika. Hari datang dan pergi dengan tertib, pekerjaan selesai sesuai jadwal, tubuh relatif sehat, relasi sosial tidak sedang retak. Hidup, jika diukur dari permukaan, terlihat aman dan terkendali.
Namun justru pada saat seperti itulah kegelisahan yang paling sunyi sering muncul. Bukan sebagai teriakan, melainkan sebagai perasaan ganjil yang sulit diberi nama. Kita menjalani hari, tetapi seolah tidak sepenuhnya hadir di dalamnya. Waktu berlalu, tetapi tidak meninggalkan bekas. Segalanya bergerak, tanpa benar-benar menyentuh batin.
Pertanyaan yang muncul sebenarnya sederhana, tetapi mengganggu: apakah hidup masih sungguh hidup ketika ia tidak lagi menggetarkan rasa? Ketika hari-hari datang dan pergi tanpa luka yang perlu disembuhkan, tanpa kegembiraan yang layak dirayakan, bahkan tanpa kesedihan yang pantas ditangisi.
Kesadaran semacam ini hadir dengan jernih dalam puisi “Hari yang Berbahaya” karya Beno Siang Pamungkas. Bukan melalui peristiwa besar, melainkan lewat pengakuan tentang sebuah wilayah waktu yang terasa datar dan hambar:
Hari yang Berbahaya
Aku merasa telah tiba di sebuah tempat
di mana segalanya tak mampu
mengundang perhatian
Kulihat helai-helai hari
berguguran tanpa kesan
juga kenangan
dan segalanya terlihat biasa
tanpa rasa sedih juga gembira
benci, marah, dendam, kangen, rindu juga cinta.
Aku yakin ini wilayah yang selama ini kuhindari
sepotong waktu, di mana segalanya kehilangan makna
karena telah menjadi rutin dan biasa,
hari yang berbahaya.
Semarang, 17 Januari 2010
Yang dihadapi dalam puisi ini bukan kekacauan, melainkan ketiadaan getaran. Hari-hari “berguguran tanpa kesan”, kenangan kehilangan daya sengatnya, dan perasaan-perasaan yang biasanya menjadi penanda hidup (sedih, gembira, marah, rindu, cinta) tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Semua hadir sebagai daftar, bukan sebagai pengalaman.
Bahaya yang dimaksud Beno tidak datang dari luar. Ia tidak berupa ancaman konkret atau peristiwa ekstrem. Ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus: kebiasaan yang tidak lagi dipersoalkan. Keadaan yang tampak stabil, tetapi diam-diam menggerus kedalaman batin. Dalam situasi seperti ini, manusia tetap hidup, tetapi relasinya dengan makna mulai terputus tanpa disadari.
Argumen pembuka esai ini berangkat dari titik tersebut: kehidupan modern paling berbahaya justru ketika ia tampak baik-baik saja. Ketika rasa berhenti bekerja bukan karena luka, melainkan karena kelelahan yang tidak pernah diakui. Pada tahap ini, kita belum perlu tergesa-gesa mencari sebab atau solusi. Yang lebih penting adalah berhenti sejenak dan mengakui kegelisahan itu, bahwa ada hari-hari tertentu yang terasa aman, tetapi justru menyimpan bahaya paling senyap.
2. Puisi sebagai Alarm Kesadaran
Puisi-puisi Beno Siang Pamungkas tidak hadir sebagai khotbah. Ia tidak menunjuk jari, tidak memberi petunjuk moral, dan tidak menawarkan jalan keluar yang serba cepat. Cara kerjanya jauh lebih senyap: seperti alarm yang berbunyi pelan justru ketika manusia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Dalam “Hari yang Berbahaya”, kesadaran itu tidak dipicu oleh konflik atau tragedi, melainkan oleh pengalaman yang terlalu biasa. Segalanya terlihat normal, terkendali, bahkan membosankan. Dan justru di situlah letak ancamannya. Kehilangan makna tidak datang sebagai ledakan, tetapi sebagai pengikisan perlahan: sepotong waktu di mana segala sesuatu menjadi rutin, hingga rasa tidak lagi memiliki alasan untuk bereaksi.
Puisi “Malam Minggu” memperlihatkan mekanisme yang serupa, tetapi dalam skala yang lebih intim. Situasi tampak ideal: bulan bulat bundar, hujan tak turun, malam berjalan tenang. Namun tiba-tiba muncul kesadaran yang mengusik:
“ternyata aku tak merasa bersalah
dan tak lagi merisaukanmu.”
Larik ini tidak emosional. Ia dingin, hampir datar. Tidak ada luapan rindu atau penyesalan yang dramatis. Justru karena itulah ia terasa menohok. Ketika rasa bersalah dan kerisauan (dua penanda keterikatan emosional) tidak lagi hadir, pertanyaan yang muncul bukanlah tentang hubungan, melainkan tentang kepekaan batin itu sendiri.
Di titik inilah puisi berfungsi sebagai alarm kesadaran. Ia tidak memaksa pembaca untuk merasa sedih atau tersentuh. Sebaliknya, ia membiarkan pembaca berada dalam wilayah netral, lalu menyalakan tanda peringatan yang samar: ada sesuatu yang tidak beres, meskipun sulit dijelaskan.
Dalam dunia yang dipenuhi slogan motivasi, nasihat instan, dan ajakan untuk selalu merasa “baik-baik saja”, puisi semacam ini memilih jalur yang berbeda. Ia tidak memperkeras suara, melainkan mempertajam keheningan. Kesadaran dibangunkan bukan lewat kejutan dramatik, melainkan melalui pengakuan jujur bahwa ada sesuatu yang tidak lagi kita rasakan sebagaimana mestinya.
Puisi berfungsi sebagai alarm eksistensial. Ia membangunkan kegelisahan yang tertidur dalam rutinitas; tanpa menggurui, tanpa memaksa pembaca untuk segera memahami atau menyimpulkan. Membaca puisi Beno, kita tidak sedang diajak untuk berubah. Kita hanya diajak untuk sadar. Dan sering kali, kesadaran itulah langkah paling sulit sekaligus paling mendasar.
3. Kehidupan yang Menjadi Biasa: Dari Rasa ke Rutinitas
Jika lapisan batin yang disentuh puisi-puisi Beno ditelusuri lebih jauh, tampak bahwa krisis makna yang ia hadirkan tidak lahir dari peristiwa traumatis. Ia justru tumbuh dari kehidupan yang tampaknya aman: hari-hari yang teratur, berulang, dan mudah diprediksi.
Dalam “Hari yang Berbahaya”, kondisi ini dirumuskan secara terang:
“sepotong waktu, di mana segalanya kehilangan makna
karena telah menjadi rutin dan biasa,
hari yang berbahaya.”
Rutinitas di sini bukan sekadar kebiasaan praktis yang membantu hidup berjalan lancar. Ia telah berubah menjadi kekuatan yang menggerus kesadaran. Emosi tidak benar-benar lenyap, tetapi menipis. Sedih dan gembira tidak lagi saling berlawanan; keduanya sama-sama redup. Rindu, cinta, marah, masih disebut, tetapi tidak lagi memanggil pengalaman konkret.
Puisi “Malam Minggu” menunjukkan gejala yang sama dari sudut lain. Bukan konflik yang hilang, melainkan reaksi batin terhadap konflik itu sendiri. Ketika rasa bersalah dan kerisauan tidak lagi muncul, yang tersisa adalah kesadaran dingin bahwa sesuatu yang dulu penting kini tak lagi memberi getaran.
Di sinilah pergeseran dari rasa ke rutinitas menjadi krusial. Hari-hari dijalani bukan dengan kehadiran batin yang utuh, melainkan dengan kebiasaan yang berjalan otomatis. Tubuh hadir, waktu bergerak, tetapi batin tertinggal di belakang. Hidup berlangsung, tetapi tidak lagi dialami sepenuhnya.
Krisis makna tidak selalu lahir karena hidup terlalu keras. Ia justru muncul ketika hidup terlalu lancar, terlalu tertata, dan tidak lagi direnungkan. Yang rusak bukan dunia luar, melainkan hubungan manusia dengan pengalaman batinnya sendiri.
Beno tidak mengutuk rutinitas, juga tidak mengajak pembaca meninggalkan kehidupan sehari-hari. Yang ia lakukan adalah menunjukkan sebuah fakta batin: kebiasaan yang tidak disadari dapat berubah menjadi wilayah berbahaya. Bukan karena ia menyakiti, melainkan karena ia mematikan kepekaan secara perlahan.
Pada tahap ini, fokus esai masih berada sepenuhnya pada pengalaman individual. Kita belum berbicara tentang relasi sosial, kota, media, atau struktur eksternal. Puisi berfungsi sebagai cermin yang jujur: memantulkan wajah yang mungkin selama ini kita hindari untuk dilihat terlalu lama. Dan dari titik inilah, krisis makna itu akan bergerak keluar, merembes ke hubungan antar-manusia dan ruang hidup yang lebih luas.
4. Relasi Sosial yang Menguap
Dalam puisi-puisi Beno Siang Pamungkas, krisis makna tidak berhenti sebagai kegelisahan batin individual. Ia bergerak pelan ke wilayah yang lebih rapuh: relasi antar-manusia. Namun relasi yang retak dalam puisi Beno bukanlah relasi yang pecah karena konflik besar. Ia menguap, menipis, lalu hilang tanpa suara.
Sajak “Ruang Tamu” menjadi pintu masuk penting untuk membaca perubahan itu. Ruang tamu, secara kultural, adalah tempat menyambut, berbagi cerita, dan menautkan ingatan. Tetapi dalam puisi Beno, ruang ini justru menjadi arsip kegagalan relasi. Ia menulis:
“Di ruang tamu itu
nama-nama pergi dan datang
ada beberapa yang terkenang
dan membayang
tapi banyak yang lekas
menyirna tanpa bekas.”
Yang pergi dalam larik-larik ini bukan hanya orang, melainkan kedalaman perjumpaan. Nama hadir, lalu lenyap. Ingatan sempat muncul, lalu menguap. Tidak ada konflik yang perlu diselesaikan, tidak ada luka yang harus disembuhkan. Relasi gagal bukan karena pertengkaran, melainkan karena tidak cukup penting untuk diingat.
Nada serupa muncul dalam sajak “Malam Minggu”. Malam yang biasanya dipenuhi kerinduan atau penantian justru berakhir pada kesadaran yang dingin. Beno menulis:
“setelah sekian lama
ternyata aku tak merasa bersalah
dan tak lagi merisaukanmu.”
Yang mengejutkan di sini bukan perpisahan, melainkan absennya rasa. Tidak ada penyesalan, tidak ada kegelisahan. Relasi berakhir bukan dengan tangis, tetapi dengan ketidakpedulian yang nyaris tenang. Inilah bentuk relasi yang menguap: ketika kehilangan tidak lagi menimbulkan kehilangan.
Krisis ini semakin terasa ketika Beno memindahkannya ke ruang digital. Dalam sajak “Status”, relasi tampak ramai, penuh komentar dan interaksi, namun kehilangan kedalaman pengenalan. Beno menulis:
“Di dunia maya, nyata-nyata kulihat manusia
di dunia nyata, semuanya malah sulit terduga.”
Baris ini bukan kecaman moral, melainkan catatan sunyi tentang paradoks relasi modern. Media sosial membuat manusia terlihat, tetapi tidak sungguh-sungguh dikenal. Kita membaca suasana hati orang lain, tetapi kehilangan keberanian untuk benar-benar menyelami. Relasi bergerak cepat, tetapi tidak sempat tinggal.
Dalam puisi-puisi ini, kesepian tidak lahir dari ketiadaan orang lain, melainkan dari hadirnya orang lain yang tidak lagi menjadi tempat bercermin. Hilangnya kedalaman relasi memperparah krisis makna, karena manusia kehilangan salah satu sumber terpenting untuk mengenali dirinya sendiri.
5. Informasi, Berita, dan Kebingungan Arah Hidup
Dari relasi antar-manusia, krisis makna dalam puisi Beno meluas ke ruang publik: dunia informasi dan berita. Di wilayah ini, kegelisahan tidak lagi bersifat personal, melainkan struktural. Manusia hidup di tengah limpahan informasi, tetapi kehilangan orientasi untuk menentukan arah.
Sajak “Jalan (1)” mempertautkan dua hal yang secara simbolik seharusnya memberi panduan: berita dan jalan. Beno menulis:
“Sebuah berita
dan sepotong jalan
berjajar beriringan”
Kesejajaran ini tampak sederhana, tetapi menyimpan ironi. Baik berita maupun jalan mestinya membantu manusia membaca dunia dan menentukan langkah. Namun Beno segera memperlihatkan rapuhnya keduanya:
“Sebuah berita kadang mencampur kepalsuan dan kebenaran
seperti sepotong jalan yang menyimpan jebakan dan harapan
tersembunyi di kelokan”
Yang menjadi persoalan bukan kebohongan belaka, melainkan campur-aduk antara benar dan palsu. Dalam situasi semacam ini, manusia tidak tersesat karena tidak tahu apa-apa, melainkan karena terlalu banyak tahu tanpa kepastian mana yang bisa dipercaya. Informasi hadir, tetapi tidak memberi orientasi etik maupun eksistensial.
Nada serupa muncul dalam “Wisky yang Puitis”, ketika berita kehilangan daya petunjuknya:
“Tak ada pertanda yang bisa kau baca
dari koran pagi tadi”
Berita hadir sebagai rutinitas, bukan sebagai makna. Ia dibaca, lalu dilupakan. Dunia bergerak, tetapi manusia tidak tahu harus bergerak ke mana. Informasi tidak lagi membuka kemungkinan pemahaman, melainkan menambah kebisingan batin.
Namun Beno tidak sepenuhnya menutup kemungkinan makna. Ia masih menyisakan keyakinan rapuh bahwa kebenaran, betapapun kecil, memiliki daya memelihara harapan:
“Namun
sebuah kebenaran akan terus memelihara harapan
dan berharap menemukan jalan
di sepotong berita
yang tersesat di TV dan koran.”
Kata “tersesat” di sini penting. Bukan hanya manusia yang kehilangan arah, melainkan sistem informasi itu sendiri. Dalam dunia seperti ini, pencarian makna menjadi kerja individual yang berat, karena ruang publik gagal menyediakan penunjuk jalan yang dapat dipercaya.
6. Kota dan Perjalanan: Bergerak Tanpa Pulang
Krisis makna dalam puisi Beno akhirnya menjelma paling konkret dalam ruang dan tubuh: kota dan perjalanan. Kota tidak tampil sebagai pusat kemungkinan, melainkan sebagai lanskap keterasingan. Perjalanan tidak lagi menjanjikan kepulangan, hanya gerak yang terus berlangsung.
Dalam “Senja di Kotamu”, kota hadir sebagai ruang yang kehilangan keterbacaan emosional. Penyair tiba, tetapi tidak sungguh-sungguh sampai. Beno menulis:
“Di kotamu, tak bisa kubaca lagi teritori yang dulu kita
pancangkan bersama….”
Yang hilang bukan sekadar kenangan, melainkan peta makna. Kota berubah lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk menegosiasikan hubungan dengannya. Bahkan gagasan tentang pulang menjadi problematis:
“Kadang perjalanan pulang, membawa kita pergi ke arah yang lain
apalagi segala rambu dan tanda
tanggal dikerkah cuaca”
Perjalanan yang seharusnya mengarah pada titik kembali justru menjauhkan. Mobilitas modern, dalam puisi Beno, bukan lagi simbol kebebasan, melainkan tanda ketercerabutan.
Nada ini mencapai lapisan paling gelap dalam “Gobang (3)”. Kota tampil sebagai ruang sosial yang keras, kotor, dan timpang. Beno menulis:
“Karena cuaca selalu kelam
kami memilih jalan malam
jalan satu jurusan
tanpa arah untuk pulang.”
“Jalan satu jurusan” tanpa pulang menjadi metafora kuat bagi kehidupan urban: bergerak terus, bertahan seadanya, tanpa sempat bertanya ke mana dan untuk apa. Kota menuntut keberlangsungan hidup, bukan kebermaknaan hidup.
Namun dalam “Jalan (2)”, Beno masih menyisakan satu kemungkinan yang tidak gegap gempita. Di tengah kelelahan ruang dan tubuh, perjalanan dilanjutkan bukan demi dunia, melainkan demi sesuatu yang lebih sunyi:
“Aku akan terus berjalan,
melacak jejak-Mu,
hingga ke hulu.”
Puisi Beno tidak menawarkan solusi, tetapi sikap. Makna tidak ditemukan dalam kota atau perjalanan itu sendiri, melainkan dalam kesediaan untuk terus berjalan sambil mencari jejak, meski arah pulang tidak pernah benar-benar pasti.
7. Cinta sebagai Residu Luka
Dalam sejumlah puisi Beno Siang Pamungkas, cinta tidak lagi tampil sebagai janji penyelamatan. Ia hadir justru sebagai sisa, sebagai residu yang tertinggal setelah harapan runtuh dan makna tak sepenuhnya pulih. Cinta bukan energi yang menghidupkan, melainkan jejak yang masih terasa perih ketika disentuh kembali. Pada tahap ini, subjek liris tidak sedang merayakan pertemuan, melainkan menimbang apa yang tersisa ketika kehilangan tak dapat diperbaiki.
Puisi “Sehari Tanpamu” menandai titik ekstrem dari pengalaman tersebut. Kehilangan tidak dihadirkan sebagai kesedihan sentimental, tetapi sebagai invasi fisik ke dalam kesadaran:
“Sehari saja tanpamu
seekor ketam menghampiri, menggali sarang di kepalaku
: gelap tanpa pintu!”
Larik-larik ini bekerja dengan daya tekan yang brutal. “Ketam” (makhluk kecil, keras, dan bergerak menyamping) menjadi metafora gangguan mental yang terus-menerus, menggali dan melukai dari dalam. Cinta yang absen tidak melahirkan kenangan manis, melainkan kekacauan kognitif. “Gelap tanpa pintu” menunjukkan bahwa krisis ini bukan fase sementara, tetapi ruang tertutup tanpa jalan keluar. Di sini, cinta telah gagal menjalankan fungsi pemulihan eksistensial.
Nada serupa, meski dengan artikulasi yang lebih reflektif, muncul dalam “Januari Penghabisan”. Puisi ini tidak berbicara tentang putus cinta secara dramatik, melainkan tentang kelelahan makna yang pelan-pelan mengering:
Sengaja kulupakan janji
yang kau pahat dari kotamu
hampir gila kucumbu kangen dan bosan
yang mengintip dari celah cuaca
Kata “sengaja” penting di sini. Lupa bukan kecelakaan, melainkan keputusan. Subjek liris memilih menjauh dari janji karena janji itu sendiri telah kehilangan daya hidupnya. Cinta berubah menjadi beban temporal, sesuatu yang harus dilampaui agar subjek dapat bertahan. Bahkan pada bagian akhir, keputusan untuk membatasi waktu (“dua atau satu hari saja, bukan milik kita”) menegaskan bahwa cinta tidak lagi dimaknai sebagai masa depan, melainkan sebagai batas yang harus disudahi.
Sementara itu, “Secangkir Kopi” menghadirkan suasana yang lebih tenang, namun justru memperdalam luka secara eksistensial. Benda sehari-hari menjadi medium refleksi kehilangan:
“Di sela air terjerang
di jarak yang kini menghadang
secangkir kopi bertanya
seribu janji, dan secangkir kopi
mana yang lebih bermakna.”
Pertanyaan ini bukan retorik kosong. Ia lahir dari pengalaman konkret: menunggu, jarak, dan kesadaran bahwa janji-janji besar sering kali kalah oleh kehadiran kecil yang setia. Namun kemenangan “secangkir kopi” atas “seribu janji” bukan kabar gembira. Ia justru menunjukkan penyusutan skala makna. Cinta tidak lagi diproyeksikan sebagai komitmen besar, melainkan direduksi menjadi momen singkat yang sekadar bisa ditahan.
Di titik ini, cinta dalam puisi-puisi Beno berfungsi sebagai uji terakhir makna personal manusia. Ketika cinta tidak sanggup menyembuhkan, tidak pula mampu menawarkan horison baru, subjek liris dipaksa berhadapan langsung dengan kehampaan. Inilah eskalasi emosional tertinggi: bukan tangis, bukan kemarahan, melainkan kesadaran pahit bahwa tidak semua luka dapat disublimasi menjadi harapan.
8. Ironi dan Humor Gelap sebagai Cara Bertahan
Jika pada bagian sebelumnya cinta gagal memulihkan makna, maka pada tahap berikutnya subjek liris mencari cara lain untuk bertahan hidup. Bukan dengan solusi moral, bukan pula dengan optimisme palsu, melainkan melalui ironi dan humor gelap. Dalam puisi-puisi Beno Siang Pamungkas, tawa tidak pernah hadir sebagai penyangkalan atas luka, melainkan sebagai strategi sadar untuk tidak runtuh sepenuhnya.
Puisi “Reklame Bunuh Diri” merupakan contoh paling ekstrem sekaligus paling jujur dari sikap ini. Sejak awal, suara liris menyadari absurditas tindakannya:
“Mungkin ini terdengar konyol, atau tepatnya bodoh
seorang lelaki menyerahkan lehernya
dan menyatakan cinta
kepada seseorang yang tak mungkin dimilikinya.”
Ironi bekerja di sini bukan untuk menghibur pembaca, melainkan untuk membuka jarak kritis antara subjek dan penderitaannya sendiri. Dengan menyebut dirinya “konyol” dan “bodoh”, subjek liris merebut kembali kendali atas narasinya. Ia tidak ingin dikasihani; ia memilih menertawakan tragedinya sendiri. Bahkan ketika sampai pada metafora yang sangat rapuh, …..
“Aku hanyalah gelembung sabun.
Sekilas memang penuh warna.
Berikutnya kosong dan musnah.”
….. humor gelap itu justru mempertegas kesadaran akan kefanaan. Tidak ada romantisasi bunuh diri di sini. Yang ada hanyalah pengakuan jujur tentang rapuhnya eksistensi manusia modern.
Nada serupa, meski lebih subtil, muncul dalam “Wisky yang Puitis”. Minuman keras, puisi, dan dendam dirangkai dalam satu lanskap ironis:
“Di langit
kau tulis puisi cinta
yang sengit
Di dalam sebotol wisky
kapal-kapal kumpeni
karam”
Puisi cinta tidak lagi menjadi sarana pencerahan, melainkan latar ironi bagi kehancuran batin. “Wisky” bukan simbol kebebasan, tetapi ruang tempat sejarah, dendam, dan kekalahan dipendam bersama. Humor gelap di sini bekerja sebagai mekanisme bertahan: subjek tahu ia tidak menang, tetapi ia juga menolak menyerah pada kepatuhan moral yang pura-pura suci.
Penting dicatat, ironi dalam puisi-puisi ini tidak pernah ditawarkan sebagai solusi. Ia tidak menyembuhkan luka, tidak pula mengembalikan makna yang hilang. Fungsinya lebih sederhana sekaligus lebih manusiawi: menjaga subjek agar tetap hidup, tetap sadar, dan tidak terjerumus ke dalam sentimentalitas kosong.
Pada tahap ini, eskalasi krisis bergeser. Bukan lagi dari luka ke ratapan, melainkan dari luka ke strategi hidup. Ironi menjadi cara untuk berkata: aku tahu hidup ini retak, dan justru karena itu aku memilih menertawakannya, bukan untuk menang, tetapi agar tidak sepenuhnya kalah.
9. Penyair dari Kehidupan yang Tidak Dramatis
Ada penyair yang lahir dari peristiwa besar: tragedi nasional, pergolakan ideologi, atau konflik terbuka yang memaksa suara puisi berteriak. Beno Siang Pamungkas (lahir di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 1968) tidak berada di jalur itu. Ia justru muncul dari kehidupan yang tampak biasa: hari-hari yang berjalan tanpa klimaks, relasi yang tidak meledak, kota yang tidak selalu gaduh. Namun justru dari wilayah yang nyaris tak dramatik itulah puisinya menemukan legitimasi.
Biografi, dalam konteks Beno, tidak perlu dibaca sebagai daftar pencapaian atau lintasan karier. Ia lebih tepat dipahami sebagai pola keberadaan. Kehidupan yang dilaluinya tidak menuntut pernyataan heroik. Ia berhadapan dengan rutinitas, dengan pekerjaan waktu, dengan relasi yang datang dan pergi tanpa upacara. Dalam situasi seperti ini, puisi tidak berfungsi sebagai panggung, melainkan sebagai cara bertahan agar kesadaran tidak tumpul.
Nada tenang dan getir dalam puisinya tidak lahir dari kemiskinan pengalaman, tetapi dari pengalaman yang terlalu akrab. Ketika seseorang hidup cukup lama di tengah yang “biasa”, ia akan berhadapan dengan risiko terbesar manusia modern: hilangnya rasa. Dalam salah satu puisinya, Beno menuliskan situasi ini secara telanjang, tanpa retorika berlebih:
“Kulihat helai-helai hari
berguguran tanpa kesan”
Larik tersebut bukan keluhan, apalagi pemberontakan. Ia lebih menyerupai pengakuan. Dan justru karena pengakuan itulah suara Beno menjadi sah. Ia tidak memaksakan diri menjadi juru bicara generasi, tidak pula mengklaim posisi moral tertentu. Ia berbicara dari tempat yang rendah, dari pengalaman yang tidak istimewa: tempat yang diam-diam dihuni banyak orang.
Di sini, kita bisa mengingat apa yang pernah ditegaskan oleh Charles Taylor dalam Sources of the Self, bahwa identitas modern tidak selalu dibentuk oleh peristiwa luar yang besar, melainkan oleh “kerja batin yang sunyi dan berulang” dalam menghadapi kehidupan sehari-hari (Taylor, Cambridge: Harvard University Press, 1989). Puisi Beno bergerak persis di wilayah itu: kerja batin yang nyaris tak terlihat, tetapi terus menggerogoti kesadaran.
Karena itu, nada puisinya tidak sloganistik. Ia tidak menawarkan solusi, tidak pula menuntut simpati. Ia hanya menjaga agar pengalaman yang sering dianggap sepele (menunggu, kehilangan jarak, menua dalam rutinitas) tetap memiliki bahasa. Dalam pengertian ini, kehidupan Beno justru menjelaskan mengapa puisinya tidak perlu berteriak. Ia tidak sedang mencari perhatian, melainkan menjaga kewarasan.
Maka, pertanyaan “mengapa suara ini sah didengar?” menemukan jawabannya di sini. Justru karena ia lahir dari kehidupan yang tidak dramatis, suara Beno mewakili pengalaman yang paling luas, paling umum, dan paling rentan: hidup sebagai manusia biasa di tengah waktu yang terus berjalan.
10. Memposisikan Puisi Beno dalam Puisi Indonesia Mutakhir
Jika ditarik ke peta yang lebih luas, puisi Beno Siang Pamungkas menempati wilayah yang khas dalam puisi Indonesia mutakhir: lirisisme getir dengan ironi sunyi. Ia tidak berada di kubu puisi retoris-politik yang mengandalkan ketegangan sosial sebagai bahan bakar utama, tetapi juga tidak sepenuhnya tenggelam dalam estetika personal yang tertutup. Puisinya berdiri di antara keduanya: sebagai kesaksian, bukan manifesto.
Dalam lanskap sastra kontemporer, kecenderungan ini penting. Di tengah derasnya puisi yang ingin segera relevan, segera viral, atau segera mengambil posisi ideologis, puisi Beno memilih bergerak pelan. Ia tidak menolak kenyataan sosial, tetapi mengalaminya melalui dampaknya pada batin individual. Kota, relasi, media, bahkan agama, hadir bukan sebagai tema besar, melainkan sebagai latar yang terus-menerus menggeser keseimbangan jiwa.
Puisi-puisi seperti ini mengingatkan kita pada gagasan Seamus Heaney tentang puisi sebagai “crediting of marvels”, upaya memberi kepercayaan kembali pada pengalaman kecil yang nyaris tak diperhitungkan (The Government of the Tongue, London: Faber & Faber, 1988). Dalam konteks Indonesia mutakhir, sikap semacam ini menjadi semacam koreksi diam-diam terhadap kecenderungan puisi yang terlalu ingin signifikan.
Beno tidak sedang merumuskan generasi, apalagi mazhab. Ia menulis dari posisi manusia yang hidup di dalam ketidakpastian makna. Karena itu, puisinya tidak menutup luka dengan heroisme, tetapi juga tidak memamerkan penderitaan. Bahkan ketika menyentuh wilayah paling gelap, nada yang dipilih tetap terkendali, nyaris datar, seolah subjek liris sadar bahwa berlebihan justru akan merusak kejujuran pengalaman.
Dalam pengertian ini, puisi Beno dapat dibaca sebagai kesaksian sunyi manusia modern. Ia tidak meminta kita terkejut, melainkan mengajak kita menyadari bahwa banyak krisis terbesar justru berlangsung tanpa suara. Kehilangan makna, kelelahan batin, dan ironi hidup sehari-hari sering terjadi tanpa peristiwa besar. Puisi Beno memberi bahasa pada situasi itu.
Posisi ini membuat puisinya relevan bukan karena tema-temanya baru, tetapi karena caranya bersikap terhadap dunia. Ia menolak dramatik palsu, menolak kepahlawanan emosional, dan memilih kejujuran yang getir. Dalam peta puisi Indonesia mutakhir, suara seperti ini penting sebagai penyeimbang; pengingat bahwa sastra tidak selalu harus menjadi terompet, kadang cukup menjadi napas yang tertahan.
Dengan demikian, dari pengalaman individual menuju generalisasi estetik, puisi Beno menegaskan satu hal: bahwa kesunyian juga memiliki hak bicara. Dan justru dari sanalah kita belajar kembali mendengar.
11. Bahasa Puisi sebagai Upaya Menyelamatkan Rasa
Dalam lintasan puisi-puisi Beno Siang Pamungkas, yang paling menggetarkan bukanlah ledakan emosi, melainkan justru ketiadaan letupan itu sendiri. Banyak puisinya bergerak di wilayah rasa yang nyaris datar, bahkan dingin, seolah penyair sengaja menanggalkan dramatisasi agar pembaca berhadapan langsung dengan satu hal yang kerap dihindari: kesadaran yang telanjang.
Dalam “Hari yang Berbahaya”, wilayah itu ditandai dengan kalimat yang hampir tanpa intensitas emosional:
“dan segalanya terlihat biasa
tanpa rasa sedih juga gembira”
Di sini, bahaya tidak datang sebagai ancaman eksternal, melainkan sebagai kondisi batin: ketika rasa tak lagi bereaksi. Kehampaan bukan sekadar kekosongan, tetapi keadaan di mana manusia berhenti menyadari bahwa dirinya sedang kehilangan sesuatu yang esensial.
Puisi, dalam konteks ini, tidak berfungsi sebagai luapan perasaan, melainkan sebagai penanda. Ia menamai kehampaan agar kehampaan itu terlihat. Tindakan menamai inilah yang menjadi bentuk penyelamatan minimal. Kesadaran, betapapun rapuhnya, masih lebih bermakna daripada ketumpulan yang tak disadari.
Lintas puisi Beno menunjukkan pola serupa. Dalam “Ruang Tamu”, misalnya, dunia dipotret sebagai lalu lintas kehadiran yang cepat menguap:
“nama-nama pergi dan datang …
tapi banyak yang lekas
menyirna tanpa bekas”
Tidak ada ratapan. Tidak ada protes. Justru di situlah daya pukulnya. Bahasa yang tenang ini memaksa pembaca menyadari bahwa kehilangan terbesar sering terjadi tanpa suara.
Puisi-puisi seperti “Sehari Tanpamu” atau “Januari Penghabisan” juga tidak membangun tragedi dengan hiruk-pikuk. Keterasingan dan luka disampaikan melalui citraan sederhana, bahkan nyaris kasual. Namun di balik kesederhanaan itu, bahasa bekerja sebagai alarm batin: ada sesuatu yang sedang aus, dan kita nyaris terbiasa dengannya.
Dengan demikian, bahasa puisi Beno tidak menawarkan penyembuhan dalam arti menenangkan. Ia lebih jujur: puisi hanya bisa menyelamatkan rasa sejauh manusia masih mau menyadari bahwa rasanya sedang terancam. Kesadaran itulah bentuk penyelamatan paling minimal, sekaligus paling mungkin.
Di titik ini, puisi tidak mengklaim mampu mengubah dunia. Ia hanya memastikan satu hal: manusia tidak sepenuhnya hilang dari dirinya sendiri.
12. Penutup: Menyadari Bahaya agar Tetap Hidup
Kesadaran akan bahaya adalah syarat menjadi manusia.
Kita kembali ke puisi “Hari yang Berbahaya”, bukan untuk mengulang, melainkan untuk melihatnya dengan kesadaran yang telah berlapis. Di puisi ini, Beno menandai sebuah wilayah batin yang selama ini dihindari:
“Aku yakin ini wilayah yang selama ini kuhindari
sepotong waktu, di mana segalanya kehilangan makna”
Bahaya yang dimaksud bukan kekacauan, bukan bencana, bukan tragedi besar. Bahaya justru hadir ketika hidup menjadi terlalu normal, terlalu rutin, terlalu biasa, hingga makna kehilangan urgensinya.
Karena itu, hari yang berbahaya adalah hari ketika manusia berhenti merasa perlu waspada terhadap dirinya sendiri.
Dalam keseluruhan esai ini, puisi-puisi Beno dibaca bukan sebagai arsip pengalaman personal semata, melainkan sebagai peta kesadaran. Ia menunjukkan bagaimana manusia modern dapat hidup dengan rapi, berfungsi dengan baik, tetapi pelan-pelan tercerabut dari rasa, dari empati, dari kepekaan paling dasar.
Puisi hadir untuk mengganggu kenyamanan itu. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan kalimat-kalimat yang datar, bahkan nyaris dingin. Justru karena itulah ia efektif. Ia membuat pembaca berhenti sejenak dan bertanya: apakah aku masih merasa, atau hanya menjalani?
Menyadari bahaya tidak otomatis membuat manusia selamat. Namun tanpa kesadaran itu, manusia bahkan tidak tahu bahwa dirinya sedang berada di ambang kehilangan. Dalam pengertian ini, puisi bukanlah solusi, melainkan pengingat. Ia menjaga agar manusia tetap terjaga, meski hanya sebentar.
Dan mungkin, di zaman ketika segalanya bergerak cepat dan dangkal, menjaga kesadaran itulah bentuk keberanian paling sederhana, sekaligus paling manusiawi.
Puisi, pada akhirnya, tidak menyelamatkan hidup. Tetapi ia menjaga agar hidup tidak sepenuhnya lupa bahwa dirinya sedang hidup. ***
Daftar Pustaka
Heaney, Seamus. 1988. The Government of the Tongue. London: Faber & Faber.
Pamungkas, Beno Siang. 2006–2013. Kumpulan puisi (berbagai judul). Diakses dari: https://www.sepenuhnya.com/p/puisi-karya-beno-siang-pamungkas.html
Taylor, Charles. 1989. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
—
*Penulis adalah penyair, Ketua Sekolah Kepenulisan Sastra Pedaban (SKSP) dan Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.