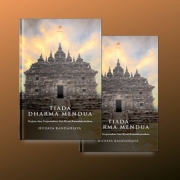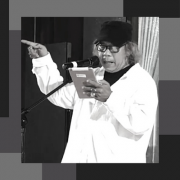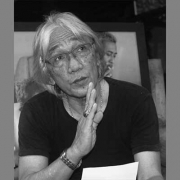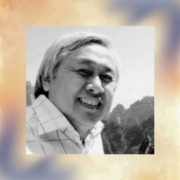Merawat Ingatan Keindonesiaan Melalui Keterlibatan di Pinggiran
Oleh: Indro Suprobo*
Tanah air adalah tempat penindasan diperangi, tempat perang diubah menjadi kedamaian, tempat kawan manusia diangkat menjadi manusiawi, oleh siapa pun yang ikhlas berkorban. Patriotisme masa kini adalah solidaritas dengan yang lemah, yang hina, yang miskin, yang tertindas. Menuntut ilmu dan mengabdi kepada rakyat bukanlah dua perkara yang sepantasnya dipisah-pisahkan.
— YB. Mangunwijaya
Pernyataan YB. Mangunwijaya ini menunjukkan esensi dari visi hidupnya yang radikal. Ada tiga hal yang ditegaskan di dalamnya. Pertama, tanah air dipahami sebagai locus utama bagi upaya untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki komitmen untuk mengabdi kepada tanah air, ia musti menjadi subyek yang ikhlas berkorban agar dapat menjalankan prinsip memanusiakan manusia itu. Kedua, yang dimaksud dengan kecintaan kepada tanah air atau patriotisme, adalah praksis solidaritas dengan semua kaum tertindas. Mengapa demikian? Karena solidaritas dengan semua kaum tertindas adalah nafas utama bagi upaya memanusiakan manusia yang merupakan penghuni utama tanah air itu. Ketiga, mencintai ilmu pengetahuan tak dapat dipisahkan dari praksis solidaritas kepada kaum tertindas sebagai upaya memanusiakan manusia. Mencintai ilmu dan mengabdi kepada rakyat merupakan satu hal yang terikat erat.
Dalam diri YB. Mangunwijaya, ketiga hal yang tersimpan di dalam pernyataan itu telah benar-benar terwujud nyata. Seluruh laku hidup Mangunwijaya menjadi praksis nyata pelaksanaan kata-kata. Contemplatio (rumusan, pengetahuan, kata-kata dan pernyataan-pernyataan) dan actio (tindakan dan praksis nyata) telah mengejawantah di dalam unio (satu kesatuan tindakan). Sehingga seluruh praksis hidup Mangunwijaya boleh disebut sebagai contemplatio in actione, yakni upaya merumuskan, merefleksikan, mengonstruksi pengetahuan dan pernyataan melalui praksis atau tindakan nyata di lapangan. Namun boleh juga disebut sebagai actio in contemplatione, yakni tindakan dan praksis nyata yang dikerangkai, dijiwai, disinari, serta dilandasi oleh pengetahuan atau refleksi kritis atas realitas.
Dari praksis hidup YB. Mangunwijaya ini kita dapat menjumput suatu pembelajaran radikal bahwa seluruh refleksi atas pengalaman dan ilmu pengetahuan itu, senantiasa mencerminkan keberpihakan, secara internal mengandung preferential option, dan tidak bebas nilai karena ia memilih dan berpihak kepada nilai-nilai, yakni nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, pengetahuan dan praksis hidup tidak pernah bersifat netral. Seluruh rumusan refleksi dan pengetahuan serta praksis hidup YB. Mangunwijaya merupakan satu laku keberpihakan.
Merawat Ingatan
Visi hidup YB. Mangunwijaya yang radikal itu terbentuk pada saat remaja, yakni pada usia 16 tahun, saat ia menjadi bagian dari Tentara Pelajar antara tahun 1947-1949, terutama setelah ia mendengarkan secara langsung isi pidato Mas Isman, Komandan batalion Tentara Rakyat Indonesia Pelajar (TRIP). Setelah rakyat Malang mengelu-elukan kedatangan mereka, dalam pidatonya Mas Isman menyatakan,
“Kami bukan pahlawan. Kami telah membunuh, membakar, merusak, tangan kami penuh darah. Yang pantas disebut pahlawan adalah rakyat yang terjajah dan teraniaya. Maka jangan mengelu-elukan saya, lebih baik perhatikan anak-anak muda ini, yang bisa berguna nantinya.”[1]
Atau dalam versi lain, pidato mas Isman itu berbunyi demikian,
“Jangan sebut kami pahlawan atau kesuma bangsa… Kami bukan pahlawan! Yang menjadi pahlawan adalah rakyat jelata, petani-petani yang menghidupi kami.”[2]
Pidato mas Isman ini sedemikian menggetarkan kesadaran YB. Mangunwijaya. Ia melihat bahwa di dalam pidato itu tersimpan kebenaran sebagaimana ditemukan dalam pengalaman nyata, kejujuran, kerendahan hati, dan integritas mas Isman sebagai pimpinan. Pidato itu menyusup ke dalam jaring-jaring tatanan simbolis dirinya, dan memengaruhi seluruh proses pemaknaan hidupnya kemudian, sehingga lahirlah kehendak, cita-cita, janji dan komitmen bahwa ia musti membayar hutang kepada rakyat, dan untuk itu ia musti mengabdikan dirinya untuk membela dan memuliakan serta memanusiakan kehidupan rakyat.
Dalam konteks inilah, seluruh pengabdian hidupnya di masa kemudian, di mana ia mengambil pilihan untuk melakukan segala daya upaya, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya, untuk memilih keberpihakan kepada rakyat, terutama mereka yang dipinggirkan, dimiskinkan, didiskriminasi, dimanipulasi, diintimidasi, dan ditindas, dengan cara membela mereka dan mengambil posisi berdiri bersama mereka yang dipinggirkan, sangat pantas dibaca sebagai sebuah jalan untuk terus-menerus merawat ingatan. Melalui pilihan tindakan berpihak kepada mereka yang dipinggirkan ini, Mangunwijaya merawat ingatan tentang nilai-nilai perjuangan, tentang cita-cita kemerdekaan, tentang harapan akan keadilan dan kesejahteraan, tentang hidup yang penuh martabat, yang pada masa lalu dihidupi oleh rakyat dalam tindakan nyata, dalam pengorbanan mereka selama masa perjuangan. Dengan cara itulah, yakni dengan benar-benar berpihak dan membela rakyat yang dipinggirkan, Mangunwijaya senantiasa merawat ingatan bahwa ia berhutang kepada rakyat, bahwa rakyatlah yang merupakan subyek utama dari seluruh perjuangan kemerdekaan untuk membangun keindonesiaan.
Merawat Ingatan dan Inkarnasi Kemanusiaan
Merawat ingatan tentang keindonesiaan melalui keberpihakan dan keterlibatan langsung di dalam hidup rakyat yang berada di posisi pinggiran, pada saat yang sama merupakan sebuah praksis dan metode untuk menyelamkan seluruh diri ke dalam duka, kecemasan, kegelisahan, penderitaan, perasaan, pengalaman, ketakutan, kemarahan, ketidakberdayaan dan harapan mereka. Ini merupakan langkah untuk mengosongkan diri sendiri (kenosis), dan melebur ke dalam seluruh pengalaman manusia pinggiran, menjadikan seluruh pengalaman dan kecemasan mereka sebagai pengalaman dan kecemasan dirinya sendiri, sehingga ia sungguh-sungguh mengalami apa yang dialami oleh mereka, dan mengenali apa yang benar-benar mereka harapkan dan mereka rindukan di dalam kehidupan. Langkah ini merupakan sebuah praksis mendarah-daging ke dalam kehidupan nyata rakyat yang dipinggirkan. Dalam bahasa Latin praksis ini disebut sebagai incarnatio atau inkarnasi, masuk menelusup melebur dan menyatu secara radikal di dalam “darah dan daging” pengalaman dan kehidupan rakyat yang terpinggirkan (Lat. caro, carnis artinya daging).
Karena seluruh pengalaman nyata kehidupan rakyat yang terpinggirkan itu telah menjadi “darah dan daging” kehidupannya sendiri, maka itu menjadi “(per)ingatan” yang tegas dan tajam bahwa nilai-nilai, kerinduan, harapan, cita-cita dan kebutuhan mereka, lengkap dengan seluruh derita dan kesulitan yang dihadapinya, musti menjadi referensi utama bagi seluruh keprihatinan, komitmen dan proses produksi makna atas realitas sehari-hari, serta menjadi landasan bagi pertimbangan-pertimbangan dan pengambilan keputusan, terutama terkait perumusan kebijakan.
Dengan demikian, merawat ingatan tentang keindonesiaan melalui keterlibatan dalam kehidupan rakyat di pinggiran, yang sekaligus merupakan praktik inkarnasi ke dalam seluruh kehidupan mereka, akan menjadi cara yang paling ampuh untuk terus-menerus menjadikan pengalaman nyata rakyat, sebagai sumber dan referensi utama bagi pengambilan keputusan dan pilihan tindakan. Ia akan senantiasa menjadi bagian dari rakyat pinggiran, berpikir dan bercita-cita sebagaimana mereka berpikir dan bercita-cita, menyuarakan apa yang benar-benar menjadi suara mereka, dan mengenali apa yang benar-benar menjadi kebutuhan mereka. Orang Jawa merumuskannya dengan istilah manjing ajur ajer dalam kehidupan rakyat pinggiran. Itulah inkarnasi kemanusiaan.
Dalam perspektif psikoanalisis Lacan, inkarnasi kemanusiaan sebagaimana dijalankan oleh YB. Mangunwijaya dipahami sebagai proses pembentukan identitas diri yang tanpa henti. Keterlibatan langsung atau inkarnasi dalam kehidupan rakyat pinggiran, merupakan jalan bagi Mangunwijaya untuk terus-menerus merumuskan identitas dirinya sebagai bagian dari identitas rakyat tertindas. Seluruh tatanan bahasa dan relasi yang hidup di dalam keseharian rakyat pinggiran menjadi bahasa dan elemen yang memengaruhi seluruh proses pembentukan dirinya sebagai subyek, dan memengaruhi seluruh produksi makna dalam menghadapi realitas. Maka ketika ia berpikir, berbicara, bersikap dan memilih tindakan, semuanya dipengaruhi oleh bahasa dan relasinya dengan orang-orang pinggiran. Meskipun Mangunwijaya memiliki banyak identitas simbolis lainnya, yakni sebagai rohaniwan, sastrawan, budayawan, intelektual, dan arsitek, seluruh kehadiran dirinya yang dilengkapi oleh kompetensi-kompetensi yang beraneka rupa itu senantiasa merupakan negosiasi dan pembelaan demi penghormatan terhadap martabat manusia pinggiran. Ini sekaligus merupakan peringatan bahwa martabat kaum pinggiran tak pernah boleh untuk diabaikan. Dengan beragam identitas simbolis yang melekat padanya, YB. Mangunwijaya senantiasa menghadirkan dirinya sebagai subyek yang berdiri di pinggiran.
Merumuskan Pengetahuan dalam Keberpihakan
Praktik melibatkan diri di dalam kehidupan masyarakat pinggiran, yang dapat disebut sebagai inkarnasi kemanusiaan sekaligus kenosis kemanusiaan, di mana subyek membuka diri, memberikan ruang seluas-luasnya bagi kehadiran pengalaman kaum pinggiran, agar dapat mengenali duka, kecemasan, kesulitan, ketakberdayaan, sekaligus harapan, cita-cita, kerinduan, kebutuhan, potensi, kompetensi, dan energi resiliensi yang hidup di dalam diri kaum pinggiran ini, merupakan metode dan sarana fundamental untuk merumuskan pengetahuan yang berpihak dan sesuai dengan realitas kaum pinggiran. Pengetahuan yang dirumuskan dan direfleksikan dari pengalaman kaum pinggiran ini menjadi pengetahuan yang empatik dan bersifat liberatif, yakni merangkul kebutuhan, kepentingan dan harapan mereka sekaligus menuntun jalan pembebasan dari segala yang bersifat manipulatif dan dominatif.
Meminjam istilah yang digunakan oleh Antonio Gramsci, pengetahuan yang demikian ini disebut sebagai pengetahuan organik, yakni pengetahuan yang diproduksi oleh intelektual organik. Intelektual organik adalah kaum intelektual yang tidak bisa bersikap tidak peduli terhadap realitas masyarakat, melainkan berani mengambil sikap yang jelas yakni melabuhkan keberpihakan, dan melalui keberpihakan itu ia turut mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan dibutuhkan oleh masyarakat.[3] Sifat organik ini, oleh Gramsci juga disebut sebagai bersifat partisan, yang berasal dari bahasa Italia partiggiare, yang memiliki arti berpihak atau mengambil bagian, sebagai lawan dari sifat tidak peduli atau indifferent.[4] Terutama dalam situasi di mana martabat manusia pinggiran itu diabaikan dan terancam oleh tindakan-tindakan penindasan, merumuskan pengetahuan organik yang berpihak, yang bersifat partisan, menolak sikap netral dan ketidakpedulian, merupakan sebuah pilihan tindakan moral karena dengan demikian tindakan ini sedang membela, mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang penting dan mendasar bagi kehidupan kemanusiaan.[5]
Melawan Konstruksi Ingatan dan Pengetahuan Dominan
Pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian berencana menjalankan program untuk mencetak sawah 1 juta hektare (ha) di Merauke, Papua Selatan. Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi mendukung upaya cetak sawah yang akan dilakukan pemerintah itu. Beberapa pernyataan dukungannya dirumuskan sebagai berikut:[6]
“Saya dukung program ini 100 persen karena di situ ada tujuan memanusiakan orang dengan pertanian. Maka kami dari Gereja-Gereja juga punya tujuan yang sama yaitu memanusiakan orang, bukan mengkotak-kotakkan orang. Orang itu harus selaras dengan hukum kemanusiaan yang kita anut.
Kadang-kadang ada aktivis yang belum mengerti apa itu Pancasila karena menilai cetak sawah ini dari satu sisi. Padahal ini adalah proyek Pancasila karena di situ ada kemanusiaan. Jadi menurut saya pemerintah perlu melakukan lebih banyak sosialisasi supaya orang baik kita perbanyak dan orang jahat kita singkirkan.
Menurut saya, ini tanah milik Tuhan Allah dan orang Papua menyerahkan tanah Tuhan ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Kenapa? Ini Proyek kemanusiaan dan ini harus berdampingan dengan Tuhan.”
Tragisnya, pernyataan-pernyataan itu diungkapkan oleh seorang pimpinan Gereja Katolik sambil berfoto dan tersenyum hangat bersama para pejabat dan aparat. Sementara itu, masyarakat Papua, yang selama ini merawat dan mengolah tanah-tanah itu, menyatakan penolakan dan kritik tajam terhadap rencana itu. Dengan demikian, pernyataan pimpinan Gereja Katolik itu menuai banyak sekali kritik dari masyarakat.
Dalam kategori pemikiran Gramsci, pernyataan-pernyataan itu mencerminkan bahwa Mgr. Mandagi sebagai rohaniwan sekaligus intelektual Gereja Katolik merupakan rohaniwan dan intelektual yang indifferent, tidak memiliki kepedulian terhadap duka, kecemasan, kesulitan, kepentingan, kebutuhan, harapan dan cita-cita masyarakat Papua sendiri. Mengapa ini terjadi? Jawabannya, barangkali karena Uskup Mandagi tidak menjalani laku kenosis dan incarnatio ke dalam kehidupan nyata masyarakat Papua sehari-hari. Ia tidak mengenali jejak-jejak penderitaan dan peminggiran yang telah dialami dan dilalui oleh masyarakat Papua sepanjang perjalanan hidupnya. Ia tidak manjing ajur ajer ke dalam darah dan daging kehidupan masyarakat Papua. Akibatnya, ia sama sekali tak memiliki ingatan tentang kehidupan nyata masyarakat Papua dan sama sekali tak memiliki keterlibatan di tengah kehidupan masyarakat Papua sebagai manusia pinggiran. Karena tak melakukan kenosis, yakni mengosongkan dirinya dan menyediakan ruang yang luas bagi orang lain agar orang lain itu berada di pusat perhatian, serta mendengarkannya sekaligus belajar darinya, melalui pernyataan-pernyataan itu, Uskup Mandagi justru menempatkan dirinya sendiri pada pusat, dan meminggirkan masyarakat Papua. Tanpa kenosis dan incarnatio, seseorang tak akan sanggup memproduksi pernyataan dan pengetahuan yang empatik, organik, serta berpihak kepada mereka yang cenderung dipinggirkan. Tanpa itu semua, ia tak memiliki ingatan tentang martabat manusia pinggiran. Akibatnya, pernyataan dan pengetahuan yang ia produksi justru mencerminkan pengetahuan yang menguntungkan kekuasaan dan kaum dominan.
Pengalaman dan kenyataan ini membenarkan apa yang dinyatakan oleh Louis Althusser bahwa keluarga, sekolah maupun lembaga agama dapat berperan sebagai aparatus ideologis negara (Ideological State Apparatuses), yakni perangkat negara yang sanggup memengaruhi warga negara untuk tunduk terhadap seluruh aturan dan kepentingan kekuasaan atau kelompok dominan, tanpa represi yang kelihatan. Peran aparatus ideologis negara ini ditempatkan di dalam keseluruhan proses reproduksi tenaga kerja dalam masyarakat kapitalis. Secara gamblang Althusser menyatakan:
“Reproduksi tenaga kerja menuntut bukan hanya reproduksi keterampilannya, tetapi juga, pada saat yang sama, reproduksi kepatuhannya terhadap aturan tatanan yang mapan, yaitu reproduksi kepatuhan terhadap ideologi penguasa bagi para pekerja, dan reproduksi kemampuan untuk memanipulasi ideologi penguasa dengan tepat bagi para agen eksploitasi dan represi, sehingga mereka pun akan menyediakan dominasi kelas penguasa ‘dalam bentuk kata-kata’.”[7]
Apa yang dilakukan oleh aparatus ideologis negara ini adalah menyediakan dominasi kelas penguasa dalam bentuk kata-kata atau bahasa, atau dalam bentuk pengetahuan yang secara bawah sadar diterima sebagai kebenaran dan keyakinan. Inilah yang oleh Gramsci disebut sebagai hegemoni, yakni sebuah proses membangun ketundukan sejak di dalam pikiran dan pengetahuan tanpa kekerasan. Secara jelas Gramsci menyatakan hegemoni sebagai rule by consent and by virtue of moral and intellectual authority.[8] Hegemoni semacam inilah yang seringkali dihadapi di dalam realitas sehari-hari.
Apabila pengetahuan hegemonik yang menguntungkan kelompok dominan sebagaimana dicerminkan oleh pengetahuan yang diproduksi oleh uskup Merauke itu dibiarkan, dalam konteks Papua, ia akan menyediakan jalan mulus bagi apa yang oleh David Harvey disebut sebagai akumulasi melalui perampasan (accumulation by dispossession). Akumulasi melalui perampasan ini merupakan pengembangan dan perluasan dari praktik akumulasi primitif di dalam dunia masa kini, yang dirumuskan demikian:
“yang meliputi komodifikasi dan privatisasi tanah serta pengusiran paksa penduduk petani, konversi berbagai bentuk hak milik (umum, kolektif, negara, dll.) menjadi hak milik pribadi yang eksklusif, penindasan hak atas tanah bersama, komodifikasi tenaga kerja dan penindasan bentuk-bentuk produksi dan konsumsi alternatif yang bersifat pribumi, proses apropriasi aset kolonial, neo-kolonial, dan imperial, termasuk sumber daya alam, monetisasi pertukaran dan perpajakan, khususnya tanah, perdagangan budak, dan riba, utang nasional, dan pada akhirnya sistem kredit. Negara, dengan monopoli kekerasan dan definisi legalitasnya, memainkan peran krusial dalam mendukung dan mendorong proses-proses ini.”[9]
Dalam konteks Papua, tanah-tanah yang dirampas dan menjadi proyek strategis nasional seringkali merupakan tanah-tanah adat baik berupa hutan maupun ladang. Perampasan hutan adat bagi masyarakat Papua bukan hanya semata merupakan perampasan aset, melainkan perampasan terhadap seluruh hidup dan jiwa masyarakat, karena hutan bagi masyarakat adat Papua merupakan wilayah yang sakral dan sangat penting dalam seluruh tatanan simbolis masyarakat, yang memengaruhi seluruh produksi makna. Perampasan hutan adat bukan hanya disebut sebagai kejahatan ekologis atau biasa disebut ecosida, namun juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena merusak seluruh daya dukung kehidupan masyarakat adat baik dari sisi ekonomi, sosial, kesehatan, kultural, maupun religius.
Jika negara memfasilitasi akumulasi melalui perampasan ini, terutama terhadap tanah-tanah dan hutan adat, secara sistematis, negara telah melemahkan dan merusak insitusi lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam, sekaligus tidak hadir karena gagal menjalankan peran pengelolaan itu, malah menjalankan open access sehingga terjadi privatisasi besar-besaran dan melahirkan bencana ekologis.[10]
Kasus Merauke dan peran aparatus ideologis negara yang tercermin dalam peran pimpinan Gereja Merauke hanyalah salah satu contoh. Di berbagai wilayah lain di seantero nusantara, hal ini terjadi dengan pola yang hampir sama. Masyarakat-masyarakat lokal berhadapan dengan konstruksi-konstruksi pengetahuan hegemonik yang menguntungkan elit berkuasa, yang diproduksi oleh aparatus-aparatus ideologis lokal baik pemimpin agama, intelektual, maupun pemimpin kultural. Konstruksi pengetahuan hegemonik itu dapat berupa pernyataan-pernyataan, komentar, tulisan di media masa atau media sosial, kotbah-kotbah di mimbar keagamaan, paparan-paparan dalam diskusi atau seminar dan sebagainya. Intinya, seluruh konstruksi pengetahuan hegemonik itu berupaya membangun sebuah cara berpikir masyarakat yang mengarahkannya kepada persetujuan dan ketundukan terhadap narasi-narasi yang mengutungkan elit dominan. Akibatnya, (sebagian) masyarakat secara sukarela, tanpa represi, tanpa merasa dipaksa, menyatakan ketundukan kepada kepentingan elit kekuasaan. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi subyek dan pusat referensi, melainkan sebagai obyek dan kaum yang ditempatkan di pinggiran.
Oleh karena itu, melawan konstruksi ingatan dan pengetahuan hegemonik yang menguntungkan sekelompok elit dominan merupakan mandat dan panggilan fundamental. Upaya itu dijalankan dengan memproduksi ingatan dan pengetahuan yang emansipatoris, empatik, berpihak, solider, organik dan membela kepentingan dan martabat mereka yang cenderung terpinggirkan dan tertindas.
Belajar dari pengalaman dan kesaksian hidup YB. Mangunwijaya, upaya merawat ingatan dan memproduksi pengetahuan yang demikian itu hanya dapat dijaga dengan senantiasa berani menjalankan kenosis (pengosongan diri, melepaskan kepentingan diri, menempatkan diri di pinggiran), contemplatio (mengenali keprihatinan, duka, kecemasan, dan harapan kaum pinggiran, dilengkapi dengan seluruh perangkat analisis kritis yang dibutuhkan), incarnatio (menyatukan dan meleburkan diri di kedalaman kehidupan kaum pinggiran), dan actio (melibatkan diri secara total dalam seluruh pengalaman kaum pinggiran dan berupaya mewujudkan apa yang perlu bagi pertumbuhan dan mekarnya hidup manusia pinggiran).
Hal yang krusial dalam laku contemplatio adalah menjalani pendidikan kritis bagi diri sendiri. Mendidik sikap kritis adalah seluruh upaya untuk menunda persetujuan terhadap segala wacana yang dikonstruksi oleh kekuasaan atau kelompok dominan karena menyadari bahwa bahasa tidak netral, dan mewaspadai bahwa di balik setiap bahasa seringkali tersembunyi kepentingan atau ideologi kelas dominan yang mengonstruksi bahasa tersebut.[11] Termasuk di dalam laku contemplatio ini adalah merumuskan pengetahuan sebagai hasil analisis kritis terhadap seluruh pengalaman dan realitas yang mencerminkan sikap keberpihakan, preferential option, terhadap kepentingan dan martabat kaum pinggiran.
Hanya dengan upaya nyata yang demikian ini, tanah air akan benar-benar menjadi tempat di mana penindasan diperangi, tempat perang diubah menjadi kedamaian, tempat kawan manusia diangkat menjadi manusiawi, oleh siapa pun yang ikhlas berkorban. Dengan demikian, patriotisme benar-benar terwujud sebagai solidaritas dengan yang lemah, yang hina, yang miskin, yang tertindas. Akhirnya, seluruh proses menuntut ilmu benar-benar tak dapat dipisahkan dari praktik mengabdi kepada rakyat, karena pengetahuan diperoleh dan digali secara mendalam dari praktik pengabdian terhadap rakyat. Jika demikian halnya, YB. Mangunwijaya telah menyediakan teladan dan warisan yang sangat berharga dan sakral bahwa untuk merawat ingatan tentang keindonesiaan, sangat dibutuhkan sebuah laku berupa keterlibatan di tengah-tengah kehidupan manusia pinggiran.
***
(Artikel ini merupakan salah satu chapter dalam Abidin Fikri dkk, Jalan Gelap Demokrasi dan Keadilan, Kumpulan Esai, Tonggak Pustaka & Abidin Fikri Pandjialam Foundation, Oktober 2025, hlm.163-176. Dipublikasikan di sini agar dapat dibaca oleh khalayak lebih luas)
[1] Lih. Moh Habib Asyhad, Romo Mangun: Kami Bukan Pahlawan! dalam https://intisari.grid.id/read/0333737/romo-mangun-kami-bukan-pahlawan
[2] Lih. Hendi Jo, Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional dalam https://www.historia.id/article/pro-kontra-gelar-pahlawan-nasional-pknpz
[3] Lih. Indro Suprobo, “Cendekiawan Organik Membaca Perangi Tukang Insinyur”, kata pengantar dalam buku Riwanto Tirtosudarmo, Simposium Jokowi, Pebisnis Politik Menggapai Indonesia Emas, Tonggak Pustaka 2025, hlm.iv.
[4] Lih. https://overland.org.au/2013/03/i-hate-the-indifferent/ diakses 10-02-2025
[5] Lih. Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, Gramedia 2003, hlm. 40-41
[6] Lih. “Uskup Agung Merauke Dukung Program Cetak Sawah, Proyek Kemanusiaan untuk Rakyat Papua” dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/5711907/uskup-agung-merauke-dukung-program-cetak-sawah-proyek-kemanusiaan-untuk-rakyat-papua?page=2
[7] Lih. Louis Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses dalam https://www.csun.edu/~snk1966/Lous%20Althusser%20Ideology%20and%20Ideological%20State%20Apparatuses.pdf
[8] Lih. Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan, Resist Book 2008, hlm. 33-34
[9] Lih. David Harvey, The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession, Socialist Register 2004, hlm.73-75
[10] Lih. Mohamad Shohibuddin dan Muhammad Nashirulhaq, Fiqih Agraria, Sebuah Perbincangan, Kasan Ngali, 2022, hlm.61-71
[11] J. Haryatmoko, Critical Discourse Analysis, Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan, Rajawali Pers, 2016, hlm…. Lihat juga Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan, Resist Book, 2008, hlm.1-2
—–
*Indro Suprobo, Penulis, Editor, Penerjemah Buku, Tinggal di Jogyakarta.