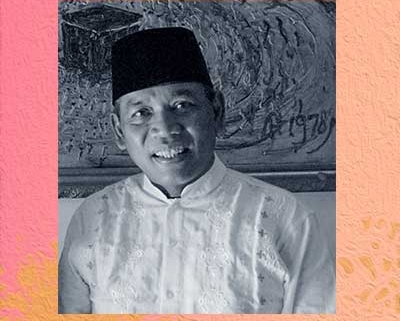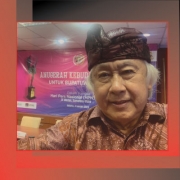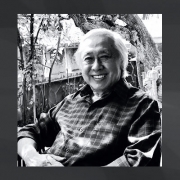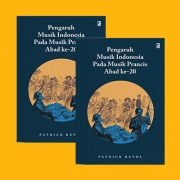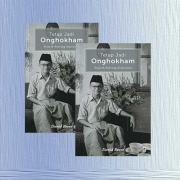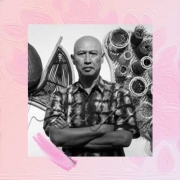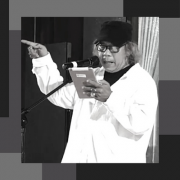Tantangan Integritas dan Akuntabilitas Tata Kelola Haji
Oleh: HM. Nasruddin Anshoriy Ch*
Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah sebuah tugas monumental yang melibatkan jutaan umat dan triliunan rupiah. Di satu sisi, haji adalah rukun Islam kelima, sebuah ibadah suci yang menuntut kesucian niat. Di sisi lain, ia adalah sebuah entitas manajemen yang kompleks, penuh dengan birokrasi, alokasi sumber daya, dan potensi penyimpangan. Kasus korupsi yang melibatkan pembagian kuota tambahan haji adalah bukti nyata dari rapuhnya sistem yang ada. Kasus ini menyingkap sebuah paradoks: ketika sebuah ibadah suci terperangkap dalam intrik politik dan keserakahan, esensinya pun terancam. Esai ini akan mengupas tuntas masalah tersebut melalui dua lensa utama: Literasi Manajemen Profesional Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Analisis Komprehensif Pentingnya Akuntabilitas dan Haji Berkeadilan.
Literasi Manajemen Profesional: Mengapa Sistem Haji Gagal?
Literasi manajemen menuntut setiap organisasi untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan. Dalam konteks haji, tujuannya adalah melayani jemaah dengan baik dan memastikan ibadah mereka berjalan lancar. Namun, kasus korupsi pembagian kuota menunjukkan kegagalan sistematis yang fundamental.
Kegagalan Prosedural dan Tata Kelola. Aturan yang jelas, yaitu pembagian kuota tambahan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus, tidak dipatuhi. Hal ini menunjukkan lemahnya tata kelola (governance) dan integritas manajerial. Keputusan untuk membagi kuota 50:50 bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga pengkhianatan terhadap prinsip keadilan. Dalam literasi manajemen, pelanggaran semacam ini menunjukkan adanya moral hazard di mana pihak pengelola menggunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, bukan untuk kemaslahatan publik.¹
Manajemen Antrean yang Tidak Efektif. Kuota tambahan haji diberikan dengan satu tujuan: mempercepat antrean panjang haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun. Ketika kuota itu disimpangkan, manajemen antrean menjadi tidak efektif. Ini bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah etika. Setiap jemaah haji yang menunggu dalam antrean memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil.
Kolusi dan Korupsi. Keterlibatan pejabat Kementerian Agama (Kemenag) dan penyedia jasa travel, seperti yang diindikasikan oleh pemeriksaan KPK, menunjukkan adanya kolusi. Dalam manajemen, kolusi adalah bentuk kegagalan pasar yang paling berbahaya. Ia merusak persaingan, mengorbankan kualitas layanan, dan pada akhirnya, merugikan konsumen—dalam hal ini, calon jemaah haji.
Analisis Komprehensif: Akuntabilitas dan Haji Berkeadilan
Kasus ini menyoroti pentingnya dua prinsip utama: akuntabilitas dan keadilan. Tanpa dua prinsip ini, penyelenggaraan haji akan terus menjadi lahan subur bagi penyimpangan.
Akuntabilitas sebagai Fondasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan tindakan. Dalam kasus kuota haji, akuntabilitas berarti pejabat yang bertanggung jawab harus mampu menjelaskan mengapa mereka menyimpang dari aturan. Pemeriksaan oleh KPK adalah salah satu bentuk penegakan akuntabilitas. Namun, akuntabilitas tidak hanya bersifat reaktif, melainkan harus proaktif. Ini berarti adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat dan transparansi yang mutlak. Lembaga seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kemenag harus secara rutin mempublikasikan laporan yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, sulit untuk membangun kepercayaan publik yang telah lama terkikis.
Haji Berkeadilan. Prinsip keadilan (fairness) menuntut bahwa setiap jemaah haji, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, diperlakukan sama. Pembagian kuota tambahan yang tidak adil adalah pelanggaran berat terhadap prinsip ini. Jemaah haji reguler, yang seringkali berasal dari kalangan menengah ke bawah dan telah menabung seumur hidup, menjadi korban dari sistem yang tidak berkeadilan. Haji khusus, yang biayanya jauh lebih mahal, adalah hak bagi mereka yang mampu. Namun, ketika kuota haji reguler yang seharusnya digunakan untuk melayani jutaan jemaah disimpangkan ke haji khusus, itu adalah pengkhianatan terhadap keadilan.
Momentum Bersih-Bersih Menuju Haji yang Berintegritas
Kasus korupsi ini, meskipun memalukan, adalah sebuah momentum untuk perbaikan. Ia adalah sebuah panggilan untuk meninjau ulang seluruh sistem penyelenggaraan haji di Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu, pembentukan Kementerian Haji dan Umroh menjadi langkah strategis yang vital. Namun, entitas baru ini tidak akan efektif tanpa sebuah komitmen fundamental: audit total berbasis kinerja sebagai momentum bersih-bersih tanpa syarat.
Audit ini harus mencakup tidak hanya aspek keuangan, tetapi juga kinerja operasional dan kepatuhan terhadap regulasi. Audit harus dilakukan secara menyeluruh dan independen, termasuk terhadap seluruh pihak yang terlibat—tanpa terkecuali. Ini berarti, seluruh anggota DPR RI yang selama ini memiliki pengaruh besar dalam alokasi kuota, juga harus menjadi bagian dari audit ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah prasyarat mutlak. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat dipulihkan, dan haji dapat kembali menjadi ibadah suci yang murni, tidak ternoda oleh keserakahan dan ketidakadilan.
——
Catatan Kaki
¹ BPK. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023. Jakarta: BPK.
Rujukan Ilmiah
Hidayat, M. (2019). Manajemen Keuangan Haji: Sebuah Kajian Komprehensif. Jakarta: Gema Insani Press.
Zuhdi, M. (2015). Dinamika Politik dan Kebijakan Haji di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ma’arif, S. (2020). Literasi Hukum Masyarakat dan Tantangan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Analisis Hukum, 5(1), 45-60.
Purnomo, S. B. (2018). Quo Vadis Pengelolaan Keuangan Haji Pasca Pembentukan BPKH. Jurnal Keuangan Negara, 12(3), 201-215.
—–
*HM. Nasruddin Anshoriy Ch, Budayawan.