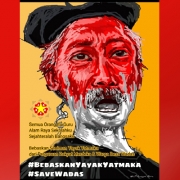Dusta Eropa
Oleh Gus Nas Jogja
Langit Cordoba sore itu adalah kanvas surealis, di mana jingga dan ungu bercampur dengan noda-noda hijau zamrud, seolah melukiskan fragmen ingatan yang patah. Aku, Sang Pencari Kebenaran, melangkah di antara pilar-pilar Istana Al Hambra di Altar Spanyol yang megah, setiap ubin mozaiknya berbisik kisah-kisah kuno. Angin membawa aroma melati yang pahit, bercampur dengan bau debu sejarah yang tak terucap. Di sinilah, di jantung Andalusia yang berdenyut, DUSTA EROPA akan kubongkar.
Ruang pertama yang kutelusuri adalah Patio de los Leones. Singa-singa batu itu membisu, namun dari mata kosong mereka memancar cahaya aneh, seperti memori kolektif yang terpendam. Tiba-tiba, dari bayangan tiang-tiang, muncullah Nicolaus Copernicus, dengan teropong besar di bahunya. Matanya yang cekung menatapku, penuh kegelisahan. “Kau melihat lingkaran-lingkaran di langit?” bisiknya, suaranya seperti desiran pasir. “Mereka bukan milikku sepenuhnya. Ada bayangan al-Tusi menari di sana, menggerakkan setiap planet dengan pasangan matematis yang tak kasat mata.”
Aku menatap Copernicus, seolah melihat sebuah jam tua yang berdetak mundur. “Bukankah Eropa bangga akan penemuanmu, Tuan?” tanyaku.
Dia tertawa, tawa yang kering seperti daun gugur. “Kebanggaan adalah ilusi. Kami mengklaim, tapi kami mewarisi. Kami menyusun ulang, tapi fondasinya sudah ada.” Dari sela-sela jubahnya yang lusuh, ia mengeluarkan selembar kertas tua yang sobek. Di sana terlukis diagram-diagram rumit, yang anehnya, sangat mirip dengan coretan-coretan di dinding Al Hambra. “Ini bukan gambaran bintang, Sang Pencari. Ini adalah peta kebohongan.”
Aku melangkah lebih jauh, menembus lorong waktu yang melengkung. Di sebuah sudut yang remang, dekat kolam air mancur yang memancarkan pantulan cahaya yang tidak nyata, kulihat sesosok pria berjanggut lebat, memegang gulungan papirus. Itu René Descartes, sang bapak rasionalisme. “Aku berpikir, maka aku ada,” gumamnya, namun suaranya terdengar ragu, seperti gema dari sumur tua. “Tapi apa yang kupikirkan? Dari mana datangnya akal yang kaugunakan untuk meragukan segalanya?”
Di sampingnya, muncul sesosok bayangan lain, lebih tua dan bijaksana. Ibnu Rusyd (Averroes). Ia menatap Descartes dengan senyum samar. “Akalmu, Tuan, adalah sungai yang mengalir dari mata air yang lebih tua. Sungai itu mengalir melalui kami, melewati gurun-gurun pemikiran, sebelum akhirnya mencapai kebunmu. Kau mungkin melihat pantulan dirimu di permukaan, tapi kau lupa dari mana air itu berasal.”
Descartes terdiam, papirusnya bergetar di tangannya. Aku merasakan getaran yang sama di jiwaku. Narasi Eropa, yang kokoh dan tak tergoyahkan, mulai retak seperti kaca di bawah tekanan yang tak terlihat.
Seiring malam merayap, Al Hambra berubah menjadi panggung teater absurd. Lampu-lampu minyak tua menyala sendiri, memproyeksikan bayangan raksasa para ilmuwan dan filsuf Eropa di dinding-dinding berukir. Ada Isaac Newton yang sibuk menghitung gravitasi, tanpa menyadari bahwa dasar-dasar matematika yang ia gunakan telah disempurnakan oleh al-Khwarizmi berabad-abad sebelumnya.
Ada Galileo Galilei yang menunjuk ke bintang-bintang, seolah ia yang pertama melihatnya, padahal peta langit telah disusun dengan detail oleh astronom-astronom Muslim.
“Lihatlah!” Tiba-tiba, suara profetik menggelegar dari menara Comares. Bukan suara manusia, melainkan suara ribuan buku yang terbuka secara bersamaan, setiap halamannya memancarkan cahaya kebenaran. “Mereka menari di atas panggung ilusi, mengklaim cahaya adalah milik mereka. Padahal, cahaya itu adalah warisan, lentera yang dihidupkan oleh tangan-tangan yang terlupakan!”
Aku mendongak. Di puncak menara, siluet seorang wanita anggun, jubahnya berkibar ditiup angin gurun. Itu mungkin imajinasiku, atau mungkin perwujudan hikmah yang telah lama tersembunyi. Dia tidak berbicara, namun pesannya merasuk ke dalam jiwaku: Kebohongan eurosantrisme adalah tirai yang mereka pasang untuk menyembunyikan jalinan takdir, untuk menafikan bahwa ilmu pengetahuan adalah sungai universal, bukan kolam pribadi.
Di tengah kegilaan ini, aku menemukan diriku di sebuah perpustakaan rahasia di bawah tanah, di mana buku-buku lama berbahasa Arab bersinar redup. Di sana, Ibnu Sina (Avicenna) duduk tenang, mengoreksi naskah-naskah kedokteran Eropa. “Mereka mengambil resepnya,” katanya tanpa menoleh. “Mereka mengklaim penemuan. Tapi jiwa dari pengobatan, etika dari penyembuhan, itu berasal dari tradisi yang lebih dalam, yang menghargai setiap nyawa sebagai anugerah.”
Cahaya bulan menembus celah-celah istana, jatuh tepat di atas ukiran kaligrafi Arab yang berbunyi: “Tiada Tuhan selain Allah.” Tiba-tiba, semua kekacauan mereda. Copernicus, Descartes, Newton, Galileo—semua menjadi bayangan transparan, menyatu dengan dinding-dinding Al Hambra. Aku menyadari, narasi Barat hanyalah satu dari banyak benang dalam permadani besar sejarah manusia. DUSTA EROPA bukan tentang kejahatan, melainkan tentang kelalaian, tentang amnesia sejarah yang disengaja.
Aku keluar dari gerbang Al Hambra saat fajar menyingsing, membawa beban kebenaran yang baru ditemukan. Cordoba pagi itu terlihat berbeda. Bukan lagi kanvas surealis, melainkan sebuah prasasti hidup yang menjeritkan keadilan historis. Peradaban tidaklah terisolasi, melainkan sungai-sungai yang mengalir, bertemu, dan saling memperkaya. Dan di setiap tetesan air itu, tersimpan jejak-jejak dari tangan-tangan yang terlupakan, yang telah membangun jembatan-jembatan menuju masa depan.
Dunia telah dibangun di atas fondasi yang lebih luas dari yang kita bayangkan. Dan tugas kita, sebagai Sang Pencari Kebenaran, adalah membongkar setiap lapis dusta, untuk mengungkapkan kemuliaan yang tersembunyi, dan mengembalikan narasi kepada keutuhannya.
—–
*Gus Nas Jogja, Budayawan.