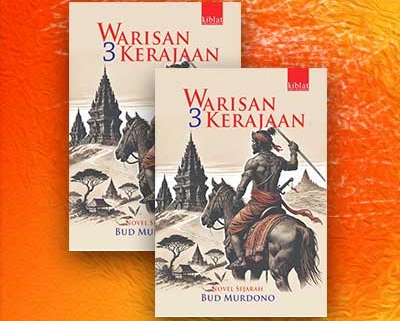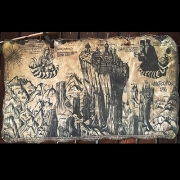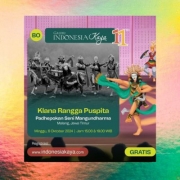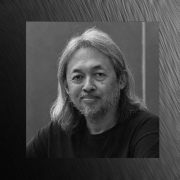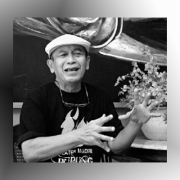Membaca Jejak Pembentukan Hasrat dan Ideologi

Oleh Indro Suprobo
Judul buku : Warisan 3 Kerajaan
Penulis: Bud Murdono
Halaman: 628 hlm
Penerbit: Kiblat Buku Utama, Bandung
Terbit: 2025
—–
“The problem for us is not whether our desires are satisfied or not. The problem is how do we know what we desire? There is nothing spontaneous, nothing natural about human desires.
Our desires are artificial – we have to be taught to desire”
Slavoj Zizek, The Pervert’s Guide to Cinema, 2006
—–
The Pervert’s Guide to Cinema adalah sebuah film dokumenter yang menyajikan paparan dan analisis Slavoj Zizek tentang berbagai macam film dengan menggunakan perspektif psikoanaisis Lacanian. Judul film dokumenter itu jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih berarti Sebuah Panduan bagi Mereka yang Terlena untuk Memahami Film. Kata “pervert” memang memiliki beragam pillihan arti, salah satunya adalah “orang mesum”. Dalam konteks ini, saya memilih untuk mengartikannya dengan Orang yang Terlena dalam arti kurang memiliki sikap kritis di dalam cara berpikir tentang realitas.
Pernyataan pokok Zizek sebagaimana saya kutip di bagian awal ini hendak menegaskan bahwa yang paling utama dalam kehidupan kita itu bukan soal apakah hasrat kita itu terpenuhi ataukah tidak, melainkan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang menjadi hasrat kita sendiri, karena hasrat manusia itu tidak bersifat spontan dan alamiah, melainkan bersifat artifisial dan merupakan buah dari sebuah konstruksi. Manusia harus diajari, dilatih dan dididik untuk membangun hasratnya sendiri.
Pernyataan Zizek ini merupakan pernyataan yang sangat kritis dan fundamental karena menghancurkan normalitas pandangan dan cara berpikir tentang hasrat. Pernyataan serupa dapat ditemukan dalam pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus di mana habitus dipahami bukan hanya sebagai sebuah praktik pembiasaan melainkan juga merupakan praktik untuk mewujudkan pembedaan (distinction) kelas, dan keunikan. Dalam pemikiran ini, selera tentang berbagai macam hal, dipahami sebagai sebuah produk dari habitus. Selera tentang makanan, model pakaian, bentuk dan destinasi liburan, serta merek produk barang-barang yang dikenakan bukanlah sesuatu yang bersifat spontan dan alamiah, melainkan sebuah hasil dari konstruksi, pembiasaan yang di dalamnya mengandung upaya pembedaan (distinction). Selera adalah buah dari habitus.
Dengan prinsip yang sama, pada tahun 2013, Zizek memproduksi film dokumenter lain dengan judul The Pervert’s Guide to Ideology, yang secara garis besar hendak menyatakan bahwa yang paling utama dalam kehidupan kita itu bukan soal apakah ideologi kita dapat diwujudkan ataukah tidak, melainkan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang menjadi ideologi kita sendiri, karena ideologi dalam kehidupan manusia itu tidak bersifat spontan dan alamiah, melainkan bersifat artifisial dan merupakan buah dari sebuah konstruksi. Manusia harus diajari, dilatih dan dididik untuk membangun ideologinya sendiri.
Novel Warisan 3 Kerajaan yang ditulis oleh Bud Murdono, dapat dibaca sebagai sebuah pembacaan tentang jejak-jejak pembentukan hasrat dan ideologi di dalam figur-figur utama yang dikisahkan di dalamnya, terutama di dalam dua figur yang memiliki manifestasi berbeda di dalam praktik kekuasaannya, yakni raja Senna di kerajaan Galuh dan Rakai Sanjaya di dua kerajaan yakni Sunda dan Bumi Mataran (Medang). Novel ini menyuguhkan sebuah realitas bahwa hasrat dan ideologi yang dimanifestasikan oleh para tokoh di dalam kehidupannya, sebenarnya bukanlah hasrat dan ideologi yang lahir secara spontan dan alamiah, melainkan merupakan konstruksi yang terjadi dalam ketaksadaran subyek. Hasrat dan ideologi itu merupakan buah dari habitus panjang yang terinternalisasi serta menjadi kerangka dan tatanan simbolis di dalam diri masing-masing, yang secara tak sadar memengaruhi seluruh cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak di tengah realitas.
Dua Manifestasi Hasrat dan Ideologi yang Berbeda
Meskipun ada beberapa subyek yang dikisahkan di dalam novel ini, saya memilih dua subyek utama yang tampaknya menonjol dalam narasi buku ini dan mendominasi dua dari tiga bagian besar buku ini. Dua subyek itu adalah Senna dan Jambri (yang kemudian bergelar Rakai Sanjaya). Senna adalah anak hasil perselingkuhan antara Pangeran Mandiminyak dan saudari iparnya, yakni Puah Rababu (istri Sempakwaja, kakak tertua Mandiminyak). Demi menjaga rahasia perselingkuhan ini, Senna dididik dan dibesarkan oleh paman ayahnya, Sang Mangukuhan dan istrinya, Nyai Wangi di wilayah Kulikuli. Seluruh lingkungan pendidikan dan pengasuhan di Kulikuli ini pada gilirannya menjadi habitus dan membentuk tatanan simbolis di dalam diri Senna, yang akan memengaruhi seluruh pembentuk dirinya sebagai subyek baik dalam cara berpikir, cara bersikap, maupun cara bertindak di tengah realitas.
Jambri yang ketika dewasa bergelar Rakai Sanjaya, adalah anak dari perkawinan Senna dengan Sanaha. Sejatinya, Sanaha adalah adik kandung Senna yang merupakan satu ayah namun berlainan ibu. Ini merupakan perkawinan incest yang sebeenarnya tak diijinkan oleh nalar kebudayaan baik pada masa itu maupun saat ini. Perkawinan incest ini dapat berlangsung karena seluruhnya dilakukan di dalam penjagaan terhadap rahasia besar perselingkuhan. Pada masa pendidikan dan pengasuhannya, Jambri atau Rakai Sanjaya merupakan anak didik dari Resi Wasista di wilayah Candrawati di kaki gunung Merapi. Seluruh lingkungan pendidikan dan pengasuhan Resi Wasista ini menjadi habitus dan membentuk tatanan simbolis dalam diri Sanjaya dan memengaruhi seluruh pembentukan dirinya sebagai subyek.
Secara garis besar, pendidikan dan pengasuhan yang dijalankan baik oleh Sang Mangukuhan di Kulikui maupun oleh Resi Wasista di Candrawati memiliki substansi dan metode yang kurang lebih sama dan fundamental yakni pendidikan nilai, pendidikan karakter, latihan-latihan olah kanuragan baik fisik maupun mental yang semuanya mengarah kepada pembentukan kepribadian integral yang menjunjung tinggi integritas, pengendalian diri dan berorientasi kepada keadilan serta perdamaian. Secara prinsip, kedua subyek, Senna maupun Sanjaya, memiliki pondasi pembentukan karakter yang serupa. Namun dalam perjalanan waktu, lingkungan terdekat yang turut mengintervensi pembentukan tatanan simbolis di dalam diri masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda di dalam proses berpikir, bersikap dan bertindak di masa-masa kemudian.
Sebagai anak hasil perselingkuhan yang dijagai dalam kerahasiaan, Senna sama sekali tak memiliki kesadaran bahwa dirinya memiliki hak untuk mewarisi tahta, dan tak memiliki habitus yang membangun hasratnya tentang perluasan kekuasaan. Pendidikan dan pengasuhan Sang Mangukuhan di Kulikuli lebih memengaruhi pembentukan dirinya sebagai subyek yang lebih berorientasi kepada filosofi kekuasaan sebagai pengabdian terhadap kesejahteraan dan kedamaian hidupan warga kerajaan. Akibatnya, sebagai penguasa, ia sama sekali tak memiliki perhatian utama kepada penguatan tentara kerajaan dan perluasan wilayah melalui penundukan dan pemaksaan. Posisinya sebagai penguasa dipahaminya bukan sebagai warisan dan hak karena keturunan, melainkan dipahaminya sebagai anugerah dan pemberian, karena ia sama sekali tak memahami siapa sebenarnya yang menjadi orangtuanya.
Sementara Jambri atau Sanjaya, meskipun mendapatkan pendidikan dan pengasuhan karakter dari Resi Wasista di Candrawati dan menjalani pendidikan kemiliteran di kesatrian dalam semangat kesetaraan dan keadilan, tanpa previledge sebagai pangeran, dalam ketaksadarannya, ia membangun hasrat tentang kekuasaan yang menaklukkan dalam upaya memperluas wilayah dan dominasi, karena hasrat yang diwarisi dari ibunya, ratu Sanaha, yang memiliki fantasi besar untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Kalingga seperti pada masa pemerintahan Ratu Shima (hlm.256-261). Hasrat ini dibentuk pula oleh pengalaman traumatis, yakni pengalaman kekalahan yang memaksanya untuk mengungsi ke Candrawati. Hasrat inilah yang kemudian di dalam ketaksadaranya menjadi hasrat dalam diri Sanjaya. Dalam psikoanalisis Lacanian, hasrat Sanjaya ini disebut sebagai hasrat dari Yang Lain (the Other). Tentang hasrat dari Yang Lain, yang memengaruhi hasrat subyek ini Sean Homer menyatakan:
Yang dimaksudkan dengan Yang Lain ini adalah sesuatu yang secara absolut berbeda dan tidak dapat diasimilasikan ke dalam subjektivitas kita. Yang Lain adalah tatanan simbolis, yakni suatu bahasa asing di mana kita dilahirkan dan harus belajar berbicara jika kita ingin mengartikulasikan keinginan kita sendiri. Ini juga merupakan wacana dan keinginan orang-orang di sekitar kita, yang melaluinya kita menginternalisasi dan memengaruhi keinginan kita sendiri. Apa yang diajarkan psikoanalisis kepada kita adalah bahwa keinginan kita selalu terkait erat dengan keinginan orang lain. Pertama-tama, ini adalah keinginan orang tua kita, karena mereka meletakkan pada bayi yang baru lahir semua harapan dan keinginan mereka untuk kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi, tetapi juga dalam arti bahwa mereka menginvestasikan pada anak-anak mereka semua impian dan aspirasi mereka sendiri yang belum terpenuhi. Keinginan dan keinginan bawah sadar orang lain ini mengalir ke dalam diri kita melalui bahasa – melalui wacana – dan oleh karena itu keinginan selalu dibentuk dan dibentuk oleh bahasa.
Inilah dua manifestasi utama dari hasrat dan ideologi yang secara dominan ditemukan di dalam narasi novel Warisan 3 Kerajaan ini. Dalam tatanan simbolisnya, yakni di dalam kerangka ketaksadaran bahasa yang memengaruhi seluruh cara berpikir dan memproduksi makna tentang realitas, subyek Senna tidak mengenali wacana atau bahasa tentang penaklukan, perluasan wilayah, atau penundukan melalui peperangan. Yang dominan di dalam tatanan simbolisnya adalah bahasa dan wacana tentang kekuasaan sebagai penjaminan keadilan, kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, dialog, diplomasi dan perjanjian kerjasama. Tentu saja ini sangat dipengaruhi oleh seluruh pendidikan dan pengasuhan padepokan Kulikuli yang memegang filososfi bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan menanamkan kesadaran bahwa setiap orang memiliki keinginan dan cita-cita yang sama. Kekuasaan bukanlah perang maupun pedang, melainkan hati yang menyatu. Kekuasaan bertahan bukan karena mengasah senjata melainkan karena mengasah kepercayaan (hlm.55)
Subyek-subyek lain, pada umumnya berada dalam hasrat tentang kekuasaan sebagai hak dan warisan yang musti direbut, dan dipertahankan. Hasrat ini memengaruhi pillihan-piihan tindakan berupa peperangan dan penaklukan kerajaan-kerjaan lain meskipun sebenarnya masih memiliki hubungan persaudaraan.
Membangun Tatanan Simbolis Melalui Narasi Edukatif
Sebagaimana Sang Mangukuhan, Nyai Wangi, Resi Wasista, dan Sanaha membangun tatanan simbolis dalam diri subyek Senna dan Sanjaya, demikian juga melalui narasi Warisan 3 Kerajaan ini, Bud Murdono sebagai penulis juga sedang menyuguhkan sebuah upaya membangun tatanan simbolis di dalam diri para pembacanya. Secara sangat menyolok, di dalam halaman-halaman novel ini tersebar beragam dialog dan narasi yang menunjukkan nilai-nilai fundamental di dalam kehidupan sekaligus pendidikan nilai dan karakter yang mendasar. Nilai-nilai fundamental itu antara terungkap di dalam filosofi tentang kekuatan, kekuasaan atau kebesaran yang tidak hanya ditentukan oleh aspek-aspek fisik melainkan terutama ditentukan oleh aspek-aspek mental, pikiran, kebajikan, keutamaan, oleh hati yang menyatukan dan membawa perdamaian, oleh kata-kata yang bagaikan benih, oleh pengendalian diri dan sebagainya. Bahkan secara panjang lebar penulis memaparkan prinsip-prinsip Niyama, yakni pedoman perilaku dan pengolahan diri baik secara fisik maupun secara mental berupa disiplin diri, latihan rohani (spiritual exercise – dalam terminologi St. Ignatius de Loyola, pendiri Ordo Serikat Jesus), di mana praktik pokoknya disebut sebagai discernment atau analisis dan pembedaan antara kebaikan dan kejahatan. Prinsip Niyama itu (hlm. 233-240) meliputi kebersihan (fisik maupun mental), rasa berkecukupan (sebagai anti tesis terhadap ketamakan), pengendalian diri, pengenalan diri (sebagai anti tesis terhadap ketergelinciran dalam pengenalan diri atau meconnaisance), dan berserah diri (atau providentia dei).
Nilai-nilai fundamental lain yang terungkap dalam halaman-halaman novel ini adalah nilai tentang kepemimpinan berdasarkan kompetensi, kemandirian atau otonomi dalam proses pendidikan (hlm.52), kesetaraan dan keadilan jender (hlm. 83, 94), prinsip pro-eksistensi atau membela dan menfasilitasi terpenuhinya hak-hak kelompok lain yang berbeda terutama jika kelompok itu sedang mendapatkan ancaman (hlm.95), kekuasaan yang dijalankan sebagai dharma dan terbuka terhadap kritik profetis (hlm.127), keberpihakan kepada mereka yang tertindas atau preferential option for the poor (hlm. 132), kesadaran akan kecenderungan kekuasaan yang mengorbankan kelas bawah (hlm. 208), dan proses pendidikan yang berdasarkan keadilan dan kesetaraan tanpa previledge (hlm. 242, 257).
Secara jelas, bagian epilog novel ini menegaskan satu prinsip nilai yang fundamental di dalam praksis kekuasaan, yakni bahwa kekuasaan itu sekali lagi semestinya dijalankan atas dasar kebijaksanaan dan bukan atas dasar pedang atau kekerasan (hlm. 620). Nilai terakhir yang pantas direfleksikan secara mendalam adalah bahwa seluruh praksis perselingkuhan dan manipulasi yang dinormalisasi melalui penjagaan kerahasiaan, yang berarti menutupi integritas dan kejujuran, akan melahirkan praktik-praktik ketidakdilan, melahirkan ketidakpekaan, orientasi kepentingan sempit, egoisme yang dibalut oleh konstruksi wacana tentang keluhuran dan kebajikan, menumbuhkan serta mereproduksi prasangka dan kebencian, dan pada akhirnya sangat rentan untuk tanpa rasa bersalah melakukan penghancuran terhadap kemanusiaan.
Secara tidak langsung, melalui novel Warisan 3 Kerajaan ini, Bud Murdono sedang berupaya untuk menyediakan jalan dalam membaca jejak-jejak pembentukan hasrat dan ideologi dari pengalaman kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa lalu, dan menegaskan sikap kritis bahwa setiap orang musti selalu berani bertanya tentang konstruksi realitas yang dihadapi di dalam kehidupan masa kini. Kembali menegaskan kutipan Zizek di awal, melalui novel ini, para pembaca diajak untuk berani menyatakan bahwa The problem for us is not whether our desires are satisfied or not. The problem is how do we know what we desire?***
*Indro Suprobo, penulis, editor dan penerjemah buku, tinggal di Jogyakarta.