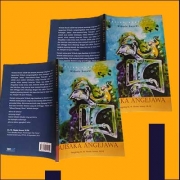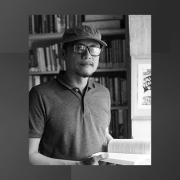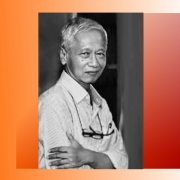Tubuh Merespon Jaman
Oleh Purnawan Andra*
Tanggal 29 April adalah Hari Tari Dunia. Dan dalam dunia yang serba bergerak ini, tari tak pernah hanya soal koreografi. Ia adalah bahasa tubuh yang, dengan sendirinya, menjadi medan politik, spiritual, dan sosial. Apalagi di tengah zaman yang penuh distorsi, disrupsi, dan disonansi ini—di mana algoritma mendikte hasrat, dan layar menggantikan lanskap perjumpaan—tari tidak sekadar hidup, tapi berevolusi sebagai respons terhadap gejolak zaman.
Kita hidup di masa ketika krisis tak lagi insidental, melainkan permanen. Krisis lingkungan, krisis identitas, krisis komunikasi, bahkan krisis kepercayaan terhadap makna “kehadiran” itu sendiri. Di tengah itu semua, tubuh manusia menjadi titik temu antara yang biologis dan yang politis. Dan tari, sebagai seni tubuh yang sadar akan ruang dan waktu, menjadi saksi sekaligus kritik atas realitas tersebut.
Tubuh sebagai Arena Tafsir Sosial
Maurice Merleau-Ponty, filsuf Prancis yang banyak mengurai tentang fenomenologi tubuh, menekankan bahwa tubuh bukanlah benda, tapi medium pengalaman. Tubuh bukan hanya mengalami dunia—ia adalah dunia itu sendiri, dalam bentuk paling konkret dan subjektif. Maka ketika penari menggerakkan tubuhnya, ia tak sedang “menampilkan” sesuatu; ia sedang “menghidupkan” dan “menyuarakan” tafsir terhadap realitas.
Gerakan tari, dalam konteks ini, tidak bisa lagi dibaca sebagai hasil eksplorasi teknik semata, melainkan sebagai artikulasi pemikiran—sebuah laku filsafat yang mengalir lewat otot, napas, dan ritme. Kita melihat ini dalam berbagai karya koreografis yang lahir pasca pandemi, ketika batas antara ruang pribadi dan ruang sosial mengabur, dan ketika tubuh—yang dahulu bebas berkeliaran—terpaksa menjelma menjadi objek disiplin dan isolasi.
Dalam karya-karya yang ditampilkan di panggung Indonesia Dance Festival (IDF) beberapa tahun terakhir, tubuh-tubuh penari menyuarakan kerentanan dan resistensi secara bersamaan. Para koreografer terpilih menunjukkan bagaimana tubuh bisa menjadi situs pertemuan antara tradisi, trauma, dan teknologi.
Koreografi sebagai Wacana Politik
Tari di era ini tak bisa tidak untuk bersinggungan dengan politik. Bukan politik praktis, melainkan politik tubuh—bagaimana tubuh disusun, diatur, disilangkan, atau justru dikekang oleh kekuasaan. Koreografi dalam pengertian ini menjadi strategi wacana. Ia menyusun ruang-ruang dalam tubuh untuk menyuarakan apa yang tak diucapkan dalam pidato atau dokumen negara.
Fenomena ini terlihat dalam pertunjukan-pertunjukan bertema lingkungan, ketimpangan sosial, dan kekerasan identitas. Para koreografer menggunakan narasi ekofeminisme untuk menggugat relasi eksploitatif manusia terhadap alam, dengan tubuh perempuan sebagai metafora ekologis.
Atau lihat bagaimana karya seniman dan komunitas tari di beberapa kota merespons urbanisasi dan dislokasi budaya melalui pertunjukan yang dilakukan di terminal angkutan umum, bukan di panggung formal. Koreografi berpindah dari ruang konvensional menuju situs-situs sosial: gang sempit, pasar, tepi sungai, bahkan media digital.
Koreografi merespon lingkungan kontemporer—yakni kesadaran bahwa ruang, waktu, dan konteks sosial adalah elemen dari tari itu sendiri, bukan sekadar latar. Ini menjadi perkembangan kreatif ketika jauh sebelumnya Sardono W Kusumo, Dedy Luthan hingga Eko Supriyanto mengkarya tari sebagai respon atas, di dan bersama elemen lingkungan setempat (para petani, masyarakat adat juga ibu-ibu di pedalaman Bali, hutan-hutan Kalimantan hingga pesisir Maluku Utara atau perbatasan Timor yang kering).
Termutakhir, koreografer seperti Rianto dan Otniel Tasman berproses kreatif dengan para lengger lanang di Banyumas, atau Anwari berkreasi dengan para penari Topeng Gulur Madura yang merespon kekeringan di tanah tinggal mereka. Pun banyak contoh lain yang pastinya masih bisa dikedepankan.
Tubuh Digital, Ekspresi Tak Terbendung
Lalu pandemi mempercepat kelahiran tubuh digital. Saat ruang fisik dibatasi, para penari, koreografer, dan seniman pertunjukan memindahkan tubuhnya ke dunia maya. Namun ini bukan sekadar adaptasi teknis. Yang terjadi adalah pergeseran epistemik: tubuh kini tak lagi sekadar objek penglihatan langsung, melainkan citra—yang bisa direkam, diedit, dipotong, dan diputar ulang.
Beberapa koreografer muda justru menyambut ini sebagai peluang kreatif. Mereka membuat karya yang tak hanya dipresentasikan di YouTube atau Zoom, tapi memang dikonseptualisasikan sejak awal sebagai karya digital. Tubuh menjadi medan tafsir spiritual sekaligus digital. Tubuh manusia ditampilkan berdampingan dengan visual glitch, suara artificial, dan ruang virtual. Tubuh tidak hilang, tapi diredefinisi.
Namun, tentu saja, ini juga membawa risiko. Tari menjadi produk tontonan instan, kehilangan laku dan napas meditatifnya. Banyak kritik muncul soal komodifikasi tubuh digital yang dipaksa mengikuti logika kecepatan dan algoritma platform. Di sinilah pentingnya kesadaran estetik baru: bagaimana tetap menjaga kedalaman ekspresi dalam dunia yang semakin dangkal?
Perluasan Tafsir dan Misi Sosial Seni Gerak
Di tengah itu semua, tari di Indonesia tidak surut. Justru sebaliknya, ia berkembang sebagai medan eksperimentasi gagasan dan kepekaan sosial. Kolaborasi lintas disiplin semakin jamak: tari bertemu dengan seni rupa, film, desain suara, bahkan riset sosial-politik. Inilah masa ketika tari tak bisa berdiri sendiri. Ia harus bicara dengan dunia.
Dalam IDF, Salihara, dan beberapa platform eksperimental seperti Bodies of Care atau Jejak-Tabi Exchange, banyak koreografer muda yang tak lagi hanya belajar dari tradisi atau teknik tari Barat. Mereka juga belajar dari aktivisme, ekologi, sejarah lokal, dan pengalaman komunitas. Tari menjadi jembatan antara estetika dan etika—ia tak hanya tampil untuk dipuji, tetapi untuk membongkar asumsi, mengguncang kenyamanan, dan menciptakan ruang perenungan kolektif.
Menuju Koreografi Empati
Jika dunia hari ini dipenuhi kekerasan simbolik dan fragmentasi sosial, maka tari bisa menjadi laku yang menyambung kembali tubuh-tubuh yang tercerai. Koreografi hari ini bukan hanya tentang menyusun gerak, tapi tentang menyusun pengalaman bersama. Koreografi sebagai empati: bagaimana tubuh-tubuh saling merasakan, saling menanggapi, saling mengakui eksistensinya dalam keberbedaan.
Tari bukan sekadar bentuk seni. Ia adalah ruang dialektika tubuh dengan zaman—sebuah strategi hidup untuk tetap waras, tetap peka, tetap bergerak di dunia yang terus berubah.
Di masa depan, mungkin kita tak lagi bisa memisahkan mana tubuh manusia dan mana tubuh digital, mana yang sakral dan mana yang profan, mana panggung dan mana medan sosial. Tapi selama tubuh masih bisa merasa dan bergerak, tari akan terus menjadi laku yang subversif dan solutif—karena ia tidak hanya mencerminkan dunia, tapi juga menafsirinya secara kritis, dan jika perlu, menggugatnya.
—
*Purnawan Andra, bekerja di Direktorat Bina SDM, Lembaga & Pranata Kebudayaan, Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan & Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan.