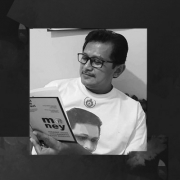Tari Jawa Krisis Jiwa
Renungan Pasca Pentas Triwulan ISI Surakarta
Oleh Razan Wirjosandjojo
Rembulan hampir bulat, dihiasi dengan awan yang menjaring. Rasanya sudah jarang saya melihat bulan, kali ini paduannya cantik. Pengalaman menyaksikan terang bulan ditaburi oleh rasa penasaran untuk menyaksikan Pentas Triwulan yang barangkali terakhir dipentaskan pada puluhan purnama yang lalu. Kedatangan yang terlambat dari jadwal di poster mempertemukan saya pada pendopo yang gulita. Gelapnya Pendopo ISI Surakarta menyatu dengan malam, namun binar-binar layar ponsel mengelilingi ruangan. Para penonton yang mayoritas merupakan mahasiswa sudah menjaga tempat duduk dan berdirinya masing-masing untuk menyaksikan tiga repertoar tari Jawa Gaya Surakarta klasik sebagai sajian pementasan malam Jumat (21/03) itu.
Lampu menyala, penonton mulai siaga. Pertunjukan dimulai dengan sambutan dan jargon-jargon akademik yang diutarakan oleh dekan fakultas Seni Pertunjukan, cukup makan waktu bagi sebuah pertunjukan yang mulai pada waktu yang larut. Repertoar pertama dimulai setelah rangkaian sambutan tersebut selesai. Tujuh penari yang membawa watang (sejenis tombak namun tak berpisau) masuk panggung. Mengetahui latar belakang para penampil yang merupakan mahasiswa tari di ISI Surakarta angkatan 2022, menjadikan momen ini sebagai tampilan hasil dari pendidikan tari pasca-pandemi.
Repertoar pertama memulai tarian serempak. Selayaknya pertunjukan tari wireng/keprajuritan yang umum saya ketahui, penari “Watang Keprajuritan” memenuhi mulutnya dengan sorakan sejak awal pertunjukan, sayangnya malam itu sorakan mereka terasa sayup. Tubuh para penari tidak menjulang namun perawakannya serupa, dapat dikatakan jadi elemen yang paling rampak dalam penyajian repertoar ini. Pose demi pose mereka tampilkan dalam formasi yang simetrikal. Melompat onclang sana-sini dalam peralihan gerak individu dan kelompok yang bermacam-macam. Sesekali perintilan kostum mereka berjatuhan dan terlempar, antara terkesan energik sekaligus lalai menggunakan busana.
Pola rantainya saya anggap cukup rumit, namun kerumitan itu terkunci pada arah hadap ke sisi utara panggung. Ada dua penari yang selalu berada di barisan depan, mungkin yang paling hafal. Pertunjukan terasa sekilas, lalu silam. Saya yang duduk di sisi barat laut pendopo merasa kesal dan menyesal karena pandangan saya sering terhalang saka/pilar pendopo. Pada masa peralihan antara repertoar pertama dan kedua, saya memutuskan untuk pindah ke sisi barat pendopo.
Awal mula pertunjukan kedua memperlihatkan para penari yang berbaris masuk dari sisi selatan pendopo ke sisi barat panggung sebagai tampak awal pertunjukan. Kapang-kapang terasa ampang, seketika mata saya menyaksikan mbak Rambat. Waktu terasa melambat karena hadir tubuhnya. Pertunjukan “Bedhaya Kidung Gayatri” berjalan saja seperti bedaya pada umumnya, walaupun terkadang ada bunyi saxophone yang asing dan tersisihkan di antara dengung instrumen karawitan Jawa. Sebelas penari itu masuk ke panggung, semua menghadap ke utara panggung seperti kesebelasan klub bola yang sedang menghadap musuhnya.

Sumber : laman Instagram @isi_surakarta
Gerak mereka berjalan melintasi alur musik, saya mulai bisa membaca ada 2-3 penari yang diistimewakan. Teknik (peng)garapnya membuka kesempatan yang terlalu mudah untuk membaca keputusannya yang pilih kasih. Pola lantai bermunculan, menunjukkan kemampuan penggarap menciptakan spektakel dari perpindahan tubuh dalam panggung. Walaupun penari didominasi oleh penari yang telah lulus dari ISI Surakarta, namun saya tidak menangkap satu kesan yang signifikan, jika dibandingkan repertoar yang pertama. Bagaimana pun, mbak Rambat sejak awal pertunjukan adalah “alien” di antara para penari lainnya. Garis pandangan dan kehadirannya menghampar dan mendalam.
Pertunjukan terakhir merupakan repertoar yang cenderung baru, menampilkan penafsiran kisah Arya Penangsang dan Sutawijaya yang ditawarkan dalam bangunan garap Tari Klasik Gaya Surakarta. Pertunjukan “Tari Kusuma Jipang” membuka dirinya dengan menampilkan Arya Penangsang dan empat prajuritnya. Saya sebagai orang yang sebelum begitu memahami kisah tersebut hanya bisa menebak-nebak. Menebak tokoh tersebut sebagai Arya Penangsang karena ia menyebut-nyebut “penangsang”, menebak empat penari sebagai prajurit karena sering sembah ke tokoh yang diperankan oleh Bedjho, tebakan itu pun diselimuti keraguan karena terkadang gestur yang hadir menampilkan psikologi karakter yang berbeda.

Sumber : laman Instagram @isi_surakarta
Bedjho bertemu dengan Sriyadi di tiga perempat panjang pertunjukan. Setelah mereka membuat-buat konflik, lalu mereka akhirnya sepakat untuk berkelahi. Keris ditarik sampai warangka–nya copot. Biar pun copotannya tergelimpang, mereka tetap percaya diri saling menusuk. Sepanjang perkelahian Bedjho unggul dalam cerita, namun seperti babak belur dipukuli panjangnya pertunjukan. Sriyadi yang baru masuk, terlihat lebih segar bugar walau telah diinjak oleh si Jipang. Pertunjukan berakhir tidak jelas bagi saya, siapa yang menang? Barangkali Bedjho Penangsang menang tapi mati, Sriyadiwijaya kalah tapi bugar. Teks dan psikis yang dipancarkan tubuh mereka campur aduk menjadi bias di mata saya.

Sumber : laman Instagram @isi_surakarta
***
Dilema Postur dan Gandar
Pertunjukan Triwulan yang saya saksikan malam itu berbeda pada mata kanan dan kiri saya. Pada satu mata, saya menyaksikan pertunjukan sebagai hasil kerja profesional, sedangkan di mata lain saya melihat sebuah potret pendidikan tari pasca-pandemi di ISI Surakarta. Mengenal pribadi dari sebagian dari penari yang terlibat membuat saya semakin merasa berjalan di atas tali. Beberapa penari adalah para alumni yang telah bekerja sebagai penari, dan di dalam pertunjukan ini mereka nyempil di antara mahasiswa. Para sutradara dan koreografer juga merupakan praktisi dan akademisi di jurusan tari ISI Surakarta. Keberagaman pengalaman dari jangka waktu (umur) yang berbeda justru memicu kecemasan di benak saya.
Repertoar pertama sudah dibekali oleh suasana militeristik dari tata gerak ciptaan S. Maridi yang terolah kembali oleh Sunarno Purwolelono, ditambah dengan iringan musik Blacius Subono. Nama-nama tersebut tak asing dalam sejarah tari dan karawitan Jawa pasca-ASKI. Pada pertunjukan malam itu, suasana repertoar ini seakan menjelma jadi latihan para calon taruna yang sedang berlatih agar diterima masuk AKMIL. Mereka tampak sebagai penari yang pintar karena nurut. Kerampakan mereka kompetitif, seperti calon taruna yang diam-diam sinis di antara sesamanya. Siswa andalan ditempatkan di baris depan sebagai contoh teladan bagi siswa terbelakang, atau yang tidak diajak pentas. Pertunjukan ini adalah ajang para taruna menunjukkan kebolehannya yang baru ia pelajari kepada para “jenderal” yang duduk manis di kursi undangan. Kondisi fisik maupun mental penari belum optimal membawakan bangunan karakter yang dibawakan.
Sebagai repertoar tari yang menunjukkan keprajuritan sebagai karakter, tampilan fisiologis penting untuk diperhatikan. Perbincangan saya dengan mbak Melati Suryodarmo mengenai postur badan yang sesuai dengan tokoh tersebut cenderung tarik-menarik. Baginya, penari Prawiro Watang harus berpostur tinggi. Saya sendiri mempertanyakan kembali keharusan elemen fisiologis tersebut yang tidak tercapai karena beberapa alasan.
Biarpun debat memanjang, pendapat mbak Melati cukup masuk akal. Hubungan penting antara fisikalitas dan karakter terbukti menjadi faktor krusial, baik di panggung pertunjukan maupun panggung kehidupan. Hal ini dapat dipelajari dari wayang yang mempertimbangkan bentuk tubuh sebagai satu cara membahasakan karakter, walaupun tetap dengan catatan bahwa statapan atas postur tubuh berkaitan pada konstruksi sosial di masanya atas tubuh itu sendiri. Fisikalitas tubuh tetap berfungsi sebagai satu tanda yang bisa menyapaikan karakteristik secara puitik dan filosofis. Semar sebagai contoh, gemuk dan bundarnya tidak menyoal obesitas atau kerakusan, seperti citra gemuk di dunia modern. Kehadiran semar yang bundar justru hadir sebagai abstraksi “lingkaran” kebijaksanaan, salah satunya dengan mengaburkan citra gender dari bentuk tubuh. Begitu pun strategi ini berlaku pada karakter wayang lainnya.
Pertimbangan mbak Melati diperkuat dengan alasan-alasannya mengenai konservasi arsip ketubuhan. Ia melihat fungsi lembaga pendidikan dalam mengarsipkan praktik tari klasik sebagai warisan keilmuan. Lembaga selayaknya mempertimbangkan secara seksama bentuk garap awal sebagai acuan kualitas satu nomor / repertoar tari. Hal ini dilihat penerapannya pada reenactment karya-karya kontemporer berbasis tubuh seperti “Cafe Muller” karya Pina Bausch, “Impondebarilia” karya Marina Abramovic and Ulay, atau juga saya temukan pada performans mbak Melati yang didelegasikan kepada orang lain sebagai performer. “Perekaan ulang” karya tersebut dilakukan dengan menggunakan tubuh dengan kapasitas ketubuhan/kepenarian yang semirip mungkin, termasuk mempertimbangkan aspek postur tubuh. Walaupun demikian, ada pula garapan “Rite of Spring” gubahan Pina Bausch yang melakukan perubahan terhadap fisik tubuh penarinya di versinya belakangan, dalam hal in terkhusus ke kulit hitam setelah sebelumnya dikerjakan dengan penari kulit putih. Contoh ini pun belum begitu sesuai, karena perubahan yang terjadi lebih pada konteks rasial dan kultural, belum pada tataran anatomikal.
Rata-rata kondisi postur dan anatomi tubuh mahasiswa tari ISI Surakarta tidak proporsional, jika diperbandingkan dengan standar yang ditetapkan ASKI pada masanya. Persoalan postur ini saya rasa cukup pelik, karena berkaitan dengan sistem yang lebih besar. Budaya olah raga masyarakat yang masih sangat rendah, rutinitas-rutinitas baru yang kontra-produktif dengan pertumbuhan anak muda, sampai kualitas gizi makan yang masih di bawah standar mininum. Hal ini tidak hanya terjadi di dalam tari, namun juga sebagai masalah lingkup lebih luas. Gendhon Humardani sebagai rektor ASKI dan kepala PKJT (sekarang TBJT) sudah mengupayakan solusi atas permasalahan ini, menamakannya sebagai “injeksi”. Para mahasiswa ASKI punya jadwal rutin setiap 6 pagi untuk olah tubuh dan latihan fisik, dengan intensitas yang cukup tinggi. Seusai latihan, mereka disuntik makanan tinggi nutrisi, disuntik dengan gizi yang cukup untuk menopang kebutuhan energi yang dibutuhkan tubuhnya. Kini injeksi dipahami sekadar olah fisik, melupakan esensi dari istilah penyuntikan itu sendiri.
Lembaga sebagai pemegang peran utama dalam melakukan pelestarian juga tidak bekerja optimal untuk mengontrol kualitas. Kuantitas mahasiswa tari di ISI Surakarta setiap tahunnya mencapai 140- 160 orang. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak ini, tuntutan kedisiplinan, baik dari mahasiswa maupun pengajar akan sangat tinggi untuk menjaga aspek kualitatif. Pada praktiknya, kualitas proses ajar-mengajar terabaikan. Kelas menjadi kandang ayam ternak, perlombaan “memakan” pelet paling banyak, menjadi ayam yang paling gemuk. Saya sendiri mengalami sebagai ayam tersebut, yang lebih sering tidak kebagian pelet pelajaran. Kadang dapat tapi mengeluh karena peletnya basi, bikin peternak marah.
Terlepas dari persoalan yang kusut, fenomena ini justru saya pertanyakan sebagai titik didih bagi tari tradisi untuk melakukan perenungan ulang. Tentara di negara-negara Eropa akan terlihat menjulang jika dibandingkan oleh tentara di Indonesia. Demikian adanya, perbedaan itu dapat terpinggirkan jika faktor perbandingan mengikutsertakan kompetensi TNI di Indonesia yang meraih posisi atas dalam hierarki prestasi militer di dunia (walau image ini tidak serta merta perlu dilihat sebagai prestasi). Mengambil contoh lain, Leo Messi dengan tubuhnya yang pendek di antara pesepak bola lain tetap dapat menjadi penembak yang ulung, fisiologis yang tinggi akhirnya tetap tertandingi oleh tubuh yang taktikal. Apakah fenomena ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memposisikan kembali postur kaitannya dengan pengkarakteran repertoar tari klasik? Saya sendiri masih berpikir.
Sayangnya, kecanggihan tubuh taktis juga tidak muncul dalam repertoar pertama. Tujuh penari belum menemukan gandar, belum mampu memproyeksikan keselarasan ekspresi ke seluruh anggota tubuh sebagai kesatuan wajah. Gandar dalam hal ini saya kaitkan dengan pengalaman menyaksikan kemampuan penari mengolah ekspresi tubuh sebagai wajah. Saya temukan ketika menyaksikan pak Daryono, bu Ketut Arini, atau mbak Nani Losari, yang wajahnya (atau topengnya) menyatu dengan seluruh anggota tubuh sebagai kesatuan ekspresi jiwa. Hal ini sepertinya belum sampai, melihat pemeranan prawiro watang masih berkutat pada soal tampang.
Saya sendiri paham bahwa olah gandar adalah kemampuan cukup rumit dan dengan latihan panjang, sehingga bisa katakan kekurangan ini dapat saya mengerti pada kasus mahasiswa yang masih belajar. Elemen maskulinitas dari tubuh mereka belum memberikan pengalaman rasa gagah. Saya merasakan binar keraguan di mata mereka. Begitu adanya, saya percaya salah satu cara menyadari satu hal adalah dengan menyadari ketiadaannya. Pertunjukan ini dapat menjadi pelajaran yang baik bagi penari maupun penonton, agar menyadari peran penting keberadaan postur dan gandar di dalam seni gerak tubuh.
Ulahing Jaja : Wajah dalam Tari Jawa Klasik
Selain pada repertoar pertama, permasalahan wajah juga dapat ditemukan pada repertoar kedua. Ekspresi kecantikan menjadi hal yang begitu masif di wajah para penari. Ada kesibukan tersendiri pada setiap individu, yang menjadikan tari kesebelasan ini tidak mencapai kebersamaan. Pertunjukan menjadi salon kecantikan yang diisi oleh para perempuan yang memiliki agendanya sendiri-sendiri.
Ulahing Jaja (mengolah dada) adalah istilah yang saya pinjam dari Serat Kridhwayangga, tidak hanya mempersoalkan olah dada sebagai seonggok daging dan otot. Perbincangan saya mengenai istilah tersebut dengan pak Daryono membukakan pemahaman bahwa “wajah” di dalam tari klasik gaya Surakarta bersemayam di dalam dada. Wajah tidak meletup di permukaan wajah, ia justru mencari kedalaman di antara paru-paru dan ulu hati. Ekspresi menjadi cahaya jiwa yang tersaring oleh awan, terangnya tak mencolok. Pak Daryono menambahkan bahwa dirinya mengimajinasikan torso sebagai cermin yang memantulkan “cahaya” ke seluruh ruang pertunjukan. Bagi saya metafora ini indah sekali, menyikapi politik ruang dengan sangat puitis.
Bedhaya Kehilangan Ombaknya
Tarian repertoar kedua rapi secara visual. Gerakannya presisi, dimensi tubuhnya juga cukup teliti. Pencapaian kerapian itu menjadi salah satu kualitas yang saya nikmati. Demikian rapi membuat pengistimewaan penari sangat kentara, pengistimewaan penari yang terlalu terlihat menurunkan ke-nyawiji–an mereka sebagai satu organisme yang padu. Tiga penari yang selalu tertangkap di mata saya membuat bingkai mata saya menjadi terus mengerucut kepada mereka, saya kehilangan kesempatan untuk menyaksikan bedaya sebagai sebuah samudera penuh ombak, atau menurut versi saya di tahun 2017, seperti menyaksikan tari hip-hop.
Saya mengingat tahun 2017, masa awal di mana saya mulai bisa terjaga ketika menyaksikan pertunjukan bedaya, setelah sebelumnya selalu ketiduran di tempat duduk. Setelah menyaksikan, saya jadi tertarik pada ketidak-rampakan pada pertunjukan Bedhaya Ela-Ela yang saya saksikan. Pengalaman itu mengingatkan saya pada kebinekaan rasa yang sebelumnya kerap saya alami kala menari hip-hop bersama teman-teman di Jakarta. Tuntutan kapasitas fisik tubuh untuk saling-sama persis tidak begitu penting, namun intensitas gerak dan energi kelompok jadi poin pamungkas. Meskipun dulu saya bahasakan dalam ungkapan,”wah power nya gak bareng nih”.
Kepolosan saya mengunggah pendapat tentang tari bedaya dan hip-hop itu ke sosial media saya, membuat geram beberapa dosen di ISI Surakarta kala itu, karena opini ini saya unggah ke sosial media dengan mengambil contoh satu kelompok hip-hop bernama “Royal Family”. Saya menangkap rasa kesal mereka yang menganggap bedaya tidak pantas dibandingkan dengan tarian perempuan yang bagi mereka terlalu “vulgar” sebagai bahan perbandingan. Semakin buruk karena opini saya yang diutarakan dalam bahasa inggris membuat kesalahpahaman, karena kalimat yang tidak diserap utuh justru mengira “Royal Family” itu berarti “keluarga Keraton”. Saya yang belum memahami selubung hierarki di Solo polos saja mengunggah opini tersebut.
Melihat pertunjukan Triwulan mengingatkan saya pada pengalaman itu kembali. Erotisme dalam bedaya bagi saya telah muncul dalam sejarah Bedhaya Ketawang yang menghadirkan elemen perempuan sebagai daya eros yang membahasakan perkawinan dalam level spiritual. Melihat dari lini waktu kini, saya rasa kita juga harus menerima realitas bahwa tari klasik Jawa hari ini dikerjakan oleh kebudayaan tubuh yang digeprek habis-habisan oleh industri sebagai sajian erotik. Terima atau tidak, proyeksi tersebut muncul di atas panggung Triwulan pada malam itu.
Tari Tidak Menjadi
Repertoar ketiga menjadi tutup yang tak rapat, menjadikan isinya melempem. Bedjho sebagai Arya Penangsang cukup ekspresif menghadirkan karakter sebagai tokoh yang bengis. Menikmati ekspresi geraknya yang lihai, ramai gerak yang ia tunjukkan dari tubuhnya sepertinya juga cukup menguras energi. Hal itu tak mengagetkan bagi saya jika melihat kerangka koreografis yang menaruh tuntutan fisik yang besar pada Bedjho sebagai karakter utama. Tubuh yang letih akhirnya berdampak luas pada kesadaran tubuh untuk mewaktu.
Tari Klasik Gaya Surakarta saya yakini punya kecanggihan tertentu dalam bernegosiasi dengan waktu. Ada kecerdasan tradisional dalam menekan dan mengulur waktu, menjadikan waktu sebagai entitas yang lentur. Kecerdasan ini diekspresikan dalam bentuk audio visual, memberikan pengalaman ruang yang surealis. Kualitas itu justru menurun sepanjang perjalanan Bedjho menari. Momen sering lepas, kesatuan diri tidak terkepang baik dengan gema bunyi.
Kesadaran ini muncul di kepala saya karena membandingkan dengan mbak Rambat yang saya saksikan di repertoar kedua. Satu penari di repertoar kedua cukup berhasil mengalami peralihan ruang-waktu dengan lebih khidmat. Selayaknya objek properti tari seperti keris atau gendhewa, waktu diolahnya sebagai material. Satu penari itu memainkan benang waktu dengan baik dengan jepitan ngithing-nya. Sriyadi dalam momen-momen tertentu juga menunjukkan intensitas dan peka terhadap momen, walaupun belum konsisten.
Teknik koreografi dan penyutradaraan tidak membantu saya sebagai penonton untuk mengenali peran Sriyadi, selain sebagai si penari berkostum hijau. Ketidakmampuan saya mengenali karakter itu bukan hanya secara tekstual pengisahan (si Arya atau si Suta), namun juga melalui penubuhan atas karakter tersebut. Lapisan pikir saya yang mengenal mereka berdua secara pribadi tidak dapat dikalahkan dengan kemampuan tubuh penari tersebut untuk menjadi (becoming). Karakter tidak dimaknai sebagai arwah yang merasuk dalam tubuh, baik dalam Sriyadi maupun Bedjho, sehingga pertarungan itu terasa menjadi momen saling tusuk antara Bedjho si kostum merah dan Sriyadi si kostum hijau.
Skenografi “Gawang”
Perbedaan dari tiga repertoar yang telah selesai pentas, dikemas pada struktur pola ruang yang sama-sama memunggungi saya dan penonton lain di sisi barat dan timur pendopo. Posisi duduk saya yang pindah ke barat tidak membuat pertunjukan semakin “terlihat”, saya seperti sedang mengintip pertunjukan yang tidak diperuntukkan kepada saya, walaupun jarak antara saka pendopo itu terbentang lebar. “gawang” sebagai ungkapan skenografis tari Jawa klasik tidak bermakna krusial dalam pertunjukan malam itu.
Saka sebagai tiang, membentuk satu dimensi gawang imajiner, yang tidak hanya diperuntukkan pada satu arah tertentu. Gawang berarti menempatkan satu garis lurus yang absolut atas ruang kepenontonan. Pencapaian penari menembak daya geraknya juga tidak hanya sebatas mendatar, ia juga meninggi pada ruang atas pendopo (yang sebetulnya secara arsitektural pendopo telah memperhatikan “langit-langit” yang memberikan pengalaman vertikal). Pementasana Triwulan membantu kita melihat residu penjajahan panggung prosenium terhadap tarian di Indonesia. Tari Jawa dalam momen ini kehilangan cakrabawa (lingkar ruang gerak) yang bersumber pada filsafat kiblat papat lima pancar–nya.
***
Lepas dari pertunjukan tersebut, perdebatan mulai terjadi di dalam mobil, saya dan mbak Melati Suryodarmo saling melempar argumen dan pertanyaan. Spontan perdebatan itu direspons oleh pak Halim yang duduk di depan. Ungkapannya cukup menarik perhatian. Ia mengatakan bahwa tari Jawa kehilangan kekhusyukannya. Penonton bertepuk-tepuk tangan dan berteriak-teriak dari awal hingga akhir. Pendapat ini seperti melingkar berbagai kesah yang saya rasakan.
Pendopo tidak menjelma ruang bagi semua orang yang hadir untuk menghayati tari sebagai ibadah gerak. Kualitas ketubuhan penari juga tidak menampilkan kedalaman selain sebagai spektakel yang nanggung. Ruang tidak padat dan pekat dengan energi, seperti gang kosong yang menggemakan sahutan-sahutan penggemar mahasiswa yang keceriaannya obsesif menyoraki penarinya.
Istilah “Tari Jawa” dalam tajuk artikel ini bermasalah karena cenderung memukul rata kemajemukan tari di pulau Jawa dengan satu gaya tertentu. Kendati demikian, saya rasa tulisan ini jelas merujuk pada gaya Tari Klasik Gaya Surakarta bersama dengan permasalahan krisis jiwa dan penghayatan batin di dalamnya. Pementasan Triwulan malam itu menghasilkan satu catatan atas pergeseran makna Tari Klasik Gaya Surakarta, yang sebelumnya merayakan tubuh sebagai paduan jiwa-raga yang penuh misteri, kini menjadi gebyar festival yang frontal.
—
*Razan Wirjosandjojo adalah seniman yang saat ini tinggal di Solo, Indonesia. Ia menyelesaikan studinya di Jurusan Tari Institut Seni Indonesia Surakarta. Razan mulai aktif menari pada tahun 2010 dengan mempelajari berbagai disiplin gerak dari berbagai ruang dan komunitas di Jakarta hingga tahun 2017. Setelah pindah ke Solo, ia belajar bersama Melati Suryodarmo sejak tahun 2018 hingga sekarang. Sejak 2020, Razan mulai menciptakan karyanya sendiri dan memperluas sudut pandangnya dalam melihat tubuh sebagai poros gagasan dan mengembangkannya dalam berbagai wahana. Saat ini Razan merupakan murid dan staf paruh waktu di Studio Plesungan.